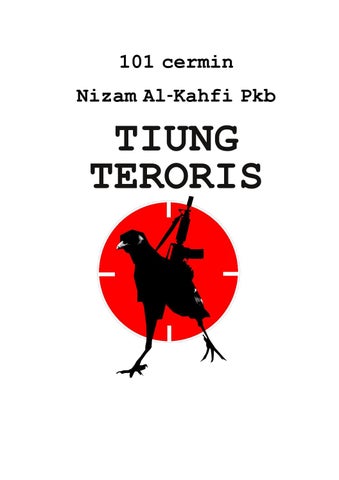101 cermin Nizam AlKahfi Pkb
TIUNG TERORIS
Â
N
izam AlKahfi Pkb adalah nama yang digunakan Hj Morshidi bin Hj Marsal saat menulis cermin (cerpen mini). Hj Morshidi bin Hj Marsal lahir di Brunei pada tanggal 22 Juni 1955. Ia tidak pintar menulis tapi senang berbagi ceritacerita yang tidak masuk akal. Ia mula menulis cerpen pada tahun 1980 saat lagi menganggur, di koran, majalah dan radio. Pada tahun 2008 sudah tidak lagi menulis cerpen, tapi lebih fokus menulis cermin di medsos yang sifatnya kompak (1000 jumlah kata maksimum). Selain nama Nizam AlKahfi Pkb, Hj Morshidi bin Hj Marsal juga menggunakan nama Mussidi dan Putera Katak Brunei. Katanya ia punya personaliti ganda. Sekarang ia sudah pensiunan, tinggal bersama istri dan empat orang anak dan seekor kucing betina yang bernama Ms Normah yang hobinya suka pamer diri. Bukubukunya yang lain adalah kumpulan cerpen Kecoh, novelet dan kumpulan cerpen A4, novelet Tum, kumpulan cerpen Tai, kumpulan cermin 365 Fiksi Mini Putera Katak Brunei, dan kumpulan cermin 16:60.
Â
Nizam AlKahfi Pkb kumpulan cermin
TIUNG TERORIS
© Nizam AlKahfi Pkb 2017
kandungan 01 DESTINASI KE MANA SAJA 1 02 PAHAM 3 03 KEMISKINAN 4 04 KELEBIHAN 5 05 KELEBIHAN II 6 06 SISIPUS 7 07 PENYIAR 9 08 KE DALAM DOMPET 11 09 LOMBA TULIS CERPEN 13 10 ANAK 15 11 MONYET PALING TAMPAN SEDUNIA 16 12 PAMANKU 19 13 TOPENG 22 14 HUJAN PANAS 24 15 MARAH 27 16 TAMAN 31 17 MATI 35 18 MULUT 38 19 KENCAN SAMA ISTRI DI RUMAH BARU 44 20 MAKAN 46 21 NO MORE WARS 52 22 ANAK KUCING BELANG TIGA 57 23 KISAH SEEKOR ELANG 59 24 MONYET 60 25 SEHAT 61 26 SI PELUPA 63 27 EMAS 67 28 IQRA 68 29 KEJUTAN 70 30 ANAK DURHAKA 71 31 UNDANGAN 73 32 PULANG 75 33 TELAJAK 77 34 UNTUK DIJUAL 82
35 NILAI 84 36 SENI LUKIS 87 37 AKU 91 38 TASYA 93 39 ALLI JADDI 99 40 SAHABAT 104 41 AYAM 105 42 EKOR 108 43 TV MIMPI 109 44 TULISAN CANTIK 113 45 BENCI 116 46 BANDEL 119 47 WANITA YANG BERJOGING MUNDURMUNDUR 123 48 SEPERTI DULU 125 49 KECELAKAAN 127 50 ENAK 128 51 KEMBALI 131 52 TEBING KETIGA 134 53 AKU LAGI LEBIH .... 138 54 DESA YANG TENANG 140 55 PULANG KE BUMI 145 56 POTRET 149 57 BUNGA 152 58 DI DALAM LIF 154 59 BAYANGBAYANGKU 158 60 (<>..<>) 161 61 HUJAN 164 62 DI KLINIK 166 63 PINDAH 169 64 MEMANCING 172 65 SERULING 175 66 TINA 177 67 MALING 180 68 NADIRAH 182 69 AKU, ISTRI dan TETANGGA 188 70 TIDAK BERGUNA 191
71 DOAKAN AKU 195 72 KOLAM 199 73 TERAPI ALTERNATIF 203 74 TIDAK ADA APAAPA YANG TERJADI 207 75 TARIF 209 76 PENGUNGSI 210 77 NGUUUNGGG... 213 78 ANAK 217 79 MATINYA SEORANG PEMBULI 222 80 TEMAN LANGKA 225 81 LIMA JUTA SERATUSSERATUS RIBU LIMA PULUH KEPING 227 82 UNGGUL 230 83 FANA 233 84 GUNTING KUKU 237 85 SERVIS 239 86 SAHABAT SAHABAT 243 87 I LOVE YOU 247 88 AMBILLAH 248 89 XKRITA 249 90 PUPUS 252 91 RIMBA 253 92 WANITA MISTERI 256 93 FOTOKOPI 258 94 CINTAKU JAUH DI HUTAN 261 95 BUAYA 264 96 KENTUT 266 97 tHe FReAKS! 269 98 SALJU PANAS 1974 271 99 BUDAK DI DALAM FOTO 273 100 NAMA 276 101 JAMUR 281
Â
01 DESTINASI KE MANA SAJA
A
ku terbangun apabila terasa becak yang kutumpangi bergegar seolaholah sedang melalui jalan yang berbongkah batu besar. Aku melihat kelilingku dan mataku kesilauan kerana sejauh mataku memandang seluasluasnya berwarna putih. Ada sedikit tumbuhtumbuhan hijau berbunga kuning, jingga dan merah, yang dikerumuni ramarama. Aku tercium bau harum kasturi. Tidak ada pokok kayu. Tukang becak memandangku dengan senyumsenyum. Semasa aku menaiki becak ini tadi ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Khodir. Meski tidak tampak kerut kerut di mukanya, aku berasa ia seorang yang sangat tua. "Jalanjalan, Pak," katanya. "Wisata keliling kota?" Memangnya penampilanku seorang wisatawan. "Iya," kataku. "Bawa aku ke mana saja." "Okey," kata Pak Khodir. "Destinasi ke mana saja untuk seorang." Tidak pula aku menyangka akan dibawa ke mari. "Kita ini lagi di mana?" "Kita sudah sampe di Mana Saja," kata Pak Khodir. "Di Mana Saja." Aku menyuruh Pak Khodir berhenti di tepi jalan. Aku turun. Kakikakiku menginjak tulangtulang dan tengkoraktengkorak manusia. "Tulang dan tengkorak bayibayi yang diaborsi dan dibunuh," kata Pak Khodir. "Aborsi dan pembunuhan yang dahulu, yang sekarang dan yang akan datang." Pak Khodir memungut sebiji tengkorak yang belum
1
menjadi sepenuhnya. Ia memberikannya kepadaku. Baunya harum kasturi. "Sovenir Pak," katanya. "Gratis."
2
02 PAHAM
P
ak Khodir melihat ke dalam mataku. Aku melihat ke dalam matanya. Hanya sekelip mata keseluruhan hidupku. "Paham?" katanya "Ya, aku paham," kataku.
3
03 KEMISKINAN
I
a menulis tentang kemiskinan dan kelaparan di kamar berhawa dingin, duduk di kerusi putar yang empuk, mengetik komputer yang baru dibelinya tunai kemarin, mengolah faktafakta yang digoogle, sambil makan pizza, minum kopi luwak dan menghisap rokok Dunhill.
4
04 KELEBIHAN
I
a menyeluk celana dalamnya, menanggalkan penisnya dan meletakkannya di atas meja di depanku. "Nah," katanya. Aku melihat penisnya, warnanya cerah, tidak ada istimewanya. Itu warna penis anakanak ingusan. Aku menyeluk celana dalamku, menanggalkan penisku dan meletakkannya di atas meja di depannya. "Nah," kataku. Ia melihat penisku. "Kok item banget," katanya. "Yang paling item di Nusantara," kataku. Ia merabaraba skrotum penisku. Ia senyum senget. "Gak ada istimewanya," katanya. Ia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan tiga jari kepadaku. "Penisku punya tiga testis," katanya. Aku merabaraba skrotum penisnya sambil mengira ngira di dalam hati. Satu dua tiga. Mustahil! Satu dua tiga. Mustahil! Satu dua tiga ... Akhirnya aku harus menerima hakikat bahwa ia punya kelebihan yang aku tidak punya: testisnya tiga biji.
5
05 KELEBIHAN II
A
ku sedang makan apel ketika ia mampir untuk bertanding kelebihan lagi. Ia sekali lagi mengandalkan penisnya. Ia menyikat rambutnya yang lurus ke belakang dengan jarijari tangan kanannya sambil bibirnya menyungging senyum. Senyum yang kurasa memperkecilkanku. "Kita lawan punya siapa yang lebih panjang," katanya. Lelaki jagoan ini memang tidak habishabis bangga dengan penisnya. "Kaumenang tanpa bertanding," kataku. "Tidak," katanya. "Kita harus bertanding sebagai bukti." Ia memandang mataku dengan tajam. Ah, aku malas mau melayaninya lalu tercetuslah di lidahku: "Punyamu panjang," kataku. Fayakun kata wujudku. Lalu penisnya jadi panjang dan terus mejulur keluar melilit betisnya sehingga ia tersungkur. Penisnya terus memanjang dan melilit tubuhnya seperti seekor ular. Aku tunduk menyuguhkan buah di tanganku ke mukanya yang tampak pucat dan biji halkumnya bergerak payah. "Apel?" kataku.
6
06 SISIPUS
A
ku sedang menuruni bukit memerhatikan orang tua compangcamping bajunya itu berjalan menaiki bukit menuju ke arahku, ia membongkok memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu membongkok lagi memungut sebutir batu kerikil kemudian berdiri tegak, batu kerikil itu dibalingnya ke dalam guni yang dipikulnya kemudian ia melangkah satu langkah lalu ... begitulah yang dilakukannya bagi setiap langkah dan guni itu sudah separuh sarat dan keliatan berat. "Bikin apa?" kataku seperti kemarin ketika berpapasan. "KAUPEDULI APA!" katanya seperti kamarin. "MIND YOUR OWN BUSINESS!" Di bawah bukit aku memerhatikannya memungut batu kerikil bagi setiap langkah sehingga ia sampai di puncak bukit. Sampai di puncak bukit, isi guni dihamburnya keluar sampai habis kemudian ia berlari
7
menuruni bukit, sementara aku menaiki bukit semula kerna panasaran. "Bikin apa?" kataku ketika berpapasan. "KAUPEDULI APA!" katanya. "MIND YOUR OWN BUSINESS!" Dari bawah bukit itu ia memulai semula aktivitasnya: membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, melangkah satu langkah ... dan aku meski sudah tahu apa jawabannya akan bertanya juga ketika berpapasan: "Bikin apa?" "KAUPEDULI APA! MIND YOUR OWN BUSINESS!" Entah kapan pula bermulanya aku yang menjadi si pemungut batu kerikil, dan dia pula yang bertanya: "Bikin apa?" katanya ketika berpapasan. "KAUPEDULI APA!" kataku. "MIND YOUR OWN BUSINESS!" Aku menyeka keringat di dahiku, aku melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, aku melangkah satu langkah, membongkok, memungut kerikil, berdiri tegak, baling kerikil ke dalam guni, aku melangkah satu langkah ...
8
07 PENYIAR
A
ku teringat sesuatu yang samasekali tidak lucu, dan orang di auditorium kompak itu tibatiba tertawa. Aku jadi malu. Aku tidak berkata apaapa hanya aku berpikir. Semakin aku bertambah malu, semakin kuat tertawa mereka. Kebetulan saja. Tidak mungkin orang tahu apa yang sedang kupikirkan, tapi aku tetap saja malu. Aku keluar dari auditorium dengan langkah langkah yang cepat sambil menundukkan kepala. Di pintu, aku ketemu kawan akrab yang sedang tertawa. "Entah," katanya, "dari mana datangnya cerita itu. Tibatiba saja ada persis siaran radio, tapi ini langsung di dalam kepala kami. Cerita memalukan yang pernah kauceritakan kepadaku dulu hahaha." Aku lihat di luar masih ada yang tertawa dan menyeka air mata. Lucu sekalikah peristiwa memalukanku itu? Pagi itu aku berusaha keras menyembunyikan fikiranku tanpa sukses. Bukan mauku apabila peristiwa peristiwa yang memalukan mula bermunculan di otakku. Publik tertawa mujur tidak ada yang tahu bahawa sumbernya aku. "Bikin malu aja," kata seorang perempuan yang lewat di depanku. "Hahaha tapi lucu banget." Kelebihanku adalah aku bisa belajar dengan cepat, dan kuasa observasiku sangat akut. Aku mendapati jika aku menyengetkan kepalaku pada 'angle' tertentu maka apa yang aku fikirkan akan terpancar seperti gelombang radio FM ke dalam kepala publik berdekatan.
9
Sore itu juga aku memulai siaranku ketika dosen menyampaikan kuliahnya. "Selamat sore, pamirsa. Ketemu kita kembali di FM Memalukan. Kita mulai siaran dengan sebuah lagu Cita Citita. ENJOY!" Aku pun menyanyikan di dalam kepalaku lagu 'Sakitnya Tuh Di Sini'. Aku lupa beritahu, aku tidak bisa bernyanyi nada dan suaraku sumbang 100% walau menyanyi di dalam kepala. Dosen memegang kepalanya yang berambut nipis itu persis sedang disiksa. "Baik!" kata dosen yang separuh baya itu. "Siapa yang nyala radio?" Gak ada kataku. Semua orang tertawa meski aku tidak tampak di mana lucunya. Kemudian aku lanjutkan siaran dengan gosip kampus yang terkini. Aku menamatkan siaranku dengan melontarkan gambar penis yang basah sebesar tugu Monas. Ini hanya permulaan dari siaran anarkisku. **** Aku mula rajin hadir di rapatrapat umum, di kajian kajian para kiayi, dan apa saja acara publik. Memang enak jadi anarkis apabila publik gampanggampang diagitasi.
10
08 KE DALAM DOMPET
G
adis itu berlari ke arahku. Seorang lelaki berbadan sasa mencaricarinya di selasela orang ramai yang berbaris di kounter bayaran. "Tolong aku Mas," katanya. "Tolong aku. Sembunyikan aku." Tidak ada apaapa yang bisa aku buat. Sosok tubuhku yang kurus bukanlah 'tiang' yang ideal buat bersembunyi bagi gadis yang sedikit gemuk sepertinya. "Aku ada hutang sejuta padanya," katanya dengan muka yang ketakutan. "Tapi dia ada hutang 1,5 juta padaku yang dia buat purapura lupa." Masalah biasa. Kataku, biarlah aku sahaja yang melunaskan hutangnya itu, supaya masalah selesai. "Moodku lagi baik, nih," kataku. "Jangan Mas," katanya. "Ia yang berhutang padaku." Aku mengeluarkan dompetku yang diperbuat dari kulit buaya. "JANGAN!" katanya lalu ia melompat masuk ke dalam dompetku. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa melakukan itu. Lelaki berbadan sasa sudah berada di sisiku. "Di mana Nita?" tanyanya. "Di mana dia?" "Nita?" kataku. "Gadis yang ginigini itu," katanya sambil mengayakan aksi dan saiz gadis itu. "Tadi dia di sini bersama Mas." "Oh," kataku. "Baru saja dia melompat masuk ke dalam dompet ini." Aku menunjuk ke dalam dompetku sambil senyum.
11
Lelaki berbadan sasa itu meninggalkanku sambil ngomel ngomel yang aku tidak pasti apa. "Nita," panggilku ke dalam dompetku. "Keluarlah, dia sudah pergi." "Ga mau," katanya. "Aku enak banget di sini di dalam dompetmu."
12
09 LOMBA TULIS CERPEN
I
a menang lomba tulis cerpen yang dikelolakan Tentara Nasional. Hadiahnya sebuah kereta kebal. Hadiah itu dikirim ke kediamannya di luar kota. Di dalam formulir lomba itu tidak ada disebutkan hadiah apa yang bakal dimenangkan. "Tahniah Pak," kata wakil tentara yang berpangkat Kolonel. "Bapak menang hadiah juara." "Kereta kebal Scorpion siri 90," tukas seorang lagi, yang berpangkat Sersan. Ia diajar bagaimana mengendalikan kereta kebal itu, dan ternyata gampang sekali. Ia juga diberitahu bahawa kereta kebal itu tidak boleh ditukar milik atau dijual. Konsensi memilikinya hanya khusus untuk dirinya. "Seru banget cerpennya, Pak," kata Pak Kolonel. Mereka berfoto di depan kereta kebal. Setelah menandatangani semua dokument pemilikan, dan setelah wakilwakil tentara ini pergi, ia pun memandang hadiah yang besar ini. Inilah pertama kali ia memenangkan lomba tulis cerpen, dan dapat hadiah juara pertama pula. Besoknya ia masuk koran di rubrik Budaya dan Sastra. Cerpennya yang menang itu juga dipublikasikan di situ. Beberapa orang sutradara filem telah mengontaknya untuk cerpen itu dijadikan filem. "Saya suka banget dengan tema antiperangnya," kata seorang sutradara. "Jalan ceritanya juga seru." Begitulah ia jadi terkenal sebagai penulis cerpen antiperang yang dapat hadiah kereta kebal. "Mau aku bikin apa dengan kereta kebal ini?" katanya
13
sambil menampar jidat. Sekarang setiap hari ia pergi ke kantor dengan kereta kebalnya. Mungkin imaginasinya saja, tapi ia seperti terdengar orangorang berkata: "Tuh penulis cerpen antiperang pergi kerja dengan kereta kebalnya."
14
10 ANAK
K
ata doktor anak itu akan lahir dengan kecacatan yang parah dan tidak akan bertahan lama. Barangkali selepas dilahirkan sepuluh minit atau paling lama limabelas minit ia akan mati. Terlalu banyak komplikasi pada fetus itu. Doktor mensarankan agar fetus itu diaborsi saja sesegera mungkin sebelum ia berkembang lebih jauh lagi. Sekarang adalah saat paling sesuai untuk itu. "Namun." kata doktor, "itu terserah kepada kamu suami isteri, mau diaborsi atau tidak." Mereka tidak mahu melakukan aborsi. Anak itu lahir prematur sebulan kemudian dan hanya bertahan sepuluh menit. Sepuluh menit mereka suami isteri membelainya, membisikbisik kasih sayang di telinga yang kecil itu. Apabila mereka menyuguhkan jari kelingking ke tapak tangan yang mugil itu, mereka hampirhampir tidak percaya betapa kuat dan erat genggemannya. Anak itu tibatiba senyum seolaholah mengatakan: terima kasih ibu, terima kasih ayah kerna memberi aku peluang lahir di dunia walau hanya sekejap. Dia pergi dengan senyuman dan tanpa mengurangi sedikitpun genggaman erat di jari kelingking ibu dan ayahnya.
15
11 MONYET PALING TAMPAN SEDUNIA
I
sterikulah yang mulamula sekali terlihat akan monyet yang paling tampan di sedunia itu, bertenggek di dahan pokok mangga, kirakira 200 meter dari jendela dapur. "Bang monyet, bang," kata isteriku. Tidak ada apa yang istimewanya dengan monyet. Aku melihat monyet setiap hari tetapi kali ini isteriku bersikeras memanggilku untuk melihat monyet itu dan apabila aku melihat monyet itu aku tepegun. "Masya Allah," kataku dengan spontan. "Tampan banget ya bang monyetnya," kata isteriku seperti berbisik. "Iya," kataku. "Tampan sungguh." "Haaaaaaaahhhhh," desah isteriku, matanya sedikit tertutup lembut, bunyi haaaaah itu seperti lahir dari dalam hatinya yang paling dalam. "Haaaaaahhhhhh." Aku memandangnya. Ia merenung monyet itu dan monyet itu seolaholah tersenyumsenyum, memandang ke dalam rumah kami itu. "Tampan sekali dia ya bang," kata isteriku lagi. "Haahhhhhhhhhhh." Aku kembali ke meja makan untuk menyambung sarapan pagiku. Selepas itu aku terus pergi kerja. Samasekali aku telah lupa hal monyet itu, apabila pulang ke rumah untuk makan siang, aku mendapati rumahku dipenuhi orang. Ketika masuk aku berpapasan dengan isteri tetangga terdekat. "Tampan banget yang Pak, monyetnya," katanya. Barulah aku teringat kembali tentang monyet itu.
16
"Monyet itu masih di situ?" kataku. "Ya, Pak," kata isteri tetanggaku itu. "Tampan sekali dia ya pak, haahhhhhhhhhhh." Aku memandang ke luar jendela dapur, monyet itu memandangku dengan senyumsenyum. Aku memandang isteri para tetangga yang duduk berkeliling meja makan yang bundar. Mereka semuanya tunduk tunduk. "Ah," kata seorang dari mereka. "Kalaulah suamiku setampan monyet itu, alangkah ..." Isteriku memandangku dengan mata yang redup kuyu. "Iya," katanya. "Kalaulah suamiku ini setampan monyet itu ahhhhhhh alangkah alangkah ..." Aku tidak mahu lamalama di rumah ini, apalagi isteriku telah tidak menyediakan santapanku dan tidak ada harapan akan disediakan apaapa dengan keadaan dapur yang dipenuhi isteriisteri tetangga. "Mengapa tidak saja kamu kasih makan monyet itu?" kataku. Aku meninggalkan mereka. Aku singgah di sebuah warong untuk makan siang sebelum ke kantor. Sore itu aku pulang dan mendapati rumahku bertambah kompak dengan para perempuan, yang tua, yang muda, yang remaja malah yang masih sd pun ada, ibuibu isteri kepalakepala desa, isteri para menteri dan vip, guruguru, isteri pak imam, ustaz dan para kiayi semua datang ke rumahku ini. Aku ingin menghentikan semua ini dan aku tahu apa yang harus aku buat. Aku masuk ke kamar dan mengambil senapang. Mereka kaget melihat aku memikul senapang di bahu kananku serentak pula mereka berkata:
17
"BAPAK CEMBURU YA SAMA MAS MONYET ITU?" Aku membidik senapangku ke arah monyet yang sedang makan pisang di atas meja makan bundar yang sudah diangkat keluar dan dihiasi dengan alas yang cantik, dan di atasnya terhidang makanan yang hanya pantas untuk makanan anak raja. Aku menekan pelatuk senapang. DOR! TIDAKLAH AKU CEMBURU SEDIKIT PUN PADA MONYET CELAKA ITU DAN AKU ADALAH MANUSIA PALING PENYABAR.
18
12 PAMANKU
A
ku keponakan kesayangan Paman. Sejak aku berusia sepuluh tahun dialah yang memeliharaku. Sebelum itu pamanku itu menghilang. Kata orang ia masuk penjara, entah untuk apa, aku tidak tahu. Aku punya bapa dan emak tapi mereka membiarkan Paman memanjaiku semaunya. Meskipun sudah tiga kali menikah, ia sampai sekarang tidak punya anak. "Nizam," katanya kepadaku satu hari. "Usiamu sudah 33 tahun, kapan lagi kau menikah?" "Paman kan tahu aku pemalu banget sama cewe," kataku. "Kau ini apa?" katanya. "Tuatua masih pemalu!" Besoknya tanpa kudugaduga, Paman membawa seorang gadis untuk dijodohkan denganku. "Ini pilihanku," katanya. Memang aku malu juga diperlakukan Paman seperti itu, tapi aku lagi terdesak, usia 33 masih membujang, pengen cepatcepat menikah, jadi aku turuti kemahuannya. Lina berusia 22 tahun baru saja wisuda dalam jurusan Bahasa Inggeris. Ia seorang gadis peramah, berambut sederhana panjang, hitam manis, bermuka bujur, dan cantik juga. Ia hanya mengambil masa sepuluh menit untuk membongkar rahsia diriku. Habis semua rahsia peribadiku aku dedahkan kepadanya. Memang ia punya bakat alami membongkar rahasia orang. "33 tahun," katanya, sedikit tertawa, "dan gak pernah sekalipun kencan sama cewe Kang Nizam mang cowo
19
langka di zaman ini. Punya pekerjaan sendiri, punya mobil, harusnya sudah lama menikah dan punya anak." Aku punya perusahaan kecil dalam bidang grafik dan pengiklanan, pendapatanku ikut musim, dan serajin mana aku mencari dan meyakinkan pelanggan, dan memang sudah pantas untuk berumahtangga. Dua bulan kami berteman, keluar makan bersama sepertinya orang sedang pacaran sehingga bapaku yang selama ini tidak pernah ambil peduli bertanya: "Kapan lagi kau menikah?" Dan pamanku dengan bangga bertanya: "Bagaimana dengan pilihanku itu?" Yang benarnya aku menyukai Lina, tapi aku tidak merasakan apaapa dari dirinya, karena itu aku ragu ragu, dan jika aku raguragu aku tidak akan bertindak apaapa. Aku diam saja seperti biasa apabila subjek menikah ditimbulkan, dan paman seperti faham. "Apa?" katanya. "Kaumau tunggu sudah tua seperti aku baru mau menikah?" Aku diam saja. Linalah yang akhirnya berterusterang kepadaku, ketika kami keluar makan siang di sebuah restoran, bahwa memang ia tidak ada perasaan apaapa terhadap diriku, ia lebih tertarik pada lelaki yang lebih tua, jelasnya. "Seperti pamanmu," katanya. "Kami akan menikah." Entah mengapa aku tidak terkejut seperti satu dejavu pula rasanya. "Tapi Paman ada isteri," kataku. "Iya," kata Lina. "Tapi isterinya gagal beranak. Aku harap aku bisa memberikannya anak." Aku memandang muka Lina yang senyumsenyum padaku.
20
"Bagaimana kautahu masalahnya bukan pada Paman?" tanyaku. "Bukankah Paman sudah menikah tiga kali dan masih juga belum punya anak? Itu ertinya masalah mandulnya adalah pada Paman bukan pada isteri." Lina membongkok sedikit ke depan agar lebih dekat padaku, ia memandang mataku dengan tajam. "Kang Nizam," katanya dengan berbisik, "mau tau rahsia pamanmu yang sempat aku bongkar? Pamanmu punya anak." Oh, ini aku tidak tahu, memang gadis ini punya bakat membongkar rahsia orang. "Kang Nizam adalah anak kandung Paman," katanya dengan nada yang muktamad yang bikin aku percaya tanpa ada soalsoal. Jujurnya aku benarbenar kaget, namun aku tidak mahu tahu cerita selanjutnya dan Lina paham itu. Mereka menikah tiga bulan kemudian, memang ia pilihan Paman. Aku terus membujang hingga sekarang. ................ palinglah enak si mangga udang hei sayang disayang pohonnya tinggi, pohonnya tinggi buahnya jarang palinglah enak si orang bujang, sayang ke mana pergi, ke mana pergi tiada yang larang ................
21
13 TOPENG
D
i dalam kabinet personaliti itu, di rak teratas, aku memiliki 100 biji jantung. Di rakrak lain pun ada 100 biji otak dan 100 buah muka. Aku hanya perlu memilih seperti memilih kemeja ketika keluar apartement, sesuai untuk ketemu orang tertentu atau untuk sesuatu upacara. Saat keluar aku tidak pernah keluar sebagai diriku sendiri. Kadangkala ketika berada di dalam apartement pun, aku tidak ada waktu untuk mengubah diri balik ke yang asli. Aku akan menjadi orang lain selama satu minggu atau dua minggu, bahkan adakalanya sampai satu bulan. Ini sudah menjadi tren di kota yang ramai dan sibuk ini. Memiliki teman yang banyak sepertinya tidak berarti karena aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya, begitu juga mereka: mereka tidak tahu siapa aku. Kami hanya berpurapura kenal. "Aku suka kau seperti adanya sekarang ini," kata seorang teman wanitaku, dia ingin menseriuskan hubungan. "Tapi aku ingin tahu kau yang sebenarnya." "Inilah aku yang sebenarnya," kataku berbohong. Ia tahu aku berbohong: tidak ada orang keluar apartementnya meninggalkan topeng. "Aku ingin ikut ke apartementmu," katanya. "Aku ingin melihat kabinetmu. Berapa sebenarnya personalitimu?" "Termasuk diriku sendiri ada 101," kataku, kali ini aku berkata jujur. "Banyak sekali," katanya. "Aku cuma memiliki 50 personaliti. Kau bisa melihat kabinetku nanti." Aku membawanya ke apartmentku. Sebenarnya aku sudah capek berpurapura. Ia melihat kabinet
22
personalitiku dan menebak dengan benar mana jantung, otak dan mukaku yang sebenarnya. Ia mengambil dan memakai jantung dan otakku. "Aku suka jantungmu, kau seorang yang baik hati," katanya. "Tapi otakmu terlalu lamban." "Otak itu sudah lama tidak dipakai," kataku. "Aku hanya menggunakannya untuk konferensi setahun sekali."
23
14 HUJAN PANAS
O
rangorang berlari mencari perlindungan dari hujan deras yang tibatiba turun. Malah aku tampak anjing dan kucing menyusupnyusup di bawah timbunan kotak. Air mengalir menganak sungai membawa hanyut sampahsampah bergabung dengan selokan yang mulai melimpah. Tadi cuaca panas sekali. Burung berkicauan. Matahari memancar seperti membalas dendam setelah tiga hari hujan. Dengan konfiden aku keluar tanpa berbekal payung. Hujan turun ketika aku sudah tidak punya pilihan untuk berpatah balik. Aku malas mencari perlindungan. Ya hujan, hujanlah, biar aku basah kuyup, tidak apa. Ternyata derasnya hujan hanya sekirakira sepuluh menit, kemudian ia pelanpelan reda. Matahari mucul semula, tapi hujan terus renyairenyai. Hujan panas. Sudah lama tidak hujan panas. Aku melihat ke atas, ke langit. Air hujan apabila terkena cahaya matahari tampak seperti manikmanik berlian. Aku memandang semula ke bawah. Meski hujan panas masih renyai renyai, sudah mulai ramai orang berkeliaran dan beraktivitas. Mereka tidak berpayung hanya memakai ponco kalis air warna gelap ada 'hood' yang melindungi kepala mereka. Aku mulai curiga di mana aku berada. Mereka semuanya berpakaian serupa. Mereka tertunduk tunduk. Beberapa orang mengangkat kepala memandangku. Kaget, mereka berlari menuju ke satu arah, ke rumah jauh di depanku. Orangorang lain mula ikut berlari anak ke rumah itu. Rumah itu tampak seperti
24
sebuah Rumah Adat. Dari situ keluar tiga orang berpakaian ponco masingmasing berwarna hijau, merah dan kuning, berjalan tergesagesa menuju ke arahku. "Selamat datang Nak Nizam," kata yang tua berponco merah. Ia berjenggot putih dan berkumis panjang serta lebih banyak kedut di dahinya berbanding yang dua orang lagi. "Kami menunggu kedatanganmu." Bagaimana mereka tahu namaku, aku bingung memikirkannya. Di dalam rumah itu sudah ramai yang menunggu. Aku disuruh bersila di sisi seorang wanita yang sedangsedang cantiknya. "Ini calon isterimu," kata seorang dari mereka. "Sebentar lagi upacara nikahnya." "Tapi aku sudah punya isteri dan anak," aku berbohong. Lelaki berponco merah yang kelihatannya paling tua tersenyum. Yang lain ikut senyum. "Kami tahu datadata penting tentang dirimu," kata yang tertua. "Ga usah berbohong." Lelaki tua berponco merah duduk menghadapku, rapat sekali sehingga lututnya menyentuh lututku. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Tua Adat. Ia memegang keduadua tanganku, sambil memandang ke dalam mataku. Dua orang lelaki berponco hijau dan kuning duduk di kiri dan kanannya, sementara yang lain duduk bersafsaf di belakang, mereka menghadapku dan wanita calon isteriku. "Adat di sini," katanya dengan serius, "setiap orang yang tersesat ke alam kami ketika hujan panas akan kami angkat jadi Presiden." Ia memandang ke kiri ke kanan seolaholah minta diiyakan.
25
Aku dinikahkan dan diangkat jadi Presiden dengan upacara yang sederhana. Mengikut keterangan Tua Adat aku akan menjawat tugas President sehinggalah ada orang baru yang tersesat ke mari ketika hujan panas. "Sementara itu jadilah Presiden yang baik," katanya. "Selamat Bapak Presiden Nizam AlKahfi!" Orangorang lain ikut melaungkan namaku sebanyak dua kali. "Selamat Bapak Presiden Nizam AlKahfi!" "Selamat Bapak Presiden Nizam AlKahfi!" Besoknya aku menyampaikan hasratku untuk melakukan lawatan ke seluruh negeri sebagai tugas pertamaku. "Untuk apa?" kata Tua Adat memandangku dengan matanya yang tajam itu. "Sebagai Bapak Presiden aku harus tau keadaan rakyatku," kataku. "Di sini," kata Tua Adat dengan nada muktamad, "Presiden ga perlu berbuat apaapa. Presiden ga perlu perihatin keadaan rakyat." Diamlah aku di Istana Presiden bersama isteriku yang sedangsedang cantik menunggu ada orang lain dari alam kita tersesat ke mari ketika hujan panas.
26
15 MARAH
T
ok!Tok!Tok! Aku coba mengontrol kemarahanku. Aku mengunci pintu. “Bapak, saya Direktur mau masuk. Buka pintu.” Mulamula sekali mukaku keringatan disusuli dengan napas yang keluar masuk tidak teratur. Kuping telingaku terasa panas, tidak serentak; telinga sebelah kiri dahulu, bergerakgerak sedikit, kemudian telinga kananku. Gerak gerak telinga kananku turun ke lengan dan aku mengepalngepalkan jariku. Sudah menjadi tabiatku untuk marahmarah setiap hari di kantor sekitar jam sembilan setengah pagi. Marahku tidaklah sampai memukul sesiapa. Aku hanya memaki hamun dengan katakata yang sangat kesat dan kotor. Aku memerlukan seseorang untuk dimakihamun: lima minit sahaja dan aku akan kembali tenang; semua tugasan akan beres. Siapa saja yang kebetulan masuk ke kamarku inilah yang akan menerima amarahku. Memang kita perlu alasan untuk marahmarah dan memang juga banyak alasan untuk kita marahmarah belum habis alasan yang sedia ada akan datang pula alasanalasan yang baru tetapi aku tidak memerlukan apaapa alasan untuk marahmarah. Marahku adalah marah semulajadi seperti semulajadi orang yang pengasih dan penyayang. Apabila tabiatku ini sudah menjadi pengetahuan publik, tiada sesiapa mahu ketemu denganku sekitar waktu ini. “Ga wajarwajar pemarahnya bos itu.”
27
Tiada sesiapa yang berani berligarligar di luar ofisku dan aku terpaksa membendung marahku ini sehingga ada orang masuk. “CELAKA!” kataku kepada orang ini. “CUKIMAI TAIE ANJING GOBLOK BINCACAK LONTE KUNTILANAK TUYUL GENDRUWO.” Entah macamana aku bisa mempertahankan hamburan sumpah seranah tersebut selama lima minit. Maki hamun ini pula memang dengan ikhlas aku tujukkan kepada orang yang kebetulan berada di depanku. “Serem,” kata pesuruh kantor yang pernah aku maki. “Nama hantu semua disebut. Sesuka hatinya kita dimaki, mentangmentang aku kuli.” Tidak lama selepas aku memaki hamun itu dia telah berhenti kerja dan buat kerja sendiri menjual nasi bungkus dan soto. Khabarnya sukses juga bisnesnya. Aku sendiri sering memesan nasi bungkus dan soto darinya untuk traktir anakanak buahku pada hujung bulan, menurut aku sendiri, aku kepala bagian yang baik hati juga, kecuali pada jam sembilan setengah. “Lumayan enak soto dan nasi bungkusnya, ya boss.” Begitulah namanya mula tersebar dan kantorkantor lain pun ikutikutan memesan darinya. Kebanyakan orang akan berterima kasih kepada kita kalau kita berbuat baik kepada mereka. Pesuruh kantor inilah manusia pertama yang berterima kasih kerana aku menyumpah dan memakinya. “Terima kasih bos kerana maki hamunnya dulu itu,” katanya sambil ketawa. “Samasama,” kataku pula. “Kalau ada anak buahmu atau keponakanmu yang kaumau dimaki hamun hantar saja ke kantorku ini sekitar 9.30 pagi hahaha.”
28
“Insyaallah nanti aku hantar seorang anak yang keras kepala,” katanya. Aku sangka dia bercanda. Lima minggu kemudian dia menghantar keponakannya untuk aku maki hamun datangnya tepat ketika marah semulajadiku sedang meluap. Keponakannya itu dihantar oleh pekerjaku, yang sudah pasti, aku fikir, merasa lega menghantar orang luar yang tidak tahumenahu tentang tabiatku ini. “CILAKA CUKIMAI TAIE ANJING GOBLOK BINCACAK LONTE KUNTILANAK TUYUL SETAN GENDRUWO BANJINGAAN.” Lima bulan kemudian mantan pesuruh pejabat itu datang lagi untuk mengucapkan terima kasih. “Terima kasih boz kerana memaki ponakanku,” katanya sambil tersenyum lebar nampak gigigiginya yang sedikit kekuningkuningan. “Sekarang ia sudah jadi supplier ikan segar ke hotelhotel seluruh negeri. Maju juga bisnesnya bozz.” Kemudian dia menghantar lagi beberapa orang keponakannya untuk kumaki hamun dan memang kemudian kesemua mereka menjadi orang yang berjaya; ada yang naik pangkat dengan tidak didugaduga, ada yang mendapat kontrak untuk projek besar bernilai tinggi, ada yang dapat menantu jutawan luar negeri, paling kecil menang ‘holeinone’ setengah miliar. Aku tidak memiliki kuasa untuk menentukan apa yang orang lain mahu percaya. Orang mula berdatangan ke ofisku minta dimaki hamun. Ada yang datang minta dimaki hamun berseorangan; ada yang datang minta dimaki hamun berkumpulan; ada yang datang minta dimaki hamun sekeluarga; ada yang datang minta dimaki hamun satu keturunan lima generasi sekaligus; datuk, nenek, bapa, anak dan cucu. Ada Bu Guru yang datang
29
berserta anakanak murid sdnya tepat sebelum jam sembilan setengah pagi. "Pak," katanya, "Coba deh Pak maki hamun nih anak anak muridku supaya mereka jadi berguna untuk bangsa, negara dan agama." “CILAKA CUKIMAI TAIE ANJING BINCACAK LONTE KUNTILANAK TUYUL SETAN GENDRUWO BANJINGAN BLOODY SHIT.” Maki hamunku tidak mengenal diskriminasi dan tidak bisa dibendung apabila ia datang. Ketukan di pintu pun semakin rancak. Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok! “PAK BUKA PINTU PAK. SAYA DIREKTOR MAU MINTA DIMAKI HAMUN!” Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok!Tok! Pernah ada orang mengkhabarkan kepadaku yang Bapak Direktur ini sudah lama bercitacita mau jadi menteri.
30
16 TAMAN
A
da sepotong tanah di tepi rumahku yang telah dengan pelanpelan kuperbaiki. Kuberi lansekap, kutanam bunga yang beranika macam warna dan semerbak wangi sehingga menjadi taman kupukupu; di situ juga kugali kolam kecil untuk memelihara ikan, dengan semburan dan air terjun yang dihiasi serumpun bambu. Kutanam juga beberapa pohon bunga bugenvil tempat burung bersarang dan tanaman serai untuk penghalau nyamuk. Di satu sudut yang selalu terlindung dari panas matahari aku bina sebuah meja bulat semen dengan payung serta bangkubangkunya. Di beberapa tempat yang sesuai aku susun dua puluh satu pacak lampu surya. Di sinilah tempat aku beristirahat pulang dari kerja, minum kopi panas dan makan cucur pisang atau cucur udang bersama istri. Inilah tempat favorit kami sekeluarga bersantai, bahkan anakanakku mengulang bahan kuliah di taman ini. Dapur, jika dibuka pintu seluasluasnya akan menyatu dengan taman ini. Sudah menjadi tabiatku jika aku makan buah aku akan membuang sisasisa seperti bijinya atau kulitnya di taman ini juga, sebagai pupuk untuk bungabunga dan pohonpohon perhiasan yang lain. Dua kali setiap bulan pada akhir pekan, aku dan istri meluangkan sedikit masa untuk memelihara taman ini; memotong dahandahan yang terlalu panjang, mengumpulkan daundaun yang mati dan sebagainya, membersihkan semen dan kolam ikan. Ketika memelihara taman inilah satu hari aku ketemu apel yang tidak habis kumakan tumbuh mengeluarkan bibit pohon. Biasanya jika aku
31
menemukan anak pohon buah yang tumbuh dari biji yang kubuang itu, ia akan kucabut dan pindah ke tempat lain. Kali ini karena ia buah apel aku membiarkannya saja tumbuh; jarang sekali pohon apel tumbuh di khatulistiwa. Tumbuhnya rendah, tidak melebihi pundakku, tapi teduh dan menjadi bagian dari dekorasi taman. Aku samasekali tidak menyangka yang pohon apel ini akan berbuah; ia berbuah dengan lebat, buahbuahnya berbentuk mungil, bisa dimasukkan sebuah keseluruhannya ke dalam mulut. Ketika buahbuahnya sudah mulai masak berwarna merah aku terhalang pula dari memetiknya karena ada seekor ular yang ujung ekornya melilit dahan dan ia tergantunggantung membentuk huruf 'U' dengan kepalanya mengacung ke depan dan lidahnya yang bercabang sentiasa terjulur julur. Aku mencoba menghalaunya tapi ia tidak mau lari. Kemudian aku terlihat ular itu melilit sebiji apel yang masak ranum, memulasnya sehingga buah itu jatuh. Buah itulah yang kupungut. "Thank you," kataku. Isteriku datang. Ia hanya berkain, sebelah atas badannya telanjang memamerkan buah dadanya. Tidak pernah istriku bertelanjang seperti itu, apalagi di luar rumah dan pada waktu siangsiang seperti ini. "Ada ular di sana, Bang," katanya. "Tapi ular yang baik. Sebentar tadi ia memetik sebuah apel untukku. Manis banget!" Ternyata ia yang duluan makan buah dari pokok apelku itu. "Aku juga dipetikkannya sebuah nih!" Aku memperlihatkan apel itu kepada istriku. "Coba abang makan," kata istriku. "Manis banget!
32
Enak banget!" "Apa buah ini bisa dimakan?" aku sekadarnya saja bertanya. "Iya," kata istriku. "Aku sudah makan tadi. Manis banget!" Isteriku merampas buah apel itu dari tanganku tapi sebelum ia sempat menyumbat apel itu ke dalam mulutnya, aku merampasnya kembali dan terus memakannya. Memang manis. Memang enak. Tidak pernah aku, sebelum ini, merasa apel seenak ini. Enaknya 100 kali lipat dari apel yang berjual di pasaraya atau di manamana. Enaknya tidak akan terpuaskan dengan memakan hanya sebuah atau dua buah saja. Aku menanggalkan bajuku. Aku dan istri mendekati pohon apel itu, duduk berjongkok menghadapnya. Ular itu melihat kami, kemudian ia menjatuhkan dua buah apel untuk kami. Kami memungut lalu memakannya. "Enak banget," kata istriku sambil menanggalkan kainnya. "Kalo dijual sebuah lima puluh ribu pun bisa laku nih." "Gak boleh dijual," kataku sambil melepaskan celana jeansku. "Panen pertama seharusnya disedakahkan ke tetangga atau ke masjid." "Rugi juga tuh kalau disedekahkan buah yang enak kayak gini," kata istriku. Memang ia pelit tentang buah yang enak. Kami makan beberapa buah lagi yang disodorkan oleh ular itu. Aku menanggalkan celana dalamku. Istriku juga menanggalkan celana dalamnya. Apabila anak dara remajaku masuk ke taman itu membawa buku untuk membuat ulang kaji, aku dan istri sudah bertelanjang bulat sepenuhnya dan kami tidak merasakan itu apaapa. Kami menoleh ke arahnya. Ia
33
menjerit melihat kami, ibu dan ayahnya sedang duduk berjongkok makan apel. "EI! TELANJANG!" serunya. "MALU! MALU! NGAPA BAPA MAMA TELANJANG GAK PAKEI BAJU! WHEI! " Aku dan istri tersentak, dan cepatcepat memetik beberapa daun apel untuk menutup alat kelamin kami. Daundaun itu terlalu kecil. Aku menyuruh anakku cepat cepat masuk ke rumah. Ia masuk dengan memalingkan kepalanya ke arah lain dan menutup mukanya dengan keduadua tangannya. Mungkin tidak lucu ketika anak daramu melihat kamu berdua telanjang bulat siangsiang bolong, tapi tidak ada apaapa yang dapat kita buat tentang kejadian yang sudah terlanjur seperti ini, selain pasrah dan melihatnya dari sudut lucunya dan menertawakannya. Memang tak terlalu buruk bagi isteriku tertangkap bertelanjang bulat oleh anak perempuan, berbanding aku ayahnya. Aku buruburu memakai celana dan menghumbankan kain kepada istriku. "Iya," kata istriku, "sebaiknya kita sedakahkan saja apel itu ke masjid." Hahaha!
34
17 MATI
T
emanku, yang tiga tahun tua dariku, Kakang Saufi, yang baru menikah tahun lepas, yang mati dua minggu lalu, datang ke rumahku, berselimutkan kain kafan putih yang bertanahtanah, aku tidak bisa bergerak atau bersuara. "Ga usah kaget Nizam," katanya dengan suara yang susah keluar, "ternyata aku masih hidup." Kemudian ia minta air dan sedikit makanan. Aku sebagai sahabat yang bujang menyajikannya apa yang ada saja: mie instant dan air dalam botol. Sebelum makan ia menadah tangan, dengan suara yang pelan, berdoa panjangpanjang sehingga aku merasakan panjangnya doanya itu seakanakan ia tidak jadi makan. Ia makan dengan penuh selera sehingga licin mangkuk tidak tersisa apa pun. Ia minum air tiga kali hirup sedikitsedikt untuk sekali teguk, sebanyak tiga kali teguk, air itu cuma air masak tapi ia meminumnya seolah olah air dari surga, dengan mata pejam penuh nikmat. Setelah itu ia berdoa panjangpanjang lagi sehingga membuat aku merasa bahwa yang mati hidup kembali memang begitu jadinya. Sedangkan sebelum kematiannya dulu ia anti orang yang berdoa panjang panjang, bikin lelah tanganku menadah, katanya, sengal sampai sepuluh hari. "Aaah Alhamdulillah," Kang Saufi mengalihkan pandangannya kepadaku. "Terima kasih, Nizam." "Panjang banget doanya Kang," kataku. "Dulu ga suka doa panjangpanjang. Apa ini ada hubungannya dengan pengalaman di dalam kubur?"
35
Ia tidak menjawab dan di kemudian hari ia tidak ingin merespond kepada pertanyaanpertanyaan tentang kematiannya. "Nizam," katanya. "Temani aku pulang ke rumah." Meski sudah aku desak untuk mandi dulu, ia bersikeras pulang ke rumahnya dalam keadaan aslinya keluar dari kubur, berselimut kain kafan yang bertanah tanah. Sepanjang perjalanan setiap langkah bibirnya kumatkamit entah apa dizikirkannya. Sampai di rumahnya, istrinya yang membuka pintu. Perempuan itu berdiri di situ, tidak bisa bergerak dan tidak bisa bersuara. "Ga usah kaget Mbak," kataku. "Ternyata Kakang masih hidup." Aku mencoba menjelaskan bahwa ini adalah suaminya yang mati hidup kembali. Lama sekali ia berdiri di pintu, wajahnya seperti tidak senang akan kedatangan kami. Kami disilakan masuk juga, meski dengan ragu ragu. Kakang Saufi duduk berdepanan dengan istrinya. Mereka hanya berpandangan. Istrinya sesekali memandang ke bawah kemudian kembali memandang kepadanya, wajah istrinya tampak jelas tidak senang. Mereka samasama diam. Kakang Saufi tenang saja. Kemudian ada orang masuk. "Sayang, aku sudah pulang," kata orang itu. "Siapa yang datang?" Istri Kakang Saufi bangun, tapi tidak pula pergi menyambut kedatangan orang itu. "Oh, suamimu," kata orang itu. "Kan dia sudah mati?" "Dia hidup kembali," kata istri Kakang Saufi, tampaknya masih tidak percaya. "Sertifikat kematiannya kan sudah dikeluarkan," kata
36
orang itu, memeluk istri Kakang Saufi. Kakang Saufi memandang ke arah lain. Isterinya mengambil satu amplop besar dan memberikannya kepada Kakang Saufi. Kakang Saufi mengeluarkan dokumendokumen di dalamnya, ternyata sertifikat kematiannya, dan klaim insuransi. Kakang Saufi menyimpan kembali baikbaik dokumendokumen itu ke dalam amplopnya, dan menyerahkannya kepada istrinya. Kakang Saufi bangun dan memandangku. "Kita pulang," katanya. "Kita berangkat pulang." Kita berangkat pulang, itulah katakata terakhirnya untuk beberapa bulan mendatang. Ia sepertinya tidak apaapa yang istrinya sudah punya pacar sebelum habis idah. Kalau aku, pasti aku marah, dan suruh mereka keluar dari rumah yang aku bina dengan uangku sendiri. Entahentah mereka sudah pacaran sebelum ia mati. Ia tinggal bersamaku, tidak berbicara apaapa makan hanya sekadarnya, ia lebih banyak berpuasa, dan salatnya hanya di masjid. Ia membersihkan area masjid dan sekitarnya. Ia tidak menganggu siapa. Satu hari ia memanggilku kerana ingin bicara, dan itu setelah tiga bulan tidak bicara. Ia duduk dengan melipat lutut dan menegakkannya sehingga keduadua telapak kakinya menjejak lantai, keduadua tangan merangkul lututlututnya. Ia menatap ke depan seperti tidak melihat apaapa. "Nizam," katanya. "Hidup ini adalah tidur. Ketika kita mati kita terjaga." Kemudian ia tidak bicara lagi selama beberapa bulan.
37
18 MULUT
A
pabila Agam, lelaki berusia 45 tahun, berdahi luas berambut nipis keriting yang hidupnya selama ini biasabiasa saja yang bicaranya tiada sesiapa peduli, bocah berusia lima tahun saja tidak peduli, apalagi orang orang dewasa yang berakal, masa bodoh kata mereka si jembel anak luar nikah dan kampungan apa tahunya, cari bini saja tidak tahu dan tidak laku, pada pagi yang dingin karena hujan yang sudah turun berterusan selama dua puluh hari, dua puluh jam, dua puluh menit, dua puluh saat, dan seakanakan tidak akan pernah berhenti, pada pagi yang gelap seperti baru saja mau malam, pada pagi muram yang ayam jantan di desa itu gagal berkokok, pada pagi yang burungburung tidak berkicau, dan ia, jika bisa, tidak mahu bangun sampai besok lagi, tetapi ia harus bangun juga, harus bangun segera karena berasakan ada sesuatu di sendi kaki kanannya yang membuatnya gelisah tidak selesa, berputar ke kiri, berputar ke kanan, lalu ia yang masih di dalam selimut yang sudah tidak dicuci selama sepuluh tahun, dua bulan, tiga minggu, lima hari, menghulur tangan kanannya ke bawah, hujung jarijarinya menyentuh sesuatu yang lembut seperti jamur menempel atau baru tumbuh akibat kelembapan udara di situ, langsung ia menyiahkan selimutnya yang berbau apak ke tepi, bertelanjang bulat, bergegas bangun dan melihat ada mulut di sendi kaki kanannya itu. Mulut itu tersenyumsenyum manis padanya. Agam memejamkan mata. Agam membuka matanya semula. Ia memandang ke mulut di sendi kaki kanannya.
38
Ini diulanginya beberapa kali untuk memastikan bahawa mulut yang tumbuh di sendi kaki kanannya itu bukanlah halusinasi mainan hari hujan renyairenyai dan cuaca yang berterusan seperti malam, dingin dan lembap. Tanpa mandi, tanpa cuci muka, tanpa menyikat gigi, Agam memakai baju dan celana khaki baru bercuci dan berseterika untuk ke warung Mas Sunardi dan istri, meredah hujan dan jalan yang becak dan basah. "Mas," kata Agam, "ada mulut di kakiku." Mas Sunardi yang selama ini tidak pernah peduli pada Agam, ia yang sedari tadi menunggu pelanggan yang sejak bermulanya cuaca buruk ini tidak lagi ramai datang karena orang malas keluar menghadapai basah dan becak atau yang sudah keluar tidak punya masa untuk minum di warung karena telat bangunnya, kali ini kaget melihat Agam berpakaian seperti mau menjemput pacar. "Sejak kapan kaupacaran Agam?" kata Mas Sunardi senyumsenyum. "Bukan Mas," kata Agam memamerkan kaki kanannya. Ia duduk dan meletakkan kaki kanannya di atas meja. "Ada mulut di kakiku." Mas Sunardi yang kalau bicara, bicaranya tidak putus putus itu melihat ke kaki Agam, terus saja terdiam, ada sesuatu tentang bibir yang mungil dan mulus itu yang buat ia tibatiba berasa rindu dan berbungabunga di hatinya. Kemudian dengan pelanpelan ia bertanya: "Boleh aku sentuh?" Tanpa menunggu izin dari Agam, selama ini tiada sesiapa juga pernah menunggu izinnya, Mas Sunardi menyentuh mulut tersebut dan bibir itu senyum padanya dan bibir itu seperti mengisap hujung jari telunjuknya itu. Ia memasukkan lagi sedikit jari telunjuknya ke dalam
39
mulut itu dan terasa satu aliran listrik menjalar dari jarinya menuju ke penisnya lalu impotensi sepuluh tahunnya terus saja hilang, mengakibatkan ereksi yang sukar untuk disembunyikan, saat itulah istrinya keluar mau tau apa saja yang bikin suaminya lamalama di situ, melihat mulut itu ia tibatiba saja dapat membaca pikiran suaminya lalu timbul rasa cemburunya, ia mengambil yang kebetulan mangkuk bekas soto bakso sapi yang ada di atas meja. Mangkuk itu dihentakkannya ke kepala suaminya sehingga pandangan suaminya itu berbintang bintang. "Dasar lelaki otak mesum," katanya namun ia berterima kasih juga sebelas bulan kemudian ternyata ia bunting dan melahirkan anak perempuan yang normal dan imut. Orang lain yang ada di warung itu ikut berkerumun mau tau apa yang diributributkan oleh pasangan suami istri yang setahu mereka tidak pernah bercekcok itu, bukannya mereka tidak terdengar apa yang dikatakan Agam, dengan jelas sekali mereka mendengar, ada mulut di kakiku, tapi tuh siapa mau peduli bicara si Agam, mereka mau tau apa sebenarnya lagi ulah si sinting ini yang buat suami isteri ribut, tetapi apabila mereka melihat mulut imut di kaki Agam itu para lelaki tibatiba berasa rindu, alangkah kalau wanitawanita mereka punya bibir semugil itu dan semulus itu, dan para wanita berasa cemburu karena mereka tibatiba saja dapat membaca pikiran lelaki mereka, untuk jatuh cinta pada wanita cantik yang lebih cantik dari mereka itu bisa difahami tetapi untuk jatuh cinta pada kaki si Agam, ini sudah keterlaluan, masa kami dibandingbandingkan dengan kaki si Agam yang mandinya saja kali cuma sebulan sekali, lalu mereka menariknarik lengan lelaki
40
mereka supaya segera meninggalkan warung itu, tetapi para lelaki tidak ada yang mau pergi, apalagi ketika ini mulut di kaki Agam sedang memunjungmunjung seperti munung itik dengan lidah diulurkan sedikit seperti gaya yang keren di fotofoto selfi di medsos yang bukan saja gadis remaja melakkukannya bahkan remaja lelaki juga ikut imutimutan. Begitu cepat tersebarnya, lewat sms dan medsos, foto berbagai ragam mulut mungil di sendi kaki Agam, mulut bibir tercantik yang hanya bisa dipercaya dengan melihat sendiri, yang tumbuh di kaki Yang Berbahagia Mas Agam, datanglah medekat ke mari untuk melihatnya, sehingga orang mulai berdatangan meredah hujan renyairenyai, tidak peduli pada basah dan jalan becak, barangkali ini lebih menarik dari peristiwa Bu Item melahirkan anak buaya putih tiga bulan dua hari yang lalu yang mereka harap bisa mengobati penyakit yang ternyata tidak juga, atau lebih menarik dari peristiwa orang mati hidup semula setahun lima bulan yang lalu yang juga tidak bisa mengobati apaapa penyakit, semua orang mau sihat tapi penyakit lebih mencintai kita dan biaya jumpa doktor dan perawatan itu mahal sekali dan hanya untuk orang kayakaya karena kesihatan itu khusus milik orang kayakaya, iya semua datang, yang tua datang bertongkat, yang lemah dipapah, anakanak berlari duluan, dari datuk ke kakek ke bapak ke anak ke cucu, lelaki dan perempuan, tantetante, omom, mari mari ke mari, kita saksikan fenomena ajaib ini, tiada sesiapa yang mau tertinggal malah yang buta juga ikut ke sana dipimpin yang celik, mana tau mulut itu bisa mengobati buta sejak lahir seperti ia mengobat inpotensi Mas Sunardi, tapi mereka mendapat tahu juga kemudian bahawa mulut itu tidak bisa mengobati apaapa penyakit,
41
dan kasus anu Mas Sunardi kembali ereksi selepas sepuluh tahun itu hanyalah kebetulan saja, malah ibuibu berasa kesal karena suamisuami dan anakanak lelaki mereka tanpa selindungselindung lagi jatuh cinta sama mulut di kaki si Agam dan ini lebih parah dari kaum Lut. "Orang sinting bikin semua orang sinting," kata seorang ibu. "Harusnya kaki itu diamputasi saja dan dikasih makan sama buaya putih anak Bu Item." Kejengkelan para ibu tidak bisa menghalangi media masa datang untuk mewawancara Yang Berbahagia Agam untuk tv, koran dan majalah. Ia sudah masuk tv sebanyak 63 kali dalam masa satu minggu. Agam tidak menjawab apaapa soalan dari jurnalis dan tukang wawancara tapi kakinyalah yang bicara. Bicaranya petah, lancar seperti hujan turun, seperti air yang mengalir meliukliuk di selokan, sentiasa bersedia untuk memberikan pandangan dan pendapat bagi apa saja isu yang diutarakan kepadanya, baik itu politik, budaya, sastra, sosial, ekonomi, sampai kepada prediksi sepakbola domestik, piala dunia, Liga Inggeris, La Liga Sepanyol, meski tidak pernah benar, orang tetap juga mahu mendengarnya. Agam diam saja dengan senyumnya. Ia tidak ikut campur urusan kakinya. "Aku, aku," katanya. "Kakiku, kakiku." Hanya sekali ia bicara apabila ditanya pandangannya tentang kakinya yang sok pintar itu. "Masa bodo," kata Agam seolaholah ia sudah lama menunggu soalan ini diajukan kepadanya, dan seperti sudah lama ia mau menjawabnya. "Dulu tiada sesiapa mau peduli bicaraku orang sinting si jembel kampungan anak haram jadah." Ia memandang tajam ke depan dengan senyum yang
42
halus. "Sekarang sedunia mau mendengar omongan kakiku."
43
19 KENCAN SAMA ISTERI DI RUMAH BARU
D
iam di rumah mertua aku tidak betah. Diam di rumah ayahku, istriku tidak betah. Oleh karena masalah ini, kami tangguhkan dulu untuk punya anak sehingga punya rumah sendiri. Akhirnya kami punya rumah sendiri juga. Aku berencana meniduri rumahku yang sedangsedang besarnya pada malam ini. Istriku menolak apabila kuajak sama, karena ia punya halhal yang bersangkutan dengan kerjanya sebagai bu guru yang tidak bisa ditangguhkan, dan besok ia punya kelas ekstra untuk muridmurid bermasalah. Aku dan istri akan berpindah sepenuhnya mungkin dalam masa dua minggu lagi. Aku ke sana dengan motor, dan sampai hampir hampir waktu maghrib. Aku tinggalkan mobil untuk kegunaan istriku, nanti besok biar ia nyetir sendiri. Besok aku mahu membersihkan kawasan rumah yang baru kami beli ini. Bagi rumah yang punya lima kamar tidur, dua di bawah dan tiga di atas meskipun harga yang telah ditawarkan lebih sedikit dari tabungan kami berdua, namun amat sukar untuk kami lepaskan. Ini rumah mahal dengan harga yang murah. Sejurus selepas aku solat Isya listrik mati. Rumahku gelap. Aku tidak berbekal lampu suluh atau dian, malah pemetik api juga aku tidak punya. Untuk tidur, ini terlalu awal. Aku duduk di beranda di lantai atas menikmati sepoi angin malam. Sunyi dan sepi hanya ditemani bunyi jangkrik dan gongongan anjing di kejauhan. Mujur nyamuk tidak ada untuk menganggu ketenteramanku.
44
Sebuah mobil masuk di pekarangan rumah. Itu istriku datang. Aku cepatcepat ke bawah membuka pintu. Ia masuk senyumsenyum nakal. "Katanya tadi lagi sibuk," kataku. "Cuman mau ngintip, janganjangan abang bawa cewe lain," katanya. "Gak adalah," kataku dengan gembira melihat ia datang. "Mukaku kayak beruang siapa mau." Malam itu aku kencan sama isteriku penuh romantis di rumah baru. Kami samasama mematikan hp supaya tidak diganggu. Kami berbulan madu di setiap kamar, berkucupan, berpelukan, bergaul suami isteri dengan intens seperti pada malam pertama. Kata istriku ia sudah satu minggu tidak mengambil kontraseptif. Kami tertidur keletihan di kamar tamu di lantai bawah. Aku bangun kesiangan, capek, tenagaku belum pulih sepenuhnya. Istriku sudah pergi, seperti katanya, ada kelas ekstra. Aku menghidupkan hp, terus saja masuk panggilan dari istriku. "Abang di mana semalam? Kenapa hp dimatiin? Siapa dengan abang di sana? Hah siapa? Siapa? Hah, ngapa diam?" Kemudian aku terdengar bunyi hilaian tawa yang memanjang dari dapur. Aku melihat tubuhku penuh dengan gigitan berahi.
45
20 MAKAN
S
udah lima ratus lima puluh lima hari hujan renyai renyai turun di desa Suring yang berpenduduk seribu lima ratus tiga puluh orang itu. Mereka sudah terbiasa mendengar bunyi tik tik tik tik hujan menimpa atap, daun serta tanah. Bunyi tik tik tik itu masuk ke dalam otak, ke dalam hati, dan akhirnya menjadi sebagian dari kehidupan mereka tanpa disadari, dan sekarang ditambah lagi dengan suara katak dan kodok yang bersahutsahutan, mulamula suara seekor dua disusuli perlahanperlahan oleh suara yang semakin ramai sehingga seluruh desa bergema dengannya, kemudian katakkatak itu berhenti, tibatiba sepi hanya kedengaran bunyi tik tik tik hujan, sebelum katakkatak itu mengulangi semula kroakkroak mereka seperti satu orkestra. Penduduk desa betah dudukduduk di dalam rumah menanti hujan itu berhenti dan katakkatak yang semakin ramai memenuhi laman rumah itu lari. Mereka hanya keluar sekali sekala, dan pada hari ke seratus hujan itu turun mereka sudah malas hendak keluar keluar rumah lagi. Jalan raya tidak berorang. Seekor anjing berjalan merundukrunduk, basah kuyup menuju ke warung Mas Sunardi. Mas Sunardi melemparkan seketul lumayan besarnya ayam goreng kepadanya. Anjing itu berhenti. Ia menghiduhidu daging tersebut. Anjing itu mengangkat kepala memandang Mas Sunardi seolaholah mau mengatakan: masa bodo. Ia tidak memakan bahkan tampak tidak menyentuh ayam goreng itu.
46
Wof. Wof. Ia meneruskan perjalanannya dengan kepalanya merunduk dan bergoyang sedikit ke kiri ke kanan, cuba mengelak dari terinjak katakkatak yang memenuhi jalan raya. Mas Sunardi melihat saja anjing itu pergi sehingga anjing itu jauh dan tidak tampak lagi. Mas Sunardi menjenguk ke dapur melihat istrinya duduk dengan wajah yang murung seperti orang yang kehilangan kerja. Ia memanggil istrinya dengan lembut dan menyuruhnya menyediakan bahanbahan untuk seratus mangkuk soto bakso sapi. "Kita akan bikin soto bakso sapi yang paling enak sedunia," katanya dengan serius matanya bersinar. Dengan bingung istrinya memandang warung yang kosong itu kemudian ia memandang muka suaminya. Sudah lama ia tidak melihat sinar mata suaminya seperti itu, ini tandanya ia baru mendapat inspirasi resepi baru yang hebat tapi siapa akan memakannya? "Jika orang tidak datang ke mari," kata Mas Sunardi membaca pikiran istrinya, "akulah yang akan mendatangi rumah mereka. Tidak akan bisa mereka menolak." Tengah hari itu, cuaca seperti awal pagi yang berterusan, suram, hujan renyairenyai, udara dingin, Mas Sunardi dengan mengenakan jas hujan, menolak gerobak dorongnya dari rumah ke rumah menjaja soto bakso sapi, melaunglaung dengan lantang akan jajaanya sehingga katak kekagetan dan terdiam, soto bakso, soto bakso sapi, resipi terbarunya yang ringkas tapi terbaik, seperti biasa setiap resepi barunya adalah yang terbaik dan paling enak, dimasak dengan suhu api tertentu, yang katanya itulah rahsia masakannya suhu api. Katakkatak di jalan raya mengelak dari terkilir roda gerobak atau terinjak kakinya. Katakkatak itu seperti
47
mengiringinya ke mana ia pergi tapi mereka tertinggal juga di belakang dengan suara yang sudah tidak teratur lagi. Rumah pertama yang dimampirinya seperti tidak ada orang di dalam, tapi Mas Sunardi terus memanggil dan mengetuk pintu, apabila tidak ada jua jawapan ia menolak pintu yang tidak berkunci itu, yang memang di desa ini ratarata penduduknya tidak pernah mengunci pintu, karena kami orangorang miskin tidak punya apa apa untuk dicuri, dan kalau kau maling adalah lebih baik kaupergi ke desa sebelah karena di sana mereka punya sedikit harta, namun mereka juga masih rakyat miskin tidak terlalu lebih baik dari kami, dan adalah membuang masa mencuri dari orangorang miskin. Mas Sunardi mendapati penghuni rumah itu tidur atau separuh tidur. Mereka semua baring di atas lantai tanpa alas. “Siapa?” “Aku Mas Sunardi. Jaja soto dari rumah ke rumah.” “Makasih aja ” jawab suara seorang lelaki dengan malas. “tapi kami tidak lapar, Mas.” Lelaki itu tidur semula, sementara yang lain tidak bergerakgerak. Di rumah kedua Mas Sunardi terlihat sepasang suami isteri sedang dudukduduk di pintu melihat hujan turun dan halaman rumah dibanjiri katak. Mas Sunardi menolak gerobak dorongnya ke halaman dengan tidak sabar sehingga beberapa ekor katak tidak sempat mengelak lalu terkilir roda. Mas Sunardi senyum pada dua suamiisteri itu sambil mengangkat tangan kanannya dan memberi salam. “Soto Pak,” kata Mas Sunardi. “Hangathangat, cocok banget, untuk cuaca begini.”
48
“Kami tidak lapar, Mas. Makasih aja.” Tiada sesiapa yang mahu soto bakso sapinya, ia telah menurunkan harga, semakin jauh jalannya semakin besar diskaunnya, dan akhirnya ia menawarkan soto itu gratis, tapi tetap saja di setiap rumah yang disinggahinya katakata yang sama atau hampirhampir serupa didengarnya: “Kami tidak lapar, Mas. Makasih aja.” “Makasih Mas, kami tidak lapar. Gak ada selera.” “Pasti enak tuh Mas, sotonya, tapi kami tidak lapar Mas. Makasih aja." Setelah tiga puluh satu buah rumah, sotonya tidak laku, Mas Sunardi mahu berpatah balik apabila ia terlihat di beranda sebuah rumah yang sedikit condong, seorang ayah sedang bermain catur dengan anaknya. Mas Sunardi singgah dan menawarkan soto bakso sapinya dengan agresif. “Gratis nih pak sotonya,” kata Mas Sunardi. “Ambillah, makanlah semaumaunya. Gratis!” “Maaf Mas, makasih saja. Kami tidak lapar.” Mas Sunardi mengalihkan perhatiannya kepada bocah yang dahinya berkerutkerut sedang berpikir keras menghadap papan catur. “Dek, berhentilah main catur,” kata Mas Sunardi. “Makan soto dulu. Gratis. Bahkan jika kaumakan habis satu mangkuk aku akan bayar kau duaratus ribu.” Bocah sekolah dasar yang tidak lebih lapan tahun usianya itu, yang empat puluh lima tahun akan datang, ketika ia dipilih jadi presiden dan kemudian berkuasa selama tiga belas tahun sehingga dikudeta itu, akan ingat hari ini, apabila ia berhenti sekejap dari bermain catur dengan ayahnya, mengangkat kepalanya memandang Mas Sunardi, dengan pandangan yang
49
tajam, terganggu dan sedikit bingung, karena mengapa orangorang dewasa tidak mau pahampaham juga. “Bung,” katanya seperti orang dewasa yang sudah hilang sabar. “Kami bukan orang kaya. Hanya orang kaya makan. Kami orang miskin. Orang miskin tidak butuh makan.” Mas Sunardi kaget, karena sama sekali tidak menduga akan dijawab oleh seorang bocah SD sebegitu rupa. Mas Sunardi menolak gerobak dorongnya keluar dari halaman rumah itu ke jalan raya yang basah, kosong manusia, penuh dengan katak yang bising, yang hanya diam kalau ia melaunglaungkan: “Soto bakso sapi gratis! Soto bakso sapi gratis!” Perlahan sekali ia menolaknya. Ia berpikirpikir dan mulai teringat bahawa ia dan istri juga sudah satu minggu tidak makan apaapa, tidak berasa lapar, satu minggu lupa makan. Tidak ada kemahuan untuk makan. Sama sekali tidak ada. Seperti orang insomnia yang tidak ada kemahuan untuk tidur. Mungkin saja ini efek hujan terusmenerus dan suara kroakkroak katak yang tidak berhentihenti meresap ke dalam jiwa dan otak seperti meresapnya air hujan ke dalam tanah. Sampai di rumah, istrinya sudah menunggu dengan pertanyaan apa sotonya laku atau tidak, yang dijawabnya dengan malas, dikasih gratis bahkan dibayar untuk makan saja orang menolak apalagi kalau dipinta bayar, setiap orang di desa Suring ini tidak berasa lapar lagi, mereka semua sudah lupa makan, yang membuat istrinya sangat khawatir akan nasib perniagaan mereka. Hidup mereka akan jadi payah. “Apa yang hendak kita makan nanti?” tanya istrinya Mas Sunardi mengulangi katakata bocah bakal persiden empat puluh lima tahun akan datang, yang bermain catur dengan ayahnya di beranda rumah yang
50
sedikit condong. “Orang miskin,” kata Mas Sunardi, “gak butuh makan.”
51
21 NO MORE WARS
A
KU mendorong troli yang penuh. Saat mahu membayar belianku, kasir memberitahu bahwa semua barangbarang di supermarket ini gratis mulai hari ini. “Ambil saja Pak, manamana yang dibutuhkan. Gratis,” katanya. Aku sedikit bingung. “Jadi,” kataku, “supermarket ini akan tutup?” “Tidak Pak,” katanya. “Kami akan buka jualan seperti biasa setiap hari tapi semuanya gratis.” “Jadi,” kata orang yang setelahku, “mengapa kami harus antrean untuk membayar?” “Oh,” kata kasir, “silakan Mas, silakan jalan saja terus ke exit.” Sebelum keluar kami dikumpul dan diberi penerangan oleh seorang CEO, yang aku kurang faham, katanya uang sudah tidak digunakan lagi, money is the root of all evil, uang adalah punca segala kejahatan, katanya. Uang hanya akan membedakan dan membikin jurang antara yang kaya dengan yang miskin; itu aku faham seratus persen. “Mulai hari ini,” kata CEO itu, “Otoritas Tertinggi Kewangan Dunia mengisytiharkan uang dihapuskan.” “Jadi bagiamana dengan uang yang aku tabung di bank bertahuntahun itu?” aku bertanya. “Tidak ada gunanya lagi,” katanya. “Kalau tidak percaya pergilah ke bank.” Aku ke bank. Aku keluarkan kesemua uangku. Kasir wanita manis senyum kepadaku. Ia menawarkan untuk
52
menambah berapa kali ganda yang aku mahu di atas jumlah uangku itu. “Jadinya,” kataku, “bank ini akan ditutup?” “Iya,” katanya. “Tidak akan ada bank lagi di seluruh dunia.” Ketika aku keluar dari bangunan bank itu aku terlihat puluhan orang juga sepertiku memikul satu atau dua karung uang. Terasa berat dan sakit bahuku. Aku ke satu tempat; ada seorang pengemis sahabatku yang hampir hampir setiap pagi aku berbagi makanan dan kopi. Kadangkadang jika aku tidak sibuk aku duduk sarapan bersamanya di situ; di bawah jambatan batu. “Selamat siang Mas Nizam,” katanya sebaikbaik saja melihat aku datang. “Apa ada di dalam kantung itu Mas?” “Uang,” kataku. “Mau?” “Ga mau Mas,” katanya. “Makasih aja.” Selama aku hidup, inilah kali pertama aku ketemu pengemis menolak uang. Ia mengajak aku makan siang di warung seberang jalan yang terbilang enak baksonya. Aku tampak tumpukan pakaian baru di sisinya, sementara ia masih lagi dengan pakaian pengemisnya. Seolaholah tahu apa yang kupikirkan ia mejelaskan; kesemua pakaian itu sudah dicobanya tiada satu yang cocok dengan perasaannya, jadi ia memakai semula kameja dan celana pengemisnya yang compang camping. “Aku butuh waktu menyesuaikan diri,” katanya sambil melihat tumpukan salinan pakaian yang barubaru kesemuanya. Di tepi tumpukan itu aku terlihat seekor tikus gemuk bermainmain dengan seekor kucing.*(¹) Sampai di warung seberang jalan, pengemis ini memberi salam dengan penuh semangat, orang menjawab salamnya dengan semangat juga.
53
“Pamirsah,” katanya, “silahkan pesan makanan lagi, saya si Pengemis traktir semuanya hari ini.” Semua orang tertawa. Ternyata pengemis sahabatku ini punya bakat ‘standup comedian’ juga. Dulu ia selalu bilang kepadaku; “Dunia ini sudah penuh dengan comedian, tapi ga seorang pun yang lucu”. Penghapusan uang kemudian disusuli deklarasi pemerintah kuasakuasa besar dunia bahawa peperangan di kesemua rantau (yang bergolak) akan segera dihentikan, dan mereka tidak lagi akan campur tangan, baik secara sembunyisembunyi maupun terang terangan, di manamana negara pun di dunia ini. Oleh sebab uang sudah dihapuskan tidak ada apaapa kepentingan lagi untuk mereka campur tangan. Amerika memohon maaf karena telah mecampuri urusan domestik banyak negara: Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, China, Colombia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait,
54
Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Palestine, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain,Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, TimorLeste, Togo, Tonga, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda,Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe ... dan komited akan membangun negaranegara yang telah hancur. Malah ia juga meminta maaf kepada dirinya sendiri United States of America. Ia memanggil pulang kesemua agen spionasenya dari seluruh dunia. “I swear there wil be no more wars,” kata Presiden Amerika. “We will live in peace and posperity forever.” *(²) notakaki: *(¹) Hewan juga tibatiba saja berbaikbaik sesamanya. Singa, macan dan lainlain hewan predator tidak lagi makan daging, cuma makan buah, pucuk, daundaun dan rumput. Malah ada singa betina
55
yang baru melahirkan membiarkan anak zirafah ikut menetek. Buaya makan kulitkulit kayu. *(²) ”Aku bersumpah tidak akan ada lagi peperangan,” kata Presiden Amerika. “Kita akan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran untuk selamalamanya.”
56
22 ANAK KUCING BELANG TIGA
A
da anak kucing belang tiga, hitam, putih dan jingga, terperangkap di atas dahan yang tinggi. Karena takut jatuh, ia tidak bisa bergerak hanya kepalanya bergoyang sedikit. Meownya yang halus kedengaran seperti minta bantuan. Mungkin ia telah dikejar anjing dan dalam ketakutannya ia telah tidak sengaja memanjat pokok sampai setinggi itu. Kucing tidak ada masalah panjat pokok. Turun itu yang jadi masalah besarnya. Aku suka kucing, begitu juga beberapa orang lain yang sudah terkumpul di situ; mereka semuanya pencinta kucing. Tiada seorang pun dari mereka yang bisa panjat pokok. Terpaksa aku yang panjat. Aku panjat pokok itu pelanpelan. Mencari tempat berpijak dan coba mengelak dari digigit semut merah. Aku tidak suka panjat pokok. Aku panjat pokok hanya kalau terpaksa seperti sekarang ini. "Hatihati Mas," pekik seorang perempuan yang sudah berjanji akan kencan bersamaku nanti jika aku menyelamatkan anak kucing itu. "Be my hero." Dengan susahpayah, dua kali kakiku nyarisnyaris tergelincir, aku sampai juga di dahan yang tinggi itu. Aku menghulurkan tangan kananku untuk mengambil anak kucing itu. "Meow," kataku dengan lembut membujuk. "Mari sini, meow. Mari." Anak kucing itu tidak bergerak. Aku berinsut perlahan di atas pantatku, mendekat kucing itu. Apabila sudah dekat aku pun mengambilnya. Keras dan kaku. Ini kucing mainan. Di perutnya ada label Made in China. Aku
57
membanting kucing boneka itu ke bawah. "Maaaas!" pekik perempuan bakal kencanku melihat anak kucing belang tiga itu melayang ke bawah. "Mas dzolim! Mas kejam!" Entah setan mana yang gila panjat setinggi ini hanya untuk menganiaya pencinta kucing sepertiku.
58
23 KISAH SEEKOR ELANG
B
ukit itu dibuldoser pada waktu pagi. Pokok kayu tua yang tinggi itu tumbang. Maghrib sore, seekor elang berkelilingkeliling mencari sarangnya yang hilang.
59
24 MONYET
A
ku bangun mendapati diriku adalah seekor monyet pagi ini. Monyet jantan yang berahinya sedang tegang menongkat mencari monyet betina. Di kota sesak dengan kenderaan tidak putusputus mengeluarkan asap hitam; tidak berhentihenti hirukpikuk klakson memekakkan telinga; yang hidup dan yang mati berbaur: tidak ada monyet lain di sini, yang ada hanya manusia.
60
25 SEHAT
K
emarIn awalawal pagi ia ziarah aku di rumah sakit. Katanya ia baru tau aku sakit. Sudah dua minggu aku di sini. Maaf katanya. Tidak apaapa kataku. Sakitku hanya sakit biasa saja, penyakit orang menjelang tua. Aku sepuluh tahun tua dari dia. Ia 45 tahun. Mukanya lebih muda dari umurnya, berbanding aku yang tampak lebih tua dari umurku dengan rambutku yang beruban dan nipis. Aku selalu sakit yang bukan penyakit sebenarnya; pegal linu, encok, darah tinggi. Katanya itu penyakit orang kaya. Alhamdulillah, kataku. Kurang senam dan terlebih makan. Makanlah selagi bisa makan aku berfilosofi. Ia tersenyum kemudian tertawa kecil. Ia tidak kurus dan tidak juga gemuk, sejak dulu lagi ia begitubegitu saja. Rambutnya tebal dan hitam. Aku menyuruhnya mencari isteri. Tidak bagus, kataku, lelaki membujang lamalama. Ia duduk di kerusi di sebelah kanan kasurku dan menandah tangannya berdoa agar aku cepat sembuh. Aku mengaminkan dan mengucapkan terima kasih kepadanya, kemudian aku berdoa untuknya agar ia cepatcepat mendapat jodoh. "Ya Allah," kataku, "berilah sahabatku ini jodoh bidadari dari syurgaMu." "AmIn, amIn, amIn," katanya. "Ya Rabbul Izzati, ya Khairal Masulin, ya Mujibaddaawaat, ya Qadialhajat." Ia menyalami dan mencium tanganku, mohon maaf karena harus permisi. Sore itu aku diizinkan keluar dan pulang ke rumah. Besoknya awalawal pagi aku menerima berita bahawa kawanku itu meninggal dunia. Aku segera ke
61
rumahnya. Tiba di halaman rumahnya aku tercium bau kasturi yang semerbak. Dari ceritacerita yang dapat aku kutip, ia meninggal dunia di dalam sujud ketika solat tahajjud.
62
26 SI PELUPA
S
ollehuddeen adalah kawanku yang paling pelupa. Saat samasama bersekolah dulu, dia tertinggal dua tahun dalam pembelajaran. Kami, temantemannya, berusaha membantunya karena rasa kasihan. Pelupanya itu bukanlah karena dia makan kepala ikan atau alasan gizi yang lain, dia menjaga makan minumnya: dia sedaya upaya makan makanan yang bisa membantu daya ingat, kismis, biji almond, madu, kurma, habbatus sauda, ginko; dia tidur sekejap waktu siang; dia mengelak dari tidur waktu Asar dan setelah solat Subuh. Dia tidak pernah peduli akan sifat pelupanya ini, misalnya ketika hendak menghafal rumus matematika dia akan melakukannya dengan sungguhsungguh; dia akan hafal sekejap kemudian lupa lagi dan mulai menghafal lagi. Pada waktu malam, seminggu dua kali, kami belajar membaca AlQuran di rumah seorang ustaz. Ketika pulang dari belajar inilah Sallehudin menyatakan hasratnya. "Aku mau menghafal AlQuran 30 juz." Aku memandang wajahnya. Aku tahu dan dia sendiri tahu yang dia pelupa. Aku tahu dia bersungguhsungguh dan bukan bercanda; dia seolaholah mengatakan: aku tidak akan mengalah. Pada kelas berikutnya dia menyampaikan keinginannya itu kepada ustaz. "Baguslah," kata ustaz. "Pasang niat sudah dapat pahala tinggal disertai usaha lagi. Sebelum menghafal luruskan bacaan dulu. Baca di depanku, jika aku kata OK baru mulai menghafal. " Ustaz pun mengajak kami semua ikut menghafal
63
mulai dari surahsurah pendek dalam Juz Amma; dari surah AdDuha. "Ga hafal 30 juz, setidaknya hafal surahsurah pendek Juz Amma pun Alhamdulillah," kata ustaz. "Tergantung kemampuan masingmasing." Kami pun memulai proses menghafal: membaca dengan benar, memahami hukum tajwid ayatayat yang akan dihafal, kemudian baru menghafal. Setelah setahun aku dan kawankawan lain hafal seluruh surahsurah pendek Juz Amma dan beralih menghafal surah As Sajda (atas perintah ustaz), Sollehuddeen masih menghadapi kesulitan menghafal Wad Duha (surah Ad Duha). Meskipun sulit dia tidak juga mau mengalah. Hafal ayat baru lupa ayat sebelumnya. Dia selalu menjaga whuduknya karena pada setiap kesempatan dia akan menghafal. Kami temanteman yang membantunya pula merasa susah hati melihat dia bersusahpayah mencoba menghafal dua tiga ayat. Bahkan dia menyalin ayat yang akan dihafal itu di dalam sebuah buku khusus. Kami yang melihatnya pula merasa kesulitan sementara dia nampak rileks saja. "Solleh," kataku, "kau ini udah tau pelupa banget tapi mau juga menghafal." "Iya," kata kawanku yang lain. "Apa itu ga menyusahkan?" Sollehuddeen memandang kami dengan tajam. "Pelupa itu satu hal," katanya. "Menghafal AlQuran satu hal lain yang gak ada hubungannya. Kalau aku terpaksa mengambil sepuluh tahun atau labih menghafal WadDoha, insya Allah aku akan ambil sepuluh tahun atau labih itu." Begitulah dia menghafal surah AdDuha, sedikit demi sedikit, membaca, kemudian menyalin berulang kali ayat
64
yang akan dihafal, dengan bantuan tafsir perkata, di bawah setiap kata ditulis pula maknanya. Aku dan teman teman lain selesai menghafal surah AsSajda dan atas perintah ustaz beralih menghafal surah Yasin pula; Sollehuddeen baru selesai menghafal surah AdDuha (tidaklah dia mengambil waktu sepuluh tahun lebih, cuma satu tahun lebih) dan dia beralih menghafal surah AlInsyirah sambil terus menjaga surah AdDuha agar tidak lupa. Dia mengambil dua kali lebih lama menghafalnya. Aku dan temanteman selesai menghafal surahsurah AsSajda, Yasin, AdDukhan, ArRahman, Al Waqiah, AlMulk, AlInsan dan mulai hendak menghafal juz 30 keseluruhan, Sollehuddeen masih bekerja keras dengan dua surah itu (AdDuha dan AlInsyirah) tapi dia tidak pernah mengalah. Aku hanya sempat menghafal bagian dari juz 30 selain dari surahsurah yang dihafal sebelumnya dan tidak meneruskannya lagi karena kesibukan bekerja. Setelah beberapa tahun berpisah aku ketemu kembali dengan Sollehuddeen di sebuah masjid. Dia membacakan kepadaku surah AdDuha, surah Al Insyirah dan surah AtTiin dengan tartil. Dia mengeluarkan selembar kertas kosong dari tas yang dibawanya dan mulai menulis surah AdDuha dan surah AlInsyirah dengan tulisan khat yang cantik beserta makna setiap kata di bawahnya tanpa merujuk pada mushaf. Dia memberikan kertas itu kepadaku untuk kubaca dan aku meminta untuk menyimpannya sebagai kenangan. Katanya dia sekarang dalam proses menghafal surah AlAlaq ayat pertama. "Iqra 'bismirabbikal lazii khalaq," katanya. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan."
65
Meskipun pelupanya tetap tegar, namun kecekalannya tidak pernah luntur. "Aku akan terus menghafal sampai habis 30 juz," katanya. "Insya Allah." Itulah kali terakhir aku bertemu dengannya karena dia meninggal dunia di usia 33 tahun saat liburan di kampungnya. Jenazahnya dibawa ke masjid karena orang yang datang ingin mensalatinya terlalu ramai, sehingga masjid juga penuh. Orangorang ini banyak yang aku tidak kenal, dengan bau harum yang seni. Aku tidak pernah tahu yang dia punya kenalan seramai itu. Cuaca redup sampai jenazahnya selesai dimakamkan. Bau harum yang menempel di bajuku hingga kini belum hilang meskipun sudah berkalikali dicuci.
66
27 EMAS
B
agaimana saya mahu menjelaskan kepada mereka. Mereka tidak akan percaya. Setiap orang punya untung nasibnya sendirisendiri; begitu juga saya. Pertanyaan mereka berjelajela dan penuh jebakan. Berkalikali saya menegaskan bahwa kekayaan saya ini bukanlah hasil korupsi. Lihat muka saya: saya adalah orang jujur. Mana mungkin orang jujur melakukan korupsi. Mana mungkin orang jujur melakukan penipuan. Mana mungkin orang jujur melakukan penyimpangan. Mana mungkin orang jujur berbohong. Saya bersumpah bahwa saya berkata benar. "Setiap pagi," kata saya kepada mereka, "perut saya berasa amat sakit dan keras lalu saya buang air besar. Ternyata yang keluar dari lubang dubur saya itu adalah lantaklantak emas. Emas murni 24 karat. Itulah yang saya niagakan dan membikin saya kaya." Sialan, mereka tidak mahu percaya saya!
67
28 IQRA
A
ku berusia 28 tahun ketika itu, terperangkap di dalam masjid antara Maghrib dan Isya karena hujan yang deras. Sementara menunggu hujan reda untuk pulang atau masuk waktu Isyak, kata orang Inggeris 'whichever comes first', aku duduk mendengarkan dari jauh beberapa orang jemaah bertadarus. Mendengar mereka membaca AlQuran itu timbul juga sedikit keinginanku hendak ikut tapi aku langsung tidak tahu membaca, dan rasanya sudah terlambat untuk belajar. Aku duduk menundukkan kepala sambil memejamkan mata mendengar dari jauh. Setidaktidaknya mendengar pun dapat pahala juga. Tidak lama kemudian aku perasaan ada seseorang duduk di sisiku. Awalnya aku tidak peduli, aku cuma mendengar bunyi kerisikkerisik halaman yang dibuka dengan cepat untuk beberapa saat. Aku menduga orang ini sedang membaca AlQuran tanpa suara dari satu halaman ke satu halaman dengan lancar. Aku mengangkat kepala dan memandangnya: seorang kakek sekitar usia 82 tahun. Barangkali ia perasaan yang aku memerhatikannya, ia pun berhenti membaca, lalu menoleh kepadaku. Aku terkejut melihat mukanya. Seperti mukaku, ada bintil hitam di pipi kanannya. Ia mengunjukkan AlQuran itu kepadaku dan menyuruh aku membacanya; ia ingin mendengar. Terus terang aku mengatakan yang aku tidak tahu membaca Al Quran. Aku mengambil AlQuran yang diunjukkannya itu dan aku mencoba juga membaca dengan tersangkut sangkut, entah benar entah tidak, dengan harapan ia
68
akan menawarkan diri mengajarku selancar ia membaca atau setidaktidaknya memberi satu petuah ajaib. "Carilah guru," katanya. "Belajarlah membaca." "Bisa ga kakek ajari aku membaca?" kataku. Ia memandangku, senyum sumbing. Gigi depannya sudah tidak ada. "Macam mana aku mau ngajar," katanya, "aku sendiri langsung gak tau membaca. Gak pernah mau belajar membacanya." Aku memandangnya dengan tidak mengerti. Bukankah tadi ia telah membaca AlQuran dari satu halaman ke satu halaman dengan cepat meskipun tanpa suara? "Kata ustaz," ujarnya, "dengan melihat hurufhuruf Al Quran kita masih bisa mendapatkan pahala. Itulah sahaja yang bisa dilakukan oleh orang tua sepertiku yang gak ngerti membaca: lihat hurufhuruf AlQuran sampai khatam 30 juz." Aku membuka AlQuran itu kembali, melihat huruf hurufnya, dari satu halaman ke satu halaman dengan cepat seperti yang telah dilakukannya tadi. Ia mengetuk kepalaku dengan kuat. "Aduh!" kataku memandangnya. "Bodoh! Otak lembu!" katanya dengan marah. "Kau masih muda. Jangan ikut macam aku. Hati pengen membaca tapi lidah sudah keras. Mau belajar, udah tua banget, ga mampu lagi." Ia mengambil semula AlQuran dari tanganku lalu bangun dan pergi meninggalkanku. Azan Isya mulai dilaungkan.
69
29 KEJUTAN
D
ia tertidur menonton berita di tv, menunggu suaminya pulang. Apabila dia terbangun dia sempat melihat di kaca tv satu kecelakaan jalanraya yang mengerikan. Polisi, tim ambulans dan beberapa orang sibuk membantu. Seorang lelaki diusung di atas tandu, mukanya dan bajunya berlumuran darah. Ada closeup: kepalanya nampak sedikit retak. Dia mengenal muka lelaki itu. “Abang!” jeritnya, kaget. “Huk!” Dia mati di situ juga, diserang sakit jantung. Tidak lama kemudian suaminya pulang. “Yaaang,” panggil suaminya di pintu. “Kaulihat ga abang berlakon drama tadi?” Itu adalah drama pertamanya. Bertambahlah duitnya jadi pelakon. Sudah ada tawaran untuk berlakon drama tv berseri. Dia tidak memberitahu isterinya. Dia mahu drama pertama itu sebagai satu kejutan.
70
30 ANAK DURHAKA
I
bu tua miskin menitiskan airmata apabila anak tunggalnya yang baru pulang dari Amerika, durhaka tidak mahu mengakuinya ibu, membawa pacaran cantik berkulit putih yang wajahnya iras penyanyi dan pelakon Taylor Swift. Ibu itu membawkannya cilok. "Nak," kata ibu itu, "ini cemilan kegemaranmu cilok." Anak lelaki itu menepis pemberian ibunya sehingga cilok itu terbanting jauh, terus direbut dan dimakan anjing anjing, kucing dan tikus. "Syaya thidak tahu hini makhanan hapa, horang tuha," katanya. "Syaya hanya tau makan pizza, burger, hotdogs and chips. Perghi sana horang tua tidak tahu diri." "Who is this disgusting old woman?" kata pacarnya. "Is she your mom?" "I DON'T KNOW HER! SHE IS NOT MY MOTHER!" Cuaca tibatiba redup dan gelap, diikuti dengan angin kencang. Ibu tua menadah tangan ke langit, rambutnya terburai menutupi sebahagian mukanya yang berkedut, angin bertiup dari tepi. "Tuhan," katanya, "jika ini benar anakku yang sudah lupa pada ibunya, lupa pada cilok aku sumpah dia, ya Tuhan, jadi cilok!" Seorang bocah menghampiri ibu tua ini, menarik narik lengan bajunya. "Bu," katanya, "daripada disumpah jadi cilok mending disumpah jadi emas. Bisa kaya kita bu." Ibu tua memandang bocah itu, anak siapa ini, pinter
71
banget, kemudian kembali berdoa. "Koreksi ya Tuhan. Nggak jadi." katanya. "AKU SUMPAH DIA SAMA PACARNYA JADI EMAS!" Hujan mengguyur, kilat memancar berserta guntur, beberapa pokok kayu rebah ditiup angin kemudian cuaca kembali normal. Anak durhaka dan pacarnya jadi patung emas mengkilau dipancar matahari, dikerumuni orang yang terus berdatangan dari setiap arah. Massa menjadi rusuh karena ada yang mau mengambil patung emas itu, ada yang coba mematah jarijari emasnya untuk dijual. Terjadi percekcokan, saling pukul memukul; limapuluh orang cedera berat, seratus orang cedera ringan, sepuluh orang mati tertindih, selebihnya hilang akal dan gila. Tentara datang menembakkan gas pemedih mata sambil melaungkan dengan pengeras suara: "BUBAR! BUBAR! PATUNG EMAS ITU MILIK PEMERINTAH!"
72
31 UNDANGAN
A
ku menerima satu kartu undangan dari sahabat lamaku. Sudah 15 tahun aku tidak mendengar kabar darinya. Jika menerima kartu undangan pernikahan seperti ini, biasanya aku tidak mahu membuang masa membacanya. Cukup sekadar aku mencatat di buku harianku bahawa majlis perkahwinan si Anu pada hari dan jam sekiansekian di tempat sekiansekian. Mula mula ada juga tanda tanya di kepalaku karena sahabat lamaku ini sudah pun menikah 20 tahun yang lalu dan sudah punya anak. Tetapi pertanyaan ini kubiarkan saja karena ia tidak penting untuk kupikirkan pokoknya aku akan hadir. Majlis resepsinya diadakan di sebuah hotel berbintang lima. Majlis ini meriah sekali dengan acara acara sampingan hiburan, (berbeda majlis pernikahannya yang pertama dulu, sederhana dan diadakan di kampung). Ia memelukku apabila aku tiba. Ia mengenakan pakaian tradisi sukunya; tampak tampan meski sudah tidak muda lagi. "Alhamdulillah," katanya. "Aku khawatir kau tidak hadir." "Tahniah," kataku. "Terima kasih," katanya. "Aku mau kaujadi saksiku pada majlis ini juga." Juga? Ya, dulu aku jadi saksi di majlis pernikahannya yang pertama. Ini satu penghormatan bagiku. Aku rasa bangga. Aku diantar ke pentas. Aku duduk di belakang sahabat lamaku ini, di sebelah kiri. Acara sebentar lagi akan dimulakan.
73
Pengantin perempuan keluar senyumsenyum manis kepadaku; tapi dia itu isteri yang sama, yang dinikahi sahabat lamaku ini 20 tahun dulu. Ia tetap ayu dan manis malah aku sendiri terpikat karena ia senyumsenyum kepadaku seperti itu sehingga jantungku berdegdug ah, fikiran gila. Ia duduk bersimpuh penuh sopan di depan suaminya. Acara pun dimulakan tanpa basabasi. "Saya," kata sahabat lamaku ini, "Ahmad Fadouli bin Fadilah dengan ini menceraikan engkau, isteriku, Purnama Dewi Persik binti Dani dengan talak tiga." "Saya Purnama Dewi Persik binti Dani menerima penceraiannya Ahmad Fadouli bin Fadilah dengan talak tiga." Diminta pengesahan dari para saksi dan aku mengesahkannya saja. Purnama Dewi Persik bekas isteri sahabat lamaku tidak habishabis memandang dan senyum padaku. Ya, ia memang masih cantik dan ayu. Purnama Dewi Persik, selepas itu, di sepanjang majlis, sentiasa berada dekatku. "Pernikahan itu bisa jadi sorga atau penjara," kata Purnama Dewi Persik kepadaku semasa acara makan. "Jika pernikahan itu sudah jadi penjara maka talak adalah pembebasannya. Tidak salah kita meraikannya ya, seperti ini? Aku mengangguk saja. "Tapi kita manusia butuh dicintai dan mencintai," katanya lagi. Sebenarnya aku bingung.
74
32 PULANG
A
ku pulang dari luar negeri untuk kali pertama. Di desaku masih belum ada listrik. Tidak ada air leding. Aku mandi di sumur di belakang rumah. Aku mandi ketika sudah hampir gelap, ketika tidak ada orang lain lagi menggunakannya, ketika suasana mulai dipenuhi bunyi krikkrik jangrik dan krokkrok katak. Aku menyalakan obor. Asap obor mengusir nyamuk. Bau kerosin menusuk hidungku. Aku mengaut air dengan batok dan menuangkannya pada tubuhku. Sejuk dan segar. Aku terdengar bunyi kerisikkerisik geselan seseorang datang dari semak. Aku mengenali Melissa. Aku cepatcepat meraih handuk. Ia tertawa. "Gak apa," katanya. "Aku juga akan telanjang." Api dari obor melemparkan bayangan kami. Aku menuangkan air ke tubuhnya. "Baru pulkam?" "Ya." "Mas akan pulang lagi ke Inggeris?" "Masih ada dua tahun untuk aku menamatkan kuliah." Ia mengeringkan tubuhnya dengan handukku. Aku menarik dan memeluknya eraterat. Ia tidak menolak. Kami berciuman. Kemudian ia teresakesak. "Aku dihamili oleh pamanku." Ini buruk sekali.
75
"Tidak ada yang percaya padaku. Aku takut Paman yang dimuliai akan membunuhku." Aku menawarkan diri untuk berjalan bareng ke rumahnya. Ia menolak. Ia juga menolak obor yang kuberikan. "Aku sudah biasa berjalan di dalam gelap." Ia berjalan pergi. Di rumah aku bertanya pada ibu tentang Melissa. "Gadis tidak baik, baru enam belas tahun. Dia tewas bunuh diri setahun yang lalu." "Oh."
76
33 TELAJAK
T
idak dapat dihindari orang bujang sepertiku ini menerima usikan. Sayang juga membujang tidak ada keturunan, kata mereka. Aku sudah lali dengan usikan seperti ini. Jika aku menikah pun belum tentu juga aku akan mendapat keturunan. Sudah terlambat untuk menikah. Ketika usia sudah mencapai 61 tahun ini memang sudah tidak ada harapan lagi. Memang sudah nasibku membujang seumur hidup. Jika pun masih ada yang mau menjadi isteriku, aku pula akan berpikir 100 kali. Aku tidak ingin menyusahkan sesiapa pun. Aku tidak mau, sebenarnya, menyusahkan sesiapa pun. Untuk ini aku telah mengambil langkahlangkah yang perlu yang bisa aku usahakan sendiri, yaitu menjaga kesehatan dan mengamalkan cara hidup yang sehat, jasmani dan rohani. Aku berolahraga pagi dan sore sekedar sepuluh ke dua puluh menit, mengeluarkan keringat. Menjaga permakananku, mengurangi makanan berlemak atau masakan berminyak dan membatasi makan daging merah. Aku memperbanyak makan sayursayuran, buah buahan dan sereal. Untuk kesehatan mental dan spiritual aku meluangkan waktu setiap hari untuk membaca buku, AlQuran dan lainlain, di samping memperluas pergaulan, melibatkan diri dengan aktivitasaktivitas masjid dan organisasi di kampung. Aku mencoba menjadi tua dengan cara yang terhormat, memang aku dihormati dan orang kampungku menganggap aku ini orang alim juga. Aku cuma bisa senyum malu mengingat masa mudaku.
77
Rumahku pula adalah rumah terbuka dan menjadi pusat untuk anakanak muda yang tertarik dalam bidang fotografi dan jurnalisme karena aku adalah seorang fotografer dan jurnalis yang berpengalaman juga disamping sesekali menulis cerpen dan artikel untuk koran dan majalah. Sebagai orang tua yang berpengalaman aku adalah narasumber bagi mereka tidaklah aku pelit dengan ilmu dan pengalaman yang kumiliki. Oleh sebab profesiku dulu itu, aku memang akrab dengan teknologi informasi: internet, photoshop, youtube, facebook, ebay, email, skype, paypal dan manamana yang membutuhkan akun, aku memang memiliki akunnya mudah untuk berkomunikasi dengan temanteman lama di luar negeri dan melebarkan network. Alhamdulillah, meski aku bujang tua, hidupku tidaklah pernah sunyi. Satu hari aku menerima pesanan di inboxku, seorang teman fesbuk dari Inggeris ingin hendak menghabiskan liburannya di tempatku. Dia meminta rekomendasi hotel untuknya menginap bersama istri dan tiga orang anakanaknya. Sebenarnya aku tidak kenal dia ini karena terlalu banyak teman fesbuk, jika ada orang mengadd, aku terima saja. Aku pun mengatakan datang sajalah, nanti aku mengambil kamu di bandara. Dia mengemel gambarnya sekeluarga. Dia berperawakan Inggris dan berkulit putih, tiga orang anak yang mungil berpakaian warna biru, jingga dan merah muda: dua lelaki dan seorang perempuan. Isterinya pula memakai jilbab berwarna hitam jadi tidaklah aku bisa menduga rupa dan bangsanya. Dalam emel itu dia menjelaskan bahwa dia dan istrinya dulu tidak menganut apaapa agama tetapi mereka sebelum bertemu sudah pun tertarik kepada agama Islam dan mereka sama
78
sama memeluk agama Islam sebelum menikah. Anak anak mereka lahir dalam agama Islam. Dia memperkenalkan nama Islamnya: Edward Solihin, istrinya Ayesha dan anakanaknya Iqbal, Faheemah dan Ghazali. Pada hari yang ditentukan aku pun mengundang mereka sekeluarga di bandara dan membawa mereka ke rumahku yang kosong ini. Kataku tinggalah di sini, lupakan hotel. Aku membawa mereka ke kamar yang sudah kusediakan. Mengingat mereka tampak letih, Ayesha pula dengan jilbabnya tunduktunduk malu, aku menyuruh mereka supaya istirahat sajalah dulu, tidur, kemudian mandi dan nanti masuk waktu Zuhur aku akan mengundang mereka turun ke bawah. Kita solat bersama kataku. Setelah makan dan solat Zuhur kami berkumpul di ruang tamu. Mereka semua tampak segar. Selama makan barulah aku berpeluang melihat muka Ayesha. Setiap kali aku memandangnya dan setiap kali mata kami bertembung, jantungku berdegup kencang. Ayesha pula tunduk dan nampak sedikit gemetar. Dia adalah keturunan darah campuran. Aku pun menatap wajahnya lamalama sehingga degup jantungku yang kencang perlahanlahan menjadi reda. "So how's your mother, Mary?" aku bertanya sambil menduga apa yang ada di dalam kepalaku: betulkah sangkaanku dia anak Mary. Katanya ibunya, Mary, sudah memeluk agama Islam, setahun selepas mereka. Sekarang namanya Siti Maryam. Tanpa kupinta dia bercerita: katanya ibunya tidak pernah menikah setelah melahirkannya karena membesarkannya dan dia tidak pernah mengenal seorang ayah. Dia sendiri menikah ketika berumur 30
79
tahun. Suaminya Edward Solihin dua tahun lebih muda darinya. "So where is the wife?" tanya Edward Solihin melihat rumahku kosong saja. Aku pun menjelaskan yang aku tidak pernah beruntung dalam perhubunganku dengan wanita. Aku belum menikah sejak aku pulang dari Inggeris 38 tahun yang lalu. Aku melihat Ayesha seperti hendak menangis. Aku pula terharu melihatnya. Aku juga malu melihatnya. Aku tahu dan tidak ada keraguraguan di dalam hatiku. Aku malu sekali melihat wajahnya yang memiliki fiturfitur dan sedikit imbas mukaku. Tapi apalah yang bisa aku buat. Inilah zaman mudaku yang mencaricariku menagih utang yang bertahuntahun. Tidaklah aku ingin hendak bercerita dan mencari alasan untuk membenarkan zaman mudaku itu. Semuanya sudah tertulis dan ditakdirkan. Aku bersyukur karena semua mereka mendapat hidayah Islam. Kemudian Iqbal anak yang sulung bertanya kepadaku dengan polos. "So, are you our grandpa?" Aku memeluk ketigatiga mereka, Iqbal, Faheemah dan Ghazali. "I am your grandpa," kataku. "I am going back to UK with you and then I will marry your grandma." "It was grandma who sent us here to find you, grandpa," kata Iqbal. "She said if we ever find you she will be coming too later, if it is ok." "I suppose it is ok," kata Edward Solihin. "It is very ok," kataku. "How did your grandma find out about me?" "Dad," kata Ayesha tampaknya sudah sekian lama dia ingin mengatakan kata itu, aku merasa tersentuh dan
80
sangatsangat aneh disebut sebagai seorang ayah begitu. "Mom has been you fb friend for years." Ketika aku meneliti daftar sahabatku memang ada yang bernama Siti Maryam tidaklah mungkin aku tahu dia itu Mary dan sudah memeluk Islam dan itu namanya dia menggunakan gambar kartun seorang Muslimah. Aku pula tidak pernah berinteraksi dengannya. Begitu juga dia adalah sekali dua kali dia menjempol statusku. Meski sudah tua seperti ini aku tetap juga berdebar debar menanti kedatangannya.
81
34 UNTUK DIJUAL
A
ku melihat ke luar dari jendela. Ada mobil van besar di depan rumahku. Van itu berwarna putih krim. Mulanya aku sangka itu ambulans, ternyata bukan. Dari van itu keluar tiga orang pria perpakaian rapi dan seragam putih. Mereka berjalan ke rumahku berbaris lurus dengan gerakan yang serentak seperti tentara. Yang di belakang sekali membawa tas eksekutif warna hitam. Terdengar bunyi hentakan sepatu berhenti serentak di depan pintu. TAK! Aku membuka pintu sebelum diketuk. Mereka masuk dengan berbaris dan duduk tanpa kupelawa. Aku tercium bau ubat dan steril antiseptik. Tas eksekutif dibuka ternyata itu bukan tas tapi sebuah kursi baring. Aku kira mereka ini salesmen menjual kursi baring model baru. Aku disuruh duduk baring di kursi ini. Memang sungguh nyaman aku mau beli. Belum sempat aku bertanya harganya, ketiga tiganya segera memeriksa seluruh anggotaku: kepala, telinga, hidung, tangan dan kaki, bahkan anuku tidak terkecuali. "Kau masih baik," kata seorang dari mereka. "Untuk satu tanganmu kami menawarkan 200 ribu dolar US. Untuk satu kakimu kami tawarkan harga 350 ribudolar US. Untuk satu kuping telingamu 10 ribu dolar US ...." "Aku jual telinga kiriku," kataku tanpa pikirpikir lagi, 10 ribudolar US itu lumayan juga bagi orang tidak berpenghasilan tetap sepertiku; bisa buat modal usaha. Seorang dari mereka menempelkan sesuatu di telinga kiriku. Sepuluh menit kemudian telingaku itu tanggal
82
dengan sendirinya, tidak ada darah, tidak ada rasa sakit. Aku mendapat 10 ribu dolar US. Sebelum pergi mereka memberiku kartu bisnes. Aku melihat van mereka pergi. Di belakang van itu ada tercetak katakata: WHEN BUSINESS IS MEAN, WE MEAN BUSINESS. WE BUY BODY PARTS. Itu dulu, sudah lama terjadi, dan sekarang keduadua kuping telingaku tidak ada, juga kaki kiriku sudah diganti dengan kaki palsu, dan hidungku hidung plastik. Sekarang aku melihatlihat tangan kiriku. Hidup mewah cara mudah memang seperti candu. Aku melihat anuku, kata mereka bisa mencapai jutaan dolar US.
83
35 NILAI
A
ku punya teman yang pada harihari tertentu akan tergerak hatinya memberi nilai kepada sesiapa saja yang dilihatnya. "Dua per sepuluh," katanya, saat diperkenalkan pada hari pertama aku pindah ke kantornya. Aku tidak mengacuhkannya karena belum tahu. Pada hari lain, setelah aku tahu, aku bertanya apa yang telah diberinya nilai itu. Dia seperti bingung. Dia seperti sudah lupa yang dia sebentar tadi memberi nilai pada sesuatu. Aku kurang yakin apakah ini senghaja dilakukannya atau memang satu keanehan natural pada dirinya yang tidak dapat dikontrol. Kami yang satu bagian dengannya di kantor itu tidak ada yang mendapat nilai tinggi: tidak ada yang mencapai lima per sepuluh. Paling tinggi empat persepuluh, dan itu pun akan turun kembali. "Woh," kata seorang teman, "nilaiku naik hari ani." "Berapa?" kataku. "Aku dari dulu, satu persepuluh, satu persepuluuuh mulu," kata kawanku itu. "Hari ani aku dapat dua setengah persepuluh." "Dua setengah persepuluh?" kataku. "Itu mengalahkan aku tuh!" Dia senyumsenyum sepanjang hari, tapi ini membuat aku yang paling rendah nilai. Tidaklah aku senang dibuatnya. Bersama temanteman yang lain kami bertemu teman yang memberi nilai ini. Bukan setiap hari dia didatangi gerakan ini. "2/10," katanya melihat mukaku.
84
Temanteman yang lain juga mendapat nilai mereka. "2,5/10." "2,9/10." "3,1/10." Nyatalah aku mendapatkan nilai yang paling rendah lagi. Bosku mendapat 4,2 persepuluh. Ini nilai yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya: 3,3 persepuluh. Dia gembira sekali sehingga dia traktir kami minum di kantin. "Minumminum, pesan apa saja," kata bos. "Aku traktir. Aku traktir." Aku coba membayangkan bagaimana jika dia mendapat nilai sepuluh persepuluh: mungkin kami akan dibawa makan di hotel bintang lima. Aku membawa pacarku untuk diberi nilai. Kantor pacarku di seberang jalan. "2,2/10." Aku mengantarnya bareng hingga ke kantornya setelah menemaninya minum di kantin kami. "I love you," kataku. "I love you too," katanya. Dia tidak tahu itu nilai dirinya; kuberitahu yang kawanku itu berbicara tentang tugasan yang sedang dibuatnya. Temanteman yang lain tidak mau kalah membawa pacar atau tunangan untuk diberi nilai. Kawanku yang naik nilai dari satu ke tiga desimal dua persepuluh tadi sangat senang ketika pacarnya mendapat nilai enam desimal tiga persepuluh. Itu nilai yang paling tinggi yang pernah kami dengar. "6,3/10! I'm very proud," katanya setelah mengantar pacarnya itu ke hingga pintu bangunan kantor kami. Aku berasa seperti tersindir pula karena pacarku dapat markah yang rendah. Kawanku itu pada hari lain markahnya turun lagi ke
85
satu persepuluh atau dua persepuluh. Hanya sekali itu dia dapat dua setengah persepuluh. Untuk mempertahankan nilai dua setengah persepuluh itu saja susah baginya. Akhirnya dia menetap pada satu setengah persepuluh. Tidak lama selepas itu dia putus dengan pacarnya. Dia yang kena putuskan tapi dia tampak senang pula seperti orang yang baru lepas dari penjara. "Sulit," katanya. "Terlalu tinggi gengsinya, ga sanggup aku keep up. Juga keluarganya ga suka padaku." Satu hari seorang menteri datang ke kantor kami membuat kunjungan resmi; kebetulan pula kawanku itu didatangi gerakan memberi nilai. Aku dan kawan kawanku pun membawanya ikut menyambut kedatangan menteri itu: kami ingin tahu menteri itu dapat nilai berapa. Kami berada di depan. "11/10," katanya ketika bersalaman dengan menteri itu. Menteri itu tidaklah ambil endah; dia melanjutkan bersalaman dengan orang lain. Menteri memang sibuk untuk memikirkan halhal sepele seperti ini. "11/10?" kataku. "Lebih seratus persen tuh!" "Lebih dari sempurna tuh," kata seorang dari kawanku. Kami semua garugaru kepala. Kawanku yang putus cinta dengan pacarnya itu membisik kepadaku. "Pinter juga dia ya, modus jilatmenjilat menteri," katanya.
86
36 SENI LUKIS
S
eorang kawanku yang tidak tahu apaapa tentang seni lukis telah membawa seorang pemuda, yang menurutnya adalah seorang pelukis yang hebat. Pelukis yang dibawanya ini tidak memiliki sifatsifat seorang pelukis atau orang seni. Mukanya terlalu jernih, pakaian pula putih dan bersih, tidak ada efekefek atau bekas cat atau warna yang melekat pada tangan, baju dan celananya. Rambutnya sederhana panjangnya bersikat rapi ke belakang, ia memiliki jenggot yang segenggaman tangan panjangnya, ya seniman biasanya menyimpan jenggot tetapi jenggotnya ini bukan jenggot seniman. Jenggot dan rambut seniman biasanya kusut dan tidak terurus. Terurus: itulah kata yang tepat untuknya, penampilannya terlalu terurus bagi seorang pelukis atau seniman. Gaya penampilannya itu pantas bagi seorang imam muda yang menghabiskan waktu dengan beribadah dan bukannya melukis dan berseni seni. Kesan pertamaku adalah ia bukan seniman. Sangkaanku itu tepat sekali ketika melihat lukisan yang dibawanya. Sebuah lukisan lanskap di atas kanvas berukuran 150cm X 91cm. Tidak ada apaapa yang istimewa tentang lukisan itu untuk menantang daya intelektual seseorang. "Ini lanskap daerah mana?" tanyaku. "Imajinatif saja," kata pelukisnya. "Oo," kataku. Pelukisnya juga tidak tahu tentang seni lukis. Zaman pascamodern ini kita tidak lagi melukis lukisan imajinatif apalagi lukisan imajinatif lanskap untuk bisa kita
87
memperakuinya sebagai karya seni. Sebuah lukisan karya seni itu harus memiliki konsep dan tema yang diangkat, diintepretasi dari dan berakarumbi kepada realitas; bukan yang dikhayalkhayalkan. Sebuah lukisan yang memiliki nilai seni harus membuat audiensnya berpikir dan berpikir dan membuat intrepretasi yang mungkin berbeda dari intrepretasi orang lain bahkan intrepretasi pelukisnya sendiri. Pokoknya setiap karya seni harus mampu menantang daya pikir atau intelektual seseorang. Lukisan yang dibawanya itu hanyalah sebuah lukisan lanskap yang 'cantik' itu saja, dan lebih buruk lagi ia adalah pemandangan imajinatif yang dibuat buat oleh pelukisnya dengan nilai seni yang paling bawah. Untuk menjaga hati kawanku dan pelukis muda itu aku membeli juga lukisan tersebut. Awalnya aku ingin berbincangbincang secara intelektual tentang seni dan segala teoriteorinya, tetapi saat melihat lukisannya, aku batalkan saja. Aku juga tidak jadi membawa pelukis ini mengunjungi galeriku yang memamerkan koleksi lukisan lukisan modern, abstrak dan konseptual, yang jika aku ingin membahas sebuah lukisan saja aku bisa membahasnya sehingga sehari suntuk. Sudah tentulah lukisan lanskap imaginatifnya ini tidak akan aku pamerkan di dalam galeriku ini. Apapun aku tetaplah menghormat jerihpayah seseorang; lukisan ini aku gantung baikbaik di sebuah kamar tidur yang jarang jarang digunakan kamar untuk tamu yang datang bermalam. Aku tidak pula bertanya siapa namanya. Lukisan itu tidak pernah lagi aku pikirkan sehinggalah seorang Profesor dari luar negeri datang ke rumahku untuk membuat penelitian seni lukis kotemporari Asia Tenggara. Aku membawanya ke galeriku yang
88
memamerkan koleksi seratus buah lukisanlukisan mewakili seluruh Asia Tenggara dan kami berbincang sehingga larut malam. Profesor Edreis bermalam di rumahku dan esoknya ia tidak mau keluarkeluar dari kamar tidur untuk tamu itu. Jika orang tidak ingin keluar hanya ada satu pilihan saja: kita masuk. Aku minta izin untuk masuk. "Masuklah," kata Profesor Edreis. Aku masuk. Ah, nyaman sekali kamar ini. Tidak panas dan tidak juga dingin. Alat pendingin dan kipas angin dimatikan, jendela masih tertutup, jadi aku tidak tahu dari mana datangnya angin lembut yang bertiup. Udaranya segar, aku menarik nafas dalamdalam. Pikiranku menjadi tenang. Aroma wangi yang lembut memenuhi ruang. Aku melihat Profesor mengamatamati lukisan pemandangan imajinatif yang kugantung di dinding. Aku ikut mengamatamati lukisan itu dan baru menyadari bahwa cahaya di kamar ini, aroma harum semerbak dan angin lembut yang bertiup datangnya dari lukisan itu. Lukisan itu adalah sebuah lukisan menggambarkan sebuah taman dengan pohonpohon yang rindang dan lebar, sungai yang airnya mengalir tenang, bungabunga yang mekar beraneka warna: merah, merah muda, putih, ungu, jingga, dan rumput rumput yang hijau dengan titiktitik embun masih tersebar seperti manikmanik permata yang berkilaun di atasnya seolaholah tidak akan pernah kering untuk selamalamanya. Kupukupu berterbangan di sana sini. Aku merasa wajah dan rambutku disentuh angin yang nyaman: aku memejamkan mata dan menarik napas dalamdalam. Aroma harum semerbak yang lembut yang masuk ke lubang hidungku tidak pernah sama setiap kali aku menarik napas. Kalau bisa aku tidak ingin keluar dari
89
kamar ini. Aku melawan perasaan nyaman ini. Aku menarik tangan Profesor. "Prof," kataku, "mari kita keluar!" "Yah, yah," katanya. "Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan." "Diskusi intelektual kita belum selesai," kataku. "Yah, yah, benar," katanya. Setelah beberapa langkah meninggalkan kamar itu, ia memutar balik. "Capku tertinggal di dalam," katanya. Ia masuk ke kamar itu lagi. Agak lama juga ia mencari topinya itu. Akhirnya aku ikut masuk. Porfesor Edreis sedang berbaring di atas kasur, topi di atas kepala, keduadua tangannya berlipat di atas dada, mata pejam dengan senyuman di bibir. Aku terpaksa menariknya keluar lagi. Setelah beberapa langkah berada di luar kamar itu ia berbalik. "Tongkatku tertinggal di dalam," katanya. "Apa benar Prof membawa tongkat kamaren?" Aku ingat ia tidak membawa tongkat. "Entah," katanya. "Tapi aku rasa seperti tongkatku tertinggal di dalam." Ia masuk kembali ke kamar itu. Sekali lagi aku terpaksa menariknya keluar. Sebenarnya aku sendiri merasa sulit untuk keluar dari kamar tersebut, karena nyamannya berada di situ, tapi aku lebih tegar melawan perasan nyaman itu. Sore itu aku menelepon temanku yang tidak tahu apa apa tentang seni lukis, bertanya tentang pelukisnya. "Dia bukan orang provinsi sini," kata kawanku itu. "Dia anak bekas pembantu rumahku. Santri pasentren. Dia melukis sesekali saja. Lukisannya semua tentang bayangan surga. Namanya Ahmad Firdaus."
90
37 AKU
A
ku menerima panggilan telepon dari kantor polisi untuk isteriku. Panggilan itu sangat penting dan konfidential. Aku memberikan ganggang telepon ke isteriku. Kami baru saja siapsiap hendak tidur. Jam ketika itu sudah lalu sebelas malam. Setelah selesai panggilan telepon itu isteriku diam kemudian terisak menangis. "Kenapa?" kataku. "Abang," katanya, "abang diamankan dan dilokap di kantor polisi." Aku mencoba memikirkan ini. Ini sangat membingungkan karena jika dia mengatakan 'abang' itu maksudnya aku (suaminya) bukan abang saudara kandungnya, dia memang tidak punya saudara kandung, atau sepupu pria. Kemudian dia tersadar dan berhenti menangis segera. "Kalau abang ada di sini," katanya, "yang diamankan dan dilokap itu siapa?" "Itulah yang abang pikirkan," kataku. Kami kehilangan nafsu untuk tidur dan lainlainnya. "Ayo kita ke kantor polisi," kataku. "Ada orang mencuri identitasku." "Itulah abang simpan semua detail pribadi di pesbuk," kata istriku. Aku dikawal rapi ketika tiba di kantor polisi. Mereka kaget melihat aku. Mereka mengendurkan kawalan ketika memeriksa tahanan di mana 'aku' seharusnya berada. Aku dan istriku meminta untuk kami dibawa melihat
91
'aku' yang dilokap itu. Di sinilah aku mengamati 'aku' yang dilokap itu, persis seperti aku, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gaya, gerakgerik dan tingkah lakunya persis seperti aku. "Kau siapa?" aku bertanya. "Akulah kau," katanya dengan suaraku dan gayaku. Sebelum meninggalkan kantor polisi aku bertanya apa kesalahan 'aku' itu. "Berkelakuan kurang sopan," kata polisi. "Mempamer kemaluannya kepada orang banyak." "Dia bukan aku," kataku kepada polisi (meskipun sebenarnya aku pernah ingin berbuat seperti itu). "Dia tidak ada hubungannya dengan diriku." Dalam perjalanan pulang istriku mulai berpikir yang bukanbukan. "Kita jamin dia keluar, ya bang," katanya. "Aku kasihan melihat abang dilokap begitu." "DIA BUKAN AKU," kataku. "Abang sendiri pernah mengatakan ingin jadi flasher, pamer kemaluan pada orang banyak," kata istriku. "Nah, sudah tertangkap basah tidak pula mau mengaku." "DIA BUKAN AKU!" kataku. "Besok kita bebaskan saja dia, bang," kata istriku. "Kita ambil dia bekerja dengan kita kita pergunakan dia untuk kebutuhan kita." "Termasuk untuk kau selingkuhan dengan dia?" kataku. "Aku tidak terfikirkan tentang itu," kata istriku dengan perlahan setelah diam seketika, tersenyumsenyum, seolaholah sedang berpikir. "Tapi gak juga apa yah, kalau aku selingkuhan dengan abang sendiri?" "DIABUKANAKU!"
92
38 TASYA
K
etika dokter mengkonfirmasikan yang istriku tidak akan bisa melahirkan anak, aku menerimanya dengan tenang saja. Istriku merasa dirugikan dan merasa dirinya kurang sempurna sebagai seorang istri. "Kalau abang mau menikah lagi," katanya, "aku izinkan, asal aku yang pertama tau siapa calonnya." Aku memandang istriku. "Apa beneran sayang nyuruh abang?" kataku dengan senyuman setan. "Ga nyesal nanti?" "Aku kasian abang gak punya anak," katanya. Itu sebenarnya katakata untuk dirinya sendiri. Aku tidak masalah tidak punya anak. "Kalau abang menikah baru, apa dijamin dapat anak?" kataku. "Entah," katanya. "Tapi aku udah dikonfirmasi ga bisa melahirkan anak." "Tapi ya selama 15 tahun ini kita bahagia juga walau ga punya anak," kataku. "Iya, mang bener," katanya, "hidup kita cukup tapi rasanya masih gak lengkap." "Sudahlah," kataku. "Bukan kita aja yang ga punya anak di dunia ani. Pasrah aja." Dia diam sebentar saja, kemudian menimbulkan pekara yang sudah berulangkali ditimbulkannya. "Ambil anak angkat bang," katanya. "Abang ga ingin memelihara anak orang lain," kataku. "Kita coba aja dulu," katanya dengan rendah. Pendirianku dan jawabanku adalah sama sejak dulu, tidak akan berubah. Membesarkan anak angkat tidak
93
akan pernah sama dengan mebesarkan anak kandung. Tidak mungkin aku akan bisa menyayangi anak angkat sepenuhnya, mungkin orang lain bisa, tapi aku? Tidak mungkin. Aku tidak merasakannya di dalam hatiku. "Aku gak mau," kataku dengan final. Permintaan istriku adalah lebih untuk dirinya sendiri dari untukku. Pastinya ia merasa sunyi sendirisendiri di rumah. Sejak beberapa tahun belakangan ini ia mengisi masa dengan memasak kue untuk dijual, dan aku sendiri telah mengambil seorang pembantu untuk menolongnya. Istriku tidak pernah berputus asa tentang mengadopsi anak ini. Sejak dikonfirmasi tidak akan bisa beranak, ia meminjam anak kecil tetangga sebelah yang memang banyak anak. Anak ini berumur tiga tahun lebih dan pendiam. Sesekali aku melihat anak ini di ruang tamu menonton tv seolaholah kamar tamu dan tv itu dia yang punya. Aku pula selalu memberi reaksi yang dingin. Aku tidak suka anakanak, terutama kalau bukan anakku sendiri. Mereka semuanya besar kepala, suka mengaturatur orang dewasa. Ketika anak ini menonton dvd lagu anakanak yang telah dibelikan istriku, cukup dengan system suara teater 3D, aku mematikan dvd tersebut dan mengubahnya ke siaran tv. Anak ini memandangku dengan diam. Aku pasti memang dia perasaan yang aku tidak suka sama dia. Baguslah kalau dia sudah tahu. Kemudian istriku masuk ke kamar tamu mungkin karena lagu anakanak sudah tidak terdengar lagi. "Sejak kapan abang suka liat tv?" kata istriku. Memang aku tidak suka dan jarang sekali menonton tv. "Suka hati aku mau liat tv," kataku. "Tvku."
94
"Tega benar," kata istriku, "melulu mau nyakiti anak. Sini Tasya ikut tante ke dapur. Ommu itu!" "Sejak kapan aku jadi Omnya?" kataku. Selain tidak suka anakanak, aku juga tidak suka istriku terlalu tertagihtagih seperti itu. Selama seminggu dua aku tidak melihat Tasya di rumahku lagi, tapi istriku tidak pernah putus akal, ada ada saja rencananya untuk mendapatkan anak. Pada suatu sore pulang kerja aku ke kamar tamu seperti biasa menunggu istriku membawakan aku minuman petang, tapi yang datang bukan istriku tapi seorang gadis muda berusia sekitar 25 tahun. Dia tersenyumsenyum manis menyajikan kopi dan kue. Pembantu yang kuambil tidaklah secantik dan semanis ini. "Kau ini siapa?" kataku. "Tasya," katanya. Kaget, aku buruburu ke dapur menemui istriku. "Kok, si Tasya cepet benar membesar," kataku. "Kebetulan Tasya juga namanya," kata istriku. "Itu udah basar banget ga pantes dibuat anak angkat," kataku. "Itu calon istri abang, aku sendiri yang carikan," kata istriku dengan santai. "Mereka keturunan banyak anak, kembar lagi. Saudara kembarnya sudah menikah. Dia bukan siapasiapa, bukan anak orang lain, anak kerabat sebelah tanteku." Aku terdiam. "Pilihlah," kata istriku, "anak angkat atau istri baru. Abang bisa beristri empat, no problem." "Iya," kataku. "Kalau empat istri, kayak sound system full 3D theater tuh, cukup dengan tweeter sama sub woofer. Aku gak mau ah. Temani aku minum di kamar tamu."
95
"Anak angakt ga mau. Istri baru ga mau," omel istriku sendirisendiri. "Kalo aku yang jadi lelaki ga akan aku tolak berbini muda. Apalah nasibku dapat laki macam ini." "Hahaha," kataku. "Mang Tasya itu cantik, tapi cantik lagi istri abang." Sejak hari itu aku tidaklah menghalang istriku menjemput Tasya anak tetangga sebelah. Aku membiarkan Tasya mendengarkan lagu anakanak di tv. Aku memang bukan tipe manusia yang suka melihat tv. Tasya pun kadangkadang memberanikan diri duduk dekatdekat denganku tapi aku tetap dingin meskipun aku tidak menghindarinya. "Tasya itu butuhkan kasih sayang," kata istriku pada suatu malam sebelum tidur. "Kan ada ibu dan bapanya di sebelah itu," kataku. "Mereka itu sudah punya anak yang ramai sepuluh orang," kata istriku. "Kalo udah tau ga sanggup membesarkan, ngapa bikin anak banyakbanyak," kataku. "Tasya itu bukan anak mereka," kata istriku. "Tasya itu anak yatim piatu; ayah dan ibunya meninggal kecelakaan mobil. Hanya tetangga kita itu saudara kandung ayahnya. Saudarasaudara sebelah mamanya buat ga tahu saja karena pernikahan ayahmamanya itu ga direstui keluarga sebelah mamanya." Memang cerita sedih tapi tidak juga bisa memancing simpatiku. Bagiku dia tetap anak orang lain, cukuplah saja sejauh aku membenarkannya sesekali berada di rumahku. Tapi semua ini berubah ketika pada suatu hari aku menyiapkan tugas di sebuah bangunan toko yang buruk di kota. Aku mampir di situ sebelum pulang ke rumah. Ada seekor anak kucing yang comot merengek
96
rengek, kemudian seekor anjing betina yang sedang menyusui tiga ekor anaknya tibatiba bangun mendekatinya, menciumciumnya, lalu membaringkan diri, anak kucing comot itu pun menyusu dari puting susu yang terkecil. Kemudian anak anjing yang tiga ekor ikut menyusu sama. "Kasian," kata pemuda Cina yang aku berurusan. "Itu anjing biarkan anak kucing nyusu sama dia ah," kataku. "Itu anjing sayang betul sama anak kucing, macam dia punya anak sendiri," kata Cina itu. "Lebih dari anak sendiri." "Itu kucing dia punya mama mana?" kataku. "Mati ditabrak mobil." Ketika itulah aku teringat akan Tasya. Aku tidak langsung pulang ke rumah aku mampir di rumah tetanggaku, memberi salam dan bertanya Tasya di mana. Ia membawa aku ke belakang rumah. Tasya sedang dudukduduk di tepi selokan. "Dia kenapa tuh?" kataku. "Bermainmain sendiri." "Kasian juga," kataku. "Iya," kata tetanggaku. "Kami sendiri ga terperdulikan lagi. Anak sendiri aja udah banyak banget." "Tasya," aku memanggilnya. Aku memegang keduadua pipinya dan memeluknya kemudian mengecup dahinya yang comot dan berkeringat. Dia seperti belum mandi dari pagi tadi. "Tasya ikut Om jumpa Tante. OK," kataku. Tasya mengangguk walau nampak sedikit bingung. Di rumah akulah yang memandikannya, menyampu rambutnya, menggosok badannya bersih dari dakidaki, sehingga baunya harum. Aku membalutnya dengan
97
handuk besar yang bersih, memeluknya eraterat dan menggendongnya keluar dari kamar mandi. Kedua tangan Tasya merangkul tengkukku. Aku membawanya bertemu istriku yang tidak sadar akan kepulanganku. "Tante," kata Tasya. "Om cayang aku." Itulah pertama kali aku mendengar suaranya.
98
39 ALLI JADDI
I
nnalillahi wa inna ilaihi ra ji'uun. Aku menerima berita kematian sahabatku, Alli Jaddi, dari anaknya, seusai salat Subuh Jumat. Ia meninggalkan seorang janda, tiga orang anak dan dua orang cucu. Sebelum jadi istrinya, jandanya itu dulu adalah wanita yang kudambakan. Ia sahabat karibku semenjak samasama tinggal di asrama dulu. Ia seorang yang berbadan kurus dan mudah sakit. Cuaca berubah sedikit, ia sudah batuk batuk dan flu. "Ehuk! Uhuk! Putra," katanya,"temani aku ke klinik." Aku kasihan melihatnya terbaring berselimut di tempat tidur. Mukanya pucat dan bibirnya pecahpecah dan kering. Pagi itu ia tidak turun untuk sarapan. Akulah yang membawakan sarapannya ke kamar. Ia sudah siap berpakaian untuk ke klinik. Ia minum dan makan sarapannya. Ia hanya minum dan makan sedikit saja. "Tidak ada selera," katanya. "Temani aku ke klinik." "Aku masuk kelas dulu," kataku. Kami pelajar satu kelas. "Aku beritau Bu Guru dulu. Klinik pun belum buka nih." "Jangan kau tidak jadi," katanya. "Iya," kataku, senyum memandangnya. Setelah habis pelajaran pertama aku meminta izin keluar dari Bu Guru untuk menemani sahabat karib ke klinik. "Alli flu," kataku. Aku diizinkan keluar malah dijadikan contoh sebagai teman yang baik. Di asrama, Alli berbaring di bawah
99
selimut. "Ayo kita ke klinik," kataku. "Aku tidak jadi," katanya dengan suara lemah. Rasanya aku ingin marah. "Kasih saja aku obat," katanya. Aku ingat aku masih ada sisa obat flu saat aku demam dulu, aku memberinya dua biji. Setelah menelan obat itu ia berbaring kembali. Aku menyentuh dahinya. Memang panas. "Suhumu panas banget," kataku. "TIDAK LAMA LAGI KAU AKAN MATI!" Aku kembali ke ruang kelas. Bu Guru memandangku dengan senyum. "Cepat banget," kata Bu Guru. "Mengapa? Alli tidak jadi lagi? " Aku senyum saja. Mahasiswa lain tertawa. Bu Guru pun sudah tahu akan kebiasaan kawanku ini. 'Aku tidak jadi' itu sudah seperti moto baginya. Ia tidak jadi masuk perguruan tinggi teknis. Ia tidak jadi masuk tentara, malah pesta pernikahannya yang pertama pun dibatalkan. "Aku tidak jadi kawin," katanya. Pernikahannya kali kedua, yang kuharapharap tidak menjadi, memang menjadi pula sampai ke akhir hayatnya ini. Kalau aku mengunjungi rumahnya ia selalu bertanya: "Kau kapan lagi kawin? Kawinlah. Carilah wanita lain. Sarabanun itu bukan jodohmu." Ceritanya begini: istrinya itu adalah perempuan yang ingin kutebak. Tapi Sarabanun tidak mencintaiku, sekadar berteman biasa saja. "Aku cinta benarbenar padamu, Sarabanun," kataku. "Aku cinta Alli Jaddi. Cinta benarbenar," kata
100
Sarabanun. "Kau tidak kucintai, sayang pun tidak. Biasa saja." Apa boleh buat. Aku memberitahu Alli Jaddi yang Sarabanun cinta gila padanya. "Kaukawinlah dengan Sarabanun," kataku. "Kawin untukku. Kaujaga ia baikbaik." Mereka hidup bahagia. Aku sebujangbujangku masih merindui Sarabanun, dan tanpa malumalu selalu mengunjungi mereka. "Kaurindukan istriku ya?" kata Ali Jaddi senyum senyum, ia memanggil istrinya. "Yang, Putra datang." Sarabanun keluar berkerudung membawa hidangan, kemudian ia duduk di sisi suaminya. Kemudian Alli Jaddi melingkarkan lengannya ke pinggang istrinya. Sarabanun dengan manja menyindingkan badannya ke arah suaminya. Aku merasa bahagia melihat Sarabanun bahagia, tapi aku juga merasa cemburu. Mereka sama sama maklum. Alli Jaddi menasihatiku: nikahilah wanita yang benar benar mencintaimu niscaya ia akan setia dan membahagiakanmu sepanjang hidupmu; kahwini wanita yang kaucintai tapi tidak mencintaimu, hidupmu akan jadi neraka. Pernyataannya ini membuat aku sedikit sedih karena secara tidak langsung menggambarkan bahwa ia tidak mencintai Sarabanun. Hanya Sarabanun yang mencintainya. Pertanda mati pada Ali Jaddi memang ditampakkan kepada kami bertiga dan anakanaknya. Satu Jumat ia memanggil kami semua berkumpul. Aku bukan anggota keluarga, cuma teman. "Kalau aku mati," kata Ali Jaddi, "kalau aku mati, kalau aku mati, Sarabanun kaunikahlah dangan sobatku ani, Putra. Kalau aku mati, kalau aku mati, kalau aku
101
mati, Putera kaunikahlah dengan bekas istriku ini nanti, Sarabanun." "Bang," kata Sarabanun. Air matanya mulai mengalir. "Itu perintah dan wasiat," kata Alli Jaddi. "Putra jangan sekalikali kau membohongi dirimu." Aku kasihan pada Sarabanun tapi suaminya benar: aku tidak akan mampu membohongi diri. Aku mencoba juga mendesak Alli Jaddi untuk membatalkan perintah zalimnya itu. Aku tahu Sarabanun, karena cintanya, karena taatnya kepada suami, akan mematuhinya, dan aku tidak akan bisa menolaknya karena cintaku kepadanya (meskipun kami sudah samasama berumur). "Kasihan Sarabanun," kataku. "Tarik kembali perintahmu, Li! TARIK BALIK!" "Tidak kau harus kawin sama Sarabanun kalau aku mati. Tidak lagi lama aku akan mati." "Pikirkan baikbaik," aku mencari akal. "Kalau aku jadi suami terakhir Sarabanun, tentu Sarabanun akan jadi bidadariku di surga nanti." Aku bangun dan meninggalkan mereka, dan tidak datangdatang lagi ke rumah sahabatku itu. Aku masih berpikirpikir gagasan yang tidak senghaja tercetus dari kepalaku karena terdesak itu: Sarabanun akan jadi bidadariku 'forever' di surga nanti. Aku senang, tapi aku tidak senang. Subuh Jumat, dua minggu setelah itu, Ali Jaddi meninggal. Aku ikut mengelola jenazahnya dari di kamar mandi, mengafankan, mensalatkannya tepat di belakang imam, dan sampai ke kuburan. Akulah yang ikut masuk ke liang lahad. Karena hari itu hari Jumat, Pak Imam tidak banyak membuang waktu, talkin sudah dibacakan saat aku menyambut jenazah sahabatku ini. "Ketahuilah wahai Ali Jaddi Bin Tiara, bahwasanya
102
Mungkar dan Nakir itu hamba Allah Taala, sebagaimana kamu juga hamba Allah Taala. Ketika mereka menyuruh kamu duduk maka duduklah, mereka juga akan menginterogasi kamu. Mereka berkata: Siapakah Tuhan kamu? " Ketika itulah Ali Jaddi bangun duduk. "ALLAH TA'ALA TUHANKU!" kata Alli Jaddi dengan lantang. "KELUARKAN AKU CEPAT!" Pak Imam kaget dan bangkit dari duduknya hendak lari ke belakang tapi berpikir dua kali. Reputasi ahli agama harus dipertahan: terpaksa kuatkan iman. Orang lain sudah ada yang lari ketakutan. Alli Jaddi hidup semula. Aku yang faham ini hanya mampu menampar jidat, kebiasaan 'aku tidak jadi' kawanku ini kambuh kembali, sampai ke liang lahad. "AKU TIDAK JADI!" katanya. "AKU TIDAK JADI MATI!" Aku membantunya membuka kain kafannya. Ia memandangku seperti orang yang tidak pernah mati seperti tidak ada apaapa. "Maaf Putra," katanya. "Aku tidak mau Sarabanun jadi bidadarimu forever. Aku sayangkan dia." Aku membantunya keluar dari liang lahad itu, anaknya membantu menarik lengannya. Aku duduk di dalam liang lahad seketika, menggarukgaruk tengkuk dan kepala. Aku menampar jidat lagi. Aku tidak senang, tapi aku senang.
103
40 SAHABAT
K
ami kehilangan kontak selama lebih dari tiga puluh tahun. Ketika melihat saya, dia tersentak kekagetan. "Aku minta maaf," katanya. "Sungguhsungguh minta maaf. Aku tidak hadir di hari pemakamanmu." "..........."
104
41 AYAM
I
a bukanlah tetangga yang dekat. Rumahnya jarak sepuluh buah rumah dari rumahku, masuk ke sebuah persimpangan, trek jogging harianku. Tetanggaku itu telah menuduhku mencuri ayam serama jantannya. Ini kali kedua dia menemukan ayam serama jantannya itu berada di halaman rumahku. Masalahnya ini: dia ada memelihara lima ekor ayam serama, ayam serama yang cantik berbadan kecil dan lucu itu, yang jika memilik 'pedigree' pasti bisa mencapai harga jutaan ribu seekor. Tapi aku yakin ayam seramanya itu tidak memiliki 'pedigree' namun tetap juga berharga mahal. Ia memiliki hanya seekor ayam serama jantan, yang sisanya empat ekor itu ayam serama betina. Ayam serama jantan ini memang 'ganteng' dan kadangkala 'pamer' pula. Ayam serama memang suka 'pamer' mungkin mereka sadar yang mereka itu cantik dan fotogenik. Jika kita berjalan mereka ini akan senghaja lewat di depan kita dengan santai, berhenti sekejap dan memandang kita sejenak, seolaholah memamerkan sudut tepi mereka. Ayam serama jantan lebih 'pamer' dari ayam serama betina. "Aku ga tahu gimana ayam itu berada di sini," kataku. "Jarak rumahku ke rumahmu ini jauh banget untuk ayam serama berjalan sendiri," kata tetanggaku itu. "Tentu ada orang membawanya ke mari." "Kautuduh aku mencuri?" "Terserah," katanya menantang mataku. Ini adalah satu tuduhan yang akulah mencuri ayamnya. Tiada sesiapa suka dituduh mencuri. Pencuri
105
saja tidak suka dituduh mencuri apalagi orang baikbaik dan mulia sepertiku. Ingin sekali aku meninju mukanya. Aku sabarkan diriku. Aku menyuruhnya menangkap ayamnya itu dan membawanya pulang. Seperti pertama kali dulu ayam serama jantannya itu lari dari tuannya itu, tetapi ketika aku yang menangkapnya ayam itu jinak pula. Malah ayam itu menyerahkan dirinya kepadaku. Aku mengambilnya dan memberikannya kepada tuannya. Ayam serama jantan itu memiringkan kepalanya memandangku dan kemudian tunduk. "Kok," katanya. "Kook." "Kalau bisa kurunglah ia supaya tidak ke mari lagi." "Aku tidak suka mengurung binatang," kata tetanggaku itu. "Hewan juga punya perasaan ingin bebas." "Kitok kook!" kata ayam serama jantan itu. Aku meminta nomor hpnya dan akan meneleponnya jika ayam serama jantannya itu ke mari lagi. "Kau orang baik sebenarnya," kataku. "Kasih kepada hewan. Tidak guna kita bercekcok karena seekor ayam." "Ya, betul juga," katanya. "Maafkan aku." Ia membawa ayamnya pergi. Ayam serama jantan itu memandangku kemudian menundukkan kepalanya. "Kok," katanya, "kok kok." Pada hari Minggu berikutnya aku berjogging waktu pagi, aku terlihat tetanggaku itu menyuci mobil, aku mengangkat tangan, ia membalas mengangkat tangan juga. Setelah jauh sedikit aku terlihat ayam serama jantannya keluar mengekoriku. Aku berhenti, ayam serama jantan itu berhenti juga. Aku memandangnya, ayam jantan itu berpurapura memandang ke belakang dan ke atas. Aku berjalan, ayam itu berjalan. Aku berhenti, ia berhenti.
106
Aku menelepon tetanggaku itu meminta ia cepat cepat keluar dan memerhatikan gelagat ayam serama jantannya itu. "Ayam itu berperilaku aneh," kataku. Setelah sampai di rumah aku duduk di tangga. Tidak lama setelah itu muncul ayam serama jantan tetanggaku itu, pelanpelan, sembunyisembunyi seperti malumalu masuk ke halaman rumahku. Ayam serama jantan itu berjalan seperti itu terus menuju mendekatiku. Sejurus kemudian tetanggaku muncul tertawatawa dan duduk di sisiku di tangga. "Aku pikir," kata tetanggaku itu masih tertawa, "ayam serama jantanku itu sudah jatuh cinta sama kau." Aku percaya diriku ganteng dan mengangan angankan kalau perempuan yang jatuh cinta sama aku. Aku tidak keberatan kalau perempuan yang 'stalking' aku. Ini satu pukulan telak bagi egoku. Ini bukan main main. Ini ayam yang jatuh cinta sama aku; bukan lagi ayam betina tetapi ayam jantan! Shit! "Apa kauyakin ayammu itu ayam jantan?" "Barangkali juga ayam itu gay," kata tetanggaku. "Hingga kini ayamayam betinaku gak ada yang bertelur." "Ya," kataku. "Barangkali juga ayam serama jantan itu gay." "Kau ambillah ayam itu," kata tetanggaku dengan serius. "Ternyata ia sudah jatuh cinta sama kau." "Buat apa?" kataku. "Palingpaling dia akan aku sembelih saja!" Ayam serama jantan itu memiringkan kepalanya dan memandangku. "Loh," katanya, "koook kitok?"
107
42 EKOR
I
a menurunkan celananya sedikit, mendedahkan punggungnya kepadaku sambil menarik keluar ekornya. "Ekor ini tumbuh semalam," katanya. "Cantik banget," kataku sambil mengeluselus ekor itu. Ia seorang perempuan yang cantik dan pastilah ekornya cantik juga. "Kau beruntung," kataku. "Hanya orangorang pilihan ditumbuhi ekor. Satu saat nanti kau akan jadi seorang pemimpin dunia." "Aku bahagia sekarang," katanya. "Sungguh bahagia." "Aku juga ikut bahagia," kataku. "Hari ini sempurnalah hidupku," katanya. Aku mengangguk.
108
43 TV MIMPI
A
ku mulai terjaga oleh suara bising seakanakan seribu buah tv nyala serentak menayangkan programprogram yang tidak sama, bercampur dengan suara orang bercakapcakap dan membuat aktivitas aktivitas lainnya. Aku merasa seolaholah sedang berada di tengahtengah pasar atau mungkin sebuah supermarket yang luas. Aku membuka mata pelanpelan dan mencoba memfokuskan pandanganku yang sedikit kabur. Aku bangun dan duduk memeluk lutut. Aku tidak tahu di mana aku dan bagaimana aku berada di sini. Aku memandang kelilingku saat penglihatanku mulai jelas. Aku sedang dikerumuni orang yang sangat ramai. Di atas kepala mereka ada tv 'flatscreen' lebar, 36cm X 25cm, yang menayangkan segala macam film: cerita horor, thriller, perang, dokumenter, drama yang bercampuraduk. Seorang budak yang di depan sekali menunjuk nunjuk ke arah layar tvnya, dengan bangga meminta perhatian semua. Layar tvnya menayangkan satu tayangan yang sedikit porno. Perhatian beralih kepadanya, beberapa orang dewasa menepuknepuk bahunya sambil menyampaikan ucapan selamat. "Selamat, kau sekarang sudah baligh." "Welcome to the club, boy!" "Heee, kau sudah bisa menikah sekarang." Meski tertutup, aku nampak ereksi pada kemaluan anak itu. Ia tersenyumsenyum bangga. Budak ini menghampiriku dengan lagak orang
109
dewasa. "Mana tv mimpimu?" katanya. "Tv mimpi?" kataku. "Apa itu tv mimpi?" "Ini, ini," dia menunjuknunjuk pada tv 'flatscreen' yang di atas kepalanya. Aku merasa malu melihat tayangan tv atas kepalanya itu. "Semua orang harus ada!" "Ini, ini," kata orang ramai dengan suara serempak. "Tv mimpimu mana?" Bergemuruh dan berdengung suarasuara mereka. Mereka menunjuknunjuk tv yang di atas kepala mereka. "Semua orang harus ada!" "Dia tidak normal," kata anak yang baru baligh tadi. "Dia tidak normal," kata orang dengan serempak. Setiap kali anak itu berbicara, orang akan mengulangi katakatanya. Bergemuruh dan berdengung bunyinya. Kemudian tampil seorang wanita dangan gaya seorang berkuasa memegang tongkat emas. Di atas kepalanya ada tv yang dua kali lebih besar dari orang lain. Tayangan gambarnya sangat jelas dalam 'super high resolution'. Aku juga melihat tayangan itu sekejap di rewind, difastfoward, dipause, dislowmotion, dizoom in dan dizoomout. Orang membungkuk tanda hormat kepadanya. "Beta Sang Ratu di sini," katanya. Aku membungkuk seperti yang dibuat orang banyak. "Di negeri ini, sangat menyalahi adat jika seseorang tidak punya tv di atas kepalanya," kata Sang Ratu. "Pasang TV di atas kepalanya!" "Pasang TV di atas kepalanya!" "Pasang TV di atas kepalanya!" "Pasang TV di atas kepalanya!" Aku diarak menuju ke sebuah bangunan, masuk ke
110
sebuah laboratorium operasi. Aku dibius. Ketika aku sadar, di atas kepalaku sudah ada sebuah tv 'flat screen' yang lebar seperti orangorang lain. Aku diberi penjelasan bahwa setiap orang di negeri ini menayangkan mimpinya di layar tv atas kepala masing masing. Di negeri ini penduduknya membuat kerja dan beraktivitas sambil bermimpi. Mereka tidak tidur. "Kami bekerja sambil bermimpi." "Kami bermain sambil bermimpi." "Kami berbagi mimpi dengan setiap orang." "Tidak diizinkan merahasiakan mimpi." Sang Ratu memeritahkan agar aku mulai bermimpi sekarang. Dengan tv di atas kepalaku, tidak pula sulit untuk aku memulai mimpi. Aku mulai mimpi sebuah film dokumenter tentang ikanikan dan batu karang di dasar laut. Ikan yang ratusan jenis dan bermacammacam warna, perak, kuning, biru berenangrenang dengan damai. Dari satu sudut di sebelah kiri masuk aktris Korea, Park MinYeong, aktris kesukaanku yang cantik dan manis berenangrenang dengan santai tanpa sehelai benang pun di tubuhnya, aku tidak tahu apa yang dibuatnya bertelanjang di dalam film dokumenter tentang ikan dan batu karang, sangat lama juga dia berenang renang dengan gaya erotis dan explisit bersama ikan sampai aku tersadar bahwa mimpi ini tidak pantas jadi tontonan orang banyak. Aku pun menghitamkan seluruh tubuh Park MinYeong kecuali muka dan tangannya. "Whoi! Tidak boleh disensor!" Sang Ratu menghetakkan tongkat emasnya dengan kuat sehingga terasa gegarannya seperti gempa. Orang banyak ikut memekik. "Whoi! Tidak boleh disensor!" "Whoi! Tidak boleh disensor!"
111
"Whoi! Tidak boleh disensor!" "Ampunkan patik Sang Ratu," kataku dengan gegabah. "Di negeri patik semuanya bersensor untuk menjaga moral publik. Dan patik sudah terbiasa membuat penyaringan sendiri ampunkan patik. Ampunkan patik Sang Ratu!"
112
44 TULISAN CANTIK
A
ku mencaricari pulpen Parkerku. Aku telah menulis surat cinta pertamaku dengan pulpen itu. Sudah lebih 23 tahun aku menggunakan komputer. Segala korespondensi tidak lagi ditulis menggunakan pulpen. Aku dulu memiliki tulisan tangan yang indah yang berbungabunga. Memang menyenangkan juga bisa menulis dengan tulisan tangan. Kepandaian ini aku warisi dari ayahku, ia memiliki tandatangan yang paling cantik bagiku. Pulpen merek Parker dengan matanya dilapisi emas itu hadiah dari ayah. Surat cinta pertama yang kutulis itu bukanlah surat cintaku tapi surat cinta teman seasrama. Ia bijak bermadah cinta tapi tulisan tangannya buruk sekali sehingga ia minta bantuan jasa baikku. Aku menulisnya sampai sepuluh kali ulang, sehingga aku hafal kata katanya, baru aku berasa puas. Untuk merahasiakan hal ini akulah yang juga menjadi perantaranya: ia takut cintanya ditolak; jika ditolak biarlah aku dan ia saja yang tahu. Masalahnya perempuan yang ditujunya itu jatuh cinta pada tulisanku. Akhirnya aku dan Nonoi yang kahwin. Kawanku itu 'gentleman' juga tidak ambil hati. "Cinta itu tidak bisa dipaksa," katanya. Patah hati, ya mungkin, tapi ia menyembunyikannya. Ia melanjutkan kuliahnya dan menjadi dokter, bekerja dengan pemerintah dan kemudian membuka kliniknya sendiri. Tulisan tangannya tetap jelek dan berantakan. Setelah sekian lama menikah dan anakanak juga sudah membesar, hubungan antara suami dan istri bisa menjadi rutin dan hambar. Jika situasi ini dibiarkan
113
berlarutan pekara kecil bisa menjadi gawat. Aku membongkar bawah kasur. "Apa lagi yang abang cari?" kata Nonoi. "Semua mau dibongkar." "Pulpen Parkerku," kataku dengan senyum. "Aku mau nulis surat." "Pakai aja itu komputer," kata Nonoi. "Mengapa mau balik ke jaman batu?" Aku menemukan kotak tempat aku menyimpan peralatan tulisan tanganku, masih ada tinta Quink biru, kertas 'blotter', 'writing pad' berwarna biru muda, karet penghapus, semuanya dalam kondisi 'mint'. Aku membawa semua ini ke kamar tamu di mana ada meja luas. Dengan menarik nafas dalamdalam, bermeditasi selama satu menit, dengan tenang aku menulis sepucuk surat cinta. Madah dan katakatanya milik kawanku yang sudah jadi dokter itu, aku masih ingat setiap kata katanya. Nonoi, istriku datang. Aku memberikan surat cinta itu kepadanya. Ia membacanya. "Romantis juga abang ini," katanya. "Hihihi." Nonoi kemudian menggulat leherku dengan lengannya, ia dulu juara olahraga lempar lembing dan ikut wrestling. "Ampun Noi," kataku. "Ampun." Anakanakku datang mendengar kami ribut di kamar tamu. "Ngapa sih mama, tuatua, kayak teenager?" "Nih bapa kamu," kata istriku, "nulis surat cinta." Anakku mengambil surat cinta tulisan tanganku itu. "Woah," kata anakku. "Cantik banget tulisan bapa, ma!" "Itulah awal mama jatuh cinta pada ayahmu ini, karena tulisan tangannya yang cantik," kata istriku. "Isi
114
surat itu bukan karangannya. Itu karangan temannya yang mau nebak mama. Bapamu tukang tulis sama antar surat aja." Terbongkarlah kisah cinta kami kepada anakanak. "Jaman dulu belum ada komputer," kata istriku. "Kalau pake komputer mungkin mama ga akan jatuh cinta sama monyet ini gaklah kamu akan lahir ke dunia." "Romantis juga ya Ma," kata anakku. "Tukang tulis dan antar surat yang meraih cinta mama." Aku, memang sifatku pemalu jika kisah cinta zaman mudamuda diungkit, tuatua begini mukaku jadi merah juga. Tapi tidak apalah, asal rasa bahagia itu kembali.
115
45 BENCI
A
ku benci padanya. Benci pandang pertama. Kami menghadiri pesta ulang tahun seorang teman. Aku bersama temantemanku. Ia juga bersama teman temannya. Aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Aku tidak tahu dia siapa atau anak siapa; pastinya orang baru di sini. Ketika pandangan kami bertemu aku sudah merasakan getaran kebencian di hatiku. Aku rasa dia pun begitu juga karena setelah itu pandangan kami selalu saja bertembung; misalnya ketika kami berjalan ke arah yang berlawanan aku akan melihat ke belakang dan ternyata dia juga menoleh ke belakang. Atau tibatiba aku merasa hendak menoleh ke kiri lalu aku pun menoleh ke kiri, dan ternyata dia ada di situ mengangkat kepala dan memandangku. Aku mencoba saja tenang seolaholah tidak ada apaapa dan aku terus mengobrol dengan temanteman dan dia pun kulihat dari sudut mataku seolaholah tidak ada apaapa. "Hey," kata kawanku dengan suara rendah, "gadis baru itu sejak tadi selalu curicuri lihat kepadamu." "Aku tahu," kataku. "Kau tau siapa dia?" "Aku dengar dia sepupu birthday girl," kata kawanku. "Namanya Nur Kasih." "Nur Kasih?" kataku. Tolol juga nama itu! Tidak ada nama yang lainkah? Di acara itu kami tidak sempat berkenalan walau sudah seratus kali kami bertukar pandangan dan mata kami bertemu. Aku benci benar padanya. Hanya tiga hari kemudian di kantin, aku yang saat itu terburuburu dengan secangkir kopi di tanganku dengan
116
senghaja (dan klise sinetron) melanggarnya dan kopiku tumpah mengenai bajunya. Kotorlah bajunya yang hijau krim oleh hitam kopiku. "Maaf, maaf," kataku. "Aku senghaja." "Tidak apa," katanya. "Tidak apaapa." Aku meminjamkan jas yang baru kubeli kemarin, yang memang cocok juga dengan dirinya. Aku sempat menanggalkan tag harga di jas itu, yang aku lupa tanggalkan sebelumnya. "Masih baru," kataku. "Pakailah dulu ini untuk menyembunyikan kotoran kopi itu." Aku tidak ulang minta maaf lagi karena harus pergi terburuburu untuk menghadiri kuliah. Aku meninggalkannya, berjalan dengan cepat sambil menghabiskan sisa kopiku. Siasia saja aku menghadiri kuliah itu karena konsentrasiku terganggu. Aku tidak melihatnya lagi pada hari itu, tidak juga besoknya. Lusanya ketika istirahat aku berjalan santai menuju ke kantin ada seseorang bergabung denganku, berjalan di sisiku. Aku memandangnya. "You look nice in my jacket," kataku. "Aku juga berpikir begitu," katanya. "Aku pikir kaubeli jas ini dengan aku dalam pikiranmu walau kita belum saling kenal." "Kita istirahat samasama," kataku. "Aku tidak ada kuliah setelah ini. Aku akan ke perpustakaan membuat studi dan referensi sehingga jam lima nanti." "Aku kuliah setelah ini," katanya. "Sipp," kataku. Dia tidak pernah memberi balik jasku. Memang jas itu cocok benar dengannya seolaholah direka khusus untuknya, dan aku pula tidak pernah memintanya kembali. Sepanjang pengajian, aku di tahun terakhir dan
117
dia di tahun pertama kuliah dua tahun, kami selalu saja bersama pada waktuwaktu yang terluang kuliah yang kami ambil adalah sama jadi kami saling bantu membantu dan bertukar pikiran. Aku menamatkan kuliah dengan hasil yang sangat baik dan dia juga pada tahun berikutnya berakhir dengan hasil yang cemerlang. Aku rasa aku sudah mengenalnya dan dia juga mengenaliku dan sudah saatnya untuk aku menyatakan perasaanku. "Aku benci padamu," kataku, "sebencibencinya." "Aku juga benci padamu," katanya, "sebenci bencinya."
118
46 BANDEL
K
ami berdua samasama bandel kepala batu, sama sama berusia 11 tahun, bertetangga jarak dua buah rumah. Kami selalu bertengkar dan saling berbalas dendam sehingga bapabapa kami ikutikutan berkelahi. Bapaku menyalahkan dia kepada bapanya. Bapanya menyalahkan aku kepada bapaku. Akhirnya mereka berdua bertengkar. "Cobalah kaudidik anakmu itu baikbaik!" "Kaufikir anakmu itu baik juga, cukup didikan?" Setelah mereka bertengkar kami berdua pula akan melanjutkannya di tempat lain. "Bapaku kuat, bapamu gak kuat." "Bapaku yang kuat, bapakmu yang gak kuat!" Terkenallah kami berdua di desa itu sebagai budak yang suka berkelahi. Kami tidak berkelahi dengan orang lain hanya antara kami berdua. Kami tidak bisa bertemu. Garagara kami berdua, bapa kami bergaduh sampai bertinju dan kepala desa harus ikut campur. Ini bukan sekali terjadi. Satu hari aku merasa hendak membalas dendam. Aku tidak tahu dendam apa. Itu tidak penting: balas dulu kemudian baru cari dendamnya. Aku pun ke rumahnya. Ia tidak ada. Bapanya pun tidak ada. Ibunya ada, sedang dudukduduk di luar. "Assalamualaikum, Bu," kataku. "Waalaikumsalam, Nak," jawabnya. "Sianu mana?" "Dia jalan entah ke mana. Kenapa?" "Aku mau cari kelahi."
119
Aku pun pergi dari situ. Aku tidak senang hati. Aku tahu ada dendam yang harus aku bayar. Bayangkan ketika aku terlihat dia, dari jauh dia sudah kaget dan seperti orang berdosa. Aku pun terus mengejarnya. Ia terus lari. Ia lebih cepat berlari dari aku tapi aku lebih tahan nafas. Dalam olahraga tahunan sekolah dia biasanya dapat nomor satu dan aku nomor dua dalam lari 100 meter dan 200 meter tapi aku nomor satu dan dia nomor dua dalam lari 400 meter dan 1500 meter. Dalam lomba lari estafet sekolah, kami juara seluruh kabupaten, aku pelari pertama dan dia pelari penutup. Kami berdua tidak bisa ditemukan karena aku tidak akan menyerahkan baton kepadanya, begitu juga dia. Sekarang dia sudah jauh di depanku dan menghilang membelok masuk ke satu simpang. Aku masuk ke simpang itu, tapi aku tampak dia bertiarap, kepalanya melihat ke dalam selokan, di sisinya ada seekor anjing yang dewasa berwarna coklat. Aku memperlambat lariku. Ketika tiba di situ aku terus ikut bertiarap di sisinya, menengok ke dalam selokan. Di selokan yang sedikit kering, dalam dan curam itu ada lima ekor anak anjing. "Kasihan," kataku. Dia, tanpa pikir panjang lagi, langsung terjun. Seekor demi seekor anak anjing itu diulurkannya kepadaku dan aku mengambilnya dan menyerahkannya kepada ibu anjing yang sedang gelisah. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan anakanak anjing itu sendirian. Kemudian aku mengulurkan tanganku untuk menariknya keluar dari selokan itu. Kemudian kami duduk dengan keduadua kaki menjulur ke dalam selokan. Kami tahu apa masalah kami: kami tidak tahu bagaimana praktik membersihkan diri setelah memegang anjing. Kami tahu anjing itu najis berat. Akan ditanya pada masingmasing
120
orang tua takut dimarahi. Silapsilap mereka berdua pula akan bergaduh lagi. Lama juga kami memikirkannya. "Pak Imam," tibatiba kami serentak mengatakannya. Kami ke rumah Pak Imam. Mujur dia ada di situ. Ia memberikan kami dua ember yang besar dan membawa kami ke sebuah bukit, dekat rumahnya, yang susur tidak lama dahulu. Ia mencangkul kepingankepingan tanah liat yang bersih dan memasukkannya ke dalam ember kami masingmasing. Di rumahnya dia sendiri yang mencampurkan tanah liat dengan air dari pipa dengan tangannya sampai halus. "Tangan kamu masih bernajis," katanya. "Kamu bisa gunakan kayu untuk membaurkannya." Dia memberikan kami batok sebiji seorang dan menyuruh kami melumurkan anggota kami yang terkena anjing dengan air yang bercampur tanah itu. "Lepas itu kamu bersihkan dengan air biasa sekurang sekurangnya enam kali," katanya. Sebenarnya kami sudah tau ini cuma tidak yakin bagaimana prakteknya. Di sekolah cuma diajarkan teorinya saja. Sebagai budak yang nakal aku tidak peduli. Aku buka pakaian dan bertelanjang bulat. Sianu tidak mau mengalah, dia juga bertelanjang bulat. Aku mandi dengan air tanah liat dari ujung kepala ke ujung kaki begitu juga Sianu. Bukan setiap hari kita ada alasan untuk melumurkan seluruh badan dengan air tanah liat. Pak Imam gelenggeleng kepala. "Uh, sudah berpotong rupanya," kata Pak Imam sambil tertawa, dia nampak yang kami samasama sudah dikhitan. "Mudahmudahan setelah ini kamu menjadi dua budak yang suci lahir batin." "Amin," kata kami serentak. Pakaian juga kami cuci seperti yang diajarkan. Kami
121
berjalan kaki dari rumah Pak Imam pulang ke rumah, bertelanjang bulat, seperti tidak ada apaapa, sambil ketawaketawa, pakaian kami yang basah dijepit di bawah ketiak. Kami samasama ke surau petang itu ikut salat Maghrib langsung Isyak. Kami memaksa Pak Imam untuk mengajar kami mengaji seusai Maghrib. Sejak itu setiap lepas Maghrib kami belajar mengaji dari Pak Imam. Pak Imam juga mengajar kami azan. Oleh sebab surau ini surau desa, Pak Imam memberi kami kesempatan untuk melaungkan azan. Kami masing masing punya nafas yang panjang. Jika aku azan Maghrib, dia pula akan azan Isyak dan begitulah sebaliknya. Bilal permanen tidak ada di surau ini. Kami tidak pernah lagi bergaduh, kami hanya saling berlawan lawan mengaji dan azan. Tidak cukup Maghrib dan Isya kami bersepakat untuk bangun awal dan samasama ke surau untuk Subuh juga. Kami samasama ingin sekali melaungkan: Assolaaaatu Khairumminannawuuuum! Assolaaaatu Khairumminannawuuuum!
122
47 WANITA YANG BERJOGING MUNDUR MUNDUR
M
ungkin ini adalah cara ia melakukan senam: berlari lari anak ke belakang, seolaholah ia punyai mata di belakang kepalanya. Saya melihat ia setiap hari Senin dan Rabu berjoging seperti itu di jalan kecil di depan rumah saya. Ia kelihatan gesit dan cekatan. Saya tidak dapat menebak dengan tepat umurnya. Saya tidak mengenalinya, ia bukan dari kampung kecil ini. Kadang kadang saya melambai padanya dan ia membalas kembali sambil tersenyum. Satu hari, saya membuat keputusan untuk menyertainya. Tepat jam 08:00 pagi ia muncul di jalan raya di depan rumah saya. "Saya hampirhampir berfikir," katanya, "yang awak tidak akan pernah mahu menyertai saya." Gaya bahasanya asing di telingaku, pasti ia datang dari dunia lain dan saya terikutikut berbahasa seperti itu. Dia berlarilari anak cara biasanya dia, mundur mundur, dan saya berlarilari anak cara biasanya saya, maju ke hadapan; tetapi kami berdua menuju ke arah yang sama. Kami bercakap tentang cuaca yang lembap, pokok pokok yang tumbuh dan mati dibelit parasit, awan kelabu dan udara berasap, burungburung dan unggasunggas yang pagipagi sibuk bising, dan segala sesuatu yang lain sehingga kami kehabisan subjek untuk dibualkan. Keadaan menjadi sepi dan sedikit janggal dan terdengar bunyi tupai melompat dan terjatuh ke tanah.
123
"Adakah awak tidak akan bertanya saya soalannya?" ia berkata. "Soalan apa?" "Mengapa saya berlarilari anak ke belakang," katanya. "Mengapa awak berlarilari anak ke belakang?" kata saya. Dia tersenyum. "Saya sedang mengundurkan waktu," katanya. "Itu satu alasan bijak untuk jogging mundurmundur," kata saya, ketawa sedikit. Jadi saya pun berjogging mundurmundur dengannya dalam perjalanan pulang dan mengucapkan selamat jalan apabila sampai di rumah. Saya berjalan mundurmundur menuju ke rumah. Isteri saya sedang menyapu tangga. "Ngapain sih abang jalannya mundurmundur?" "Saya sedang mengundurkan waktu," saya berkata. "Sinting," kata isteri saya. "Pukul berapa sekarang, adinda?" "7.15 kakanda," kata isteri saya terikutikut gaya bahasa saya. “Sintingnya gak bisa diubatin lagi.” "7.15? Saya pasti saya mula keluar tadi jam 8.00 pagi." Jam dinding menunjukkan sudah pukul 7.25 pagi. Selepas minum segelas air saya menyertai isteri saya membersihkan halaman rumah. Tepat jam 08:00 pagi wanita berjoging mundur mundur muncul di jalan raya di depan rumah saya, berlarilari anak ke belakang memandang lurus ke depan, seolaholah ia punya mata di belakang kepalanya.
124
48 SEPERTI DULU
M
iyul jatuh cinta pada hidung dan lubang hidung Alisa. Alisa memiliki hidung yang lucu, ujungnya ternaik sedikit sehingga lubangnya berbentuk oval. Setelah berkenalan dan berkawan rapat Miyul pun menyatakan cintanya. Ia memijit hidung Alisa. "Aku suka hidung dan lubang hidungmu," katanya. Alisa pun membalas dengan menjewer telinga Miyul. "Aku suka telinga dan lubang telingamu," kata Alisa. Mereka pun menikah dalam upacara yang sederhana mendapat lima orang anak. Anakanak ini tidak mengerti kenapa ayah mereka suka memeriksameriksa dan mencabut dengan kaliper bulu hidung emak mereka. Mereka juga tidak mengerti kenapa emak mereka suka memeriksameriksa dan mengorek lubang telinga ayah mereka. Mereka tidak pernah mendengar cinta pada hidung dan lubang hidung atau cinta pada telinga dan lubang telinga. Sementara bentuk tubuh Alisa semakin berisi dan tidak seramping dulu, namun hidungnya tetap seperti dulu, malah bertambah cantik dengan peningkatan usia, karena itu cinta Miyul terhadap Alisa tidak pernah berubah malah bertambah. Begitu juga dengan Alisa cintanya terhadap Miyul tetap seperti dulu meskipun perut Miyul gendut karena kurang berolahraga, rambut putih menipis tetapi telinganya tetap seperti dulu, jika ada perubahan pun tidak begitu signifikan. Untuk mengatakan yang Miyul tidak pernah tertarik pada perempuan lain setelah menikah memang tidak benar juga. Ia pernah tertarik pada barisan gigi seorang
125
perempuan. Kemudian ia membayangkan dirinya bercinta lalu kawin dengan perempuan itu. Gambaran ia mencungkil sisasisa makanan dari celahcelah gigi perempuan itu dengan dengan tusuk gigi adalah satu gambaran yang keterlaluan. Ia juga membayangkan bagaimana jika sudah tua nanti gigi perempuan itu akan buruk, terkena karies, plak, terpaksa dicabut, jadi ompong dan diganti dengan gigigigi palsu. Ia samasekali tidak dapat mencintai gigi palsu. Ia melupakan saja perempuan bergigi cantik itu. Dengan mata rabun sekali pun gigi palsu tetap gigi palsu. Setiap pulang kerja Miyul memijit hidung Alisa. "Hummmwh," kata Miyul. Alisa pula menjewer telinga Miyul dan terus menariknya ke dapur untuk minum sore. "Eeeeeeeh," kata Alisa. Bahagia.
126
49 KECELAKAAN
I
ni adalah sebuah kecelakaan. Seseorang dalam kerumunan itu mendorongku. Aku terjatuh di atas tubuhnya. Ia sedang membantu ibunya menjual makanan di pinggir jalan di bawah payung birumerah kuning yang lebar. Hampirhampir aku menciumnya. Aku sudah siap untuk ledakan marah dari ibu dan anak. Putri tersenyum. Ibunya tertawa. Jadi mereka mengerti bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Sekarang aku menjual makanan di pinggir jalan di bawah payung birumerahkuning yang lebar bersama putri dan ibunya.
127
50 ENAK
K
ami punya teman yang sama yang entah sudah sebulan lebih hilang. Aku tidaklah seakrab ia dengan teman itu. Tapi aku dapat merasakan juga kesunyiannya atas kehilangan tersebut. "Apa kabar?" tanyaku. "Okeylah," katanya. "Biasa aja." "Apa rencana hari ini?" "Biasa ajalah," katanya dengan senyum yang seni. "Siang nanti gak ke manamana?" "Ngapa?" "Aku cari teman makan," kataku. "Gak pulang ke rumah?" katanya. "Ga." "Aku pulang ke rumah," katanya. "Tapi kalau kau ga keberatan kita makan aja di rumahku." "Istrimu gak keberatan?" Dia menelepon istrinya dan memberitahu ia akan pulang siang dengan membawa seorang tamu. "Seperti biasa," katanya kepada istri. Aku numpang mobilnya, rumahnya agak jauh juga, masuk jalan kecil terpencil dari rumahrumah lain, di dalam hutan. Istrinya sudah menunggu kedatangan kami. Kami terus saja ke meja makan. Aku menawarkan diri untuk membaca doa. Aku berdoa untuk kesejahteraan kami semua dan juga kesejahteraan teman bersama kami yang hilang entah ke mana itu. "Moga teman kita itu cepat ketemunya," doaku. "Amin," sahutnya beserta istri. Hidangan makan siang adalah sederhana saja; nasi,
128
sayur kobis, ikan goreng dan sup, tapi inilah makanan yang paling enak yang pernah kumakan; aku berselera sekali. Aku memujimuji istrinya karena pintar memasak. "Tidaklah," kata istrinya merendah diri. "Biasa aja." Rasa supnya adalah di luar dari dunia ini. Aku mengelenggelengkan kepala karena sedapnya itu. Sup itu kuhirup sampai habis. Kemudian aku terlihat ada sepotong tulang dengan sedikit daging masih melekat yang jelas terlihat seperti jari kelingking. Aku pun menyendok jari kelingking itu dengan sendok sup. "Ini daging apa?" "Bukan apa tapi siapa," kata kawanku itu, kepalanya sedikit menunduk, sambil memandangku dengan tajam dari sudut matanya. "Kita sekarang sedang makan teman." "Teman yang hilang itu?" Aku memandang mukanya. "Iya, teman bersama kita," katanya, ada senyum halus di bibirnya. "Enak yah? Teman adalah makanan yang paling enak untuk dimakan." Aku berhenti makan. Katanya ia mengambil 'off' selebih hari ini, jadi ia tidak akan menghantar aku pulang ke tempat kerja. "Kau juga bisa mengambil off," katanya. "Bermalamlah di sini." "Makasih," kataku. "Aku akan jalan kaki dan naik angkot atau ojek saja nanti." Aku buruburu meninggalkan rumah itu. Aku hendak berlari tapi kakiku seperti ada lem di bawahnya, dan aku tidak bisa bergerak lebih cepat, aku menoleh ke belakang kemudian melangkah lagi, kakikakiku seperti amat berat untuk kuangkat, aku menoleh ke belakang lagi setiap beberapa langkah, takut ia mengekoriku. Aku terpaksa juga menbenarkan pada diri sendiri
129
bahwa hidangan siang itu tadi, meskipun singkat dan sederhana, enaknya tak tertandingi. Enak banget. Betul betul enak dan aku setuju dengan katakatanya tadi itu: Teman adalah makanan yang paling enak dimakan.
130
51 KEMBALI
I
striku pulang ke negeri asalnya. Kami sudah menikah lebih lima belas tahun. Dia yang merencanakan untuk tidak beranak. Antara kami berdua sudah tidak ada rasa apaapa lagi sebagai suami istri. Aku tidak menceraikannya namun kepergiannya ini sudah dapat kurasakan sebagai perceraian; ia tidak akan kembali ke mari lagi. Aku mengantarnya ke bandara dan mengucapkan selamat jalan. Aku terus saja pulang ke rumah sebaikbaik ia masuk ke ruang tunggu. Ini salahku sendiri. Aku Islam hanya di KTP. Istriku itu memeluk agama Islam hanya sebagai syarat: ia tetap tidak percaya kepada adanya Tuhan. Ketika aku mencapai umur 40 tahun aku mulai meretrospeksi diri. Aku merasa kurang senang dengan cara hidupku selama ini. Aku tidak bisa menerima bahwa hidup ini berakhir di dunia ini. Akhirat wajib ada. Balasan buruk baik wajib ada. Manusia memiliki tanggung jawab, memiliki akal untuk membuat pilihan. Jika kehidupan berakhir di dunia ini, jika akhirat tidak ada, jika balasan buruk baik tidak ada, tentu saja perbuatan buruk tidak berbeda dari perbuatan baik, tentu saja semua aturan dan kode moral tidak diperlukan; kita dapat hidup bebas seperti binatang berkendali pada instink. Pikiran ini saja sudah cukup untuk membuatku gelisah. Pada hakikatnya hidupku tidaklah sebebas seperti orang yang tidak beragama karena aku terpaksa juga akur pada kode moral buruk dan baik dalam masyarakat dan ini aku kira aku sudah berbuat sebaikbaiknya. Pada saat yang sama aku tidak pula menjalankan suruhansuruhan agama, aku tidak
131
pernah merasa senang meninggalkannya. Di dunia aku hanya senang setengahsetengah dan di akhirat aku tahu aku samasekali tidak akan mendapat apaapa bagian. Aku mencoba menjelaskan ini kepada istriku yang berbangsa Eropa itu, katanya ia lebih nyaman dan akan terus nyaman dengan Nietzsche dan Sarte. Ugama baginya hanyalah untuk orang 'delusional'. Di sinilah titik pemisah antara kami; tidak ada pertengkaran, tidak ada rasa benci, hanya perpisahan yang tidak kuasa dihindari lagi. Aku diberikan didikan agama secara formal saat kecil. Aku tunaikan salat fardu lima waktu meskipun ada saatnya dengan gampang aku meninggalkannya. Kemudian aku berangkat untuk kuliah ke luar negeri saat berumur 19 tahun. Selama transit dua hari di Singapura aku membeli banyak barang dan terpaksa mengeluarkan beberapa barang untuk tidak dibawa. Aku mengeluarkan sajadah dan kitab terjemah AlQuran. Keduaduanya aku tinggalkan di sebuah masjid di Singapura. Aku serahkan kepada pekerja masjid. "Anak ne nak pegi mane?" tanya pekerja masjid dalam logat yang kental. "Kuliah di Inggris," kataku cobacoba meniru logatnya. "Oooo mengape tak bawa saje?" "Beg dah penuh," kataku. "Di UK nanti pun mungkin saya tak akan solat lagi." Aku menggoncangkan kedua dua bahuku. Pekerja di masjid itu menerimanya dengan senyum. Ia mengucapkan terima kasih dan berjanji akan menyimpan barangbarang tersebut. Peristiwa ini sudah lama, zaman remajaku. Terkenang peristiwa ini aku mengambil cuti untuk ke Singapura mengunjungi masjid
132
tersebut. Pekerja masjid yang menerima barangku dahulu sudah tua namun masih ingat kepadaku. Ia memelukku. "Ne budak yang pegi ke UK dulu ye?" Ia menatap mukaku dengan senyum. "Iya," kataku. "Bapak masih ingat saya." "Pakcik selalu berharap yang anak akan kembali ke mari," katanya. "Barangbarang anak masih pakcik simpan." Katanya tidak apaapa jika aku mengambilnya kembali karena saat menyerahkannya dulu pun aku tidak meniatkan dan tidak menyatakannya sebagai wakaf. "Anak ambillah balik karena anak lebih memerlukannya dari orang lain," katanya, persis ia tahu kondisiku saat itu. "Itu tanggung jawab anak pada diri sendiri." Ia menyerahkan barangbarang tersebut: sehelai sajadah pemberian almarhum ayah, dan terjemah Al Quran pemberian almarhumah mama. ********** Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orangorang yang paling merugi perbuatannya?" Yaitu orangorang yang telah siasia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik baiknya. Mereka itu orangorang yang telah kufur terhadap ayatayat Tuhan mereka dan (kufur terhadap) perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalanamalan mereka, dan Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi (amalan) mereka pada hari kiamat. AlKahfi ayat 103105 **********
133
52 TEBING KETIGA
A
ku takut pada anjing. Sialnya, anjing pula seperti tahu yang aku ini takut kepada mereka. Mereka seperti senghaja menggonggong kepadaku jika aku lewat. Anjing yang sama tidak berbuat begitu kepada orang lain. Aku akan lari lintangpukang sekalipun yang menggonggong itu anak anjing. Aku coba juga melawan rasa takut ini ketika aku berjalan kaki ke toko untuk membeli paracetamol, obat panas dan sakit kepala. Aku berjalan santai dengan seluar jeans biru dan baju Thitam yang ada gambar band rock di dadanya dan tengkorak di belakangnya. Tidak ada anjing. Dalam perjalanan pulang aku membayangkan dunia tanpa anjing ketika itulah ada salakan yang kuat mengagetkanku dan aku terus berlari sekencang mungkin. Aku berlari dengan tidak melihat ke belakang lagi. Aku terdengar bunyi tapaktapak kaki kecil mengejarku dengan salakan yang terusmenerus. Aku tidak tau ke mana lariku. Aku kira aku telah melimpasi rumahku. Aku berlari terus. Di satu kelok, aku tampak ada anak sungai yang disebabkan oleh rasa takutku aku merasa aku bisa lompati ke tebing sana. Airnya deras. Kautau, sungai cuma memiliki dua tebing, tetapi ketika aku berada di atas saat melompat itu, aku tampak dengan jelas tebing ketiga. Di tebing ketiga inilah aku jatuh. Seperti ketibaanku sudah diramalkan dan dinanti nantikan, aku disambut dengan pukulan kompangan dan lagu marhaban. Aku diarak ke sebuah rumah. Tuan rumah memperkenalkan dirinya sebagai Kepala Desa.
134
"Ini adalah perkampungan orang halus," katanya. "Kami sekarang sedang dilanda musibah penyakit yang telah membunuh anakanak, orangorang tua dan wanita yang sedang mengandung. Tuan adalah Kejaiban yang kami nantinantikan. Tuan adalah Sang Penyelamat." Aku anak 'rock' tentunya merasa aneh digelar Keajaiban dan Sang Penyelamat, namun ketika disebut ada anakanak menderita sakit timbul rasa pilu di hatiku. Kepala Desa membawa aku masuk untuk melihat anaknya yang sakit. Katakanlah apa yang kaumau, di samping takut pada anjing aku juga memang sentimental, melihat kondisi anak ini yang sangat lemah, aku meneteskan airmata. Aku menyentuh dahinya panas. Tapi tidaklah sepanas demam yang biasa orang kita alami. Mungkin bagi orang halus ini sudah sangat panas. Aku memegang pergelangan tangan anak ini denyut nadinya lemah sekali. Apa yang bisa aku buat? Aku teringat paracetamol di dalam kocek jeansku. Aku meminta segelas air beserta sendok teh. Aku melarutkan sebiji paracetamol obat sakit kepala ke dalamnya. Bismillah, kucicipi bibir dan lidah anak ini dengan sendok air obat tersebut, hanya tiga tetes. Suhu badannya tiba tiba menurun dan nadi di pergelangan tangannya kembali. Ia sembuh segera. Aku telah mengobati lebih lima puluh orang pada hari itu dengan hanya sisasisa dari segelas air larutan sebiji paracetamol itu tadi, dan masih ada 99 biji di dalam botol yang kubeli tadi. Aku diam di desa ini untuk beberapa waktu, memonitor dan memastikan penyakit yang menimpa desa ini tidak akan kembali. Meski aman dan damai aku rindu juga untuk pulang. Orangorang di sini tidak tahu macam mana hendak mengirim aku pulang. Aku diberikan ganti pakaian dan tempat tinggal. Aku
135
tinggal di sana lebih sebulan. "Bersabarlah," kata Kepala Desa. "Bila saatnya, tuan akan pulang juga. Bagaimana tuan datang begitu jugalah tuan akan pulang." Bukan sekali dua, hatiku tergerak untuk menikah dengan gadis di sini mereka semuanya cantikcantik dan ayu. Pasti tidak ada yang akan mampu menolak lamaranku karena jasaku. Cuma akalku menolak, di samping alam ini bukan alam yang aku diciptakan untuknya, aku juga membutuhkan adrenalin dunia kita. Di sini semua terlalu aman, semua damai, semua tenang, burungburung berkicauan, angin sepoisepoi berpuput nyaman sepanjang masa menebarkan keharuman bungabunga yang berbagai warna yang aku tidak tahu namanya, dan yang penting tidak ada anjing atau benarkah begitu? Satu sore ketika aku berjalanjalan di sebuah denai dengan keduadua tangan kusilang ke belakang, aku terkejut oleh salakan anjing. Aku berlari sekencang mungkin. Aku berlari, terus berlari, tidak melihat ke belakang lagi. Aku terdengar bunyi tapaktapak kaki kecil mengejarku dengan salakan yang terusmenerus. Di satu kelok aku nampak ada anak sungai yang aku rasa aku bisa melompat ke tebing sana untuk menyelamatkan diri. Airnya deras. Ketika aku berada di atas saat melompat itu, aku tampak dengan jelas tebing ketiga. Di tebing ketiga inilah aku memilih untuk jatuh, aku menanda tempat aku jatuh itu. Kemudian aku langsung pulang ke rumah. Menurut anggota keluargaku, aku telah gaib selama setahun. Aku nampak sehat dan berseriseri dan bajuku pula tampak aneh sekali. "Baju dukun," kata kakakku. "Mana sih bajut rock
136
favoritmu?" Ya, jika sesekali aku gaib, tahulah kamu ke mana pergiku, aku rindu juga gadisgadis di sana. Sekali sekala timbul juga keinginanku untuk menikah dengan seorang dari mereka. Mungkin satu hari nanti akan ada yang jatuh cinta kepadaku, dan mau menikah denganku bukan karena jasaku. Entah apakah itu jasa atau bukan karena aku telah mengenalkan paracetamol ke alam mereka, obat sakit kepala dari Barat yang sangat biasa di alam kita, yang punya kesan sampingan buruk kalau diambil berterusan.
137
53 AKU LAGI LEBIH ....
K
adangkadang timbul juga rasa bosan kami sama si Jamil. Hampirhampir dalam semua hal si Jamil tidak mau kalah. Kalau berbicara atau bercerita ia mau menang melulu. Ingin sekali kami mendengar ia mengalahkan diri sekali pun cukuplah. Percakapan yang paling normal sekalipun ia tidak ingin kalah. "Aku terbangun awal pagi tadi," kataku, ngobrol sama temanteman di kantin. "Jam tiga pagi, lalu aku nda mau tidurtidur lagi." "Aku lagi lebih awal bangun," Jamil memotong cakapku. "Aku terbangun jam setengah dua." Aku memandangnya, kawankawan pun memandangnya juga. Kami terdiam. Aku lupa apa yang mau kuceritakan berikutnya. Satu saat kami lagi ngomongngomong tentang zaman persekolahan kami, memang banyak sekali kenakalan dan kenekatan yang kami lakukan. Memang menyenangkan berceritacerita santai seperti ini penuh dengan kelucuan. Kemudian Jamil datang dan langsung membajak cerita kami. "Aku lagi lebihlebi nakal saat kusekolah dulu," Jamil membuka ceritanya. Seorang kawanku bangun pamit karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan segera. Kawanku yang seorang lagi permisi karena mau buang air besar. Seorang kawanku lagi bangun karena ia akan pergi ke bank membayar utang kartu kriditnya. "Khawatir nanti didenda telat bayar," katanya. "Sudah
138
dua kali aku didenda telat bayar." "Uh, aku sudah lima kali," kata Jamil. Kawanku itu memandang muka Jamil. Aku tahu Jamil bukan senghaja ingin menang melulu tetapi memang sudah tabiatnya begitu. Aku senyum saja. Tinggal kami bertiga, aku, Jamil dan seorang kawanku lagi, Sobri. Sobri memang tidak bisa diandalkan untuk bercerita karena ia pendiam. Aku pula sudah lupa apa lagi yang mau diceritakan. Aku pun berdiri hendak meninggalkan Sobri dengan Jamil. "Kemaren," kata Sobri tibatiba. Aku duduk kembali. Ingin sekali aku mendengar cerita si pendiam ini. Kalau tidak menarik tentu ia tidak akan bercerita. "Kemaren," kata Sobri, memulai kembali setelah aku duduk. "Aku telah membuat sesuatu yang paling bodoh ...." Belum lagi habis omongannya ia sudah dipotong Jamil. "Aku lagi lebihlebih bodoh," kata Jamil. Sobri berhenti bercerita. Ia memandang wajah Jamil. Aku memandang wajah Sobri, ia seperti senyum halus. Pendiampendiamnya, memang kurang ajar temanku yang seorang ini. Memang kurang ajar si Sobri ini!
139
54 DESA YANG TENANG
P
eristiwa paling buruk dalam hidupku adalah ketika orang tuaku bertengkar. Perkelahian mereka begitu intens sehingga aku ketakutan dan lari bersembunyi di bawah ranjang. Aku akan berada di bawah tempat tidur itu sampai besok pagi. Mereka tidak peduli lagi akan perasaan anak kecil sepertiku. Saking traumanya aku hingga sekarang aku tidak bisa melihat orang berkelahi; aku akan menangis dan ngompol. Mereka mulai bertengkar ketika aku berumur sembilan tahun lebih. Aku adalah anak tunggal dan sering kali pula aku merasakan bahwa akulah penyebab utama perkelahian mereka. Ketika krisis mereka berdua bertambah runcing ayah pun mengirim aku untuk diam bersama kakek di sebuah desa terpencil. Aku tidak pernah ke desa itu tetapi kakek sesekali ke kota menjenguk kami dan untuk mengobati aku jika aku demam. "Kau akan tinggal dan bersekolah di desa kakek," kata ayah. "Sementara saja." Di sekolah kota, desa digambarkan sebagai tempat yang aman damai, tidak ada kejahatan, penduduknya hidup dalam harmoni sesama sendiri dan sama alam. Di desa kakekku ini tidak ada listrik dan tidak ada air pipa. Sebuah desa yang benarbenar terpencil dekat sungai. Jumlah penghuninya hanya sekitar 70 orang dan ini termasuk anakanak. Ada sebuah toko ritel yang kecil barang jualannya berdebu dan sudah kedaluwarsa. Ada sebuah sekolah (sebuah rumah buruk) yang hanya dihadiri oleh beberapa orang murid, hanya ada
140
seorang guru. Anakanak di desa ini datang ke sekolah tidak ikut waktu. Aku seharusnya berada di kelas enam tapi aku masih lagi di dalam kelas empat karena pelajaranku terganggu. Kedatanganku di desa ini tidaklah seperti yang kuharapkan. Aku merasa orang orang di desa ini tidak begitu ramah. Anakanaknya tidak ingin dibuat kawan. Saat aku bermain di depan rumah kakek, seorang budak seumur denganku datang. Ia tidak berbaju, hanya memakai celana pendek. Ia tidak memakai sepatu atau sandal. Ia mendekatiku dan berhenti dalam jarak dua meter. Ia memandangku dengan mata yang tajam kemudian dia menghentakkan tumit dengan kuat ke dalam tanah dan memutarmutarnya ke kiri ke kanan. Aku merasakan tubuhku seperti terputar dan aku tumbang. Ia meninggalkan aku sambil tertawa. Peristiwa ini aku ceritakan kepada kakek. "Itu anak Sipuli," kata kakek. "Dia ingin mencoba ilmunya." "Ilmu itu apa, Kek?" Kakek tidak menjawab karena ada sekelompok kalajengking merayap menuju ke arahku. Kakek mengetuk lantai tiga kali dengan buku jarinya. Kalajengking itu berbalik. Tidak lama setelah itu seorang pria seumur bapaku datang, mukanya hitam dipenuhi kalajengking. "Ampun, ampun, lepaskan aku," katanya. "Aku tidak buat lagi." "Ini cucuku," kakek memegang pergelangan tanganku. "Dia kosong jangan dicobacoba ilmu kamu kepadanya. Dan kawal anakmu." "Ya, ya," kata orang itu. KRASH! THUD!
141
Ada benda keras dan berat seperti jatuh di dapur. "Bukan aku," kata orang itu. "Itu bukan aku yang buat." Datang pula seorang pria yang kepalanya terpusing ke belakang. "Ampun, ampun," katanya. "Aku cuma mencobacoba budak kota itu. Ampun." "DIA CUCUKU," kakek memperingatkan. "Beritahu semua orang, jika ada yang ingin mencoba ilmunya, aku akan pusing kepala mereka ke belakang!" Ini baru hari pertama aku tiba di desa damai dan harmonis ini. Sore itu kakek membawaku mandi di sungai. Aku seram melihat air sungai yang berwarna gelap itu. Kakek menampar permukaan air tiga kali, dan ketika itu juga timbul beberapa ekor buaya. Kakek menepuknepuk tangan dan buayabuaya itu berenang cepat menuju ke hulu. Kami mandi. Dingin sekali airnya. Setelah salat Magrib kakek mengajariku caracara menarik napas dan mengeluarkan napas melalui mulut dan hidung. "Hu masuk hidung. Hu keluar mulut." katanya. "Hu masuk mulut. Hu keluar hidung." Tentulah aku tidak mengerti apaapa tapi aku mematuhi apa yang diajarkannya. Itulah yang aku lakukan, semakin lama, aku merasa tenang dan nafasku tenteram. Aku tidak tahu berapa lama aku melakukannya. Kakek menepuk bahuku. "Qamat, Kita solat Isya." Malamnya aku bertanya kepada kakek apakah aku yang menyebabkan ayah dan mama bertengkar. Kakek mengambil semangkuk air dan menyuruh aku melihat ke dalam air itu. "Kita hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi,"
142
kata kakek. Di dalam mangkuk itu aku terlihat ayahku sedang makanmakan di sebuah restoran mahal dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda dari ibu. Kakek mengocak air di mangkuk itu dan aku terlihat ibu asyik bercakapcakap di hpnya entah dengan siapa, dia tampak ceria. "Semua ini adalah penyebab untuk kaudatang ke mari dan berguru dengan kakek. Kau bernapaslah selalu selalu seperti yang kakek ajarkan tadi. Jika bisa biarlah bernapas kayak gitu sepanjang masa." Esoknya aku pergi ke sekolah. Termasuk aku hanya ada lima orang murid yang hadir: tiga orang perempuan, dua orang lelaki. Aku merasakan bahwa anakanak di desa ini sedikit sebanyak ada memiliki 'ilmu' dan ini termasuk tiga orang bocah perempuan itu. Saat guru mengajar mereka asyik bermainmain dengan pensil tanpa menyentuhnya. Pensilpensil itu terapungapung dan berpusingpusing di depan mereka. Bocah lelaki yang seorang itu pula duduk bersila di atas udara. Hanya aku yang duduk diam menarik dan mengeluarkan napas seperti yang diajarkan kakek. Guru itu seperti baru sadar yang aku adalah murid baru. "Kau pula siapa?" tanyanya. Aku pun memberitahunya bahwa aku baru pindah dari kota, tinggal bersama kakek. "Karena," kataku, "bapa dan mama tidak henti hentinya bertengkar." "Alhamdulillah," kata guru itu. "Akhirnya ada juga anak normal di desa ini." Aku memandang guru itu sambil terus bernapas seperti yang diajarkan kakek. Kemudian terlintas pula di hatiku agar guru ini terangkat naik. Ia terapungapung di
143
udara, kepalanya menyentuh plafon yang tidaklah begitu tinggi. Aku membiarkannya terangkat begitu beberapa saat. Kemudian aku menurunkannya perlahanlahan dan ketika sudah sedikit rendah, sontak melepaskannya. Buk! "Entah," katanya sendiri. "Mengapalah aku mengajar di desa ini yang anakanaknya sudah punya ilmu yang tinggi." Dia menyuruh kami pulang saja. Aku senyum memandangnya. Muridmurid lain juga senyum. Ketika kau memikirkan bahwa desa kecil, seperti desa ini, yang terpencil jauh di sudutsudut dunia itu aman tenteram, pikirlah sekali lagi. Setiap hari di desa ini aku dicoba dengan ular, kalajengking dan kelabang, pun begitu aku merasakan desa ini jauh lebih baik dari rumah tangga neraka.
144
55 PULANG KE BUMI
K
ami meninggalkan bumi. Ini adalah petualangan angkasa yang ambisius yang mungkin melampaui ruang dan waktu konvensional. Kami sekeluarga masuk kapal angkasa yang berbentuk bulat berdiameter satu kilometer ini dengan dada yang berdebardebar aku, istriku dan tiga orang anakku. Di dalamnya sudah ada keluargakeluarga lain yang terpilih secara random: seratus keluarga termasuk kami. Kami keluar masuk keluar dari satu sistem galaksi ke satu sistem galaksi yang lain. Kadang kala siang benderang memanjang, terkadang malam gelap hitam memanjang, tatapi hampirhampir sepanjang waktu keadaan adalah seperti waktu subuh. Kami singgah di beberapa planet yang dihuni makhluk bukan manusia; ada yang menyambut kami dengan curiga dan permusuhan; ada yang buat tidak apaapa saja seoalah olah kedatangan kami adalah pekara biasa. Paling menarik di sebuah di planet kami disambut dengan ramah dan besarbesaran. Ini adalah sebuah planet yang bulat seperti bumi juga. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang kami pahami dengan sedikit perbedaan dari segi sturktur ayat. DATANG SELAMAT KEMBALI Inilah tiga kata yang kami nampak jelas dari atas angkasa tertulis di tengahtengah planet ini. Kami memutuskan untuk singgah. Kami disambut dengan pukulan gendang dan bunga manggar. Rupa mereka seperti manusia dengan beberapa perbedaan yang signifikan seperti telinga mereka yang dua kali besar dan
145
lebar dari telinga kami. Mereka berbicara dengan suara yang rendah. Mereka memiliki mata yang kecil dua kali kecil dari mata kami. Tangan mereka lebih panjang dari tangan kami. "Ke Bumi datang selamat kembali," kata seorang tua yang kami kira seorang dari pemimpin di planet ini. "Kami dari Bumi," kataku mewakili rombongan yang turun. "Singgah sebentar kemudian nanti akan melanjutkan petualangan lagi sebelum kembali lagi ke Bumi." "Kamu mengerti tidak, kamu tinggalkan, yang telah lima ratus lebih tahun sebelumnya, asal inilah Bumi, asal tempat kamu kakeknenek. Sekarang kamu asal keturunan kembali sudah," kata orang tua itu. Tapi aku merasa seperti aku belum pulang. Betapa mesra sekalipun mereka menyambut dan melayani kami, aku tetap merasa seperti aku belum pulang. Ini mungkin Bumi asal tempat kakeknenek kami yang mengembara (seperti kami) kemudian menetap di sebuah planet yang mereka namai Bumi juga, tapi yang pastinya ini bukan Bumi yang kami tinggalkan dulu. Sebagian dari kami memutuskan untuk mengakhiri petualangan dan menetap di sini tanah air kakek nenek. Aku dan keluargaku dan beberapa yang lain lagi meneruskan perjalanan. Kapal angkasa kami masukkan ke 'mode autopilot'. Semua seting, koordinat dan sebagainya kami kuncikan menuju ke Bumi: kami ingin pulang. Kami tidak akan singgahsinggah di planet lain lagi. Kali ini kami masuk ke dalam 'cubicle'; akan tidur sepanjang perjalanan dan hanya akan bangun ketika memasuki atmosfer dan gravitasi bumi. Setelah tidur yang panjang akhirnya kami bangun, dan dari layar besar kami melihat permukaan bumi
146
dengan laut, awan dan cerobongcerobong pabrik yang mengeluarkan asap tebal hitam kelabunya, ladang ladang yang terbakar, pergolakanpergolakan di Timur Tengah yang ruparupanya belum selesaiselesai lagi, layar besar juga telah menangkap beberapa siaran dan laporan berita di televisi yang menunjukkan demonstrasi dan kerusuhan di kotakota utama dunia, dengan kata kata yang akrab: teroris, 'ethnic cleansing', 'homocide', LGBT, pemanasan global, korupsi, buang anak, 'Nigerian scams', kudeta, pilkada; juga pemandangan pemandangan rumah kumuh dan kemiskinan; entah berapa lama kami telah meninggalkan Bumi, kami tidak tahu karena waktu terasa seperti nonlinear sepanjang petualangan tersebut, yang jelasnya penduduk Bumi tidak banyak berubah. Aku benarbenar terasa seperti sudah pulang. Kapal angkasa memanfaatkan energi magnet untuk terapung setengah kilometer dari permukaan bumi. Kami baru saja siapsiap untuk mendarat ketika pesawat kami bergegar terkena beberapa tembakan misil. Di bawah kami terlihat tentara, tank, peluncur rudal dan kondisi masyarakat yang panik. Kali ini kami nampak dengan lebih jelas lagi meski kondisi manusia tidak banyak berubah: berperang, merusuh dan destruktif, tetapi penampilan mereka sudah jauh berubah, kepala mereka menjadi lebih besar, bersegisegi dan kulit mereka nampak sangat tebal. Mereka seperti manusia Neanderthal. Untuk membukitkan yang kami adalah manusia kami memancarkan hologram3D. "Kami mau pulang ke Bumi tercinta," kata kami melalui hologram tersebut. "Kami tidak kenal siapa kamu, makhluk asing, pulanglah ke planet asal kamu!" Terdengar suara nyaring
147
dari corong. "Kami akan terus meluncurkan misil jika kamu tidak pergi!" "Kami datang dengan damai," kata kami, meniru kata kata makhluk asing di dalam filmfilm Hollywood. "We come in peace!" Tiga biji misil diluncurkan. Kami tidak ada pilihan lain. Kami meninggalkan Bumi. Kami akan mencari planet lain untuk memulai hidup baru.
148
56 POTRET
S
emua anggota keluargaku tidak setuju pada rencanaku akan menikah dengan janda ini. Ia kira kira sepuluh tahun tua dariku dan punya sembilan orang anak. Meskipun kehidupannya susah, atau mungkin karena kehidupannya yang susah itulah membuat bentuk badannya langsing dan cantik. Tapi keluargaku tetap percaya aku telah dipelet oleh janda ini. Aku jatuh cinta pada senyumannya yang tenang dan ia nampak muda dariku atau paling tidak sebaya denganku. Ia bekerja sebagai buruh wanita. Ketika melihatnya pertama kali membuka tutup kepalanya, terbetik di hatiku, kasihan juga wanita secantik ini bekerja sebagai buruh. Ia berkulit putih. Aku membuat asumsi bahwa ia belum bersuami karena aku tidak dapat membayangkan suami macam mana yang sanggup membiarkan istrinya bekerja sebagai buruh berhujan dan berpanas (sementelah istri yang cantik sepertinya). Tentunya suami yang tidak sayangkan istri. Setelah mengamatinya, dan mencatat jadwal kerjanya, dan sekali sekala berpurapura mobil rusak dekat tempatnya bekerja itu, aku mengintipintip peluang untuk mendekatinya. Mulamula aku senyum saja dan berpurapura membuka kap mobilku. Pada waktu lain aku senghaja tidak memandangnya, dan pada waktu lain lagi aku menegurnya dan bertanya jika ada pipa terdekat karena tangki air mobilku kering, setelah aku merasa ia sudah terbiasa dengan kehadiranku, aku pun mengeluarkan jenakaku. "Mobilku ini berperangai aneh," kataku. "Sebaik terlihat kau, terus aja mogok, enjinnya jadi panas keluar
149
asap." "Ha ha," katanya. "Mobilmu tuh sudah jatuh cinta sama aku kali." "Ha ha," kataku. Macammacam usaha keluargaku untuk mengobatiku. Mereka menggunakan dukun, kataku kita bisa jatuh syirik kalau tidak berhatihati. Aku tidak menolak untuk diobati karena aku yakin aku benarbenar cinta padanya. Dan sampai sekarang tidak ada dukun atau ustaz yang berhasil mengobatiku. Apa salahnya aku menikah dengan janda? Cintaku padanya bertambah kuat saat aku berkunjung ke rumahnya yang kecil dan buruk. Ia seorang ibu tunggal yang membutuhkan pembelaan. Siapa lagi yang lebih ideal jadi pembelanya selain seorang pria yang mencintainya? Ia tidak pernah berbohong tentang status dan umurnya. Aku ingin sekali hendak mengeluarkanya dan keluarganya dari rumah usang ini. Di ruang tamu yang juga kamar tidur ini aku terlihat di dinding tergantung satusatu gambar yang sudah lusuh: potret lima orang pria. Aku bertanya siapa priapria tersebut. Ia pun memperkenalkan mulai dari bingkai yang paling kiri. "Itu laki pertamaku," katanya. "Ia meninggalkan aku saat aku beranak tiga, ia orang seberang, akulah yang menceraikannya karena ia nda balikbalik sampai setahun lebih. Itu lakiku kedua, ia meninggal karena kolera. Dangan ia aku dapat anak lima orang. Ia laki yang baik. Ngapa sih orang baik cepat matinya? Lakiku yang ketiga aku minta cerai karena ketahuan curang sama perempuan lain. Aku nda mau dimadu. Lakiku yang keempat mati kecelakaan mobil, nyetir terlalu laju, dangan ia aku dapat anak seorang. Lakiku yang kelima masuk penjara dan aku minta cerai, ia tertangkap basah
150
coba memperkosa anak tirinya anakku. Kalau kau benarbenar sanggup jadi lakiku, 'kan kugantung juga potretmu di sana. Laki yang keenam. Aku pasrah apa saja yang ditakdirkan bagiku." Aku suka caranya bercerita yang polos itu. Kalau sudah cinta, kita sanggup melakukan apa saja, kita tidak peduli apa yang orang lain mahu katakan. Esoknya aku datang lagi ke rumahnya membawa hadiah istimewa. "Nah," kataku. "Ini potretku. Silahkan gantung di sana. Aku berjanji taun ini kita akan nikah. Insya Allah."
151
57 BUNGA
B
UNGA besar itu tibatiba saja ada di simpang tiga itu, tumbuh di seberang parit. Ia seperti kaca yang memantulkan warnawarna pelangi. Ibuibu dan bapak bapak yang dalam perjalanan menghantar anak ke sekolah berhenti untuk melihatnya. Mereka mengambil foto bunga tersebut dengan ponsel. Bunga itu tegak setinggi 1,5 meter. Bergoyanggoyang ditiup angin pagi. Setiap orang memuji kecantikan bunga itu. "Cantik!" "Sundar!" "Lawa!" "Maganda!" "Beautiful!" "Magnifique!" "Swy!" "Schön!" Seorang pria memberanikan diri melompat parit yang kecil itu lalu menciumnya. "Phoah!" katanya. "Shit! Busuknya!" Ada lagi beberapa orang yang lain menciumnya karena tidak percaya bunga secantik itu berbau busuk. "Bushuk!" kata mereka. Mereka baru saja hendak meninggalkan bunga itu ketika seorang pria melompat parit kecil lalu menciumnya sambil memejamkan mata dan tersenyum senyum lebar. "Hmmmm," katanya. "Harum semerbak mewangi!" Meskipun baunya busuk karena ia seorang pria yang mencintai apa saja jenis bunga dan ia tidak suka bunga
152
dihina. Ia menanam berjenisjenis bunga di rumahnya. "Hmmmmm. Harummm!" Kemudian ia mendengar suara orang riuhrendah lalu ia membuka matanya. Orang menunjuknunjuk ke arahnya. Ia memandang ke belakang; bunga itu sudah tidak ada. Di situ berdiri seorang gadis muda yang sangat cantik bagai bidadari turun dari langit tersenyum senyum manis dan malu kepadanya. Banyaklah pria yang menyesal pada hari itu. Alangkah bagusnya kata mereka, kalau kata 'busuk', 'bushuk', 'shit' tidak pernah ada di dalam kamus. Gadis itu mengikuti pria pencinta bunga. Pria pecinta bunga menjual semua bungabunga yang ditanamnya sehingga habis karena gadis itu sangatsangat cemburu kepada bunga.
153
58 DI DALAM LIF
A
ku terperangkap di dalam lif yang rusak bersama istri dan mantan istri. Kami berada di lantai 12. Kami mau turun. Lantai paling atas adalah lantai 15. Ketika aku dan istriku masuk, lif ini sudah hampirhampir penuh. Cukupcukup untuk dua orang saja lagi. Dalam kerumunan seperti ini, berbagai bau menusuk hidung kita bau hapak, bau keringat hangit, hanyir malah bau hancing. Istriku memegang erat lenganku, sehingga terasa dadanya menghempit tubuhku. Aku senyum melihat wajahnya. Aroma minyak harum yang dipakainya membelai berahiku. Jika ini bukan tempat publik pasti kukucup bibirnya. Kami baru sebulan lebih menikah dan ini adalah kali kedua aku menikah. Ia duapuluh tahun lebih muda dariku. Jodohku dengan istri pertamaku tidak berkepanjangan. Ia yang minta cerai setelah aku sendiri menceritakan kepadanya tentang orang ketiga yang baru kukenal dan aku telah jatuh cinta seperti jatuh cinta pertama kali. Aku ingin memperkenalkan mereka berdua karena menyangka istriku yang selalu lemahlembut kepada suami itu pasti tidak keberatan aku menikah lagi. Memang bodoh sekali aku, sangkaanku salah; mukaku dicakar dengan kukukukunya yang kebetulan belum sempat berpotong. Sejak kawin akulah yang memotong kukukukunya setiap hari Kamis, sebagai persiapan ramah menghadapi malam Jumat. Hal ini memang ditunggutunggunya sebagai sesuatu yang sangat istimewa dan pribadi. Ketika dua Kamis berturutturut
154
aku lupa memotong kukunya itu ia mulai curiga. Hanya dua Kamis ia sudah bisa menebak. Dengan lembut ia bertanya langsung ke dasarnya. "Siapa perempuan itu?" Aku mengambil kesempatan ini untuk menceritakan semuanya. Begitulah mukaku dicakar oleh kukukukunya yang dua minggu tidak berpotong. Habislah mukaku berdarah, bercalar goresan merah pedihnya sampai beberapa hari setiap kali tersentuh air. Kini kukukuku istriku yang sekarang inilah yang kupotong setiap hari Kamis. Kami akan duduk berdepanan bertemu lutut dan aku akan mengambil tangan kanannya dan mulai memotong kukukukunya, memperhalus bekas potongan itu dengan kikir. Selanjutnya aku mengangkat kakinya dan meletakkannya di atas pangkuanku dan mulai memotong kukukuku kakinya, sesekali mengeletiknya sehingga ia kegelian. Ia juga menunggununggu upacara 'manicure' setiap hari Kamis ini dengan penuh antisipasi. Lif ini berhenti di setiap lantai; ada saja orang yang keluar. Aku tidak pula ambil peduli sangat karena asyik menatap wajah istriku ini aku benarbenar jatuh cinta padanya. Hari ini hari Kamis dan ia seperti tidak sabar sabar hendak pulang ke rumah. Aku hanya sadar ketika terdengar bunyi geselan yang keras dan kasar. Lif ini bergetar, ketarketar seperti nyawanya sedang sakarat, kemudian berhenti dan mati. Aku menekan tombol darurat dan menunggu pertolongan datang. Lampunya mati. Gelap seketika, kemudian lampu darurat nyala. Ketika inilah aku menyadari di dalam lif ini hanya tinggal tiga orang: aku, istriku dan seorang wanita seumur denganku mungkin satu atau dua tahun tua dariku. Wanita ini senyum sumbing padaku. Barulah aku
155
sedar bahwa ia adalah mantan istriku memakai baju warna hijau ringan, warna favoritnya. Ia memandang aku dan istriku dari atas ke bawah berulang kali. Aku melihat kukunya panjang. Melihat aku, mantan suaminya, tercegat di situ, ia mengetikngetik kukukukunya itu satu satu dengan ibu jari. "Lif macet," kataku dengan payah. "U um," katanya, senyum sumbing tetap di bibirnya. Kemudian kami diam. Aku menekan tombol darurat beberapa kali lagi. Ini darurat besar. Istriku memegang erat lenganku. Ia belum tahu yang wanita itu mantan istriku. Mantan istriku memandang istriku dengan mata yang tajam dengan kepala yang miring dan tunduk sedikit. Setelah lama merenung wajah istriku ia pun melirik padaku. "Pantas banget," katanya dengan senyum halus. Mungkin sekarang ia faham dan mengerti kenapa aku jatuh cinta pada istriku ini. Baguslah kalau begitu. Aku tidak tahu apa yang akan kucakapkan. Aku memandang kukunya yang panjang itu ada terlihat sedikit dakidaki berwarna hitam. Mungkin ia jarangjarang memotongnya sejak kami bercerai. Melihat aku menatap kukunya yang panjang itu, mantan istriku tertawa kecil. Ia memamerkan kukukukunya itu kepadaku. "Panjang banget tuh," kataku dengan gugup. "Sangat berguna untuk mencakar muka," katanya. "Grrrrrrrgh!" Ia berlakon seolaholah hendak mencakar mukaku. Aku kekagetan. Aku mundur sedikit. Kemudian kami diam. Lif mulai bergerak turun. Aku melepaskan nafas lega. Di mobil istriku bertanya siapa wanita itu. Aku menjawab bahwa saat terkurung di dalam lif rusak, kita
156
manusia, terkadang berperilaku yang anehaneh sebagai pelepasan dari 'stress'. "Mukanya mirip mukaku," kata istriku. "Tapi dia sudah tua." Aku diam saja. Memang benar, wajah dan sosok istriku ini persis wajah dan sosok mantan istriku saat ia muda, pertama kali aku jatuh cinta padanya. "Potong kuku nanti ya bang," kata istriku. “Iya,” kataku.
157
59 BAYANGBAYANGKU
B
ayangbayangku memprotes. "Aku tidak ingin ikut kau lagi," katanya. "Aku ingin bebas merdeka." Jam sembilan pagi. Cuaca cerah, matahari memancar terik. Bayangbayangku memang jelas tampak di atas aspal. Aku ada urusan penting yang harus diselesaikan di warung kopi. Ini bukanlah waktu untuk bertengkar dengan bayangbayang. Semua orang ingin bebas merdeka. "Aku sudah bosan ikutkau ke warung," katanya. "Aku ingin ke tempat lain." Seorang pria gemuk melihat bayangbayangku. "Eh," kata pria gemuk itu. "Kok, bayangbayang Mas bisa bicara." "Iya. Dia mang gitu. " "Apa sih dimaunya?" "Dia mau merdeka," kataku. "Matahari baru panas sedikit, dia sudah sombong." Pria gemuk itu memandangku dari atas ke bawah: "Mas ini hantu atau orang?" Aku menginjak bayangbayangku dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri aku angkat dengan mendadak, terputuslah bayangbayang di kaki kiriku. Aksi yang sama aku lakukan untuk kaki kanan. "Kau bebas sekarang," kataku. "Byebye," kata bayangbayangku dengan girang. "MERDEKA!" Pria gemuk itu melihat bayangbayangku lari menyeberang jalan dan aku berjalan dengan tenang
158
menuju ke warung kopi. Aku memandang ke belakang dan terlihat pria gemuk tadi menirukan aksiku tapi bayangbayangnya tetap menempel di kakinya. Tidak semua bayangbayang ingin bebas. Pada dasarnya juga tidak semua bebas itu merdeka, dan tidak semua merdeka itu bebas. Bayangbayang itu tetap bayangbayangku. Aku tahu ke mana ia pergi, tapi ia tidak tahu yang aku tahu. Aku tahu di mana ia berada, tapi ia tidak tahu di mana aku. Aku nampak apa ia lakukan, tapi ia tidak nampak apa yang aku lakukan. Aku tahu sekarang ia lagi menyusupsasap di celah bayang bayang orang lain di pasar sayur. Ada orang merasa curiga ketika terimbas sesuatu yang gelap bergerak gerak di antara mereka. Bayangbayangku menjadi lebih berhatihati. Aku senyumsenyum sendirian di warung kopi ini. "Minumnya apa pak?" Aku memesan kopi dan murtabak. Aku tampak bayangbayangku coba menggoda bayangbayang tiga orang perempuan Filipina yang sedang berwisata. "It's weird," kata seorang dari mereka. "The shadow!" "What's it doing?" kata seorang lagi. "Nangko, itu flirting with our shadows!" "Ha ha, it's a playboy shadow for sure." Aku makan, aku minum. Ada sedikit keributan di luar. Bayangbayangku ingin bergabung denganku kembali. Ia sedang mencaricariku. Aku akan membiarkannya dulu. Orang banyak sedang memerhatikannya. Aku tahu ia tidak merasa nyaman diperhatikan seperti itu. Ia mencoba berpurapura jadi bayangbayang orang lain tapi orang lain itu melarikan diri takut. Bayangbayangku lari dari satu orang ke satu orang. Tidak ada yang mau
159
menerimanya. "Eh, eh," kata orang sambil melompat ke tepi. "Ngapa dia?" Kemudian pria gemuk awal tadi muncul di celah celah orang banyak. "Aku tau bayangbayang ini punya siapa," katanya. Ia menjenguk ke dalam warung kopi. "Kebetulan dia ada di dalam." Aku mengakhiri makan minumku, membayar di konter lalu keluar. "Mas," kata pria gemuk, "bayangbayang Mas kayak orang sesat gak ada tujuan." "Iya," kataku. "Merdekanya gak ada tujuan." Aku menghentakkan kaki kananku. Bayangbayangku menepel di kaki kananku. Kususuli aksi sama dengan kaki kiri. Aku berjalan meninggalkan orang banyak.
160
60 (<>..<>)
hi, boleh ga aku datang ke rumahmu? boleh, tetapi bagaimana kautahu di mana rumahku? sekarang kau chatting deganku di mana? di rumahku ok ok apa? ok aku sudah dapat posisi rumahmu dengan hanya chatting kau bisa tahu? dengan teknologi primitif kamu aku bisa menjejak posisimu hahaha dengan teknologi kami aku bisa melihat ke dalam rumahmu hahaha bye bye goodnight Aku mengenal Krrrgt22 apabila ia mengadd aku di fb nya. Sudah setahun lebih kami jadi 'friends'. Ia banyak soal apabila berchatting. Aku pula lebih banyak menjawab kerana aku memang tidak percaya pada dunia siber. Namanya saja Krrrgt22 sudah menunjukkan yang ia tidak mahu sesiapa mengenalinya. Ia memperkenalkan dirinya kepadaku sama seperti informasi di fbnya. Tidak ada fotonya atau familinya. Tidak ada yang boleh dipercayai. Pagi ini ada message darinya di inboxku. hi, aku ingin meminangmu untuk anak daraku? hahaha, jelitakah anak daramu itu?
161
Ia menginboxku foto seorang gadis yang manis dan sangat cantik. wah, cantik benar anak daramu!!!! ini bukan anak daraku. anak daraku tidaklah sehodoh yang di dalam foto ini hahahaha wkwkwkwkwk lucu ok aku terima pinanganmu aku bukan mainmain aku juga, kebetulan aku masih jomblo ok berapa umur anak daramu itu? mengikut perkiraan duniamu 150 tahun tua amat! tidak, mengikut perkiraan dunia kami baru masuk remaja 15 tahun whatever, tapi masyarakat kamu primitif primitif? ya, pasangan anak daranya saja ditentukan oleh orang tuanya oh itu, jadi masyarakat kamu itu maju kerana anak anak mudanya boleh bergaul bebas sebelum menikah dan memilih pasangan sendirisendiri? iyalah, iyalah kaudatang sajalah bawa anak daramu itu, aku akan mengahwininya hi, ini aku (<>..<>) bakal istrimu hi, hahaha datanglah ke mari adinda alien, sekarang juga :* ok kami datang Aku bangun dari kerusiku dan menuju ke pintu kerana kebetulan ada bunyi ketukan. Aku seperti mengenali mereka, seorang lelaki, seorang perempuan
162
dan seorang lagi perempuan remaja. Perempuan remaja inilah yang menarik perhatianku, kecantikannya, kemanisannya, cahaya yang menyinar dari dirinya menyelinap hingga ke keseluruh jiwaragaku, ke setiap puripuri tubuhku, kesetiap sel jasadku: atomatomku bergetar dalam kelazatan. Aku rasa aku tidak akan mahu mengalihkan pandanganku dari wajahnya ke arah lain selama enam puluh ribu ratus tahun atau selama lamanya. Mereka ini bukan manusia. Mereka ini makhluk asing. Aku seperti terdengar bapanya itu bercakapcakap di dalam kepalaku. "Sudah, sudah," katanya. "Jangan kaugoda dia seperti itu. Kasihan bakal suamimu itu. Jiwanya masih primitif."
163
61 HUJAN
B
ersiapsiaplah," kata Kek Guntur yang berusia 101 tahun, lelaki tertua di Desa Suring kepada istrinya. "Hujan akan turun selamalamanya di desa ini." Ia menyatakan ini seolaholah ia satu perintah dan bukan pernyataan. Ia telah mengamati hujan ini turun sejak dari awal. Mulamula hujan turun tidak berhentihenti untuk tujuh hari tujuh malam kemudian pada hari kedelapan datang ribuan ekor katak dengan jumlah mereka semakin bertambah, ratusan ekor setiap hari, yang hijau, hitam, coklat gelap, yang cerah, merah, biru, jingga, yang berbintikbintik kuning, hitam dan bertaristaris, bahkan ada juga yang berwarna putih seluruhnya, seolaholah semua spesies katak di dalam dunia ini datang ke mari, melompat mengambil tempat masing masing untuk merayakan hujan yang turun sedang sedang lebat, berisik suara mereka tidak putusputus menggetar jagat raya sehingga orangorang terpaksa menutup pintu dan jendela karena takut katakkatak ini akan masuk menguasai rumah mereka, berpikirpikir apa ini hujan katak, apa ini pertanda sesuatu akan terjadi, apa akan terjadi kiamat atau perang dunia ke3, namun katak katak ini tidak berniat hendak masuk karena jika mereka hendak masuk mereka bisa saja masuk melalui lobanglobang lantai bambu yang jarang, mereka betah di luar rumah, ada di manamana, yang besar, yang kecil dan sederhana, di daundaun hijau yang basah dan di dahandahan pohon, di dinding dan atap rumah, di tangga, di halaman, di jalanraya, membiarkan tetestetes
164
hujan menimpa diri mereka, dan suara Tung! Tung! sepesis kodok menggema setiap sepuluh menit mengiringi suara krikkrikkrik kroakkroak kroak yang tidak putusputus dari pagi sampai ke malam dan bersambung lagi ke pagi besoknya, yang bau amis dan hanyirnya menusuknusuk sehingga kau terpaksa menutup hidungmu dengan telapak tangan tapi lama lama penduduk Desa Suring ini menjadi terbiasa dengan bau ini, terbiasa dengan hujan yang tidak berhentihenti, bunyi tetestetesnya menimpa atap mengisi setiap jaga mereka dan masuk ke dalam tidur, dan apabila mereka terbangun, sulit untuk tau apakah sudah siang atau sudah malam. Tubuh Mba Melati yang berusia 30 tahun, istri yang ke sepuluh, istriistri yang sebelumnya sudah meninggal semuanya kecuali seorang yang kabur ke kota bersama seorang pria muda, berbungkus selimut buruk yang berbau hapak karena udara yang lembab. "Dingin," bisiknya lebih kepada diri sendiri dari kepada suaminya. Mba Melati memandang suaminya itu melangkah dengan tangkas di ruang dapur menutup setiap tajau dan bekas penyimpan air. Kek Guntur kemudian menjenguk ke luar jendela pada katakkatak yang berkumpul di halaman rumahnya saking banyaknya tampak seperti hamparan karpet. "Kalau kita tidak menutupnya," kata Kek Guntur, "katakkatak bisa masuk dan kita tidak akan ada air untuk diminum meski hujan sepanjang tahun." (fragmen work in progress)
165
62 DI KLINIK
S
aya menemani suami ke klinik. Bukan, ia yang minta ditemani. Jadi kalimat yang benar adalah: Suami saya minta kepada saya untuk menemaninya ke klinik. Ia ada perjanjian dengan dokter. Sebenarnya saya tidak mau dikatakan sebagai istri yang tidak memberi kebebasan kepada suaminya sehingga pergi ke klinik saja harus ikut. Kalau mau dipikirpikirkan, di klinik ini ada beberapa dokter perempuan yang muda dan cantik. Saya tidak mau ikut sebenarnya, ada pekerjaan di kantor yang harus diselesaikan tapi saya minta izin dari bos untuk keluar. Saya harus mengampu bos untuk keluar menemani suami ke klinik. Saya sangat sayang suami saya. Selama menunggu gilirannya di klinik ini, saya memegangmengang tangannya dan menyandarkan bahu ke bahunya. Saya melihat wajahnya. Suami saya memang tampan. Memang saya merasa ada mata yang memperhatikan saya menggeselgesel bahu ke bahu suami saya peduli apa mereka! Saya sayang suami saya. Kalau saya tidak sayang tidaklah saya mau sampai repotrepot menemaninya ke klinik. Sebenarnya saya yang menawarkan diri untuk menemaninya, maafkan saya karena berbohong awal tadi. Kita tidak bisa melepaskan suami kita (terutamanaya yang tampan seperti suami saya) ke klinik yang dokter perempuannya cantik dan mudamuda. Saya tidak tahu mengapa suami saya ditahan lamalama di dalam kamar dokter itu. Pintu pula ditutup. Bukan tertutup; ditutup! Tup! Di pintu itu ada label nama dokotor: Dr.Nur Amalyina Syafikah. Cantik namanya. Harus cantik seperti orangnya juga. Apa saja
166
yang dilakukan Dr.Nur Amalyina Syafikah itu lamalama di dalam kamar yang ditutup pintunya itu? Apa saja yang suami saya buat bersama dokter itu? Barangkali suami saya itu ada perselingkuhan dengan dokter itu. Bila saya pikirpikir, memang ini benar suami saya ada 'appointment' setiap bulan dengan dokter ini sejak enam bulan lalu, saya kira sejak tujuh bulan lalu atau mungkin sejak delapan bulan, bisa saja sembilan bulan lalu. Memang suami saya itu berlaku curang terhadap saya! Celakalah saya! Saya tidak rela berbagi kasih sayang suami dengan orang lain! Tidak! Tidak! Tidak! Tidak! Ini semua khayalan saya suami saya memang setia kepada saya. Mengapa lama sangat suami saya ditahan di dalam kamar yang ditutup itu? Apa saja yang Dr.Nur Amalyina Syafikah rundingkan dengan suami saya itu? Barangkali ia ingin suami saya menceraikan saya. Sial! Barangkali mereka sudah terlanjur dan dokter perempuan goblok itu telah bunting tujuh atau delapan bulan. Shit! Shit! Shit! Shit! Shit! Saya menunggu hampir hampir seribu tahun baru suami saya keluar dengan senyuman di bibirnya. Dokter cantik itu mengantarnya sampai ke pintu! Dokter itu mengirim suami saya sampai ke pintu? Ini tidak sepantasnya! "Jangan lupa appointment dalam waktu sebulan lagi, ya," kata dokter itu. Huh, bepurapura! Ia membuka pintu itu besarbesar memanggil pasien yang lain. Saya melihat perut dokter itu buncit besar, paling tidak bunting tujuh bulan! Saya mendapatkan suami saya. Saya mencoba mengontrol diri; tapi tangan saya memiliki akalnya sendiri. Paap! Saya hempas kepala suami saya dengan tas tangan. "Apa saja yang kaubuat di dalam kamar itu," tanya saya, "sehingga dokter itu bunting tujuh bulan?"
167
Suami saya memandang saya. Saya pukulkah ia tadi? Apa benar saya pukul ia tadi?
168
63 PINDAH
H
ari ini hari ulangtahun ke10 aku mati. Aku tidak ingin memberikan namaku meskipun aku sudah sepuluh tahun mati. Kautau orang hidup bisa saja menggugat dan menyusahkan orang mati. Aku mau membuat 'disclaimer' di sini: Cerita ini tidak ada hubungannya dengan orang yang hidup maupun yang sudah mati hahaha. Aku lahir pada tahun 1962 dan meninggal pada tahun 2002. Mati kecelakaan lalulintas. Mati ketika berumur 40 tahun. Aku dikubur di pemakaman dekat dengan jalan raya. Cerita ini bukanlah tentang kematian atau kecelakaan jalan raya cerita seperti itu di samping tidak enak juga terlalu mengerikan. Ini tentang satu aspek kehidupanku yang pendek. Hidupku tidak pernah menetap. Dari kecil aku pindah dari satu desa ke satu desa tergantung di mana ayahku ditugaskan. Kadangkala ayahku ditugaskan di satu tempat sehingga tiga tahun (itu yang paling lama) sebelum dipindahkan ke tempat lain. Aku yang baru 'settled down' dan mendapatkan teman karib akan pindah ke tempat lain, dan memulai kembali kehidupanku menemukan teman baru. Ini tidak mudah bagi anakanak sepertiku, aku membesar tanpa ada seorang teman karib. Ada kalanya aku belum sempat berkawan baik dengan sesiapa, baru satu tahun, kami akan pindah lagi. Hidupku tidak habishabis pindah sana, pindah sini. Ketika aku sudah dewasa dan bekerja pun hidupku tidak menetap. Aku menikah ketika berumur 30 tahun dan tinggal di rumah keluarga istriku. Itu sudah pasti tidak kekal. Ketika beranak satu isteriku mendesak
169
supaya aku mencari rumah. Kami pindah ke rumah sewa. Angkut semua barang. Beli segala macam mebel. Aku rasa kali ini akan tetaplah hidupku sampai aku pensiun. Tidak juga, kami hanya tinggal di sana selama tiga tahun. Kawasan rumah tersebut dibutuhkan untuk satu proyek. Kami pindah lagi, ketika ini anakku sudah dua orang. Angkut barang lagi, lebih banyak dari pertama kali. Di rumah ini aku dan istriku merencanakan bahwa kami membutuhkan rumah sendiri sehingga kami tidak lagi berpindahpindah. Isteriku memiliki sebidang tanah, jadi dengan uang pinjaman aku pun mendirikan rumah di sini. Akhirnya kami pindah ke rumah sendiri. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati selain memiliki sebuah rumah yang bisa kita akui sebagai rumah sendiri. Aku membeli banyak barang dan peralatan rumah yang baru dan termodern. Inilah rumahku, inilah KUBUKU atau kata orang Inggeris "My house is my castle". Aku dan familiku akan bertahan di sini. Aku akhirnya akan berakar di sini. Akar yang tidak dapat dicabutcabut lagi. Tidak juga, cuma dua tahun lebih saja. Daerah rumahku ini termasuk dalam wilayah yang ada minyak di bawahnya. Kami diberikan sebuah rumah yang besar di atas sebidang tanah yang luas juga di tempat lain sebagai ganti dan uang kompensasi. Aku tidak ada pilihan pindah lagi. Aku hanya tinggal di rumah ini selama beberapa tahun (aku tidak peduli akan menghitung lagi), meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Aku sudah mati sekarang, dikubur di pemakaman dekat sebatang jalanraya. Di sini tetaplah sudah rumahku. Inilah rumah terakhirku. Akhirnya aku tidak akan pindahpindah lagi. Aku akan menetap di sini sampai hari kiamat. Tidak juga, kata mereka, (orang orang hidup itu dengan segala kepintaran mereka) jalan
170
raya ini terlalu kecil dan harus dilebarkan. Kata mereka demi pembangunan, kuburkubur ini harus dipindahkan. Kata mereka bukan semua kuburkubur ini harus dipindahkan cuma sebagian kecil saja. Dan sebagian kecil itu termasuklah kuburku. Pindah lagi.
171
64 MEMANCING
M
ata kail pancingku menyangkut pada sesuatu yang berat. Jika aku tarik dengan kuat tentu talinya putus. Aku belum dapat ikan lagi dan hari masih awal. Kopi dalam termos pun belum kuminum. Tanpa banyak pikir aku buka sepatu dan terjun ke dalam sungai itu dan jatuh terduduk di sebuah taman bunga, dengan kupukupu beterbangan dari kelopak ke kelopak yang mekar, burungburung berkicauan. Banyak pasanganpasangan pria dan perempuan berjalanjalan, dudukduduk di bangku yang tersedia. Cuaca sangat nyaman. Ke mana saja aku memandang, di taman ini, semua orang berpasangpasangan. Aku duduk seorang diri. Aku nampak seorang pria yang lebih tua dariku, yang berseragam coklat. "Teman mana?" tanyanya. "Tidak ada. Aku bersendiri." "Kau bukan orang sini?" "Bukan. Aku baru datang." "Oh, OK," katanya. "Sudah menikah?" "Belum," aku berbohong. "Kalau jomblo, pergi ke Taman Bunga Lajang di sana." Aku bangun, berjalan ke arah yang ditunjukkannya. Aku menoleh ke belakang, barulah tampak label Taman Bunga Berpacaran. Sebelum masuk ke Taman Bunga Lajang aku berjalanjalan dulu melihat tamantaman bunga di sini, labellabelnya jelas sekali: Taman Bunga Rumit, Taman Bunga Menikah, Taman Bunga Menjalin
172
Hubungan dan Taman Bunga Lagi Selingkuhan. Di masingmasing taman orangorangnya memiliki fiturfitur yang khusus misalnya di Taman Bunga Lajang orangnya ceria yang seperti dibuatbuat namun jelas ada yang malumalu berani; di Taman Bunga Rumit manusianya kusutkusut belaka. Aku terus saja masuk ke Taman Bunga Lajang dan nampak beberapa orang gadis yang senyumsenyum kepadaku. Aku membalas senyum kepada seorang dari mereka, lalu kami samasama berjalan mendekatkan diri. "Mau pacaran sama aku?" kataku. "OK," katanya, senyum dan mengangguk kepala. "Aku Gadizceriamiyntadicayangicilalu." "Owh, panjang banget namanya." "Panggil Cayang aja," katanya. "Aku," kataku, sambil sibuk berpikirpikir nama apa yang harus kugunakan untuk menandingi namanya. "Aku Cowokzetiazlagijujurcilalusampekiamat. Panggil Zetiaz aja." Kami pun keluar dari Taman Bunga Lajang menuju ke Taman Bunga Berpacaran. Kami berjalanjalan di Taman Bunga Berpacaran, dudukduduk di bangku, aku rasa sangat bahagia. Aku percaya Cayang juga merasa bahagia dan kami samasama memutuskan untuk pergi ke Taman Bunga Menikah. Di situlah kami bersiarsiar santai. Setelah punya beberapa orang anak, aku melihat Cayang sudah tidak seperti dulu lagi. Sesekali aku mencuri keluar dari Taman Bunga Menikah dan masuk ke Taman Bunga Rumit dan tanpa kusadari aku masuk ke Taman Bunga Lajang kemudian ke Taman Bunga Menjalin Hubungan. Saat bersantai di Taman Bunga Lagi Selingkuhan aku ternampak Cayang mondarmandir di luar dengan golok di tangannya. Ia memandangku
173
dengan mata yang melotot sehingga terasa perutku kecut lalu aku melaju lari. Cayang mengejarku dengan dibantu mertua dan beberapa orang lain yang tidak kukenal. Aku berlari kencang sehingga tidak bisa lari lagi karena di depan ada sebuah danau. Cayang dan orang orangnya melihat aku terperangkap terus ingin menangkapku. Aku terjun ke dalam danau itu, dan jatuh terduduk di tepi sungai. Aku mengemas barangbarangku, jam di hpku menunjukkan sudah hampir pukul enam sore. Ada beberapa pesan dan 'misscall' dari istriku. Aku telah berjanji kepadanya akan pulang sebelum siang. Sampai di rumah aku diinterogasi. "Dipesanpesan gak berjawab. Dimisscall gak berbalas. Ke mana saja abang sepanjang hari? " "Memancing," kataku. "Sehari memancing gak dapet apaapa!" "Benar Yang, aku memancing." "Memancing atau selingkuhan?" Aku pun menceritakan kepadanya apa yang terjadi sepanjang hari ini. Memanglah ia tidak percaya.
174
65 SERULING
A
ku bermimpi ada seruling bambu di belakang rumahku terkubur di bawah serumpun serai. Esoknya aku menengok rumpun serai itu. Ia telah mengeluarkan bunga. Isteriku yang tidak kuberitahu tentang mimpi ini mengatakan bahwa jika serai berbunga artinya ada benda terkubur di bawahnya. "Harta karun," katanya. "Barang antik dari logam." Kuceritakan kepadanya tentang mimpi itu. "Kalau seruling bambu pasti sudah hancur," katanya. Aku menggali tanah bawah rumpun serai itu dan menemukan sebuah seruling terbuat dari tembaga. Seruling tersebut kucuci dan gosokgosok sampai bersih dan mengkilap. Aku bukanlah seorang yang pintar bermain seruling, tetapi ketika aku mula meniupnya jarijemariku bergerak sendiri seperti bernarinari pada lagu yang tidak pernah kudengar. Merdu dan rancak iramanya. Ketika sampai pada satu tangga nada, badanku ikut melenggok lenggok asyik sesuai irama dan ritme. Aku mula berjalan meniup seruling tersebut sambil bernarinari. Ada bunyi berkerisikkerisik, mencicitcicit di kiri dan kanan; tikus tikus keluar melenggoklenggok dari semua rumah sepanjang jalan. Aku membawa tikustikus ini menuju ke selokan besar dan lebar yang airnya penuh karena hujan deras semalaman. Ketika sampai di tepi selokan aku meniup satu not berfrekuensi tinggi dengan panjang, sepanjang napasku, lalu tikustikus tersebut berterjunan ke dalam arus yang deras dan mungkin saja semuanya mati lemas.
175
Aku memeriksameriksa seruling ini. Ada tulisan Latin terukir di sisinya yang hampirhampir tidak tampak: Rattenfänger von Hameln. Ini pasti milik peniup seruling Jerman yang legendris itu. Di kota tentu banyak tikus, pada sorenya aku ke sana. Aku akan membawa semua tikustikus itu nanti berterjunan ke sungai biar tidak ada tikustikus lagi. Sambil bersandar pada tiang di kaki lima aku mula meniup seruling tembagaku. Jarijariku mula bergerak dengan akalnya sendiri memainkan sebuah irama berbeda dari yang pagi tadi. Ketika sampai pada satu tangga nada, badanku mulai melenggoklenggok dengan sendirinya. Musik yang keluar dari seruling tembaga ini semakin rancak. Dari tokotoko keluarlah anakanak muda dengan pacar mereka ikut bernarinari. Aku mula berjalan meniup seruling keliling kota, mereka semua ikut di belakang. Kepalaku menghayun ke kiri, ke kanan dan ke atas; badanku meliuklintuk. Pasanganpasangan baru keluar dari gedunggedung. Juga ikut bergabung orangorang dewasa, omom, tantetante, menteri menteri, bapakbapak dan kakekkakek berbaju bisnes dan jas hitam bersama temanteman berlainan kelamin yang jauh lebih muda, bernarinari seperti anakanak baru gede, berjoget riang sambil menepuknepuk tangan. "Yeeah hei!" Aku membawa semuanya menuju ke tepi sungai. Ketika sampai di tebing, aku meniup satu not berfrekuensi rendah dengan panjang. Mereka yang mengekoriku itu berterjunan ke sungai yang dalam dan deras arusnya. Aku tidak tahu ada yang mati lemas atau tidak. Kata orang, di hulu sungai itu banyak buaya.
176
66 TINA
T
ina! Tina!" "Tina! Tina!" "Tina! Tina!" Perempuan muda itu memanggilmanggil. Nada suaranya tinggi sekali. Menjeritjerit. Melihat dari gerakgeriknya aku pasti yang disebut dan caricarinya itu adalah anaknya. Ia seorang ibu muda yang kehilangan anak. Pakaian dan rambutnya seperti orang baru bangun tidur yang belum sempat mengurus diri. Tapi di mana pula suaminya? Kenapa suaminya tidak ikut mencari anak yang hilang? Ini bukan anak lelaki yang hilang, tetapi Tina, anak perempuan! Bukan pula aku mau mengatakan jika anak lelaki yang hilang biarkan saja hilang, tidak, jika anak lakilaki yang hilang kita cari juga sampai dapat cuma kita merasa lebih khawatir dan lebih kasihan jika yang hilang itu anak perempuan. Pada anak perempuan lebih banyak perlakuan kriminal bisa terjadi dibandingkan pada anak lelaki. Meski aku bujang belum beristri apalagi beranak, aku dapat membayangkan bagaimana rasanya jika yang hilang itu anak perempuanku. Terbawabawa oleh perasaan ini aku pun bergabung dengan ibu muda ini dan ikut mencari si Tina. "Tina! Tina!" pekikku. "Tina!" "Tina!" jerit perempuan muda ini. "Tina!" "Tina! Tina!" "Tina!" Keringat bercucuran di tubuhku pada pagi yang panas ini. Aku sedih karena belum bertemu dengan si
177
Tina. Aku merasakan bahwa si Tina itu adalah anak perempuanku. Seorang lelaki paruh baya yang berpapasan sempat bertanya: "Siapa yang hilang?" "Anak perempuanku," ujarku. "Si Tina." "Aku juga pernah kehilangan anak perempuan," kata lelaki paruh baya ini. Ia pun ikut bergabung mencari si Tina. "Tina," panggilnya dengan suara garau. "Tina!" "Tina! Tina!" "Tina!" Sekitar siang, matahari di atas kepala dan bayang bayang bundar di kaki, sudah ada delapan orang ikut mencari si Tina. Hatiku terkesan karena masih ada orang yang mau membantu. Masih ada orang yang mau peduli. Masih ada orang yang prihatin. Aku memegang bahu perempuan muda ini dengan lembut. "Sudahlah," kataku dengan suara yang membujuk. "Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan mencari si Tina, yah." Ia mengangguk. Aku mengajak yang lain untuk istirahat sama. "Kita makan siang," kataku. "Biar aku yang traktir." Selesai makan lelaki paruh baya bertanya kepadaku: "Si Tina ini umurnya kirakira berapa?" Tidak pernah terpikirkan olehku akan umur si Tina. Aku menoleh ke arah perempuan muda yang tadi senghaja kusuruh duduk dekatku di sebelah kanan. "Mengapa liat aku seperti itu?" Perempuan muda ini memandangku dengan bingung. "Si Tina itu kan anak perempuanmu?" "Bukan," kataku. "Aku masih bujang." "Aku juga masih bujang," katanya.
178
"Jadi si Tina yang kaupanggilpanggil itu siapa?" Aku memandang wajahnya. "Ooooo itu," kata perempuan muda ini. "Bangun pagi tadi ada satu keinginan yang kuat di dalam hatiku untuk memekikmekik dan menjeritjerit. Ya, daripada menjerit jerit seperti orang sinting, mending aku memekikmekik seperti mencari anak yang hilang biar sintingnya tak kentara Tina itulah nama yang terlintas di kepalaku saat itu."
179
67 MALING
T
idaklah, aku bukan pencuri. Di kampung ini cuma ada seorang saja pencuri. Semua orang tahu itu. K namanya. Kalau ada kecurian dialah yang mulamula ditunjuki. "Tidak lain K yang mencuri," orang akan berkata. Sesekali aku mencuri juga. Kalau peluang itu terbuka, seperti jika adanya jendela terbuka tengah malam, aku akan masuk. Apa yang dapat kuambil aku curi. Yang kena tuduh pastinya K. Itu salahnya sendiri. Kalaulah ia menjaga penampilannya agar tampak lebih terhormat sepertiku, pasti ia awalawal lagi tidak akan dituduh. Ia terlalu jelek. Aku selalu berpakaian rapi, dan aku hanya bergaul dengan orangorang pilihan yang dihormati masyarakat. Satu malam aku menyelinap masuk jendela yang tidak terkunci, rumah seorang ibu tua miskin yang sakitsakit. Aku tidak ada niat hendak mencuri, cuma aku terlihat jendela itu renggang, dan aku tahu ibu tua ini baru saja menerima sumbangan uang. Aku curi uangnya. Tidaklah aku ambil semua, aku tinggalkan 200 ribu dari tiga juta lebih. "Tidak lain K yang mencuri," orang akan berkata. Ibu tua ini tidak pula melaporkan kepada polisi, cukup ia memberi tahu kepada beberapa orang kampung. Aku pun ikutan orang ke rumahnya melihat sisasisa penggeledahan yang dilakukan oleh pencuri itu. Aku menggelenggelengkan kepala melihat hasil perbuatanku semalam. "Memang pencuri itu tidak manusiawi," kataku. "Mengapalah ia mencuri di rumah orang yang memang
180
susah hidupnya." "Iya, iya, memang benar itu, Tuan." "Tidak lain ini K yang punya kerja." "Jangan tuduhtuduh orang sebelum ada bukti," ujarku. "Siapa lagi kalau bukan dia?" K dibawa ke halaman rumah buruk ini. Ia tidak melawan. Rambutnya panjang. Bajunya selekeh. Ia bertelanjang kaki. "Bukan aku yang mencuri," kata K. "Aku sudah lama tidak mencuri. Aku sudah bertobat." Kautaulah, kalau pengadilan diserahkan ke tangan publik, tinju itu jadi ringan melayangnya. K dipukuli, ditinju wajahnya sampai hidungnya berdarah. Aku tidak ikut memukul. Aku tidaklah sekejam itu. Karena kasihan melihat ia dikerjakan, kupinta orang supaya bersabar dan menyerahkan kasus ini kepada polisi. Orang mendengar cakapku karena penampilanku yang sangat dihormati. K diserahkan ke polisi setelah babak belur. Entah, malam itu, tergerak pula hatiku untuk menggembalikan uang curianku. Kupastikan bukan not not uang yang sama atau mirip tidak semua kusumbangkan cukuplah satu juta. Esoknya tersebarlah namaku sebagai donor yang baik hati. Itulah kataku awalawal lagi, cobalah K menjaga penampilannya agar terlihat lebih terhormat sepertiku, tentu ia tidak dituduh maling.
181
68 NADIRAH
A
ku sudah pasrah kepada keadaan ini dan sudah tidak peduli lagi. Pemalu itu memang sifat semulajadiku. Sesama sejenis saja aku canggung apalagi sama perempuan. Aku anak tunggal yang dibiarkan mandiri. Bapa dan mama bekerja sepanjang hari. Aku pulang balik ke SD berjalan kaki tante dan om sebelah rumah mengawasiku saat aku kecil. Setelah aku besar sedikit, kelas lima, aku sudah pintar menyediakan makanan sendiri. Aku hanya menjenguk tante dan om sekadar mengatakan aku sudah pulang. Aku menghabiskan masa di rumah dengan membaca, terutama novel dan buku masakmasakan. Aku menjadi lebih mandiri setelah memasuki alam remaja. Sebagai anak tunggal aku tidak ada masalah keuangan. Bapa dan mama memberiku uang secukupnya. Aku agak mereka merasa sedikit berdosa karena terlalu membiarkan aku sendirian, jadi mereka sangat murah hati dengan uang. Aku pergi dan balik sekolah dengan bus, kadang kala aku terus ke kota untuk membeli buku dan barangbarang dapur, jika ada resep yang akan kucoba. Aku suka memasak dan mencoba resepresep baru. Satu ketika aku duduk di dalam bus, menunggu saat berangkat, seperti biasa kusyuk membaca novel yang baru kubeli, seorang gadis seumur denganku duduk di sisiku. Menyadari ada perempuan di sisiku, timbul pula rasa maluku. Aku bertambah tekun membaca buku. Pura pura tidak tahu. Sebenarnya aku tidak bisa fokus dengan
182
baik. Aku canggung. Kemudian perempuan ini menekan ke bawah buku yang kubaca dengan jarijarinya lalu menengok mukaku yang selama ini tersembunyi. Mukaku jadi merah dari telinga ke telinga melihat matanya yang dekat sekali. "Parah banget juga kau," ucapnya. "Say hellokah padaku!" "Hello," kataku, suaraku kedengaran seperti suara katak. Aku tidak pernah berbicara dengan perempuan kecuali dengan mama, tante sebelah rumah dan Bu guru di sekolah. Ia mengambil buku yang sedang kubaca dan membukabuka mukasuratnya. "Tante," katanya kepada wanita yang duduk di kursi sebelah. "Coba liat nih orang sebelahku ini." "Loh," tante itu memandang mukaku. "Merah banget tuh mukanya!" "Aku Nadirah," ia memperkenalkan diri dan memberi balik novelku. Entah, apa masalahnya. Ia amat ceria. Tidak ada suara yang keluar dari mulutku karena gugup. Sebenarnya aku senang juga digodagoda seperti itu. Betapa bagusnya jika semua siswi di sekolahku berani menggodaku agar aku keluar dari kepompong. Aku sebenarnya ingin jika ia terus duduk di sisiku sepanjang perjalanan pulang itu, tapi ternyata ia tersalah naik bus dan buruburu turun sebelum bus berangkat. "Byebye," katanya. Di luar ia melambailambaikan tangannya sambil tersenyum lebar. Aku membalas lambaiannya. Sejak hari itu aku selalu langsung saja ke kota habis sekolah, 'browsing' di toko buku, kemudian ke supermarket membeli bahanbahan
183
yang akan kumasak nanti. Setiap kali juga aku pulang dengan perasaan kecewa. Aku tidak mahir dalam menyembunyikan perasaanku. "Siapa perempuan itu?" tanya mama. "Perempuan apa?" "You are in love with someone." Mama tertawa. Mama memang tidak pernah berselindung omongannya. Bapa cuma duduk makan masakanku dengan diamdiam. "Bapamu sama juga, kalau mama ga godain ia dulu mang ia jomblo sampe sekarang dan kau ga akan lahir ke dunia," kata mama diikuti dengan tawanya. "Pamalu tuh bapamu!" "Gak adalah aku pemalu," kata bapa. "Pandaipandai bikin cerita." "Enak banget masakanmu ini," mama cepatcepat mengganti topik pembicaraan karena tau aku malu. Aku menjelaskan dengan penuh minat tentang resep yang baru kucuba itu. Oleh sebab selalu ke kota aku telah membeli banyak buku masakmasakan: jika aku nampak satu gambar hidangan yang menarik aku akan membeli buku itu. Berbeda dengan novel, jika belum habis kubaca, aku tidak akan membeli yang baru. Akhirakhir ini, karena mencaricari Nadirah, aku sulit fokus membaca novel. Aku lebih suka memasak untuk membawa rasa. Enam bulan lebih aku berharapharap akan bertemu dengan Nadirah di kota, di stasiun, di halte, untuk mengulang kembali pertemuan pertama yang belum selesai itu. Setiap kali aku akan berputus asa aku teringat daerah ini bukanlah besar sangat, jadi kesempatan untuk bertemu harus ada. Jika tidak hari ini, esok lusa masih ada, itulah yang ada di dalam pikiranku
184
setiap kali aku pulang untuk meredakan rasa kecewa. Satu kali aku turun di stasiun bus di kota dan terus berubah bus untuk pulang, aku merasa tidak perlulah aku terlalu mencaricari Nadirah. Aku pulang lebih awal, berpikirpikir apa yang akan kumasak di rumah nanti. Sampai di rumah, seperti biasa ayah dan mama memang tidak pulang siang, aku menanggalkan baju dan celana hendak mandi karena terlalu berkeringat. Jika aku sendirisendiri di rumah aku santai saja. Aku ke dapur mengeluarkan bahan yang akan kumasak dari freezer. Kemudian aku keluar hendak mandi. "Hai pemalu." Aku terlihat bayangan Nadirah duduk minum teh dengan biskuit di dapur. Barangkali cuma halusinasiku. Ia tertawa. "Ga malukah pake cd aja?" Aku buruburu keluar dari dapur, memakai celana dan bajuku semula dan masuk ke dapur. Nadirah senyum selebarlebarnya. "Kau bikin apa di rumah ini?" tanyanya. "Hello, ini rumahku," kataku. "Kau bikin apa di rumahku ini? Masudku, aku senang liat kau ada... bukan maksudku... maksudku aku...." "Pergilah mandi," katanya. "Asem amat." Aku mandi sambil berharapharap semua ini bukanlah satu halusinasi. Aku mandi lamalama dan berwuduk. Aku ke dapur semula setelah salat Zuhur. Nadirah masih di situ tersenyumsenyum. Dapur adalah gelanggangku. Percaya diriku tinggi di sini. Aku akan memasak. Aku mengambil sendok kayu dan mengetuk kepala Nadirah, tidak kuat sedikit saja. Tuk! "Adoi!" katanya.
185
Mungkin terlanjur kuat. "Sori," ujarku. "Hanya memastikan kau beneran. Sudah makan?" "Belum, mamamu bilang kau pinter memasak." "Oke," aku melihat wajahnya dan aku tahu apa yang akan kumasak. Ia nampak sedikit kurus dari pertama kali dulu. Ia seperti orang yang kehilangan selera makan. "Aku akan memasak. Nanti makan bareng. Resep simple aja untuk dua orang." Aku memotong bahanbahan sayur, jamur, green peppers. Aku melihat mukanya lagi; ia membutuhkan sedikit daging corned beef. Selama aku menyediakan masakan aku bertanya itu ini, mengapa ia berada di rumahku. Meskipun ia tampak ceria aku tahu ada masalah besar sedang dihadapinya. Dari nada suaranya aku tahu secara instink bahan apa, rempah apa yang diperlukan dalam masakan untuk menyeimbangkan elemenelemen yang kacau di dalam diri dan emosinya. Aku memang mahir dalam hal ini secara natural dan karena minatku yang mendalam dalam masakan. Dapur adalah gelanggangku. "Bapa ketahuan berhubungan sulit enam bulan lalu," katanya dengan mendatar seolaholah pekara 'berhubungan sulit' adalah hal biasa. "Mamamu bestfriend mama. Aku akan diam sini sementara waktu. Mamamu bilang kau in love with someone dan ia suruh aku barangkali bisa bantu." "Gak adalah," kataku mengontrol perasaan gembiraku. "Mama tuh mang suka bikin cerita kayak sinetron." Masakan siap. Kami makan samasama. Sungguh aku senang melihat dia. Aku terus memerhatikannya. Enam bulan mencaricarinya tibatiba ia ada di dalam
186
rumahku makan masakanku seperti orang yang baru mendapatkan kembali seleranya. "Janganlah liatliat aku gitu," katanya. "Aku malu." LOL.
187
69 AKU, ISTRI, dan TETANGGA
A
ku buatbuat tidak tahu ketika tetanggaku membeli tv flatscreen LCDHD 47". Ia pastinya ingin pamer. Kadangkadang ia datang ke rumahku ngobrol pada waktu petang, tidak habishabis berbicara tentang tv layar lebar barunya itu. Katanya, dulu tv 29" itu terasa sangat besar tapi sekarang sudah tampak kecil seperti semut. Tvku masih tv lama 29". Sesekali ia mengundang aku ke rumahnya untuk melihat tvnya itu. Istriku mulai mendesak supaya aku membeli tv seperti tetanggaku itu. Kataku bersabar sajalah dulu, kita tunggu model terbaru, dan nanti kita beli tv yang lebih besar dari dia. Ketika saatnya, aku pun membeli sebuah SMART Tv 3D LED dengan layar 55". Aku tidak ingin menceritakan hal ini kepada tetanggaku itu. Aku bukan tipe manusia yang suka pamer, ia sendiri yang datang ke rumah. Apabila melihat ia datang ke mari, aku cepatcepat memutar film blueray "Avatar" dalam 3D, memfast forward sehingga tampak seperti aku sudah setengah jam menontonnya. Tentu tanpa memakai kacamata 3D yang disediakan gambarnya tampak seperti berlapis lapis dan tidak jelas. "Tv besar," kata tetanggaku itu. "Baru beli ya, tapi sudah rusak gambarnya. Tv buatan Korea memang ga baik." Tv ini dilengkapi dengan tujuh pasang kacamata 3D dengan gratis. Aku pun mengunjuk sepasang untuk dipakainya. Ia memakai kacamata itu, dan jelas air mukanya berubah. Isteriku keluar menyajikan minuman
188
petang. "Bawabawalah juga istri dan anak dara ke mari," kata isteriku bermanis muka. "Samasama kita nonton film in 3D." Tetanggaku itu balik dengan mood kurang baik. Sepanjang enam bulan mendatang ia mulai membeli peralatanperalatan rumah yang baru yang semuanya bersais besar: kulkas, microwave oven, mesin penyuci pakaian otomatik, furnitur, karpet, dan entah apa lagi yang kami tidak tampak. Aku tidak mau kalah, dan ternyata istriku juga tidak mau kalah. Kami membuat penambahan pada rumah kami, aku membuka sebuah toko mejual keperluan harian. Kebetulan juga aku dan istri adalah Manajer Emas bagi satu bisnis multilevel, dan di sinilah kami menambah stok produkproduk yang kami jual. Di sinilah juga aku memberi ceramah motivasi dan demo produkproduk baru kepada downlineku. Tetanggaku pun membuat penambahan pada rumahnya, dan ia membuka sebuah restoran kecil. Aku membeli sebuah mobil besar; ia membeli sebuah mobil sport. Ia sudah tidak datangdatang lagi ke rumahku. Buat selama lima bulan mendatang tidak ada kegiatan persaingan antara kami berdua. Penghabisan sekali aku membelikan istriku sebuah mobil baru. Tetanggaku itu menyepi saja. Kemudian aku menerima kartu undangan pernikahan darinya. Ia tidak punya anak selain seorang anak perempuan yang baru berumur empat belas tahun. Ini sudah melampau, anak itu masih ingusan untuk menikah. Timbul rasaku untuk memprotes kepadanya. Meskipun aku rindu mau bersaing, kali ini kami mengalah saja, tidaklah aku tega hendak menikahkan anakku yang baru berusia sembilan tahun. Asumsi kami ternyata menyimpang pula. Bukan anaknya
189
yang hendak menikah, tetapi tetanggaku itu sendiri. Aku memandang istriku. Ia membelalakkan matanya sebelum aku sempat berbicara apaapa.
190
70 TIDAK BERGUNA
M
asih awal pagi, tokotoko lainnya belum buka, yang buka hanyalah warungwarung makan dan minum. Aku baru selesai minum. Memang lengang Jalan Bundo awalawal pagi seperti ini. Aku tampak seekor anjing menciumcium sesuatu di seberang sana kemudian ia membawa benda itu dengan mulutnya. Ketika ia sudah dekat, aku tampak benda itu seperti tangan yang terputus mungkin saja tangan boneka. Lembar koran bergulingan ditiup angin perlahan, angin itu berubah jadi angin pusar dan kertas suratkahbar ikut berputarputar naik kemudian jatuh ketika angin itu berhenti dan hilang. Aneh juga karena angin pusar biasanya hanya ada tengah hari atau ketika cuaca sudah panas terik. Seorang pria tua berambut dan berjenggot putih menyapaku. "Maaf," katanya. "Aku terlambat datang. Sudah lama menunggu?" Sebenarnya aku bukan menunggu; aku cuma berdiri diri sambil mencungkilcungkil celah gigi. Aku baru tahu ada toko di sebelah kiriku ini. Ia memasukkan kunci dan membuka pintu tokonya. Pintunya antik, kecil dan hanya bisa dilalui oleh satu orang saja dalam satu waktu. Toko ini menarik perhatianku karena papan labelnya: MENJUAL BARANGBARANG TIDAK BERGUNA. Menurutku ini agak lucu; jika barangbarang itu tidak berguna siapa pula hendak membelinya. "Silahkan masuk! Silahkan masuk!" Aku mengikutinya naik tangga ke lantai satu. Memasuki tokonya ini, aku hampirhampir saja tertawa.
191
Memang barangbarang yang dijualnya ini barang barang tidak berguna: sepatu buruk yang cuma ada sebelah, buku sekolah yang sudah setengah terbakar, celana dalam yang sudah koyak, boneka yang kehilangan tangan, dan segala macam barang yang sebagian pernah aku dan kaumiliki, dan sekarang tidak berguna lagi; barang buangan. Tidak ada satu pun benda yang aku mau. Ia mambawa aku masuk ke ruang kedua. "Ini tempat binatangbinatang piaraaan yang tidak berguna." Di sini ada kucing, anjing, kelinci, berbagai jenis burung dan hewanhewan lain, semuanya di dalam kurungan, tunduktunduk, kuruskurus, berpenyakit, senyap, setiap mata kurasa memandangku seolaholah aku yang bersalah. Ia membawa aku masuk ke ruang ketiga. "Ini tempat orangorang yang tidak berguna," ujarnya. Di sini ada bayibayi yang baru lahir, anakanak yang kelaparan, remaja pria dan perempuan, aku juga nampak orang dewasa sepertiku, masingmasing mereka menyepi, berpikir berat dalam kurungan. Kemudian aku terlihat dalam beberapa kurungan ada bapabapa, ibuibu dan neneknenek, tunduktunduk memeluk lutut. Aku ingin keluar secepat mungkin dari toko ini. Aku tidak ingin melihat semua ini. "Anakanak manalah yang sangat kurang ajar dan durhaka ini?" kataku kesal. "Mereka tidak berguna lagi akan orangorang tua mereka!" Kemudian orang tua berambut dan berjenggot putih menarik tanganku dan membawa aku ke satu kurungan. Di situ aku melihat ibuku yang sudah tua duduk memeluk lutut. Ia memandangku seolaholah tidak lagi
192
kenal kepadaku. Di satu kurungan aku melihat ayahku yang sudah 10 tahun meninggal dunia. Aku merenggut dan menarik jenggot orang tua pemilik toko. Aku tidak peduli orangorang lain itu, tapi mengapa pula ibu dan ayahku berada dan dikurung di sini? "Sejak kapan kau mengurung orang tuaku?" "Ibumu sejak tiga tahun lebih," katanya, "dan ayahmu sejak 9 atau 10 tahun aku sudah tidak ingat lagi." "Kau memang kurang ajar!" Aku segera meninggalkan toko ini. "Aku cuma menjual barangbarang yang tidak berguna." Orang tua itu menertawakanku. Tawanya bergaung. Aku terus ke mobilku dan menyetir menuju ke desa. Bukan jauh sangat cuma perjalanan lebih sedikit dua jam. Ibu dudukduduk di luar rumah. Melihat aku datang wajahnya terus berseriseri. Entah, mungkin saja duduk duduknya itu duduk menunggu kepulanganku. Dengan bersusah payah ia bangun menggunakan tongkat untuk menyambut kedatanganku, jalannya tidak teguh, aku mengambil dan mencium tangan yang hanya dibalut kulit, terasa tulangnya gemetar. Tangan yang gemetar inilah yang telah membesarkanku, membelaibelaiku, membersihkan najis dan kekotoranku, menyuapi makanan ke mulutku, memberi aku minum saat aku kecil dan tidak berdaya, saat aku sakit, sekarang tangan tangan ini sudah tinggal tulang, tidak habishabis ketarnya, dan dengan uraturat yang timbul. Aku memimpin ibuku masuk ke rumah, jalannya lambat sekali, goyah dan susah. Sangat susah. Entah selama ini siapa yang telah baik hati menjaganya. Ibu tidak pula menyoal kenapa aku tidak pulangpulang sudah lebih
193
tiga tahun bahkan hari lebaran pun aku tidak menziarahinya. "Besokbesok jika kau ada waktu Nak," kata ibu, "bawa ibu menziarahi kuburan ayahmu sudah lama kita tidak menziarahi kuburnya." Pagi itu juga aku memandikan ibuku, menggosok daki dan kulitkulit mati di belakangnya, menyikat rambutnya. Setelah mandi, tolong memakaikan pakaian yang bersih. Ada orang berbaik hati menyumbangkannya pakaian, terima kasih, terima kasih, seharusnya akulah yang memedulinya. Aku tidak menunggu besokbesok lagi, aku membawanya ke pusara ayah pagi itu juga. Semenjak ayah meninggal aku tidak pernah ke makamnya. "Ayahmu membutuhkan doa anaknya," kata ibu. Meskipun sudah lebih tiga tahun aku tidak menjenguk ibu, sedikit pun aku tidak melihat tandatanda kesal pada wajahnya. Aku rasa ia tidak pernah merasa kesal karena aku adalah anak yang telah dikandungnya selama sembilan bulan. p.s toko menjual MENJUAL BARANGBARANG TIDAK BERGUNA itu masih ada di Jalan Bundo, cuma toko itu muncul sekalisekala, kemudian menghilang. Aku telah mengunjunginya lebih tiga kali.
194
71 DOAKAN AKU
A
ku terdengar bunyi sepeda motor di luar. Ia temanku saat di asrama dahulu. Katanya ia sudah lama mencaricari rumahku ini. Selama di asrama dulu, ia ini bukanlah teman yang baik. Ia tidak ada teman sebenarnya. Orang hanya berpurapura berteman dengannya. Tabiatnya suka membuli orang. Jika perasaanya disakiti ia akan mengamuk. Jadi teman temanku tidak ada yang suka kepadanya. Ia tidak pula pernah mengacau aku. Ia tiga tahun senior dariku. Jika ada apaapa hal, ia mengadu kepadaku. Jadi teman temanku yang lain menggelar ia sebagai 'temanmu itu' kepadaku. "Temanmu itu mengamuk lagi," kata mereka. Bukan ia tidak mengacau aku, ia mengacau juga. Ia menunggu aku siap salat, sebaikbaik saja aku memberi salam ia menggamit bahuku. "Eh," katanya. "Doakan aku." "Doa apa?" kataku. "Doakan aku lulus ujian." Aku pun berdoa untuknya. "Ya Allah, ini sahabatku datang meminta aku mendoakan untuknya agar ia lulus ujian aku memohon kepadaMu agar Engkau luluskan ia dalam ujiannya." "Amin," ia mengaminkan. Katanya, itulah saja cara ia ingin 'mengacau' aku. Ya, ia lulus ujian dan kami samasama naik kelas. Kebetulan saja. Sebelum itu, ia telah dua tahun duduk di kelas ulangan. Pernah ia demam selama satu minggu lebih. Seminggu lebih kawankawan aman dari gangguannya.
195
Ia datang kepadaku dan menggamit bahuku setelah aku memberi salam. "Eh, doakan aku." "Doa apa?" "Doakan aku sembuh." "Ya Allah, ini sahabatku datang meminta aku mendoakan untuknya agar ia sembuh aku memohon kepadaMu agar Engkau sembuhkan dia." "Amin." Esoknya ia sembuh. Kebetulan saja. Temantemanku menyalahkan aku pula. "Apalah kau ini," kata mereka. "Kaudoakan ia sembuh." "Ia sembuh bukan karena doaku," kataku. "Dan takkanlah aku doakan ia mati." "Kau ini terlalu lurus." Kami samasama mengakhiri persekolahan dan berniat untuk bekerja. Kami samasama melamar satu pekerjaan di sebuah kantor pemerintah. Cuma ada satu kekosongan. Ia datang kepadaku dan menggamit bahuku setelah aku memberi salam. "Eh,doakan aku." "Doa apa?" "Doakan aku berhasil mendapatkan pekerjaan itu." "Ya Allah, ini sahabatku datang meminta aku mendoakan untuknya agar ia berhasil mendapatkan pekerjaan yang samasama kami lamar aku memohon kepadaMu agar Engkau berikan ia jabatan itu." "Amin." Ia berhasil mendapatkan pekerjaan itu. Kebetulan saja. Aku menganggur lebih setahun. Kemudian aku mendapat pekerjaan lain dan bertugas di daerah lain. Sejak itu aku tidak mendengar kabar tentangnya.
196
Ia turun dari motornya dan memelukku. "Hanya kaulah sahabatku," katanya. Aku mempersilakannya masuk. Setelah bertukar tukar kabar barulah ia menyatakan hajatnya mencariku. "Doakan aku," pintanya. "Doa apa?" "Aku ini jahat," ujarnya. "doakan aku agar menjadi baik dan tidak menyusahkan orang lain." "Ya Allah, ada orang jahat, ia tidak sadar ia jahat, lalu terus menyusahkan orang. Ya Allah, ada orang jahat, ia tidak mengakui kejahatannya, lalu ia terus menyusahkan orang. Ya Allah, ini sahabatku datang mengakui ia jahat, ia meminta aku mendoakan untuknya supaya ia menjadi baik dan tidak menyusahkan orang lain. Ya Allah, aku memohon kepadaMu agar Engkau jadikan ia baik dan tidak menyusahkan orang lain. " "Amin, amin," ia mengaminkan. Oleh karena waktu Asar sudah dekat, ia mengajak aku ke masjid. Tidak pernah ada orang mengajak aku ke masjid. "Marilah samasama," katanya. "Aku hendak salat Asar berjemaah di masjid." "Berwuduklah dulu," kataku. "Kau sudah berwuduk?" tanyanya. Aku senyum saja. "Karena itulah," katanya, "sejak di asrama dulu aku tidak suka membulimu aku tau kau sentiasa berwuduk." Setelah berwuduk, aku menawarkan minyak atar kepadanya. Ia menerima saja. Dahulu ia membenci minyak atar. Aku memberinya sebotol, oleholeh dari musim haji lalu. Ia menaiki motornya. "Ketemu di masjid nanti," katanya. "Lepas salat kita makanmakan dan minum," kataku.
197
"Aku belanja. InsyaAllah." "Assalamualaikum." "Waalaikumussalam warahmatullah." Itulah penghabisan sekali aku melihat ia hidup, karena lima menit kemudian ia kecelakaan keluar simpang ditabrak truk membawa batu. Ia meninggal di situ juga. Ketika ia dikeluarkan dari bawah truk, matahari tibatiba redup dan ada angin yang nyaman bertiup. Ada senyuman di bibirnya. Akulah yang menutupi jenazahnya dengan kain serbanku. Jenazahnya mengeluarkan aroma yang semerbak yang bukan dari minyak atar yang kuberi tadi, karena minyak atarku tidak ada yang seharum itu.
198
72 KOLAM
N
enekku berumur 65 tahun. Ia telah menjanda sejak lima tahun lalu. Meski sudah tua, namun ia masih bersemangat dan tampak lebih muda dari wanitawanita seusia dengannya. Nenek bukanlah tipe orang yang suka berkurung di rumah. Ia berjogging, ia bersepeda dan sesekali berolahraga arobik di sebuah gym. "Dudukduduk di rumah hanya mengundang penyakit," katanya. "Penyakit membuat kita tua, bukan usia." Dari sekian banyak cucunya. aku adalah cucu kesayangannya. Pada waktu liburan sekolah aku biasanya menemani nenek di kebun buahbuahannya, menebas semak belukar, membakar kayu mati, dan menyiarami tanamtanamannya dengan air dari kolam dan air terjun kecil terdekat. Airnya jernih, dingin dan segar; tampak cebong katak berenangrenang, batubatu kecil dan daunmati di dasarnya. Aku meluangkan waktu setidaktidaknya sebulan sekali tidur di rumah nenek. Sekarang aku sudah jarang jarang mengunjunginya. Aku punya temanteman sebaya yang ramai, punya pacar, dan banyak aktivitas. Rumah nenek jauh dari rumah kami, jauh masuk ke jalan kecil menuju ke hutan. Untuk ke rumah nenek, aku bersepeda kurang lebih satu jam baru sampai. Setelah dua bulan lebih, aku baru muncul di rumahnya. "Wah," kata nenek. "Kau sudah muda sekarang." "Nenek pun tampak muda juga," kataku spontan karena memang ia tampak jauh lebih muda dari terakhir
199
aku melihatnya. Ia tidak mengenakan mekap. "Betulkah?" ujarnya. "Betulkah?" "Betul betul betul," kataku. Kemudian dari dalam, keluar seorang pria muda ganteng yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Nenek menarik lengan pria itu supaya dekat dengannya. "Ini lakiku," kata nenek. "Namanya Putra Bungsu. Kami diamdiam menikah bulan lalu." Aku melihat Putra Bungsu, dan tertanyatanya bagaimana ia bisa terpikat pada nenekku yang meski tampak muda tapi tetap juga tua. Jika aku memiliki wajah Putra Bungsu pasti aku jadi rebutan gadisgadis di sekolah. "Ini cucuku," nenek memperkenalkan. Putra Bungsu pamitan masuk ke dalam, ke dapur, dan terdengar sibuk mempersiapkan makanan dan minuman. "Ia pinter memasak," kata nenek. "Tidak menyesal nenek menikah dengannya." Memanglah ia tidak menyesal, yang seharusnya menyesal adalah Putra Bungsu. Tanpa kupinta nenek bercerita. Ia telah tertinggal hpnya di kebun, sudah malam baru ia menyedarinya. Pada malam itu juga ia ke kebun untuk mengambil hp itu. Ketika itu kebetulan bulan penuh. Ia terdengar suara riuhrendah. Ia pun bersembunyisembunyi mengintip. Ada tujuh orang pria muda dan tampan sedang mandi berendam di kolam. Penghabisan sekali masuk berendam adalah Putra Bungsu. "Aku jatuh cinta padanya," kata nenek. "Aku mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya. Karena pakaian saktinya tidak ada, Putra Bungsu tidak bisa ikut pulang bersama abangabangnya. Dialah yang
200
mengajar supaya nenek berendam pada bekas air mereka tujuh beradik berendam itu supaya nenek jadi muda." "Nenek pilih yang paling muda," kataku dengan senyum. "Ceh! Kau pikir kamu pria saja yang berhak suka pada yang mudamuda?" Malam itu nenek mengajakku ikut bersamanya ke kolam air terjun kecil dekat kebunnya. Malam bulan penuh abangabang Putra Bungsu akan turun mandi berendam. Putra Bungsu juga ikut, untuk ketemu dengan abangabangnya, tetapi ia tidak ikut mandi. Nenek akan berendam lama setelah mereka pergi. Kata nenek setiap kali ia mandi berendam itu, ia akan tampil lebih muda dari sebelumnya. Memang terbukti benar. Sekarang nenek tampak seumur dengan ibuku, tapi bagiku ia tetap juga nenekku. Rahasia nenek jadi muda akhirnya tersebar juga. Jangan heran jika kamu terlihat perempuanperempuan tua berlari terencotencot menuju ke kolam air terjun kecil di dalam hutan dekat kebun nenek. Mereka, perempuanperempuan tua ini, neneknenek ini, berendam di situ dengan tidak menghitung waktu. Menurut cerita Putra Bungsu abangabangnya tidak lagi ingin berendam di kolam itu. "Setiap kali mereka mandi di situ," kata Putra Bungsu, "abangabangku menjadi lebih tua karena kolam itu telah dicabuli oleh neneknenek tua dengan tidak memilih saat yang benar." Nenek telah membakar baju sakti Putera Bungsu agar ia tidak bisa pulang selamalamanya. "Kasihan Putra Bungsu," kataku kepada nenek dengan polos pada suatu hari. "Ia menikah dengan
201
orang tua." "Ceh, kamu memang double standard!" ujar nenek. "Kalau pria tua keriput kawin dengan perempuan muda remaja, kau tidak pula kasihan pada perempuan itu." Benar juga. "Paling tidak aku tampak lebih muda dari pria tua keriput," kata nenek. Aku tidak dapat mengingkarinya karena nenek memang tampak amat muda, mengalahkan mereka yang berbotox dan berbedah plastik.
202
73 TERAPI ALTERNATIF
K
ata dokter tumor di pipiku bukanlah tumor yang membahayakan, jadi tidaklah ada kebutuhan mendadak untuk membedahnya, namun ia harus juga dibedah untuk dibuang. Operasi tersebut akan dilakukan setelah tiga bulan nanti, menurut giliran dan urgensi. Aku sendiri tidak ingin mukaku dibedah. Jika dibedah tentu akan meninggalkan bekas yang jelek. Entahlah, aku harap waktu tiga bulan cukup untukku mencari terapi alternatif; jika tidak aku akan minta tangguh lagi pada dokter. Waktu tiga bulan tersebut aku mencoba minum jus campuran herbal yang mahalmahal dijual di dalam botolbotol yang cantik barangkali botolnya yang menyebabkan harganya mahal. Minum jusjus tersebut membuat badanku sehat segar tapi tidak pula menghilangkan tumor tersebut. "Bagus kaucoba terapi tampar," kata abangku. "Aku dulu ada tonjolantonjolan di belakangku. Dua kali tampar hilang semua nda kambuhkambuh lagi." "Eh, bagus tuh," kataku. "Gak makan obat apa?" "Ga. Rawatan tampar aja." "Di mana siapa perawatnya?" "Anak muda," kata abangku. "Dia dapat teknik ini dari mimpi. Gak pake jampi mantra." Abangku faham yang aku tidak suka pada jampi jampian. Pada hari Minggu yang kami janjikan, kami pun ke rumah praktisi terapi tampar ini. Banyak juga orang yang sedang menunggu giliran. Dari dalam kamar perawatan, aku terdengar bunyi pukulanpukulan yang cukup kuat juga diikuti oleh suara orang mengaduh.
203
Plakk! "Adduh!" Paap! "Adddoi!" Pasien keluar dari kamar itu, dan perawatnya anak muda berusia tidak lebih 30 tahun keluar untuk memanggil pasien berikutnya apabilaa dia terlihat aku dan kakakku. Dia memandangku. "Pak Guru," katanya sambil mendekatiku dan terus menyalami dan mencium tanganku. "Ingat masih saya, Pak Guru?" "Kasim," kataku melihat gigi depannya yang ompong. "Iya," katanya dengan senyum. "Pak Guru mau barobat?" Dia mengamatamati pipi kananku yang ada sedikit bungkul. Kemudian dia menghadapi pasienpasien lain dan meminta izin dari mereka semua untuk merawat aku dulu. "Ini Pak Guruku saat aku di SD dulu," katanya, "Aku rawat dia dulu, yah. Gak lama nih, insya Allah, sekejap aja." Saat SD, Kasim adalah anak muridku di kelas tiga. Dia adalah murid yang paling lembab tetapi ambisius. Dia bercitacita ingin jadi dokter. Hampirhampir kesemua anakanak muridku bercitacita ingin jadi dokter. Ketika ditanya, jawaban yang diberikan biasanya disampaikan dengan suara yang seperti berlagu. "Citacita saya adalah ingin jadi dokter." Dengan kelembapannya itu memang Kasim sangat tipis akan jadi dokter. Di kamar perawatan ini dia memegangmegang dan merasarasa dengan ujung jari jarinya akan bungkul di pipi kananku. Besar juga tapak tangannya.
204
"Maaf yah, Pak Guru," ujarnya. Plakk! "Addduuhh!" Paap! "Adddoi!" Mukaku seperti terkena api, memang nyeri tamparannya, tapi aku merasa bungkul di pipiku mengempis dan menghilang. Sekejap saja perawatan tersebut, tidak sampai lima menit. Kasim menolak uang pemberianku. "Gak usah Pak Guru, gratis aja tuh tamparannya," katanya dengan senyum. Dia mengirim aku dan kakakku sampai ke pintu. Dia menyalami dan mencium tanganku. "Kalau kambuh, Pak Guru datang lagi untuk pukulan ketiga," kata Kasim. "Tapi, insya Allah, gak kambuh tuh. Assalamualaikum." "Waalaikumussalam." Dia masuk kembali dan aku terdengar suaranya memanggil pasien selanjutnya. "BERIKUT," laungnya. "SIAPA LAGI MINTA DITAMPAR?" Aku pernah beberapa kali menampar mukanya saat dia di SD dulu karena terlalu begonya dia tidak faham faham apa yang diajarkan. Kesabaran seorang guru itu tentu saja ada batasnya, dan aku memang terkenal seorang guru yang garang dan kurang sabar. Gigi depannya yang ompong itu terkena tamparanku. "SIAPA LAGI MINTA DITAMPAR?" gertakku, menantang anakanak murid yang lain. Ayahnya datang ke sekolah besoknya dengan membawa parang ini memang pekara biasa yang terjadi pada zaman itu. "Mana Guru yang namparin anakku," seru ayahnya
205
dengan suara yang tinggi. "Sampe copot gigi! Gak berakal tuh, Pak Gurunya!" Menurut pendapatku, gigi depannya itu sudah buruk dan goyang, dan memang saatnya untuk tanggal. Aku diberi peringatan oleh kepala sekolah dan tidak lama kemudian dipindahkan ke SD lain karena banyak aduan dari bapakbapak dan ibuibu. "Siapa lagi minta ditampar?"
206
74 TIDAK ADA APAAPA YANG TERJADI
K
emarin tidak ada apaapa yang terjadi. Aku pergi ke kantor, aku lihat semua orang buat kerja diamdiam. Bos tidak keluarkeluar dari kamar kerjanya untuk memberi ceramah motivasi, atau marahmarah. Tidak ada karyawan yang bertengkar. Tidak ada rapat untuk dihadiri. Tidak ada sesiapa pun mengajak aku keluar minum. Tidak ada sesiapa menelepon aku, baik teman teman sekerja maupun bos. Bos tidak memanggil aku. Tidak ada apaapa yang terjadi kemarin: tidak ada kecelakaan lalulintas, tidak ada pencurian, tidak ada kebakaran, tidak ada anak baru lahir dibuang di dalam kantong plastik, tidak ada pemerkosaan, tidak ada mereggut tas, tidak ada peceraian, tidak ada orang naik pangkat, tidak ada orang dihentikan kerja, tidak ada rasuah, tidak ada karyawan lari dari majikan, tidak ada orang jatuh bangkrut, tidak ada orang kena bunuh atau bunuh diri, tidak ada orang kena tipu. Tidak ada apaapa yang terjadi kemarin: tidak ada perang di Syria, tidak ada demonstrasi di Pakistan, tidak ada tembakmenembak di Palestina, tidak ada latihan militer di Laut Cina Selatan, tidak ada pengebom berani mati meledakkan dirinya, tidak ada pesawat jatuh atau helikopter terhempas, tidak ada kerusuhan di mana mana, tidak ada gempa bumi, tidak ada tsunami, tidak ada gunung berapi meledak, tidak ada tornado, tidak ada banjir, tidak ada tanah runtuh. Pemimpinpemimpin dunia tidak ada seorang pun muncul di tv. Koran pagi hari ini hanya memuat ulang berita harihari sebelum kemarin karena kemarin tidak ada apaapa yang terjadi. Berita di
207
tv dan di radio juga serupa. "Kami minta maaf," kata penyiar. "Kami hanya dapat memuat beritaberita hari sebelum kemarin karena kemarin tidak ada apaapa yang terjadi."
208
75 TARIF
K
atanya ia ke toko mau hutang beras untuk makan malam. Ia meninggalkan istrinya, yang bunting empat bulan, duduk di pintu rumah mereka yang sudah miring; bocah empat tahun duduk di sisi kirinya. Sepuluh tahun kemudian baru ia pulang. Istrinya masih duduk di pintu rumah mereka yang kini sudah tegak bertiang batu, berlantai ubin, beratap spandek biru tua dengan dinding abuabu dan putih yang masih berbau cat; interiornya kombinasi warna pink lembut dan biru muda. Istrinya tampil lebih matang, berhias sederhana, bergincu warna lembut, lebih mulus, jauh lebih jelita dari saat ia ditinggalkan. "Met sore, Mas," sapa istrinya. Kemudian dengan tegas katanya: "Tarifku satu juta untuk sekali atau setengah jam. Lima juta untuk sepanjang malam. Dibayarin dulu dan uang tidak dikembalikan."
209
76 PENGUNGSI
A
ku tersenyum miring memandang kelompok sepuluh orang pria dan perempuan. Aku yakin mereka itu 'alien'. Seorang dari mereka, yang perempuan, berkemeja warna jingga, mencuricuri pandang ke arahku. Aku dapat melihat keningnya berkerut. Ia tunduk seolaholah menghindar renungan tajam mataku. Ia menggigit bibir bawahnya. Ia berbicara kepada teman temannya sambil mengarahkan pandangannya kepadaku. Kemudian mereka semua berjalan menuju ke tempat dudukku di Dataran Yayasan. Manusia tidak akan berjalan seperti itu, mereka menyembunyikan cara berjalan mereka yang melunsur, tapi aku memiliki daya observasi yang tajam. Aku menyandarkan belakang di kursi memandang mereka dengan senyum yang miring di bibirku. Perempuan itu duduk di sisi sebelah kanan, rapat sekali, sehingga pahanya yang dibaluti celana jeans biru yang ketat menyentuh pehaku. Hangatnya melebihi hangat tubuh manusia. Hidungku mencium bau kamper. Ia meletakkan telapak tangan kirinya di atas lututku; menepuknepuk lututku itu. Aku membiarkannya saja. Yang lain duduk di kiri dan kanan, dan tiga orang berdiri di depanku. "OK," katanya. "Kami tahu kaucuriga siapa kami." "Sudah berapa lama kamu tinggal di negara kami ini?" kataku. "Dua puluh tahun lebih," kata perempuan itu. "Jadi, apa pendapat kamu tentang negeri kami ini, tentang Bumi?"
210
Hampirhampir saja mereka berbicara serentak meluahkan segala keluhan: blah blah blah blah blah blah blah blah nasionalisme blah blah blah kaya blah kaya blah blah blah blah blah blah miskin blah miskin blah blah patriotisme blah blah blah blah blah blah provokasi blah blah blah blah blah blah blah blah bunuh bunuh bunuh blah blah blah blah blah blah sensitif blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah agitator blah blah blah blah blah.... Bibirku gemetar menahan amarah. Menyebalkan. Dadaku berombak. Aku menghela napas dalamdalam, melepaskannya perlahanlahan. Ini aku lakukan sehingga tiga kali. Setelah sedikit tenang aku memandang mereka semua. "Jika kamu banyak keluhan seperti itu, mengapa kamu masih terus tinggal di sini? Pulang saja ke planet Kcpbuymtgglpqqqtwg jika kamu rasa di sana lebih baik!" "Kami sangat suka di sini," kata mereka serentak. "Hidupnya santai dan malasmalasan. Dan juga kami adalah pengungsi politik." Perempuan di sisiku memijitmijit lembut lututku. Aku memandang wajahnya dan ia memandang ke dalam mataku. Aku melihat mata hitamnya yang bulat berubah jadi bentuk diamond. Aku terasa dia memaksakan supaya mata hitamku juga berubah bentuk, dan dia mencuri namaku. "Nizam AlKahfi," katanya dengan senyum yang miring, "hanya orang sebangsa yang mampu menyebut nama planet kami dengan benar. Sudah berapa lama kautinggal di sini?" "Aku lahir di sini," ujarku. "Ibuku menikah dengan
211
orang di sini. Bapaku awalnya tidak tahu yang dia menikah alien." "Kljklklajnkielajgg," katanya. "Gmnatkyllbnwrcd," kataku. "( '<I> .. <i>')" katanya dengan matanya. "(<^> .. <^>)" aku membalas dengan mata juga. Mereka meninggalkanku. Aku melihat mereka pergi bercampur dengan orang banyak. Dua puluh tahun tinggal di bumi ini, mereka masih belum mahir berjalan seperti manusia, namun mereka seperti tidak ada niat untuk kembali ke planet asal. Aku tersenyum miring.
212
77 NGUUUNGGG...
K
ami ada rapat pada pukul sepuluh pagi itu. Aku tidak tahu apa yang telah menimpa. Tuan Ketua tidak dapat membaca menit rapat. Katanya ia tibatiba tidak tahu membaca, ketika itu sudah pukul 10:10 menit. Tidak seorang pun (kecuali aku) yang hadir itu bisa membaca. Setiap orang tibatiba saja jadi buta huruf. Rapat dibubarkan. Karena sudah menjadi kebiasan ada yang melihat jam tangan, tapi mereka jadi panik karena tidak bisa membaca jam mereka. "Ini sudah jam berapa? Pukul berapa?" tanya sekretaris. Aku hanyalah tukang catat. Ini adalah catatan peristiwa dari hari pertama ketika hampirhampir seluruh penduduk dunia diserang tunaaksara. Hanya tinggal sekitar jumlah ribuan orang yang tidak terpengaruh oleh kondisi tersebut. Aku akan mencoba bercerita seringkas mungkin (entah untuk apa karena tidak ada yang akan bisa membacanya nanti). Pukul enam pagi kondisi masih normal kecuali ada suara dengungan di langit. Suara ini berlangsung sampai pada pukul sepuluh pagi. Selama periode dengungan itu tidak ada apaapa yang terlalu mencurigakan terjadi; kecuali halhal kecil seperti penyiar di radio seperti kesulitan membaca naskah yang kemudian diadlip saja supaya tidak kentara. "Kami baru menerima informasi bahwa satu kecelakaan yang mengakibatkan ke ma ma ke mace tan jalan raya terjadi di ja ja lan lan J A J A .... mohon maaf ada sedikit masalah teknis, sekarang kita berhibur
213
dengan sebuah lagu ..." Kemudian tidak ada siaran berita seperti biasanya. Pada jangkaanku tepat pukul sepuluh pagi ketika dengungan itu berhenti setiap orang sudah jadi buta huruf. Pukul sepuluh setengah kondisi itu dikonfirmasi terjadi di seluruh negeri. Aku tahu kemudian, melalui siaran tv luar negeri bahawa kejadian tersebut berlaku di seluruh dunia. Semua sekolah ditutup. Guruguru tidak ada yang bisa membaca dan menulis. Gedunggedung bisnis juga ditutup karena tidak ada sesiapa yang bisa membaca nilai uang lagi; sebelum ditutup aku sempat membeli barang berharga sepuluh ribu lalu aku membayar dengan uang lima puluh ribu dan aku menerima sisanya, uang kertas satu juta. Untuk beberapa hari kantorkantor masih beroperasi meski dalam kondisi kecoh karena segala perintah disampaikan secara lisan; dari mulut atasan turun ke petugas bawah, ketika perintah itu sampai kepada kuli yang mengerjakannya arahan itu sudah 100% berubah. "Tidak seorang pun diperbolehkan mengambil cuti," kata petugas administrator. "Sampaikan kepada semua staf." Ketika perintah ini sampai kepada yang paling bawah ia sudah berubah jadi satu perintah yang membingungkan. "Cuci toilet tidak diizinkan." Untuk beberapa hari berikutnya toilet di kantor kami dibiarkan kotor karena itu adalah perintah direktur melalui petugas administrator melalui pembantu petugas administrator melalui pembantu pembantu petugas administrator melalui pembantu pembantu pembantu petugas administrator melalui ... mesin administrasi
214
terhambat, lebihlebih lagi di departemendepartemen yang besar dengan kaki tangan yang ramai: perintah tidak ada yang dilakukan seperti yang diinginkan. Aku sendiri menerima arahan disampaikan dari mulut ke mulut: "Anda diarahkan untuk menikah cepatcepat dengan kambing. Kambing cari sendiri." Sementara di luar, di jalanjalan raya, tandatanda dan labellabel tidak berarti langsung, tidak ada yang bisa membacanya, banyak peraturan jalan raya yang dilanggar. Polisipolisi lalu lintas mengejar dan menahan pelakupelaku tersebut, tetapi ketika mereka hendak mengeluarkan surat tilang mereka jadi bingung karena sudah tidak tahu menulis lagi. Saman disampaikan secara lisan. "Silakan bayar denda 500,000 di kantor polisi." Tentulah gugatan tersebut tidak dapat dipakai. Kondisi di mahkamahmahkamah pula jadi kacau karena tiada sesiapa tahu menulis surat, misalnya pemberitahuan kebangkrutan, dan koran pun sudah tiada ada untuk menyiarkannya. Akhirnya pemberitahuan kebangkrutan itu disampaikan secara mulut saja, dan ketika ia sampai ke orangorang yang bersangkutan itu sudah jadi lain: "Anda diarahkan mengambil tiket berlayar dengan kapal mewah mengelilingi dunia dengan gratis." Ini aku ketahui dari cerita temanteman yang awalnya dituntut bangkrut oleh bankbank sebelum kejadian dengungan. Aku berusaha keras berpurapura buta huruf agar tidak dibebani tugastugas yang tidak diundang: aku hanyalah tukang catat. Aku kira kepurapuraanku itu ketahuan juga ketika seorang bule datang membawa pesan.
215
"Tuan diangkat jadi Presiden Amerika," katanya. "Sila cepatcepat migrasi ke negeri kami." Permintaan terhadap orangorang yang pintar membaca dan menulis, sangat tinggi, mereka dibutuhkan untuk mengurus dunia. Aku agak, jika pesanan mulut itu benar, pastilah di Amerika, penduduknya, buta huruf semuanya. Kemudian aku mendengar suara dengungan kedua yang durasinya lebih panjang dari yang pertama dahulu, lebih dari setengah hari. Nguuunggg...
216
78 ANAK
S
udah pukul sembilan malam. Aku terdengar suara bocah memanggilmemanggil namaku. Dalam suasana pesta dan bersesaksesak, suara bocah itu terdengar seperti khawatir, tetapi juga seperti bermain main. "Asriiii!" "Asriiii!" Pasti mereka berdua telah lolos dari pengawasan orang tua. Langkahlangkahku otomatis menuju ke arah suara yang memanggilmanggil itu. Meskipun kondisi sesak, aku tidak kesulitan menemukan mereka: dua orang anak yang sebaya, mungkin kembar, lelaki dan perempuan, kirakira berumur sepuluh atau sebelas tahun. Mereka berputarputar di trotoar di bawah lampu listrik yang tidak berfungsi. Aku duduk tidak jauh dari situ sambil mengambil minuman kaleng dari kantong plastik yang kubawa. "Asriiii!" "Asriiii!" Mungkin Asri itu abang mereka. Mereka datang ketika aku panggil. "Asri itu siapa?" "Bapa kami," kata mereka serentak. "Kamu panggil bapa kamu Asri?" "Oh," jawab yang lelaki. "Bapa kami sudah tidak ada lagi." "Sudah mati kata mama," kata yang perempuan. "Adek jangan cakap gitu. Aku gak percaya bapa sudah mati."
217
Aku memandang mereka berdua. "Kamu berdua kembar?" Mereka mengangguk. "Tapi aku abang ia adik." "Bang, kata mama jangan bicara sama orang gak dikenal." Mereka cukup petah juga berbicara. "Kamu lapar?" Aku mengulurkan ke abang kantong plastik yang kubawa. Di dalamnya ada dua biji burger ayam dan sepaket kentang goreng. "Makanlah. Rejeki." Abang mengambil kantong plastik dan memberi sebiji burger kepada adik. Mereka makan dengan gelojoh. "Makan pelanpelan," kataku. Aku bangun untuk membeli es krim. Aku memberi si abang satu dan si adik satu. Aku senghaja duduk di tengahtengah mereka. Kami makan es krim. Si adik di sebelah kiriku, dan si abang di sebelah kananku. "Mama kamu mana?" "Hilang," kata si abang. "Pesan mama," kata si adik, "kalau hilang jangan ke manamana tunggu di satu tampat sampai mama ketemu." Aku merenungrenung muka mereka berdua lagi. "Mama kamu namanya Monalisa?" tanyaku. Si abang memandang dan merenungku dengan tajam. "Om ini bapa kamikah?" tanya si abang. Aku diam saja. Si Abang merapatrapatkan dirinya kepadaku. Badannya bersentuhan dengan badanku. Aku memeluknya dengan lengan kananku dan menepuk nepuk pahanya. "Kata mama bapa sudah mati," ujar si adik.
218
"Syyy, jangan cakap macam itu dik," kata si abang. "Itu kata mama, tapi kata orang lain bapa masih hidup." "Sudah, jangan gaduh," kataku. "Adek mari sini, duduk dekatdekat. Kita samasama tunggu mama." Si adik tidak membantah. Ia merapatkan badanya padaku. Aku menepuknepuk kakinya. Mungkin karena terlalu lelah, tidak lama setelah itu mereka tertidur. Sekitar duapuluh menit kemudian aku terlihat Monalisa berjalan, sesekali berhenti untuk bertanya pada seseorang. Sepuluh tahun, sebelas tahun, ia tidak banyak berubah, lenggok jalannya masih sama. Ada orang menunjuk ke arah kami. Aku menggerakkan si abang dan si adik supaya mereka segera bangun. "Mama kamu sudah datang," kataku. Si abang bangun dan terus berlari mendapatkan ibunya. Ia menarik lengan ibunya. "Tuh, bapa," serunya. "Bapamu sudah mati," kata Monalisa. Si adik masih terus tidur. Aku sudah mengangkatnya dan melatakkannya di atas pundakku. Kepalanya terkulai. Monalisa memandangku. Aku nampak bekas luka di dahinya masih ada. Aku tahu ia tidak mampu berpurapura tidak mengenaliku. "Hantar kami pulang," katanya. Suaranya dingin. "Mereka anakanakmu. Amilin dan Alisya." Baguslah, setidaktidaknya ia tidak berselindung selindung. Memang juga semua ini salahku sendiri, tapi itu sudah sepuluh tahun yang lalu, ketika muda dan berdarah panas. Sepanjang perjalanan, Monalisa menjawab soalanku seperti selama ini ia tidak pernah memaafkanku. Ia telah pulang ke desa orang tuanya. Ketika aku menceraikannya ia tidak memberitahu aku yang ia hamil.
219
"Sebagai suami kau harus tau sendiri," kata Monalisa dengan suara yang sedikit keras, "bukan enakenak bikin anak dan asyik sama cewek lain!" Aku memukulnya di dahi ketika mengetahui ia telah memasang spion untuk mengintip dan menggambar perilaku gelapku. Tidak ada suami suka diintip. "Itu anakanakmu," kata Monalisa. "Kalau kaumau jenguk mereka, aku gak menghalang. Mereka ada hak terhadap bapa mereka. Bagi aku kau sudah mati. Bagi mereka kau masih hidup. Mereka gak percaya kau sudah mati." Memang tidak berselindung omongannya. Aku percaya Amilin sedang mendengarkan bicara kami. Anak yang pintar seperti Amilin, pasti mengerti apa yang kami bicarakan. "InsyaAllah," kataku. "Aku akan mengunjungi mereka selalu. Beri mereka tinggal sama aku sesekali." "Terserah." "Aku masih membujang, perempuan itu cuma bertahan satu tahun saja kemudian kami bercerai," kataku. Aku memberanikan diri bertanya apakah ia menikah lagi setelah aku menceraikannya? "Jangan harap!" ujar Monalisa. Ia telah membaca fikiranku. "Aku gak akan menikah lagi. Kaumau aku menikah lagi agar kaubisa rujuk cina buta?" Aku memeluk erat keduadua anakku dan mencium pipi mereka sebelum melepaskan mereka masuk ke rumah. "Salam dan cium tangan bapa kamu," kata Monalisa, suaranya dingin sekali di telingaku. Mereka patuh. "Esok bapa datang bawa kamu jalanjalan, OK," kataku. "InsyaAllah."
220
Amilin dan Alisya mengangguk. Sepuluh tahun yang lalu, aku telah menceraikan Monalisa dengan talak tiga.
221
79 MATINYA SEORANG PEMBULI
K
etika aku menerima sehingga lebih sepuluh sms bahwa ia sudah mati, aku bergegas ke rumahnya. Aku tidak percaya bahwa orang sepertinya akan mati awal. Ia baru berumur sekitar 30 tahun. Sehat, kuat, tubuh kekar dan pembuli. Tangannya yang besar dan tebal itu, jika menampar orang akan meninggalkan dengung yang mengiangngiang di dalam otak selama seminggu. Telinga kananku tuli sampai sekarang, aku tidak ingin mendakwanya, karena aku yakin hukuman pengadilan dunia tidak akan pernah adil dan setimpal. "Alhamdulillah," kataku, spontan, saat sampai di pekarangan rumahnya. Sudah banyak orang di sana. Dari obrolan yang kucuri dengar, ia mati sore kemarin, bangkainya telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, kematiannya diduga tidak normal dan dicurigai karena ia memiliki banyak musuh. Kesimpulan dari informasi yang tidak menentu itu, matinya adalah karena pendarahan otak, dipukul di dahinya dengan kuat dan digigit nyamuk. "Tau juga ia mati, aku sangka ia akan hidup selama lamanya," aku terdengar ada orang berkata. Satu sentimen yang dirasakan bersama oleh sebagian banyak orang yang hadir. Aku hadir pun hanya untuk memastikan pada diri sendiri bahwa ia telah benarbenar mati. Aku tidak yakin ia dipukul di dahinya. Tidak ada sesiapa berani melakukannya secara berdepanan begitu. Mencuri pukul dari belakang mungkin saja ada. Aku tidak akan berani mencuri pukul ia dari belakang, meski aku ingin benar melakukannya, apalagi berdepanan memukul dahinya.
222
Tiada sesiapa akan merasa kehilangannya kecuali lembaga perbankan dan para rentenir yang tergantung pada solusi masalah secara kasar yang tidak ada peradaban. Aku tidak akan bercerita tentang kejahatan dan kekejamannya karena ia sudah mati, Alhamdulillah, ia sudah mati. Aku cuma ingin tahu bagaimana sebenarnya si celaka itu mati. Tidak banyak yang ikut mensalatinya, tidak sampai sepuluh orang (sepuluh dengan imam). Aku kepayahan mengingati bacaanbacaan salat mayat, aku tidak ingat satu huruf pun dimulai dari niat, Takbir, Basmalah, Fatehah, Selawat dan doadoanya otakku kosong, yang ada hanya suara ngiangngiang di telinga kananku, yang ada di dalam hatiku hanyalah persumpahan bahwa aku tidak akan memaafkannya sampai telinga kananku sembuh seperti sediakala. Meskipun hadir, aku terhalang dari mensalatinya. Seorang perempuan tua menghampiriku. "Maafkanlah jika ia ada membuat kesalahan kepada anak," katanya. "Aku ibu kandungnya. Kasihani dia." Apabila melihat wajah si ibu tua, aku terkenang dan terbayang pula wajah ibuku. Hanya seorang ibu yang sanggup, tanpa syarat, mengasihi anak yang pembuli dan jahatnya seperti ini. Timbul pula rasa belas kasihan di dalam hatiku. "Ya, ia pernah memukulku sehingga telingku tuli," kataku, "tapi karena ibu kandungnya yang meminta, aku maafkan dia, aku maafkan dia, aku maafkan dia." Segera selepas aku memaafkannya, telinga kananku sembuh. Allahu Akbar. Akulah yang berada di depan sekali ikut mengusung kerandanya. Semua orang di desa ini tahu aku adalah pembenci utama si mati, peristiwa aku ditampar sampai tuli memang diketahui
223
umum, bahkan ada orang mengatakan jika aku memaafkan orang ini, mereka juga akan memaafkannya. Akulah yang mengumumkan saat keluar berada di ambang pintu. "Aku telah memaafkan orang ini," kataku. "Ibu kandungnya meminta supaya kita mengasihani dan memaafkan anaknya ini. Maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Aku telah memaafkannya." Kemudian, barulah bertambah orang yang mengusung kerandanya ini masuk ke van jenazah, dan ikut serta ke pemakaman. Saat menghadiri acara tahlilan, adiknya bercerita kepadaku sekitar kematian kakaknya itu. Ia dan kakaknya sedang istirahat di belakang rumah sehabis membersihkan daerah sekitar. "Seekor nyamuk datang menganggu kakak," katanya. Berkalikali nyamuk itu ditampar tapi tidak kena, sehingga kakaknya jadi sangat marah dan menyumpah nyumpah seluruh nyamuk di dunia. Nyamuk itu hinggap di dahi kakaknya. Dengan sekuat tenaga, dengan tangannya yang besar, yang tebal, yang jika menampar orang akan meninggalkan dengung yang mengiang ngiang di dalam otak selama seminggu itu, ia menampar nyamuk di dahinya. Nyamuk itu mati tapi ia juga ikut mati terkena pukulan tangannya sendiri. Inna Lillahi wa inna ilayhi ra ji'uun.
224
80 TEMAN LANGKA
M
emang sulit untuk ketemu dengan teman yang seorang ini seolaholah ia tidak ingin berhadapan denganku. Mau dikatakan ia sombong, tidak pula, karena ketika berpapasan ia yang menyapaku dahulu dan terus saja mengajak aku minum di warung. Ia punya kebiasaan yang aneh sejak sekolah; ia suka meminjamkan uang kepada temanteman. "Hei," katanya, "aku ada uang lebih, kaumau minjam lima puluh ribu?" Mau dikatakan ia hendak mengambil untung, tidak pula, karena ia tidak pernah menagih utangutang itu. Jika kami bayar, ia terima; jika tidak, ia tidak ambil kisah. Lucu juga ketika ketemu denganku setelah sepuluh tahun terputus hubungan. "Hei, Nizam," katanyanya sebelum aku sempat menyapa, "aku ada uang lebih, kaumau minjam lima puluh juta?" Aku menahan tawa sampai perutku terasa keras. Susah mau mencari teman seperti ini. Kami samasama pergi ke warung. Katanya sekarang ia berbisnis sendiri, tidaklah ia menjadi jutawan, tapi bolehlah ia bertahan, kadang kala untung besar, kadang kala cukupcukup makan, tapi rezekinya tidak pernah terputus. Ketika hendak berpisah ia meletakkan amplop di depanku. "Nah," katanya. "Ini lima puluh juta aku utangkan kau." Aku tidak pula berniat hendak berutang karena belum ada kebutuhan yang mendadak, tapi aku ambil juga
225
amplop itu. Aku tidak sempat bertanya di mana ia tinggal dan di mana kantor bisnisnya. Ia meninggalkanku dengan cepat. Di mobil, aku memeriksa amplop itu dan memang ada lima puluh juta tunai di dalamnya. Di amplop ini juga ada logo bisnis dan numbor telepon kantornya. Aku tidak menggunakan uang ini, cuma aku simpan di bawah kasur. Setiap hari aku merasa susah hati pula dengan keberadaan uang ini. Aku mau mengembalikannya. Jadi aku pun menghubungi kantornya, tapi setiap kali pula aku diberitahu bahwa ia tidak ada yang ada orang lain. "Ia tidak ada," kata suara perempun di ujung sana. "Yang ada Tuan Ahmad." "Ia tidak ada. Yang ada Tuan Ali." "Ia tidak ada. Yang ada Tuan Saiful." "Ia tidak ada. Yang ada Tuan Abdul." "Ia tidak ada. Yang ada Tuan Sumaidi." Begitulah aku diberitahu setiap kali menelepon kantornya. Mau tidak mau, aku harus pergi ke kantornya dengan uang tunai lima puluh juta itu. Aku memberitahu siapa aku dan mau ketemu dengan siapa kepada perempuan penyambut tamu. Suara itulah yang selalu menjawab panggilan telefonku. "Ia tidak ada," katanya. "Yang ada Tuan Bokhari." "Gak apa," kataku, "aku jumpa Tuan Bokhari saja." Ternyata Tuan Bokhari itu tidak lain adalah kawanku itu juga. Melihat Tuan Bokhari itu adalah dia, aku pun bertanya mengapa ia mengatakan ia tidak ada, dan suka mengganti ubah namanya. "Aku takut," katanya. "Aku takut orang mencari aku untuk membayar utang."
226
81 LIMA JUTA SERATUSSERATUS RIBU, LIMA PULUH KEPING
A
ku baru saja mengeluarkan uang dari bank. Itu yang terbanyak yang bisa aku ambil dari akun. Aku memasukkan uang kertas lima juta seratusseratus ribu, lima puluh keping ke dalam tasku. Melihat dan mencium bau uang itu tibatiba muncul satu dorongan yang kuat di dalam diriku untuk mencuri. Sudah lama aku tidak mencuri. Aku mencuri bukan karena kelaparan, tapi karena jiwaku memang pencuri. Iblis suka membisikbisikkan rencana yang bodoh: mencurilah, katanya, mencuri dari orang suci, orang yang baikbaik, mereka orang yang sabar. Curi dua juta saja. Dua juta bukan banyak pasti akan dihalalkan uang yang kaucuri itu. Mereka juga akan mendoakan kau yang baikbaik: Ya, Allah, jadikanlah pencuri itu insan baik dan murahkan rezekinya sehingga dia tidak mencuri lagi aameen. Nah, tidakkah kau mau didoakan seperti itu? Doa orang suci makbul. Setelah bertanya dari beberapa orang, aku ditunjuki ke rumah, yang menurut mereka, milik seorang alim. Pintu tidak terkunci. Aku mengetuk dan memberi salam. Aku masuk apabila tidak ada jawaban. Bodoh juga aku, sampai setengah jam menggeledah rumah ini. Iblis menertawakanku, rumah orang alim memang tidak ada harta. Aku tertangkap, entah dari mana orangorang ini tibatiba saja ada. Aku diseret keluar. Dipukul. Dihantam, hampirhampir babak belur, mujur orang alim datang mengamankan situasi. "Sudah, sudah," katanya.
227
"Dia pencuri, Pak Kiayi," ujar seseorang. Pak Kiayi memandang mukaku. "Apa benar kau pencuri?" tanyanya. "Iya, aku pencuri," aku mengangguk. "Nah," kata Pak Kiayi. "Dia pencuri, kerjanya memang mencuri." Pak Kiayi memandang orangorang yang memukulku. "Apa kerja kamu memang tukang pukul?" "Tidak, Pak Kiayi aku tukang ojek." "Aku tukang kebun singkong di belakang sana." "Aku nelayan, Pak nangkap ikan." "Nah, tukang ojek mengojek. Tukang kebun singkong berkebun singkong. Nelayan udah tahu kerjanya nangkap ikan. Jadi apa salahnya pencuri mencuri, kan itu wajar?" jelas Pak Kiayi. Jenggotnya yang putih bergerakgerak turun naik. Aku mau tertawa, tapi pipiku sakit dan gigiku patah. Entah, apa ini ilmu hakikat dan makrifat Pak Kiayi? Aku tidak paham. Bagiku, pencuri kalau tertangkap, pukul saja sampai babak belur, kemudian baru bawa ke kantor polisi. Jika tertangkap aku sedia pasrah pada nasibku. Dipukul sampai mati pun aku rela. Semua orang terdiam saat seorang pria masuk dengan terburuburu. "Pak, aku tetangga, rumahku dimasuki pencuri," kata orang ini, napasnya singkatsingkat. "Aku kehilangan uang seratusseratus ribu, lima puluh keping." Semua orang memandang ke arahku. Giliran aku pula digeledah. Tasku dirampas. Uang lima juta seratus seratus ribu, lima puluh keping, dikeluarkan dari tas itu. "Itu pasti uangku tuh, Pak Kiayi," seru tetangga itu. Itu uangku, bukan uang curi. Aku berani bersumpah, tapi aku tidak bisa protes. Aku tidak bisa membantah.
228
Tidak ada apaapa yang bisa aku buat. Omongan pencuri tidak akan dipeduli. Mau menangis, pasti jelek. Biasanya jika tertimpa situasi seperti ini aku akan tertawa pasrah. Tidak ada apaapa yang bisa dilakukan selain tertawa pada lelucon yang dimainkan kehidupan kepada kita. Tapi aku menahan diri. Kemudian masuk lagi seorang pria terengahengah, badannya kekar, dahinya berkeringat, mengaku tetangga, dan rumahnya dimasuki pencuri juga, kehilangan uang kertas lima juta seratusseratus ribu, lima puluh keping. "Aku yakin itu uangku, Pak Kiayi, bukan punya orang itu," ujarnya sambil ia memandang dengan mata yang menusuk tajam, menunjuki tetangga seorang tadi. Suaranya keras. "Lima juta seratusseratus ribu, lima puluh keping!" Tawaku terus pecah, meski aku capek.
229
82 UNGGUL
A
ku bercerita kepada istriku, dan ia bercerita kepada istri tetangga bahwa aku telah bermimpi berutang satu juta dari suaminya itu. Sekarang aku lagi raguragu apakah aku cuma mimpi atau benarbenar berutang. Terasa seperti aku benarbenar berutang. Aku dengan tetanggaku itu tidak begitu akrab karena ia menuduh aku selalu menyindirnyindirnya yang suka berutang tapi tidak mau bayar. Bagiku itu hanya persangkanya. Buat apa aku menyindirnya, ia tidak pernah berutang dariku? Ia tidak ada hubungannya dengan hidupku selain dari jadi tetangga. Sekarang ia datang kepadaku menagih utang. Bukan lagi satu juta, tapi satu juta setengah. "Jangan purapura itu mimpi," katanya dengan tegas, "kau minjam satu juta setengah dariku!" "Tapi aku cuma bermimpi," kataku. "Dan dalam mimpi itu pun cuma satu juta saja." "Kau tidak bermimpi," ujarnya. "Jangan cari alasan untuk tidak mau bayar! Utangmu satu juta setengah! Kaudatang ke rumahku tiga hari lalu, pake kemeja biru muda bedasi biru gelap polka dot kuning dan celana hitam, sabuk coklat merk Dunghill, hari Senin, jam sembilan delapan menit pagi. Katamu kau lagi butuh uang mendadak. Kau mendesak dan aku kasian. Kebetulan aku punya dua juta baru pinjam dari orang desa sebelah. Sekarang tinggal lima ratus ribu. Jangan kau purapura itu mimpi." Ia meletakkan uang lima ratus ribu itu di atas meja di depanku.
230
Aku diam memandang uang itu dan kemudian memandang mukanya yang cengkung sawo matang. Tampak keras muka itu, dan yakin seratus persen yang aku tidak bermimpi. Ia mengambil uangnya kembali dan pergi. "Aku akan datang lagi," katanya. Sekarang aku jadi tambah raguragu. Diskripsi tuntasnya tentang diriku itu jelas terbayang di dalam kepalaku. Iya, itu memang aku pada saatsaat genting dan formal. Tapi mengapa sampai aku terdesak minjam uang darinya? Itu sama sekali tidak mungkin. Ia orang miskin. Jika mungkin pun, pasti sudah kubayar seperti yang dikatakannya kujanjikan itu. Kemungkinan yang lain adalah memang aku berutang padanya, tapi karena sifatku yang tidak pernah berutang (kecuali sekali itu) membuat aku lupa. Aku tempat orang berutang pokoknya, cuma ia tidak mau berutang padaku karena perinsipnya (menurutnya), meskipun apa yang terjadi, tidak akan berutang pada tetangga. "Apa, ia menagih utang?" tanya istriku. "Iya." "Tapi itu kan cuma mimpi berutang." "Iya," kataku. "Tapi aku masih raguragu." Sebelum tetanggaku itu datang lagi, aku ke rumahnya, membawa uang yang dituduhnya aku berutang itu. Jika ada sesuatu yang tidak aku suka, itulah ia dituduh berutang. Aku membawa perasaan sedikit gusar. Aku meletakkan uang satu juta setengah di atas meja di depannya. Plak! "Gak usah kasar," katanya. "Walau aku miskin aku masih punya harga diri. Aku gak mau nerima uang itu kalo bayarnya gak ikhlas. Ambillah saja, anggap itu
231
sedekah dariku. Kalau gak mau bayar, ya, udah." Iya, sudah. Aku ambil balik uang satu juta setengah dan ternyata itu sebuah kekhilafan. Sejak hari itu, tetanggaku berlagak besar seolaholah aku pernah berutang padanya dan tidak mau membayar walau utang itu tidak banyak. Setiap kali aku mau membayar ia menolaknya. "Aku sudah halalkan," ujarnya. "Pekara kecil aja. Satu juta setengah tidak banyak." Pernah juga aku coba membayarnya melalui istriku kepada istrinya. Itu juga ditolak. Kata istrinya mereka ikhlas melepaskan utang itu. Tetanggaku itu tidak menyapaku saat berpapasan, hanya tersenyum unggul.
232
83 FANA
K
hutub Zaman, Tuan Guru mengangkat aku sebagai orang kanannya, dan sebagai Khalifah Zikir mewakili dirinya, jika ia tidak hadir. Tentu ini sedikit banyak menimbulkan iri hati muridmuridnya yang lama aku baru berguru dengannya satu tahun. Aku juga bertanya tanya mengapa aku yang ditunjuki. Aku adalah anak murid yang banyak raguragu dari yakin. Aku juga adalah anak murid yang kurang berzikir. Tuan Guru telah memberiku beberapa zikir khusus, tetapi aku tidak pernah mengamalkannya seperti yang diarahkan. Salat farduku juga tidak konsisten. Jika dibandingkan dengan muridmurid lain aku tidak memiliki kehebatan. Murid murid lain ada yang bisa mengobati orang sakit; ada yang bisa berjalan di atas air; ada yang bisa menjatuhkan barang dari jauh hanya dengan pandangan dan gerak tangan. Aku ingin sekali jadi hebat seperti mereka. Sebagai Khalifah Zikir, aku selalu duduk di sisi Tuan Guru, ikut mengawasi muridmurid fana dan tidak sadar diri. Ada yang mengluarkan cahaya dari belakang mereka; ada yang keluar asap dan ada yang terapung apung di udara. "Perhatikan," kata Tuan Guru. "Semua ini hanyalah special effects. Tapi mereka tidak tahu. Biarkan mereka tenggelam di dalam special effects." Aku tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuan Guru. Ketika semua muridmurid dalam keadaan fana Tuan Guru bangkit dan mengajak aku keluar dari kamar zikir itu. Sebenarnya ini selalu kulihat saat aku masih anak murid biasa: Tuan Guru meninggalkan kami.
233
Pernah juga sekali dua kali aku terlihat Tuan Guru bangun dan menghampiri seorang murid perempuan yang tidak sadar, memimpinnya keluar dan kembali beberapa waktu kemudian dengan anak murid tersebut menjadi lebih khyusuk berzikir dan mengeluarkan cahaya dari belakangnya. "Kita tinggalkan mereka," kata Tuan Guru. "Mari kita minum dan makanmakan." Aku membawa Tuan Guru ke restoran yang dimahunya. Kami singgah di sebuah restoran milik bukan orang Islam. Aku sendiri tidak akan mau makan minum di sini jika sendirisendiri. "Halalkah ini Tuan Guru?" kataku. Ia memandangku mempertanyakan aku mempersoalnya. Dengan pandangannya itu aku terdiam, tentulah ia sebagai Tuan Guru Khutub Zaman lebih tahu apa yang dibuatnya. Ia memesan mie tiaw goreng dan teh pekat. Sebagai seorang murid aku mencoba menggemari apa yang Mursyidku gemari, aku pun memesan mee tiaw goreng dan teh pekat. Sementara Tuan Guru Khutub Zaman melahap makanannya dengan berselera aku pula merasa loya, tapi aku paksa juga menghabisinya. Selesai makan minum, kami tidak pula dipinta bayar dan ini aku sandarkan kepada kehebatan Tuan Guru. "Silalah datangdatang lagi," kata empunya restoran. "Tuantuan bole makan minum di sini gratis." Aku melihat menumenu di dinding restoran ini yang jelas bukan makanan untuk orang Islam. Aku percaya Tuan Guru lebih tahu karena ia kasyaf. Ini selalu kami lakukan dan kami akan pulang setelah tengah malam. Kami akan duduk di tempat kami seolaholah kami tidak pernah ke manamana. Walau apa pun kehebatan yang
234
dinampakkannya, betapa pun ia disanjung oleh anak muridnya, semakin aku dekat kepada Tuan Guru, semakin pula aku nampak bahwa ia hanyalah orang biasa. Ada kalanya aku nampak ia sangat muram berpikir terlalu dalam. "Apa yang Tuan Guru susahkan?" selalu juga aku bertanya. Ia seperti terlalu berat mau menjawab. Kemudian pada suatu malam saat sesi zikir, dan anakanak muridnya semua fana, ia pun menjelaskan kepadaku dengan suara rendah. "Semuanya hanyalah sepecial effects," katanya. "Kaulah yang akan menjadi penggantiku." Kemudian aku nampak apa sebenarnya yang terjadi. Di sekelilingnya ada enam ekor makhluk yang taat pada perintahnya. Setiap muridnya didamping seekor makhluk serupa yang masuk ke dalam tubuh mereka membuat mereka seperti tidak sadarkan diri. Ia memerintahkan seekor makhluk untuk mengangkat seorang murid supaya ia melayang di udara. Aku nampak ada makhluk bermainmain 'lampu' di belakang seorang murid, dan ada yang bermainmain asap; begitulah aku mengerti semuanya hanyalah 'special effects'. Tuan Guru kemudian bangkit memimpin tangan seorang murid perempuan yang muda keluar menuju ke satu kamar lain, aku mengikuti mereka. Di kamar ini murid tersebut dirogol dan diperkosa oleh seekor makhluk yang tersenyum sinis kepadaku. Seminggu setelah menampakkan semua ini, Tuan Guru ditimpa kecelakaan yang mengerikan. Aku lebih cenderung percaya bahwa ia sebenarnya membunuh diri. Tinggal aku memimpin kelompok tariqat ini seperti yang dipesankannya kepadaku dan kepada murid
235
muridnya. Murid tertua yang memiliki rumah tempat kami mengadakan sesi zikir ini seperti tidak senang, dan nampak seperti menentang. Dari jauh aku menudingya dan secara rahasia memerintahkan dua ekor makhluk yang mendampingiku untuk mengangkatnya mengikuti gerakan jari telunjukku dan mendorongnya ke dinding. Ia meminta ampun dan maaf. Aku menyuruh makhluk makhluk itu melepaskannya dan ia jatuh di atas lantai. Aku merasa sangat kuat dan hebat. Selama enam bulan aku memegang kekuasaan dan kehebatan ini, dan ternyata aku lebih hebat dari Tuan Guru. Bahkan aku diberi dua ekor makhluk ekstra untuk jadi hambaku. Apa saja yang aku suruh mereka taat melakukannya. Setelah enam bulan itu makhluk pemerkosa yang senyum sinis muncul di depanku. "Semua ini menjadi milikmu," katanya dengan lembut. "Aku hanya minta dua pekara. Satu aku berhak memilih manamana murid perempuan untuk pelempias nafsuku. Kedua kausujud di kakiku sekali saja seumur hidupmu. Aku beri kau satu bulan untuk memikirkannya." Dalam waktu satu bulan itu, kekuasaanku semakin bertambah dan menjadijadi. Setiap orang mengagumi kehebatan 'keramat' yang kumiliki itu dan muridmuridku semakin ramai. Pada saat yang telah dijanjikan makhluk permerkosa itu datang, lengan disilangkan dan dengan senyum sinis memandangku. "Sekarang," katanya dengan lembut, "kausujudlah di kakiku. Hanya sekali ini saja."
236
84 GUNTING KUKU
J
ika lebih dari seminggu kukuku tidak dipotong aku akan merasa kurang nyaman. Sekarang kukuku sudah lewat empat hari tidak berpotong karena gunting kukuku hilang. Gunting kuku ini sudah lebih sepuluh tahun kupakai. Hanya gunting kuku ini saja yang cocok dengan kukuku. Dulu aku telah mencoba beberapa kali membeli gunting kuku yang baru tetapi tidak aman kupakai. Aku masih menyukai gunting kuku yang lama itu. Tidak mungkin gunting kuku itu dicuri orang karena banyak lagi barangbarang lain yang berharga yang pantas dicuri. Tidak juga mungkin jauh hilangnya, pasti masih ada di dalam rumah ini. Semakin lama aku mencaricarinya semakin galau rasa di hatiku, dan semakin terganggu pikiranku. Iblis atau jin mana yang telah mengambil gunting kukuku itu? Ke mana saja ghaibnya? "Ini pekara kecil," kata istriku. "Gak usah dibesar besarkan." "Aku tidak akan berhenti selagi belum ketemu," kataku. Aku tidak tahu kenapa aku terdorong untuk terus mencaricarinya. Aku mencaricarinya di setiap sudut rumah, di atas atap, di dalam gudang, di loteng, di balik lemari, di bawah kasur; kadangkala berharihari aku menghilangkan diri. Hingga kini aku masih mencaricarinya. Hari ini adalah hari ulangtahun kesepuluh aku mencari gunting kuku itu. Kukuku pula selama itu tidak pernah berpotong. Aku tidak ke manamana, aku masih mencaricarinya di dalam rumah ini; gunting kuku itu tidak mungkin berada
237
di tempat lain. Istriku telah bersuami baru tiga tahun setelah aku dilaporkannya hilang, dan ia tampak bahagia bersama suami baharunya itu. Aku tidak ingin mengganggunya; sesekali aku akan melepaskan rindu lalu berbaring di sisinya, sebelum melanjutkan semula mencari gunting kukuku itu. Istriku akan terbangun, dan melepaskan nafas keluhan yang hampirhampir tidak terdengar. Karena tidak ingin mengganggu kebahagiaannya, aku pun meninggalkannya kemudian ia pun membangunkan suaminya. "Shhh," katanya. "Itu suara mantan suamiku yang gaib mencaricari gunting kukunya yang hilang." Itu sudah cukup bagiku, karena ia masih ingat kepadaku. Aku tidak meminta yang lebih dari itu. "Itu hanya suara tikus," kata suaminya sambil memeluk mantan istriku itu. "Janganlah dipikirpikir lagi. Ia hilang mencari benda hilang."
238
85 SERVIS
D
ua orang mereka datang dengan gaya salesman. Pakaian rapi celana hitam dan kameja putih: yang pria, kurus, pakai dasi, dan yang perempuan sedikit gemuk berjas hitam. Aku tidak suka salesman. Jika aku harus membeli barang aku ke toko saja. Kali ini aku benarkan mereka masuk. Jika mereka akan mendemo penyedot dubu, aku akan suruh mereka bersihkan seluruh rumah. Mereka tidak membawa apaapa produk untuk didemo. "Kami menawarkan servis," kata pria yang kurus, "dengan biaya yang terjangkau." "Apa sih servisnya?" "Begini," kata pria kurus. "Jika Tuan ada melakukan kejahatan kepada sesiapa dan Tuan belum mengakui kejahatan itu, tetapi Tuan sudah dituduh, kami bersedia mengakui atau mengambil alih kejahatan itu dengan biayabiaya tertentu." Menarik juga servis mereka ini. Aku coba memikir mikirkan apa saja kejahatan yang pernah kulakukan. Sulit juga mencari kesalahanku karena aku ini orang yang baikbaik. Korupsi? Aku tidak pernah dituduh korupsi. Mencuri? Tidak juga. Membunuh? Tidaklah membunuh nyamuk memang ada. Barangkali aku harus coba melakukan kejahatan sebelumnya dan suruh mereka ini mengakui melakukannya nanti. Aku menggelenggelengkan kepala. "Aku ini keturunan orang baikbaik," kataku. "Jadi aku tidak dapat menemukan kejahatan yang pernah kulakukan."
239
"Ya, kami percaya Tuan keturunan orang baikbaik," kata pria kurus. "Tapi Tuan juga manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Tak usah pikirkan yang besar besar seperti korupsi dan penyimpangan." "Ya," sampuk perempuan gemuk. "Misalnya, mulai dengan kejahatan kepada tetangga." "Oooh, kalau itu memang ada," kataku. Mereka berdua tersenyum. "Ceritakan kepada kami," kata perempuan gemuk. "Kami bersumpah akan merahasiakannya." Aku pun menceritakan bahwa tetanggaku itu ada memelihara tiga ekor bebek. Bebekbebek ini kadangkala tembus ke kawasan rumahku dan tahinya berceceran di sanasini. Ini menyebalkanku. Aku sudah ke rumahnya mengeluhkan hal ini berkalikali, tapi ia tidak peduli. Aku disuruhnya memagar area rumahku. Satu hari tiga ekor bebeknya ini hilang. Tentulah ia tuduh aku melenyapkannya. Tentulah aku menyangkalnya. Sampai sekarang ia cemberut denganku. Setiap hari aku disindirnya. Jika ia marah anaknya, ia senghaja akan menaikkan suara sehingga aku terdengar. Katanya: "Celaka kau pencuri bebek!" Anaknya itu baru juga berumur tujuh tahun. "Aku tuh yang disindirnya," kataku. "Tapi apa benar Tuan yang mencuri bebekbebek itu?" kata pria kurus. "Memang benar," kataku. "Masih ada dua ekor di dalam freezer. Sebenarnya sedap juga daging bebek jika diBBQ." "OK," kata perempuan gemuk. "Kami siap mengambil alih kejahatan Tuan itu. Kami ada menawarkan tiga paket. Paket pertama kami mengakui yang kamilah yang melakukan kesalahan itu. Paket kedua, seperti yang
240
pertama plus kami akan menyebabkan ia merasa sedikit menyesal. Paket ketiga kami akan menyebabkan ia menyesal besar dan memohon maaf sembari nangis nangis kepada Tuan." "Bagaimana kamu akan membuatnya begitu?" Aku kurang yakin. "Itu urusan kami, Tuan tak usah pikirkan," kata perempuan gemuk. "Paket ketiga itu yang paling mahal dan paling memuaskan hati. Untuk kasus kecil Tuan ini, kami cuma minta 500 ribu saja. Diskon 20% jadi 400 ribu, uang muka 100 ribu." "Ada garansi uang muka dikembalikan jika gagal," kata pria kurus. "Tapi Tuan pasti akan puas hati." "Aku ingin tetanggaku itu datang menangisnangis minta maaf kepadaku," kataku. Aku memberikan mereka uang muka 100 ribu. "Apa jaminan kamu." "Tidak ada apaapa," kata mereka serentak. "Ini bisnis kami," kata pria kurus. "Kami sedang membangun reputasi sudah lebih seratus orang kami tolong, tapi namanama mereka semuanya confidential." Ya, apalah jumlah seratus ribu. Aku siap dengan risiko kehilangan seratus ribu, jika mereka kabur, aku kira sedekah saja. Tiga hari kemudian tetanggaku itu mendatangiku. Ia memelukku dan meminta maaf padaku. Ia mencium tanganku berulang kali. "Aku telah berburuk sangka kepadamu," katanya dengan menangisnangis. "Cemberut dan menuduhmu mencuri bebekku. Maafkan aku, Tuan. Maafkan aku, Tuan." Wah, ia bertuantuan denganku. Aku orang baikbaik, keturunan dari orang baikbaik. Aku memaafkannya. Aku mengundangnya beserta
241
familinya untuk BBQ bersama kami malam nanti sebagai tanda silaturahmi yang ikhlas dariku. "Mari kita mulai lembaran baru dan jernih," kataku. "Memang Tuan keturunan orang baikbaik," kata tetanggaku. "Insya Allah aku akan datang." Setelah ia pergi, aku menyuruh pembantu rumah mengeluarkan bebek dua ekor dari freezer, dipotong potong dan direndam dengan saus BBQ. "Malam nanti kita BBQ bebek dengan tetangga sebelah," kataku. Salesman dua orang itu datang seminggu kemudian untuk mengutip sisa biaya servis mereka. Aku ada kerja baru untuk mereka. Reputasi harus dipertahankan. Aku orang baikbaik, keturunan dari orang baikbaik. Aku orang baikbaik di langit dan orang baikbaik di bumi.
242
86 SAHABAT SAHABAT
I
A datang menjinjng sebuah koper berwarna hijau tua. Mukanya yang sawo matang berkeringat. Senyum senyum. Katanya ia sahabat kepada sahabatku. Ia cuma ingin menumpang sementara. Sahabatku itu tidak pula pernah memberi tahuku tentang ini. Dengan penuh hormat aku mempersilakannya masuk. Sebenarnya rumahku ini besar. Masih ada beberapa kamar yang kosong. Rumah ini kubeli dengan harga yang rendah. Tuan punyanya dahulu membutuhkan uang mendadak. Aku memiliki uang tunai yang dibutuhkannya itu. Habis kikis uang tabunganku di bank. Aku tidak punya uang lagi untuk membeli furnitur dan segala macam selain yang benarbenar dibutuhkan, karena itu rumah ini tampak kosong. Yang penting aku memiliki rumah dan tanah sendiri. Aku masih muda dan lajang (beruntung siapa yang bakal jadi istriku nanti). Ibu dan ayahku sudah tidak ada. Satusatunya saudara kandungku meninggal saat kecil tertelan batu. Tanah pusaka di desa pedalaman sudah kujual, harganya tidak seberapa. Dari uang penjualan tanah itulah beserta uang tabungan yang kusisih dari gajiku setiap bulan, aku berhasil menyimpan jumlah yang dibutuhkan itu. Aku mengajak seorang sahabat sekantor yang juga datang dari pedalaman di daerah lain untuk tinggal bersamaku. Inilah sahabatnya yang datang itu. Ia ingin menumpang sementara mendapatkan pekerjaan di kota ini. Awalnya aku merasa tidak senang karena sahabat sekerjaku itu tidak memberi tahu aku dahulu, tapi
243
ternyata sahabat kepada sahabatku ini tidak hanya sekedar menumpang: ia membuktikan dirinya berguna. Meskipun ia lelaki, ia pintar memasak. Setelah seminggu lebih makan masakannya yang hebat aku pun bertanya ia mau melamar pekerjaan apa di kota ini. "Tukang masak," katanya, "di restoran bereputasi baik, kalau bisa di hotel." Aku menyarankan agar ia jadi tukang masak di rumah ini saja buat sementara waktu. "Dan berjajalah nasi bungkus di depan sana," kataku. "Pasti meledak!" "Tapi kita harus membuat pondoknya dulu," katanya. "Yang teguh dan tampak bersih. Karena aku tidak akan mau berjaja masakanku seenakenaknya saja." Bagus juga. Orang ini memang pintar. Aku tidak keberatan jika sebuah pondok permanen dan cantik didirikan di tanahku ini; bisa juga digunakan untuk hal lain selain berjualan nasi bungkus nanti. Cuma kataku aku tidak ada alokasi uang yang cukup untuk itu. "Hey," katanya. "Aku ada sahabat seorang tukang buat pondok yang bagus. Aku bisa minta pertolongannya. Tentang biaya ia itu tidak cerewet." Esoknya sahabat sahabat sahabatku ini datang dengan peralatan pertukangannya. Katanya ia akan tinggal di rumahku ini sehingga kerjanya selesai nanti. Jadi ia pun tinggal dengan kami. Kemudian ia terus saja menyukatnyukat kawasan di mana pondok itu akan didirikan. Kawasan itu sedikit semak dan harus ditebas dan dibersihkan. "Hey," katanya. "Aku ada sahabat yang bisa membersihkan kawasan ini dengan baik. Ia tidak cerewet tentang biaya." Esoknya sahabat sahabat sahabat sahabatku ini
244
datang dengan peralatan pemotong rumput, cangkul dan lainlain. Ia terus bekerja membersihkan kawasan semak tersebut. Memang bagus juga hasil kerjanya. Ia menawarkan untuk terus memotong rumput di keliling rumah. Katanya kawasan rumah ini terlalu membosankan. Tidak ada bunga dan pohonpohon perhiasan. "Hey," katanya, "Aku ada sahabat tukang kebun bunga yang bagus. Ia tidak cerewet tentang biaya." Esoknya sahabat sahabat sahabat sahabat sahabatku ini datang dengan peralatan berkebun bunganya. Katanya ia akan tinggal di rumahku ini sehingga kerjanya selesai nanti. Ia terus saja menyukat nyukat kawasan rumahku. Malam itu ia dengan cermat merencanakan kebun bunga yang akan dibuatnya. Tapi ia membutuhkan dua puluh biji pasu bunga yang dibuat khusus. "Hey," katanya, "Aku ada sahabat tukang buat pasu. Ia tidak cerewet tentang biaya." Esoknya sahabat sahabat sahabat sahabat sahabat sahabatku ini datang dengan peralatan membuat pasunya. Katanya ia akan tinggal di rumahku ini sehingga kerjanya selesai nanti. Jadi ia pun tinggal dengan kami. Sahabat kepada sahabatku menjalankan bisnes nasi bungkus, bukan nasi bungkus biasa katanyanya, karena enaknya orang bersedia membeli dengan harga yang tinggi sedikit dari di tempat lain. Dalam satu hari yang normal, ia bisa dapat hasil lebih satu juta bersih, dan itu cuma kerja setengah hari. Katanya ia akan melanjutkan bisnes ini. Ia suka rumahku. Ia berencana untuk memperluas bidang bisnisnya kepada katering untuk majlis sederhana, tapi ia harus punya ruang memasak
245
yang lebih besar, jadi ia mengontrak sahabatnya tukang buat pondok untuk membuat tambahan pada rumahku ini. Meski sudah selesai tugas, mereka semua terus tinggal di rumahku dengan alasan rumahku besar, tidak bagus dibiarkan kosong, nanti didiami hantu, juga sebagai biaya kerja mereka, dan alasanalasan lain yang masuk akal. Aku tidak bisa membantah alasan dan logika yang mereka ajukan. "Rumah besar dan nyaman seperti ini harus dioptimum pemanfaatannya," kata seorang dari mereka. Perlahanlahan ahliahli keluarga mereka diangkut untuk tinggal bersama. Aku sudah tidak berkuasa untuk bertindak apaapa lagi. Mereka bebas berbuat sesuka hati.
246
87 I LOVE YOU
I
a seorang pria yang pemalu. Terlalu sulit untuk ia memberanikan diri menyatakan perasaannya yang sebenar. Selama ini hubungan mereka terasa seperti biasa saja, seperti tidak akan menuju ke manamana. Jika dibiarkan terus seperti ini, mungkin gadis pujaannya itu akan terlepas kepada orang lain. Sekarang gadis ini berada tidak jauh darinya, dan mereka hanya berdua. Tapi ia tidak berani. Setelah susahsusah berpikir sambil jarinyajarinya bermainmain dengan koin di dalam saku celananya, ia pun mendapat satu pikiran. Ia mengeluarkan koin lima ratus rupiah itu lalu melambungkannya ke udara, menangkapnya dengan telapak tangan kanan, menukupnya di belakang tangan kiri. Pelanpelan ia membuka telapak tangan kanannya: BUNGA MELATI. "Melati," katanya kepada gadis yang sekarang berada di sisinya. "I love you." Hampirhampir saja Melati pingsan. Kaget.
247
88 AMBILLAH
S
ebuah mobil Mercedes hitam berhenti di depan rumahku. Dari pintu belakang keluar seorang lelaki berusia sekitar lima puluh tahun. Dari gaya jalannya dan penampilannya, ia seorang yang kaya. Aku yang berada di pintu segera menemukannya; mungkin ada masalah. Ia mengunjukkan sebuah kantong kertas besar berwarna biru kepadaku. Aku melihat ke dalam kantong kertas itu. Katanya ada tiga ratus juta di dalamnya. "Ambillah," katanya. "Terima kasih," kataku. Ia masuk mobil dan pergi.
248
89 XKRITA
K
atanya ia keturunanku yang datang dari masa depan karena terdesak untuk mencari xkrita. "Xkrita itu apa?" kataku. "Dan untuk apa?" Ia pun menjelaskan dan menceritakan kepadaku. Aku tidak yakin apakah aku benarbenar mengerti ceritanya itu atau tidak. Beginilah ceritanya: bumi sudah tidak mengeluarkan minyak lagi. Negaranegara yang dulunya kaya karena minyak jatuh miskin. Buat beberapa dekade kondisi hidup di seluruh dunia yang tergantung sangat pada minyak jadi sangat sulit. Ilmuwan, saintis, jurutera bergabung dan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk mencari pengganti minyak. Akhirnya solusi yang sangat mudah ditemukan dan segera dikembangkan. Dengan penduduk dunia yang mencapai 50 miliar dan terus meningkat solusi itu sebenarnya berada di bawah hidung setiap orang: tahi manusia. Tahi manusia menjadi komoditas yang sangat berharga. Kata tahi diganti dengan kata lain yang lebih exotik xkrita. Karena sangat perlunya xkrita itu bagi kelangsungan hidup manusia, ia menjadi sangat mahal, jauh lebih mahal dari emas. Seluruh kegiatan manusia dipusatkan kepada mengeluarkan xkrita yang berkualitas secara berkelanjutan. Manusia bekerja untuk mengeluarkan x krita. Tidak semua xkrita setaraf, ia punya kelas dan grednya yang tersendiri. Negara yang berpenduduk banyak menjadi produsen xkrita terbesar. Semua orang hidup nyaman. "Orang miskin sudah tidak ada lagi karena orang miskin juga mengeluarkan xkrita, meski grednya
249
rendah," katanya. Xkrita inilah yang mereka jual untuk membeli makanan yang lebih baik, yang akan menghasilkan x krita yang lebih baik, dan pelanpelan kemiskinan terhapus dari dunia. Ia dan keluarganya adalah produsen xkrita gred kelas teratas. Hal ini membuat mereka tergolong orang berada, memiliki hotel di sanasini. Mereka juga memilik pusat pemeroses xkrita yang berkualitas tinggi dengan bagian 'R and D' yang sangat aktif dan efesien. Mereka juga adalah pembeli xkrita dari orang umum. "Sekarang," katanya, "kami lagi dilanda wabah diare yang mempengaruhi pengeluran xkrita yang berkualitas. Harga xkrita melambung tinggi. Harga barangbarang lain juga ikut naik." "Kami ada tiga tangki tahi yang sudah tiga tahun tida diurus," kataku. Aku membawanya ke belakang rumah. Ia mengambil contoh tahi dari tangki itu, melakukan sedikit pemeriksaan tampak wajahnya gembira. Matanya membesar. "Aku akan membeli ini dengan sepuluh ketul emas bagi isi setiap tangki," katanya, ia tahu emas masih berharga pada zaman ini. "Ini sudah mencapai gradeA. Bagus sekali!" Sebentar kemudian muncul kapal angkasa yang menyedot semua tahi habis dari tiga tangki itu. Aku tahu ini belum cukup, aku menelepon tetanggatetanggaku dan menawarkan untuk membersihkan tangki tahi mereka sekarang juga. "Aku akan bayar satu ketul emas untuk membersihkan semuanya," kataku. Mereka pikir aku gila. Masa yang buat kerja
250
membayar, bukan mereka? Lalu aku menceritakan semua ini, dan mereka bertambah yakin bahwa aku sudah gila, tapi ketika mereka terlihat kapal angkasa penydot tangki tahi itu mereka tahu aku berbicara benar. "Berapa harga riil untuk satu tanki?" tanya seorang tetangga. "Sepuluh ketul emas," kataku dengan jujur, karena aku tidak bisa berbohong. Berita pula tersebar cepat; esoknya, setiap orang jadi pintar tidak ada sesiapa yang waras pikirannya akan mau berurusan dengan orang tengah. Setiap keluarga menjaga tangki tahi mereka dengan siaga siang dan malam karena takut isinya dicuri orang. Pemerintah tidak ingin melepaskan kesempatan ikut mengaut hasil, lalu segera merilis Akta Pajak Tangki Tahi.
251
90 PUPUS
A
ku batukbatuk kecil. Koh! Koh! Cuma dua kali batuk. Atuk (bapa kepada Kakek) yang sudah sangat tua, yang tuli (tapi kali ini hilang tulinya), cepatcepat mendekatiku. Menyentuh dahiku. "Aku terdengar ia batuk tadi," kata Atuk. "Aku rasa ia panas sedikit," katanya seperti raguragu pula. Koh! Batuk lagi. Kakekku berlarilari orang tua, datang cepat, menghitung nadi di pegelangan tanganku. "Anak ini sakit! Anak ini sakit!" katanya terpekikpekik. Bapa segera mendekatiku, menyentuh dahiku, leherku, pipiku. Ia mengangakatku masuk ke mobil. "Kita ke klinik swasta sekarang juga," katanya. Atuk dan Kakek ikut sama. Mereka lebih khawatir dan susah hati dari aku sendiri. Jika aku jatuh sakit, semua orang akan berusaha mencari obat. Berusaha agar aku cepat sembuh. Aku anak tunggal Bapa. Bapa anak tunggal Kakek. Kakek anak tunggal Atuk. Jika aku mati pupuslah keturunan kami semua.
252
91 RIMBA
K
awanku membawa aku masuk ke dalam rimba. Katanya ada satu suku di dalam rimba itu, "the lost tribe". Kawanku itu sudah lama tinggal bersama suku bangsa itu. Bahkan ia menikahi seorang wanita dari sana. Entah bagaimana pula adat pernikahan mereka. Aku dibawanya untuk mengambil foto sebelum puak ini punah, dan jadi manusia modern. Tandatanda modernitas itu sudah ada kata kawanku itu. "Kalau mereka sakit kepala mereka makan Paracetamol," kata kawanku itu, "atau Ponstan." Kebanyakan dari anggota suku ini berpakaian terbuat dari kulit kayu: yang pria sekadar menutup anggota sulit, sementara wanita yang bersuami menutup dada dan dari pinggang ke lutut; anak dara hanya menutup dari pinggang ke lutut. Ada seorang ibu yang memakai jersi berwarna merah klub sepakbola Manchester United GIGGS 11, yang sudah pudar warnanya. Ternyata ibu itu adalah mertua kawanku ini. Populasi suku ini, kata kawanku, adalah sekitar 200 orang. Menurut pendapatku mereka tidaklah begitu primitif apalagi anakanak mudanya, karena potongan rambut mereka adalah fashion punk dan berjambul. Cuma satu yang sangat menarik perhatianku, yaitu mereka semua bermuka membatu; tidak ada yang senyum. "Senyum artinya gak suka," kata kawanku. "Jadi jangan senyum kecuali kalau mau cari gaduh." Mujur juga aku dan suku bangsa ini berbagi satu kesamaan: aku dilahirkan dengan wajah yang selalu datar. Barangkali juga kawanku itu memilih aku karena
253
itu: aku tidak mudah senyum, bahkan tidak pernah senyum. "Kalau kita menyukai sesuatu macam mana?" "Ludah," kata kawanku. "Berludahlah." Ketika itulah seorang gadis muda menghampiriku. Pakaiannya dari kulit kayu sekadar menutupi badannya sampai ke lutut. "Ptui!" ludahnya. "Ptui!" ludahku. Aku tidaklah hendak mencari gaduh. "Ptui!" "Ptui!" "Ptui!" "Ptui!" "O o," kata kawanku dengan santai. "Kalau tiga kali ludah berturutturut itu artinya kamu sudah jadi pasangan suami istri." Kemudian seorang ibu memegang tangan gadis muda ini dan menyerahkannya kepadaku. Kawanku menyuruh aku menerima saja tangan itu. Terlanjur tiga kali ludah berturutturut; aku patuh, menyambut tangan yang mungil ini. "Sekarang," kata kawanku lagi. "Kau harus menghadiahkan sepasang baju kepada mama mertuamu. Apa saja baju, itu maharnya." Kemudian kawanku itu berbisik kepadaku: "Mama mertuamu itu gak suka mama mertuaku sejak aku jadi menantunya. Sekarang mereka samasama punya menantu orang luar. Mogamoga saja ia gak lagi senyum senyum pada mertuaku." Aku segera menurunkan tas sandangku. Dengan tergopohgopoh aku mengeluarkan sepasang baju, lalu kuberikan kepada ibu mertuaku. Ia menanggalkan
254
pakaiannya lalu memakai baju berwarna merah yang kuserahkan kepadanya itu: jersi klub sepakbola Liverpool, GERRARD 8.
255
92 WANITA MISTERI
S
udah lebih tiga malam berturutturut ia bermimpi wajah seorang wanita yang sangat cantik, meski tua dari istrinya. Wanita ini seperti terkejut memandangnya. Kecantikan wanita ini membuat ia kasmaran. Bayangan wajah itu ada di dalam cangkir kopi yang diminumnya, ada di mana saja ia memandang. Ia tidak tahu siapa wanita itu, atau di mana ia berada. Memang bukan di negeri ini. Kemudian ia teringat ceritacerita kuno yang pernah dibacanya dulu. Tokoh di dalam ceritacerita itu jika bermimpi sepertinya akan coba menemukan wanita tersebut sehingga dapat, untuk dijadikan istri, meskipun mereka sudah beristri. Inilah yang dinamakan jodoh. "Sayang," katanya kepada istrinya, "aku rasa aku mau berpergian ke luar negeri." "Boleh ga aku ikut?" tanya istrinya. "Kalo kauikut, siapa yang akan jaga anak?" "Abang tibatiba mau berlayar, ada apa sih?" "Haaah," katanya, wajah wanita misterius yang cantik itu terbayangbayang lagi di matanya. "Terpaksa. Dipaksa. Kena paksa. " Istrinya memang mengerti jika ia mengatakan, terpaksa, dipaksa dan kena paksa, itu berarti tidak ada apaapa yang bisa dilakukan lagi; ia harus membuat apa yang harus dibuat. Sebelum berangkat ia berpesan pesan pada istrinya. "Jaga anak baikbaik," katanya. "Aku mungkin berpergian sekejap, mungkin juga lama." Ia meninggalkan rumah mertuanya tempatnya ia dan istri menumpang. Ia menghilang selama sepuluh tahun
256
tanpa mengirim berita. Tidak diketahui apakah ia mati atau hidup. Setelah lebih lima tahun ditinggalkan tanpa berita Istrinya menuntut cerai di pengadilan kadi karena suaminya itu telah dihitung melanggar shighat talak takliq. Tuntutannya diterima. Istrinya menikah dengan seorang pemuda yang ternyata bintangnya bersinar, menjadi menteri. Hidupnya menjadi senang dan mewah setiap minggu ke salon memanjakan diri, spa, pijat dan 'facial'. Anakanak semua terpeduli, dikirim belajar ke luar negeri. Dibangunkan sebuah rumah besar dan mewah di bekas rumah mertuanya. Setelah sepuluh tahun menghilang itu, ia kembali tanpa memberitahu, dan agak kaget juga melihat rumah yang seperti istana itu. Ia tidak menemukan wanita misterius di dalam mimpinya. Ia nampak sangat tua dan lelah. Ia bertanya tetangga yang masih bisa mengenalinya. Apa sudah terjadi ke rumah mertua dan istrinya? Ia diberitahu semuanya: istrinya telah menuntut cerai dan sudah menikah dengan orang lain dan ia sudah bukan lagi suaminya. Ia mengerti dan menerima saja keadaan, menerima kesalahan diri sendiri mengejar wanita di dalam mimpi, ia akan pulang ke rumah orang tuanya. Ia ingin ketemu mantan istrinya untuk bertanya tentang anakanak sebelum pergi. Ia menekan bel di pintu dan memberi salam. Mantan isterinyalah sendiri membuka pintu. Tercegat di situ memandangnya dengan wajah yang agak terkejut. "Abang gak boleh masuk," kata mantan istrinya. "Aku sudah jadi istri orang." Ia juga agak terkejut melihat perubahan mantan istrinya itu: itulah wanita misterius di dalam mimpinya dulu.
257
93 FOTOKOPI
P
astinya karena aku bukanlah seorang suami yang baik, maka istriku jadi seorang yang cerewet. Manisnya percintaan kami mulai berakhir sebaikbaik saja kami menikah. Meskipun kebahagian sudah tidak ada lagi, kami tetap juga bertahan sebagai pasangan suamiistri setiap hari pasti ada yang aku gaduhkan dan ia cerewetkan. Namun begitu kata cerai tidak pernah terlintas untuk kupikirkan. Tidak juga terniat sedikit pun di hatiku untuk menceraikannya. Begitu juga istriku tidak pernah ia meminta cerai, meski aku (dalam pandangan mataku sendiri) adalah seorang suami yang paling buruk sedunia. Sudah tiga puluh tahun kami menikah secara fisik aku sudah tidak tertarik lagi terhadap istriku, ia sudah tidak lagi memiliki sosok yang diidamkan pria. Namun aku tidak pernah mau mencari perempuan lain. Selagi ia tidak minta cerai, selama itu ia istriku. Jika ia mati dulu, aku tidak akan menikah lagi. Cukuplah bagiku seorang istri saja di dalam seluruh hidupku. Cukuplah seorang saja. Semua inilah yang kupikirkan saat ini, pada pukul 12 tengah malam ini, mencaricari toko fotokopi. Setelah bergaduhgaduh dari pukul sepuluh malam tadi, aku akhirnya mengalah saja ya daripada melanjutkan perkelahian karena pekara sepele seperti ini, mending mengalah saja. Aku tidak tahu mengapa istriku bersikeras ingin aku memfotokopi sertifikat kelahirannya malammalam begini esok kan masih ada. Entah mungkin ia sengaja mau mencari gaduh karena sepanjang siang tadi kami tidak bertengkar. Macam sudah jadi keharusan dalam hidup kami bahwa setiap
258
hari kami harus bertengkar. Kondisi pekan agak sunyi ada sebuah dua toko makan yang masih buka. Aku merasa seperti orang gila membawa sertifikat kelahiran istriku mencaricari toko fotokopi tengah malam seperti ini. Aku sebal. Entah sudah berapa lama aku mencari akhirnya aku ketemu juga. Ini toko baru yang aku tidak sadari keberadaannya selama ini dengan papan label yang jelas: SPESIALIS FOTOKOPI. Di dinding toko ini ada beberapa label peringatan: BERHATIHATI APA YANG KAMU FOTOKOPI; FOTOKOPI YANG DIBUTUHKAN SAJA; MEMFOTOKOPI LEBIH DARI YANG DIBUTUHKAN TIDAK MEMECAHKAN MASALAH; KAMI MEMFOTOKOPI APA SAJA YANG DIMAU. Label peringatan paling lucu yang buat aku ketawa adalah: JANGAN MEMFOTOKOPI DI SINI. Aku tertawa dan menyerahkan sertifikat kelahiran istriku kepada lelaki tua yang mungkin saja manager toko ini. Mukanya tidak menampakan kerutan usia tapi ia memiliki jenggot putih yang memanjang ke bawah ke level pusarnya. "Satu salinan saja," kataku. "Sertifikat kelahiran istrimu? Hatihati apa yang kamu fotokopi," katanya tersenyumsenyum, melihat kertas yang kuberikan itu. "Satu salinan, ya?" "Jadikan itu empat salinan," aku merubah pikiran dengan maksud menantang label peringatan di dinding toko itu. "Istriku itu satu salinan saja tidak akan pernah cukup!" "Memfotokopi lebih dari yang dibutuhkan tidak memecahkan masalah," katanyanya tertawa kecil. "Jangan memfotokopi di sini," aku menyambung sambil tertawa besar.
259
Dia juga tertawa. "Tapi kami memfotokopi apa saja yang dimau." Aneh dan lucu toko itu. Aku pulang sambil tertawa terus. Hilang segala kegusaran dan kesebalanku. Jangan memfotokopi di sini, kataku dalam hati, hahaha. Tiba di rumah, aku membuka pintu, di situ, berdiri dengan bercekak pinggang, istriku menunggu dengan muka cemberut lima orang semuanya. Istriku dan empat orang yang mirip, seperti salinannya. Mampuslah aku! Toko fotokopi itu sampai sekarang aku tidak pernah ketemu lagi.
260
94 CINTAKU JAUH DI HUTAN
B
eban di hatiku terasa berat. Aku baru pulih dari kemurungan dan disarankan untuk terus istirahat, mengambil satu hobi dan cuti panjang. Biasalah orang mudamuda bercinta kemudian putus, karena terlalu mengharap, akhirnya aku ditimpa gangguan jiwa dan depresi. Hampirhampir aku gila. Ketika hampirhampir gila inilah aku membeli kamera yang berharga 50 juta dan sangat sulit untuk dipakai (dari sebagian uang yang kusimpan untuk belanja nikah). Baik untukku mengisi pikiran dan melupakan hati yang terluka. Aku lari ke dalam hutan mencari kali dan air terjun kecil, memotret margasatwa. Kalau kau sudah hamirhampir gila sepertiku kau tidak peduli lagi, ya, jika ada hewan predator aku tidak berniat hendak lari. Aku akan memotretnya. Ada waktunya aku senghaja menyukar nyukarkan diriku, misalnya, aku hanya akan memotret burung berwarna putih atau semut atau ular atau daun berwarna jingga. Lebih sulit lebih kusukai. Aku menghabiskan waktu di dalam hutan, kadangkala sampai sehari suntuk dengan tantangan limitasi itu. Kadang kala aku tidak mendapat apaapa untuk dipotret, karena aku tidak ingin merubah subjek yang telah kurencanakan. Begitulah satu pagi aku turun dari rumah, rambut gondrong, dagu tidak bercukur, memakai baju dan celana kemarin, seperti orang gila, membawa kameraku, masuk ke dalam hutan dengan niat akan memotret katak. Sebaikbaik saja aku melangkah ke luar rumah aku tampak seekor katak, kecil dan lucu. Hari ini hari mudah.
261
Aku pun memotretnya. Oleh karena katak ini tidak lari, aku menggambilnya, meletakkannya di atas bahu kiriku dan membawanya masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan aku bercakapcakap dengan katak ini. "Hari ini aku hanya akan memotret katak," kataku. "Kork kroak krueik," katanya. "Itulah yang kurasakan tadi. Hari ini hari mudah." "Krok Krok kerouk," katanya. "Iya. Barangkali juga." "Krek krook kruk." "Hahaha. Banyak benar tuh. Aku gak percayalah." "Kirk kurok kreek." "Oh, oh itu dari sajak Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang." "Kkkrek kurik kurok." "Hilang sudah pedih dan perih, sekarang kaumau pulang ke kumpulanmu sebelum perahumu merapuh." "Kruuuk kruuuk kruuk." "Kita sama tapi gak serupa," ujarku. "Kau masalah jantan aku masalah betina. Kau punya pilihan yang banyak. Mudah mencari pengganti." "Kreeh kerih khruk," jawabnya. "Benar, benar, pilihan hati cuma satu sampai bilabila pun," kataku. Kami tiba di tempat aku biasa memotret. Ketika aku memasuki hutan itu aku melihat begitu banyak katak di daundaun, di batangbatang pohon; lebih dari sepuluh spesies. "Hahaha. Memang kau tidak berbohong; saudara maramu lebih dari seribu. Ramai banget mereka datang menyambut kepulanganmu. Pasti kau seorang Puteri Raja." "Krweek kuuurk keeerk," katanya.
262
"Terima kasih. Tapi sebenarnya kau tak perlu beritahu mereka yang aku mau memotret katak you spoilt the challenge." "Keersk kkuuurrk kquerk," katanya. "Pinter juga ya kau berbahasa Inggris," aku senyum. "So they like to be photographed." Katakkatak ini berlombalomba minta dipotret. Dengan memori kameraku yang terbatas, ini jadi satu tantangan pula. Ada seribu lebih katak yang minta dipotret. Penghabisan sekali aku memotret ramai mereka. Saat aku hendak pulang, katak dibahuku minta aku mengucupnya. "Krok Krok Krok," bisiknya ditelingaku. "I love you too," kataku. Ia melompat ke telapak tangan yang kutadahkan. Aku mengucup kepalanya. Ada sedikit perasaan kecewa di hatiku, karena ia tidak berubah jadi Putri jelita. Ia juga mengucup pipiku, dan aku tidak berubah jadi Pangeran Katak. Ia melompat dan bergabung dengan saudaramaranya. Mereka semua menghilang ke dalam hutan. Aku pulang, beban di hatiku terasa sedikit ringan.
kepustakaan: petikan dari puisi Aku Chairil Anwar 1943 'Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang' 'Hingga hilang pedih perih' petikan dari puisi Cintaku Jauh Di Pulau Chairil Anwar 1946 Perahu yang bersama ‘kan merapuh!
263
95 BUAYA
A
walawal pagi sudah ada bunyi bisingbising di luar. Suara berkerisikkerisik. Aku ingin menyambung tidur tetapi karena gangguan ini aku pun turun dan membuka pintu. Ada dua ekor buaya dewasa, lakibini, dan satu anaknya di balkon rumahku. "Kau ke kota hari ini?" tanya buaya laki. "Kalau ke kota, kami mau ikut." Hari ini hari Minggu, sebenarnya aku ingin istirahat di rumah saja, tapi ini satu kesempatan pula untuk ke kota dengan tiga ekor buaya. Di kota tidak ada apaapa yang khusus kami buat; cuma jalanjalan dengan santai. Di kiriku buaya laki dan bininya; anak buaya di kananku. Hanya satu peristiwa kecil yang menggangu kesantaian kami. Anak buaya di kananku menangkap dan menggigit kaki seorang pria berumur sekitar 40 tahun. Ia tidak ingin melepaskannya. Pria ini sangat bergaya; dengan kacamata hitam, kameja denim, celana jeans biru, ikat pinggang yang semuanya bermerek. "Adduduh, adduh," katanya, mencoba menarik kakinya yang digigit anak buaya. Ia terduduk. Aku melihat kaki orang ini. Dengan cepatcepat aku menanggalkan keduadua sepatunya barulah anak buaya melepaskan gigitannya. "Lain kali," kataku kepada pria itu. "Jangan pake sepatu kulit buaya!" Aku membuang sepatunya itu ke dalam tong sampah terdekat. Ia terincangincut bertelanjang kaki, meninggalkan kami.
264
Selain itu tidak ada apaapa yang terjadi lagi. Sesuatu yang sangat menarik tentang orang kita adalah mereka tidak memandang apaapa hal seperti ini. "Bareng dengan buaya, yah?" sapa seorang temanku. "Iyah," kataku. "Habitat mereka terganggu sehingga mereka ingin berjalanjalan di kota." "Like," katanya sambil memberikan tanda ibu jarinya kepadaku. "Thanks for the jempol," kataku.
265
96 KENTUT
kentut 1 angin atau gas berbau busuk yg keluar dari lubang pelepasan (anus); 2 mengeluarkan angin melalui lubang pelepasan; berkentut busuk 1 berbau tidak sedap (spt bau bangkai)
A
ku menjumpai kamus ini di loteng rumah kakekku. Berdebu, halamannya ada yang melekat, sangat rapuh dan sudah berumur. Kulitnya sudah tidak bisa dibaca lagi. Cetakan pertama pada tahun 2003 sudah mahu mencapai 300 tahun tiga abad. Memang dalam waktu 300 tahun sudah banyaklah yang berubah, aku meneliti secara acak beberapa entri yang masih bisa dibaca. Entri tentang kentut itu sangat mengherankan karena dalam kamus kontemporer kentut itu adalah angin atau gas berbau enak, wangi, harum semerbak yang keluar dari lubang dubur (kadangkala disertai dengan letusan bunyi). Karena kurang yakin aku pun mencari entri makna busuk; mungkin busuk itu maknanya bau yang enak atau wangi, tapi ternyata pula busuk itu tetap juga busuk. Pastinya zaman dahulu berkentut itu sesuatu yang menjijikkan dan memalukan, tidak seperti sekarang berkentut itu dilakukan secara terangterangan, apalagi kalau dilepaskan di dalam kubikel tertutup penghatar antarruang. Orang akan merasa senang jika kita berkentut. "Makasih untuk kentutnya." "Enak ya, bau kentutmu." "Itu kentut berbintang lima!"
266
Aku jatuh cinta pada pacarku karena kentut. Kami hanya berdua di dalam kubikel tertutup penghatarantar ruang; kami menuju ke tujuan yang sama. Aku tercium bau yang sangat enak, dan aku hampirhampir mabuk karenanya. Bukan aku yang berkentut. "Terima kasih untuk kentutnya," aku menatap wajahnya. "Inilah kentut yang paling nikmat, yang gak ada tandingannya, paling harum, paling indah, paling cantik yang pernah aku cium." Ia mengulurkan tangannya kepadaku seperti meminta sesuatu, dan memandangku dengan pandangan yang imut. "Apa?" kataku. "Gak usah lebihlebih gombalnya ya, Bang," kata gadis ini senyumsenyum. "Sepuluh ribu untuk kentutku tadi." Ha ha ha dan kami samasama tertawa. Selama tertawa itu pula aku terkentut. "Wah, tidak kalah harum juga kentut Abang," katanya. Kami saling jatuh cinta. Kentut kami kompatibel. Kentut serasi hidup harmonis. Sejak kapan kentut itu berubah dari busuk kepada harum semerbak? Inilah yang aku tanyakan kepada kakekku. Ia sendiri pun tidak tahu. Ia juga lahir dengan kentut yang harum. Tapi ia ingat kakeknya pula. "Kentutnya busuk seperti bau bangkai," katanya. "Ia pernah bercerita zaman ia mudamuda dan nakal, ia suka melepaskan kentut dengan sembunyisembunyi, kentut yang tidak ada bunyi, cuma bau yang busuk dan lethal! Ia akan menuduh orang lain berkentut sebelum ia dituduh. Hahaha." "Ha ha ha, seronok juga zaman dahulu itu ya, Kek?" "Eh," kata kakek, "sebenarnya aku bisa megeluarkan
267
kentut busuk. Ia adalah seni." Ia mengeluarkan kentut. "Waduh, harum banget kentut Kakek," kataku. Kemudian ia berkentut kali kedua saat aku masih menghiruphirup kentut pertamanya. PUUUWAAAH! Busuknya! Aku berlari ke kamar mandi dan muntah empat kali. Aku terdengar kakekku tertawa terbahak bahak. "Kek," kataku setelah aku mengeluarkan kentut wangiku. "Ajarkan aku berkentut busuk, Kek." "Ia adalah seni yang menghilang," kata kakek. "Tapi Kakek akan ajarkan kau berkentut yang benar." "Aku ingin sekali melepaskan kentut seperti kentut zaman dahulu itu di acaraacara resmi, pertemuan yang berjelajela panjang, dan sesekali untuk kesenangan," kataku kepada kakek. "Kita ini memang keturunan nakal, hahaha!" kata kakek dengan senyuman gilanya.
268
97 tHe FReAKS!
D
engan ledakan populasi dunia dalam gandaan yang tinggi, makanan dan air jadi tidak mencukupi. Makanan dan air sintetis pun dibuat dari bahanbahan kimia; diproduksi dengan murah dan dipopulerkan melalui promopromo dan iklan. Karena tidak ada pilihan, penduduk dunia terpaksa menerimanya. Makanan dan air ciptaan ini sangat efektif menghilangkan lapar dan dahaga, memberi energi yang dibutuhkan untuk satu hari, umumnya tidak ada efek samping pada kesehatan, kecuali beberapa kasus muntahmuntah yang kecil jumlahnya. Efek samping yang jelas adalah pada perubahan fisik pemakannya. Makanan sintetis ini mengubah struktur genetik dan DNA. Wajah manusia perlahanlahan berubah jadi wajah hewan yang sebagian besar sudah punah. Ada orang mukanya seperti anjing, kucing, kelinci, unta, buaya dan lainlain. Tidak ada yang merasa khawatir atau terganggu dengan perubahan ini. Semuanya dilihat sebagai sesuatu yang pantas saja. Ada yang merayakannya seperti ulang tahun ketika wajahnya berubah sepenuhya kepada wajah hewan yang sudah punah itu. Percakapan mereka pula mulai jadi aneh namun masih bisa dipahami. Hanya orangorang seperti kami menolak makan dan minum santapan sintetis ini. Kami mencoba bertahan dengan berkebun sendiri, di potpot kecil, memompa air dari perut bumi, tetapi jumlah kami semakin mengecil; hidup kami susah, tidak heran kalau kami juga akan punah akhirnya. Hanya kamilah yang masih berwajah manusia; dalam jumlah puluhan orang yang diperlakukan
269
dengan prejudis; diisolasi dan tidak diberi apaapa keistimewaan. Kami dianggap tidak normal. Jika kami menagih hak, semuanya akan ditolak. “tUMBUhKan EkoR DuLu,” kami diberitahu, “baRU KAMU puNYA HAK MemINTA ItuINI!” Satu hari kami dikumpulkan dengan paksa oleh orang orang yang berwajah kerbau dan sapi. Kami dibagikan kepada kelompok kecil tiga ke lima orang, diceraiberaikan, dan ditempatkan di kelompokkelompok sirkus untuk jadi bahan pameran dan tontonan. "tuANtuan, puANPuaN dan ANAKanaK, saKSIkan tHe FReAKS!" Anakanak ada yang takut dan kecut melihat kami. Ibuibu yang mengandung enggan memandang kami. Bapakbapak ada yang berludah jijik. “MeMpersEMBahKaN tHe FReAKS!"
270
98 SALJU PANAS 1974
D
ARI kaca pintu hotel di Bayswater, tampak salju mulai turun meski musim dingin belum bermula. Aku baru seminggu berada di Kota London yang cuacanya seperti pagi sepanjang hari. Langit ditutupi awan kelabu. Ini pertama kali aku berada di luar negeri dan aku saat itu memasuki usia 19 tahun; penerima beasiswa untuk meneruskan kuliah di negeri Inggeris ini. Aku segera ke balkon untuk melihat salju, nafasku keluar seperti uap. Aku melihat ke atas; berbeda hujan (yang mengguyur), salju turun melayanglayang seperti petal petal putih memenuhi ruang udara, bahkan beberapa keping sempat mendarat di telapak tangan yang kutadah. Setelah puas menyaksikan keindahan ini, dan karena dingin yang tidak tertahankan lagi, aku masuk semula dan duduk di kerusi panjang. Di situ sudah ada gadis kecil sekiraku berusia 15 atau 16 tahun. Kaki kanannya kudung dari paha. Tongkat ketiak di sisinya. Aku belum pernah menyapanya, meski sering duduk bersama di kerusi panjang itu. Ia tampak melankolik; manis dalam kesunyian. Karena euforia sehabis melihat salju turun buat pertama kali dalam hidupku, aku jadi berani mengajaknya bicara (pastinya dalam bahasa Inggeris). "Anda dari mana?" tanyaku. "Palestina," jawabnya pendek. "Kaki Anda kenapa?" "APA MAKSUDMU, KAKIKU KENAPA?" ia meledak marah. Aku baru teringat Palestina dilanda peperangan yang
271
ganas dan memakan banyak korban yang tidak memilih usia dan gender. Ia setentunya seorang dari korban peperangan yang tidak berkesudahan itu. Tahun sebelumnya juga telah tercetus Peperangan ArabIsrael 1973. Aku segera memohon maaf dan menganjurkan kepadanya supaya bersabar saja atas apa yang menimpanya. Ia menghentakkan tongkat ketiaknya. "APA TAUMU TENTANG SABAR?" hampirhampir ia menjerit. Ia memarahiku selama lima menit yang tidak putusputus dalam bahasa Arab yang bertabur sedikit katakata bahasa Inggeris. Aku tidak paham sepenuhnya, namun aku bisa menanggapi api kemarahannya. Kehilangan sebelah kakinya bukanlah pekara besar, tapi ia telah kehilangan bapa, mama, kakak, adik, kakek, saudara mara, kawankawan dan semua orang yang dikenalinya. Ia kehilangan tempat tinggal, negeri, bumi kelahirannya. Ia kehilangan zaman kanakkanak dan remajanya. "KAU SIAPA, ENAKENAK SAJA MENGAJARIKU UNTUK BERSABAR?" katanya dalam bahasa Inggeris yang jelas. "APA TAUMU TENTANG SABAR?" Ia meninggalkanku. Ia benar, aku tidak tahu apaapa tentang sabar. Aku termangumangu di kerusi panjang dilanda perasaan malu yang mendalam.
272
99 BUDAK DI DALAM FOTO
A
ku teringat saat berusia 10 tahun, membolakbalik halaman album foto keluarga turuntemurun, dari moyang ke datuk ke nenek ke bapa dan beberapa generasi ke atas dari mulanya kamera diproduksi. Sekarang aku yang memegang album tersebut. Di dalam album itu ada foto ramai setiap generasi. Menurut bapa, berpotret ramai itu tradisi turuntemurun yang biasanya dilakukan ketika anak bungsu lelaki berumur 15 tahun. Datuk adalah anak bungsu, begitu juga kakek dan bapa. Aku juga adalah anak bungsu lelaki. Di dalam gambar ramai keluarga bapa, aku tampak seorang budak yang seumur dengan bapa tetapi bukan ahli keluarga. Bapa cuma lima orang adikberadik. Di dalam gambar itu ada enam orang. Hal ini aku tanyakan kepada bapa. “Ia kawan baik bapa,” kata bapa. “Namanya Suhaimi tapi ia menghilangkan diri beberapa hari selepas ikut acara berpotret ramai itu.” Secara kebetulan juga saat aku berusia 14 lebih aku berkawan dengan seorang budak yang baru berpindah ke sekolahku, yang namanya juga Suhaimi. Dalam masa yang singkat kami menjadi akrab. Ia banyak membantuku dalam belajar, menerangkan apaapa yang aku kurang paham, juga memotivasiku apabila menghadapi masalahmasalah remaja. Sebenarnya hanya ia sahaja kawanku, kerana itu ia kupaksa ikut berpotret ramai keluarga ketika menyambut harijadi yang ke15 tahun. Seperti kawan bapa, kawanku Suhaimi juga menghilangkan diri seminggu selepas ikut berpotret ramai itu. Tentulah aku merasa sedih tetapi aku belajar
273
untuk melupakannya dengan mengingat dan mematuhi segala nasihatnasihat yang telah diberikannya. Meskipun Suhaimi sebaya denganku saat itu, namun ia sangat matang dari segi fikiran dan tingkahlaku. Aku teringat semua ini kerana anak lelakiku yang bungsu tidak lama lagi akan menyambut ulangtahun ke 15. Akhirakhir ini aku melihat perubahan yang sangat kentara pada anak lelakiku itu: ia lebih bersemangat belajar dan tidak pernah tinggal salat berjemaah denganku apabila berada di rumah; seperti ada seseorang telah menasihati dan memotivasinya, seperti aku semasa remaja dulu. Sehari sebelum ulangtahun ke15, anakku itu mebawa kawan rapatnya untuk tidur di rumah kami, kebetulan esoknya adalah hari libur. Aku memandang kaca spion untuk melihat kawan rapat anakku itu. Aku terkejut kerana itu adalah Suhaimi, tetapi tidak masuk akal juga kerana mustahil ia masih berumur 15 tahun. “Ini kawanku Pa,” kata anakku. “Namanya Suhaimi.” Di rumah selepas salat berjemaah Isya, aku berbicara dengan Suhaimi dan mengucapkan terima kasih kepadanya kerana perubahanperubahan positif pada anakku. Ia sangat santun dan matang fikirannya, sukar untukku mempercayai yang ia berumur 15 tahun. Malam itu sebelum tidur, aku membuka semula album lama turuntemurun, aku meneliti foto ramai keluarga datuk, nenek, bapa dan aku sendiri: dari gambar hitamputih yang kurang jelas sehinggalah ke gambar berwarna penuh keluarga bapa dan keluargaku, mesti ada dua orang budak lelaki yang sebaya, berumur 15 tahun. Malam itu juga aku menelefon bapa; harap haraplah bapa ada di rumah, kerana akhirakhir ini bapa selalu menghilangkan diri. Tentu bapa terkejut. Aku
274
bertanya apakah kawannya yang hilang semasa ia berumur 15 tahun dulu itu namanya Suhaimi? Bapa cuma tertawa. Ia menebak dengan tepat bahawa anakku akan menyambut ulangtahun ke15 esok, dan kami akan berpotret ramai melanjutkan tradisi keluarga turun temurun, ia mahu ikut juga. “Jemput aku esok pagi,” kata bapa. “Aku mau ketemu Suhaimi.” Esoknya apabila bapa melihat Suhaimi, ia terus menyalami dan mencium tangannya dan memeluknya. Ini terbalik. Bapa menyuruh kami semua menyalami dan mencium tangan Suhaimi. Anehhnya Suhaimi tidak pula menolak diperlakukan seperti itu, ia senyumsenyum sahaja. “Dia ini bukan siapasiapa kamu,” kata bapa. “Ini kakek datuk moyang kamu. Umurnya bukan 15 tahun tapi beratusratus tahun. Selepas ini ia akan menghilang dan muncul lagi apabila tiba saat berpotret ramai keluarga akan datang.” Kali ini Suhaimi tidak menunggu seminggu untuk menghilangkan diri. Esoknya, kata anakku, Suhaimi tidak hadir sekolah. Anakku itu juga sekalisekala menghilangkan diri tetapi ia terlebih dahulu memberitahu kami. “Ke mana saja kau pergi?” tanyaku. “Ikut Tok Suhaimi,” katanya. “Time travelling. Kakek pun kadangkadang ikut jua.” Pantaslah bapa kadangkadang menghilang.
275
100 NAMA
A
ku suka pada nama. Namaku Fatin 'Aliyah Nuqayah. Itu namaku yang tercatat di sertifikat kelahiran. Secara jujur aku lebih suka jika namaku itu kompak seperti Ina atau Lia. Tapi itulah kita, hakikatnya, dilahirkan dengan tidak memiliki sedikit pun pilihan untuk menentukan nama sendiri nama yang akan kita bawa hingga ke Akhirat. Jika temanteman sekolahku suka membaca novel novel cinta, aku pula suka membaca buku daftar nama. Di dalam tas sekolahku saja ada lima buah buku seperti itu. Bukubuku ini milik ayahku. Aku ambil dan bawa ke sana ke mari. Aku juga memiliki sebuah buku catatan nama. Jika ketemu namanama yang menarik aku akan menulisnya di dalam buku ini. Novelnovel cinta yang dibaca temanteman sekolahku biasanya ditulis oleh novelisnovelis yang memiliki nama yang cantik. Aku meminjam sekejap novelnovel ini untuk menyalin nama penulisnya di dalam bukuku. "Jangan beli yang sama judul," kata kawanku Hanna Ikrimah. "Beli judul lain nanti kitani bisa bertukar novel." Aku memandang wajah kawanku ini. Aku suka menyebut nama lengkapnya yang cantik. "Hanna Ikrimah," kataku, "aku nda berminat membaca novel. Aku hanya suka nama penulisnya." "Fatin 'Aliyah Nuqayah," kata kawanku Hanna Ikrimah. "Buku apa yang kausuka baca?" Aku mengeluarkan sebuah buku dari tas sekolahku dan dengan bangga mengunjukkannya kepadanya. Ia mengambil dan melihat buku itu. Novel yang dibacanya
276
lima kali lebih tebal. "NamaNama Muslim?" kata Hanna Ikrimah. "Aku suka nama, Hanna Ikrimah," kataku. Aku mengeluarkan buku daftar namanama yang lain. "Banyak nama yang cantik di dalam bukubuku ini." "Fatin 'Aliyah Nuqayah," kata kawanku Hanna Ikrimah. "Adaada saja kau ini. Orang baca novel kaubaca buku nama." Ketika berada di tahun tiga sekolah dasar aku sudah mulai mencatat semua nama kawankawanku di dalam sebuah buku khusus. Nama guruguru, pegawai, buruh, tukang cuci, penjual di kantin, siapa saja aku tanya namanya dan masukkan di dalam buku itu. Jika ada guru baru aku dengan berani akan bertanya namanya. "Assalamualaikum Pak Guru. Nama Pak Guru siapa?" "Farid bin Burut." Aku menulis namanya di dalam bukuku, mengucapkan terima kasih, lalu pergi. Pak Guru Farid inilah yang mulamula sekali memberi perhatian tentang apa yang kubuat ini. Aku menjadi rujukannya karena aku hafal semua nama murid di sekolah dasar itu, nama guru gurunya, nama petugaskeraninya, Om tukang kebun dan Tante di kantin, dan aku baru saja di kelas tiga. Ini terus aku lakukan sampai sekarang cuma tidak lagi terangterangan, karena aku sudah remaja dan ada perasaan malu. Aku tidak berani lagi mendekati seseorang hanya untuk bertanya namanya, lebihlebih lagi pada pria. Nanti mereka salah paham. Takut mereka sangka aku sudah jatuh cinta, ini bisa menyebabkan mereka kurang tidur memikirkan dan terbayang bayangkan wajahku. Aku punya seorang adik lelaki yang tidak tidur karena seorang siswi menanyakan namanya.
277
Aku tidak ingin ini terjadi. Sekarang aku hanya mencatat nama yang kudapat secara pergaulan biasa. Rezekiku pula ada pada nama. Jika ada tanteku atau kenalan mereka melahirkan anak, mereka biasanya menghubungiku untuk minta rekomendasikan nama. Sejak aku mula berada di SMP aku telah memberi nama kepada lebih seratus orang anak. Aku ada buku catatan khusus untuk itu. Entah mungkin namanama yang kuberikan itu sangat pantas dengan bayibayi yang dilahirkan, khidmatku mulai dicaricari. Aku tidak ada sistem tertentu cukup berdasarkan 'rasa' di dalam memberi nama. Tantetante ini sangat bermurah hati pula ketika memberiku kado yang tidak kupinta ada yang menyerahkan dua ratus ribu. Semuanya aku simpan di dalam rekening; sudah mencapai lima juta lebih. Uang yang banyak bagi anak sekolah sepertiku. Pacar pertamaku putus karena uang tabungan dalam rekeningku. Ia di SMA dan aku SMP. Ia meminta uang dariku ketika ia tahu bahwa aku ada uang tabungan. Ia merayurayu, ia merajukrajuk ketika aku tidak mau. Akhirnya ia mengancam akan memutuskan hubungan. "Kalau kau nda mau kasih aku uang, aku putus sama kau," katanya dengan serius. "Iya, kita putus ajalah," kataku, malas mau peduli, lagi pun emak yang pegang buku rekening. Pacar yang kedua putus karena terlalu bingung. Kautau namaku Fatin 'Aliyah Nuqayah, tetapi aku berpendapat kita tidak harus berpegang pada satu nama saja, apalagi nama itu bukan kita sendiri yang memberinya. Dengannya aku suka menggantitukar namaku. "Fatin," ia menelefonku. "Ini Haifa Aneesa bicara," kataku.
278
"Ini kan nomor hp si Fatin?" "Bukan, ini telepon Haifa Aneesa." "Maaf," katanya. "Aku salah nomor kali." Kemudian ia menelepon lagi. "Halo," jawabku. "Hana Nabiha bercakap." "Bukan si Fatin?" tanyanya. "Apa ini bukan nomor si Fatin?" "Bukan," kataku. "Ini nomor Hana Nabiha." Hal seperti ini sering kulakukan. Ia bersikeras bahwa nomor yang ditelefonnya itu milik Fatin 'Aliyah Nuqayah. Aku dapat membayangkan ia seperti orang gila di ujung sana. Setia juga ia itu sebenarnya, begitu banyak gadis bernama cantikcantik, si Fatin juga dimahunya. Apa boleh buat, pada harihari tersebut aku memutuskan bahwa namaku bukan Fatin 'Aliyah Nuqayah. Ia memutuskan hubungan karena aku disangkanya sinting. Pacar ketiga sudah tahu yang aku sesuka hati menggantitukar namaku. Ia ini baik hati tapi sangat penyemburu tidak boleh disebut nama pria lain di depannya; hanya namanya saja, Saad Safwan. Masalahnya sekarang ini adalah aku telah memutuskan tidak ingin menggunakan namanya Saad Safwan itu. Aku ingin menggantitukar namanya kepada nama pria yang lain. Aku pun meneleponnya. "Halo," kataku. "Bisa bicara sama Rasyad Ridhwan ga?" "Kaukah itu Fatin?" katanya. "Iya, aku mau bicara sama Rasyad Ridhwan." "Apa kau sudah punya boyfriend baru?" "Apa ini bukan telepon Rasyad Ridhwan?" "Bukan," ujarnya. "Ini aku, Safwan!" "Sori," katakku. "Aku salah nomor kali." Aku meneleponnya kembali.
279
"Bisa bicara sama Rasyad Ridhwan?" kataku dengan suara merdu, lembut dan manja. "INI BUKAN TELEPON RASAD RIDWAN! INI TELEPON SAFWAN!" Telepon itu seperti dibanting. Aku mendial kembali nomor itu. Barangkali aku harus ubah namanya lagi kepada yang lain pula. Ada seratus lebih nama pria yang bagusbagus di dalam kepalaku.
280
101 JAMUR
K
etika berjogging di pinggir kota aku terlihat banyak jamur tumbuh di tepi jalan. Paling tidak ada lebih dari tiga spesies. Tibatiba timbul keinginanku untuk memetiknya. Ketika aku mendapatkan sebuah kantong plastik yang besar, aku pun mulai memetik jamurjamur ini. Aku memetiknya satusatu dan terbongkokbongkok. Setelah kantong plastikku penuh aku pun berhenti dan memandang kelilingku. Ternyata sudah banyak orang lain yang ikutikutan memetik jamur puluhan orang atau mungkin mencapai seratus orang. Aku pulang saja ke rumah. Tiba di rumah, jamurjamur ini kubuang di area belakang. Tidak ada keinginanku hendak memakan jamur. Aku sekadar ingin memetiknya saja karena jamur jamur itu tampak seperti sampahsampah putih di tepi jalan, bahkan aku memang benci makan jamur. Malam itu aku nonton tv, dan diberitakan bahwa lebih seratus orang masuk rumah sakit karena keracunan makan jamur.
281
Â
Â
Â
Â
N
izam AlKahfi Pkb adalah nama yang digunakan Hj Morshidi bin Hj Marsal saat menulis cermin (cerpen mini). Hj Morshidi bin Hj Marsal lahir di Brunei pada tanggal 22 Juni 1955. Ia tidak pintar menulis tapi senang berbagi ceritacerita yang tidak masuk akal. Ia mula menulis cerpen saat lagi menganggur, pada tahun 1980, di koran, majalah dan radio. Pada tahun 2008 sudah tidak lagi menulis cerpen, tapi lebih fokus menulis cermin di medsos yang sifatnya kompak (1000 jumlah kata maksimum). Selain nama Nizam AlKahfi Pkb, Hj Morshidi bin Hj Marsal juga menggunakan nama Mussidi dan Putera Katak Brunei. Katanya ia punya personaliti ganda. Sekarang ia sudah pensiunan, tinggal bersama istri dan empat orang anak dan seekor kucing betina yang bernama Ms Normah yang hobinya suka pamer diri. Bukubukunya yang lain kumpulan cerpen Kecoh, novelet dan kumpulan cerpen A4, novelet Tum, kumpulan cerpen Tai, kumpulan cermin 365 Fiksi Mini Putera Katak Brunei, dan kumpulan cermin 16:60.