




Assalamu’alaikum wr. wb
Rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Swt. Berkat limpahan karuniaNya, dan tak luput dari segala upaya yang kami kerahkan. Akhirnya, kami dapat menghadapi aral yang menghadang, sehingga dengan penuh rasa hormat kami persembahkan Majalah Edukasi edisi ke-59 kepada para pembaca.
Dalam edisi kali ini, kami menghadirkan suatu fenomena yang tengah melanda para sarjana pendidikan terutama bagi para guru honorer, yakni sebuah dilema tentang arah profesi mereka sebagai guru. Keadaan status guru honorer yang belum mengalami kejelasan, serta jalan yang rumit untuk mendapatkan status sebagai pegawai negeri, menimbulkan masalah tersendiri pada sarjana pendidikan.
Fenomena ini berpotensi mempengaruhi kekurangan guru dalam skala nasional.
Padahal, kebutuhan guru di Indonesia sangat besar. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2024, Indonesia kekurangan jumlah guru sebesar 1,31 juta, sedangkan angka pensiunan guru berada pada jumlah 69 ribu di tahun yang sama.
Selain itu, dilema ini muncul disebabkan karena regulasi yang rumit dalam pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Diterbitkannya Undang Undang nomor 20 tahun 2023 yang

mengatur tentang penyelesain PPPK tahun 2024, menjadikan beban tambahan bagi guru honorer.
Secara lebih lanjut, kami uraikan dalam rubrik laporan utama yang akan menyajikan tentang realita guru honorer memperoleh jalan menuju ASN. Terdapat beberapa guru honorer yang kami himpun datanya dari SMA dan SMK di Semarang, terdampak karena regulasi dan ketidakjelasan status mereka.
Pada rubrik artikel, kami menyajikan bagaimana distribusi dan pemerataan pendidikan dari beberapa daerah di Indonesia. Di samping itu, terdapat peluang untuk sarjana pendidikan menjadi ASN.
Demikianlah majalah edisi ke-59 kami suguhkan kepada para pembaca. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan majalah ini. Kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk menjadikan lebih baik lagi ke depannya. Besar harapan kami, majalah ini dapat menjadi salah satu referensi bacaan mengenai pemahaman akan profesi guru, serta dapat membuka wawasan terutama bagi sarjana pendidikan yang masih mengalami dilema. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb
IZIN TERBIT SK Dekan No.IN/D-3/HK.005/1021/1992 PELINDUNG Dekan FITK UIN Walisongo Semarang PEMBIMBING Dr. Abdul Wahib M.Ag., Prof. Dr. Fatah Syukur, M.Ag., Dr. Syamsul Ma’arif, M.Ag. Ubaidillah Achmad M.Ag., M. Rikza Chamami, M.SI. PENANGGUNG JAWAB PEMIMPIN UMUM Nila Umi Salamah PEMIMPIN REDAKSI Fajar Fahrozi Kurniawan SEKRETARIS REDAKSI Sekar Suryaningtiyas TATA LETAK Nila Umi Salamah ILUSTRASI Teguh Arif Wibowo DESAIN COVER M. Fathun Ni’am REDAKTUR PELAKSANA Shihatud Diniyah An Nabilah, Nur Khasanah, Agustin Fajariah, Kharisma Salsabila Nuraini, Muhammad Fathun Ni’am, Ainurrifda Sakinatul Latifah, Lailatul Maghfiroh, M. Muhajirin, Nurul Laely Mahmudah, Rima Nihayatul Aida, Sabrina Akmalunnajwa, Firda Rahmatun Nuzula, Faizul Ma’ali, Muqtafa Deka Yunensa, Rintan Febriyanti, Natasha Shafa Salsabila, Hilyatul Karimah Azzahra, Muhammad Rangga Noor Sabila, Mahreshaibati Bilqis Ikramina, Farhatun Zulfiyah, Zidni Rosyidah, Dwi Susanti
EDISI LVIX/TH.XXXI/FEBRUARI/2025
EDUKASI 3
ALAMAT REDAKSI Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Lantai 2 Kampus II FITK UIN Walisongo Jl. Prof. Hamka KM. 01 Ngaliyan Semarang 50158 | TELEPON 024 7601296 | SUREL eduonline9@gmail.com | WEBSITE www.lpmedukasi.com | INSTAGRAM @lpm_edukasi | FACEBOOK LPM Edukasi | TWITTER @LPM_edukasi | TIKTOK LPM EDUKASI
Kepada Yth, Dosen FITK
Adanya penugasan yang mengharuskan mahasiswa untuk bisa menerbitkan artikel di jurnal sinta saat ini tengah terjadi perbincangan hangat di dunia perkuliahan kampus. Dimana ketika mahasiswa mampu menerbitkan artikel di jurnal sinta 2/3 maka mahasiswa akan bisa di nyatakan lulus tanpa skripsi.
Hal ini hampir terjadi di semua mata kuliah saat ini, dimana tugas-tugas saat ini lebih banyak terkait dengan artikel tersebut, tentang bagaimana mahasiswa harus mampu menyesuaikan untuk mulai menulis artikel yang baik agar nantinya bisa terbit di jurnal sinta.
Awal adanya kabar tersebut menjadi sebuah hal yang bagus, karena dengan itu mampu menjadikan mahasiswa untuk lebih semangat dan memiliki motivasi untuk berlatih.
Namun, menurut saya terbit di jurnal bukan lah hal yang mudah. Karena menulis karya ilmiah biasa seperti makalah saja masih ada beberapa mahasiswa yang masih belum bisa atau dengan kata lain masih ada tatanan yang kurang rapi. Sehingga masih perlunya bimbingan lagi dari para dosen terkait dengan penulisan ilmiah.
Oleh: LL, Mahasiswa Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo
Kepada Yth, Dosen FITK
Adanya penugasan dengan membuat artikel yang kemudian mengharuskan untuk mampu diterbitkan dijurnal sinta, menurut saya awalnya mampu menjadi kabar yang bagus untuk beberapa mahasiswa yang suka menulis, dan bisa menjadikan mahasiswa lain jadi semangat karena memiliki motivasi untuk bisa berlatih menulis.
Namun, terbit jurnal tidak semudah menulis karya ilmiah biasa seperti makalah, adanya kapasitas dan kemampuan dari setiap individu mahasiswa menjadi salah satu hal yang perlu dicarikan sebuah Solusi. Karena cara berfikir dan cara seseorang mahasiswa setiap individunya tentunya berbeda dan juga memiliki kapasitas kemampuan yang berbeda. Bagi mahasiswa yang suka menulis dan rajin membaca mungkin ini bisa menjadi peluang bagi mereka untuk bisa lulus dengan cepat melalui artikel yang terbit di jurnal, namun bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan hal ini tentunya akan menjadi suatu hal yang sulit dan perlu adan-
ya perjuangan ekstra agar mampu mengikuti teman-temannya. Seharusnya kampus yang memiliki visi sebagai universitas riset terdepan ini tentu sejalan, mampu memberikan kiat² tambahan mengenai cara bisa tembus Scopus, karena sebagai mahasiswa siapa yang tidak ingin lulus tanpa skripsi, tentu saya juga ingin, namun juga sudah pernah mencoba ternyata untuk tembus jurnal sinta itu tidak mudah, tentu banyak sekali halang rintang, seperti biaya, waktu dan lainya. Selain itu tidak semua mahasiswa memiliki komunikasi yang baik terhadap dosen² jika sewaktu-waktu ingin menjadikan pembimbing untuk terbit jurnal, dan tidak semua mahasiswa juga memiliki budget untuk hal tersebut..
Oleh: ZH, Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Walisongo
Kepada Mahasiswa
Penulisan artikel itu salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan akademik disamping itu mampu menjadikan peningkatkan kemampuan dalam hal menulis karya ilmiah, tidak heran sekarang menulis artikel yang publish SINTA itu diharuskan oleh dosen agar mahasiswa dapat belajar lebih banyak selain materi yang ada di perkuliahan. Selain itu, untuk menambah wawasan atau pengetahuan yang luas bagi mahasiswa menjadi salah satu alasan dosen menganjurkan atau merekomendasikan menulis artikel penelitian, sehingga menambah grade mahasiswa yang diberikan oleh dosen untuk memenuhi tugas mata kuliah dalam perkuliahan.


Menurut saya mengerjakan tugas dalam menulis artikel baik dari perintah dosen maupun dari minat atau kemauan diri sendiri itu merupakan bentuk jalan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi diri mahasiswa itu sendiri, karena hal itu menyebabkan mahasiswa dapat melakukan kegiatan ilmiah seperti penelitian untuk menulis artikel. Walaupun artikel yang akan dipublish perlu menempuh proses yang tidaklah mudah, dan ada standar maupun ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi, jika seorang individu mahasiswa mampu menjalani dan mengerjakan dengan tekun maka akan berhasil dan nantinya juga akan mendapatkan apresisasi atau reward dari kampus bagi mahasiswa yang berhasil dalam mempublish artikel dan poin plusnya mahasiswa akan mampu lulus tanpa skripsi
Dengan lulus menggunakan artikel yang di publish dapat memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa, tentu penulisan tersebut memiliki kesempatan dan peluang untuk membuka jalan lebih dekat baik dalam peningkatan prestasi mahasiswa maupun sebagai penunjang kelulusan yang intangible dalam bentuk karya tulis ilmiah artikel yang sudah terindex SINTA dan sebagai penyuplai pengetahuan hasil penelitian ilmiah terhadap penemuan serta pemecahan masalah agar dapat diakses publik untuk memberikan manfaat ke orang lain atau pembaca.
Oleh: AN, Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Walisongo
Redaksi menerima kiriman untuk rubrik surat pembaca berupa pertanyaan, keluhan, dan gagasan seputar kampus UIN Walisongo, sekitar Semarang, atau nasional. Surat yang dikirim dilengkapi dengan identitas diri ke surel: eduonline9@ gmail.com, atau bisa datang langsung ke sekertariat LPM EDUKASI di PKM Kampus II UIN Walisongo Semarang.
DARI KAMI- 03
SURAT PEMBACA Dilema Penugasan Perkuliahan saat ini, Pandangan Dan Tanggapan Mahasiswa Terkait Dilema Penugasan Artikel? & Mahasiswa Yang Tertarik Untuk Lulus Lebih Cepat Dengan Artikel?- 04 DAFTAR ISI- 06
EDUSKET- 07 FOKUS Berikan Kejelasan pada Guru Honorer– 08 KOLOM TEMA Guruphobia- 10
MUKADIMAH- 12 LAPORAN UTAMA Jalan
Berliku Sarjana Pendidikan Meraih Status Pegawai Negeri- 14
WAWANCARA Penghapusan Guru Honorer
Bukan Solusi- 20 INFOGRAFIS Fresh Graduate
Prodi Pendidikan; Berjuang 4 Tahun namun Tidak Diperkenankan Mengikuti CPNS- 22 ARTIKEL UTAMA Dilema Guru Honorer dan Fresh Graduate dalam Kebijakan PPPK 2024- 24 SEMARANGAN
Pertunjukan Kolosal Legenda Goa Kreo yang Jadi Pelurus Miskonsepsi Budaya- 26 KAJIAN ISLAM Mengulik Akar Permasalahan Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Qira’ah Mubadalah- 30
LAPORAN KAMPUS Ujian Komprehensif di Sebagian Prodi FITK UIN Walisongo Resmi Ditiadakan - 33
ARTIKEL Nilai KKM Semakin Tinggi, Kualitas Pendidikan Semakin Rendah- 38 KOLOM Frugal Living- 42
LENSA Tentang Gamma, Adilkah?- 44 SUARA
MAHASISWA Metode Presentasi: Sistem Pembelajaran yang “Basi”?- 46 BUDAYA SEDEKAH
LAUT Simbol Rasa Syukur Masyarakat Muslim
Pesisir Pantura- 48 UNDANGAN MENULIS- 52
PUJANGGA Agam Wispi, yang Melawan dari Balik
Sadjak- 53
CERPEN Si kembar dan Persimpangan Jalan- 56 Harap yang Penuh Haru- 60
DIORAMA Pengaruh Teman Sebaya dan Dinamika Sosial, Pluralisme dan Dominasi Aliran Tertentu dalam Pendidikan Agama di UIN, Kritisisme terhadap Kelompok Luar: Kecenderungan individu untuk lebih kritis terhadap pihak di luar kelompoknya, Urgensi Karya Ilmiah sebagai Tugas Akhir, Kurangnya Kesadaran Mahasiswa Terhadap Kebersihan
Lingkungan Kampus Aksesibilitas Pendidikan Tinggi di Indonesia- 64
RESENSI BUKU Kutukan Kecantikan- 70 RE-
SENSI FILM Gadis Kretek: Menyorot Perempuan dalam Masyarakat Patriarki- 72
NUSANTARA Memutus Perundungan di Sekolah Yang Tak Kunjung Usai Sejak Dini- 74
PUISI Yang Hidup Akan Mati Yang Datang Akan Pergi- 76 SILUET
Bocornya Payung Hukum yang Dimiliki Saksi Ahli77 BUNG EDU- 79


Pada 2023 lalu, para sarjana pendidikan terutama bagi yang baru memulai perjalanan kariernya sebagai guru, sempat dikejutkan dengan adanya regulasi pemerintah yang mengatur soal pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara).
Lebih tepatnya terletak pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di dalamnya disebutkan bahwa pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN selain pegawai ASN.
Dengan disahkannya regulasi untuk menyelesaikan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam waktu dekat, para guru non-ASN atau sebelumnya dikenal sebagai guru honorer, mendapatkan nasib beresiko kehilangan status mereka sebagai pegawai di instansi pemerintah.
Sebelumnya, guru honorer yang akan menjadi pegawai negeri, harus mendaftar melalui tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun, sejak diber-
lakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seleksi untuk guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara bertahap mulai dialihkan dengan skema PPPK, atau biasa dikenal dengan sebutan P3K. Hal ini dimaksudkan untuk mengutamakan banyaknya guru honorer yang masih belum menjadi pegawai negeri, terutama bagi yang sudah lama mengabdi.
Berbeda dengan PNS yang memiliki masa jabatan sampai usia pensiun. Ketentuan masa jabatan PPPK diatur dalam Pasal 37 PP Nomor 49 Tahun 2018, bahwa batas kontrak bagi PPPK paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja. Sedangkan dalam Pasal 42 PP Nomor 28 Tahun 2021, batas kontrak PPPK paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Instansi Daerah. Sedangkan bagi pelamar yang tidak lolos seleksi, diatur dalam keputusan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 347, 348, dan 349 Tahun 2024. Disebutkan bahwa pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Namun, tidak berhasil mendapatkan formasi yang tersedia, mereka masih memiliki peluang untuk men-
jadi PPPK paruh waktu. Dalam regulasi terbaru yang dikeluarkan MenPAN-RB Nomor 15 tahun 2025, kriteria pelamar tambahan PPPK tahap dua diperuntukkan untuk tenaga honorer yang terdaftar dalam database BKN (Badan Kepegawaian Negara). Sedangkan menurut keterangan dari Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penataan non-ASN, bahwa database BKN yang akan diselesaikan dihitung per tanggal 31 Desember 2022, sisanya menunggu kebijakan selanjutnya. Status guru honorer yang tidak termasuk dalam kriteria pengangkatan PPPK masih belum memperoleh kejelasan. Upaya dari pemerintah sudah tepat dalam mempercepat penuntasan status guru honorer. Akan tetapi, regulasi tersebut membuat guru honorer berpotensi dirumahkan, serta akan memicu krisis ekonomi dan sosial di kalangan mereka dalam waktu dekat.
Ketidakjelasan status guru honorer tidak hanya menjadi isu penting yang patut dibahas secara tuntas, tetapi juga perlu dicari solusi yang tepat. Pemerintah sebaiknya memberikan alternatif bagi guru honorer yang terdampak karena kebijakan tersebut, dengan lebih meminimalisasi dampak secara holistik bagi mereka.

LAPORAN UTAMA:
Menjadi pegawai negeri adalah tujuan utama bagi banyak guru honorer, tetapi regulasi pemerintah yang terus berubah membuat jalannya semakin sulit. Dalam laporan ini, Majalah Edukasi menyoroti kisah beberapa guru honorer yang menghadapi tantangan besar dalam memperoleh status ASN.
T, seorang guru agama berusia 51 tahun di Semarang, telah mengabdi selama puluhan tahun tetapi belum berhasil menjadi pegawai negeri karena tidak adanya formasi untuk guru agama di daerahnya. Ia terus berusaha melalui jalur PPPK, meski masih menghadapi ketidakpastian. Hal serupa dialami Ivan Aziz Abdullah, guru BK honorer berusia 28 tahun, yang terpaksa mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Regulasi baru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 membuka peluang bagi guru honorer untuk diangkat sebagai ASN melalui PPPK. Namun, aturan ini juga menimbulkan masalah, seperti penguncian database BKN yang membuat sebagian guru honorer kehilangan kesempatan. Beberapa guru yang terdampak bahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi gugatan mereka ditolak.
Dampak dari kebijakan ini sudah terasa di berbagai daerah, dengan banyak guru honorer yang diberhentikan secara massal. Di sisi lain, forum guru honorer terus mendesak pemerintah agar memprioritaskan mereka yang telah lama mengabdi. Bagi guru-guru muda, ketidakpastian ini membuat mereka mempertimbangkan alternatif lain di luar profesi guru.
Selain laporan utama ini, Majalah Edukasi juga menghadirkan berbagai tulisan lain terkait dunia pendidikan. Selamat membaca!
“Kenapa kamu nggak mau jadi guru?”Pertanyaan itu seringkali muncul setiap saya bercerita tentang ketakutan-ketakutan yang akan saya hadapi ketika menjadi sarjana pendidikan. Bagi sebagian besar orang, profesi guru adalah panggilan mulia, pilar peradaban yang membentuk generasi masa depan. Namun, bagi saya dan mungkin banyak lulusan lainnya, menjadi guru bukan sekadar soal idealisme, melainkan keputusan yang penuh dengan realita pahit.
Sebagai mahasiswa pendidikan yang akan segera lulus, saya sering merenung, apa artinya menjadi guru di negara ini? Apakah itu hanya cita-cita masa kecil yang perlahan terkikis oleh realita? Atau haruskah saya berpura-pura optimis? Padahal saya tahu betapa beratnya jalan yang akan saya lalui. Saya tak ingin menjadi orang yang hanya menyerah pada keadaan, tapi bagaimana bisa melangkah jika setiap jalannya penuh dengan hal-hal yang
menakutkan?
Salah satu ketakutan terbesar saya adalah soal kesejahteraan. Bagaimana tidak? Guru, terutama yang baru lulus atau fresh graduate, sering kali harus menghadapi kenyataan pahit: Gaji minim, beban kerja yang besar, dan proses sertifikasi yang rumit.
Menurut data dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa ada 1,63 juta guru yang belum tersertifikasi dan 1,35 juta guru yang tersertifikasi pada 2022. Ini menunjukkan bahwa 54,6% guru belum tersertifikasi di Indonesia. Per April 2023, jumlah guru tersertifikasi meningkat menjadi 1,43 juta dan guru yang belum sertifikasi menjadi 1,55 juta. Dengan demikian, persentase guru yang belum tersertifikasi turun menjadi 51,9%. Fakta bahwa lebih dari separuh guru di Indonesia belum tersertifikasi menunjukkan berapa panjangnya jalan yang harus ditempuh untuk mencapai standar profesional.
Masalah sertifikasi ini terutama dirasakan oleh guru-guru di daerah terpencil. Prosedurnya berbelit-belit dan sering kali apa yang diperjuangkan tidak
sebanding dengan apa yang didapatkan.
Cerita dari Kating (Kakak tingkat) saya semakin memperkuat ketakutan-ketakutan ini. Banyak dari mereka yang akhirnya mengajar di sekolah swasta dengan gaji yang bahkan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok. Beberapa yang lebih beruntung bisa menjadi guru honorer di sekolah negeri, tetapi tetap tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Yang lain? Mereka menyerah dan beralih ke profesi lain di luar pendidikan.
Di dunia pendidikan hari ini, guru dituntut lebih dari sekadar kemampuan mengajar, ia juga sekaligus harus bisa menguasai teknologi, memahami manajemen kelas, dan terus beradaptasi dengan perubahan kurikulum. Semua itu memerlukan pelatihan dan dukungan, yang sayangnya masih sangat minim. Apalagi kenyataannya ia tidak hanya menjalani tugas sebagai guru, ada beban non-guru yang ditanggungkan kepadanya. Dengan gaji yang sangat minim, guru dipaksa untuk multitalenta di segala bidang.
Dengan keadaan yang ironis seperti itu, menyuarakan kesejahteraan guru seakan menjadi hal

yang tabu atau aib atau bahkan dosa. Sebab lembaga Pendidikan dan pemerintah terkadang berpegang pada kata-kata manis: “guru adalah sebuah pengabdian” atau “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Hal tersebut mengesankan guru dianggap sebagai sosok yang seharusnya bekerja tanpa banyak menuntut dan sangat lumrah untuk digaji ala kadarnya.
Namun, apakah pandangan ini adil? Bukankah yang menganggap profesi guru sebagai pengabdian harusnya adalah guru itu sendiri, bukan pemerintah atau lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan profesional?
Jika lembaga pendidikan mengharapkan guru bekerja maksimal, maka sudah seharusnya mereka diberi gaji yang layak, bukan hanya sekadar kata-kata manis tentang pengabdian ataupun pahlawan tanpa tanda
Sebagai mahasiswa, saya merasa ini seperti lingkaran yang tak berujung. Idealisme saya untuk menjadi guru sering kali berbenturan dengan realita sosial yang ada. Di satu sisi, saya ingin berkontribusi pada pendidikan bangsa. Namun di sisi lain, saya juga harus realistis, bagaimana saya bisa bertahan jika kesejahteraan guru masih terabaikan?
Jika ditanya, “Apa sebenarnya alasanmu tidak ingin jadi guru?” Jawaban saya sederhana, saya takut; takut tidak mampu memenuhi harapan; takut terjebak dalam sistem yang tidak mendukung; takut kehilangan semangat yang selama ini saya miliki untuk mendidik generasi muda. Meskipun ada satu hal yang selalu saya yakini, pendidikan adalah kunci masa depan bangsa. Jika guru tidak dihargai,
bagaimana mungkin pendidikan bisa menjadi jalan untuk kemajuan? Karena itu, harapan saya sederhana, pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru. Dengan cara sederhana: proses sertifikasi harus disederhanakan, gaji harus ditingkatkan, dan pelatihan harus lebih merata.
Pada akhirnya, saya tahu menjadi guru bukanlah pilihan yang mudah. Namun, jika suatu saat saya memilih untuk tetap melangkah di jalur ini, saya ingin melakukannya bukan karena terpaksa, melainkan karena panggilan hati. Bagaimanapun juga, pendidikan adalah cara saya berkontribusi. Meskipun sulit, saya berharap suatu hari nanti dunia pendidikan akan benar-benar menjadi tempat yang layak untuk para pendidik.
Dalam dunia pendidikan, seorang sarjana tidak hanya diharapkan menjadi pengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam menanamkan nilainilai keilmuan. Sedangkan dalam realitasnya, banyak lulusan sarjana pendidikan yang terjebak dalam dilema besar antara idealisme dan kenyataan profesi. Terutama ketika dunia kerja yang mempersempit kesempatan untuk menjadi seorang guru profesional, sebab tuntutan yang dihadapi menjadi semakin berat.
Lebih jauh, sistem pendidikan di Indonesia turut berperan dalam menciptakan dilema ini. Lulusan sarjana pendidikan sering kali dihadapkan pada kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, dan terpaksa mencari jalur lain yang jauh dari dunia pendidikan. Ironisnya, mereka yang seharusnya menjadi pilar utama dalam mencerdaskan bangsa malah terpinggirkan oleh birokrasi dan tuntutan ekonomi.
Adanya regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan profesi guru menjadi pegawai negeri, turut hadir menghantui guru di Indonesia. Undang Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan akar dari permasalahan ini. Desakan untuk menuntaskan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada tahun 2024, menambah beban baru bagi para guru yang belum menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara). Bagaimana tidak, regulasi untuk segera menyelesaikan formasi pengangkatan PPPK, membuat fokus
guru jadi teralihkan. Tugas utama guru yang tertuang dalam Pasal 20 tahun 2005, yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, harus terbagi dengan tugas mempersiapkan seleksi PPPK dalam waktu dekat.
Esensi guru yang tidak berjalan sesuai dengan realita, membuat guru nonASN atau dikenal sebagai guru honorer akan bernasib buruk, serta berada dalam posisi tergantung dengan regulasi yang ada. Dengan melihat dari banyaknya guru honorer yang masih belum diangkat jadi ASN, keadaan seperti ini akan menciptakan dilema yang berakibat pada krisis dalam dunia pendidikan. Salah satu hal yang paling krusial ialah kekurangan guru di Indonesia yang cukup besar. Di satu sisi, guru yang berada dalam usia pensiunan, semakin bertambah setiap tahunnya. Padahal, guru memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan data dari Kemendikbudristek (Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), pada 2024, Indonesia mengalami kekurangan guru sebanyak 1.312.759 orang. Sedangkan, guru yang akan memasuki usia pensiun sebanyak 69.762 orang.
Kekurangan guru di Indonesia memiliki angka yang cukup besar dalam skala nasional. Hal tersebut menjadi sebab pemerintah melakukan gebrakan besar, yaitu dengan mengeluarkan regulasi untuk segera menuntaskan seleksi PPPK. Namun, perlu dipertanyakan kembali apakah hal tersebut merupakan solusi yang tepat. Atau justru sebaliknya akan menyebabkan efek domino bagi guru yang tidak lolos, terutama bagi fresh graduate yang berniat mendaftar menjadi guru.
Sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan regulasi yang akan dikeluarkan. Solusi yang ditawarkan pemerintah untuk menuntaskan segera seleksi PPPK tidak selebihnya tepat, harus ada alternatif lain bagi mereka yang terdampak karena adanya regulasi ini.

Oleh: Fajar Fahrozi Kurniawan, Kru Edukasi angkatan 2022
Status pegawai negeri menjadi tujuan utama bagi tenaga honorer terutama bagi sarjana pendidikan yang berprofesi sebagai guru.
Namun, tahapan untuk mencapai pegawai negeri tidaklah mudah. Apalagi regulasi pemerintah yang mengatur tentang penetapan guru sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin rumit
Derap langkah siswa di pelataran SMA N 14 Semarang terdengar riuh, diiringi pekikan guru yang memperingatkan untuk berhati-hati dalam berjalan. Hari itu (18/10/2024), bertepatan dengan Jumat Sehat, kegiatan rutin yang dilaksanakan sekolah untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat, salah satunya jalan sehat di sekitar lingkungan sekolah. Umumnya, semua warga sekolah ikut andil dalam kegiatan ini, baik siswa, guru, maupun tenaga pendidik. Na-
mun, ada beberapa guru yang tidak mengikuti kegiatan ini, dan terlihat sudah menunggu kami di ruang komite sekolah. Mereka adalah guru non-ASN, biasa disebut dengan Guru Tidak Tetap (GTT), atau biasa dikenal dengan sebutan guru honorer.
Salah satu di antaranya, T merupakan seorang guru Agama Islam berusia 51 tahun yang enggan disebutkan namanya. Ia telah mengabdi selama puluhan tahun, menjalani kehidupan yang berliku-liku sebagai guru honorer.

-ku sebagai guru honorer. Tak mudah bagi T untuk menjalani hari-hari sebagai seorang guru honorer. Sebagai seorang ayah yang masih mempunyai tanggungan anak dan istri, ia harus berjuang agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal seperti ini kerap dirasakan para guru honorer yang masih belum mendapatkan kesempatan menjadi ASN.

Pada awalnya, setelah lulus dari universitas, T langsung mengambil tawaran untuk menjadi seorang guru. Dalam pengabdiannya sebagai seorang guru, T juga mengambil pekerjaan lain yang sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu desain. Kedua pekerjaan tersebut sudah ia jalankan berbarengan sejak awal. Hal demikian dilakukan selain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, juga dimaksudkan bila terjadi masalah pada pekerjaan satu, bisa ditopang oleh pekerjaan lainnya.
Semenjak awal mengajar hingga memasuki usia 51 tahun, berbagai upaya telah T usahakan untuk mendapatkan status sebagai pegawai negeri. Namun, hasilnya nihil. Ketika ingin
sudah tercantum dalam
Data Pokok Pendidik (Dapodik) tidak dapat mendaftar, sebab tidak ada formasi untuk guru agama di daerahnya.
Saat tim redaksi Majalah Edukasi temui, T menceritakan pengalaman yang dilalui selama mengajar menjadi guru honorer. Ia merupakan salah satu guru honorer yang terdampak karena regulasi, serta ketidakjelasan status guru honorer. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi peluang untuknya dalam mencapai status sebagai ASN. Saat ini, ia mencoba mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah desakan pemerintah un-
tuk segera menuntaskan formasi perekrutan untuk guru non-ASN.
Kalau saja tidak lolos dalam seleksi, T tetap akan berharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Karena saya tahu petanya kayak begini-begini, tetap berharap saja,” katanya. Pengalaman selama bertahun-tahun yang sudah ia lewati, hanya berharap merupakan satu-satunya pilihan untuknya.
Nasib serupa juga menimpa Ivan Aziz Abdullah, seorang guru honorer yang mengajar sebagai guru BK (Bimbingan Konseling) di SMA N 14 Semarang. Ivan merupakan guru honorer berusia 28 tahun yang berasal dari Provinsi Lampung. “Kebetulan di SMA ini membutuhkan guru bimbingan konseling atau guru tamu, akhirnya saya masuk,” terangnya pada (18/10/2024). Awalnya ia telah mengajar di sekolah swasta, tetapi tempat ia melaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang kebetulan membutuhkan lowongan guru BK, menjadi salah satu alasan untuk pindah, walau hanya sebagai honorer. Sama seperti T, selain mengajar di sekolah, Ivan juga mempunyai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan gaji yang tidak seberapa dari guru honorer, Ivan memilih pekerjaan sampingan
menjadi editor artikel. Ivan mengaku, pekerjaan sampingannya sudah cukup untuk menunjang biaya hidupanya sehari-hari. Ivan menceritakan latar belakang kehidupannya yang berasal dari keluarga guru honorer. Ayah, ibu, dan kakaknya merupakan seorang guru di daerah asalnya. Kerja keras dan kegigihan dari kedua orang tuanya, membuatnya memiliki keinginan menjadi seorang guru.
Dengan adanya regulasi untuk segera menuntaskan PPPK pada 2024 dan dilarang mengangkat honorer di tahun 2025, Ivan akan tetap berharap menjadi seorang guru kalau dirinya tidak lolos seleksi dan guru honorer dihapuskan. “Saya akan mencari alternatif di swasta, harapan saya masih bisa menjadi guru tetapi ada sampingan juga,” kata seorang guru honorer SMA N 14 Semarang ini. Keingi nannya untuk tetap menjadi guru, menunjukkan tekadn ya yang kuat.
Terdampak Regulasi
Baru
Guru honorer jumlahnya meruah, tersebar di berb agai daerah. Mereka dipak sa bergulat dengan ribetnya regulasi yang terus bergan ti. Mirisnya, masa depan pekerjaan sebagai guru hon orer tidak lekas mendapat kejelasan.
Pada 31 Oktober 2023 silam, Presiden ke-7 Re publik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Regulasi ini merupakan salah satu jawaban atas keresahan dari guru honorer. Dengan mempercepat formasi seleksi PPPK, membuat guru honorer yang belum terangkat selama bertahun-tahun segera mendapatkan status ASN.
Dalam pelaksanannya, ternyata dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk menyelesaikan formasi PPPK. Seperti penuturan dari Nasikin, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
“Kalau kita hitung di atas kertas, di atas meja, perkiraan penyelesaian PPPK itu antara 2—3 tahun. Kalau kebijakannya masih sama seperti ini, tetapi kalau kebijakannya berbeda lagi, saya tidak tahu,”
tuturnya saat diwawancara pada (11/11/2024).
Di satu sisi, regulasi ini juga menelurkan masalah lain. Bagi pendaftar yang tidak lolos seleksi, seperti tercantum dalam keputusan dari MenPAN-RB Nomor 347, 348 Tahun 2024, mereka masih memiliki peluang untuk menjadi PPPK Paruh Waktu. Dalam aturan terbaru MenPAN-RB Nomor 15 tahun 2025, terdapat kualifikasi bagi para pendaftar PPPK Paruh Waktu, yakni dikhususkan bagi mereka yang sudah tercatat dalam BKN (Badan Kepegawaian Negara). Sedangkan, database BKN sudah ditutup semenjak Desember 2022 silam. Artinya bagi yang tidak ada formasi dan tidak lolos seleksi, berpotensi dirumahkan.
Hal tersebut sempat membuat Dhisky, seorang

guru honorer yang berasal dari Jakarta tergerak untuk melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Dilansir dari Detik. com, dalam gugatannya, Dhisky meminta penerapan pada Pasal 66 Undang-Undang 20 Tahun 2023 ditunda pelaksanannya.
Keberadaan pasal itu akan merugikan dirinya sebagai guru honorer jika belum diangkat menjadi ASN. Dia merasa terancam kehilangan pekerjaan jika belum diangkat sebagai ASN sesuai batas waktu Desember 2024. Nahasnya, MK menolak secara keseluruhan isi dari gugatannya. MK mengatakan keberadaan batas waktu Desember 2024 dalam pasal 66 UU 20/2023 telah memberikan kepastian hukum. Atas dasar itu, MK menolak seluruh permohonan pemohon. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Suhartoyo dalam sidang putusan pada (16/10/2024). MK menyatakan pemohon tidak perlu khawatir hak konstitusionalnya terlanggar dengan pemberlakuan UU 20/2023 tentang ASN, sebab UU tersebut menjamin hak pegawai honorer.
Sementara itu, dampak dari cleansing guru honorer benar-benar dilakukan. Kondisi tersebut sudah dirasakan secara langsung dampaknya oleh sebagian guru honorer. Seperti yg dialami Dasrial, guru honorer di SMP Solok Selatan,

Sumatera Barat. Ia kerap membagikan keluh kesahnya di akun TikTok miliknya, @dasrial_95. Dalam salah satu postingannya, dia mengaku mendapat surat pemecatan pada 23 Januari 2025, padahal sudah menjadi guru honorer sejak 2021 sebagaimana keterangan di Dapodik yang ia tunjukkan di unggahannya.
Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jembrana, Bali. Dilansir dari Spadadikti. id, terdapat ratusan pegawai non-ASN dengan masa kerja di bawah dua tahun harus merelakan pekerjaan mereka mengajar sebagai guru dan dirumahkan. Dengan penguncian database BKN tahun 2022 silam, serta penguncian Dapodik 2025. Pemerintah berusa-
ha menyelesaikan guru honorer yang sudah lama belum diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, dampak dari diberhentikannya guru honorer secara sepihak dalam satu waktu, menjadi masalah yang urgen untuk segera dicarikan solusi alternatif. Pemecatan secara sepihak juga akan mempengaruhi krisis ekonomi dan sosial mereka yang terdampak.
Harapan Guru Honorer Pelaksanaan regulasi untuk segera menuntaskan status guru honorer menjadi ASN, membuat para guru honorer dari berbagai daerah bersuara memastikan regulasi berjalan dengan baik. Walau menimbulkan masalah besar

kepada guru honorer muda yang tidak dapat diangkat
ASN, mereka berharap guru honorer yang sudah lanjut usia segera diselesaikan dan diangkat menjadi ASN.
Salah satunya terjadi di kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dilansir dari Detik. com, ribuan honorer yang tergabung dalam gerakan forum honorer database
BKN Indramayu melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indramayu. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu untuk membuka formasi sesuai jumlah honorer yang terdaftar di BKN. Pasalnya, banyak pendaftar yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, tetapi belum diangkat menjadi
ASN.
“Yang sudah puluhan tahun mengabdi dan usia sudah tua ini harus benar-benar diprioritaskan. Kami yang muda-muda mengalah dengan itu,” kata Ilham Ketua Gerakan Forum Honorer Database BKN Indramayu.
Tidak dapat dipungkiri, imbas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah menjadikan sebuah dilema bagi para sarjana pendidikan, terutama bagi sarjana pendidikan yang baru mengajar di sekolah negeri dan memperoleh status sebagai guru honorer. Pemberhentian massal berdasarkan regulasi yang benar-benar ditegakkan, menjadikan dilema tentang arah mereka ke depannya.
Kesaksian dari beber-
apa guru honorer yang terdampak, menjadi bukti dari semua masalah yang dihadapi. Dandi Putri Subagyo, seorang guru honorer berusia 24 tahun dari SMK
Negeri 10 Semarang mengaku baru beberapa tahun mengajar, sempat mengeluhkan hal yang sama. Ia tidak terlalu berharap kepada pekerjaannya sebagai seorang guru, kalau saja terdampak akan dirumahkan, maka ia memilih pekerjaan lainnya.
“Kalau dari saya pribadi, tidak bergantung pada PPPK. Apalagi umur saya kan juga masih terbilang muda, jadi masih ada kesempatan di CPNS walaupun bukan yang guru. Kalau ternyata regulasinya sudah tidak jelas, lama nunggunya, mencari yang pasti-pasti aja,” katanya.
Sementara Ifa Luthfia, seorang guru Bahasa Indonesia di sekolah yang sama, memberikan pernyataan akan nasibnya ke depannya. Ia tetap akan menjadi seorang guru, walau bagaimanapun profesi guru tetap akan dibutuhkan, dan tidak akan terganti oleh apapun.
“Jika tidak lolos, mungkin opsi lain adalah saya akan tetap menjadi honorer. Opsi lagi lainnya yang saya pikirkan adalah mungkin saya akan tidak di (sekolah) negeri, tetapi mending di swasta dengan pertimbangan sertifikat pendidik saya akhirnya terpakai,” ucapnya.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang penghapusan tenaga honorer, telah menjadi topik perdebatan di kalangan pendidik dan masyarakat. Kebijakan ini mengharuskan penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada akhir 2024 dan melarang pembukaan rekrutmen tenaga honorer baru. Meskipun langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya sangat kompleks. Banyak guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun kini merasa terancam oleh ketidakpastian masa depan mereka, terutama dengan kebutuhan tenaga pendidik yang masih sangat tinggi. Maka dari itu, tim redaksi Majalah Edukasi mencoba berbincang dengan Ivan Aziz Abdullah, salah satu guru honorer di SMA N 14 Semarang. Menceritakan jalan terjal yang dilalui untuk memperoleh status sebagai pegawai negeri, serta curahan harapan mereka terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Ivan Aziz Abdillah, salah satu guru honorer: Penghapusan Guru Honorer Bukan Solusi
Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya regulasi yang tertuang pada Pasal 66 UU No. 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa PPPK harus diselesaikan akhir 2024 dan tidak membuka tenaga honorer di tahun depan?
Menurut saya, adanya regulasi yang dilakukan oleh Kementerian sudah disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat. Akan tetapi, terkait tenaga honorer yang akan dihapuskan kemungkinan sangat sulit, sebab hal ini pernah terjadi pada tahun 2013 dan nyatanya belum terselesaikan sampai tahun 2024. Sedangkan, kebutuhan guru mulai dari yang honorer sampai pada ASN itu tidak seimbang. Realitanya yang dibutuhkan di lapangan itu sangat banyak, namun yang dianggarkan pada P3K sekarang itu belum maksimal. Walaupun nantinya mendapatkan dana pensiunan, akan tetapi masih membutuhkan waktu dan proses yang lama untuk perekrutan ASN dan tidak semua pendaftar akan diterima. Maka dari itu, adanya guru honorer masih dibutuhkan untuk memenuhi kekosongan posisi ketika ada guru yang meninggal, mutasi, dan sebagainya. Seperti halnya saya sekarang adalah guru BK (Bimbingan Konseling) yang mana masih kewalahan, sebab di sini hanya ada 4 guru BK, dan idealnya 1 guru BK membimbing 150 siswa. Sedangkan realitanya di sini 1 guru hampir membimbing 250 siswa. Jadi, dari hal tersebut membuktikan bahwa masih kekurangan guru. Apabila nantinya terjadi penghapusan tenaga honorer, maka kurang efektif untuk menjadi salah satu solusi untuk menyejahterakan pendidikan.
Bagaimana tanggapan Bapak terkait pernyataan MenPAN-RB bahwasanya pendaftar PPPK harus mendaftar guru non-ASN, walaupun di wilayah yang berbeda. Apabila pindah di wilayah berbeda pastinya membutuhkan tempat tinggal dan transportasi?
Menurut saya, untuk penempatan bagi non ASN itu yang sudah mengajar dalam waktu 2 tahun berturut-turut bahkan lebih. Nantinya mendapat prioritas P1, P2, P4. Prioritas 1 dan 2 ditempatkan di tempat dia mengajar, sedangkan untuk prioritas 4 ini akan disebar di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Contohnya, teman saya jurusan sosiologi orang Semarang di tempatkan di Sulawesi untuk mapping setelah mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru). Jadi, sudah bisa terbayang untuk lulusan pendidikan swasta kemungkinan sesuai kebijakan masing-masing yayasan, sedangkan untuk sekolah negeri itu memproritaskan yang sudah atau mempunyai sertifikat pendidik.
Terkait kebutuhan biaya hidup dan transportasi untuk yang ditempatkan wilayah yang jauh seperti golongan P4, yang mana untuk mengisi kekosongan posisi guru. Maka, dari itu kita harus memiliki kemampuan lain selain bidang keguruan untuk bisa memenuhi kebutuhan, apabila mengikuti kegiatan mapping nantinya. Seperti halnya saya memiliki sampingan sebagai editor artikel, buku, dan sebagainya yang mana dari situlah saya mencukupi kebutuhan saya untuk mapping nantinya.
Apabila belum lolos P3K, apakah Bapak memiliki rencana pekerjaan lain atau tetap berharap pada kesempatan berikutnya?
Berdasarkan pengalaman saya yang berlatar belakang dari anak guru honorer. Menurut saya, menjadi guru itu harus atas dasar sukarela, apabila dikatakan sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi, melihat dari dedikasi kedua orang tua saya, menginspirasi saya untuk terus berjuang menjadi guru yang sejahtera. Apabila nantinya saya tidak lolos, saya tetap berharap untuk kesempatan lainnya. Akan tetapi, saya harus memiliki alternatif lain seperti mendaftarkan diri di sekolah swasta yang pastinya membutuhkan banyak pendidik. Jadi, walaupun tidak di sekolah negeri, saya masih bisa mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi guru.
Bagaimana pandangan bapak terkait adanya keputusan
MenPAN RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 hanya diperuntukkan untuk pegawai non-ASN, sedangkan Fresh Graduate tidak bisa mendaftar?
Menurut saya, aturan tersebut dapat menghilangkan kesempatan bagi fresh graduate dan mahasiswa pendidikan yang tengah menempuh pendidikan. Hal ini menjadi dilema mereka, karena setelah lulus tidak bisa mendaftar ASN. Padahal selama menjadi mahasiswa pendidikan sudah dibekali bagaimana cara mengajar yang baik dan menjadi guru yang berkompeten melalui microteaching dan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan). Akan tetapi
hal tersebut tertutup dengan adanya aturan, bahwasanya setelah lulus strata 1 pendidikan harus mengikuti pendidikan profesi guru terlebih dahulu selama 1 tahun, dan setelah lulus nantinya baru mendapat sertifikat, serta melaksanakan mapping yang ditempatkan di seluruh Indonesia. Apabila mengikuti kegiatan tersebut, 80% bisa diterima sebagai ASN, mendapat tunjangan sertifikasi walaupun di sekolah swasta, serta mendapat prioritas 4 untuk mendaftar PPPK. Maka dari itu, untuk fresh graduate tidak usah berkecil hati apabila tidak bisa langsung mengikuti seleksi PPPK. Ikuti alurnya, taati aturannya, dan mendaftar PPG terlebih dahulu.
Adakah pesan untuk fresh graduate yang ingin menjadi guru?
Teruntuk mahasiswa pendidikan yang sekarang tengah bimbang dengan adanya regulasi seperti sekarang ini. Pesan saya, setelah lulus strata 1 lanjutkan PPG baik melalui jalur mandiri atau pun beasiswa pemerintah, walaupun harus melewati seleksi yang cukup ketat. Karena, kalian nanti akan ditempatkan di tempat yang dibutuhkan dan mengisi kekosongan posisi guru. Setelah mengikut PPG, kemungkinan 80% kalian bisa menjadi ASN, sebab guru itu adalah profesi yang seiring perkembangan waktu tidak dipandang sebelah mata dan membutuhkan sertifikasi. Maka, untuk fresh graduate kedepannya ikuti PPG karena terdapat peluang besar nantinya.


Agustin Fajariah Asih, Kru Edukasi angkatan 2021. Selain itu, merupakan mahasiswa prodi Manajemen Pendidikan Islam
Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi tenaga pendidik dan kesehatan di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), menetapkan kebijakan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan formasi terbesar sepanjang sejarah, yakni 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN. Kebijakan ini diatur dalam tiga peraturan utama: Surat Keputusan (SK) MenPANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK T.A 2024, SK MenPANRB No. 348/2024 tentang Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru, serta SK MenPANRB No. 349/2024 terkait Jabatan Fungsional Kesehatan.
Dengan kebutuhan tenaga pendidik yang terus berkembang, kebijakan PPPK 2024 menjadi titik balik bagi banyak guru dan calon pendidik di Indonesia. Namun, apakah kebijakan ini memberikan peluang yang adil bagi semua pihak? Tahun 2024 menjadi momen penting bagi tenaga pendidik dan kesehatan di Indonesia. Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), menetapkan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terbesar dalam sejarah, yakni 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Pemerintah memfokuskan kebijakan ini pada tenaga non-ASN, sebagaimana diatur dalam tiga peraturan utama: Surat Keputusan (SK) MenPANRB No. 347/2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK 2024, SK MenPANRB No. 348/2024 tentang Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru, serta SK MenPANRB No. 349/2024 terkait Jabatan Fungsional Kesehatan.
Prioritas Guru Honorer dan Dilema Bagi
Fresh Graduate
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menegaskan bahwa seleksi PPPK 2024 sepenuhnya ditujukan bagi pegawai nonASN. Hal ini menjadi angin segar bagi guru honorer yang telah lama mengabdi, tetapi menjadi tantangan bagi fresh graduate yang ingin masuk ke dunia pendidikan. Prioritas diberikan kepada guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Guru Tidak Tetap (GTT). Fresh graduate harus bersaing dengan tenaga berpengalaman, membuat peluang mereka semakin sempit.
Menurut Nasikin, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, formasi guru di provinsi tersebut mencapai 2.990 posisi, sedangkan tenaga teknis hanya 247 posisi. Seleksi tetap memprioritaskan kategori P1, yaitu guru honorer dengan kriteria tertentu. Sebagai solusi, Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan menjadi jalur bagi fresh graduate agar lebih kompetitif. Namun, mekanisme seleksi yang mengutamakan kategori P1 membuat mereka harus menunggu 2-3 tahun untuk memperoleh posisi jika kebijakan ini tetap berlaku. Pandangan Guru dan Strategi Menghadapi
Seleksi
Kebijakan PPPK menuai Beragam Tanggapan Dari praktisi pendidikan. Vicky Zulfikar, guru SMA Negeri 14 Semarang, menilai bahwa prioritas bagi guru honorer senior lebih adil karena banyak yang telah mengabdi bertahun-tahun, tetapi belum mendapat kesempatan hanya karena kurangnya sertifikasi. Sebaliknya, Sofi, guru SMK Negeri 10 Semarang, berpendapat bahwa sertifikasi adalah indikator kompetensi yang penting, sehingga fresh graduate harus memanfaatkan jalur PPG untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu, Ifa Luthfia, lulusan PPG Prajabatan, menyarankan fresh graduate memilih formasi dengan tingkat persaingan rendah, seperti jenjang SMA, untuk meningkatkan peluang lolos seleksi. Distribusi Guru dan Pemerataan Pendidikan Meski ada banyak formasi, distribusi guru ke daerah terpencil, terutama di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia timur, masih menjadi tantangan.
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan bahwa pada semester ganjil 2023/2024 terdapat 3,36 juta guru di Indonesia. Namun, provinsi di Indonesia timur memiliki jumlah guru terendah: Papua Pegunungan hanya memiliki 6.932 guru (0,20% nasional), Papua Selatan 8.283 guru (0,24%), dan Papua Barat Daya 9.855 guru (0,29%). Selain itu, Kabupaten Jayapura kekurangan 514 guru, dari berbagai jenjang: 44 guru SD, 198 SMP, 101 SMA, dan 171 SMK.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Eqberth C. Kopeuw, menyebut bahwa solusi sementara adalah mengangkat guru kontrak sambil menunggu perekrutan CPNS dan PPPK. Di Kota Balikpapan, defisit guru mencapai 520 guru dari jenjang TK hingga SMA/SMK, diperburuk oleh regulasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan guru non-ASN.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menjelaskan bahwa lonjakan jumlah siswa tidak sebanding dengan ketersediaan sekolah negeri, sehingga pemerintah fokus merevitalisasi sekolah dan pembangunan SMPN baru.
Ivan Aziz Abdillah, guru Bimbingan Konseling (BK) di SMK Negeri 10 Semarang, menyarankan pemerintah meningkatkan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil. Sementara itu, peserta seleksi PPPK
EDUKASI

yang tidak mendapat formasi di Jawa Tengah diarahkan ke wilayah lain, termasuk luar Pulau Jawa.
Namun, Nasikin menegaskan bahwa lokasi kerja tetap menjadi pilihan individu. Setelah diangkat, mereka akan menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas sesuai aturan, meski biaya hidup di tempat baru tetap bergantung pada gaya hidup masing-masing.
Kolaborasi untuk Sistem Pendidikan yang Lebih Baik
Terkait rencana penghapusan tenaga honorer pada akhir Desember 2024, Nasikin menyebutkan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan sistem yang lebih adil. Salah satu wacana yang tengah dikaji adalah skema PPPK Paruh Waktu bagi guru honorer yang belum lolos seleksi, meskipun teknis pelaksanaannya masih belum jelas. Program PPG Prajabatan dirancang untuk mempersiapkan tenaga pendidik yang kompeten dan siap bersaing, mirip dengan proses pendidikan profesi di bidang medis. Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan tenaga pendidik menjadi kunci dalam membangun sistem seleksi yang lebih inklusif. Dengan perbaikan regulasi, peningkatan pelatihan, dan pemerataan distribusi guru, diharapkan pendidikan Indonesia semakin berkualitas.
Saran bagi Fresh Graduate
Nasikin berpesan kepada fresh graduate untuk terus mempersiapkan diri melalui seleksi PPPK maupun jalur PPG Prajabatan.
Di tengah ketatnya persaingan dan perubahan kebijakan, daya saing serta kesiapan menjadi faktor utama. Dengan strategi yang tepat dan peningkatan kompetensi, fresh graduate tetap memiliki peluang untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Fresh graduate dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan mengikuti jalur pendidikan yang tersedia, sehingga dapat mengubah tantangan menjadi peluang besar di dunia pendidikan.

Oleh: Fajar Fahrozi
Pemberian sesaji pada kera di sekitar Goa Kreo kerap dipandang sebagai perbuatan musyrik. Untuk itulah, Pertunjukan Kolosal Mahakarya Goa Kreo muncul meruntuhkan miskonsepsi terhadap budaya yang ada.
Di daerah dataran tinggi wilayah Selatan Kota Semarang, berada di ketinggian 300 mdpl, menjulang tinggi sebuah perkampungan yang lengkap dengan kekayaan alamnya. Perkampungan itu bernama Dukuh Talun Kacang yang bersinggungan langsung dengan destinasi wisata terkenal di Semarang, yakni wisata Goa Kreo.
Dikenal dengan alamnya yang masih asri, ditambah keberadaan sekawanan kera ekor panjang sebagai penyambut tamu yang tak segan-segan memberi sikap selamat datang, menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Di selingkungnya terdapat Waduk Jatibarang, terhampar pemandangan yang menakjubkan jika dilihat dari tangga yang mengarah langsung ke Goa Kreo. Para wisatawan yang berkunjung terkadang memberi makan sekadarnya pada sekawanan kera. Itulah yang sudah terjadi dan dilakukan masyarakat di sekitar Goa Kreo selama bertahun-tahun. Setiap ada sisa makanan yang berlebih, mereka selalu memberikannya pada sekawanan kera. Bahkan, setiap tahun di bulan Sawal dalam penang-
EDUKASI
galan Jawa, tepatnya pada 3 hari setelah lebaran atau tanggal 3 Sawal, masyarakat berbondong-bondong untuk berkumpul mengadakan runtutan acara tahunan. Dimulai dengan kirab yang mengitari Goa Kreo, dan diakhiri dengan membagikan gunungan yang penuh dengan makanan kepada warga dan sekawanan kera. Acara tahunan ini dinamakan dengan “Sesaji Rewanda”, atau jika diartikan berarti pemberian sesaji untuk rewanda atau kera. Selain Sesaji Rewanda, digelar pula pertunjukkan kolosal yang merupakan runtutan dari acara tahunan, dikenal dengan “Mahakarya Goa Kreo”. Menceritakan tentang legenda Goa Kreo yang diperankan oleh para pegiat seni di sekitar Goa Kreo. Pertunjukkan diawali dengan pembacaan prolog, disertai dengan para lakon yang memasuki area pertunjukkan dengan khidmat, seolah menyihir penonton yang hadir. Sembari diselingi dengan guyonan receh ala seni Ketoprak, menjadikannya menarik dan tidak monoton untuk dilihat.
Dianggap Musyrik
“Ada yang mengatakan bahwa kebiasaan masyarakat memberikan makan kepada hewan di Goa Kreo adalah musyrik. Padahal, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbagi makanan pada sesama makhluk ciptaan-Nya merupakan hal
yang sudah barang tentu dilakukan.” Ucapan yang keluar dari Abdul Karim saat diwawancarai pada (19/5/2024) di kediaman rumahnya. Ia merupakan warga asli yang mendiami Dukuh Talun Kacang. Sesaji Rewanda sebetulnya memiliki pengertian yang berbeda jika diartikan secara tersurat, seperti arti sesajen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bermakna, pemberian makanan yang dipersembahkan dengan tujuan berkomunikasi dengan kekuatan gaib. Sehingga timbulnya pandangan buruk bagi sebagian masyarakat, bisa terjadi karena miskonsepsi antara pengertian dan makna yang sesungguhnya.
Jika diruntut dari sejarahnya, Sesaji Rewanda memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya. Pertama, dengan adanya Sesaji Rewanda masyarakat ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan, sebab keberadaan kera yang ada di sekitar menjadi bukti bahwa lingkungan masih tetap lestari. Kedua, berbagi sesama kepada kawanan kera yang ada di sekitar Goa Kreo, mengajarkan nilai berbagi terhadap sesama.
Miskonsepsi bisa terjadi karena tidak adanya sinkronisasi antara pemahaman masyarakat luas terhadap suatu budaya. Menurut penelitian yang berjudul “Suatu Tinjauan tentang Jenis-Jenis dan Penyebab
Miskonsepsi Fisika”, menyatakan bahwa miskonsepsi terjadi karena kesalahanpemahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada. Sehingga terbentuk konsep yang salah dan bertentangan dengan konsepsi.
Kolosal Pendobrak Miskonsepsi
Adanya pandangan buruk terhadap kebiasaan masyarakat di sekitar Goa Kreo, membuat masyarakat akhirnya melakukan cara untuk memperkenalkan budaya, sekaligus meluruskan pandangan buruk mengenai Sesaji Rewanda. Tercetuslah sebuah kolosal bernama “Mahakarya Goa Kreo”, berkisah mengenai legenda perjalanan Sunan Kalijaga mencari kayu jati untuk membuat saka masjid Demak.
Awal diadakannya Mahakarya Goa Kreo diinisiasi langsung oleh warga sekitar, dengan memanfaatkan pegiat seni di beberapa desa sekitar, berjalanlah kolosal yang beriringan langsung pelaksanaannya dengan Sesaji Rewanda. “Tahun 90-an dikonsep pertunjukan untuk daya tarik wisata, untuk personilnya hanya dari masyarakat sekitar hingga akhirnya kekurangan orang, dan lambat laun dibantu oleh pemerintah yang bekerja sama dengan sanggar-sanggar,” papar
Abdul Karim melanjutkan pembahasan saat diwawancara.
Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Semarang, Suraso memberikan keterangan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Disbudpar mengemas acara pertunjukan dengan tetap melibatkan masyarakat sekitar. “Panitia pasti dari Pemerintah Kota, tetapi tetap melibatkan masyarakat sekitar, baik Lurah, RW, RT, ataupun golongan masyaraat yang lain, sebab sebetulnya semua ide itu dari masyarakat,” terangnya saat ditemui di kantornya pada (23/4/2024).
Seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai tidak mempermasalahkan anggapan musyrik pada budaya setempat, mereka merasa senang dengan adanya pertunjukan yang telah dirancang sedemikian rupa. Rafi (20), salah satu penonton yang merupakan warga asli warga Semarang menuturkan, pertunjukan seperti ini perlu diadakan untuk memperkenalkan budaya Goa Kreo secara luas. “Pertunjukan seperti ini cukup membantu menambah wawasan, khususnya bagi mereka yang belum mengenal Goa Kreo beserta budayanya,” tuturnya saat diwawancara pada (19/4/2024).
Anggapan musyrik dari sebagian masyarakat, berubah menjadi rasa ketertarikan untuk menonton
kolosal, tak lepas dari peran para penari dan pegiat seni. Maulana Mulyakin (25), seorang pegiat seni membeberkan tentang perpaduan antara seni kontemporer dengan seni tradisi, terbukti dapat menarik atensi dari masyarakat umum. “Sebenarnya alur pertunjukannya masih sama, hanya saja

kita memasukan imajinasi baru. Jadi kita bukan hanya menampilkan seni tradisi, tetapi juga dapat menarik atensi masyarakat suapaya tidak membosankan,” bebernya.
Dampak terhadap Perekonomian Warga Merujuk pada UU nomor 5 tahun 2017 tentang pema-
juan kebudayaan. Pemerintah turut berupaya mengelola kebudayaan yang ada di seluruh penjuru negeri, terkhusus pada lingkup wilayah kota Semarang. Salah satu upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pemajuan kebudayaan, ialah dengan melestarikan budaya yang ada di objek wisata Goa Kreo.
starikan. Ketika diangkat dan terkenal, masyarakat di sekitar juga akan terlibat langsung, secara ekonomi akan membantu UMKM dari masyarakat,” lanjut Suraso dalam sesi wawancara.
Hal ini senada dengan Abdul Karim saat memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kondisi ekonomi

Suraso melanjutkan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pemajuan kebudayaan, terutama di bidang ekonomi masyarakatnya dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Pemerintah membuat bagaimana mengangkat objek wisata Goa Kreo untuk dikembangkan dan dile-
setelah pertunjukan kolosal, bantuan dari pemerintah turut serta mengangkat objek wisata Goa Kreo menjadi terkenal. “Dengan adanya pertunjukan kolosal, perekonomian di sekitar sini juga ikut terbantu, kita sediakan homestay bagi para pengunjung yang ingin menginap,” terangnya.
Para masyarakat di sekitar
Goa Kreo juga menetapkan aturan bagi pembangunan hotel, dan tidak segan-segan untuk menolak segala bentuk pembangunan hotel, sebab akan merusak perekonomian masyarakat sekitar.
Di lain sisi, masyarakat diharuskan untuk menyediakan kamar-kamar kosong di masing-masing rumah, dalam satu rumah paling tidak harus ada satu kamar yang kosong. Hal ini dimaksudkan sebagai penginapan bagi para pengunjung yang datang, serta juga dapat membantu perekonomian mereka.
Selain dengan ikut memberikan dukungan kepada masyarakat di sekitar objek wisata, para warga yang hidup berdampingan dengan situs sejarah, akan merasa memiliki dan merawat objek wisata supaya tak lekang oleh masa. Generasi selanjutnya juga akan merasakan kekayaan budaya beserta alamnya.

Fajar Fahrozi Kurniawan merupakan kru edukasi angkatan 2022.
Sejarah telah mencatat bahwa seorang perempuan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan pelengkap atau bahkan menjadi korban. Pada era Yunani kuno misalnya, perempuan ditempatkan sebagai makhluk Tuhan yang disekap di istana. Peradaban Romawi menempatkan perempuan di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan pindah di tangan suaminya. Dalam masyarakat Arab Jahiliyah ditemukan adanya tradisi menghalalkan pembunuhan bayi perempuan (Munib Abadi, 2009).
Hingga saat ini pun sebagian besar perempuan masih belum menikmati kebebasan sebagaimana yang dinikmati oleh kaum laki-laki. Bahkan masih banyak kaum perempuan yang masih menanggung beban akibat tindakan semena-mena kaum lelaki. Faktor penyebab masalah ini adalah adanya kondisi sosial yang secara turun-temurun berpihak pada kepentingan laki-laki atau biasa disebut dengan budaya patriarki. Konstruksi budaya patriarki yang berlansung selama berabad-abad inilah yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan (Busriyati, 2012).
Lebih lanjut, budaya patriarki tersebut juga masuk dalam tafsir teks keagamaan, termasuk Al Qur’an. Konstruksi budaya dan penafsiran para ahli agama terhadap teks keagamaan
merupakan faktor yang krusial sebagai penyebab terjadinya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Banyak penafsiran agama yang kemudian menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua. Ada juga ayat Al- Qur’an yang secara tekstual mentoleransi kekerasan terhadap perempuan.
Padahal, jika kita membaca secara seksama Al-Qur’an dan Hadis, akan ditemukan bahwa syariat Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia tanpa membeda-bedakan jenis kelamin. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menguraikan akar dari kekerasan terhadap perempuan dan menegaskan bahwa islam tidak membenarkan sama sekali segala bentuk kekerasan terhadap seseorang termasuk pada perempuan.
Pandangan Islam terhadap Perempuan
Perempuan memiki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Mereka merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan segala kelebihannya. Islam tidak mengenal adanya diskriminiasi antara laki-laki dan perempuan (Lulu Mubarakah, 2021). Pada hakekatnya perempuan dalam pandangan Islam dapat kita cermati di beberapa surah dalam Al-Qur’an. Salah satunya Q.S Al-Hujarat: 13 yang artinya: “Wahai manusia sesungguhnya Kami mencipkatakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Alah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Melihat dan Maha Mengenal”. Jika dicermati, ayat tersebut dapat dipahami bahwa perempuan memiliki aspek kemanusiaan yang sama dengan laki-laki, yang membedakan antara mereka adalah ketaqwaan di sisi Allah SWT. Adapun hak-hak perempuan yang melekat dalam beberapa aspek kehidupan yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis yaitu, (1) Hak beribadah dan beragama untuk masuk surga sesuai dalam Q.S An-Nisa: 124. (2) Hak dalam bidang politik antara lain disinggung dalam Q.S At-Taubah: 71 dan QS. Al-Mumtahanah: 12. (3) Hak kebendaan, menerima waris, memiliki hasil usahanya sendiri dan hak untuk bekerja sesuai dalam Q.S An-Nisa: 32,11, dan 34. (4) Hak memilih dan menentukan pasangan hidup.(5) Hak menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi disebutkan yang artinya : “Menuntut Ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap islam laki-laki dan perempuan” (Moh Bahradin, 2012).
Kekerasan terhadap Perempuan dalam Penafsiran Al-Qu’ran
Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan
dalam masyarakat muslim adalah begitu mengakarnya budaya patriarki di kalangan umat Islam sendiri. Patriarki muncul sebagai bentuk kepercayaan ideologi bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Hal ini muncul di antaranya karena penafsiran yang kurang tepat terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, terutama relasi suami-istri dalam rumah tangga.
Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang jika dipahami secara tekstual seolah memberikan pembenaran terhadap tindak kekerasan, utamanya kekerasan terhadap perempuan, salah satunya adalah Q.S An-Nisa: 34. Di dalam ayat tersebut, disebutkan suami adalah pemimpin rumah tangga. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa suami berhak secara mutlak menguasai istrinya dengan memperlakukannya semena-mena dengan dalil mendidik. Ketika istri nusyuz (tidak melakukan kewajibanya) maka seorang suami boleh melakukan tiga hal, yaitu memberikan nasehat, memisah tempat tidur, dan memukulnya. Istilah “memukul’ di sini seringkali dimaknai bahwa Al-Qur’an membolehkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istirnya (Umi Sumbulah, 2010).
Ada banyak tafsir terhadap teks-teks suci keagamaan yang mengadung misoginis yakni ideologi kebencian terhadap perempuan. Tafsir arus utama yang masih dipercayai mayoritas masyarakat muslim hingga saat ini tetap meletakkan laki-laki sebagai pusat dari kehidupan domestik maupun

publik. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan dalam AlQur’an sebagai bagian dari pandangan Islam. Penafsiran Al-Qur’an dengan semangat misoginis tersebut masih sering dijadikan dasar untuk menolak kesetaraan gender (Busriyati, 2012).
Padahal, sejak awal kehadirannya Islam memang sudah dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial baru yang egaliter, anti diskirminasi dan anti kekerasan terhadap perempuan. Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan yang kemudian memandang rendah terhadap satu golongan, jelas tidak dibenarkan karena bertentangan denga teks-teks lain yang membawa visi adanya kesetaraan manusia disisi Allah SWT. Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang kesetaraan dan perlakuan terhadap perempuan diantaranya Q.S Al-Hujarah:13. Q.S Az-Zariyat:56, dan QS. Al-An’am:165. Maka perlu ada cara pandang
baru terhadap teks-teks AlQur’an yang bisa mendobrak tafsir misoginis dan menghadirkan semangat kesetaraan, kedamaian dan ketersalingan. Di antara cara pandang itu adalah metode Qira’ah Mubadalah.
Doc. Internet Membumikan Qira’ah Mubadalah
Selama ini kibat-kitab fikih yang menjadi sumber dalam memahami Al-Qur’an dan Hadis banyak yang memberikan bias penafsiran terhadap gender. Akibatnya, dalam kehidupan sehari-hari, perempuan banyak dirugikan. Dari sinilah muncul kekerasan gender di tengah masyarakat Islam di Indonesia. Maka dari itu saat ini diperlukan suatu pendekatan baru untuk merumuskan pandangan Islam atas masalah-masalah perempuan selama ini. Pendekatan yang diperlukan untuk
memahami ajaran moral agama yang bersifat prinsipil mesti membutuhkan analisis sosial (Busriyati, 2012).
Qira’ah mubadalah menjadi salah satu pendekatan terhadap interpretasi Al-Quran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Qadir..Secara metodis, Qira’ah Mubadalah memberikan peluang untuk melakukan pengembangan pemahaman dan praktik terhadap sebuah teks agar memiliki nilai kesalingan-hubungan. Pendekatan ini mencoba menawarkan penempatan posisi laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam konteks penafsiran Al-Qur’an (Anisa Dwi, 2020)
Faqihuddin membagi pendekatan ini dalam tiga tahapan yaitu, operasional teks (aspek kebahasaan), purpose of verses (histori ayat), dan double reader (mengacu pada dua pembacaan). Berpijak pada tiga premis itu, Qira’ah mubadalah mencoba menawarkan cara dalam menemukan gagasan utama dari setiap teksnya agar selalu selaras dengan prinsip-prinsip universal Al-Qur’an. Sehingga hukum yang ada di dalamnya memberikan kemaslahatan bagi laki-laki dan perempuan (Wahyu f, Amrul P, 2021).
Sebagai contohnya kata
“dharaba” yang artinya memukul pada QS. An-Nisa: 34. Dengan metode Qira’ah Mubadalah kita akan menemukan makna berbeda dengan penafsiran yang selama ini telah populer. Adapun langkah-langkah dalam menafsirkan kata “dharaba” mencangkup tiga oprerasional yang saling berhubungan. Operasional pertama ialah berkenaan dengan aspek kebahasaan bahwa kata ini lebih bervariasi digunakan dalam AlQur’an, dan pada ayat ini ditemukan makna kata lain selain memukul, yaitu pergi. Untuk melacak makna dari kata ini dan bagaimana digunakan dalam konteks islam maka dapat ditelaah melalui operasi kedua yaitu, historisasi ayat. Historisasi ayat ini melalui dua jalur berbeda yang sama-sama memberi gagasan utama tentang pentingnya penanganan perselisihan dalam keluarga yang sama sekali tidak menggunakan kekerasan.
Setelah kemudian menemukan gagasan utama pada ayat ini, melalui dua pembacaan, maka pesan utamanya tidak hanya menyasar pada perempuan tetapi juga laki-laki (double reader). Dengan demikian makna dharaba, yakni pergi ke pengadilan dapat diperuntukkan kepada suami dan istri yang keduanya diharap dapat menyelesaikan permasalahanya secara seksama. (Wahyu f, Amrul P, 2021).
Dari uraian di atas, terdapat perbedaan antara tafsir populer yang selama ini ada di masyarakat (tafsir misoginis) dengan penafsiran menggunakan metode Qira’ah Mubadalah. Jika tafsir misoginis fokus pada dominasi serta memaknai ayat hanya berdasarkan konteks sejarah, Qira’ah Mubadalah fokus pada kesetaraan dan relasi timbal balik. Dengan begitu akan dihasilkan penafsiran yang lebih memberikan maslahat dan adil gender.
Selama ini, seringkali agama menjadi alat legitimasi terhadap adanya tindak kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, penting bagi lembaga keagamaan, lembaga kajian dan pendidikan keagamaan untuk memiliki bagian pengkajian teks-teks yang masih bias gender, serta sebagai wadah untuk mengkaji kedudukan perempuan dalam agama islam. Dengan adanya kajian tersebut diharapkan akan hadir tafsir ataupun fikih perempuan yang berspektif keadilan, ketersalingan serta mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan yang kasusnya saat ini kian meningkat. Dengan demikian, metode Qira’ah Mubadalah bisa menjadi salah satu pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk memahami kembali ayatayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan, sehingga memiliki kesetaraan dan keadilan.

Ujian Komprehensif di Sebagian Prodi FITK UIN Walisongo Resmi Ditiadakan Oleh: Lailatul Maghfiroh
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang membuat kebijakan peniadaan ujian komprehensif yang sudah berlaku di sebagian besar program studi di FITK.
Hal ini diberlakukan sejak Februari tahun ajaran baru 2024/2025. Diketahui, ujian komprehensif merupakan bentuk ujian untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa secara komprehensif (menyeluruh) terhadap materi-materi perkuliahan yang telah dipelajari. Kebijakan ini dinilai mahasiswa sebagai kebijakan yang mendadak dan belum jelas kebenarannya. Dari sejumlah informasi yang kami himpun dari bulan Agustus sampai September, ditemukan fakta bahwa diberlakukannya kebijakan peniadaan ujian komprehensif mendapat banyak tanggapan dari mahasiswa FITK UIN
Walisongo Semarang. Salah satunya adalah mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 2020 bernama Ana. Ia mengatakan, isu ujian komprehensif ditiadakan sudah ada sejak bulan Februari atau tahun ajaran baru 2024/2025 dan disebarkan secara lisan dari dosen maupun mahasiswa.
“Awalnya ujian komprehensif memang ada kemudian di Bulan Februari sudah muncul isu penghapusan dan kebijakan penghapusan ujian komprehensif mulai berlaku di tahun ajaran baru tanpa adanya surat edaran. Bisa dikatakan

informasi disebarkan dari lisan ke lisan seperti pesan burung,” jelasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (MPI) angkatan 2021, Fadhilah Rahmawati, mengaku mendapat informasi penghapusan ujian komprehensif dari kepala jurusan dan ketua angkatan.
“Saya mengetahui informasi penghapusan ujian komprehensif dari ibu kepala jurusan dan ketua angkatan MPI,” terangnya.
Sedangkan, mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) angkatan 2021, Rizqi Putri mengaku mendapat informasi peniadaan ujian komprehensif dari WhatsApp. “Dosen PIAUD memberitahukan kebijakan penghapusan ujian komprehensif melalui grup WhatsApp angkatan,” jelasnya.
Hal ini dibenarkan oleh mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) bernama Wulan mendapatkan informa-
si penghapusan ujian komprehensif dari dosen PAI melalui grup WhatsApp ujian kompre sehari sebelum ujian.
“Saya diberitahu dosen PAI melalui grup WhatsApp, sehari sebelum saya ujian komprehensif,” ujarnya.
Dengan informasi yang sangat mendadak ini, Wulan merasa sedih karena sudah mempersiapkan diri untuk ujian komprehensif namun tiba-tiba dibatalkan.
“Saya sangat merasa sedih karena sudah belajar untuk mempersiapkan ujian komprehensif,” keluhnya.
Meskipun kebijakan peniadaan ujian komprehensif sudah diberlakukan, sebagian kecil mahasiswa FITK angkatan 2020 masih melaksanakan ujian komprehensif yaitu bekisar 10-15% dari total mahasiswa angkatan 2020.
“Mahasiswa angkatan 2020 sebagian kecil masih ada yang merasakan ujian komprehensif, termasuk saya. Jika dipersentasekan sekitar 15% atau bahkan 10% mahasiswa

yang mengikuti ujian komprehensif,” ucap Ana.
Sementara itu, prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) masih masih mengadakan ujian komprehensif.
Salah satu mahasiswa PBI, Hanna, mengatakan bahwa informasi diadakannya ujian komprehensif di prodi PBI disampaikan oleh kepala jurusan. “Dari informasi yang diberitahukan oleh kepala jurusan, prodi PBI masih mengadakan ujian komprehensif,” jelasnya. Hanna juga menambahkan bahwa pelaksanaan ujian komprehensif di prodi PBI fleksibel disesuaikan dengan dosen penguji.
“Pelaksanaan ujian komprehensif di jurusan PBI terbilang fleksibel karena durasi pelaksanaannya dan forumnya disesuaikan dengan dosen penguji. Dari beberapa pengalaman saya dan teman-teman PBI, beberapa di antara kami ujian komprehensif di dalam majelis, sebagian yang lain di luar majelis karena menyesuaikan dosen penguji. Pelaksanaan-
nya juga berbeda, ada yang membutuhkan waktu satu hari ada yang lebih dari itu.
Sedangkan untuk materi yang diujikan terkait dengan bahasa Inggris dan materi keagamaan,” imbuhnya.
Menanggapi kebijakan penghapusan ujian komprehensif, Ana mengaku setuju namun menyayangkan dengan pemberitahuan yang mendadak.
“Saya setuju dengan penghapusan ujian komprehensif namun saya kurang setuju dengan penyampaian informasi yang mendadak dan tanpa surat edaran,” tegasnya.
Menanggapi hal tesebut, mahasiswa PGMI angkatan 2020, bernama Farikha, tidak mempermasalahkan diadakan atau ditiadakannya ujian komprehensif.
“Saya tidak mempermasalahkan ada tidaknya ujian komprehensif, justru dengan tidak adanya ujian komprehensif mahasiswa menjadi lebih fokus dengan tugas akhir yang mereka kerjakan,” jelasnya.
Hal ini serupa dengan yang disampaikan mahasiswa bernama Fadhilah, ia merasa senang dan bisa fokus untuk mengerjakan skripsi.
“Saya bersyukur ujian komprehensif ditiadakan karena bisa fokus untuk mengerjakan skripsi,” terangnya.
Sama halnya dengan yang dikatakan Rizqi, dengan penghapusan ujian komprehensif diharapkan mahasiswa akhir lebih fokus pada penelitiannya.
“Dengan tidak adanya ujian komprehensif, kami berharap mahasiswa akhir bisa lebih fokus dengan tugas akhir atau penelitiannya dan segera lulus,” terangnya.
Untuk mengganti ujian komprehensif, salah satu program studi (prodi) Pendidikan Bahasa Arab (PBA) mewajibkan untuk menghafalkan kitab amsilatut tasrifiyah. Seperti yang dikatakan mahasiswa PBA angkatan 2021, Laila Nur. “Di jurusan PBA ada tugas untuk menghafalkan amsilatut tasrifiyah dan hafalan setiap mahasiswa disetor ke dosen wali masing-masing untuk dicatat,” ucapnya.
Sementara, prodi-prodi di FITK selain PBA tidak ada tugas pengganti.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Jurusan PBA, Tuti Qurrotul Aini mengatakan bahwa hafalan amsilatut tasrifiyah digunakan sebagai syarat ujian munaqosah.
“Mahasiswa PBA harus menyelesaikan hafalan amsilatut tasrifiyah ke dosen wali masing-masing setelah skripsi mereka selesai sebagai syarat ujian munaqosah, “ jelasnya. Terkait hal tersebut, Wakil Dekan I, Mahfud Junaedi mengatakan, pihak fakultas tidak mewajibkan adanya tugas

Istock
pengganti ujian komprehensif.
“Fakultas tidak mengharuskan adanya tugas pengganti ujian komprehensif yang dihapus, kalaupun ada itu untuk kepentingan jurusan sebagai penguat mata kuliah tertentu,” terangnya.
Mahfud juga menyampaikan, tidak ada komplain dari pihak mahasiswa terkait pemberlakuan kebijakan peniadaan ujian komprehensif.
“Penghapusan ujian komprehensif ini disambut baik oleh mahasiswa terbukti tidak ada mahasiswa yang komplain,” jelasnya.
Selanjutnya Mahfud menyampaikan bahwa pemberlakuan kebijakan ditiadakannya ujian komprehensif merupakan bentuk realisasi
kebijakan dari UIN Walisongo Semarang.
“Kebijakan penghapusan ujian komprehensif merupakan pelaksanaan kebijakan yang didasarkan pada pedoman akademik terbaru dari UIN Walisongo Semarang tahun 2024,” ucapnya.
Menurut Mahfud, pemberlakuan kebijakan ini dimulai dari angkatan 2020.
“Jika didasarkan pada panduan akademik terbaru, mahasiswa mulai angkatan 2020 sudah tidak diadakan ujian komprehensif, jadi angkatan sebelumnya masih ada,” tegasnya.
Pihaknya menambahkan peniadaan ujian komprehensif dilatarbelakangi oleh berbagai mata kuliah yang sudah
ditempuh mahasiswa.
“Alasan ditiadakan ujian komprehensif karena mahasiswa dianggap sudah lulus berbagai mata kuliah sehingga tidak perlu adanya ujian. Itu akan menghambat kelulusan mahasiswa karena prosesnya yang cukup panjang,” imbuhnya. Meskipun sudah tidak ada ujian komprehensif, Mahfudz berharap mahasiswa tetap belajar untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan saat munaqosah.
“Harapannya mahasiswa tetap belajar untuk menghadapi munaqosah karena beberapa materi ujian komprehensif biasanya ditanyakan juga ketika munaqosah,” tegasnya.


nilai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) sering kali dikaitkan dengan menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Meskipun KKM dianggap sebagai indikator kualitas pendidikan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan KKM tidak selalu sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terjadi karena peralihan fokus utama pada pencapaian angka KKM semata, tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang mendalam dan pengembangan daya kritis siswa. Selain itu, tuntutan untuk mencapai nilai KKM yang lebih tinggi, mendorong guru untuk menurunkan bobot soal atau mengurangi kedalaman materi yang justru dapat mengabaikan pemahaman yang sesungguhnya. Pada umumnya, nilai KKM bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik serta meningkatkan mutu pendidikan yang digunakan sebagai acuan oleh masing-masing guru. Setiap sekolah memiliki nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang berbeda-beda dan ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti, kompleksitas materi, kemampuan awal siswa, dan daya dukung sekolah. Berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Badan
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah(BAN-S/M), tuntutan nilai KKM sebesar

Pixabay
75% dipergunakan sebagai salah satu kriteria penilaian dalam akreditasi sekolah. Maka dari itu, sejumlah sekolah berupaya untuk menerapkan nilai KKM yang tinggi.
Salah satu pengamat pendidikan di Sumenep, Rabiatul Adawiyah mengatakan bahwa terdapat adanya peningkatan nilai KKM yang signifikan di kalangan siswa, tetapi kualitas pembelajaran masih tertinggal. Menurutnya, peningkatan nilai KKM tersebut terkesan dipaksakan, karena tidak diimbangi dengan perbaikan dalam metode pen-
gajaran dan pengembangan kompetensi guru. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara pencapaian nilai dan pemahaman materi yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam sistem pembelajaran yang melibatkan peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan guru, dan pendekatan yang lebih holistik terhadap perkembangan siswa.

Penerapan nilai KKM yang terkesan tinggi menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap proses pembelajaran. Pertama, siswa akan merasa terbebani karena harus mencapai target yang semakin tinggi serta menambah tekanan psikologis mereka. Kedua, guru cenderung lebih fokus pada pencapaian nilai daripada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, sehingga aspek-aspek penting seperti kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan sosial dapat terabaikan. Ketiga, sekolah dapat terjebak dalam mengejar target kuantitatif, seperti ketuntasan nilai siswa tanpa memperhatikan kualitas pembelajaran yang sesungguhnya. Nilai KKM yang dikategorikan tinggi, memerlukan bobot soal yang berkualitas. Namun, pada kenyataannya banyak siswa masih menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, meskipun nilai KKM menjadi acuan yang harus dicapai. Un-
tuk memenuhi nilai standar KKM yang tinggi, mayoritas guru terpaksa menurunkan tingkat kesulitan soal, sehingga siswa tidak terlatih menghadapi tantangan akademis yang sebenarnya. Akibatnya, meskipun nilai siswa menunjukkan hasil yang baik, pemahaman mereka terhadap materi justru mengalami penurunan. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dan pemahaman materi dapat terabaikan oleh siswa.
Ketika fokus utama pendidikan bergeser pada pencapaian nilai KKM yang tinggi, kualitas pendidikan secara keseluruhan dapat terancam. Pendidikan yang seharusnya bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan bermanfaat untuk kehidupan siswa malah terjebak dalam pengejaran angka semata. Hal ini juga menghambat terciptanya lingkungan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kegiatan yang seharusnya mendorong eksplorasi, kritis, dan pengembangan
pemikiran siswa menjadi terbatas karena terfokus pada penilaian yang hanya mengukur kemampuan menghafal atau reproduksi informasi. Akibatnya, secara perlahan pendidikan kehilangan tujuan utamanya. Peningkatan nilai KKM secara terus-menerus belum tentu menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Sebaliknya, jika tidak diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka peningkatan nilai KKM justru dapat berdampak negatif pada pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama semua pihak untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Hal ini melibatkan peningkatan kompetensi guru, penyempurnaan kurikulum, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung proses pembelajaran secara efektif. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak, diharapkan kualitas pendidikan dapat meningkat secara signifikan dalam pengembangan karakter dan keterampilan siswa.



“Kenapa kamu harus hemat?”
Pertanyaan itu kerap kali saya dapatkan ketika ada kebimbangan akan membeli atau tidaknya suatu barang. Menurut sebagian orang, membeli barang tidak harus menunggu kebutuhan mendesak—ketika menginginkannya, langsung saja dibeli tanpa berpikir panjang. Namun, bagi saya dan banyak orang, membeli barang harus dilihat terlebih dahulu apakah itu benar-benar ke-
butuhan atau sekadar keinginan. Dengan begitu beberapa orang beranggapan bahwa hidup hemat berarti hidup susah. Menyinggung mengenai persoalan gaya hidup hemat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan frugal living, menurut sebagian orang istilah tersebut dinilai sama dengan kekikiran. Padahal, makna frugal living tidak seringan itu. Frugal living merupakan kebiasaan-kebiasaan seseorang dengan penuh kesadaran membagi uang yang dimiliki dengan pertimbangan efektif untuk mencapai tujuan keuangan masa
depan yang jelas. Dalam hal ini, gaya hidup hemat memungkinkan pelakunya untuk memilih mana yang menjadi kebutuhan dan keinginan, sehingga dapat mengetahui penting tidaknya barang tersebut. Keterbalikan dari penjelasan di atas, istilah konsumerisme juga berhubungan erat dengan gaya hidup masyarakat. Konsumerisme merupakan keadaan dimana seseorang atau kelompok yang mengkonsumsi maupun memakai barang-barang produksi secara berlebihan. Konsumerisme memiliki arti yang sama dengan pemborosan, peng-
hamburan, dan pembaziran. Dalam dunia psikologi, ini dikenal dengan shopping addiction (kecanduan belanja).
Dari teori konsumerisme yang dikemukakan oleh Jean Baudrillard, seseorang menjadi konsumerisme bukan karena orientasi kebutuhan melainkan ingin menunjukkan status sosialnya. Saat ini, konsumerisme sudah memengaruhi masyarakat luas yang mengakibatkan timbulnya budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme dijadikan pijakan bahwa kemewahan sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, bahkan pemuasan diri sendiri. Dari beberapa bahkan semua lapisan masyarakat belum bisa memprioritaskan antara barang yang harus dipenuhi atau keinginan belaka, tak terkecuali mahasiswa.
Secara umum, para remaja menyadari perilaku konsumtif merupakan sikap yang kurang diterima dalam lingkup sosial maupun agama, terlebih agama Islam. Seperti dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 27, bahwa para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Pertanyaan yang sering ada dibenak saya yaitu bagaimana bertahan hidup di realita sekarang yang semakin maju, harga barang pun semakin menggila. Tantangan hidup kian bertambah terutama dalam pemenuhan kebutuhan dengan pendapatan hasil kerja yang stagnan bahkan belum mempunyai gaji (sebagian besar untuk kalangan mahasiswa). Sering saya temui sebagai seo-
rang mahasiswa, ada beberapa teman dan bahkan orang lain di luaran sana yang hidupnya berfoya-foya. Mereka hangout ke kafe, mall, membeli baju baru tiap bulan, checkout di marketplace secara terus menerus, bahkan ada yang mempunyai hutang sampai menumpuk. Seketika yang saya pikirkan, kenapa dengan mudahnya mereka membeli barang tanpa memikirkan kedepannya? Apakah hidup hemat bagi mereka itu aneh? Apa mereka tidak memikirkan dana jangka panjang? Kebutuhan mahasiswa dewasa ini bukan hanya sekedar UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan finansial semata, tetapi terdapat kebutuhan lain untuk menunjang penampilan dan gengsinya. Bahkan, konsumtif cenderung mengarah pada gaya hidup glamor, boros, dan hedon. Perilaku konsumtif inilah yang kemudian dianggap biasa dialami saat masa-masa remaja. Budaya konsumerisme lebih banyak memakan kerugian dibandingkan keuntungan. Dampak negatif yang akan ditimbulkan yaitu gaya hidup boros dan mewah, memicu tekanan sosial, memperbanyak angka kemiskinan, terjadi ketimpangan kelas sosial, bahkan akan membuat seseorang malas bekerja, kehilangan semangat, kurangnya keinginan untuk maju dan tidak memikirkan masa depan. Namun, masih tetap ada seseorang yang memilih untuk hidup hemat. Alasan mereka yakni karena ada tujuan keuangan jangka panjang yang telah ditetapkan. Sesekali, seseorang juga dapat membeli barang ses-
uai keinginannya sebagai bentuk apresiasi diri sendiri atas pencapaian yang telah dilakukan— hal tersebut tidak masalah. Ketika dalam keaadan yang tidak menentu, seseorang akan sadar bahwa saving money lebih penting daripada menghabiskannya untuk menuruti gaya hidup hedonisme. Perlu diketahui bahwa gaya hidup hemat itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang usia, status sosial, maupun bidang pekerjaan. Adanya pemikiran yang seperti ini, nantinya seseorang akan memiliki masa depan finansial yang lebih terjamin. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memulai dan menerapkan gaya hidup hemat, yakni menetapkan tujuan finansial yang nyata dan logis, karena hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Kemudian, sebelum membeli barang selalu menganalisis antara kebutuhan atau keinginan. Selanjutnya, memiliki kesadaran untuk menata kehidupan masa depan. Dengan begitu saya sangat paham, gaya hidup hemat perlu diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, tak terkecuali kalangan ekonomi ke atas. Bagaimanapun juga menjadi seseorang yang hemat bukan suatu kesalahan besar. Justru akan memberikan keseimbangan dalam hidup untuk menentukan mana yang dibutuhkan dan diinginkan. Meskipun ini tidak mudah untuk dijadikan kebiasaan untuk semua orang, akan tetapi saya berharap nantinya semua orang tahu masih ada kehidupan masa depan yang perlu diperhatikan.
Kamera saya menangkap lautan manusia yang berkumpul di depan kantor Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), pada Kamis, 28 November 2024. Suara gemuruh menggema, membuncah dari dada ratusan mahasiswa dan pelajar SMK, buntut lemahnya penegakan hukum kasus Gamma, pelajar SMK Semarang yang tewas ditembak oknum polisi.
Banyak tuntutan dibawa massa aksi, terutama bertajuk “Justice for Gamma” dan “Police Everywhere, Justice Nowhere”, begitulah yang tertulis di spanduk usang yang dibawa massa. Tuntutan membentang di depan gedung, diterpa angin sore yang berlalu lalang.
Para mahasiswa berangkat dari kampus masing-masing pada pukul 14:00 WIB, dengan satu tujuan titik kumpul, Polda Jateng. Mereka membawa semangat juang yang membara. Mereka rela berpanas-panasan, berdesakan, dan menantang risiko untuk memperjuangkan keadilan. Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB. Mereka meneriakan yel-yel, lagu perjuangan, dan penyampaian aspirasi. Sebagai bagian dari aksi, massa aksi menggelar reka adegan insiden penembakan. Berusaha menggambarkan kronologi peristiwa penembakan terjadi, sehingga jelaslah peristiwa tragis di malam durjana itu. Sang orator menyampaikan orasi dengan suara yang tegas dan lantang.
“Kami ingin menekankan bahwa penembakan ini benar dilakukan oleh aparat kepolisian. Adapun reka adegan ini dilakukan agar aksi berjalan kondusif,” ujar Akmal, orator aksi.
Akmal juga menjelaskan tujuan dan harapan aksi kali ini, dengan pandangan mata yang serius ke massa aksi.
“Tujuan kami, memojokkan kepolisian dan menciptakan bayangan ke masyarakat, bahwa pernyataan dari kepolisian yang menyebutkan bahwa siswa melakukan tawuran, adalah salah. Harapannya, keadilan hukum berpihak kepada keluarga korban,” tegasnya dengan menggenggam erat mikrofon yang dia pegang.



Tidak hanya mahasiswa, pelajar SMK, rekan Gamma, juga ikut menyuarakan aspirasi dengan lantang di depan ratusan massa aksi.
“Kami di sini untuk menuntut keadilan. Hal yang semakin jarang ditegakkan oleh pihak komersial. Dengan adanya aksi ini, semoga keadilan akan tetap ditegakkan, meskipun tidak sepenuhnya,” kata Satrio, pelajar SMK ketika berorasi.
Aksi damai berlangsung tertib, meskipun sempat terjadi sedikit ketegangan di tengah orasi. Sesekali terdengar teriakan provokasi yang berusaha memecah konsentrasi massa. Namun, situasi ini berhasil dikendalikan hingga aksi selesai. Selain orasi, aksi ini juga diisi pembacaan sumpah mahasiswa dan doa bersama agar negeri ini dijauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat. Ketika malam mulai

menyelimuti, aksi pun berakhir. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib, membawa harapan baru dalam hati. Saya pulang dengan perasaan campur aduk.
Di satu sisi, saya kagum dengan semangat perjuangan mereka. Di sisi sisi lain, saya juga merasa sedih karena melihat ketidakadilan dimana-mana. Tidakkah kau merasakanya?



Oleh: M. Rifqy Rabbani
Sistem pembelajaran memegang peran yang sangat fundamental dalam pendidikan. Sistem pembelajaran juga menjadi salah satu indikator yang sangat berpengaruh terhadap tercapai dan tidaknya capaian pembelajaran. Namun tak ayal sistem pendidikan terkesan dikesampingkan dan terlupakan untuk di evaluasi.
Pemangku pendidikan lebih fokus mengevaluasi kurikulum yang di gunakan namun terkesan melupakan sistem pembelajaran sebagai bentuk implementasinya dikelas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia menggunakan metode presentasi dalam sistem pembelajarannya. Lantas mengapa saya menyebutnya metode presentasi sebagai metode yang basi? Mari kita jawab bersama. Menurut data yang saya dapatkan, metode presentasi telah digunakan dalam sistem
pembelajaran di perguruan tinggi sejak dekade 1950-an, seiring dengan perkembangan metode pengajaran berbasis diskusi dan kolaborasi di kelas. Menurut Smith dan Pollock (2017), metode presentasi mulai diterapkan secara luas di perguruan tinggi setelah reformasi pedagogi di Amerika Serikat yang menekankan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran.
Di Indonesia, metode ini semakin populer sejak implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada awal 2000-an, yang menempatkan keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah sebagai kompetensi inti.
Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 80% perguruan tinggi di Indonesia menggunakan presentasi sebagai bagian dari metode evaluasi dan penilaian dalam mata kuliah utama, den-
gan variasi penerapan mulai dari diskusi kelompok hingga presentasi individu. Studi ini menyoroti bahwa meskipun metode presentasi telah digunakan selama lebih dari 70 tahun, efektivitasnya sering kali bergantung pada keterampilan penyampaian mahasiswa dan dukungan fasilitasi dari dosen. Meskipun presentasi dinilai mampu melatih kemampuan berbicara di depan umum dan mengasah keterampilan analitis mahasiswa, efektivitasnya sering dipertanyakan.
Data menunjukkan bahwa metode ini tidak selalu berhasil meningkatkan pemahaman materi secara mendalam. Sebuah studi oleh Bligh (2000) mengungkapkan bahwa dalam metode presentasi, mahasiswa hanya mengingat sekitar 10% dari apa yang disampaikan dalam waktu 72 jam setelah sesi. Hal ini mengindikasikan bahwa metode ini cenderung
kurang efektif untuk pembelajaran yang membutuhkan pemahaman kompleks dan partisipasi aktif. Selain itu, mahasiswa sering merasa jenuh karena metode presentasi yang berulang, sementara dosen cenderung memprioritaskan evaluasi dari segi performa presentasi ketimbang pemahaman materi. Masalah lain yang muncul adalah ketidakseimbangan partisipasi; beberapa mahasiswa menjadi pasif, sementara yang lain mendominasi sesi. Selain itu masalah lain juga muncul, di era yang serba canggih ini materi yang digunakan presentasi bisa sangat mudah di susun menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI). Hal ini menimbulkan masalah baru bahwa peserta didik tidak benar-benar mencari, membaca, dan menyusun materi prrsentasi yang menyebabkan pemateri tidak mengetahui topik apa yang akan ia bawakan. Situasi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memodernisasi metode pembelajaran agar lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa dan perkembangan teknologi.
Berdasarkan survei yang dilakukan di beberapa universitas, banyak mahasiswa merasa bahwa metode presentasi cenderung lebih menekankan keterampilan berbicara di depan umum daripada pemahaman mendalam terhadap materi. Sebuah studi di Universitas Padjadjaran (2021) menemukan bahwa sekitar 65% mahasiswa merasa kurang memahami materi secara komprehensif karena keterbatasan waktu dalam persiapan presentasi dan pembagian
waktu yang tidak seimbang dalam diskusi kelompok. Dalam teori pembelajaran aktif (Active Learning), mahasiswa seharusnya secara aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya sebagai pendengar pasif.
Menurut teori konstruktivisme oleh Piaget, pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan interaksi. Sementara itu, metode presentasi dapat mendukung hal ini jika diimbangi dengan diskusi mendalam. Namun, teori Zone of Proximal Development (Vygotsky) menggarisbawahi pentingnya peran mentor dalam memfasilitasi proses belajar, yang kadang kala kurang diakomodasi dengan baik dalam sistem presentasi yang terlalu mengandalkan mahasiswa.
Salah satu dampak positif dari sistem presentasi adalah pengembangan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri mahasiswa. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode ini tidak selalu efektif dalam meningkatkan pemahaman substansial terhadap materi. Sebagai contoh, penelitian
di Universitas Gadjah Mada (2020) menunjukkan bahwa hanya 40% mahasiswa merasa presentasi meningkatkan penguasaan materi, sementara sisanya menganggap metode ini hanya efektif dalam pengembangan soft skills.
Apakah Efektif atau Tidak? Efektivitas sistem presentasi sangat bergantung pada implementasinya. Jika diiringi dengan pembimbingan yang tepat, waktu yang memadai, dan evaluasi yang berimbang, sistem ini dapat efektif dalam meningkatkan keterampilan kritis dan analitis mahasiswa. Namun, tanpa unsur-unsur tersebut, sistem ini cenderung lebih menjadi latihan soft skills daripada sarana pembelajaran akademis yang mendalam.

Rifqy Rabbani merupakan mahasiswa
prodi Pendidikan
Agama Islam UIN Walisongo angkatan 2022.

Oleh: Faizul Ma’ali
Istilah “sedekah laut” merujuk pada tradisi yang sangat dikenal di kalangan masyarakat pesisir Pantai Utara Jawa, khususnya di Rembang. Tradisi ini mencerminkan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diperoleh dari hasil laut sekaligus sebagai upaya memohon keselamatan bagi para nelayan. Dalam pandangan Islam dan budaya lokal, sedekah merupakan bentuk pemberian yang mulia. Sedekah memiliki nilai religius dan sosial yang tinggi karena di dalamnya terkandung rasa peduli, tolong-menolong,
serta penghormatan terhadap sesama. Tradisi sedekah laut ini menjadi wujud nyata rasa syukur masyarakat pesisir atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, terutama hasil laut yang menjadi sumber utama penghidupan mereka.
Sedekah laut telah menjadi bagian dari budaya masyarakat pesisir Pantura selama bertahun-tahun. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk pelestarian adat leluhur.
Di Rembang, sedekah laut menjadi agenda tahunan yang rutin digelar pada bulan Muharam, atau yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai bulan Suro. Bulan ini dianggap sakral karena menjadi momen untuk melakukan berbagai aktivitas religius, seperti ziarah, tahlilan, dan bancakan.
Sedekah laut tidak hanya sekadar perayaan, tetapi juga merupakan upaya spiritual untuk memohon keselamatan bagi para nelayan dan keluarganya. Mereka berharap agar dalam menjalankan pekerjaannya di laut, para nelayan diberikan

perlindungan dari segala bahaya, serta mendapatkan rezeki yang halal dan melimpah. Selain itu, tradisi ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan alam, khususnya laut sebagai sumber penghidupan. Sedekah laut juga mencerminkan rasa kebersamaan komunitas pesisir dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tradisi ini menjadi wujud nyata dari nilai-nilai gotong royong dan solidaritas.
Acara Sedekah Laut
Perayaan sedekah laut biasanya dimulai dengan berbagai kegiatan religius. Salah satu acara yang dilakukan adalah manaqiban, yaitu pembacaan doa dan pujian kepada para nabi dan wali. Kemudian, diadakan acara kondangan berupa doa
bersama dan makan bersama di tepi pantai. Acara ini biasanya diorganisasi oleh para pemilik kapal nelayan dan melibatkan seluruh masyarakat pesisir. Setelah acara doa bersama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan hiburan budaya. Hiburan ini sering kali berupa pertunjukan wayang kulit, ketoprak, dan sebagainya. Pertunjukan ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media pelestarian budaya lokal. Masyarakat berbondong-bondong menghadiri acara ini sebagai wujud kebersamaan dan kekompakan.
Puncak dari acara sedekah laut adalah prosesi larung sesaji. Larung sesaji adalah tradisi simbolik yang dilakukan dengan cara melepaskan sesembahan ke laut. Sesembahan ini biasanya berupa kepala kambing, bunga setaman, dan dupa. Prosesi ini dipimpin oleh seorang tokoh desa, seperti Modin
Doc. Internet
atau sesepuh desa, yang memandu jalannya doa. Doa ini biasanya menggunakan bahasa lokal, mencerminkan ciri khas dan identitas budaya masyarakat pesisir.
Makna dari larung sesaji adalah simbol pengembalian rezeki kepada alam dan wujud terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Meski demikian, dalam perspektif Islam, tradisi ini lebih ditekankan pada sisi doa dan rasa syukur, bukan sebagai bentuk ritual kepercayaan kepada makhluk atau kekuatan lain.
Tradisi ini juga menjadi sarana introspeksi bagi masyarakat untuk mengingat kebesaran Allah sebagai Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Dengan demikian, larung sesaji dapat dimaknai sebagai perpaduan antara kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang menanamkan rasa tawakal kepada Allah SWT.
Eksistensi Tradisi Sedekah Laut di Era Modern Walaupun zaman terus berkembang, sedekah laut tetap menjadi tradisi yang hidup di tengah masyarakat pesisir. Tradisi ini tidak luntur meskipun budaya modern semakin mendominasi. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat pesisir.
Sedekah laut tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tetapi juga menjadi identitas budaya yang mencerminkan rasa syukur, kebersamaan, dan harmoni antara manusia dengan alam. Sedekah laut adalah tradisi yang penuh makna.
Bagi masyarakat pesisir, tradisi ini tidak hanya menjadi simbol rasa syukur kepada Allah SWT, tetapi juga sarana untuk mempererat tali silaturahmi.
Dengan melestarikan tradisi ini, masyarakat pesisir Pantura, khususnya di Rembang, turut menjaga warisan leluhur sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dapat berjalan harmonis. Tradisi

ini mengingatkan kita akan pentingnya rasa syukur, kebersamaan, dan penghargaan terhadap alam sebagai sumber kehidupan. Selain itu, sedekah laut menjadi bukti bahwa tradisi lokal dapat berkembang tanpa meninggalkan esensi keimanan kepada Allah SWT. Dengan terus merawat tradisi ini, masyarakat tidak
Doc. Internet hanya menjaga identitas budaya mereka, tetapi juga memberikan teladan tentang bagaimana kebudayaan dapat berperan dalam membangun solidaritas sosial dan kelestarian lingkungan, yang keduanya merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan modern.




Oleh: Ahmad Amirudin, Kru Edukasi 2013
Setelah bertahun-tahun tercampakkan dari negaranya, Agam Wispi pulang. Ia pulang membawa segala kerinduan yang telah dikemas. “di mana kau pohonku hijau,” tanyanya setelah sekian lama berada di negeri asing. Ia sangat antusias bertanya tentang pohon hijau, karet, Chairil Anwar, dan Banda.
Tahun-tahun yang panjang dan jarak beribu-ribu mil membuat ia melupakan cintanya. Ia lupa istrinya, ia juga telah dilupakan istrinya. Ia mungkin juga telah dilupakan anak-anaknya. Pada akhirnya ia memang pulang, tapi ia tak punya rumah. “pulang?/ke mana harus pulang? si burung samudra tanpa sarang”. Hanya puisi tempatnya pulang. “puisi hanya kaulah lagi tempatku pulang/puisi hanya
kaulah pacarku terbang,”tulisnya.
Agam Wispi lahir 31 Desember 1930 di Pangkalan Susu, Sumatera Utara.
Ayahnya adalah Agam
Puteh yang berteman dekat dengan tokoh-tokoh PKI, seperti Tan Malaka dan Muso. Sang ayah juga pendiri partai komunis di Aceh warsa 1920-an. Sebab inilah, Tempo menuliskan Agam Wispi sebagai seorang “Komunis sejak dalam kandungan”.
Cara pandang dan berpikir Agam Wispi banyak terpengaruh oleh sang ayah. Sejak masih SMP (SLP) di Langsa Timur, Aceh Timur, 1945-1949, ayahnya juga telah mengajak Agam Wispi remaja untuk bergabung ke dalam grup sandiwara keliling. Sebagai pemain sandiwara, namanya mencuat
dalam lakon patriotik yang mengisahkan pengkhianatan mata-mata Belanda terhadap tanah air.
Ia berperan sebagai anak yang mencintai tanah air dan membunuh mata-mata tersebut. Inilah yang barangkali berpengaruh besar terhadap cara berpikir Agam Wispi. Hal-hal ini pula yang membuat ia cenderung dekat dengan partai komunis serta yang berhubungan dengannya. Agam Wispi meninggalkan keluarganya, lalu pindah ke Medan, dan meneruskan pendidikan SMA di sana, sembari bekerja di surat kabar kerakyatan. Pada tahun 1951, Bakri Siregar bersama Hr. Bandaharo mengajak Wispi—panggilan Agam Wispi— bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).
Karena ia bersepakat dengan ide-ide Lekra, ia memutuskan untuk bergabung.
Melawan Para Borjuis
“Golongan seniman yang lebih mementingkan realitas,” tulis Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia merupakan ide dasar dalam pendirian organisasi Lekra pada 17 Agustus 1950. Pram juga berkata bahwa organisasi ini dihayati oleh keyakinan akan kebenaran sosialisme. Keberangkatannya juga karena “melihat, meruyak, dan meningkatnya bahaya yang mengancam perkembangan pemikiran di kalangan budayawan dan seniman, dan dengan sendirinya juga sepak-terjangnya”.
Menurut Pram, seni dalam landasan Lekra adalah seni yang beraliran realisme sosialis. Realisme sosialis, seperti yang dikutip oleh Pram dari ucapan Andrei Zidanov, secara garis besar adalah “Kenyataan dan watak historik yang konkret dari lukisan artistik mesti dihubungkan dengan tugas pembentukan ideologis dan pendidikan pekerja-pekerja dalam semangat sosialisme. Metode kerja sastra dan kritik sastra ini kita namakan metode realisme-sosialis.”
Bersama Lekra, landasan ini jugalah yang menjadi metode kerja Agam Wispi dalam membuat karya-karyanya sejak tahun 1951. Pada tahun 1957, ia ditarik ke Harian Rakyat (HR) di Jakarta, dan menjadi pengurus pusat Lekra pada 1959 dan seterusnya. Disebabkan oleh realisme sosialis, secara tidak langsung Agam Wispi juga tidak setuju dengan pilihan Hegel. Karena
Hegel memilih membinasakan seni demi menyelamatkan negara mutlak. Meski Agam Wispi mungkin juga bersepakat pada Hegel bahwa masyarakat borjuis maupun negara kristiani sama tidak kondusifnya bagi perkembangan seni kreatif. Oleh karena ini, Hegel mengusulkan dua pilihan. Pertama—Hegel cenderung memilih ini—seni harus binasa demi menyelamatkan “negara mutlak” atau kedua, pihak kedua ini harus dihapuskan demi memungkinkan kondisi-kondisi baru dunia dan terjadinya Renaisans (pencerahan) baru kesenian. Agam Wispi tentu saja memilih pilihan yang kedua: menghapus borjuis dan negara kristiani (agama). Upaya menghapus atau paling tidak melawan kaum borjuis ini bisa kita baca dalam sebagian besar sajak-sajak Wispi, yang paling terkenal tentu saja sajaknya yang berjudul “matinja seorang petani”. Dalam sajak ini, terlihat jelas Wispi berdiri di mana. Wispi menulis di baitbait akhir sajaknya: “mereka berkata/yang berkuasa/tapi merampas rakyatnya/mesti turun tahta/sebelum dipaksa”.
Sedemikian dahsyatnya sajak ini hingga Presiden Sukarno dan Suharto melarangnya untuk terbit.
“Menurut George Lukacs, kapitalisme telah mengubah kesadaran manusia menjadi kesadaran palsu yang menjauhkan manusia dari eksistensinya yang bebas,” tulis Eka Kurniawan. Akibatnya manusia hanya mempunyai nilai fungsional. Realisme datang sebagai upaya manusia untuk bebas dari keterasingan yang lahir dari kesadaran palsu dan kemudian mengantarn-
ya menuju suatu pemahaman diri sebagai manusia utuh. Menjadi manusia utuh merupakan sebuah impian utama dalam kesenian realisme sosialis. Agam Wispi menulis sajak berjudul “tangan seorang buruh batu-arang”.
Dalam baitnya ia menuliskan: “trem lari-lari anjing dibawah rintik salju/hilang dipengkolan dan derunya tinggal jauh/tangan itu masih melambai kepada dunia/ karena baginya buruh adalah batu-arang/yang dibakar dan membakar/yang apinya menghangati orang orang yang bercinta/” Dari sajak ini, jelas sekali Wispi menghadirkan realisme seorang proletarian dan impiannya: “dalam sedikit kata: aku mau damai”. Bagi Agam Wispi dan seniman-seniman Lekra yang lain, “seni dan ilmu adalah untuk rakyat.”Tentu saja, “bukan seni untuk seni dan ilmu untuk ilmu yang akhirnya adalah seni untuk kantong borjuasi dan ilmu untuk algojo perang”.
Yang terbuang, diasingkan, dan mati sendirian Agam Wispi hidup sendirian di sebuah panti jompo di Daltonstraat, Amsterdam.
F. Aziz, seorang wartawan Pantau.or.id, pernah sekali menginap. Aziz kemudian mendeskripsikan tempat tinggal Wispi sebagai “kandang”. Ia juga menyebutnya sebagai sebuah gudang kecil untuk menangguk ilmu dari berbagai macam khazanah sastra dan seni internasional. Sebagai seorang tamu, si wartawan ragu harus tidur di mana, karena dinding kamar Agam Wispi dikelilingi oleh rak penuh dengan buku dan souvenir yang tumpang tindih tak keruan.
F. Aziz yang antirokok dan antibau rokok sangat sensitif dengan tempat tinggal Agam Wispi, “bau asap tembakau yang minta ampun”. Ia menganggap bahwa orang yang tidak biasa hidup dengan sastrawan dan seniman Bohemian—seperti Agam Wispi— akan enggan untuk makan-minum di rumah semacam ini. Karena, katanya, segala serba sempit, berdebu, dan berantakan.
Semua ini--sempit, berdebu, dan berantakan—tentu saja tidak akan terjadi, jika... ya, semua ini bermula dan disebabkan oleh kudeta militer 1 Oktober 1965. Saat itu Wispi sedang berada di Beijing untuk menghadiri perayaan ulang tahun Republik Tiongkok.
Semasa di Lekra dan menjadi wartawan, Agam Wispi sering bepergian ke berbagai negara. Dari mulai Jerman, Vietnam, hingga Tiongkok. Di Berlin, ia belajar jurnalistik dari tahun 1958-1959. Sedangkan di Vietnam, ketika ditugaskan meliput perang, Wispi bertemu presiden cum penyair Vietnam Ho Chi Minh. Ketika di Vietnam, Mei tahun 1965, Wispi sudah pasrah akan hidup-matinya karena bom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Akan tetapi kenyataan berbicara lain: ia masih tetap hidup.
Bukan di Indonesia, melainkan di Tiongkok—meski ia hidup, keadaan malah lebih parah—ia tak bisa pulang: harapan akan kehidupannya mulai menipis.
Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di tanah airnya, ia masih berharap untuk pulang. Wispi sangat berharap untuk pulang. Kabar yang disiarkan selalu men-
guatkan bahwa ia akan bisa pulang, tapi kenyataan berkata lain: ia tidak bisa pulang, ia telah putus asa untuk pulang. Selama bertahun-tahun hidup di Tiongkok, Wispi bosan dengan selubung gerakan di sana. Ia kemudian pindah ke Jerman Timur di tahun 1970. Dan pada 1973-1978 di Leipzig, ia belajar di Institut fur Literatur, dan bekerja menjadi pustakawan di Deutsche Bucheret. Kemudian pada 1988, ia memilih untuk tinggal di Belanda.
Di masa-masa ini, Wispi merasa berada di awangawang. Karena ia tidak lagi punya akar dan tidak berpucuk. Ia orang indonesia, tapi tidak tinggal di Indonesia. Meski tinggal di Belanda, ia juga bukan orang Belanda. “Saya tidak akan menyanyi “Wilhelmus”, saya akan tetap menyanyi “Indonesia Raya”. Begitulah umpamanya, ya toh? Tapi saya tidak akan menyanyikan “Indonesia Raya” di sini. Nah, itu juga ‘kan?” katanya ketika diwawancarai oleh Hersri Setiawan.
Keadaan di awang-awang ini juga berpengaruh terhadap metode kerja penciptaan puisinya. Wispi tidak akan menulis puisi dengan bahasa selain bahasa Indonesia. Karena bahasa yang dikuasainya adalah bahasa Indonesia. “Saya hanya bisa Bahasa Indonesia,” katanya. Jika memakai bahasa lain, ia takut palsu, dan bisa jadi ditertawakan karena barangkali kosa kata yang dipakai sudah ketinggalan zaman. Agam Wispi mengakui bahwa ia mengalami kendala ketika mencipta puisi karena tidak lagi berada di Indonesia. Sebab puisi-puisi yang telah ditulis Agam Wispi, kebanyakan adalah puisi yang berasal
dari situasi konkret, meskipun ada beberapa yang abstrak. Karena menurutnya dalam mencipta puisi itu, “abstrak dan konkret juga. Konkret dan saya harus… benda-benda konkret itu harus saya bisa dijamah. Saya toh ingin menjamah pasir Indonesia,” katanya.
Meski demikian, Agam Wispi tetap berkeras kepala untuk mencipta sadjak.
Karena, ”menurut saya, puisi itu memberi saya daya hidup.” Wispi tetap ingin hidup karena ia
mau, “melihat bagaimana jadinya semuanya ini. ‘Kan itu ‘kan...Bagaimana semuanya ini terjadi. Jadinya ini nanti. Dan saya mau hidup terus.”
Oleh karena itu bagi Wispi, “merasa bahwa diri ini kreatif, saya pikir, penting sekali. Untuk daya tahan hidup. Kalau itu sudah tidak lagi bisa dirasakan ya, berakhirlah. Sebagai penyair, berarti mati. Sudah mati. Dan saya tidak mau mati. Itulah!”
Akan tetapi, pukul satu tanggal 1 Januari 2003, Agam
Wispi harus tetap mati, meski bukan secara metaforis: “suatu hari: kau mati/dalam sunyi/ tentu! sendirian: sendiri//”.
*) Dicari dari berbagai sumber buku & internet.

Langit sore itu memancarkan semburat jingga keemasan, memberikan kehangatan yang terasa hampir ajaib di tengah hiruk-pikuk jalan kota. Di sebuah persimpangan jalan, dua anak kembar, Aksa dan Aksan, duduk di tepi trotoar dengan wajah penuh harap. Meski identik secara fisik : rambut hitam lebat, mata tajam, dan kulit sawo matang keduanya bagaikan dua kepingan jiwa yang saling melengkapi. Namun, kehidupan tidak memberkati mereka dengan kemudahan.
Sejak bapak dan ibu mereka pergi tanpa pesan bertahun-tahun lalu, Aksa dan Aksan hanya bisa bertahan hidup dengan meminta belas kasihan orang lain. Usia mereka baru menginjak sebelas tahun, tapi dunia yang keras telah membuat mereka belajar lebih cepat daripada anak-anak seusia mereka.
“Aksan, kita makan apa malam ini?” tanya Aksa dengan suara pelan. Ia memeluk lututnya, mencoba melawan dingin yang mulai
merayap.
Aksan menggelengkan kepala. “Aku belum tahu. Kalau kita bisa mengumpulkan cukup uang, mungkin kita bisa beli nasi bungkus di warung Bu Mina.”
Aksa menatap kaleng bekas di samping mereka. Hanya ada beberapa keping uang receh. “Sepertinya belum cukup. Mungkin kita harus mencoba meminta lagi di lampu merah.”
Aksan mengangguk setuju. Mereka berdiri dan berjalan menuju perempatan jalan yang ramai. Di sana, kendaraan berhenti saat lampu merah menyala, memberikan kesempatan bagi mereka untuk meminta bantuan dari pengendara yang lewat. Dengan suara kecil, mereka berkata, “Permisi, Pak, Bu, minta sedikit rezekinya...”
Beberapa pengendara memberikan uang receh, sementara yang lain menggelengkan kepala atau pura-pura tidak melihat. Aksa dan Aksan sudah terbiasa dengan penolakan. Namun, seti-

Doc. Canva
ap kali mereka menerima uang, senyum kecil muncul di wajah mereka, seolah dunia memberi secercah harapan.
Ketika malam tiba, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli dua bungkus nasi. Mereka duduk di bawah jembatan layang, tempat yang sering mereka jadikan tempat beristirahat.
“Hari ini lumayan,” kata Aksa sambil membuka bungkus nasi. “Kita bisa makan kenyang malam ini.”
Aksan mengangguk, tapi matanya menerawang jauh. “Aksa, menurutmu bapak dan ibu pernah memikirkan kita?”
Pertanyaan itu membuat Aksa
EDUKASI
terdiam. Ia menatap wajah kembarannya, yang meski tampak tegar, menyimpan luka yang sama seperti dirinya.
“Aku nggak tahu, San. Tapi aku yakin, suatu hari kita akan punya hidup yang lebih baik. Kita harus percaya.”
Aksan tersenyum tipis.
“Kamu selalu bilang begitu. Kadang aku ingin percaya, tapi rasanya sulit.”
“Kita masih punya satu sama lain,” kata Aksa sambil menggenggam tangan Aksan. “Itu sudah cukup untuk sekarang.” Malam itu, mereka tidur di bawah langit yang gelap tanpa bintang, ditemani suara deru kendaraan yang tidak pernah berhenti. Meski dingin menusuk, mereka saling berbagi kehangatan, seperti yang selalu mereka lakukan sejak kecil. Keesokan harinya, di persimpangan jalan yang sama, mereka kembali mencoba mengais rezeki. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Seorang pria paruh baya dengan wajah ramah menghampiri mereka. “Anak-anak, kalian selalu di sini?” tanyanya. Suaranya lembut, tapi penuh perhatian.
Aksa dan Aksan saling bertukar pandang. “Iya, Pak. Kami sering di sini,” jawab Aksa hati-hati.
Pria itu tersenyum. “Namaku Pak Danu. Aku sering melihat kalian. Kalian tidak punya keluarga?”
Aksan menggeleng. “Bapak dan ibu kami sudah pergi sejak lama.”
Pak Danu menghela napas panjang. “Kalau begitu, bagaimana kalau kalian ikut aku? Aku punya panti asuhan
tidak jauh dari sini. Kalian akan punya tempat tinggal dan makanan yang cukup di sana.”
Mata Aksa dan Aksan membelalak. Harapan yang selama ini mereka pendam tiba-tiba terasa nyata. Tapi, mereka juga ragu. “Apa benar kami boleh ikut, Pak?” tanya Aksan dengan suara hampir berbisik. “Tentu saja,” jawab Pak Danu. “Di sana, kalian juga bisa sekolah dan bermain dengan anak-anak lain. Hidup kalian tidak akan seberat ini lagi.”
Air mata perlahan menggenang di mata Aksa dan Aksan. Mereka mengangguk pelan, lalu menggenggam tangan Pak Danu dengan erat. Di persimpangan jalan itu, hidup mereka berubah. Jalan yang sebelumnya terasa gelap kini mulai bercahaya.
Namun , harapan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk.
Ketika mereka tiba di panti asuhan, suasana yang awalnya terasa hangat mulai menunjukkan kejanggalan. Bangunan besar itu penuh dengan anakanak seusia mereka, namun semua tampak murung dan pendiam. Pak Danu memperkenalkan mereka pada pengurus lain, seorang wanita bernama Bu Mira, yang wajahnya keras dan dingin. “Anak-anak, mulai besok kalian akan diajari bagaimana cara mencari uang di jalanan,” kata Bu Mira tegas. “Ini bukan tempat tinggal gratis. Semua harus bekerja.”
Aksa dan Aksan saling menatap dengan bingung. “Tapi, Pak Danu bilang kami bisa sekolah di sini,” ujar Aksa.
Pak Danu tertawa kecil.
“Sekolah? Hidup itu bukan soal belajar di kelas. Kalian akan belajar cara bertahan hidup. Besok pagi, kalian akan bergabung dengan kelompok lainnya di perempatan jalan. Jangan khawatir, hasil kalian akan membantu panti ini.”
Aksan mengepalkan tangannya. “Jadi, kami cuma disuruh mengemis lagi?”
Pak Danu mendekat, wajahnya yang tadi ramah berubah dingin. “Kalian anak-anak jalanan. Sudah seharusnya tahu tempat. Kalau tidak mau ikut aturan, kalian tidak akan dapat tempat tinggal atau makanan.”
Malam itu, Aksa dan Aksan tidak bisa tidur. Harapan mereka hancur seketika. Mereka menyadari bahwa mereka hanya dijadikan alat untuk mencari uang.
“Kita harus kabur dari sini,” bisik Aksa dengan suara gemetar.
Aksan mengangguk. “Tapi bagaimana? Mereka mengawasi kita terus.”
Mereka mulai merencanakan pelarian di tengah malam. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mengamati gerak-gerik
Pak Danu dan Bu Mira. Namun, satu hal yang pasti—persimpangan jalan yang pernah menjadi tempat mereka bertahan hidup kini terasa lebih aman daripada panti asuhan yang mengerikan ini.
Mereka berdua menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lamanya dengan berjalan kaki. Akhirnya tepat jam 11 dini hari mereka berdua telah sampai di persimpangan jalan yang sama ketika mereka dihampiri oleh manusia berhati iblis.

Setelah sampai disana, aksa yang merasa kelelahan dan kelaparan setelah berjalan kaki pun mengadu pada kembarannya. ”San, aku lapar sekali, aku sudah tak mampu untuk berdiri lagi untuk turun ke persimpangan lagi”.
Aksan yang merupakan kakaknya pun berusaha tetap tegar meskipun ia juga merasakan kelelahan dan kelaparan yang sama, ”ayo sa, kamu istirahat saja biar aku yang turun kesana” ujar aksan sembari menuntun aksa ke bawah jalan tol untuk beristirahat. Dengan
beralaskan kardus yang sebelumnya sudah mereka cari, aksa berbaring dengan lemah dan tak berdaya.
Beberapa menit berlalu, aksan nampak sudah berada di sisi jalan, ia mengais sisa sisa makanan yang berada di tong sampah sebuah restoran di dekat persimpangan. Ia menemukan beberapa makanan sisa, aksan merasa senang karena ia menemukan beberapa porsi makanan yang tidak dihabiskan sang empunya. setelah terkumpul cukup banyak, ia membaginya menjadi dua

bagian dan segera menuju ke seberang untuk memberikannya ke aksa adiknya. Sesampainya diseberang aksan langsung membangunkan adiknya itu, ” Aksa bangun, aku ada nasi nih sedikit buat ganjal perut sampai besok” akhirnya mereka berdua makan bersama deangan ditemani lampu jalan di sisinya.
Bertahun-tahun berlalu, Aksa dan Aksan kini telah beranjak dewasa. Dengan kerja keras, mereka mulai bekerja serabutan, dari menjadi loper koran, kuli panggul di pasar, hingga pelayan di
Doc. Canva
warung makan. Uang yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit digunakan untuk menyewa tempat tinggal kecil dan melanjutkan pendidikan melalui beasiswa.
Aksa berhasil menempuh pendidikan di bidang bisnis, sementara Aksan memilih jalur hukum. Dengan kegigihan dan usaha keras, mereka berhasil mendirikan usaha kecil yang berkembang pesat. Tidak hanya itu, Aksan yang telah menjadi pengacara sukses, membantu banyak anak jalanan mendapatkan keadilan.
Kini, mereka tidak lagi harus meminta-minta di jalanan. Mereka menggunakan keberhasilan mereka untuk membantu anak-anak jalanan lainnya, mendirikan panti asuhan yang benar-benar memberikan kasih sayang dan pendidikan.
Di suatu senja, Aksa dan Aksan berdiri di depan panti asuhan mereka, melihat anakanak tertawa bahagia. “Kita berhasil, San,” kata Aksa.
Aksan tersenyum. “Ya, kita berhasil. Kita tidak akan membiarkan anak-anak lain mengalami apa yang pernah kita alami.”
Langit sore itu kembali memancarkan semburat jingga keemasan, sama seperti saat mereka masih kecil. Namun kali ini, mereka tidak lagi menatapnya dengan harapan kosong. Mereka telah menciptakan harapan itu sendiri.

Muqtafa Deka Yunensa merupakan kru edukasi angkatan 2023.
Pada suatu pagi yang teduh, secercah sinar dari mentari mulai menghangatkan tubuh ini. Awan yang mendung sehabis hujan dini hari, membuat suasana di hari itu terasa begitu menenangkan.
Aku baru saja membuka pagar rumahku, dan hendak berjalan pagi menikmati hari minggu yang tak seperti biasanya. Pagi itu terasa seperti menghirup udara baru, udara yang sudah lama aku impikan semenjak deretan besi-besi berjalan di jalanan beraspal.
Suasana jalanan pada saat itu cukup lengang, bisa dihitung hanya beberapa kendaraan yang melintas, selebihnya banyak yang berjalan kaki untuk sekadar mengecap rasa yang sudah lama hilang.
Aku berjalan di sekitar
Taman Masa Lalu, tempatnya teduh menenangkan karena banyak ditanami pohon trembesi di sekitar jalan masuk taman. Pada pusat taman terdapat kolam kecil dengan air mancur di tengahnya, arsitekturnya yang ikonik banyak dikenali oleh berbagai kalangan, sebab itulah yang kebanyakan dipikirkan oleh para arsitek taman. Terdapat sice panjang yang mengelilingi air mancur dan diletakan agak jauh dari kolam, letaknya ini dimaksudkan untuk menghindari basah karena percikan air.
Taman Masa Lalu, tak tahu mengapa taman itu dinamai dengan nama itu,

rasa-rasanya orang zaman dulu sekenanya saja menamai sebuah tempat. Tentang nama itu, banyak kabar burung yang beredar, tetapi yang paling masyhur di antara banyaknya kabar burung itu hanya ada dua cerita. Yang pertama mengatakan konon taman tersebut sudah ada sejak zaman purbakala, dan dulu taman ini jadi tempat singgah bagi para hewan-hewan raksasa. Mungkin saja ada benarnya, tetapi cerita yang satunya lagi mengatakan bahwa dinamakan Taman Masa Lalu sebab banyak dari para pengunjung yang berpelesir di taman ini, atau hanya
sekadar melintas saja tiba-tiba teringat akan kenangan yang semestinya dilupakan, kenangan yang dapat membuat siapapun tersedu-sedu jika berlama-lama berada di taman ini. Yang terakhir ini lebih dipercaya kebanyakan orang.
Aku berdiri di seberang air mancur, menilik orang-orang yang tengah sibuk dengan dirinya masing-masing, ada yang sedang bercengkrama dengan lawan bicaranya, ada yang bermain-main di sekitar air mancur, bahkan ada pula yang sibuk bercericau sendiri.

“Jangan terlalu berharap pada orang lain selain dirimu seorang, Rangkat” celetuk Songko di belakangku yang kedatangannya membuat diri ini hampir kena serangan jantung.
Ia melanjutkan bicaranya
“Walaupun orang yang hendak kau gantungkan harapan padanya sudah mengenalmu 100 tahun lamanya, semua bisa sirna dengan sekejap mata.”
“Behhh kau ini, macam sudah hidup 100 tahun saja,” bantahku dengan wajah kecut.
“Lihat orang yang di sana itu Rangkat, kondisi orang itu seperti plesetan nama-
mu dari kata Rungkat, hahaha?” Sambil menunjuk orang paruh baya di sudut taman yang duduk termangu sendirian dengan tatapan kosong.
“Oh bapak yang ada di pojok sana, memangnya ada apa dengan dia, kau anak asuhnya?”
“Hushh sembarangan saja kalau bicara, kalau mau tahu dia siapa ikutlah denganku, biarku tunjukkan siapa bapak itu sebenarnya.”
Aku pun terpaksa mengikuti Songko, ia berjalan lurus ke depan berlagak seperti seorang penyintas yang baru saja lolos dari ke-
jaran malaikat maut. Kami menuju seorang paruh baya di seberang taman, dan mulai menjaga jarak tak jauh dari keberadaan bapak itu. Lamat-lamat kami mendengar suara lirih, kalimat yang keluar dari mulutnya menyiratkan kondisinya sekarang, nada bicaranya menunjukkan kepasrahan dan keputusasaan.
“Ada banyak ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia yang mati sia-sia karena menggantungkan diri pada harapan, mereka terlalu bodoh percaya pada manusia selain dirinya, tak sadarkah mereka bahwa di dunia ini tak ada yang bisa mereka harapkan selain dirimu seorang,” sorot matanya menunjukkan semua masalah yang telah terjadi padanya.
Aku penasaran, hal apa yang telah terjadi pada orang itu, seolah sudah pupus harapan dalam menjalani sisa-sisa dari kehidupannya. Aku coba menghampiri dan berharap jawaban dari yang aku bingungkan.
“Mengapa bapak sampai meratapi nasib yang sudah terjadi, bukankah masa lalu tidak usah diambil pusing?” Aku memberanikan diriku, walau berpikir pertanyaan semacam ini terlalu bodoh untuk memperoleh jawaban dari orang yang jiwanya telah direnggut oleh kenangannya.
“Nak, kau masih terlalu dini untuk mengerti,” jawabnya singkat dengan

penuh ketenangan. Pikirku, bodoh betul aku ini, hampir saja kutarik pertanyaanku di awal, tetapi orang ini kemudian melanjutkan bicaranya.
“Kau mau tahu nak mengapa aku bicara sendirian begini? Sudah banyak yang menganggapku gila karena terus-terusan berucap tanpa ada yang kuajak bicara. Baru kali ini ada yang bertanya padaku setelah seminggu aku berada di
sini. Ya, seminggu sejak aku berkunjung ke Taman Masa Lalu ini, benar kata cerita itu, aku kembali teringat masa lalu di mana aku bergantung pada Sahabatku, dia teman masa kecilku, dan sudah bersamaku setengah Abad lebih. Sekarang lihatlah yang terjadi padaku, aku ditinggal sendirian di sini sejak ia sibuk dengan pekerjaannya.”
“Semua orang memang pu-
nya pekerjaan masing-masing bapak, dan sudah sepatutnya sibuk dengan dirinya masing-masing, mengapa harus dipikirkan sepilu ini?” Tanyaku dengan penuh rasa penasaran. “Memang tak perlu dirisaukan begini, tetapi kejadian sepekan lalu membuatku selalu teringat, kejadian saat dia meninggalkanku begitu saja. Sebegitu sibuknya sampai lupa sahabatnya ini sudah lama ingin bertemu
dengannya.” ia berhenti sejenak menghembuskan nafasnya. Lalu melanjutkan ceritanya kembali.
“Saat itu aku hendak berkunjung di rumahnya yang letaknya di seberang kota tempat tinggalku. Aku pun berniat untuk menginap di rumahnya sembari bernostalgia di lingkungan masa kecilku. Aku sudah lama pindah rumah semenjak punya pekerjaan sendiri sebagai seorang buruh pabrik, dan pada saat setelah aku sampai berkunjung ke sini, dia tak menghiraukanku dan meninggalkanku begitu saja.”
“Memangnya sesibuk apa dia, sampai melupakan segalanya?” Tanyaku coba mendapat penjelasan.
“Yang aku tahu, sekarang dia sudah jadi pejabat
kota, sudah jarang sekali aku berkabar dengannya. Apa sudah malu kah dia dengan diriku yang hanya bekerja sebagai buruh pabrik? Begitukah memangnya sifat seorang pejabat terhadap rakyatnya, sampai sahabatnya sendiri tak digubris begini? Tak dapat membayangkan sebegitu nelangsa rakyat yang hidup di selingkungnya.”
Aku membatin, kalau ditinggal begitu baiknya langsung cari tempat bernaung saja sekenanya, kan masih banyak di luar sana, kalau tidak begitu langsung pulang saja apa susahnya.
Ia masih saja meneruskan ceritanya, tetapi kali ini kata-katanya seolah ingin memotivasi kami berdua, wajahnya tenang menun-
jukkan sedikit ada kelegaan setelah mengeluarkan keluh kesahnya.
“Ya memang begini jadi manusia, terlalu berharap pada sesama akan membuatmu sirna dalam kubangan asa, sebaliknya terlalu mengabaikan harapan hidupmu tidak akan punya tujuan. Camkan itu baikbaik nak, sebelum tersesat dalam masa mudamu, dan berakhir di Taman Masa Lalu sepertiku.”
Kata-katanya menusuk tepat pada jantung hatiku, aku terperanjat dan segera pergi meninggalkan Songko yang ternyata sudah terpaku mati, ia menangis sejadi-jadinya, merengek seperti bayi yang ditinggal ibunya. Saat ini Ia sudah terjebak ke dalam Taman Masa Lalu.


Dialog Ragam Problema (Diorama) akan memeberikan solusi permasalahan kehidupan
Anda. Rubrik ini diasuh oleh Dr. Abdul Wahib, M.Ag., Pakar Psikologi agama UIN Walisongo Semarang. Kirim pertanyaan Anda seputar pencarian jati diri, aledemik, keluarga atau apapun ke surel eduonline@gmail.com
Pak Wahib yang saya hormati.
Suatu ketika teman saya curhat, kenapa dia tiba-tiba dijauhin teman-teman yang lain. Dan saya baru dapat jawabannya ketika teman saya yang lain curhat ke saya. Ternyata banyak yang bilang kalau teman saya dijauhi karena suka mencuri barang orang lain. Padahal setahu saya berita tersebut masih rumor, belum ada bukti yang jelas juga. Pertanyaan saya, mengapa mahasiswa yang seharusnya menjadi pioneer dunia akademik masih mudah di manipulasi, disetir, dan diprovokasi?
Gordon
Jawaban untuk Gordon
Waalaikumsalam Gordon
“Sebelumnya pertanyaannya itu masih absurd soalnya belum jelas Siapa yang menyetir dan memprovokasi, Jawaban yang paling memungkinkan itu kemandirian yang bersangkutan itu aslinya masih dipertanyakan Jadi jika seseorang itu masuk ke dalam fase kedewasaan itu kan harus belajar menegakkan kemandiriannya jadi walaupun diprovokasi itu tidak gampang kalau orang itu masih gampang di provokasi artinya masih ada


Pak Wahib yang saya hormati.
Ketika pertama kali saya masuk UIN, terlintas di benak saya bahwa label UIN kan Universitas Islam Negeri, yang mana seharusnya mengadopsi islam secara keseluruhan, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Islam di Indonesia banyak sekali kelompoknya. Tapi kok saya mendapati beberapa mata kuliah kegaamaan yang ada di UIN hanya berdasarkan satu kelompok saja, yaitu asy’ari. Kenapa dunia perkuliahan masih terdapat doktrin kekelompok-an tertentu yang tersebar luas?
-Salam
“Sebelumnya yang di doktrin itu siapa? bahwa semua orang itu punya kelompok doktrin tertentu, itu jawabannya Iya kemudian, bagaimana dosen itu menyebarkan dokter tersebut di publik saya tidak bisa membayangkan yaa, karena kita dihadapkan dengan mahasiswa yang punya kemandirian, sehingga orang itu tidak bisa mendoktrin. seharusnya tidak segampang itu dari sisi mahasiswa, itu kan adanya dia di doktrin tertentu, karena dia bisa di doktrin, dengan begitu memudahkan kalau mahasiswa itu sudah Cukup Mandiri atau mungkin tidak segampang itu, kalau dia di doktrin, semisal pertanyaannya
itu untuk mengapa dosen melakukan doktrin di kelas atau di kalangan mahasiswa atau Kenapa mahasiswa itu di doktrin? ya jawabannya kalau mahasiswa punya kemandirian punya ke penolakan dosen akan pikir-pikir kalau mahasiswanya itu kut kelompok tertentu, itupun ya aslinya hal yang wajar. Dosen mendoktrin di perkuliahan atau dalam perkuliahan itu dikarenakan adanya kepentingan atau yang mendoktrin berkepentingan untuk menyebarkan dokternya, dan juga mahasiswa menyebarkan doktrinya serta mahasiswa itu bisa di doktrin jika dosen tidak punya kepentingan tersebut jadi mahasiswa sudah kebal imun tidak akan segampang itu di doktrin”.

terhadap Kelompok Luar: Kecenderungan individu untuk lebih kritis terhadap pihak di luar kelompoknya.
Pak Wahib yang saya hormati.
Ada salah satu mahasiswa curhat dengan saya mengenai Mengapa banyak mahasiswa hanya menunjukkan sikap kritis terhadap orang atau pihak yang bukan bagian dari kelompoknya, namun cenderung lebih lembut atau bahkan membela kebijakan yang diambil oleh pihak yang merupakan bagian dari kelompoknya sendiri? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini dalam konteks dinamika sosial.
-Hamba Allah
“Ada kritisisme ada kreativitas orang yang kreatif itu akan mengendalikan sifat kritis semisal kalau Budi nilainya Cuma 7 maka orang-orang yang kreatif tidak perlu mengkritik si Budi tetapi orang itu akan membuat karya yang nilainya 8 Ya omong kosong Kalau Budi mengatakan si orang lain itu nilainya jelek nilainya Cuma 7 kalau yang dia buat itu nilainya 6 kenapa kamu harus ngomong orang lain itu nilainya 7 orang kamu aja nilainya 6 orang-orang kreatif tidak akan mempermasalahkan orang-orang yang nilainya 7 tetapi menuntun dirinya
sendiri punya nilai 8 seakan tunjukkan kepada kamu bahwa saya punya nilai 8 tidak perlu mengkritik orang lain nilainya 7 itu tidak usah jawabannya itu ada dua karena kecemburuan pada orang lain dan kemiskinan kreativitas karena orang kreatif tidak akan membuang-buang waktu untuk mengkritik orang lain Jangan pernah kritik orang lain ketika kamu sendiri itu masih minim kepada waktu kamu tidak digunakan untuk membuat karya yang lebih baik lagi”.

Pak Wahib yang saya hormati.
Berawal dari cerita kakak kelas saya alumni dari universitas di Timur Tengah yang mengatakan bahwa disana tidak ada karya ilmiah sebagai tugas akhir, dari situ saya bertanya-tanya mengapa Indonesia masih mewajibkan karya ilmiah sebagai tugas akhir disaat univer-
sitas di luar (seperti timur tengah) tidak mewajibkannya? Apa urgensi dari karya ilmiah bagi para calon S1? -MBS
“Sekedar membedakan dengan anak-anak SMA dan untuk meningkatkan mutu maupun kualitas Selain itu membuat karya ilmiah itu juga kan membuat orang yang mempunyai banyak pengalaman dan pengala-
Kurangnya Kesadaran Mahasiswa
Terhadap Kebersihan
Pak Wahib yang saya hormati.
Ketika saya menjadi salah satu mahasiswa disini, saya sering melihat dan terlintas di benak saya mengapa kebiasaan membuang sampah sembarangan banyak dijumpai di kawasan kampus yang dipenuhi akademisi dan akademisi, padahal mereka seharusnya masih
memiliki kesadaran yang lebih tinggi terkait pentingnya menjaga calon kebersihan dan lingkungan? Apa faktor yang menyebabkan kebiasaan tersebut tetap ada meskipun sudah ada fasilitas?
-NS
man itu sangat berharga kita tidak perlu memperdulikan kalau timur tengah itu gini-gini nggak ada karya ilmiah atau apapun itu urusan mereka Tapi kita masih berasumsi bahwa pengalaman itu perlu dimiliki setiap mahasiswa”.
“Contohnya saja dari segi kebersihan kamar mandi atau WC mahasiswa itu yang makai itu siapa orang yang makai itu mahasiswa sendiri kok pada protes kepada kami tentang kebersihan itu maksudnya itu mereka itu gimana Jadi intinya mereka itu minum kesadaran dari mahasiswanya
sendiri karena perilaku mahasiswa sendiri terus kadang itu sering menyalahkan kepada pihak yang bersangkutan lihat saja latih kelas itu sering kotor sekali banyak sampah dan kelas itu yang makai siapa kembali lagi ke mahasiswanya kan jadi permasalahannya itu ada di mahasiswa kurangnya kesadaran diri atas

Pak Wahib yang saya hormati.
Di Indonesia, pendidikan tinggi semakin dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing global. Namun, meskipun banyak kalangan yang menyadari pentingnya pendidikan tinggi, masih banyak pelajar yang kesulitan mengaksesnya karena terbatasnya dukungan pemerintah, baik dari segi biaya maupun fasilitas.
-Olafz

“Kalau mereka menganggap bahwa pemerintahan itu hanya kasih bantuan sedikit sekarang bandingkan biaya di Indonesia dengan di luar negeri itu berapa ratus juta sekarang kita berapa Bukankah itu sudah ada subsidi dari pemerintah Jangan tanyakan kemudian kita dapat bantuan berapa dibandingkan saja kamu kuliah di Indonesia dengan
di Singapura dengan di Malaysia maupun di Amerika di sana itu ratusan juta kita paling berapa, kenapa bisa gitu ya karena kita itu ada unsur bantuan pemerintah, bayangkan saja kalau tidak ada bantuan pemerintah jadi jangan membayangkan kalau bantuan itu hanya sekedar kita mendapat nominal berapa”.


Cantik itu Luka merupakan karya Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Novel ini menggabungkan nilai realisme magis dengan sejarah kelam Indonesia. Novel ini bermula dengan kebangkitan Dewi Ayu dari kuburannya setelah 21 tahun meninggal.
Di ceritakan, Dewi Ayu memiliki kecantikan yang sangat elok yang paling cantik di kota Halimunda yang menjadikan Dewi Ayu seorang pelacur bagi para tentara Jepang dan Belanda pada masa kolonialisme. Dalam pekerjaannya menjadi pelacur, Dewi Ayu memiliki empat anak yang tidak di ketahui pasti siapa ayahnya. Walau begitu, Dewi Ayu sangat menikmati pekerjaannya itu.
Saat ketiga anaknya sudah lahir, Dewi Ayu menyadari bahwa ketiga anaknya memiliki kecantikan yang tak kalah
Judul : Cantik itu Luka
Penulis Buku : Eka Kurniawan
Penerbit : Gramedia Pustaka
Utama
Tahun Terbit : 2002
Tebal Buku : 505 Halaman
cantiknya seperti dirinya, menjadikan ketiganya juga menjadi seorang pelacur. Saat Dewi Ayu mengandung anak keempat, dirinya berkeinginan untuk menggugurkan dan membunuh bayi yang berada di kandungannya, tetapi dengan segala cara yang di lakukannya, anak keempat dalam kandungannya tetap masih bernafas.
Upaya yang di lakukan Dewi Ayu sia-sia, sampai-sampai dirinya membiarkan anak keempat lahir, tetapi dirinya selalu berdoa agar anak keempatnya memiliki wajah buruk rupa, upaya Dewi Ayu untuk menjalankan keinginannya agar berhasil, dirinya rela meminum 5 butir paracetamol secara langasung dan menusuk perutnya dengan kayu hingga terjadi pendarahan selama 2 hari.
Saat anak ke-empat sudah lahir, tanpa melihat wajahnya
yang ternyata sangat buruk rupa, bahkan menyerupai seongkok tai, hidungnya seperti colokan listrik, sekujur tubuhnya hitam legam dan mulutnya seperti lubang celengan babi, telinganya seperti gagang panci dan yang melihatnya, akan membayangkan monster kutukan neraka. Siapapun yang melihatnya pasti tidak tahan untuk tidak mual dan muntah Dewi Ayu menamai bayinya dengan nama “cantik”. Setelah kelahiran Cantik, Dewi Ayu meninggal dan Cantik hidup bersama Rosinah—si gadis bisu yang melayani Dewi Ayu bertahun-tahun. Perlu di ketahui, bahwa Rosinah ini, di dapatkan Dewi Ayu karena telah bersetubuh dengan seorang pria, dan pria itu menyerahkan anaknya yang bisu sebagai bayaran atas perbuatannya itu.
Anak pertama Dewi Ayu
bernama Alamanda, yang menikah dengan Sang Shodanco. Anak kedua, Adinda menikah dengan Kamerad Kliwon. Anak ketiga, Maya Dewi menikah dengan Maman Gendeng. Keempat anak Dewi Ayu mengalami kisah percintaan yang tragis, cinta segitiga, penderitaan dan kutukan bahkan sampai ke cucu Dewi Ayu yaitu Nurul Aini (putri Alamanda dengan Shodanco), Krisan (putra Adinda dan Kamerad), Rengganis (putri Maya Dewi dan Maman Gendeng).
Setiap putri dari Dewi Ayu, kisah percintaan dari mereka tidak ada yang mulus-mulus saja. Seperti halnya Alamanda, yang berakhir menikah dengan Shodanco. Shodanco sangat mencintai Alamanda, tetapi, Alamanda mencintai Kliwon. Segala macam cara Alamanda lakukan agar dirinya tidak di sentuh oleh Shodanco. Bahkan, Alamanda rela memborgol kemaluannya agar tidak di perkosa oleh Shodanco. Kisah percintaan Putri kedua dari Dewi Ayu juga tidak kalah rumitnya. Adinda menikah dengan Kamerad Kliwon. Adinda yang mencintai Kamerad terlebih dahulu, walaupun di akhir Kamerad akhirnya juga mencintai Adinda. Kisah percintaan putri ke-tiga Dewi Ayu, yaitu Maya Dewi yang menikah dengan Maman Gendeng. Entah bagaimana pernikahan inii terjadi, yang jelas usia mereka terpaut sangat jauh, hingga Maman Gendeng rela menunggu lima tahun untuk bisa melakukan ritual pernikahan dengan Maya Dewi. Walau begitu, Maman Gendeng selalu berperilaku baik dengan Maya Dewi, bahkan di ceritakan Maman Gendeng
EDUKASI
sering menemani Maya Dewi bermain drama dan mengantar sekolah.
Perlu di ketahui bahwa ketiga menantu dari Dewi Ayu— Shodanco, Kamerad Kliwon, dan Maman Gendeng—ketiganya pernah tidur bersama dengan Dewi Ayu.
Kisah percintaan yang tak kalah rumitnya yaitu antara Nurul Aini, Krisan dan Rengganis yang Cantik dan Cantik. Ketiganya adalah cucu dari Dewi Ayu dan yang ke-empat adalah anak terakhir Maya Dewi. Kisah percintaan mereka yang terhalang kasih sayang sampai menjadikan tumpah darah, dan kisah cinta segitiga merupakan bagian yang paling epik dan sukar untuk di jelaskan dalam resensi ini.
Nurul Aini, Krisan dan Rengganis adalah teman. Tetapi, seperti pada kebanyakan teman, tidak ada rasa biasa-biasa pada teman cepat atau lambat. Rengganis menyukai Krisan, Krisan menyukai
Nurul Aini atau biasa di panggil Ai, dan Ai menyukai anjing. Bahkan, Krisan sampai cemburu kepada anjing. Kecemburuan Krisan, sampai membuat mala petaka, bahwa dirinya sampai membunuh Ai hanya atas nama menyayangi. Rumitnya kisah cinta mereka bertiga, ternyata tidak hanya sampai disitu, Cantik juga terseret masuk kedalam rumitnya kisah cinta mereka, membuat teka-teki yang seperti tidak ada habisnya. Apakah ini yang dinamakan kisah segi empat?
Dalam cerita Novel ini, Eka Kurniawan menggunakan narasi yang komplek dan dengan alur campuran. Diksi yang di tulis juga tergolong blakblakan dan vulgar seperti saat
menceritakan pembunuhan, seksual, cacian dan makian, menjadikan novel ini mungkin kurang cocok dibaca semua kalangan.
Pesan tersirat yang disampaikan Eka
Kurniawan dalam Novel “Cantik itu Luka” bahwasannya keindahan dan kesedihan, sebab dan akibat, karma pasti berlaku.
Setiap karakter yang di ceritakan dalam novel ini juga sangat komplek dan mendalam membuat semua tokoh mudah di ingat.
Novel ini juga telah di terjemahkan lebih dari 34 bahasa dan menjadi bestseller internasional. Novel ini mendapatkan penghargaan seperti World Readers pada tahun 2016 dan Prince Claus Awards pada tahun 2018. Karya ini juga masuk dalam daftar 100 buku terkemuka versi The New York Times. Dan Eka Kurniawan mendapat julukan The Next Pramoedya Ananta Toer.kan kru edukasi angkatan 2021.


Soeraja terbaring lemah di kasur, matanya terpejam namun memori saraf dan ingatannya seolah memutar ulang rekaman tentang seorang perempuan anggun dengan jari tangannya yang menjepit sebatang kretek yang mengepul. Dalam mimpinya, perempuan itu tampak berjalan anggun di sebuah acara yang terlihat seperti pesta. Tiba-tiba Soeraja terbangun dari tidurnya, tubuhnya bergetar, dan mulutnya berkomat-kamit menyebut dua kata yang lebih terdengar seperti sebuah nama: Jeng Yah. Dua kata itulah yang menjadi kata terakhir yang diucapkan Soeraja sebelum ajalnya. Dua kata yang menjadi misteri besar bagi ketiga anaknya: Lebas, Karim, dan Tegar. Rasa penasaran mendorong Lebas untuk mencari tahu siapa Jeng Yah sebenarnya, yang akhirnya membawanya menelusuri
jejak kehidupan ayahnya di masa muda, ketika Soeraja adalah seorang pemuda penuh ambisi yang jatuh cinta pada seorang perempuan bernama Jeng Yah. Hubungan mereka terjalin di tengah suasana politik dan sosial yang penuh gejolak, termasuk perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan perubahan besar dalam industri kretek. Itulah sepenggal sinopsis pengantar dari film serial Gadis Kretek, yang malang-melintang di platform Netflix. Sebagai seorang bocah yang lahir di Kabupaten Kudus, dimana terkenal dengan julukannya “Kota Kretek”, penulis tertarik untuk menguliti lebih dalam mengenai serial ini. Disutradarai oleh dua sejoli Kamila Andini dan Ifa Isfansyah, serial ini mengadaptasi novel dengan judul yang sama karya Ratih Kumala. Mengusung tema yang menonjolkan feminisme seperti
di film lain seperti Kartini dan Siti, Gadis Kretek membawa unsur segar dengan menunjukkan kegiatan utama yang menjadi jalan utama film ini, yaitu kegiatan di pabrik rokok atau kretek, dimana di zaman sekarang, dianggap tabu apabila perempuan bermain-main dengan kretek atau rokok. Cerita dimulai dengan membawa penonton ke masa muda Soeraja. Saat itu, ia adalah seorang pemuda idealis yang penuh gairah, terlibat dalam berbagai gerakan kemerdekaan dan juga sedang memulai kariernya di industri kretek. Di tengah perjuangan hidupnya, ia bertemu dengan Jeng Yah, seorang perempuan yang cerdas, berani, dan penuh pesona. Jeng Yah adalah sosok perempuan yang menjadi inspirasi besar dalam hidup Soeraja. Ia tidak hanya mendukung ambisi Soeraja tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dunia kretek, Doc. Internet
Cerita dimulai dengan membawa penonton ke masa muda Soeraja. Saat itu, ia adalah seorang pemuda idealis yang penuh gairah, terlibat dalam berbagai gerakan kemerdekaan dan juga sedang memulai kariernya di industri kretek. Di tengah perjuangan hidupnya, ia bertemu dengan Jeng Yah, seorang perempuan yang cerdas, berani, dan penuh pesona. Jeng Yah adalah sosok perempuan yang menjadi inspirasi besar dalam hidup Soeraja. Ia tidak hanya mendukung ambisi Soeraja tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan dunia kretek, yang menjadi latar belakang penting dalam cerita.
Cinta mereka berkembang di tengah situasi politik yang penuh gejolak, termasuk pergolakan sosial pasca-kemerdekaan dan dampaknya terhadap industri rakyat seperti kretek. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ada konflik yang muncul, baik dari tekanan eksternal maupun perbedaan pilihan hidup yang akhirnya memisahkan mereka. Soeraja, yang tidak pernah benar-benar melupakan Jeng Yah, memilih jalan hidup lain yang membawanya pada kesuksesan, tetapi meninggalkan luka mendalam di hatinya.
Perjalanan Lebas untuk mengungkap siapa Jeng Yah membawanya ke berbagai kota di Jawa, termasuk ke desa-desa kecil yang menjadi pusat industri kretek tradisional. Dalam perjalanan ini, Lebas tidak hanya menemukan fakta tentang hubungan ayahnya dengan Jeng Yah, tetapi juga belajar tentang akar budaya kretek yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Lebas menemukan bahwa kretek bukan hanya sebuah produk, tetapi juga simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan identitas dan kemandirian ekonomi. Melalui kisah Jeng Yah, ia juga menyadari bahwa di balik kesuksesan ayahnya terdapat pengorbanan besar dan
EDUKASI
cinta yang tak pernah pudar. Salah satu yang paling disorot dari serial Gadis Kretek adalah menceritakan bagaimana perjuangan perempuan untuk mewujudkan mimpinya di dunia patriarki. Dan hal ini tercermin hingga sampai ke bagian pengemasan karakter dalam serial ini. Berbeda dengan film atau serial pada umumnya, yang mengemas karakter dengan protagonis, antagonis, atau tritagonis, Gadis Kretek lebih menonjolkan karakter menjadi karakter yang menolak, mendukung, atau netral terhadap budaya patriarki. Kamila Andini dan Ifa Isfansyah sebagai sutradara film, serta Ratih Kumala sebagai penulis mencoba merepresentasikan tokoh Dasiyah atau Jeng Yah sebagai perempuan yang berjuang dalam masyarakat patriarki. Meskipun begitu, Film Serial Gadis Kretek malah menunjukkan adanya dominasi patriarki yang melemahkan perempuan itu sendiri. Nilai-nilai patriarki yang terlihat jelas dari berbagai hambatan yang dialami seorang perempuan untuk mendapatkan hak nya untuk mewujudkan mimpinya karena budaya patriarki yang mengakar di masyarakat tempat tinggal Dasiyah.
Dasiyah, yang menolak budaya patriarki yang melekat kuat, tidak hanya di lingkungannya, tetapi juga di keluarganya. Dasiyah memiliki pemikiran yang berbeda daripada perempuan seusianya kala itu. Melalui monolog dan dialognya, Dasiyah ditunjukkan tidak mau melayani dan hanya menjadi pendukung kaum laki-laki saja. Dasiyah ingin membuat sesuatu. Dasiyah ingin dilihat sebagai seorang manusia yang utuh dan ikut berkontribusi di masyarakatnya. Dasiyah juga gigih untuk memperjuangkan keinginannya tersebut.
periode 1960-an, tim pembuat film menunjukkan kepada khalayak popularitas dan cara pandang masyarakat terhadap kretek lokal serta gejolak politik yang terjadi di Indonesia, khususnya pulau Jawa pada saat itu. Namun serial ini tidak hanya fokus pada satu latar waktu Sejak menit pertama, episode pertama, penonton akan dibuat berdecak kagum dengan transisi latar waktu yang begitu smooth antara medio 1960-an, zaman kolonialisme Belanda, dan zaman setelah tahun 60-an. Adanya dua latar waktu yang saling berhubungan seolah mengajak penonton untuk menumpang kapsul waktu, berlari antara latar waktu yang satu ke yang lain, namun tanpa membuat penonton bingung. Pun begitu, satu hal yang perlu disorot adalah penggunaan beberapa properti yang penulis rasa tidak selaras dengan tahun 60-an, misalnya penggunaan mesin monitor elektrokardiogram di episode pertama yang terlalu modern dan agak tumpang tindih dengan kondisi rumah yang sudah sesuai dengan latar yang diangkat. Meski begitu, serial ini adalah salah satu serial Indonesia terbaik yang sarat dengan kisah cinta, sejarah, hingga nilai sosial yang terkandung di dalamnya.

Berkonsep unsur historis dan budaya Jawa yang berlangsung pada

perundungan dalam dunia pendidikan Indonesia merupakan kasus darurat yang seolah diabaikan oleh pemerintah. Akibatnya, jumlah pelaku dan korban perundungan terus meningkat dari waktu ke waktu. Perundungan merujuk pada perilaku yang bertujuan menakut-nakuti atau mengancam seseorang melalui perilaku, perlakuan, atau ucapan. Hal ini mencakup kekerasan secara fisik dan mental. Mengucilkan atau menyebarkan gosip tentang seseorang juga termasuk dalam tindakan perundungan. Perundungan memiliki dampak yang luas, mencakup kesehatan fisik, psikologis, serta berimbas pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Di berbagai sekolah, perundungan terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal, fisik, maupun melalui media sosial. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi para siswa. Meski upaya pencega-
han terus dilakukan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diselesaikan untuk menangani permasalahan ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak hingga Agustus 2023. Dari total tersebut, terdapat 87 kasus anak menjadi korban bullying atau perundungan, 24 kasus diantaranya melibatkan anak sebagai korban kebijakan pendidikan. Selain itu, terdapat 236 kasus kekerasan fisik dan/ atau psikis serta 487 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Masih banyak kasus lainnya yang belum dilaporkan ke KPAI. (Kompas.com:2024)
Data ini menunjukkan bahwa kasus perundungan lebih marak terjadi di lingkungan pendidikan. Salah satu kasus yang viral di media sosial baru-baru ini, terjadi perundungan pada September 2023 di salah satu SMP di Cilacap yang melibatkan dua pelaku dan satu korban. Motif perundun-
gan ini dipicu oleh ketersinggungan kedua pelaku, MK (15) dan WS (14), setelah korban mengaku sebagai anggota geng sekolah yang sama. Akibat dari perundungan ini, korban mengalami luka serius berupa patah tulang rusuk dan harus menjalani operasi. Kedua pelaku diadili dan divonis pidana penjara hingga tujuh tahun. Contoh kejadian yang lain di sekolah Binus School Serpong pada Februari 2024. Motif perundungan ini dilatarbelakangi oleh tradisi kekerasan yang dilakukan sebuah geng terhadap junior mereka. Korban mengalami cedera akibat luka bakar dan lebam di sejumlah area tubuh. Kasus ini terungkap setelah video kejadian beredar di media sosial. Hal ini mendorong investigasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka dan delapan anak yang terlibat dalam masalah hukum (ABH). Kasus-kasus tersebut merupakan alarm bagi kita semua bah-
wa perundungan masih menjadi masalah serius bagi masa depan anak-anak Indonesia. Perlu disadari bahwa edukasi tentang bahaya perundungan dan bagaimana mengenali tanda-tandanya perlu digalakkan sejak dini, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas. Yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa kasus perundungan tetap saja terus bermunculan di lembaga pendidikan? Hal ini disebabkan oleh respons yang lambat dan tidak efektif dari aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut. Dengan demikian, pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menegakkan hukum yang ada, serta menyediakan layanan dukungan bagi korban perundungan. Selain itu, perlu adanya program khusus yang berfokus pada rehabilitasi pelaku perundungan, agar mereka tidak mengulanginya di masa depan. Melansir dari CNNIndonesia.com, Ubaid Matraji selaku Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa sistem yang lemah merupakan salah satu penyebab mengapa kekerasan di sekolah masih kerap terjadi. Permasalahan seperti ini perlu diatasi dengan perbaikan sistem, perubahan mindset, dan penguatan ekosistem ramah anak. Menurutnya, pemerintah belum melakukan evaluasi dengan baik terhadap implementasi dari dasar hukum yang telah dibuat. Selain itu, menurut Ubaid, Kurikulum Merdeka yang digadang dapat menciptakan ekosistem ramah anak dan berorientasi pada pengem-
bangan karakter, kenyataannya masih menyimpan banyak problematika dan belum terlihat dampaknya dalam pencegahan kekerasan di sekolah. Sementara itu, sekolah atau lembaga pendidikan bisa melakukan pencegahan dan penindakan secara tegas terhadap perundungan sesuai dengan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023. Namun, hingga kini, implementasi kebijakan tersebut masih di bawah ekspektasi. Praktik perundungan masih menjadi masalah serius di banyak sekolah. Perlu Pencegahan Sejak Dini Berdasarkan data yang dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) terdapat 15 kasus kekerasan yang terjadi selama periode Januari hingga Juli 2024. Dari 15 kasus yang tercatat, mayoritas kekerasan terjadi di jenjang SMP/MTs dengan persentase 40%, diikuti oleh SD/ MI sebesar 33,33%, dan masing-masing 13,33% untuk SMA dan SMK. (Detik.com:2024) Jenjang pendidikan dasar yaitu SD/MI menempati urutan kedua dalam jumlah kasus perundungan. Hal ini menjadi bukti bahwa perundungan di Indonesia belum ditangani dari akarnya. Salah satu kekurangan penanganan perundungan di sekolah dasar adalah tidak adanya layanan Bimbingan Konseling (BK). Tanpa layanan ini, siswa yang mengalami perundungan merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi perasaan mereka. Hal ini sangat disayangkan, mengingat fase sekolah dasar adalah masa yang krusial dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Kasus perundungan di seko-
lah dasar memiliki dampak jangka panjang yang serius bagi korban. Anak-anak yang mengalami perundungan cenderung mengalami masalah psikologis. Jika dibiarkan, dampak ini bisa mengganggu proses belajar dan perkembangan mereka di masa depan. Biasanya guru kelaslah yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan konseling. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran guru kelas belum berjalan secara optimal disebabkan oleh beban tugas yang berat, termasuk mengajar serta mengevaluasi siswa. Melihat maraknya kasus perundungan yang semakin meningkat setiap tahunnya, pemerintah perlu membuat penguatan regulasi terkait perlindungan anak di sekolah. Sekolah harus memiliki program pencegahan perundungan yang terencana dan terukur. Selain itu, pelatihan bagi guru harus menjadi agenda rutin agar mereka memiliki keterampilan untuk menangani kasus perundungan. Selain pembinaan kepada pihak sekolah dan guru, orang tua juga memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya perundungan pada anak-anak. Perlu adanya sosialisasi kesadaran mengenai perundungan di kalangan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Terakhir, evaluasi terhadap impementasi kebijakan harus terus dilakukan dengan optimal sehingga dapat menciptakan ruang aman di sekolah dan meminimalkan kasus perundungan pada ranah pendidikan.
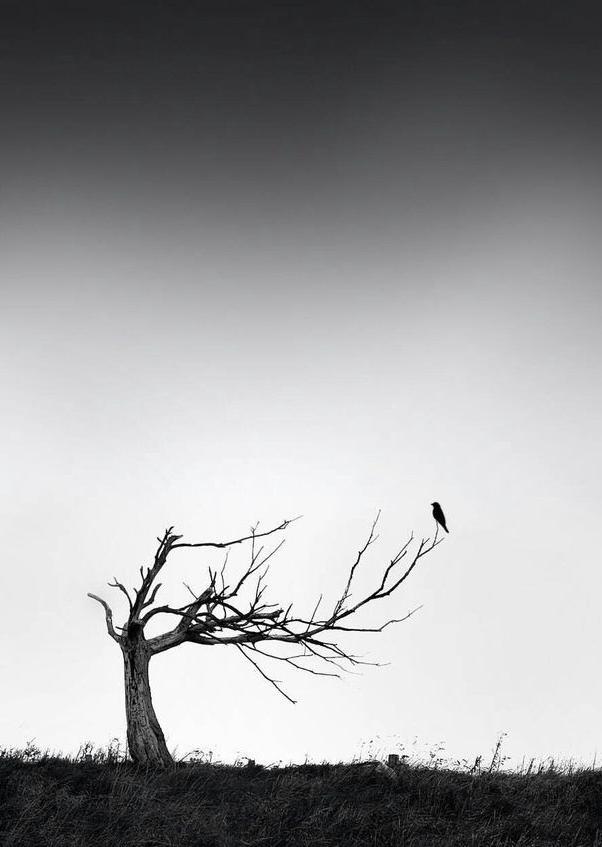
Katanya, aku tak banyak tahu Nyatanya, aku belum melewatinya Hanya dari petuah-petuahnya Diungkapkan dalam sajak bumantara
Tiap kata bagaikan mutiara nan berharga
Saat diriku terlena
Ia mulai berkata
Menyebut hidup tak ada guna Saat manusia dengan lalainya Hampir lupa sang penciptanya
Saat lelah terasa
Diri ingin menyerah saja Pun Ia mulai berkata Untuk apa hidup di dunia
Jika berjuang tak sanggup dirasa
Saat menangis terluka Hinggap penuh rasa kecewa Tak lupa Ia mulai berkata Sungguh amat keras dunia
Tangis takkan menghapus derita
Kini aku merindu
Akan segala petuahnya
Iringan cinta kasihnya
Bahkan segala pengorbanannya
Yang telah larut dalam kenangan
Ialah kata penuh makna
Ialah tutur penuh cinta
Ialah Abah dengan penuh wicara Ialah sosok dalam mahakarya Terlukis indah tiada dua
Aku tersadar
Yang hidup akan mati
Yang datang akan pergi
Tapi ku rasa tidak dengannya
Abah dengan segala petuahnya
Adalah aku dalam diriku

Oleh: Risma Alfiani, Kru Edukasi 2019
“Bambang Hero seorang saksi ahli dalam persidangan kasus korupsi timah senilai triliunan rupiah dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Persaudaraan Pemuda Tempatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas kurang validnya perhitungannya terhadap kerugian negara” Begitulah kira-kira pernyataan pewarta di salah satu stasiun televisi swasta yang ku dengar ketika hendak sarapan di awal tahun ini.
Mendengar pemberitaan tersebut, tentunya memunculkan rasa kekecewaan dan menyayangkan kenapa kejadian tersebut terjadi kembali. Iya, Bambang Hero Saharjo merupakan akademisi dan pakar forensik kebakaran Indonesia. Namanya mencuat setelah pelaporan atas dirinya sebagai saksi ahli yang dirasa
kurang kompeten oleh pelapor terhadap kasus kebakaran hutan di Riau pada tahun 2013.
Namanya kembali hangat diperbincangkan setelah menjadi saksi ahli dalam kasus timah yang merugikan negara hingga triliunan rupiah yang menjerat Harvey Mois dan rekannya yang lain. Setelah kasus tersebut selesai serta hakim sudah mengetok palu untuk menuntut para pelaku korupsi tersebut. Alih-alih mendapatkan perlindungan hukum sebagai saksi ahli, publik kembali dihebohkan dengan pelaporan kepihak kepolisian terhadap Bambang Hero yang diduga melakukan kekeliruan terhadap perhitungan kerugian negara.
Hal serupa dialami oleh Basuki Wasis, seorang dosen IPB yang menjadi saksi ahli
dalam kasus pemberian izin pertambangan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara bernama Nur Alam. Basuki digugat ke Pengadilan Negeri Ciinong oleh Kuasa Hukum Nur Alam, dalam tuntutannya asuki dinilai merugikan terdakwa dan diminta ganti rugi sebesar 3 triliun rupiah serta ganti rugi dana operasional Nur Alam sebesar 4,47 milyar.
Keduanya bak super hero yang memberikan pencerahan kepada hakim dalam memutuskan perkara. Namun, yang disayangkan nasib mereka tidaklah secerah Shinichi Kudo yang secara penuh mendapatkan perlindungan hukum dalam membuktikan kebenaran melalui analisis berdasarkan keilmuannya. Sehingga Shinichi tidak pernah dipolisikan
oleh pelaku kejahatan. Bahkan tidak seberuntung Moru, seorang detektif yang gegabah dalam menarik kesimpulan. Mereka mendapatkan payung hukum penuh sehingga mendapatkan keamanan tidak sembarang orang bisa memenjarakannya.
Berbeda dengan lakon Bambang dan Basuki di Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan lakon-lakon saksi ahli lain di negara ini. Mereka rentan terkena intimidasi melalui jalur hukum atau yang sering disebut dengan judicial harassment. Payung hukum yang melindungi mereka telah bocor sehingga banyak pihak yang bisa mengintimidasi mereka dengan melaporkan ke pihak kepolisian untuk menuntut saksi akademisi. Intimidasi tersebut wujud dari serangan atas ketidakterimaan tersangka terhadap hukuman yang ditimpakan.
Menjadi saksi ahli yang dilimpahkan tugas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menguatkan barang bukti tentunya tidak mudah. Banyak serangkaian proses yang perlu dilalui. Baik pendidikan, pengaaman, ketepatan analisis serta serangkaian proses lainnya. Suatu tugas yang tida mudah dan perlu keberanian.
Sudah selayaknya saksi ahli mendapatkan perlindungan hukum dari negara atas dedikasinya dalam mengungkap barang bukti berdasarkan dengan keahliannya. Ketika terdapat pelaporan yang menuntut saksi ahli dalam beberapa kasus, seyogyanya pihak kepolisian mencerna dengan baik apakah kasus tersebut layak diterima atau tidak.
Sangat lucu dan tidak masuk akal jika saksi ahli yang
ditugaskan oleh JPU akan dituntut oleh JPU sendiri karena dianggap memberikan keterangan yang palsu. Keadaan tersebut justru menjadi bumerang dalam kredibelitas hukum di Indonesia. Aku rasa, jalan yang bisa ditempuh oleh terdakwa ketika ia merasa kesaksian ahli yang diberikan tidaklah benar, mereka bisa mengajukan banding dengan mendatangkan atau meminta saksi ahli lain dalam persidangan. Jika jalan yang ditempuh adalah dengan melaporkan ahli setelah persidangan selesai dan sudah diketok palu oleh hakim, maka hal tersebut dianggap sebagai kriminalisasi terhadap ahli.
Pelaporan tersebut bisa dikatakan sebagai ancaman yang dilakukan oleh pihak tertentu kepada saksi ahli. Apalagi jika laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian yang notabane-nya terbantu oleh pihak saksi ahli dalam menuntaskan kasus kejahatan yang besar. Saksi ahli dianggap sebagai penerang bagi hakim yang dibawa untuk menghadap hakim untuk diadili.
Negara yang mampu memberikan perlindungan kepada para saksi ahli dalam menjalankan tugasnya, akan memberikan payung hukum yang penuh. Tentunya hal semacam ini tidak pernah terjadi.
Jika saksi ahli dalam persidangan bisa dipidanakan tentunya tidak akan ada lagi saksi ahli yang mau membantu hakim dalam menyelesaikan duduk perkara. Karena tidak ada badan hukum yang melindunginya. Kasus yang dialami oleh Bambang Hero Saharjo dan
Basuki wasis merupakan secuil sampel kasus saksi ahli yang dipidanakan di Indonesia, tidak menutup kemungkinan terdapat kasus serupa yang dialami oleh saksi ahli lain di negara ini.
Memberikan bukti-bukti kejahatan tidaklah mudah, ia perlu berani dan tangguh karena akan menghadapi ranjau-ranjau yang dipasang oleh pelakunya.
Sudah saatnya hukum di negara ini diperkuat untuk melindungi pihak-pihak yang selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Bukan untuk melemahkan hukum yang berdampak pada longgarnya hukuman bagi para pelaku kejahatan dan kerusakan lingkungan.
Pelaku yang tidak mempertimbangkan kemaslakhatan bersama dan nasib alam di masa yang akan demi mendapatkan keuntungan pribadi, sangat layak mendapatkan hukuman yang membuat mereka jera.
Mereka tidak berhak membungkan daya kritis akademisi dalam mengupas kasus kejahatan di negeri ini. Bocornya payung hukum yang dimiliki saksi ahli perlu ditambal agar kuat dalam melindungi mereka.















"Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani."

Dikeluarkan oleh :
Lembaga Pers Mahasiswa Edukasi
Universitas Islam Negeri Walisongo
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2
Ngaliyan, Kota Semarang
Jawa Tengah 50185

(Di depan memberi teladan yang baik, di tengah membangun semangat, dari belakang memberi dorongan)
-Ki Hajar Dewantara-















