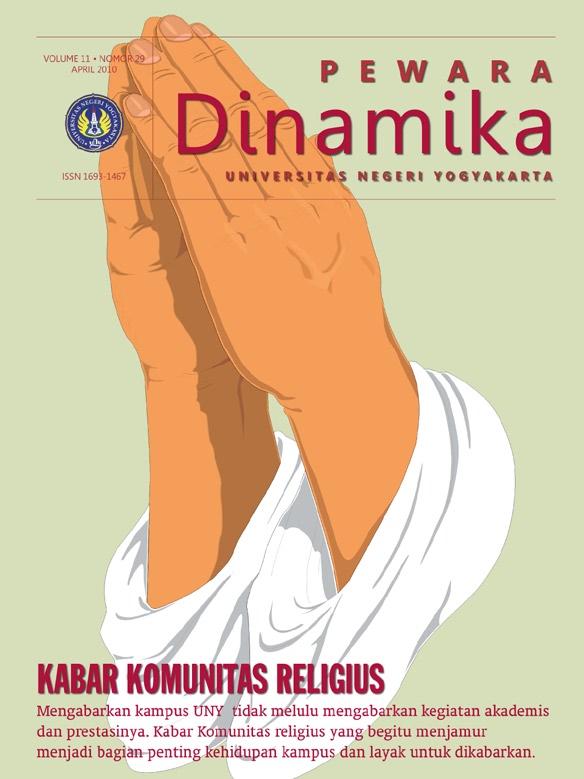9 minute read
opini
INTegRITaS DOSeN SeBagaI laNDaSaN PeMBaNgUNaN KaRaKTeR MaHaSISWa
Oleh Drs. DIMYaTI, M.Si.
Advertisement
Merebaknya fenomena plagiasi karya ilmiah yang dilakukan oleh akademisi perguruan tinggi (PT) sungguh memprihatinkan. PT yang di dalamnya orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, justru berbuat sebaliknya. KOMPAS (2/2010) menjadikan berita ini headline pada empat hari berturut-turut, serta menampilkan berbagai artikel dan opini masyarakat terkait dengan masalah plagiasi yang terjadi di PT, baik yang dilakukan oleh mahasiswa (dalam membuat skripsi), dosen (dalam membuat penelitian), dan calon guru Besar (untuk meraih jabatan gB-nya). Hilangnya kejujuran dalam pendidikan sama dengan hilangnya roh pendidikan. Mendiknas, Muhammad Nuh, menegaskan ada tiga faktor penyebab terjadinya penjiplakan di PT, yaitu rendahnya integritas pribadi dosen, ambisi mendapatkan tunjangan finansial, dan kurang ketatnya sistem di PT. Menurutnya, pendidikan karakter, budaya, dan moral mendesak diterapkan di dunia pendidikan (Kompas, 20/2/2010).
Distorsi Pendidikan Karakter di PT
Bukan hal yang mudah untuk melibatkan komunitas masyarakat PT dalam diskusi pentingnya memberikan pendidikan kepada mahasiswa yang tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan moral untuk bekal kehidupan di masyarakat. Sebagian dosen meyakini pentingnya mahasiswa memiliki karakter yang kuat. Pertanyaannya, mengapa dosen tidak mendukung pembangunan karakter secara terbuka atas mahasiswanya, bahkan di antara mereka berperilaku sebaliknya. Sederhana, namun memiliki akar persoalan yang dalam, apakah pimpinan PT, Dekan, dan Ketua Jurusan meyakini hakikat dan makna penting pendidikan karakter mahasiswa sebagai bagian utama dari tujuan pendidikan di PT.
Pendidikan yang ditunjukkan untuk mengembangkan seluruh aspek mahasiswa secara total adalah tujuan utama dari pendidikan di PT. Namun, itu semua tidak dilihat sebagai tujuan utama PT, terutama yang terjadi pada universitas riset (UR), bahkan lPTK ’penghasil’ guru. lagemann (2003), Dekan Harvard Graduate School of Education, mengatakan, laporan terbaru menyebutkan bahwa pendidikan di universitas telah menjadi lebih terfokus pada pendidikan teknis dan profesional dibandingkan yang terjadi pada era 1970-an. Dikatakannya, mahasiswa lebih difokuskan secara sempit pada ”persiapan kejuruan”. Di banyak tempat dan beberapa waktu lamanya, PT telah gagal dalam misinya memberikan pendidikan kepada mahasiswa yang mampu menetapkan ”rasa salah pada dirinya atau bersikap jujur, empati terhadap orang lain, menjadi warganegara yang baik dan efektif”, serta mampu mempersiapkan mahasiswa untuk ”berpartisipasi dalam menentukan dan menghadapi isu-isu di zamannya”.
Munculnya berbagai model UR menciptakan situasi yang pencarian bahan dan subjek penelitian sebagai sumber pencarian pengetahuan menjadi lebih penting bagi dosen dibandingkan meluangkan waktu untuk mendidik mahasiswa (Boyer, 1990). Waktu untuk aktivitas dosen hampir seluruhnya berada di lembaga penelitian, sehingga proses pembelajaran menjadi prioritas kedua. Bahkan, fokusnya lebih mengarah pada apa yang diajarkan, bukan bagaimana memberikan pembelajaran. Karena mengajar dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan tidak memberikan kontribusi atas upaya menerbitkan tulisan dalam jurnal penelitian, mendidik mahasiswa sering diletakkan pada prioritas yang rendah (Wilshire, 1990). Di sisi lain, motif ekonomi untuk mendapatkan finansial menjadikan dosen lebih berkiprah di jalur nonkependidikan di luar kampus, sehingga sering alpa dalam mendidik mahasiswanya. Manaje-
opini
men sistem akademik yang buruk juga potensi dan ancaman nyata yang membuat rapuhnya proses pendidikan karakter di PT. lahirnya buku ”Pembentukan karakter” oleh UNY yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat kepada dosen merupakan langkah maju dan solusi untuk mengembangkan karakter mahasiswa di UNY. Semoga, hal itu dapat dikembangkan lebih komprehensif. Mengatasi masalah karakter di PT harus komprehensif, tidak bisa sepotong-sepotong (Mendiknas, Kompas, 20/2/2010). Selain itu, penguatan integritas dosen harus menjadi prioritas bagi pengembangan karakter di PT.
Keteladanan hidup yang berbasis nilai adalah pemenuhan kewajiban dan kebenaran moral dengan karakter yang konsisten, atau integritas. Penjelasan ini benar-benar terlepas dari agama, budaya, ras, atau etnisitas. Seseorang dengan integritas perilaku yang saleh, seperti menjaga janji dan menahan diri untuk tidak berbohong, dan menipu. Ketika berada di masyarakat, dosen yang memiliki integritas akan dipandang sebagai model bagi suara moral masyarakat untuk diikuti.
Dosen berintegritas menunjukkan perilaku bertanggung jawab menyediakan program akademik yang berkualitas dan pengalaman pendidikan yang positif. Persoalannya, bagaimana dosen sebagai teladan mengajarkan karakter dan nilai-nilai moral, kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Itulah tantangan besar yang harus terus dikuatkan.
Mengenai nilai-nilai moral tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1) Kejujuran; dosen menunjukkan kejujuran dengan mengatakan kebenaran dan bertindak secara terhormat. Kejujuran, termasuk memenuhi janji dan komitmen, seperti menjaga kerahasiaan catatan mahasiswa, termasuk tidak berbohong/menipu. Dosen menunjukkan kejujuran berarti mengatakan yang sebenarnya tentang mengapa suatu tugas tidak disampaikan pada waktunya; menyelesaikan tugas tanpa menjiplak karya orang lain. 2) Kepercayaan; percaya kepada orang lain yang berkembang setiap kali orang tersebut memenuhi janji dan komitmennya. Dosen pada saat kuliah menetapkan dan menjunjung tinggi harapan seperti menyediakan dan memandu tugas tertulis dan belajar mahasiswa, mahasiswa dapat mempercayai dosen mereka. 3) Keadilan; berhubungan erat dengan kepercayaan, apakah mahasiswa mendapatkan perlakukan diskriminatif atau tidak adil dari dosen. Dosen yang adil percaya pada kemampuan masing-masing mahasiswa untuk belajar dan mereka mendorong mahasiswa untuk mencapai tingkat kemungkinan tertinggi. 4) Hormat; mengembangkan rasa hormat di dalam kampus sangat penting. Proses ini dimulai dengan cara dosen menunjukkan rasa hormat terhadap mahasiswa tanpa memandang suku, agama, gender, status sosial-ekonomi, karakteristik individu, atau kemampuan. Dosen harus luwes dalam menanggapi berbagai tingkat keterampilan dan kemampuan mahasiswa.
Tanggung jawab; dosen yang menunjukkan tanggung jawab adalah dosen yang secara moral bertanggung jawab atas tindakannya dan memenuhi tugas-tugasnya. Dosen juga dikatakan bertindak secara bertanggung jawab apabila membantu secara optimal pengembangan psikomotorik, kognitif, dan kemampuan afektif mahasiswa. Mengadakan persiapan dengan baik untuk setiap kelas dan memberikan umpan balik yang cepat serta konstruktif kepada para mahasiswa, membantu memfasilitasi proses pembelajaran merupakan dosen yang bertangung jawab.
kalam/pewara
drs. dImyatI, m.si. dosen Jurusan pendidikan olahraga FIk Uny
opini
SeJaRaH DaN OTORITaRIaNISMe: TaNggaPaN UNTUK V.F. JegaUT
Oleh KalaM JaUHaRI
Dalam Pewara Dinamika edisi april 2010 Jegaut menulis soal perdebatan yang marak beberapa tahun lalu mengenai PKI, pelurusan, dan penjungkirbalikan sejarah. Jegaut memulai tulisannya dengan argumen yang klise, namun ada benarnya, bahwa “semua pihak harus bisa melihat sejarah masa lalu negeri ini secara proporsional, jernih, dan objektif, tanpa mempolitisasi ... memosisikan peristiwa sejarah sesuai dengan keadaan riil saat itu, berdasarkan fakta yang sebenarnya”. Namun, sayangnya, apa yang ditulisnya malah bertolakbelakang dengan pendapatnya itu.
soal Pelurusan dan Pemutarbalikan sejarah
Setelah Soeharto makzul, muncul usaha untuk mendobrak kanon sejarah Orde Baru tentang peristiwa ‘65. Jika kanon yang tertera dalam kurikulum pelajaran sejarah masa orde baru beranggapan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) berada di balik gerakan 30 September 1965, maka disebut “g 30 S/PKI”, kurikulum 2004 menghilangkan “/PKI” dan hanya menyebut gerakan tersebut dengan “g 30 S” an sich. Penghilangan kata “/PKI” dari “g 30 S” itu menyulut emosi kelompok-kelompok yang telah mengimani bahwa PKI, “bahaya laten” itu, merupakan dalang gerakan 30 September 1965. Sedangkan sebagian kelompok pro-penghilangan kata “/PKI”, menganggap bahwa CIa, angkatan Darat, dan/atau Orde Baru-lah yang menjadi dalangnya, PKI justru menjadi korban. akibatnya, aksi saling tuduh dan perbantahan yang penuh emosi terjadi di mana-mana. Yang satu menganggap pihak yang pro-historiografi-Orde Baru memutarbalikkan sejarah, dan yang lain berpendapat sebaliknya.
Perdebatan yang emosional mengenai peristiwa ’65 itu menyisakan dua hal—dari kedua belah pihak yang bertikai—yang penting untuk dikritisi. Pertama, pihak yang pro-kanon sejarah orde baru—dan yang menjadi pemenang formal, sebab kurikulum 2004 kemudian dibatalkan—menunjukkan kecongkakannya dengan penggunaan kekerasan terhadap wacana-wacana alternatif yang berbeda dengan kanon mereka. Mereka melarang, menyita, dan membakar belasan ribu historiografi yang memiliki perspektif berbeda (Kompas, 22 dan 28/5/2007, 30/4/2007). Hal ini menunjukkan kalau pihak pro-kanon ini, seperti umumnya pembela kanonisasi sejarah, enggan menerima kenyataan bahwa konstruksi maupun pemaknaan masa lalu berangkat dari subjektivitas. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran mutlak dalam setiap penjelasan dan narasi historiografis.
Kedua, meskipun telah berusaha menyajikan wacana alternatif terhadap kanon sejarah Orde Baru, pihak anti-kanon—karena bertolak dari keinginan untuk mengadvokasi korban kekerasan Orde Baru dan lebih memilih rekayasa manipulatif daripada membangun metodologi baru—terjebak dalam prinsip framing against the enemies. Mereka, sama seperti pihak yang prokanon, tidak mau menerima sumber dan narasi historis yang beragam karena dianggap dapat mengacaukan kerangka ideologis mereka. Jika historiografi yang lama hanya memposisikan PKI sebagai kelompok yang harus bertanggung jawab, maka historiografi yang baru akan sangat mudah terjerumus pada konstruksi dan pemaknaan yang hanya mengoper kesalahan kepada Orde Baru, angkatan Darat, atau CIa, serta menghapuskan realitas yang menunjukkan keterkaitan PKI dalam peristiwa-sebagai-proses. Singkatnya, historiografi yang dihasilkan oleh kelompok ini mulai membangun wacana yang dogmatik, sehingga tidak bisa lagi dilihat perbedaannya secara konseptual dengan historio-
opini
grafi yang dikritik sebelumnya (Bambang, 2006: 225-226). Perbedaan antara kanon dan yang anti hanya terletak pada siapa berperan menjadi korban dan siapa penjahat.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kedua kelompok yang berdebat itu terjebak dalam prinsip framing against the enemies yang ideologis. Kedua belah pihak tidak mau melihat suatu peristiwa secara komprehensif: yang satu hanya memfokuskan kejadian pada masa pascatragedi 30 September 1965, yaitu pembantaian ribuan (atau ratusan ribu) orang yang dianggap komunis, dan yang lain hanya melihat faktafakta pra-kejadian, propaganda komunis untuk “mengganyang setan-setan kota dan desa”, konflik lekra-manikebu, bahkan peristiwa 1948. Nah, dalam tulisannya itu Jegaut—sebagai, seperti ia tulis, sejarawan yang seharusnya mengedepankan aspek metodologis dibanding ideologis—bukannya berusaha keluar dari prinsip framing against the enemies dan berargumen secara proporsional, tetapi malah mundur ke belakang dengan mendukung kanon historiografi Orde Baru dan mendakwa lawannya.
Pengukuhan Kekuasaan
Jika kita percaya pada anggapan bahwa sejarah memiliki fungsi untuk memperkokoh identitas nasional maupun kolektif, maka kita tidak akan terkejut bila penulisan sejarah dan klaim akan kebenaran masa lalu menjadi demikian penting dan menimbulkan banyak perdebatan. Salah satu sebab perselisihan ialah soal bagaimana masa lalu ditampilkan dan fakta diciptakan (Nordholt, Bambang, dan Ratna (ed.), 2008: 1). Di samping itu, tentu saja, perdebatan sering terjadi karena munculnya narasi yang berbeda, bahkan bertentangan, dari yang sudah ada. adanya perbedaan pendapat mengenai apa yang terjadi pada masa lalu sebenarnya wajar saja. Sebab, sejarah sebagai peristiwa objektif yang telah terjadi telah lewat dan tak mungkin lagi dijangkau seutuhnya, sedangkan sejarah yang ada sekarang adalah hasil rekonstruksi sejarawan yang sering disebut sebagai historiografi. Dengan demikian, sekali lagi, konstruksi maupun pemaknaan masa lampau selalu mengandung subjektivitas.
Tampaknya pendapat yang membenarkan adanya subjektivitas dalam sejarah itu tidak mudah diterima oleh setiap orang yang ingin meneguhkan kekuasaannya atau membenarkan ideologinya—meskipun mereka sebenarnya merayakannya. Mereka biasa menonjolkan peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, nilai-nilai, alur, dan eksplanasi tertentu yang membenarkan diri mereka dan menyingkirkan the other.
Sikap yang despotis itulah yang justru tampak dalam tulisan seorang sejarawan yang mengaku pemerhati demokrasi ini. Ia menyarankan bahwa kata “PKI” harus menyertai frase “gerakan 30 September”, tanpa memberi bukti bahwa hanya Partai Komunis itu yang menjadi arsitek atau terlibat dan tidak ada elemen-elemen lain. Sebaliknya, ia malah mengklaim bahwa “semua masyarakat Indonesia jelas-jelas tahu bahwa pemberontakan tahun 1948 di Madiun dan g-30-S tahun 1965 di Jakarta adalah noda hitam dalam sejarah yang semuanya dipelopori ketua PKI saat itu”. Dengan kata lain, ia menolak versi lain yang muncul di berbagai buku—seperti terangkum dalam Bayang-Bayang PKI yang diterbitkan ISSaI.
Yang lebih mengerikan lagi, ia mendukung pelarangan penerbitan buku-buku yang tidak sesuai dengan versi yang dianggapnya benar, juga “semua buku berbau penyebaran paham Marxisme, leninisme, dan Komunisme”. Ia bahkan menyarankan agar “Kejaksaan agung dan Kepolisian RI sebaiknya tidak ragu-ragu menindak tegas penulis, penerbit, dan percetakan” yang mempublikasikan hal itu.
Seorang negarawan Rusia, Krouchtjev, pernah berujar, “sejarawan adalah profesi yang ditakuti penguasa karena mereka bisa membongkar masa lalu dengan penjelasan yang tak terbantah”. Namun, sebagai penutup, saya— penulis artikel ini—ingin menambahkan bahwa kita juga jangan lupa bahwa sejarah sering digunakan sebagai alat pengukuhan kekuasaan dan alat pembenaran bagi para otoritarian.
IstImewa

kalam JaUharI mahasiswa program pascasarjana sejarah FIb Ugm