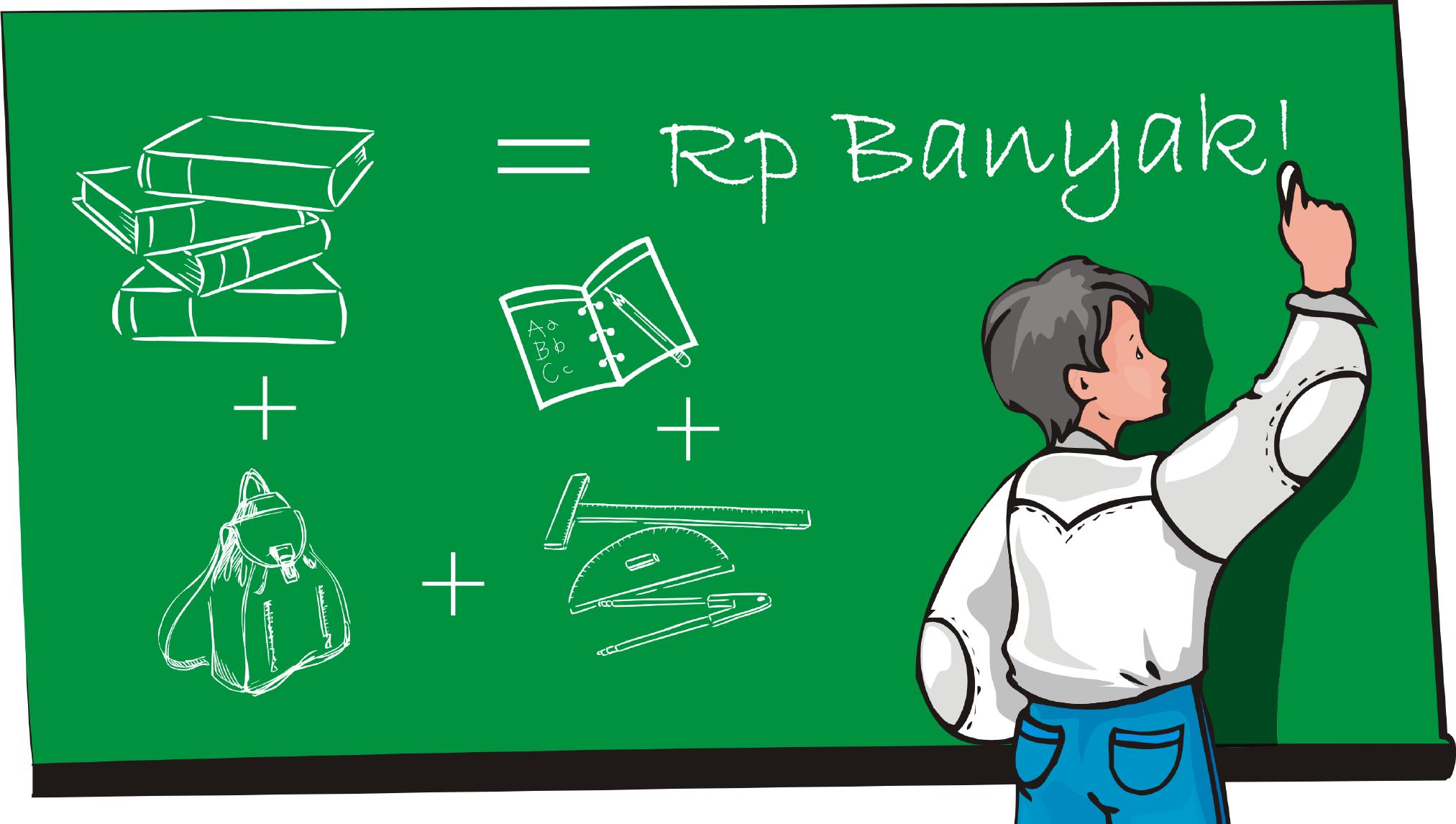
8 minute read
opini
meNYOAL PeNDIDIKAN mUrAH
Oleh SULIS STYAWAN
Advertisement
memikirkan--atau sekedar membayangkan--tentang adanya ”pendidikan gratis” di Indonesia, negeri berpenduduk sekitar 220 juta jiwa ini, adalah tak lebih dari sekedar membaca sebuah dongeng. mengapa? Diakui atau tidak, selama ini memang banyak kalangan yang selalu memperdebatkan soal pendidikan gratis di Indonesia. Kenapa pendidikan gratis selalu saja diperdebatkan?
Jlentrehnya kurang lebih begini. Kalau saja praktek pendidikan gratis itu sudah benar-benar gratis, tentu tidak akan ada yang memperdebatkannya. Pasalnya, di kabupaten atau kota mana di bumi pertiwi ini yang praktek pendidikannya benar-benar ”gratis”. Apakahdi Apakah di Jembrana (bali), di musi banyuasin (Sumatera Selatan), di Kutai Kartanegara, di balikpapan (Kalimantan Timur). Ataukah di Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah) yang notabena kota atau kabupaten tersebut sudah misuwur dan kondhang alias terkenal sebagai kota atau kabupaten yang berhasil menyelenggarakan ”pendidikan gratis”.
Apakah di ketiga daerah itu para orang tua yang memiliki anak berusia 7 - 15 tahun (usia wajib belajar) sudah tidak harus mengeluarkan dana lagi untuk membelikan seragam sekolah, tidak lagi membelikan buku tulis, tidak lagi membelikan sepatu, atau tidak lagi membelikan buku-buku pelajaran? Kenyataannya, para orang tua di kota atau kabupaten penyelenggara ”pendidikan gratis” itu tetap saja harus membiayai pendidikan anaknya. Itu artinya, praktek pendidikan itu memang belum ”gratis”!
Kita semua tentu mafhum, Pemerintah kita memang tidak pernah mengharuskan sekolah tidak memungut biaya. Artinya, Pemerintah tidak pernah menjanjikan pendidikan itu ”digratiskan” karena UU Sisdiknas No. 20/2003 memang tidak mengamanatkan pendidikan itu digratiskan. Tetapi, mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menganggarkan minimal 20% anggaran pada sektor pendidikan--di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan--dari total APbN/ APbD.
Sementara itu, dengan alokasi dana 20% dari APbD, senyatanya juga tidak serta-merta bisa menjamin orang tua murid tidak mengeluarkan biaya pendidikan, seperti yang selama ini masih saja harus mereka tanggung. Dalam tataran ini, artinya, yang paling mungkin adalah seandainya anggaran minimal 20% untuk sektor pendidikan itu sudah dipenuhi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pendidikan ”murah” akan dapat dinikmati masyarakat. Namun, tetap saja itu bukan pendidikan ”gratis”. galibnya, pendidikan murah tidak identik dengan pendidikan gratis. masih seputar ”bukan pendidikan gratis”. Jika kita cermati, istilah ”pendidikan gratis” sebenarnya lebih dipopulerkan oleh para kontestan Pilkada. menurut mereka, istilah itu lebih efektif untuk menarik simpati pemilih daripada berbicara soal anggaran pendidikan minimal 20%, ataupun memakai istilah ”pendidikan murah”. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, istilah ’pendidikan gratis’ itu tak lebih dari sekedar ”bahasa politik” semata-mata.
Pengalaman menunjukkan, bahwa bahasa politik itu identik dengan janji kosong. Selama praktek pendidikan itu tidak benar-benar gratis, tentunya akan lebih arif jika kita menghindari istilah pendidikan gratis itu. Permasalahannya bukan hanya sebatas penggunaan istilah, tetapi lebih daripada itu, dengan menggunakan istilah itu, maka ”pembohongan publik” atas rakyat banyak telah terjadi. maka, marilah kita berusaha menahan diri untuk tidak turut serta membohongi masyarakat dengan segala obral janji-janji kosong yang membuai, namun tak pernah jelas juntrungnya atau bahkan nir-realisasi.
Terkait dengan kalimat “... tanpa memungut biaya …”, dalam Pasal 34 Ayat 2 UU Sisdiknas,
opini
penulis menduga, itulah yang diartikan oleh banyak kalangan sebagai ”pendidikan gratis”. Kita tentu dapat menimbang ulang, apakah dengan hanya ”tidak membayar SPP”, serta-merta praktek pendidikan itu sudah bisa dikatakan gratis? Tentu tidak!
Pengertian pendidikan gratis itu tidak bisa dipersempit sedemikian rupa. Ketika orang tua masih harus mengeluarkan uang untuk membelikan seragam, buku tulis, buku-buku pelajaran, dan sebagainya (padahal anaknya masih dalam usia wajib belajar), maka amatlah gamblang, hal itu menunjukkan bahwa pendidikan tidaklah gratis.
Sekali lagi, karena pendidikan itu tidak pernah benar-benar gratis, kita berhenti dari membual dengan istilah itu. masalah pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat--bahkan, peserta didik itu sendiri.
Salah satu paradigma yang dibangun dalam UU Sisdiknas, yaitu ”meningkatkan peran serta masyarakat”. maka, dengan bersama-sama bertanggung jawab, kita dapat secara sungguhsungguh melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Juga, supaya kita tidak perlu lagi saling tuding ketika mutu pendidikan di negeri ini masih saja rendah. memang, untuk mewujudkan pendidikan ”murah” ini tak dipungkiri bahwa masyarakat tetap saja dituntut peran sertanya--tidak terkecuali dalam hal pembiayaan--hanya saja porsinya berbeda. Hal ini sebagai salah satu bentuk wujud partisipasi masyarakat dalam turut serta mengambil tanggung jawab terhadap masalah pendidikan. Namun,tanggungjawabitujuNamun, tanggung jawab itu juga tidak cukup hanya urun dana.
Lebih daripada itu, setelah timbul kesadaran untuk mengambil tanggung jawab, diharapkan masyarakat untuk tidak hanya seleh tangan atau pasrah bongkokan (menyerahkan begitu saja) terkait masalah pendidikan anak-anak mereka kepada lembaga-lembaga pendidikan, melainkan harus tetap ikut cawecawe (ikut mengurus) dan berperan aktif serta bekerjasama secara sinergis dengan sekolah.
Konklusinya, sebagai bagian dari warganegara yang baik, terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, tentunya kita harus menyadari, mengambil peran, serta memikul tanggung jawab atas peran itu. Kita semua tentu berharap bahwa penyelenggaraan pendidikan di negeri tercinta ini benar-benar bisa dan sampai pada pengejawantahan ketercapaian tujuan pendidikan nasional. Semoga begitu!
s�lIs styawan mahasiswa �urdik Fisika FmIpa �ny
kalam/pewara
opini
SerTIFIKASI: gUrU HArUS meNULIS!
Oleh UmU SULAImAH, S.Pd.I.
Fakta saat ini memberikan gambaran yang berbeda mengenai sosok guru. Ada cerminan gambaran negatif tentang kredibilitas moral guru. mereka melakukan pekerjaan karena berharap kenaikan gaji an sich, atau sekedar menjalankan rutinitas karena tidak ada pilihan lain. Wajarlah, kehadiran lembaga pendidikan tak mampu memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.
Ada guru yang masih memiliki pemikiran konservatif, sehingga mengekang seluruh daya kreativitasnya untuk maju. guru sering meninggalkan kultur akademis, seperti membaca dan menulis, sehingga keseharian mengajar hanya berhias text book thinking. Sungguh membosankan predikat guru seperti itu. bahkan, guru sering tak lagi menjadi sosok suritauladan digugu lan ditiru. Hal itu diperparah dengan lemahnya semangat belajar-mengajar. guru seharusnya mampu memberikan spirit atas peserta didiknya. rendahnya kapasitas intelektual pendidik mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas peserta didiknya.
Tulisan ini bukan bermaksud mendiskreditkan guru, melainkan mengajak kita melakukan perbaikan diri agar profesi guru benar-benar menjadi profesi yang mulia, penerang bagi peradaban. Kenyataan tak dipungkiri, guru menjadi profesi yang sangat dibanggakan di beberapa negara maju, karena profesi guru merupakan jantung peradaban.
Sebagus-bagus sistem pendidikan yang telah dirumuskan, secanggih apa pun kurikulum yang dirancang, tak akan bisa tanpa kehadiran guru. Tanpa guru, pendidikan kosong makna dan eksistensi. guru memiliki misi profetik yang senantiasa melakukan proses transmisi ilmu dalam upaya melakukan proses transformasi peradaban untuk lebih maju. Tidak sekedar transfer of knowledge, namun guru merupakan inovator dalam menumbuhkan budaya akademik.
Program pemerintah yang berupaya meningkatkan kompetensi dan kapabilitas intelektual guru perlu disambut baik. Salah satunya UU No. 14/2005 tentang guru dan Dosen yang di antaranya berisi proses sertifikasi. Dikemukakan di sana bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. berlandaskan UU No. 14/2005 tentang guru dan Dosen, Pemerintah memberlakukan program sertifikasi dan stratifikasi S-1 dan D-4. Dengan program ini diharapkan guru dan praktisi pendidikan akan melakukan proses akselerasi dan peningkatan kapasitas diri, sehingga mendapatkan sertifikat lulus uji dan mendapatkan tunjangan tambahan atas keberhasilannya itu.
Salah satu bentuk komponen penilaian guru dalam sertifikasi adalah penilaian portofolio yang mencakup penilaian atas pengalaman serta profesionalitas guru. Hal itu dibuktikan dengan karya pengembangan profesi, dalam bentuk buku yang dipublikasikan, artikel yang dimuat di media, modul, diktat, media pembelajaran, dan sebagainya.
Penulis melihat ada semangat yang kuat dari para praktisi pendidikan untuk lolos dalam ujian tersebut. Di samping upaya meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi, motivasi materialistik sering menjadi hal yang dikedepankan, berjibaku dalam memperjuangkan selembar sertifikat. bagi mereka yang ambisius, cara apa pun ditempuh demi memenuhi kriteria penilaian portofolio tanpa memperhatikan nilai dan asas kelayakan. Hal inilah yang sesungguhnya mencederai integritas moral asasi guru. Kejahatan intelektual pun menjadi pola kriminal yang baru.
Cara yang ditempuh untuk itu lumayan banyak dan unik, di antaranya membeli karya orang lain atau melakukan tindakan pemalsuan hasil karya. Yang lebih mengherankan lagi,
opini
sering terjadi ‘komersialisasi’ kegiatan ilmiah. guru berbondong-bondong mengikuti seminar yang dikemas secara ilmiah, berlabel regional maupun nasional, berbekal rp 50.000,00 -- 200.000,00, bukan kemanfaatan karena akan bertambahnya ilmu pengetahuan, melainkan lebih demi selembar sertifikat. Jika tak ada upaya ketat dari Pemerintah dan tim sertifikasi untuk melakukan pengawasan, kondisi seperti itu dikhawatirkan akan menjadi tradisi buruk. mendewakan formalisme dan simbolisme akan mengikis bangunan idealisme.
Proses sertifikasi seharusnya menjadi ajang dinamisasi skill yang selaras dengan upaya merealisasikan misi profetik guru. Senantiasa mengembangkan budaya membaca, menulis, meneliti, dan menelaah, demi mendapatkan pengembangan, temuan-temuan baru, serta terobosan mutakhir dalam dunia pendidikan. Setiap hari dipastikan ada hal baru yang ditemukan oleh guru karena mereka langsung berhadapan dengan peserta didik. banyak hal bisa diteliti, ditelaah, dianalisis, dan kemudian ditulis untuk semakin memperkaya referensi bagi dirinya atas hal-hal baru yang ditemuinya selama mengajar. Kenyataan yang terjadi, kemampuan dan kebiasaan guru untuk membuat karya tulis dan mempublikasikannya masih rendah. Hal ini terjadi karena rendahnya budaya membaca dan melek informasi di kalangan guru. WajarjikakemampuWajar jika kemampuan menulis menjadi kebiasaan yang jarang dilakukan.
Di tengah arus informasi dan komunikasi tanpa batas seperti sekarang ini, guru dituntut bergegas berbenah diri. Melek informasi menjadi perbekalan guru yang mengemban tugas mulia melakukan proses transmisi ilmu atas manusia pembelajar. SebagaimanadiketaSebagaimana diketahui, dunia saat ini tak lagi mengandalkan sistem komunikasi verbal yang dinilai lamban, kurang efektif, dan kurang efisien. budaya verbal tergeser oleh budaya tulisan. Terlebih,kecangTerlebih, kecanggihan teknologi telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi pertukaran informasi melalui tulisan. budaya tulis-menulis merupakan hal yang penting dilakukan guru.
Dengan menulis, guru bisa menuangkan ide/ gagasannya, menyuarakan aspirasinya, memberikan pengaruh, serta menyebarkan pemikirannya. menulis dapat menjadi instrumen perjuangan, pengabdian, dan pemberdayaan. Oleh karena itu, guru-guru yang mengemban misi profetik seharusnya menjadikan budaya menulis menjadi aktivitas rutin. menulis merupakan cara untuk mengikat ide/gagasan, sarana transmisi ilmu, dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan/kebenaran.
Kemampuan menulis di kalangan guru masih relatif rendah. Itu terjadi karena lemahnya semangat dalam belajar-mengajar, tidak memiliki pemikiran progresif, dan rendahnya budaya akademik. mengutip perkataan Imam ghazali, ”Kalau engkau bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis.”
Dengan menulis kita bisa mencerdaskan berjuta-juta manusia tanpa batas. bukan sekedar motivasi material an sich atau motivasi kenaikan pangkat saja para guru berlomba-lomba meningkatkan aktivitas menulisnya, tetapi lebih pada panggilan jiwa untuk terus menyumbangkan saran, gagasan/ide positif bagi kemajuan peradaban bangsa. membaca dan menulis adalah tradisi para ilmuwan. guru merupakan ’ilmuwan’ yang tak boleh lepas dari itu. menulis menulis berarti memberikan suluh harapan yang akan menerangi dunia dengan ide-ide yang mencerahkan. Wallahu a’lam.

kalam/pewara
�m� s�laImah, s��pd��I�� guru sdIt �lul albab kota pekalongan







