Teknologi Pelestari
Yuli Setyo Indartono Deny Willy Junaidy Rino Rakhmata Mukti Mohammad Farid

PENANGGUNG JAWAB
Dr. Yuli Setyo Indartono Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITB
PENULIS
Yuli Setyo Indartono Deny Willy Junaidy Rino Rakhmata Mukti Mohammad Farid
EDITOR Islaminur Pempasa
PERISET
Endan Suhendra Catur Ratna Wulandari Yudi Noorachman Risa Anggreini Saffanah Zahirah
FOTOGRAFER
Ferdyansyah Poernama
ILUSTRATOR Kolam Susu Studio
DESAINER GRAFIS
Irman Nugraha Fachri Fauzi
SEKRETARIAT
Noviyanti
Ferdyansyah Poernama Dian Sumardiana Suyanto Karina Dwianti Ali Hasan Asyari
Tim Administrasi, Keuangan, dan Sisfo LPPM IT
COVER STORY
Ilustrasi pemanfaatan alat penjernih berbasis membran IGW Home Ultrafilter menggunakan teknologi ultrafiltrasi untuk penyediaan air bersih bagi daerah yang mengalami kekeringan atau bencana.
UCAPAN TERIMA KASIH
Ketua LPIK ITB, Joko Sarwono, Ph.D. Ketua LPIT ITB, Prof. Taufan Marhaendrajana, Ph.D.
Cetakan pertama: Desember 2022 ISBN: 9786232972643
Hak Cipta © 2022 Dokumen ini diterbitkan oleh ITB Press. Hak cipta milik LPPM ITB - Bandung dan dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan mencetak ulang, mengutip sebagian atau keseluruhan isi tanpa izin.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung
Gedung CRCS Lantai 6 Jl. Ganesha No. 10, Bandung 40132 Jawa Barat, Indonesia (022) 86010050 / 86010051
https://lppm.itb.ac.id https://pengabdian.lppm.itb.ac.id
Email: lppm@itb.ac.id
Bumi dan Masyarakat Berkelanjutan
Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D. Rektor ITBKESADARAN global terhadap keberlanjutan bumi dan kesejahteraan masyarakat telah mengantar kita pada kesamaan langkah dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainability Development Goals (SDGs). Dalam kerangka SDGs ini, kita dipahamkan mengenai bumi yang satu dan saling terkait dengan setiap langkah kecil, baik atau buruk yang akan memberi dampak pada keseluruhan planet.
Bumi yang satu dan mungkin satu-satunya menjadi tumpuan bagi kehidupan dan penghidupan di atasnya saat ini menghadapi tekanan untuk menghidupi masyarakat dan kehidupan lain di atasnya. Inklusi sains, teknologi, seni dan humaniora bisa menjadi salah satu metode dan perangkat utama dalam mengelola dinamika optimalisasi dan distribusi sumber daya, termasuk meningkatkan resiliensi masyarakat menghadapi perubahan alam, khususnya perubahan iklim dan potensi bencana.
Di pulau-pulau kecil, misalnya, kita mendapati sumber daya perikanan yang melimpah, tetapi menghadapi tantangan dalam pengelolaan, pengawetan karena juga terkait dengan ketersediaan energi. Terkait dengan lokasi geografis seperti ini, intervensi tentu tidak bisa selesai tanpa melintasi jarak dan tantangan lain.
Inklusi sains, teknologi, seni, dan humaniora membutuhkan kerelaan para ilmuwan berinter aksi dengan konteks sosial, budaya, dan tantangan alam dalam mencoba membangun solusi bersama. Sebagian ‘petualangan’ para ilmuwan kami menjelajahi tantangan merawat bumi, meningkatkan kualitas penghidupan terangkum dalam buku ini sebagai juga ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah menerima para ilmuwan ITB dengan rasa bangga.*
Meretas Jalan Pengabdian dengan Budaya Ilmiah Unggul
Prof. I Gede Wenten, Ph.D. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITBPENGABDIAN kepada masyarakat sebagai salah satu Dharma dari tiga ‘kebenaran’ dan ‘panduan perilaku’ insan akademik di perguruan tinggi bukan fragmen atau komponen terpisah dari dua Dharma lain, yaitu pendidikan dan penelitian. Hal ini bermakna bahwa program pengabdian ITB yang dimaksudkan sebagai upaya penerapan sains dan teknologi untuk menjadi solusi masalah keluar dari ruh sains dan teknologi yang terbangun di dalamnya. Arah pengembangan riset dan inovasi ITB saat ini adalah penguatan budaya ilmiah. Kualitas menjadi prioritas lebih tinggi daripada kuantitas. Riset para ilmuwan ITB diarahkan menjadi riset berkualitas tinggi dengan salah satu indikatornya adalah karya ilmiah bereputasi yang memiliki implikasi substansial pada kontribusi keilmuan. Hal ini tidak terbatas pada publikasi di jurnal ilmiah, tapi juga paten termasuk didalamnya. Kontribusi keilmuan yang dimaksud adalah lebih kepada novelty atau kebaruan yang dikontribusikan dari setiap karya.
Salah satu implikasinya, mendapatkan paten menjadi tidak berarti jika tidak kompetitif, jika publik tidak memanfaatkannya. Demikian pula dengan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sekadar memasang sebuah alat tertentu di desa, tetapi bagaimana menemukan jalan agar sains dan teknologi memiliki pijakan yang kuat dalam menjawab tantangan di masyarakat desa dan daerah terpencil.
Pengembangan budaya ilmiah unggul dalam penerapannya di masyarakat mensyaratkan setiap invensi memiliki basis saintifik yang solid. Melalui kiprah para ilmuwan yang menjalankan Dharma-nya dengan berlandas pada prinsip ini, pengabdian kepada masyarakat akan mampu meletakkan kepemimpinan ilmiah unggul ITB dalam meretas jalan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.*
Keberpihakan kepada Masyarakat
Dr. Yuli SetyoIndartono
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITBPENGABDIAN kepada masyarakat yang dilakukan ITB merupakan penerapan hasil kepakaran sivitas akademika ITB untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Jangkauan kegiatan ini mencapai daerah luar Jawa dan daerah perbatasan terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T). Prioritas program pengabdian kepada masyarakat ITB meliputi pemberdayaan desa, reaktivasi ekonomi, mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana, serta pengembangan industri kreatif dan pariwisata.
Fokus pada desa dan daerah 3T memang bukan merupakan shortcut atas tantangan kewilayahan dan keadilan, tetapi merupakan upaya yang secara global diamanatkan dalam kerangka SDGs mengenai inklusivitas, dengan semangat bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapa pun atau no one left behind.
Sejatinya memang tidak ada jalan pintas, baik secara literal bahwa para ilmuwan yang melakukan pengabdian memerlukan waktu dan usaha yang tidak mudah untuk mencapai lokasi komunitas, maupun proses penerapan sains dan teknologi dalam konteks sosial, kultural, dan keterbatasan sumber daya.
Semua pengalaman ini menjadi berharga bukan saja bagi sivitas akademika ITB, tetapi juga diharapkan bagi masyarakat setempat, serta pengembangan sains dan teknologi dalam petualangannya menemukan konteks lokal dan potensi replikasi dan eskalasi dalam menjawab tantangan pembangunan di daerah lain yang serupa di Indonesia.*
Mencipta Kesejahteraan Masyarakat Harmoni
M B f Merawat Bios er




Pendekatan Multidisiplin

Mulai Bibit hingga Pascapanen 13. Bekal Es Para Nelayan
Mesin Pembuat Es Ramah Lingkungan
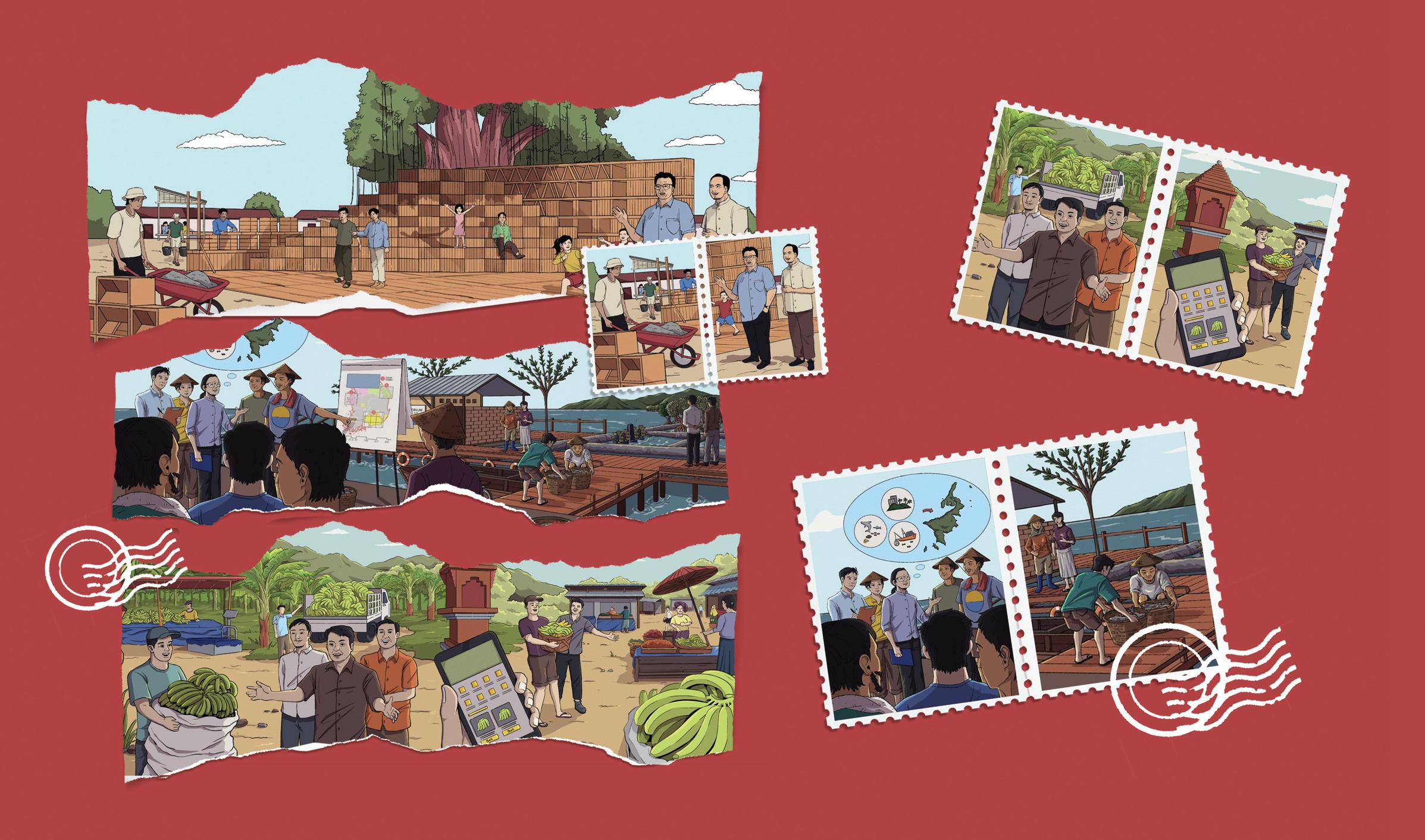
Mencari Solusi Alternatif Pengganti Es Balok
14. Peternakan Sapi Nirlimbah Manfaat Ekstra Lumpur Sisa Biogas Pemanfaatan Biogas di Pangalengan 15. Kelapa untuk Mandiri Energi Pengembangan Energi Baru Terbarukan dari Produk Turunan Kelapa 191
16.
Menjaring Energi Matahari
202 205 209 214 223

Bagian 1 Merawat Biosfer
Tanah dan air yang kita tinggali semakin terbebani. Intervensi sains dan teknologi terfokus untuk mempromosikan keselarasan kehidupan di atas permukaan bumi, ketersediaan kebutuhan mendasar, terutama air, dan resiliensi terhadap perubahan iklim.


Mengurangi Beban Bumi

 Akhmad Zainal Abidin, Ph.D.
Akhmad Zainal Abidin, Ph.D.
Sampah identik dengan kotor, bau busuk, dan tidak sedap dipandang. Sebisa mungkin sampah segera disingkirkan. Akan tetapi, yang lazim terjadi sebenarnya hanyalah memindahkan gunungan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sampah. Padahal, sampah bisa memiliki nilai ekonomi asalkan mau memilahnya dengan benar. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan salah satu bentuk atas konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), dan menjaga ekosistem darat (SDG 15).
SAMPAH organik merupakan bagian terbesar dari sampah rumah tangga. Jumlahnya sekitar 50%-70% dari total sampah. Saat ini sampah organik kebanyakan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan bercampur dengan sampah-sampah lainnya. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah yang sangat mengganggu masyarakat. Lingkungan menjadi kotor, bau busuk, hingga menimbulkan masalah kesehatan karena banyaknya bakteri patogen yang terbentuk selama proses pembusukan.
Saat ini penanganan masalah sampah organik belum teratasi karena sistem dan teknologi pengolahannya yang sulit, memakan waktu lama, bau, kotor, dan produknya bernilai ekonomi rendah sehingga kurang dilirik.
Menjawab tantangan itu, ilmuwan ITB menghadirkan Masaro sebagai solusi terbaik dalam pengelolaan dan
pengolahan sampah. Metode ini dibuat oleh Ir. Akhmad Zainal Abidin, M.Sc., Ph.D. dari Kelompok Keahlian Perancangan Produk Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri. Zainal memiliki 10 paten yang terkait dengan Masaro.
Masaro merupakan akronim dari Manajemen Sampah Zero. Dengan metode ini, sampah tak perlu dikirim ke TPA. Semua bisa diolah tanpa ada residu dan mampu menghasilkan produk lain yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Syaratnya, semua sampah harus dipilah terlebih dahulu. Tanpa pemilahan, sampah sulit dimanfaatkan. Sampah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu sampah yang bisa membusuk (biodegradable) atau yang sering salah kaprah disebut dengan organik dan yang tidak membusuk atau nonbiodegradable. Kedua golongan ini bisa ditangani dengan Masaro. Teknologi Pelestari / 17
Mengubah nilai sampah organik
Sampah organik ada yang tergolong cepat membusuk, tetapi ada juga yang pembusukannya membutuhkan waktu lebih lama. Sampah yang mudah membusuk misalnya sisa makanan, sayur, dan buah. Sementara, yang lebih lama membusuknya misalnya daun dan kayu.
Dengan Masaro sampah yang mudah membusuk diubah menjadi Pupuk Organik Cair Istimewa (POCI) dan Konsentrat Organik Cair Istimewa (KOCI). Sementara, sampah yang sulit membusuk diubah menjadi media tanam dan kompos Masaro.
Secara teknis, sampah organik dipilah terlebih dahulu antara yang mudah dan sulit membusuk. Sampah yang mudah membusuk dimasukkan ke mesin pencacah sehingga bentuknya menjadi seperti bubur. Setelah itu diproses di instalasi pengolahan pupuk dan pakan organik (IPPO). Di sana terdapat beberapa proses. Pertama, bubur sampah tadi difermentasi di tangki. Fermentasi tersebut menggunakan katalis hasil penelitian bertahun-tahun yang disebut dengan katalis Masaro 1. Setelah itu bubur tersebut diperas. Hasil perasan kembali difermentasi dengan katalis Masaro 2. Proses ini kemudian menghasilkan POCI dan KOCI.
POCI bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan pertanian organik. Sementara, KOCI digunakan sebagai pakan pada ternak organik. Dari 1 kg sampah membusuk bisa menghasilkan 12 liter POCI/KOCI. Harga jual untuk 12 liter POCI/KOCI setara dengan satu gram emas. Sisa penyaringan berupa zat padat dimanfaatkan sebagai pupuk organik padat dan pakan ternak padat.
Sampah organik sulit membusuk juga diolah dengan dilakukan pencacahan memakai alat pencacah yang sama. Daun, kulit, atau buah-buahan keras menjadi berukuran sangat kecil. Hasilnya dicampur dengan sampah yang mudah membusuk. Produknya adalah media tanam atau kompos Masaro. Penggunaannya bisa untuk tanaman di dalam polybag.
Mengolah sampah anorganik
Sampah anorganik atau sampah yang tidak membusuk bisa dipilah menjadi tiga kelompok. Pertama, sampah yang bisa didaur ulang, misalnya sampah berupa plastik kerasan, kertas, logam, dan kaca. Sampah golongan ini sudah memiliki nilai jual karena industri sampah daur ulang sudah terbentuk. Masyarakat tinggal membawanya ke bank sampah atau ke pengepul, tukang rongsok atau diserahkan kepada pemulung. Semuanya akan masuk ke industri pengolahan sampah daur ulang.
Kelompok kedua ialah sampah yang bisa diubah menjadi energi atau sampah bakar. Sampah yang termasuk kelompok ini misalnya kayu, tisu, popok sekali pakai, pembalut, kain, serta karpet. Ketiga ialah sampah yang termasuk dalam bahan berbahaya, misalnya baterai, sampah yang mengandung PVC, styrofoam, dan polybrominated diphenyl ethers (PBDE). Dua kelompok sampah ini merupakan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampah berupa plastik film seperti bungkus makanan masuk dalam kategori ini. Dengan metode Masaro, sampah kategori ini diolah di kilang plastik Masaro. Kilang ini tak ubahnya seperti tungku pembakaran. Instalasi ini berupa insinerator yang terdiri atas bagian yang berbentuk dua tabung. Di dalam silinder tersebut terdapat tempat pembakaran dan pirolisis.
Sampah bakar dan plastik film dibakar di insinerator yang dinamai instalasi pengolahan sampah anorganik (IPSA). Hasil pembakaran kemudian diolah sehingga menjadi berupa zat cair yang bisa digunakan sebagai bahan bakar yang bisa digunakan untuk industri makanan, kompor minyak, petromaks, genset, sebagai bahan bakar yang bisa digunakan oleh pedagang kaki lima. Bisa juga dimanfaatkan sebagai pestisida. Abu sisa pembakarannya bisa dimanfaatkan untuk media tanam.
Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, asap hasil pembakaran yang dilepaskan ke udara sudah memenuhi kriteria Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini karena asap pembakarannya dibersihkan terlebih dahulu di komponen yang berbentuk kotak berada di antara dua tabung.
Alternatif pengolahan sampah
Pengolahan sampah menggunakan IPPO maupun IPSA tidak menimbulkan bau. Lokasi pengolahan pun terjaga tetap bersih. Asap pembakaran juga relatif tidak menimbulkan pencemaran karena dibersihkan dengan wet scrubber. Tidak jadi soal jika instalasi ini dibuat di dekat area permukiman.
Dari sisi operasional, biayanya tergolong lebih murah ketimbang pengolahan sampah dengan pengangkutan ke TPA. Biaya pembuangan untuk setiap ton sampah Rp100.000-Rp560.000. Belum lagi biaya angkut setiap hari dari rumah warga hingga ke TPA.
Sementara, jumlah produksi sampah Indonesia setiap tahun sudah men capai 67 juta ton per hari dan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tidak semua sam pah terangkut. Akhirnya terjadi tumpukan sampah di tempat penam pung an sementara yang biasanya berada tidak jauh dari perumahan warga. Warga harus menghadapi bau sampah dan peman dangan yang tidak sedap dipandang.
Instalasi pengolahan sampah Masaro bisa mengolah sampah 5-10 ton per hari. Biaya investasi awal untuk pembangunan instalasi ini seluruhnya hampir Rp3,5 miliar. Akan tetapi, instalasi ini menghasilkan berbagai produk yang memiliki nilai jual. Dengan menggabungkan penjualan produk POCI, KOCI, pestisida organik, kompos padat dan cair berpotensi menghasilkan Rp3,9 miliar setiap bulan. Menurut perhitungan, semua modal investasi bisa kembali setelah dua tahun.
Untuk menyiasati ketersediaan modal, instalasi pengolahan sampah Masaro bisa dibuat untuk kepentingan komunal. Katakanlah instalasi ini dirancang untuk menyelesaikan sampah di suatu kota/kabupaten. Maka, IPPO bisa dibangun di setiap kabupaten atau kota, sedangkan IPSA dibuat di setiap desa/kelurahan atau di setiap pasar. Pengelolaan IPSA bisa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Skenario lainnya, insinerator bisa dibuat di tingkat kecamatan. Industri kreatif yang memanfaatkan sampah daur ulang juga bisa digalakkan di setiap kecamatan. Setiap desa/kelurahan dan pasar memiliki instalasi pengolahan sampah berupa RKM (Rumah Kompos Masaro) yang dikelola oleh BUMDes.
Dua alternatif tersebut bisa menjadi solusi pengolahan sampah yang mampu mengolah semua jenis sampah. Selanjutnya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan setiap kota/kabupaten.
Instalasi pengolahan sampah Masaro telah dibangun di berbagai daerah di Indonesia dengan kapasitas yang beragam, mulai dari skala kecil hingga ribuan ton per hari. Semakin lama kapasitas dan efektivitasnya semakin bertambah seiring dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan. IPPO Masaro sudah dibangun di Cilegon, tungku bakar Masaro sudah didirikan di Institut Teknologi Sumatera (Itera).
Instalasi pengolahan sampah sudah beroperasi di beberapa desa di Bali, Desa Babakan Ciwaringin, Cirebon, dan Desa Tinumpuk, Indramayu, juga Cibadak, Sukabumi. Pertumbuhan yang cukup cepat akhir-akhir ini terdapat pada Unit RKM (Rumah Kompos Masaro), mulai dari Kabupaten Gorontalo, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang. Hal ini mungkin dipacu oleh investasi yang relatif murah dan kelangkaan atau mahalnya harga pupuk kimia yang saat ini terjadi.
Untuk skala kota, saat ini sedang dibangun Unit Masaro di Kota Dumai untuk menangani sampah 100 ton per hari Masaro pun sudah dicobakan di berbagai daerah seperti Cirebon, Indramayu, Karawang, Sukabumi, Ciamis, dan lainnya.
Meski sudah berhasil di tempat-tempat itu, tidak semua pembuat kebijakan langsung dengan mudah menerima ide Masaro ini. Hal ini karena Masaro mengubah paradigma yang sudah kadung melekat. Pengolahan sampah yang dikenal selama ini menganut konsep kumpul–angkut–buang. Akibatnya, penanganan sampah menjadi berbiaya tinggi. Ketidaktersediaan anggaran membuat persoalan sampah tidak bisa dituntaskan.
Sementara, di Masaro konsepnya pilah–angkut–proses–jual. Konsep ini tidak hanya melihat sampah sebagai sebuah beban tanggung jawab, tetapi juga sumber pendapatan yang menguntungkan.
Masaro telah membuktikan sampah mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pemilahan sampah menjadi proses pembeda. Sampah yang tercampur akan menjadi beban. Hanya sampah terpilah yang bisa menjadi aset berharga.***
Pertanian Unggul dengan Masaro
BABAKAN merupakan desa yang luas arealnya 750 ha dan luas wilayah permukiman penduduknya 583 ha. Desa ini memiliki 69 sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, PT) dan 72 pondok pesantren. Desa Babakan memiliki wilayah permukiman yang padat. Sekitar 13.000 pelajar dari luar bermukim di pondok pesantren dan memiliki 4.600 penduduk lokal. Padatnya penghuni Desa Babakan ini memunculkan permasalahan sampah yang serius berupa sulitnya mengelola dan mengolah sampah, merebaknya sampah, bau tak sedap, mengganggu lingkungan dan kesehatan, serta berdampak buruk pada sistem pendidikan. Ditemukan banyak tumpukan sampah di sepanjang jalan, pinggir sungai, dan lahan-lahan kosong. Ironisnya, tidak ada manajemen pengolahan sampah di Desa Babakan. Sistem penanganan sampah yang masih digunakan sampai sekarang adalah pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, dan pembayaran. Sampah tidak diproses, tetapi hanya dikumpulkan dalam bentuk sampah tercampur dan kemudian diangkut menggunakan truk sampah menuju TPA. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di
TPA yang sangat mengganggu kehidupan penduduk di sekitarnya. Permasalahan sampah seperti ini merupakan tipikal yang terjadi di mayoritas desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Sampah yang dihasilkan dari desa ini sekitar 13.955 kg/hari yang terdiri atas 50% sampah organik, 38% sampah anorganik, dan 12% sampah daur ulang. Sampah berasal dari 69 sekolah, 72 pesantren, dan 1.453 KK penduduk lokal. Teknologi Masaro diterapkan dalam kegiatan di Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon berupa pelatihan pengolahan sampah organik untuk Babakan Desa Zero Waste. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah mudah membusuk dan sulit membusuk. Sampah anorganik juga dibagi menjadi dua jenis yang terdiri atas anorganik nondaur ulang dan anorganik daur ulang.
Pada pelatihan diajarkan cara penanganan sampah organik melalui gerakan Masaro Polybag Farming, yaitu cara bertani dengan menggunakan polybag mengikuti tuntunan Masaro.
Dengan metode ini seluruh sampah organik mampu dihabiskan di rumah dengan formulasi media tanam 4321, yaitu media tanam yang terdiri atas tanah, sampah organik, kotoran hewan, dan arang sekam padi dengan perbandingan volume berturut-turut 4:3:2:1. Diawali dengan memasukkan sampah organik pada bagian bawah polybag lalu diikuti di atasnya oleh campuran tiga media tanam lainnya atau keempat bahan dicampur bersamasama dari awal dan disiram dengan larutan POCI. Setelah itu, media tanam dibiarkan selama satu minggu agar terjadi proses pengomposan dan pendinginan. Bibit sayur dan buah dapat ditanam setelah itu dan pemupukannya dilakukan dengan POCI.
Polybag farming yang sudah dicobakan di pesantren membuktikan model ini bisa diterapkan untuk mencapai kemandirian pangan. Setiap santri diminta memelihara tanaman dalam 15 polybag . Ada yang menanam kangkung, terong, tomat, cabai, dan lainnya. Secara keseluruhan terdapat 15 jenis tanaman yang dikembangkan. Hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan para santri.
Sistem
pertanian
Tanaman lainnya
Selain menyelesaikan persoalan sampah, produk hasil pengolahan sampah Masaro terbukti ampuh untuk meningkatkan kualitas pertanian. Pupuk organik yang dihasilkan Masaro cocok untuk berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, sayuran, palawija, dan tanaman kebun lainnya. Keberhasilan Masaro pada tanaman padi bisa dilihat di Desa Tinumpuk, Indramayu. Produk Masaro membuat masa tanam padi semakin pendek. Dicobakan ditanam 10 hari lebih lambat dibandingkan dengan padi yang lain. Hasilnya justru bisa panen dua minggu lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Saat sawah lain diserang hama wereng, padi dengan Masaro justru mengalami kenaikan produksi. Produk Masaro memang bukan sekadar pupuk, tetapi juga bisa disemprotkan di tanaman akan menjadi pestisida. Batang padi menjadi keras, hewan pengerat yang biasa memakan batang jadi tidak kuat. Aromanya juga tidak disukai tikus. Ulat dan keong jadi tidak bisa berkembang biak. Itu sebabnya, Masaro tidak bisa dipandang sebagai pupuk
semata. Masaro sudah dicobakan pula pada tanaman jagung, kopi, juga kangkung.
Penelitian terus dikembangkan untuk menguji lebih banyak tanaman yang dipelihara dengan produk hasil Masaro, misalnya sawit dan karet. Selama ini sawit dituding sebagai tanaman perusak tanah. Masaro yang digunakan pada sawit bisa membuatnya menghasilkan pupuk sendiri sehingga tidak memakan unsur hara yang ada di tanah. Jika hasil pengembangan ini berhasil, Masaro bisa membantu kesuburan tanah di area perkebunan sawit. Uji coba ini masih dilakukan di Lampung Timur pada lahan sekitar 20 ha.
Uji coba pada berbagai jenis tanaman ini sangat penting untuk melihat berbagai potensi memasarkan produk hasil Masaro. Akan tetapi, hal itu tidak mudah dilakukan karena untuk riset ini memerlukan lahan yang cukup luas. Soal mengelola produk hasil Masaro ini memang menjadi tantangan tersendiri. Penelitian terkait sejauh mana dampak produk Masaro pada tanaman atau hewan ternak merupakan ranah keilmuan pertanian. Perlu kolaborasi yang luas untuk mengembangkan uji coba terhadap lebih banyak tanaman dan hewan ternak.
Selama tiga tahun belakangan, peneliti menjajal langsung menanam berbagai tanaman yang dirawat dengan produk Masaro. Dengan demikian, bisa dapat diketahui secara pasti kinerja produk yang digunakan. Lewat pengajuan permohonan pengelolaan lahan-lahan milik pemerintah maupun lembaga, diharapkan bisa memperluas lahan yang bisa digunakan untuk menguji produk-produk Masaro.
Semua langkah itu perlu dilakukan untuk memberi bukti nyata sehingga petani tertarik untuk menggunakan produk Masaro. Seperti diketahui, dominasi pupuk kimia sudah sedemikian kuat. Tidak mudah mengajak petani untuk beralih ke pupuk organik. Petani tidak mau bertaruh karena pupuk kimia sudah dirasa memberikan hasil yang baik.
Sebagaimana Masaro menawarkan cara pandang baru dalam pengolahan sampah, produk-produk yang ditawarkan pun masih asing bagi petani. Tidak semua petani punya keberanian untuk mencoba produk baru. Cara paling jitu untuk mengubahnya dengan memberi contoh nyata dari berbagai keberhasilan yang sudah dicapai. Seperti POCI pada tanaman padi IR64 di Indramayu menghasilkan bulir padi yang lebih baik.
Saat dikeringkan hanya susut 14%. Yang utama, biaya tanamnya 2/3 lebih murah. POCI yang digunakan pada perkebunan kopi di Girimekar, Manglayang, Kabupaten Bandung menghasilkan buah yang lebih banyak. POCI untuk tomat di Majalengka juga menunjukkan hasil yang baik.
Sementara, produk KOCI sebagai pakan sapi di Kabupaten Bandung Barat berhasil meningkatkan bobot sapi. Kenaikannya rata-rata 30-45 kg per bulan dengan biaya pakan hanya Rp1.000 setiap kilogram. Hasil yang menggembirakan juga dirasakan peternak kambing di Cicalengka. Rumput pakan yang disemprot dengan KOCI 10 menit sebelum diumpankan terbukti bisa meningkatkan nafsu makan kambing. Kambing jadi cepat besar dengan pertumbuhan rata-rata 5,5 kg setiap bulan. Kegembiraan yang sama dirasakan peternak ayam di Ciamis, petani ikan lele dan nila di Gorontalo yang juga telah mencoba pakan tanpa bahan kimia ini.
Semakin banyak bukti nyata, semestinya upaya untuk memperkenalkan dan memperluas penggunaan produkproduk Masaro akan semakin mudah. Semakin banyak pula orang yang menikmati berkah dari sampah.***

Misi Ultrafiltrasi

 Dr. Khoiruddin
Dr. Khoiruddin
Pak Empi (56) tersenyum senang. Warga RT 02/RW 05 Kampung Cisasawi, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat itu kini tak perlu lagi jauhjauh dan bersusah payah membeli air minum galon isi ulang. Sekarang di rumahnya sudah ada alat penjernih air berbasis membran temuan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D. Penyediaan akses terhadap air bersih serta inovasi teknologi yang menyertainya sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan berkelanjutan sanitasi dan air bersih (SDG 6) serta industri, inovasi, dan infrastruktur (SDG 9).
DENGAN alat penyaring air yang memanfaatkan teknologi tepat guna tersebut, keluarga Pak Empi dan 25 orang tetangga dari sekitar 6 kepala keluarga (KK) bisa mendapatkan air bersih, yang bahkan layak minum. Karena itu, saat menerima bantuan tersebut dari tim pengabdian kepada masyarakat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB yang dipimpin Dr. Khoiruddin, S.T., M.T., Pak Empi sempat menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih. Tim pengabdian kepada masyarakat di Desa Cihanjuang yang digelar sepanjang Januari-November 2020 ini beranggotakan Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D., Dr. Anita K. Wardani, S.T., M.T. (dosen ITB), Dr. Putu Teta P. Aryanti, S.T., M.T. (dosen Unjani), serta Widda Rahmah, S.T., M.T. (mahasiswa ITB).
Teknologi yang diperkenalkan dan diberikan kepada masyarakat adalah alat penjernih berbasis membran bernama IGW Home Ultrafilter yang menggunakan teknologi ultrafiltrasi
tertanam tanpa listrik untuk penyediaan air minum. IGW merupakan kependekan dari nama penemu alat penjernih air berbasis membran ini yaitu Prof. Ir. I Gede Wenten, Ph.D Dr. Khoiruddin, S.T., M.T., yang merupakan dosen Fakultas Teknik Industri (FTI) dari Kelompok Keahlian Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia, menjelaskan, teknologi ini dipilihkan buat warga Kampung Cisasawi dengan sejumlah pertimbangan. Ia mengatakan, Kampung Cisasawi sebenarnya tidak berada di pedalaman. Namun, sebagian besar warganya masih kesulitan memperoleh air berkualitas, baik untuk minum maupun kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut dimungkinkan karena Kampung Cisasawi masih belum terjangkau layanan air bersih dari PDAM dan jauh dari depot penjualan air minum. Hal itu diperparah dengan pandemi COVID-19 yang tengah berkecamuk pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tim LPPM ITB. Banyak warga Kampung Cisasawi kehilangan pekerjaan karena berbagai pembatasan sosial dan ekonomi.
Tim pengabdian kepada masyarakat dari LPPM ITB berharap, bantuan alat penyedia air bersih dan minum ini bisa meringankan biaya hidup sehari-hari masyarakat. Apalagi, alat ini tidak membutuhkan listrik untuk pengoperasiannya.
Pada awalnya, tim pengabdian kepada masyarakat ITB mencoba mengembangkan unit membran tertanam yang dapat digunakan untuk mengolah air hujan menjadi air bersih dan air minum. Namun, rencana itu berubah setelah mengetahui bahwa warga Kampung Cisasawi telah menggunakan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari.
Merespons kondisi yang ada di lapangan, tim pengabdian kepada masyarakat ITB kemudian mengembangkan unit penyedia air bersih berbasis membran terintegrasi.
Menurut Khoiruddin, pilihan ini bertujuan agar alat penjernih yang dikembangkan dapat digunakan untuk mengolah air sumur yang telah ditampung menjadi air bersih dan air minum sekaligus.
Unit terintegrasi ini juga dapat memanfaatkan ketinggian penyimpanan tangki air yang sudah ada sehingga tidak memerlukan listrik untuk pengoperasiannya. Dengan begitu, masyarakat tidak terbebani biaya listrik. Selain itu, alat penjernih air ini bisa digunakan untuk kondisi darurat dan bahkan bencana alam ketika jaringan listrik tidak ada.
Secara teknis, air dari sumur yang sudah ditampung di toren atau bak penampungan dengan ketinggian cukup, langsung dialirkan ke dalam tabung alat penjernih air. Air yang keluar dari alat penjernih ini sudah bersih dan layak pakai.
Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, tim pengabdian kepada masyarakat ITB menyiapkan alat penyedia air bersih dan air minum bernama IGW Home Ultrafilter. Penyedia air ini menggunakan teknologi filtrasi air minum berbasis membran yang menggabungkan empat tahapan proses secara terintegrasi dalam satu alat. Untuk menghasilkan air bersih dan air layak minum, alat ini menggunakan dua tabung berbeda ukuran, berdiameter besar dan kecil.
Produk yang dihasilkan dari unit ultrafiltrasi di tabung besar ini adalah air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agar air tersebut layak minum, proses dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Air dari tabung besar dilanjutkan ke tabung yang lebih kecil yang hasil penyaringannya bisa langsung diminum. Khoiruddin menjelaskan, tahap filtrasi utama memanfaatkan membran ultrafiltrasi hollow fiber dengan ukuran pori rata-rata 50 nanometer (nm) yang dilapisi nanopartikel ZnO sebagai agen antibakteri. Membran ultrafiltrasi pada tahapan ini bisa memisahkan zat besi (Fe3+), koloid, mikroba, dan partikulat secara efektif dengan tetap menjaga kandungan mineral di dalamnya. Alat ini dilengkapi karbon aktif pada tahap penyaringan awal untuk menghilangkan bau, zat organik, dan sisa klorin bebas. Pada tahapan pengolahan akhir, biokeramik digunakan untuk mengembalikan kesegaran dan mineral penting dalam air. Biokeramik ini mengandung partikel antibakteri untuk tahap desinfeksi akhir.
Pelestari
Setelah menyiapkan alat penyedia air, tim pengabdian kepada masyarakat ITB berembuk dengan warga Kampung Cisasawi. Hal yang dibicarakan terkait tempat yang tepat untuk instalasi serta penjelasan mengenai cara pengoperasian alat penyedia air ini.
Dari rembukan dengan warga, alat penyedia air ini kemudian dipasang di rumah Pak Empi. Di sekitar rumah Pak Empi ada 6 kepala keluarga lain dengan jumlah 25 orang yang bisa menikmati air bersih dari alat penyedia air ini.
Kendati hanya menyediakan di satu titik, yaitu kediaman Pak Empi, Khoiruddin mengatakan, warga Kampung Cisasawi mengaku sangat terbantu dengan alat penyedia air ini. Paling tidak, mereka kini tidak harus membeli air galon untuk minum dan kebutuhan memasak sehari-hari. Setelah ada alat tersebut, kalau membutuhkan air, warga tinggal datang ke rumah Pak Empi yang jaraknya tidak jauh.***
Terinspirasi Filtrasi Artesis Alamiah
MEMBRAN adalah selaput, kulit tipis, atau lembaran bahan tipis yang berfungsi sebagai pemisah selektif. Salah seorang pakar teknologi membran ternama –bukan hanya di Indonesia, tetapi juga mancanegara– adalah Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc., Ph.D. yang saat ini menjabat Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sejak melakukan riset, penelitian dan pengembangan pada awal dekade 1990-an, lebih dari 15 paten dikantongi IGW, sapaan akrab Prof. Wenten. Dari mulai aplikasi teknologi membran untuk industri pengolahan bir hingga berbagai varian penjernih air. Sebagian besar paten yang dikantongi IGW sudah diaplikasikan untuk kebutuhan industri. Untuk varian penjernih air, aplikasi teknologi membran tertanam karya Prof. Wenten ini sudah banyak diperkenalkan kebermanfaatannya di masyarakat, dari mulai daerah bencana hingga kawasan perkotaan dan perdesaan yang mengalami krisis air bersih.
Dr. Khoiruddin, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik Industri (FTI) dari Kelompok Keahlian Perancangan dan Pengembangan Proses Teknik Kimia, mengungkapkan, penemuan dan penciptaan berbagai varian alat penyedia dan penjenih air berkode “IGW” tersebut terinsiprasi filtrasi alamiah dalam pembentukan mata air artesis.
Dalam proses filtrasi alamiah, contohnya air hujan yang meresap ke perut bumi akan melewati saringan berbagai jenis batuan dan pasir sebelum terkumpul dalam sumur atau mata air artesis.
Persoalannya, keberadaan mata air semakin langka. Semakin berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan konservasi menjadi permukiman, perkebunan, destinasi wisata dan pembangunan infrastruktur lainnya, menjadi penyebab utama. Dampaknya, krisis air kerap dialami warga yang mengandalkan sumber dari mata air tersebut.
Menurut Khoiruddin, warga yang tinggal di kawasan rentan krisis air bersih tersebut biasanya beralih mengandalkan air hujan atau sumur-sumur buatan. Masalahnya, air hujan itu tidak datang sepanjang tahun. Begitu juga dengan air sumur yang terkadang kering di musim kemarau. Belum lagi menyangkut kelayakan air tersebut untuk konsumsi sehari-hari.
Sebagai solusi, Prof. Wenten mengembangkan berbagai varian penyedia air, termasuk yang menggunakan teknologi membran tertanam tanpa listrik. Penyedia air ini dianggap cocok untuk daerah perdesaan dan wilayah bencana.
Berbeda dengan pembentukan mata air alami, proses filtrasi dengan teknologi membran tertanam ini terdiri atas beberapa tahap yaitu penyaringan oleh pasir, bebatuan, membran, dan biokeramik.
Pasir hitam yang merupakan oksida besi berfungsi sebagai tahap filtrasi awal sekaligus sebagai agen antibakteri. Bebatuan pada tahap selanjutnya membantu proses remineralisasi air. Membran polipropilena merupakan filter utama dalam sistem ini. Ukuran pori yang relatif kecil (50 nm) membantu menyisihkan besi, partikulat, koloid, dan mikroba secara efektif, tetapi tetap menjaga kandungan mineral dalam air. Filtrasi oleh membran menghasilkan air yang jernih sejernih kristal.
Karena sistem ini dioperasikan dengan gaya gravitasi, fluks membran akan bertahan pada jangka waktu lama tanpa perlu pemeliharaan yang intensif. Sementara itu, biokeramik pada tahap akhir menghasilkan air lebih segar dan kandungan mineral yang terjaga.
Berbagai varian alat penyedia air dengan teknologi membran tertanam ini merupakan solusi potensial untuk penyediaan akses terhadap air minum atau air bersih, baik tadah hujan maupun sumber air lain bagi masyarakat di perkotaan, perdesaan, hingga daerah terpencil.
Selain mampu menghasilkan air berkualitas, teknologi membran juga dapat didesain untuk berbagai skala dengan relatif mudah, dari skala rumah tangga, lingkungan RT/RW, bahkan satu kelurahan. Terlepas dari kesuksesan penciptaan dan perakitan berbagai varian unit alat penyedia air dalam berbagai ukuran dan kapasitas, Khoiruddin mengungkapkan, ada sebuah impian besar yang hingga saat ini belum terealisasi. Impian besar itu adalah instalasi alat penyedia air bersih berbasis teknologi membran tertanam di alam terbuka dengan areal yang cukup luas.
Dalam implementasinya, teknologi membran tertanam ini diaplikasikan di sebuah kolam besar sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh lingkungan masyarakat yang lebih luas, misalnya desa atau kawasan tertentu yang memang membutuhkan air bersih.
Dijelaskan, seperti pada aplikasi penyedia air bersih berbentuk tabung, membran yang berfungsi sebagai penyaring akhir, tertanam di dasar kolam Membran itu tertanam di bawah rendaman pasir dan batuan lain sebagai penyaring pertama, baik berasal dari air hujan, sungai atau sumber air lainnya.
Khoiruddin menyebutkan, dengan tertanam di dasar kolam warga hanya akan bertindak sebagai penerima manfaat tanpa harus mengutak-atik membrannya. Tanpa kewajiban melakukan perawatan, warga hanya memanfaatkan air bersih hasil penyaringan membran di dasar kolam atau danau itu. Satu-satunya risiko dari aplikasi membran tertanam di dasar kolam adalah kapasitas produksinya yang akan terus berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Kemampuan membran menyaring air bersih pun akan terus berkurang karena timbunan endapan sisa penyaringan air yang semakin banyak.
Kendati membutuhkan dana dan effort yang relatif lebih besar, Khoiruddin memastikan, impian menginstalasi teknologi membran tertanam di areal yang lebih luas ini tidak pernah padam. Karena itu, ia pun berharap, suatu saat nanti, bakal ada kerja sama terjalin dengan pemerintah daerah sehingga impian besar tersebut bisa terealisasi. ***










































































Petualangan Kecil tentang Krisis Iklim

 Dr. rer. nat. Rima Rachmayani
Dr. rer. nat. Rima Rachmayani
Mengapa cuaca terasa panas sekali? Apa yang terjadi jika es di kutub mencair? Mengapa iklim bisa berubah? Apa itu efek rumah kaca? Ini bukan pertanyaan mudah bagi orang awam, apalagi anakanak. Menjelaskan fenomena alam yang sarat dengan data saintifik bukan persoalan mudah. Memberikan edukasi perubahan iklim dan segala dampaknya serta terkait pemanasan global sejak dini menjadi upaya penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan penanganan perubahan iklim (SDG 13) dan implementasi pendidikan bermutu (SDG 4).
TIM peneliti ITB yang dipimpin oleh Dr. rer. nat. Rima Rachmayani, S.Si., M.Si. dari Kelompok Keahlian Oseanografi memilih buku sebagai media untuk menyampaikan berbagai hal penting tentang pemanasan global untuk diketahui anak-anak.
Sebagai ahli waris bumi ini, sudah semestinya anak-anak menjadi bagian penting dalam kampanye global pemanasan global. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang apa itu pemanasan global dan bagaimana dampaknya pada kehidupan mereka. Kampanye untuk membangun kesadaran publik tentang pemanasan global tidak bisa lagi hanya menargetkan orang dewasa sebagai sasarannya. Penting untuk mulai melibatkan anak-anak dalam isu ini. Hal ini tidak bisa sekadar menambahkan anak sebagai audiens. Agar tepat sasaran, materi-materi terkait pemanasan global perlu disampaikan dalan bahasa anak-anak yang mudah dipahami. Inilah yang coba dilakukan oleh ilmuwan ITB melalui penerbitan buku anak yang fokus membahas tentang pemanasan global.
Sampai saat ini sudah ada tiga buku anak yang diterbitkan, yaitu Bumiku Demam Tinggi, Kisah Petualangan tentang Pemanasan Global (2019); Lautku Makin Tinggi, Kisah Petualangan tentang Kenaikan Muka Air Luat (2020); dan Misteri Pantai yang Hilang, Kisah Petualangan tentang Abrasi Pantai (2021). Buku-buku ini menjadi bagian dari program pendidikan untuk anak yang bertajuk “Eduventure on Climate Change for Kids (Edu-Click)”.
Buku ini merupakan buku cerita yang sarat dengan gambar dan warna-warna ceria khas anak-anak. Materi-materi tentang perubahan iklim disampaikan dengan narasi yang mudah dipahami. Cerita ditulis oleh Sarah Ismullah, S.Si., M.B.A., seorang penulis buku anak yang berlatar belakang pendidikan oseanografi. Pembuatan buku ini disupervisi oleh dosen dan peneliti oseanografi Dr. rer. nat Rima Rachmayani, S.Si., M.Si., Mika Rizki Puspaningrum, S.Si., M.T., Ph.D., Ivonne M. Radjawane, Ph.D., Ir. Hanif Diastomo, S.Si, M.Sc., dan Dr. Ayi Tarya, sebagai editor ahli.
Cerita di buku-buku ini berpusat pada Banda dan Natuna, kakak beradik yang sering bermain bersama. Nama mereka sengaja diambil dari nama-nama laut di Indonesia, tidak lain agar memantik rasa ingin tahu anak-anak terhadap laut Indonesia.
Fenomena pemanasan global coba dituturkan dengan analogi sederhana sehingga anak-anak mudah mengidentifikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pengandaian bumi yang semakin panas dengan tubuh yang demam. Bagi anak-anak, kenaikan suhu bumi yang terjadi gradual yang berdampak pada lingkungan merupakan fenomena yang sulit dibayangkan. Akan tetapi, saat diandaikan seperti tubuh yang sedang sakit karena demam, fenomena itu menjadi mudah dicerna. Demam merupakan gejala tubuh yang relatif sering dialami anakanak. Saat demam, biasanya anak menjadi lesu, tidak nafsu makan, dan tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Jika manusia bisa demam, bumi kita juga bisa demam. Pengandaian semacam ini menjadi pintu masuk untuk membahas pemanasan global lebih lanjut.
Pengenalan fenomena alam juga diceritakan melalui cerita perjalanan yang seru. Perjalanan ke pantai menjadi salah satu kegiatan wisata favorit bagi keluarga Indonesia.
Sebagai negeri yang dua pertiga wilayahnya terdiri atas lautan, Indonesia memiliki banyak laut yang indah tersebar dari Miangas hingga ke Pulau Rote. Berwisata ke pantai menjadi kesempatan untuk mengenali ekosistem pesisir dan laut.
Dalam buku Lautku Makin Tinggi, Natuna dan Banda tidak hanya diceritakan berenang dan berfoto-foto di pinggir pantai. Mereka mengamati berbagai hal di sekitar pantai. Ada hutan bakau, kampung nelayan, serta gelombang laut yang semakin naik ke daratan.
Anak-anak bisa apa?
Hal yang menarik dari buku ini yaitu ceritanya memantik anak untuk turut melindungi bumi dari kerusakan akibat pemanasan global. Anak-anak diajak untuk menyelami apa saja yang bisa terjadi saat bumi berubah menjadi lebih panas dan air di permukaan laut menjadi lebih tinggi.
Pulau-pulau bisa terendam air, darat tergerus air, makhluk hidup di daratan bisa berkurang, kelangsungan hidup manusia pun akan terancam. Banjir bisa terjadi lebih besar dan lebih sering, bangunan tenggelam, keselamatan manusia pun dipertaruhkan. Anak-anak jadi terdorong untuk terlibat untuk mencegah hal buruk terjadi di tempat tinggalnya.
Seperti tubuh yang sakit bisa sembuh dengan pengobatan dan perawatan tertentu, demikian pula dengan kerusakan bumi yang bisa dipulihkan melalui usaha-usaha tertentu. Bumi yang semakin panas bisa diantisipasi dengan menanam lebih banyak pohon, berhemat air, hemat energi, serta mengurangi produksi sampah. Air muka laut yang semakin tinggi bisa diantisipasi dengan memperbanyak hutan bakau dan merancang bangunan di pesisir yang tahan bencana. Hal-hal seperti ini akan mendorong anak untuk turut terlibat sedini mungkin. Mereka jadi tahu hal baik apa yang bisa mereka lakukan untuk ikut menyelamatkan bumi. Selain itu, mereka terinspirasi untuk melakukan hal baik lainnya saat mereka dewasa nanti. Misalnya, terinsipirasi untuk menjadi arsitek yang bisa merancang bangunan yang ramah lingkungan.
Detektif cilik dan kamus kecil
Ada beberapa hal yang menarik dari buku anak ini. Salah satunya ialah bagaimana penulis berusaha membumikan berbagai data saintifik yang digunakan untuk mengidentifikasi pemanasan global. Penulis mengajak anak-anak menjadi oseanografer cilik yang bisa mengukur tinggi muka air laut.
Seperti mengukur tinggi badan manusia, meng ukur tinggi muka air laut juga memerlukan alat ukur dan titik acuan. Dengan berdiri tegak, tinggi badan diketahui dengan mengukur telapak kaki hingga ujung kepala. Sementara, pada muka air laut bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan pe ng a mat an pa sang surut air laut dan pe ng ukuran dengan satelit. Jika mengukur tinggi manusia menggunakan telapak kaki sebagai titik nol, pusat bumi merupakan titik nol saat mengukur tinggi laut.
Dengan radar altimetri yang terpasang di satelit akan mengirim sinyal ke permukaan bumi, termasuk ke permukaan laut. Sinyal itu kemudian dipantulkan kembali dari permukaan laut ke sensor altimetri. Tinggi muka air laut merupakan jarak antara satelit ke titik pusat bumi dikurangi jarak dari satelit ke permukaan bumi. Dengan bantuan gambar ilustrasi, konsep ini menjadi lebih mudah dicerna untuk anak usia sekolah dasar.
Memantik rasa ingin tahu anak-anak bisa juga dilakukan dengan memberi tantangan yang seru, salah satunya mengajak mereka menjadi detektif cilik. Menjadi detektif cilik merupakan salah satu bagian di buku ini yang
bertujuan untuk mengajak anak-anak mencermati lingkungan sekitarnya.
Kenaikan muka air laut merupakan fenomena yang tidak mudah diamati dengan mata telanjang. Akan tetapi, terdapat tanda-tanda di alam yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Anak diajak untuk melihat tanda-tanda alam yang bisa menjelaskan fenomena pemanasan global. Misalnya saja dengan melihat karang purba. Selain itu, dengan melihat petunjuk dari benda-benda ciptaan manusia. Misalnya saja dengan cerita tentang Baia, kota di Italia yang merupakan kota Romawi Kuno yang terletak di Teluk Naples.
Salah satu keunikan buku ini yang pasti tidak dimiliki buku lain ialah adanya Kamus Kecil Ilmu Kebumian. Bagian ini berisi istilah-istilah dalam ilmu kebumian yang digunakan dalam buku ini. Bisa jadi, istilah-istilah ini masih asing bagi anak-anak, bahkan juga bagi orang dewasa. Atau ada pula istilah-istilah yang sudah akrab didengar, tetapi definisi dan fungsinya belum dipahami. Daftar istilah ini akan menambah pengetahuan anak-anak dan orang dewasa yang mendampingi anak belajar. Beberapa istilah itu misalnya iklim, atmosfer, morfologi, oseanografer, sensor, pantai, sedimen intertidal, erosi, adaptasi, abrasi, gletser, dan lain-lain. Agar lebih mudah dipahami, selain penjelasan berupa teks, istilah-istilah ini juga disertai dengan gambar ilustrasi.
Buku-buku ini diserahkan ke sekolah untuk disimpan di perpustakaan. Harapannya buku ini bisa menjangkau semakin banyak pelajar dan berkontribusi meningkatkan pemahaman anak-anak terhadap isu krisis global dengan cara yang mengasyikkan.***
Menumbuhkan Kesadaran
Ahli Waris Bumi
TIM peneliti ITB yang dipimpin oleh Dr. rer. nat. Rima Rachmayani, S.Si., M.Si. dari Kelompok Keahlian Oseanografi merancang program pendidikan untuk anak-anak bertajuk “Eduventure on Climate Change for Kids (Edu-Click)”. Setelah sukses menggelar kegiatan ini tiga tahun berturut-turut, pada 2022 tim tengah mempersiapkan penyelenggaraan keempat.
Menjelaskan tentang apa, bagaimana, dan dampak dari perubahan iklim menjadi tantangan para ilmuwan. Publik dengan usia yang lebih dewasa saja belum seluruhnya memercayai krisis iklim, tidak heran jika upaya mengedukasi anak-anak menjadi lebih sulit. Salah satu strateginya ialah dengan menjadikan peningkatan suhu atau temperatur bumi sebagai titik pangkal. Peningkatan suhu menjadi parameter perubahan iklim yang paling mudah dirasakan. Merujuk Representative Concentration Pathway (RCP) 2.6-8.5, suhu bumi diperkirakan akan meningkat hingga 1–3,7 derajat Celsius pada tahun 2100. Akibatnya, laut akan menyerap panas lebih banyak dan lebih lama. Laut akan mengalami thermal expansion atau pemuaian kolom air laut. Muka air laut pun akan meningkat secara global. Peningkatan suhu bumi juga menyebabkan gletser (bongkahan es di atas permukaan), ice sheet (lapisan es gletser yang menutupi area seluas minimal 50.000 km persegi), dan sea ice (air laut yang membeku) mencair. Hal ini akan berkontribusi meningkatkan permukaan air laut. Permukaan air laut ternyata naik 60 persen lebih cepat dari prediksi yang pernah dikeluarkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
Peningkatan muka air laut ini diperburuk dengan adanya kerusakan akibat cuaca ekstrem seperti badai, puting beliung, dan tsunami. Permukaan air laut dunia mulai naik sekitar 3,2 milimeter setiap tahunnya. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan IPCC sebelumnya, yaitu sekitar 2 milimeter setiap tahun.
Di Indonesia, hampir seluruh pesisir mengalami kenaikan muka laut dengan rentang sedang hingga tinggi. Kenaikan tertinggi sebesar 0,76 cm per tahun. Diperkirakan muka air laut Indonesia naik hingga 19 cm pada 25 tahun mendatang. Kondisi ini meningkatkan kerentanan daerah pesisir di Indonesia, seperti Belawan, Sungai Liat Bitung, Ternate, dan Ambon. Kenaikan muka air laut secara keseluruhan pada 2025 yang tertinggi diprediksi terjadi di Ambon, yaitu sekitar 1,02-3,07 meter. Sementara, yang terendah di Muara Baru, yaitu sebesar 0,63-1,71 meter.
Kenaikan muka air laut ini mengancam setidaknya 24 lokasi minapolitan. Daerah-daerah seperti Jambi, Lampung, Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur menjadi rentan terhadap genangan. Ancaman serupa juga terjadi di sentra garam di Jawa, yaitu Cirebon, Indramayu, Rembang, dan Pati. Madura dan Nagakeo, NTT juga menghadapi ancaman serupa.
Kenaikan air laut membuat garis pantai semakin maju ke daratan. Dermaga pelabuhan perikanan akan tergerus gelombang. Kekuatan struktur bangunan di pantai jadi berkurang. Penurunan muka air tanah di Pulau Jawa bahkan sudah terjadi, terutama Jakarta. Penurunan ini akan membuat air laut semakin masuk ke daratan berupa banjir. Merujuk pada iklim di masa lampau (paleo climate) kondisi bumi di masa datang mirip dengan kondisi bumi pada 700.000 tahun lalu. Hal ini bisa terjadi karena pengulangan periode astronomi. Rotasi bumi, evolusi, eksentrisitas orbit, obliquity, dan lain-lain menunjukkan posisi yang mirip. Kemungkinan kondisi curah hujannya juga mirip. Dengan begitu, kondisi suhu dan curah hujan di masa datang pun bisa mirip. Namun, pada masa lampau belum ada manusia yang menjadi sumber penghangat bumi. Sejak revolusi industri, pemanasan semakin tinggi sehingga terjadi efek rumah kaca dan sebagainya. Apalagi dengan penambahan jumlah penghuni bumi, efek pemanasan akan semakin dahsyat.
Situasi-situasi seperti inilah yang akan dihadapi oleh anakanak yang menjadi ahli waris bumi di masa depan. Maka, penting untuk menumbuhkan kesadaran tentang perubahan iklim pada anak-anak juga remaja agar mereka bisa melakukan antisipasi dan menentukan langkah-langkah penting untuk memelihara bumi.
Belajar sambil bertualang
Lantas, formula apa yang digunakan dalam kegiatan ini sehingga anak-anak bisa memiliki pemahaman tentang perubahan iklim? Di luar negeri, upaya ini sudah mulai dilakukan di sekolah-sekolah. Pelajar di sekolah diajak untuk memahami perubahan iklim lewat permainan, cerita, video interaktif, dan berbagai cara kreatif lainnya. Sayangnya, meski isu krisis iklim gencar digaungkan di Indonesia, program semacam ini belum masif menyentuh anak-anak. Inilah yang menjadi misi Edu-Click saat pertama kali diinisiasi pada 2019.
Seperti namanya, Edu-Click merupakan akronim dari Eduventure on Climate Change for Kids. Program ini menggabungkan edukasi dan adventure. Tidak mudah mengubah tema saintifik menjadi materi yang mudah dicerna anak-anak. Oleh karena itu, tim peneliti ITB menggandeng Super Kids Eduventure sebagai mitra yang kompeten mengadakan kegiatan edukatif untuk anak-anak. Isu krisis iklim diubah menjadi permainan edukatif, datadata penting disajikan dengan audio visual yang menarik. Anak-anak bisa berinteraksi dengan media pembelajaran baru ini.
Pada penyelenggaraan pertama, fokus materi pada perubahan iklim. Pelaksanaannya menggandeng Sekolah Alam Bandung. Siswa-siswi di sekolah ini sudah terbiasa
beraktivitas di alam. Sekolah sudah memiliki visi dan misi yang selaras dengan pelestarian alam sehingga tidak sulit untuk meyakinkan sekolah tentang pentingnya isu perubahan iklim.
Edu-Click 2.0 diselenggarakan pada tahun 2020 masih dilakukan di Sekolah Alam Bandung. Tema di penyelenggaraaan tahun kedua itu mulai beranjak pada kenaikan muka air laut. Jika Edu-Click 1.0 memberi wawasan tentang pemanasan global, Edu-Click 2.0 mulai berbicara tentang dampak yang ditimbulkan. Kegiatan ini dilakukan di tengah pandemi yang membatasi berbagai aktivitas fisik. Meski pandemi belum usai, Edu-Click 3.0 kembali digelar. Kali ini di SDN 3 Pangandaran. Pada awal September 2021, Kabupaten Pangandaran termasuk pada zona kuning sehingga masih memungkinkan dilakukan kegiatan.
Tema penyelenggaraan ketiga ialah tentang abrasi atau erosi pantai. Abrasi membuat garis pantai kian maju ke daratan. Anak-anak diajak untuk mencermati fenomena ini dan diajak untuk mulai mengambil langkah untuk memperbaiki lingkungan sekitarnya.
Lokasi sekolah memang dekat dengan Pantai Pangandaran. Anak-anak sudah akrab dengan pantai dan laut, tetapi kesadaran tentang perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan belum terbangun.
Pantai Pangandaran merupakan salah satu pantai unggulan wisata Jawa Barat. Masyarakat sekitarnya
bermata pencarian sebagai nelayan. Nyaris seluruh ilmu menangkap ikan di laut didapatkan masyarakat dari tradisi yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Mereka belum familier dengan pendekatan keilmuwan, termasuk datadata penting tentang pesisir dan laut belum banyak diperkenalkan maupun dimanfaatkan. Situasi ini yang mendorong peneliti ITB tidak hanya merangkul anak-anak pada Edu-Click 3.0 ini, tetapi juga para guru di SD Negeri 3 Pangandaran untuk ikut serta. Harapannya, para guru bisa membagikan berbagai informasi dan pengetahuan tentang krisis iklim kepada masyarakat sekitar sehingga memperkaya kearifan lokal yang selama ini menjadi pegangan masyarakat.
Kegiatan Edu-Click 3.0 ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu 6 dan 7 September 2021. Mengingat situasi pandemi, kegiatan hanya bisa dilakukan setengah hari dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan hari pertama di Aula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dikhususkan untuk pada guru. Para guru diajak untuk menyaksikan video “The Longest Day” yang berisi tentang kenaikan muka air laut. Peserta kemudian diajak melihat data dan bagaimana kenaikan muka air laut berdampak pada kehidupan masyarakat, utamanya yang tinggal di daerah pesisir.
Pada hari kedua, giliran siswa SD Negeri 3 Pangandaran yang mengikuti kegiatan Edu-Click 3.0. Sebanyak 50 siswa dari kelas 4, 5, dan 6 berkumpul di Pangandaran Creative
Space untuk bertualang sambil belajar tentang abrasi. Anak-anak bertualang di lima pos yang masing-masing berisi permainan seru.
Pertama, eksperimen tentang tanaman bakau yang digunakan untuk menangani erosi pantai. Kedua, mempelajari fenomena dan objek laut lewat permainan mencocokkan gambar dan mencari kata-kata tentang laut. Ketiga, mengasah kemampuan adaptasi dan mitigasi krisis iklim melalui permainan formasi yang melatih kesigapan, konsentrasi, dan motorik siswa. Keempat, mengasah kepemimpinan melalui permainan mengangkat ember air dengan mata tertutup. Kelima, aktivitas membaca.
Di tempat tersebut telah disediakan berbagai buku bacaan edukasi dalam bentuk ensiklopedia bergambar, komik, maupun buku bacaan bergambar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Buku-buku tersebut berisi pengetahuan tentang ilmu bumi dan fenomena-fenomena di laut. Kesadaran tentang kriris iklim diharapkan bisa terbangun lewat kegemaran membaca buku ini.
Anak-anak juga mendapatkan bahan untuk membuat scrap book berupa buku saku yang bisa dihias sesuai kreativitas masing-masing. Buku ini bisa mereka bawa pulang sebagai kenang-kenangan kegiatan ini. Lewat aktivitas ini, anakanak diajarkan untuk mendaur ulang sampah untuk digunakan kembali menjadi barang yang bermanfaat.
Program berkelanjutan
Program Edu-Click 3.0 bisa berjalan dengan baik berkat kerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran yang telah menyiapkan sekolah, baik guru dan siswanya, untuk mengikuti kegiatan ini. Pemerintah setempat juga menunjukkan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan program ini lewat penandatanganan memorandum of agreement (MoA) dengan ITB. Program yang dimaksud tidak hanya Edu-Click, tetapi juga kegiatan lain yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan memajukan Pangandaran.
Sebagai masyarakat pesisir, orang-orang di sana sudah terbiasa hidup di dekat laut. Akan tetapi, kesadaran untuk mengenali dan menjaga lingkungan masih harus terus diperkuat. Banyak anak-anak yang tidak mengenali nama-nama ikan menjadi salah satu parameter sederhana yang menunjukkan kurangnya kesadaran akan lingkungan. Belum lagi soal kerusakan di pesisir akibat aktivitas manusia, salah satunya buang sampah sembarangan. Kondisi seperti ini tidak akan tuntas hanya dengan pemaparan teori. Perlu upaya lanjutan agar bisa diamalkan pada kehidupan sehari-hari.
Di tengah upaya global mengatasi krisis iklim, masyarakat di pesisir menjadi bagian penting yang harus dilibatkan. Mereka akan berhadapan langsung dengan dampak pemanasan global pada peningkatan muka air laut. Pengetahuan dan kesiapan mereka perlu terus dibangun.
Di tengah upaya global mengatasi krisis iklim, masyarakat di pesisir menjadi bagian penting yang harus dilibatkan. Mereka akan berhadapan langsung dengan dampak pemanasan global pada peningkatan muka air laut.
Kegiatan seperti Edu-Click tak bisa dilakukan hanya sekali. Kegiatan serupa perlu terus diulang dan diikuti oleh semakin banyak siswa juga guru. Sekalipun tidak dalam format serupa, esensi kegiatan ini bisa dimasukkan ke program yang sudah dimiliki sekolah. Misalnya masuk dalam materi kegiatan Pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam dan sebagainya.
Edu-Click masih terus berlanjut ke jilid empat. Tahun 2022, Edu-Click 4.0 akan kembali digelar di Pangandaran, tetapi lokasinya di Pantai Batukaras. Temanya mengangkat tentang coral bleaching atau pemutihan karang. Pemutihan karang ini merupakan salah satu dampak pemanasan global yang juga sudah ditemui terjadi di Pangandaran. Di beberapa titik, karang-karang sudah mati. Karang yang sudah mati warnanya memutih. Salah satunya karena usaha penangkapan ikan yang masih menggunakan pukat harimau. Tidak hanya ikan yang mati, terumbu karang dan biota laut lainnya jadi ikut mati.
Kegiatan yang rencananya dilakukan pada Agustus 2022 ini tetap menyasar guru dan siswa. Mereka akan diajak untuk belajar memulihkan karang yang sudah rusak. Agar mudah dipelajari, kegiatan ini akan dilakukan dalam skala kecil terlebih dahulu.
Sebagai daerah wisata yang menjadikan panorama alam sebagai daya tarik utamanya, kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas. Saat lingkungan rusak, wisatawan tinggal mengubah tujuan wisatanya. Namun, tidak demikian bagi masyarakat yang bermukim di sana. Itu sebabnya masyarakatlah yang menjadi aktor utama pelestarian pesisir laut.
Pendekatan yang akan dilakukan adalah dengan pemaparan materi yang menyajikan data-data terkini mengenai dampak perubahan iklim yang terjadi baik secara lokal, regional, maupun global kepada civitas academica khususnya mengenai abrasi dan erosi pantai. Edukasi untuk para siswa dengan melakukan eduventure dengan berbagai permainan tradisional dan permainan team building yang mengangkat isu perubahan iklim dan dampaknya terhadap laut.
Terdapat juga pembuatan buku cerita anak yang bertema pemutihan karang/ coral bleaching. Buku ini merupakan lanjutan dari buku cerita anak sebelumnya, yaitu Bumiku Demam Tinggi pada tahun 2019, Lautku Makin Tinggi pada tahun 2020, dan Misteri Pantai yang Hilang pada tahun 2021 akan dibagikan ke perpustakaan serta sekolah di Bandung, Pangandaran, bahkan hingga ke luar Pulau Jawa.***

Rumah Ramah bagi Semua

 Dr. Allis Nurdini
Dr. Allis Nurdini
Rumah ramah bagi semua, mungkinkah? Ramah bagi penghuninya, bagi kehidupan sosial, dan bagi lingkungan alam untuk mencapai berkelanjutan. Agar berkelanjutan, setiap penghuni perlu memiliki pilihan (choice) untuk memanfaatkan sumber daya alam setempat dengan terjangkau, bertahap, dan bijak. Upaya ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan penanganan perubahan
iklim (SDG 13) serta kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11).
RUMAH sebagai kebutuhan pokok nyatanya sulit dimiliki semua orang. Jumlah penduduk terus bertambah, sedangkan lahan terbuka semakin berkurang. Harga lahan di perkotaan melangit, perumahan menjadi semakin ke pinggiran kota. Lahan-lahan hijau kini berubah menjadi perumahan.
Dalam kompetisi seperti itu, aspek lingkungan akan menjadi pertimbangan nomor sekian. Faktanya, perumahan merupakan penyumbang terbesar emisi karbon, gas perusak lingkungan yang mendorong pemanasan global lebih cepat. Emisi ini tidak hanya dihasilkan dari proses konstruksi, tetapi juga ditimbulkan dari proses produksi hingga distribusi material yang dipilih pada saat pembangunan.
Peneliti Institut Teknologi Bandung Dr. Allis Nurdini, S.T., M.T. dari Pusat Pemberdayaan Perdesaan membuat model rumah percontohan berkelanjutan yang terjangkau pada konteks perdesaan. Sustainable housing for all atau rumah berkelanjutan bagi semua ini sebagai upaya menerapkan prinsip hunian yang ramah, secara ekonomi (lingkup penghuni), sosial, dan lingkungan.
Pengabdian masyarakat dilaksanakan di Dusun Pangasenan, Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lokasi ini dekat dengan permukiman warga dan terdapat Kebun ITB Haurngombong. Sudah ada bangunan yang berfungsi sebagai toilet, yang akan ditingkatkan kegunaannya, untuk menjadi fasilitas singgah dan diintegrasikan dengan rumah penelitian.
Pendekatan diterapkan sejak penentuan lahan, rencana penahapan tapak dan bangunan, tenaga tukang setempat, penyediaan material termasuk pertimbangan transportasi hingga struktur dan konstruksi rumahnya. Rumah yang dibangun ini sebaiknya tidak membuka lahan baru yang produktif untuk pangan.
Pendekatan rumah ramah lingkungan dapat disesuaikan konteks tapak dan lokasinya, baik urban maupun rural. Pada konteks urban, digunakan prinsip revitalisasi atau retrofit bangunan terbengkalai atau yang sudah menurun produktivitasnya menjadi hunian kota. Area di tengah kota yang surut aktivitasnya, tetapi padat dengan bangunan minim pengguna dapat dimanfaatkan ulang menjadi hunian yang terjangkau.
55
Selain itu, pengintegrasian fungsi merupakan bagian dari rumah ramah ini. Bisa saja terdapat bangunan yang ketika dibuat hanya memiliki satu fungsi yang terbatas, sebaiknya kemudian ditata untuk memiliki lebih banyak fungsi. Jika fungsi terbatas waktu penggunaan pun tidak panjang sehingga integrasi fungsi sangat disarankan untuk mencapai efisiensi lahan serta tidak perlu membuka lahan baru. Pemilihan material merupakan hal berikutnya perlu direncanakan, terutama terkait pengangkutan material ke lokasi. Bangunan juga tidak lepas dari tren, tetapi tidak semua materialnya mudah dipenuhi. Ada yang harus mendatangkan dari lokasi yang jauh sehingga perlu transportasi dan berkontribusi pada emisi karbon.
Rumah ramah bertujuan untuk mengurangi emisi karbon saat mendatangkan material bangunan dengan mencermati bahan yang dapat diperoleh pada radius terdekat. Hal ini yang menjadi pertimbangan peneliti memilih kayu gmelina atau jati putih, pohon yang telah dibudidayakan bertahun-tahun di Kebun Haurngombong dari peneliti ITB sebelumnya dan telah siap untuk diolah. Pengolahan kayu menjadi material struktur dan konstruksi rumah pengembangan semua dilakukan di lokasi oleh para tukang setempat. Artinya keterampilan warga lokal dapat didayagunakan, terjangkau, dan kehidupan sosial ekonomi terjalin. Material kayu ini juga dapat dengan mudah ditiru warga setempat. Untuk material lainnya didapatkan dari toko bangunan terdekat. Transportasi menjadi lebih hemat.
Memanfaatkan material yang tersedia setempat bukan berarti bangunan dibuat menjadi seadanya. Dengan intervensi teknologi, material lokal dapat dimanfaatkan untuk membuat bangunan yang layak huni, nyaman, dan memiliki nilai estetika.
Pilihan sistem tapak dan bangunan
Ide dasar rumah ramah pada konteks perdesaan ini yaitu terdapat pilihan untuk mengoptimalkan lahan yang sudah terbangun. Konsep rumah panggung kali ini dipilih untuk mendayagunakan bangunan toilet yang sudah terdapat di lokasi. Bangunan dikembangkan secara vertikal dan bertahap. Dengan demikian lahan dapat efisien dimanfaatkan. Lahan terbuka di sekitarnya dapat tetap difungsikan untuk penanaman, kolam ikan, dan peresapan air.
Kayu harus dijemur di bawah sinar matahari langsung kemudian dicat antirayap lalu direndam kapur. Pengecatan antirayap kemudian diulangi sebelum dijemur kembali. Untuk perawatannya, penggunaan antirayap perlu diulangi setiap dua atau tiga tahun sekali.
Dindingnya menggunakan anyaman bambu yang didapat dari daerah setempat. Kusen jendela dan pintu terbuat dari kayu. Sebagai aksen, ranting gmelina digunakan menjadi pagar di area teras.
Dindingnya menggunakan anyaman bambu yang didapat dari penyedia setempat. Kusen jendela dan pintu terbuat dari kayu. Sebagai aksen, ranting gmelina digunakan menjadi pagar di area teras.
Rumah panggung merupakan bentuk rumah yang secara tradisional dipercaya menyelamatkan penghuninya dari bahaya, misalnya banjir dan gempa bumi. Struktur rumah panggung ini dirancang agar memiliki ketahanan terhadap gempa bumi. Dr. Endra Susila, peneliti geoteknik ITB ikut terlibat dalam penyusunan sistem strukturnya.
Di bangunan rumah ini juga dibuat sistem sanitasi yang mampu mengolah air kotor menjadi air bersih. Air kotor dari kamar mandi disalurkan ke kolam untuk disaring dengan menggunakan tanaman dan unsur alam lainnya atau yang disebut dengan fitoremediasi. Penyaringan dilakukan beberapa tahap. Air hasil penyaringan disalurkan ke kolam yang digunakan untuk memelihara lele.
Air hujan juga ditangkap menggunakan instalasi sederhana sehingga tidak terbuang begitu saja. Airnya bisa dipanen untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Pembuatan sistem sanitasi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan peneliti biorefinery ITB Dr. Taufikurrahman
Di lokasi tersebut kemudian dibangun biogas. Energinya berasal dari kotoran sapi milik masyarakat setempat. Pembangunan rumah ramah ini tidak banyak mengubah sifat tanah. Tanah tidak ditutup dengan berbagai material. Meski demikian, bangunan memiliki fungsi yang maksimal. Rumah ini difungsikan sebagai rumah singgah peneliti.
Rumah panggung merupakan bentuk rumah yang secara tradisional dipercaya menyelamatkan penghuninya dari bahaya, misalnya banjir dan gempa bumi.
Pengaruh tren
Meski diadaptasi dari kearifan lokal, kebanyakan masyarakat sudah tidak familier dengan bentuk rumah panggung dengan dinding bambu. Tren rumah di perkotaan sampai juga ke daerah-daerah. Masyarakat jadi lebih terbiasa dengan dinding tembok dengan cat beragam warna. Dinding dari anyaman bambu jadi dikesankan sebagai pilihan yang kampungan
Perkembangan teknologi konstruksi juga membuat orang mulai meninggalkan kayu sebagai material rumah. Kayu dianggap tidak awet. Pilihan beralih ke baja ringan yang lebih awet sehingga lebih hemat biaya.
Situasi ini jadi memengaruhi pola pikir masyarakat. Mereka beranggapan apa yang dilakukan developer perumahan merupakan keputusan yang paling baik. Padahal, semestinya ada kebebasan untuk menentukan material. Meski terkesan dihindari para developer, kayu merupakan material yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan riset di bidang teknologi kehutanan, diharapkan lahir terobosan baru yang bisa mempercepat masa tanam bambu dan kayu. Dengan demikian material baru terbarukan seperti ini bisa menjadi alternatif memenuhi kebutuhan masyarakat akan material bangunan.
Model rumah ramah di Haurngombong ini menyingkap pendapat tersebut. Kayu tetap bisa menjadi material pilihan selama disiapkan dengan benar. Masyarakat dapat melihat bahwa material anyaman bambu dapat menjadi material alternatif yang menarik untuk dinding rumah. Warga sekitar kebun penelitian yang sering mengikuti aneka pelatihan bidang hayati di sana dapat sekaligus memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk pengembangan huniannya.
Masyarakat pun mendapat referensi untuk sistem pengolahan air kotor menjadi air bersih di lahan yang terbatas. Hasilnya dapat digunakan untuk kolam pemeliharaan ikan lele yang bisa menjadi sumber pangan bahkan penghasilan keluarga.
Tidak sulit bagi masyarakat untuk mengadaptasi rumah ramah ini karena sebenarnya mereka sudah memiliki kearifan lokal yang sesuai dengan konsep ini. Itu sebabnya intervensi peneliti selama pembangunan ini tidak terlalu banyak.
Seluruh sumber daya di sekitar bisa didayagunakan. Masyarakat mempelajari keterampilan baru, demikian pula dengan peneliti. Interaksi keduanya menciptakan kemitraan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan seperti yang dicita-citakan Sustainable Development Goals (SDGs).





Bertahap, Terjangkau, dan Minim Jejak Karbon
PEMBUATAN rumah ramah di Sumedang ini dilakukan secara bertahap, tidak langsung jadi pada waktu singkat atau disebut dengan incremental Konsep seperti ini cocok dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah tidak dibangun sekali jadi, disesuaikan dengan kemampuan pada saat itu. Meski pembangunan bertahap telah dikenal lama, model seperti ini sudah tidak banyak digunakan. Masyarakat lebih familier dengan pembangunan ala developer. Rumah dibangun sampai siap huni dalam satu tahap. Akibatnya, harga jual rumah membubung. Masyarakat semakin sulit memiliki rumah. Model incremental justru sejalan dengan konsep sustainable housing. Pembangunan rumah dimulai dari bagian inti. Tidak semua ruang harus ada sejak mula. Hanya ruang yang benarbenar dibutuhkan oleh penghuninya nanti. Ruangan tambahan lainnya dibangun di kemudian hari saat biaya sudah tersedia.
Dari segi biaya, tentu model bertahap seperti ini akan lebih bisa diatur. Jumlah tukang atau sumber daya manusia yang diperlukan secukupnya saja. Kemampuannya disesuaikan dengan kebutuhan. Konsumsi lahan dan semua material tidak dilakukan dalam jumlah besar sekaligus.
Di luar negeri, sistem incremental terus dikembangkan. Massachusetts Institute of Technology, salah satu perguruan tinggi yang memimpin perkembangan sistem ini. Perangkat lunak dan produk teknologi lainnya, mereka kembangkan secara bertahap. Dengan begitu, tenaga kerja, bahan baku, dan kebutuhan lainnya bisa disiapkan secara bertahap juga.
Pada pembangunan rumah, sistem incremental sebenarnya masih bisa ditemukan di desa atau kota kecil. Di perkotaan, sistem ini hanya bisa dilakukan jika rumah dibangun sendiri, bukan oleh developer perumahan. Pembangunan rumah dilakukan sesuai dengan ketersediaan dana. Bahkan, terkadang rumah sudah ditempati meski belum rampung seluruhnya. Selama aktivitas bisa berjalan lancar, rumah sudah bisa dihuni dulu.
Sistem semacam itu lambat laun semakin sulit dijumpai. Salah satunya karena tren saat ini pembangunan perumahan lengkap, berbeda dengan masa rumah inti oleh Perumnas pada dekade ‘70-an hingga ‘80-an. Tidak hanya rumahnya yang lengkap, bahkan fasilitas lingkungan sudah terdesain semenarik mungkin. Memang menjadi praktis, konsumen
tinggal menempati rumah yang rampung. Akan tetapi, harga rumah jadi jauh lebih mahal. Perhitungan harga rumah tidak hanya memperhitungkan harga tanah dan bangunan, tetapi juga fasilitas penunjangnya.
Meski telah tersedia kredit pemilikan rumah, tidak semua masyarakat terjangkau sistem ini. Uang muka harus tinggi agar cicilannya terjangkau. Hak setiap orang mendapatkan rumah jadi tidak mudah terpenuhi.
Sistem incremental ini pun dapat dilakukan oleh developer. Seperti yang berlaku di Amerika Latin. Konsumen dapat membeli rumah dalam bentuk setengah jadi, bahkan hanya berupa tanah dengan bangunan satu ruang tanpa sekat. Seiring kemampuan, bagian-bagian rumah lainnya bisa dilengkapi. Model seperti ini disebut dengan infill-system. Dengan model seperti ini harga rumah bisa lebih terjangkau.
Jika sistem seperti ini bisa diterapkan di Indonesia, harga rumah bisa ditekan. Masyarakat punya opsi yang lebih banyak untuk memiliki rumah, tinggal disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Dengan begitu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah. Tidak mengapa jika dindingnya belum dicat rapi. Saat biaya sudah tersedia bisa dicat atau bahkan memilih untuk dicat sendiri. Tidak apaapa jika temboknya masih berupa batu bata. Jika dana sudah siap, pembangunan bisa dilanjutkan kembali.
Model pembangunan seperti ini sudah diakui sebagai suatu sistem karena melibatkan partisipasi dari penggunanya. Pengguna atau konsumen punya kebebasan untuk memilih berbagai opsi sesuai dengan kemampuannya.
Selain itu, model incremental ini memudahkan untuk merancang sistem sanitasi dan pengolahan air yang lebih baik. Ketika rumah sudah seluruhnya terbangun, sulit untuk dikenalkan sistem baru. Meski sudah diedukasi, implementasinya jadi sulit karena tidak ada lahan. Perubahan pada sistem perlu membongkar bangunan yang ada sehingga perlu biaya tambahan yang tidak kecil. Lahan yang masih terbuka memungkinkan dilakukan pengaturan semacam ini.
Pembangunan oleh developer dengan opsi yang terbatas ini kini menjadi standar baru. Masyarakat jadi beranggapan sistem semacam itu lebih benar. Padahal, ada banyak opsi yang bisa diambil untuk bisa mendapatkan rumah. Salah satunya sistem incremental yang selaras dengan sustainable housing. Sumber daya untuk membangun rumah tidak harus disiapkan dan dihabiskan dalam waktu bersamaan. Lahan dan jaringan infrastruktur dasar dapat disiapkan oleh developer, baik pemerintah maupun swasta, menjadi kaveling siap bangun lebih dulu dan penghuni memiliki pilihan membangun hunian masing-masing secara bertahap.
Rancangan desain rumah yang ramah lingkungan dapat diperoleh dari aneka media sebagai edukasi dari para arsitek dan akademisi. Material bangunan dapat dipilih secara bijak dari radius sekitar hunian. Dengan pembangunan bertahap sesuai keterjangkauan, diiringi implementasi sistem pengelolaan energi alami secara bertahap pada skala rumah, secara partisipatif emisi karbon pun dapat tereduksi.***

Menabuh Air di Rebana

 Dr. Sri Maryati
Dr. Sri Maryati
Metropolitan Rebana. Begitulah nama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah timur Jawa Barat yang diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil bersamaan dengan acara West Java Investment Summit (WJIS) 2020 di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, 16 November 2020. Ini adalah kawasan metropolitan ketiga di Jawa Barat setelah Bodebek (BogorDepok-Bekasi) dan Bandung Raya. Pembangunan infrastruktur air bersih di kawasan metropolitan Rebana merupakan salah satu capaian yang diinginkan dalam target penyediaan sanitasi dan air bersih (SDG 6) serta kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3).
MEMBENTANG seluas 43.913 hektare, Metropolitan Rebana meliputi 7 kota/kabupaten di wilayah timur Jawa Barat, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, dan Sumedang. Seusai penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan tujuh kepala daerah di kawasan Metropolitan Rebana, Emil —sapaan Gubernur Jawa Barat— mengatakan, kawasan ini didesain sejak awal dengan terencana dan berkelanjutan. Dua kata kunci dari Gubernur Jabar itulah yang direspons Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P., dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB). Dekan SAPPK ITB dari Kelompok Keahlian (KK) Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota ini langsung melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan air bersih di kawasan tersebut, terutama Kabupaten Cirebon.
Dalam studi pendahuluan yang dilakukan timnya terungkap, salah satu persoalan di kawasan Metropolitan Rebana adalah kekurangan air yang dialami oleh beberapa kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Berdasarkan kajian awal, persoalan air bersih di Kabupaten Cirebon muncul karena adanya disparitas ketersediaan air bersih antara wilayah satu dan lainnya. Ia mencontohkan, wilayah yang satu memiliki sumber air, sedangkan lainnya tidak punya.
Situasi tersebut diperparah dengan arah pembangunan yang tidak mengacu pada perencanaan ruang. Selain itu, pembangunan infrastruktur air bersih belum menjadi prioritas di kebanyakan daerah, termasuk Kabupaten Cirebon.
Sri mencontohkan, pembangunan infrastruktur air bersih belum bisa dilakukan di semua wilayah, kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi mendapat prioritas pembangunan infrastruktur air bersih.
Teknologi Pelestari / 67
Sementara, di daerah perdesaan yang justru rawan ketersediaan air bersih, program pembangunan tersebut tidak dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Bahkan, katanya, jika suatu daerah tidak memiliki sumber air, program pembangunan infrastruktur itu malah tidak ada.
Menurut Sri, kondisi tersebut memerlukan intervensi, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga masa yang akan datang. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah melalui perencanaan dan penataan ruang. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, menguraikan implementasi dan mengalokasikan sumber daya. Perencanaan yang baik merupakan titik awal dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk distribusi air bersih.



















Namun, pada kenyataannya, terdapat dokumen perencanaan ruang (spasial) dan dokumen perencanaan sektoral (air bersih) yang tidak terintegrasi satu dengan lainnya. Idealnya, perencanaan ruang menjadi acuan perencanaan infrastruktur. Fungsi ruang tertentu membutuhkan pelayanan infrastruktur dalam kuantitas dan kualitas tertentu pula. Karena itu, tidak terintegrasinya perencanaan ruang dan infrastruktur berimplikasi kepada tidak terlayaninya fungsi-fungsi ruang oleh infrastruktur yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterbatasan penyediaan infrastruktur air bersih sering kali ditemui di kawasan permukiman dan lainnya.



















Dalam konteks ini, Sri berpandangan, jika tidak ada integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang, masalah ini akan semakin kompleks ketika kawasan tersebut menjadi metropolitan. Disebutkan, tanpa ada pengembangan metropolitan pun Cirebon sudah tidak punya sumber air sebab selama ini sumber air Cirebon dari Kuningan. Masalah ini akan semakin kompleks ketika nanti menjadi kawasan metropolitan. Berbekal studi pendahuluan yang sudah dilakukannya, bersama dua koleganya di SAPPK ITB, Fika Novitasari S.T., M.T. (KK Sistem Infrastruktur Wilayah dan Kota) dan Lanthika Atianta, S.T., M.Sc. (KK Perencanaan dan Perancangan Kota) melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Cirebon pada 3 Februari –30 November 2021. Ketiganya dibantu dua mahasiswa dari kampus Cirebon, Imam Mustafa Yusuf dan M. Fajar Amanullah.
Bersama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB), sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam studi pendahuluan, tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menghasilkan framework atau kerangka pedoman integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang di Kabupaten Cirebon.
Sementara, target atau sasaran pada kegiatan pendampingan masyarakat ini adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon. Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mengetahui strategi integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang untuk kemudian menerapkan pedoman serta tahapannya.
Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa top-down dan bottom-up approach. Top-down approach digunakan untuk merumuskan pedoman dan strategi integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang yang didapat dari studi literatur dan survei lapangan. Sementara, bottom-up approach digunakan dengan konsep partisipatif untuk memilih bentuk integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang serta perumusan langkah-langkah untuk mewujudkan tindakan terpilih.
Kendati baru sebatas kerangka, pedoman ini bisa menjadi dasar penyusunan strategi integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan tata ruang.
Agar lebih optimal, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disinergikan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan (PPIW) ITB di kawasan Metropolitan Rebana. Selain itu, dosen dan mahasiswa PWK (Perencanaan Wilayah Kota) Kampus Cirebon juga dilibatkan dalam kegiatan ini dengan tujuannya untuk menciptakan suasana akademik di Kampus Cirebon.
Namun, untuk menghasilkan kerangka pedoman integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang di Kabupaten Cirebon ini dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Sejumlah kendala harus dilewati tim peneliti dari SAPPK ITB. Mengingat kegiatan dilaksanakan di masa pandemi COVID-19, anggota tim tidak bisa leluasa melakukan pengambilan data dan sosialisasi akibat sejumlah pembatasan. Kendati tidak ideal, kendala-kendala tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan teknologi.
Hal ini dapat diantisipasi dengan memanfaatkan information communication technology (ICT) seperti aplikasi Zoom untuk kegiatan sosialisasi, termasuk focus group discussion (FGD). Pengumpulan data melalui metode wawancara dilakukan oleh mahasiswa PWK Kampus Cirebon yang berdomisili di Kabupaten Cirebon.
Setelah berjalan lebih kurang delapan bulan, kegiatan pengabdian masyarakat ini menghasilkan kerangka pedoman integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan ruang yang sebelumnya memang belum dimiliki Pemkab Cirebon. Kendati baru sebatas
kerangka, pedoman ini bisa menjadi dasar penyusunan strategi integrasi perencanaan infrastruktur air bersih dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur.
Diakui Sri, dampak dari pengabdian yang dilakukan memang tidak secara langsung dirasakan masyarakat. Karena output-nya baru sebatas framework, masyarakat belum sampai menikmati air bersih. Namun, framework yang berisi kerangka kerja, step by step, pedoman, atau prosedur itu diakui Pemkab Cirebon sebagai sebuah inovasi yang belum ada sebelumnya. Inovasi kelembagaan ini bisa membantu Pemkab Cirebon menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan air bersih dalam kaitannya dengan perencanaan ruang di masa yang akan datang. Soal intervensi teknologi dapat berupa pemasangan pipa sederhana untuk mengatasi permasalahan air bersih di Kabupaten Cirebon, Sri berpendapat, hal itu akan relatif lebih mudah dilakukan setelah pemerintah daerah mampu mengintegrasikan perencanaan infrastruktur air bersih dengan perencanaan ruang. Intervensi teknologinya bisa saja hanya pemasangan pipa sederhana untuk mendistribusikan air bersih agar merata, terutama ke kawasan yang rawan ketersediaannya. Karena itu, Sri berharap framework yang menjadi output dari pengabdian masyarakat tersebut bisa dipakai sebagai dasar penyusunan dan perencanaan tata ruang dan infrastruktur. Dalam framework tersebut ada keterkaitan dan koordinasi antarpihak yang lebih bersifat kelembagaan.***
Mengatasi Batas-batas Kepentingan dan Otoritas
UNTUK menyusun framework atau kerangka kerja yang diharapkan bisa mengintegrasikan perencanaan infrastruktur air bersih dengan perencanaan ruang, tim pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin Dekan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Sri Maryati, S.T., M.I.P., mengadakan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) pada 5 Oktober 2021.
FGD diperlukan untuk mengumpulkan informasi spesifik dan menentukan faktor prioritas upaya mengintegrasikan perencanaan sektoral yang dalam hal ini infrastruktur air bersih dengan perencanaan ruang di Kabupaten Cirebon.
Sri mengungkapkan, upaya integrasi ini diperlukan untuk menghasilkan perencanaan infrastruktur air bersih dan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan. Pada kenyataannya, perbedaan institusi, regulasi, tanggung
jawab pihak-pihak berkepentingan, program, anggaran, budaya, skala dan penggunaan lahan, serta batas administrasi menjadi tantangan yang harus diatasi dalam upaya integrasi ini.
Konsep yang dijadikan dasar integrasi adalah spasial, sektor dan multisektor, serta pemangku kepentingan dan pendanaan. Sementara, pendekatan yang dilakukan adalah matriks dan analisis spasial, sektor infrastruktur, pemangku kepentingan dan pendanaan.
Untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan serta menemukan dan membedah permasalahan air bersih di Kabupaten Cirebon, instansi yang menjadi leading sector seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati, dan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPAM) dilibatkan.
Sasaran 6 SDGs: Akses terhadap air bersih
Potensi Kab. Cirebon dalam sektor air bersih: memiliki sumber air baku dari beberapa mata air dengan kapasitas produksi 6.291.807 m3
Adanya kebutuhan integrasi sektoral (dalam hal air bersih) dengan perencanaan ruang di Kab. Cirebon
Informasi pertama yang dihimpun dari FGD tersebut adalah dokumen perencanaan utama yang menjadi acuan penyediaan air bersih di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan informasi dari Bappelitbangda, aturan perundangan yang menjadi acuan penyediaan air bersih di Kabupaten Cirebon hanya Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon No. 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI SPAM) Kabupaten Cirebon Tahun 2015-2030 dan Peraturan Bupati Cirebon No. 154 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dalam kenyataannya, seperti disampaikan DPKPP Kabupaten Cirebon, meski sudah memiliki RI SPAM 20152030, data yang ada masih kurang dan berbeda dengan instansi lain yang dalam hal ini Dinas Kesehatan. Menurut DPKPP, acuan lain yang digunakan dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Cirebon adalah hasil koordinasi dengan PDAM Tirta Jati yang khusus terlibat dalam SPAM perkotaan serta hasil penelitian geolistrik.
Pada saat FGD digelar, Bappelitbangda menginformasikan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) sedang disusun. Regulasi ini baru ditetapkan secara resmi dua tahun kemudian melalui Peraturan Bupati Cirebon No. 53 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 2020-2024.
Selanjutnya, dari FGD ini diketahui mengenai proses perencanaan penyediaan air bersih di Kabupaten Cirebon. Narasumber dari Bappelitbangda menyebutkan bahwa perencanaan penyediaan air bersih sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Namun, perencanaan tersebut tidak termasuk ke dalam indikator daerah, melainkan hanya sebagai penyerta.
Untuk penyediaan air bersih swakelola yang dilakukan PDAM Tirta Jati, perencanaan didasarkan pada hasil survei dan kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jika penyediaan air bersih berdasarkan usulan bantuan dari pemerintah, PDAM Tirta Jati harus mengantongi surat penetapan dari kepala daerah terlenih dahulu. Sementara, untuk usulan SPAM baru, Direktur PDAM Turta Jati harus mengajukan usulan kepada Bupati Cirebon untuk dilanjutkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat yang dilanjutkan dengan workshop.
Sementara, perencanaan penyediaan air bersih yang dilakukan DPKPP lebih didasarkan kepada hasil survei, kajian dan penelitian, terutama yang menggunakan metode geolistrik. DPKPP menyebutkan, penyediaan air bersih didasarkan pertimbangan hierarki, dari mulai ketersediaan mata air, sumur gali, sumur bor dangkal, hingga sumur bor dalam (artesis). Selain itu, minimal sudah terdapat geolistrik untuk mengetahui kedalaman sumber air dengan tingkat keakuratan 70%-80%.
Pada tahapan implementasi perencanaan, seperti disampaikan Bappelitbangda, ketersediaan dan kemampuan anggaran daerah menjadi kata kunci. Meskipun tergolong kebutuhan utama dalam skala prioritas pembangunan, penyediaan air bersih kerap tersisihkan oleh perencanaan daerah yang lain.
Di PDAM Tirta Jati, ketika perencanaan anggaran sudah tersedia, direktur akan memerintahkan bidang-bidang di bawahnya untuk melakukan pengecekan dan realisasi. Namun, jika penyediaan air bersih didanai APBD atau APBN, PDAM Tirta Jati hanya menunggu mekanisme yang berjalan. Hal itu karena dalam konteks ini, PDAM Tirta Jati sifatnya hanya penerima aset, tidak telibat dalam proses bantuan dari luar.
Pelestari
Sementara itu, salah satu implementasi penyediaan air bersih yang menjadi tanggung jawab DPKPP adalah melalui program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Dalam program pemerintah pusat ini, ada berbagai jenis dana untuk penyediaan sarana air bersih perdesaan, termasuk pembentukan pengelolanya seperti yang dilakukan di wilayah Cirebon Girang.
Setelah implementasi, tahapan monitoring dan evaluasi pada umumnya dilakukan setiap tahun, termasuk mengecek keberfungsian dan pengelolaan program Pamsimas. Khusus untuk PDAM Tirta Jati yang dievaluasi adalah pelaksanaan business plan yang berlaku selama lima tahun. Rencana bisnis yang berlaku lima tahun itu dijabarkan dalam rencana tahunan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP). Pada saat FGD digelar, PDAM Tirta Jati sedang meninjau ulang business plan karena ada rencana pembangunan SPAM Regional Jatigede.
Pertanyaan selanjutnya yang didiskusikan dalam FGD menyangkut konsep wastewater reuse/recycle. Dari pemaparan Bappelitbangda, PDAM Tirta Jati, dan DPKPP terungkap, konsep pengolahan atau daur ulang air limbah menjadi air bersih belum dipertimbangkan, bahkan sama sekali tak terpikirkan karena merasa ketersediaan air dinilai masih mencukupi.
Kalaupun ada yang melakukan, konsep itu hanya diterapkan dalam skala mikro, seperti daur ulang air bekas wudu di masjid atau musala. Sementara, di PDAM Tirta Jati, konsep ini diterapkan pada tahapan pengolahan. Namun, wastewater berupa lumpur tidak didaur ulang, tetapi dibuang ke bak penampungan.
Setelah proses perencanaan, akses dan ketersediaan air bersih warga Kabupaten Cirebon juga dibedah. Menurut PDAM Tirta Jati, indikasi kekurangan air bersih tergambar dari data kiriman bantuan melalui tangki.
Berdasarkan data tersebut, kawasan nonpelanggan yang masih kekurangan air bersih berada di wilayah Cirebon timur dan tenggara. Yang sudah menjadi pelanggan di Cirebon utara seperti kawasan Gunung Jati, Suranenggala, dan daerah yang sumber air produksinya dari sungai, bukan mata air. Di musim kemarau sungai juga ikut mengering dan pada water treatment yang masuk berupa lumpur. PDAM Tirta Jati juga mengungkapkan, kawasan Cirebon
selatan minim pelanggan karena masyarakatnya merasa dekat dengan mata air.
Dalam penjelasan selanjutnya, PDAM Tirta Jati menyebutkan, musim kemarau berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air permukaan. Hal itu diperparah limbah domestik dan industri yang mencemari badan sungai. Kendati demikian, masalah kekurangan ini hanya bersifat temporal, terutama di musim kemarau. Secara reguler, PDAM Tirta Jati yang mempunyai 8 cabang sudah melayani 32 kecamatan. Bahkan, khusus wilayah Sumber, pelayanan air bersih sudah bisa 24 jam.
DPKPP mengungkapkan, kawasan yang masih kekurangan air bersih berada di Arjawinangun dan pesisir Kabupaten Cirebon. Untuk kawasan ini, sumber air yang dimanfaatkan PDAM Tirta Jati berasal dari Telaga Remis. Ketika pelaksanaan FGD, Pemkab Cirebon dan PDAM Tirta Jati masih menunggu realisasi pembangunan SPAM Jatigede. Mengenai kekurangan air, DPKPP menyebutkan, setiap daerah penyebabnya berbeda-beda, dari mulai musim kemarau hingga keterbatasan sumber air. Untuk pengecekan kualitas air, DPKPP menyebutkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) biasanya melakukannya secara berkala, 3 atau 6 bulan sekali. Jika diketahui kualitas air rendah, hal itu akan ditindaklanjuti oleh DPKPP, Dinkes atau masyarakat setempat.
Untuk meningkatkan akses air bersih masyarakat, Pemkab Cirebon sangat berharap kepada pembangunan SPAM Regional Jatigede. Proyek yang digagas pemerintah pusat ini diharapkan menjadi solusi penyediaan air di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Indramayu. Apalagi, khusus Kabupaten Cirebon, sejauh ini belum memiliki tandon atau bak penampung untuk deposito air. Tandon ini sangat diperlukan karena kalau mengandalkan air baku dari PDAM Tirta Jati sudah sangat minim dan tak dapat dikembangkan lagi. Meskipun demikian, PDAM Tirta Jati tetap berupaya mengembangkan jaringan air setiap tahunnya, termasuk ke wilayah Palimanan dan Gunungjati pada 2022.
Terkait dengan integrasi perencanan air bersih dan tata ruang, PDAM Tirta Jati mengaku dilibatkan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di dua kecamatan yaitu Sumber dan Mundu. Dalam penyusunan RPJMD, PDAM Tirta Jati diikutsertakan di sektor air minum perkotaan. Sementara, untuk air minum pedesaan menjadi wilayah DPKPP. Berbeda dengan RDTR dan RPJMD, pada penyusunan RTRW, PDAM Tirta Jati menyebutkan, penyusunan muatan struktur ruang dan jaringan perpipaan dilakukan oleh instansi lain.
Dari DPKPP menjelaskan, integrasi perencanaan air bersih dan tata ruang tergambar dalam target yang dituangkan di
RPJMD. Disebutkan, cakupan yang tertera dalam RI SPAM sebesar 75 persen sehingga target yang diharapkan sebesar 25 persen. Untuk merealisasikannya dalam rentang waktu 10 tahun, berarti target setiap tahunnya sebesar 2,5 persen yang kemudian dibagi jumlah penduduk Kabupaten Cirebon.
Dari berbagai informasi yang dihimpun dalam FGD tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat mengambil sejumlah kesimpulan yang menguatkan dibutuhkannya framework atau kerangka kerja integrasi perencanaan air bersih dan tata ruang. Dalam kenyataannya, berbagai upaya dan program penyediaan infrastruktur air bersih belum terintegrasi sehingga terkesan instansi yang menjadi leading sector berjalan sendiri-sendiri.
Akibat tidak adanya integrasi perencanaan tersebut, meski sudah memiliki rencana induk penyediaan air minum dan tata ruang, dalam penyusunannya kurang memperhatikan aspek prioritas distribusi, misalnya melayani daerah yang tidak memiliki sumber air. Akibatnya, distribusi air tetap tidak merata.
Dengan framework ini diharapkan berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Cirebon untuk penyediaan air besih terintegrasi dengan rencana tata ruang dan koordinasi antarpihak dan antarinstansi bisa terjadi tanpa ada kendala berarti.***

Air Mengalir ke Sungai Harapan
 Dr. Widodo
Dr. Widodo
SEPERTI sebagian besar wilayah di Kabupaten Tuban, Desa/Kecamatan Grabagan, kondisi geologisnya didominasi batuan kapur. Tidak mengherankan jika kawasan yang letaknya berada di dataran tinggi (+323 mdpl) tersebut hampir sepanjang tahun mengalami krisis air bersih. Warga desa sangat sulit mendapatkan air permukaan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalaupun ada sumur atau sendang, lokasinya berada di dataran rendah yang jaraknya hampir 8 kilometer dari desa tersebut. Penerapan teknologi tepat guna untuk menanggulangi krisis air bersih yang dijalankan ITB di Grabagan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sanitasi dan air bersih (SDG 6) serta kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11).
KRISIS air bersih di Desa Grabagan juga diakibatkan iklim kering yang memang terjadi di hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, curah hujan tinggi hanya terjadi di bulan Maret, April, dan Desember. Sisanya, curah hujan di kawasan ini tergolong rendah.
Karena curah hujan sepanjang tahun rendah, meski berada di dataran tinggi, masalah kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih hampir selalu dihadapi oleh sekitar 1.400 warga dari 600 kepala keluarga (KK) di Desa Grabagan. Saking ekstremnya, ketika sejumlah wilayah kebanjiran pada 2020, desa seluas lebih kurang 1.263 meter persegi tersebut tetap mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih.
Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam. Dr. rer. nat. Widodo, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik
Tambang dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dari Kelompok Keahlian (KK) Geo fisika Terapan dan Eksplorasi yang memimpin tim pengabdian masyarakat di Desa Grabagan pada tahun 2021, mengungkapkan, krisis air di kawasan tersebut sudah terjadi sejak sekitar 40 tahun lalu. Menurutnya, antrean panjang warga saat mendapatkan bantuan air bersih sudah menjadi pemandangan biasa.
Sebagai putra daerah yang merasakan langsung derita warga Desa Grabagan, hati Widodo terketuk untuk mencarikan solusi atas permasalahan kekeringan dan krisis air tersebut.
Sesuai dengan bidang kepakarannya, Widodo bersama timnya menawarkan teknologi tepat guna untuk menanggulangi krisis air bersih di Desa Grabagan. Dua teknologi yang diyakini sangat dibutuhkan masyarakat tersebut adalah river stream flow dan geofisika.
Kedua alternatif teknologi untuk menanggulangi permasalahan krisis air bersih itu coba diterapkan pada saat Widodo bersama timnya melakukan program pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Grabagan, 3 Februari hingga 30 November 2021. Timnya beranggotakan dosen FTTM ITB yaitu Dr. Ir. Fatkhan, M.T. dengan bidang keahlian seismologi, eksplorasi, dan rekayasa, Dr. Susanti Alawiyah, S.T., M.T. (Geofisika Terapan dan Eksplorasi) dan Dr. Setianingsih, S.T., M.T. (Geofisika Terapan dan Eksplorasi). Mereka dibantu oleh 6 asisten peneliti/mahasiswa, yaitu Farkhan, Kurnia Anwar Ra’if, S.Si., Ibnu Thoriq, Elis Agaustiana, Raymond Tirta, dan Kafin Mufid.
Alternatif teknologi tepat guna yang pertama diujicobakan untuk penanggulangan krisis air bersih adalah instalasi penyaringan air sungai dengan memanfaatkan komponen atau material yang ada di daerah pengabdian. Sistem ini menggunakan penyaringan dengan teknologi river stream flow water yaitu mengalirkan air sungai ke permukaan dan air bersih diperoleh dari saringan yang dimodifikasi sedemikian rupa.
Penyaringan air ini akan bekerja secara otomatis dengan memanfaatkan sistem radar dan menggunakan kolam penampungan. Dengan sistem ini masyarakat akan mudah melakukan perawatan dan dapat menghasilkan air bersih 100-300 meter kubik per hari.
Solusi alternatif kedua yang dijalankan adalah dengan mencari sumber air bersih di bawah permukaan tanah dengan pemanfaatan teknologi geofisika yaitu ilmu yang mempelajari aspek-aspek fisik dan dinamik bumi. Salah satu metode untuk pengukuran, pemrosesan data dan eksplorasi sumber daya bumi adalah geolistrik, termasuk untuk mendeteksi keberadaan air tanah.
Berbagai literatur menjelaskan, geolistrik adalah salah satu metode geofisika untuk mengetahui sifat-sifat kelistrikan lapisan batuan di bawah permukaan tanah dengan cara menyuntikkan arus listrik ke dalam tanah. Tujuan utama geolistrik adalah mencari resistivitas atau tahanan jenis dari batuan.
Metode geolistrik dapat digunakan dalam pencarian reservoir air tanah, terutama untuk eksplorasi yang sifatnya dangkal di kedalaman antara 30-150 meter. Parameter yang diukur adalah harga resistensi batuan. Batuan yang mengandung banyak air memiliki konduktivitas semakin besar sehingga resistivitasnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, konduktivitas akan semakin kecil jika kandungan air dalam batuan semakin sedikit sehingga resistivitasnya akan semakin besar.
Seperti disampaikan Widodo, penggunaan metode geolistrik di Desa Grabagan cukup merepotkan dan sulit dilakukan karena daerahnya tandus yang didominasi batuan kapur sehingga cukup banyak setting elektro yang dilakukan untuk akuisisi data di lapangan. Untungnya, di tengah kesulitan pengukuran, Desa Grabagan memiliki data sumur bor yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga bisa diindikasikan untuk kedalaman lebih dari 90 meter. Dari pemodelan yang dilakukan didapatkan indikasi batuan lempung dan sumber air tanah di kedalaman sekitar 100-130 meter.
Selain menemukan titik-titik sumber air tanah melalui metode geolistrik, tim pengabdian kepada masyarakat ITB juga menemukan adanya aliran sungai bawah tanah yang mengarah ke pantai utara, tepatnya di kawasan wisata Sungai Ngerong. Berada di kedalaman lebih dari 100 meter, jika pengeboran dilakukan di kawasan itu, diperkirakan bakal mendapatkan debit air yang sangat besar. Persoalannya, sungai bawah tanah itu terletak di dataran rendah. Sementara, kawasan yang selama ini mengalami krisis air berada di dataran tinggi. Untuk mengatasi persoalan ini, Widodo tidak terlalu khawatir dengan solusinya. Menurutnya, intervensi teknologi tepat guna bakal bisa menjawab cara mendistribusikan air dari dataran rendah ke dataran tinggi yang selama ini krisis air. Meski biayanya relatif besar, Widodo memastikan, pembuatan tandon-tandon secara estafet dari dataran rendah ke dataran tinggi yang dipastikan dengan pemasangan pipa bakal menjadi jawaban atas solusi krisis air di Desa Grabagan. Widodo mengakui, pembangunan tandon-tandon dan pipa untuk mendistribusikan air yang akan dibor dari sungai bawah ke tanah ke dataran tinggi akan menjadi prioritas ITB dalam program pengabdian kepada masyarakat selanjutnya di Tuban.***
Membaca Sumber Air dengan Geolistrik
DALAM mengatasi permasalahan kekeringan dan krisis air di Desa/Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, salah satu teknologi yang diperkenalkan tim pengabdian kepada masyarakat Institut Teknologi Bandung adalah geofisika. Sementara, metode yang digunakan untuk menemukan sumber air di bawah permukaan tanah adalah geolistrik.
Apa itu geolistrik? Dr. rer. nat. Widodo, S.T., M.T., dosen Fakultas Teknik Tambang dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) dari Kelompok Keahlian (KK) Geofisika Terapan dan Eksplorasi yang memimpin tim pengabdian masyarakat di Desa Grabagan, menjelaskan, geolistrik merupakan salah satu metode survei dalam teknologi geofisika yang berguna untuk menduga kondisi geologi di bawah permukaan tanah, terutama jenis dan sifat batuan berdasarkan sifat-sifat kelistrikannya.
Nantinya, data sifat kelistrikan batuan yang didapatkan dikategorikan dengan mempertimbangkan data kondisi geologi setempat. Dengan begitu, kondisi air tanah di suatu daerah dapat ditafsir dengan melokalisasi lapisan batuan yang berpotensi memiliki air tanah. Potensi air tanah yang disarankan untuk pengeboran adalah yang memiliki ketebalan akuifer atau kedalaman lebih dari 40 meter dari permukaan tanah.
Geolistrik merupakan metode yang sangat ramah lingkungan dan relatif murah. Dalam pengerjaannya metode geolistrik tidak menggunakan bahan-bahan peledak yang bisa merusak ekosistem lingkungan suatu kawasan.
Saat ini, peralatan untuk kepentingan survei geolistrik semakin canggih. Hal itu mempercepat pelaksanaan survei geolistrik untuk pemetaan sumber air tanah di suatu daerah atau kawasan. Debit kandungan air dan mineralnya juga bisa dihitung sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya suatu lokasi untuk dieksplorasi kandungan air maupun mineralnya.
Dari berbagai referensi ada beberapa kelebihan survei geolistrik. Pertama, dapat mengetahui titik pengeboran dengan lokasi yang mempunyai sumber air yang berlimpah. Kedua, bisa menentukan tahanan berdasarkan kontur tanah sebagai sumber air sehingga dapat ditentukan kedalaman ideal untuk mendapatkan banyak air dengan kualitas terbaik. Kelebihan yang ketiga, survei geolistrik dapat digunakan untuk mengetahui kandungan mineral lain, seperti batu andesit, pasir, bijih besi, batu bara, dan emas.
Pada prinsipnya, cara kerja metode geolistrik adalah menginjeksikan arus listrik direct current (DC) dari elektroda arus untuk kemudian mengamati hasil pengukurannya melalui elektroda potensial.
Menurut Widodo, geolistrik merupakan metode yang sangat ramah lingkungan dan relatif murah. Dalam pengerjaannya metode geolistrik tidak menggunakan bahan-bahan peledak yang bisa merusak ekosistem lingkungan suatu kawasan.
Secara umum, metode ini dibagi tiga, yaitu geolistrik resistivitas, polarisasi yang terinduksi, dan potensial diri. Tentu saja, setiap metode itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Selain itu, setiap metode juga memiliki parameter dan sifat-sifat fisika yang berhubungan. Metode geolistrik resistivitas dan potensial diri menggunakan konduktivitas listrik, sedangkan polarisasi terinduksi menggunakan kapasitansi listrik.
Untuk kepentingan penghimpunan data di lapangan, metode geolistrik menggunakan beberapa konfigurasi, antara lain Wenner, Schlumberger, dan Dipole-Dipole. Setiap konfigurasi memiliki faktor koreksi geometri berdasarkan susunan elektrodanya dan berfungsi agar nilai resistivitas semu yang terukur di lapangan bisa lebih mendekati kebenaran.
Untuk penerapan di Desa Grabagan, berdasarkan hasil akuisisi di lapangan dan proses inversi data geofisika, diketahui lapisan akuifer terletak di kedalaman 42-110 meter dengan diindikasikan adanya batuan sedimen yang nilai resistivitasnya berkisar 1-4 ohm meter. Sementara lapisan pertama berasosiasi dengan soil berupa lempung dan batuan konglomerat dengan ketebalan 42 meter dan mempunyai nilai hambatan jenis yaitu 5-110 ohm meter.
Batuan dasar diindikasikan batuan metamorf berupa batu gamping yang diendapkan setelah lapisan pertama, yaitu pada kedalaman 110 meter. Akuifer yang ditemukan diindikasikan sebagai confined aquifer dengan batuan dasar yang juga berupa batuan metamorf.
Setelah indikasi lapisan akuifer dapat ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengeboran air tanah. Pengeboran dilakukan untuk eksploitasi air tanah yang akan dijadikan sebagai sumber air bersih. Pengambilan air tanah dari sumur bor dilakukan
dengan memompanya ke permukaan dengan menggunakan pompa yang digerakan sumber tenaga.
Jika air tanah bersifat terkekang dan keluar dengan sendirinya dari sumur atau bersifat artesis, tergantung potensi dan tekanan air artesisnya sehingga dapat digunakan pompa sebagai pembantu pendistribusian. Jika tekanan artesis cukup, tidak perlu menggunakan pompa dan mesin. Setelah dipompa, air tanah ditampung atau didistribusikan sesuai fungsinya. Pengeboran di Desa Grabagan dilakukan sampai dengan kedalaman 85 meter. Ditemukan lapisan akuifer air tanah pada kedalaman 40 meter dengan formasi dari batuan sedimen, yaitu pasir halus sampai pada kedalaman 84 meter.
Dengan metode itu, tim PPM ITB yang dibantu masyarakat setempat berhasil memperoleh sumber air bersih dengan debit cukup besar, yaitu sekitar 30 liter per detik. Sumber air bersih tersebut dapat dimanfaatkan warga di tujuh dusun yang dihuni sekitar 1.200 jiwa. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan warga Desa Grabagan.
Selain untuk kebutuhan harian, sumber air tersebut juga dapat digunakan untuk kepentingan pengairan irigasi di areal persawahan yang selama ini hanya mengandalkan air hujan. Hal ini tentu saja bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.***

Bagian 2 Masyarakat Harmoni
Kami percaya membangun masyarakat selaras dengan tujuan-tujuan SDGs adalah dengan mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan kolektif berbasis penggalian sumber daya budaya dan sumber daya alam dalam mengatasi konflik sosial dan mitigasi bencana.


Berburu Getar Gempa

 Prof. Sri Widiyantoro, Ph.D.
Prof. Sri Widiyantoro, Ph.D.
INDONESIA secara geografis berada di wilayah cincin api (ring of fire) Pasifik yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng IndoAustralia, dan lempeng Eurasia. Pertemuan lempeng di wilayah Indonesia tergolong yang paling aktif di dunia sehingga rawan terjadi bencana, terutama gempa bumi. Jika terjadi
gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal, berpotensi menimbulkan tsunami sehingga wilayah Indonesia pun rawan tsunami. Pengembangan ilmu dan penelitian gempa bumi untuk keperluan mitigasi bencana mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11).
TSUNAMI yang dibangkitkan oleh gempa bumi raksasa dengan magnitudo 9,2 pernah terjadi pada 26 Desember 2004 di Samudra Hindia, dekat Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Disusul gempa besar dengan magnitudo 8,7 terjadi di dekat Nias pada 28 Maret 2005. Bencana gempa bumi dan tsunami di atas telah disusul juga oleh bencana gunung api yang kemungkinan dipicu oleh aktivitas tektonik tersebut. Pada 2018, Indonesia kembali berduka. Belum usai menata kembali puing berserak akibat gempa Lombok bermagnitudo 7,0 pada 5 Agustus 2018, Palu dan Donggala diguncang gempa pada 28 September 2018. Sesar Palu Koro menggeliat, menyebabkan gempa bermagnitudo 7,4 yang berpusat di kedalaman 10 km. Gempa memorakporandakan wilayah Palu dan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah yang disusul terjadinya tsunami dan juga fenomena
likuifaksi (tanah bergerak). Kejadian ini menjadi peringatan agar sistem mitigasi dan deteksi bencana yang memadai perlu segera diperbarui. Kondisi ini juga mendorong perlunya pengembangan ilmu dan penelitian gempa bumi atau seismologi yang tepat diterapkan di Indonesia.
Gempa bumi yang menimbulkan penjalaran gelombang seismik juga memberikan informasi penting mengenai struktur bagian dalam (interior) dari planet yang kita diami. Informasi ini terkandung dalam seismogram, yaitu hasil rekaman gerakan tanah akibat suatu gempa. Salah satu teknik yang digunakan untuk membedah isi bumi adalah tomografi. Riset mengenai teknik pencitraan tomografi telah lama ditekuni oleh Prof. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D. dari Kelompok Keahlian Geofisika Global, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, termasuk untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Dalam riset multitahun, yaitu selama tiga tahun, teknik pencitraan tomografi telah dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan data terkini dengan tujuan untuk memperoleh struktur 3-D kerak dan mantel bumi di sekitar Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur secara terperinci. Riset ini telah dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri dengan University of Cambridge (UoC, Inggris), dan Australian National University (ANU, Australia). Riset ini bermula dari perjumpaan Prof. Sri Widiyantoro dengan Prof. Nick Rawlinson dari University of Cambridge di pertemuan rutin AGU (American Geophysical Union) di San Fransisco, Amerika. Kebetulan Prof. Nick Rawlinson mengambil program post doctoral di The Australian National University (ANU), Canberra, tempat Prof. Sri Widiyantoro menyelesaikan studi S-3. Setelah melakukan penelitian di Sabah, Malaysia, ia ingin melanjutkan penelitiannya di Indonesia, yaitu Kalimantan dan Sulawesi, di antaranya Selat Makassar. Di tempat tersebut, tim ingin memasang seismometer ke dasar laut yang disebut ocean bottom seismometer (OBS). Penelitian ini dilakukan jauh sebelum adanya pengumuman bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Pelaksanaan penelitian mendapat dukungan dana dari Newton Institutional Links dan dana pendamping dari Ristekdikti. Sampai sekarang, Newton Fund Impact Scheme masih mendanai kegiatan, terutama terkait dengan proyek ketahanan gempa di ibu kota baru Indonesia. Selain dari Newton Fund, bantuan dana juga diperoleh dari The Global Challenges Research Fund pada 2019. Penelitian memerlukan banyak mitra mengingat kebutuhan biaya yang tidak sedikit.











































































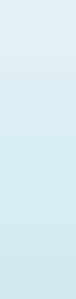




















































Tim juga bermitra dengan Prof. Phil Cummins dan Prof. Meghan Miller dari Australian National University yang telah memberikan bantuan (in kind) yaitu seismometer sebanyak 10 buah yang telah dipasang selama satu tahun di Kalimantan bersama dengan peneliti dari BMKG, yaitu Dr. Pepen Supendi.

Pada 2018, tim mulai memasang sebanyak 10 stasiun seismometer di Kalimantan. Tim BMKG sebelumnya telah memasang alat serupa sebanyak 6 buah di wilayah Kalimantan. Proses pemasangan stasiun seismometer di Kalimantan bukan perkara mudah. Butuh modal fisik dan mental yang prima. Kalimantan yang luas menjadi tantangan tersendiri sekaligus memberikan pengalaman yang tak ternilai.







































































































































Tim ITB, BMKG, Tim Greenfield dari University of Cambridge Inggris, bersama beberapa mahasiswa ikut dalam kegiatan ini. Tim harus berhari-hari melakukan perjalanan darat dengan jalur yang ekstrem. Bahkan, untuk pemasangan stasiun 10 tim harus menyewa pesawat kecil/chopper karena lokasi yang tak mungkin dijangkau melalui perjalanan darat. Stasiun seismometer tersebut ditempatkan di wilayah yang tidak dipasang seismometer oleh BMKG sehingga secara fungsional dapat saling melengkapi. Setelah dari Kalimantan, tim bergerak ke Sulawesi, tepatnya sekitar Selat Makassar untuk memasang seismometer di dasar laut (ocean bottom seismometer/OBS). Berkolaborasi dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tim Institut Teknologi Bandung dengan University of Cambridge memasang 27 unit ocean bottom seismometer di Selat Makassar, perairan Sulawesi. Pemasangan ini dilakukan oleh para peneliti dengan menggunakan Kapal Riset Geomarin III terhitung mulai 15 Agustus 2019 sampai akhir Agustus 2019 atau selama sepuluh hari. Ketika itu, tim pun sempat melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun ke-74 Indonesia di atas Kapal Riset Geomarin III.
Pemasangan OBS dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meminimalisasi gempa bumi dan bencana tsunami di Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Ocean bottom seismometer dipilih karena selain mampu mendeteksi sinyal gempa, juga memiliki kelebihan dalam kapasitas perekaman, analisis yang lebih baik, serta sistem peringatan dini yang efektif. Kegiatan ini menjadi bagian dari riset pengembangan pemodelan untuk wilayah Sulawesi yang sebelumnya telah dikembangkan oleh ITB dan BMKG.
Harga alat yang diturunkan sekitar Rp500 juta per unit dengan total alat yang dipasang sebanyak 27 OBS. Biaya sewa kapal untuk mengangkat OBS dari dasar laut pun sangat mahal. Per hari, sewa kapal kecil untuk keperluan tersebut bisa mencapai Rp100 juta. OBS tersebut dipasang di dasar laut dengan kedalaman 2.000, 4.000, juga 6.000 meter. Pemasangan ocean bottom seismometer di dasar laut di Selat Makassar belum pernah ada yang melakukan. Akhirnya, didapatkan model 3-D yang ada di bawah bumi.
Tim juga memasang seismometer bantuan dari Cambridge di Sulawesi. Penambahan seismometer baik di darat maupun di laut, diharapkan bisa mempelajari lebih baik struktur bawah permukaan di Kalimantan, terutama Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru negara, serta Sulawesi. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, proyek sempat terhambat.
Teknologi Pelestari
Mengapa Sulawesi dan Kalimantan?
Pemilihan Sulawesi dan Kalimantan bukanlah tanpa alasan. Tragedi gempa Palu bermagnitudo 7,5 mengagetkan dunia. Gempa Palu yang terjadi pada 28 September 2018 merupakan peristiwa gempa supershear langka. Lempeng bergerak dengan sangat cepat. Hal ini membutuhkan penelitian lanjutan. Selain itu, secara tektonik Sulawesi bersifat kompleks dan memiliki beberapa zona subduksi serta sesar Palu Koro, yang juga memengaruhi bahaya seismik di Kalimantan bagian timur. Kalimantan dan Sulawesi terletak dalam suatu zona kompleks interaksi antara lempeng Australia, Pasifik, Filipina, Sunda, serta beberapa microplate. Untuk itu, diperlukan riset lanjutan agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh struktur geologi dalam seperti Palu-Koro dan zona subduksi di Selat Makassar dan Laut Sulawesi.
Kalimantan dipilih karena di tempat tersebut, khususnya Kalimantan Timur, akan menjadi ibu kota negara yang baru. Data seismik Kalimantan masih sangat sedikit, karena selama ini yang banyak dipelajari adalah Sumatera, Jawa, Banda, Sulawesi. Hal itu dapat dipahami karena di Kalimantan jarang terjadi gempa. Kalimantan terletak jauh dari zona tumbukan lempeng sehingga relatif lebih stabil. Kalaupun ada gempa, magnitudonya dalam skala kecil.
Namun, tim berpikir bahwa tidak ada tempat yang bebas gempa 100% dan bukan berarti tidak ada risiko. Dulu gempa akibat pergerakan sesar di darat dekat Tarakan juga cukup merusak. Tim juga mempelajari potensi tsunami yang terjadi di Kalimantan. Meskipun gempanya terjadi dekat Sulawesi Barat, kalau berpotensi tsunami, akan sampai ke pantai Kalimantan Timur.
Awalnya, kolega Prof. Nick Rawlinson di Eropa pun sempat terheran dan menertawakan penelitian tim yang dilakukan di Kalimantan. Namun, Prof. Nick Rawlinson berpikir sebaliknya. Memang Kalimantan tidak seintens Jawa atau pulau lain di Indonesia gempanya, tetapi potensinya tetap ada. Kalau tidak dipelajari, semua tidak akan mengerti apa-apa. Boleh dibilang, Prof. Nick Rawlinson memiliki strategi samudra biru (blue ocean strategy), berani tampil beda dengan tanpa kompetitor.
Dalam sains kebaruan atau novelty menjadi hal yang penting. Ia melihat peluang kebaruan luar biasa tersebut ada di Kalimantan karena masih sangat sedikit. Jadi, semua yang dihasilkan menjadi kebaruan karena bisa dibilang belum pernah ada yang melakukan seperti yang tim lakukan. Akhirnya, dia bisa meyakinkan pemberi dana dan mendapatkan sekitar Rp8 miliar dari Uni Eropa.
Sekarang riset tersebut menjadi riset yang unik dan kebetulan Indonesia merencanakan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan sehingga waktunya menjadi sinkron. Riset sudah bergulir sebelum adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Setelah adanya kejelasan, tim sekarang telah setahun memasang 22 seismometer perekam gempa khusus di lokasi ibu kota negara hasil kerja sama dengan University of Cambridge.
Riset tersebut menjadi riset yang unik dan kebetulan Indonesia merencanakan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan.
Memotret Gerakan dalam Perut Bumi
DALAM riset ini teknik yang digunakan oleh tim telah dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan data terkini dengan tujuan untuk memperoleh struktur 3-D mantel bumi di sekitar Kalimantan dan Sulawesi secara terperinci. Model tomografi yang baru ini selain telah terbit di jurnal internasional bereputasi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan akurasi dalam penentuan dan relokasi hiposenter gempa untuk keberhasilan studi selanjutnya, seperti misalnya untuk pembuatan peta bahaya gempa. Dengan demikian, hasil riset ini akan sangat diperlukan untuk usaha mitigasi risiko bencana akibat gempa bumi di area studi.
Salah satu informasi penting yang diperlukan dalam usaha mitigasi bencana dan prediksi gempa adalah struktur interior bumi secara terperinci. Dengan demikian, tempat-tempat rawan gempa dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Untuk tujuan ini, pencitraan tomografi seismik merupakan teknik yang relevan untuk diterapkan.
Pencitraan tomografi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu rekonstruksi dari sebuah benda dari observasi besaran fisis yang merepresentasikan efek dari penjalaran suatu bentuk radiasi melalui benda yang diamati tersebut. Teknik pencitraan tomografi telah berhasil digunakan dalam bidang kedokteran. Teknik ini merupakan dasar untuk computerized tomography (CT) scanning yang diaplikasikan untuk memperoleh tomogram (slice picture) dari tubuh manusia dengan resolusi tinggi. Akhir-akhir ini, CT scanning berhasil dikembangkan untuk memperoleh tomogram yang mempunyai resolusi sangat tinggi dengan teknik magnetic resonance imaging (MRI). Teknik serupa juga telah berhasil diterapkan untuk mempelajari struktur 3-D bawah permukaan bumi, baik pada skala global dan regional dengan menggunakan data gempa bumi.
Olah data OBS
Dalam pelaksanaan penelitian ini tim mengalami kesulitan atau hambatan yang sangat berat terkait dengan masa pandemi COVID-19. OBS yang rencananya akan diambil dari dasar laut di Selat Makassar pada bulan Juni 2020 terpaksa diundur sampai pertengahan Agustus 2020. Alhasil, dari 27 OBS yang dipasang, yang dapat diangkat dari dasar laut hanya 12, sedangkan 15 lainnya dinyatakan hilang. Sulitnya medan juga menghambat proses pengangkatan OBS dari dasar laut. Terkubur selama hampir satu tahun di dasar laut membuat banyak OBS tertutupi oleh sedimen lunak sehingga sangat sulit ditarik ke atas permukaan.
Namun, dalam hal memenuhi luaran yang dijanjikan semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang telah direncanakan. Bahkan, ada beberapa tambahan output seperti memberikan keynote/invited speech pada beberapa pertemuan/ceramah ilmiah nasional.
Proses pengolahan datanya bisa digambarkan seperti berikut. Gempa di bawah permukaan, baik di kedalaman 600 km atau gempa dangkal di kedalaman 10 km, mengeluarkan energi. Energi itu akan terus menjalar dan di permukaan diterima oleh seismometer. Rekamannya tersebut berbentuk seismogram yang nanti diolah oleh tim.
Karena energi yang dihasilkan bersumber dari gempa dan diterima di stasiun, tempat-tempat yang dilewati sinar gelombang atau perambatan energi bisa ditentukan sifatsifat fisisnya, dalam hal ini kecepatannya dan kecepatan rambat gelombang di tempat tersebut dapat dipetakan menjadi semacam pencitraan 3-D. Hampir sama prosesnya dengan di bidang kedokteran, makanya disebut tomografi Yang membedakan hanya pada subjeknya, tomografi gempa bumi yang dipindai adalah bawah permukaan bumi.
Meskipun seluruh target telah dicapai selama riset tiga tahun ini, data dari OBS yang dipasang selama satu tahun sejak Agustus 2019 di laut antara Kalimantan dan Sulawesi melalui kerja sama ITB dengan Universitas Cambridge, BMKG, dan P3GL sangatlah kaya dengan informasi struktur bawah permukaan. Data OBS ini akan dapat digunakan untuk pengolahan data dengan menggunakan berbagai metode yang belum dilakukan selama ini, misalnya dengan menerapkan teknik receiver function untuk membuat mode kerak bumi di Kalimantan dengan resolusi tinggi. Hasil olah data gempa bumi itu kami mendapatkan struktur 3D di bawah Kalimantan dan Sulawesi serta di antaranya.
Hasil penelitian tim terkait struktur bawah permukaan di bawah Kalimantan, Sulawesi secara terperinci dengan teknologi terkini (full waveform inversion), metode yang paling baru dan canggih yang baru pertama kali diterapkan
di Indonesia sudah diterbitkan di jurnal bergengsi, yaitu Journal of Geophysical Research dari Amerika.
Hasil lanjutan dari penelitian juga akan diterbitkan pada tahun ini, tahun depan, dan selanjutnya. Ketika data ibu kota negara (IKN) baru sudah terkumpul dan diproses, tentu akan memberikan profil struktur bawah IKN secara terperinci yang selama ini belum ada. Untuk usaha mitigasi risiko bencana, kondisi bawah permukaan sangat diperlukan. Selain itu, manfaat penelitian ini meningkatkan keahlian para ilmuwan di Indonesia dalam ilmu gempa bumi (seismologi) antara lain melalui publikasi bersama dalam jurnal internasional, lokakarya, dan kunjungan antarpeneliti dari lembaga terkait serta membangun kolaborasi internasional antara ilmuwan dari UoC, ANU dan ITB, termasuk pengembangan proposal penelitian bersama yang lebih luas di masa mendatang.
Dengan adanya join publication ini membuat tim produktif sekali dalam menghasilkan artikel ilmiah bereputasi Q1. Dengan publikasi ini, para ahli sains terbukakan pandangannya tentang struktur-struktur bawah permukaan di wilayah yang tim pelajari, Tiga makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional Q1, yaitu Source Model for the Tsunami Inside Palu Bay Following the 2018 Palu Earthquake, Indonesia, Geophysical Research Letter, https://doi.org/10.1029/ 2019GL082717, 2019; P and S wave travel time tomography of the SE Asia-Australia collision zone, Physics of the Earth and Planetary Interiors 293, 106267, 2019;
dan Subducted Lithospheric Boundary Tomographically Imaged beneath Arc-Continent Collision in Eastern Indonesia, Journal of Geophysical Research, 10.1029/2019JB018854, 2020.
Untuk nasional, jelas kaitannya dengan joint publication yang diminta Kemenristekdikti. Publikasi Q1 tentang peneltian ini sudah melimpah, sekitar 20 dan itu nanti akan bertambah terus. Tim juga sedang menyiapkan beberapa makalah terkait dengan model kerak bumi di bawah Kalimantan dan Sulawesi dengan menggunakan metode receiver function dan tomografi bising seismik (ambient noise tomography) untuk Kalimantan.
Hasil dari lanjutan riset ini diharapkan akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan akurasi dalam penentuan hiposenter gempa untuk keberhasilan studi selanjutnya, seperti misalnya untuk pembuatan peta bahaya gempa nasional sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan demikian, hasil riset ini akan sangat diperlukan untuk usaha mitigasi risiko bencana akibat gempa secara nasional.
Hasil riset ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahaya gempa oleh masyarakat lokal di Kalimantan dan Sulawesi, khususnya mereka yang berada di daerah dengan risiko tinggi. Selain itu, meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana gempa di masa mendatang oleh para pemangku kepentingan terkait melalui penyampaian hasil pemodelan bahaya gempa di Kalimantan dan Sulawesi.
Mitigasi bencana
Riset maupun studi tentang gempa bumi selama ini masih menekankan pada pemanfaatan data gempa yang telah terjadi untuk memahami fenomena yang telah terjadi tersebut. Tidak jarang terdengar pertanyaan, “Untuk apa riset tentang kegempaan semacam ini dilakukan?”. Hasil yang diharapkan dari riset gempa bumi tentunya bahwa para ahli seismologi dapat memprediksi kejadian gempa secara tepat. Namun, hasil riset selama ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas. Bahkan, beberapa ilmuwan terkait pun masih berdebat sengit mengenai apakah kejadian gempa bumi sebenarnya dapat diprediksi atau tidak.
Oleh karena itu, diperlukan arahan riset kegempaan yang meskipun kejadiannya belum berhasil diprediksi, paling tidak risiko bencana yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Untuk menjawab tantangan ini, riset kegempaan perlu difokuskan secara bertahap pada usaha mitigasi bencana.
Dengan mengetahui kondisi di bawah permukaan harus dibuat peta sumber dan bahaya (hazard) gempa bumi. Saat ini, Indonesia sudah memilikinya, tetapi masih dalam skala regional, seluruh wilayah. Jika mempelajari lebih spesifik, misalnya untuk Kalimantan dan Sulawesi, peta hazard seismiknya akan lebih detail. Data dari peta tersebut dapat
digunakan untuk membuat building code atau kode standar bangunan.
Building code bisa diartikan aturan dalam membuat bangunan. Hal ini sangat berguna untuk tim Teknik Sipil yang akan memulai pekerjaan. Data penelitian tim bisa digunakan untuk terus memperbarui, memerinci building code sehingga mereka dapat mengetahui gedung atau rumah yang akan dibangun harus seberapa kuat strukturnya. Dengan demikian, building code-nya lebih relevan dengan kondisi setempat yang pada akhirnya kalau ada bencana terjadi, misalnya gempa, risikonya dapat dikurangi atau dimitigasi.
Bangunan yang dekat dan yang jauh dengan sumber gempa, walaupun bentuknya bisa sama, kekuatan strukturnya harus beda. Seperti di Jepang, walaupun kacakacanya tetap pecah ketika terjadi gempa, kebanyakan struktur bangunannya tidak ambruk.
Dengan demikian, pasti akan ada lebih banyak jiwa terselamatkan dibandingkan. Makanya, hal ini dikaitkan dengan memitigasi atau mengurangi risiko korban jiwa kalau terjadi gempa. Mitigasi risiko gempa harus holistik, dari sisi sains sampai pendidikan atau edukasi ke masyarakat. Di Jepang, sekolah, kantor, dan lingkungan rumah masing-masing rutin melakukan simulasi. Anak-anak, sejak kecil sudah diberi berbagai pelatihan menghadapi gempa. Di sekolah dan
setiap perumahan disediakan pengeras suara dan sirene. Jika terjadi gempa, orang-orang di gedung lantai 6 tidak boleh langsung lari ke bawah. Mereka berlindung di bawah meja-meja untuk melindungi diri dari benda yang jatuh. Kalau aman pun belum boleh turun pake lift, tetap harus berjalan kaki. Gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah dipersiapkan dengan konstruksi maksimal. Jalurjalur evakuasi gempa dan taman-taman luas di persiapkan.
Semua dilakukan untuk mengurangi risiko. Lain hal dengan yang tanpa persiapan. Masih ingat dengan gempa bermagnitudo 5,9 di Yogyakarta? Di Jepang pun pernah terjadi gempa bermagnitudo hampir sama dan di tempat yang keramaiannya hampir sama. Namun, di Yogyakarta, menelan korban lebih dari 5.000 orang, sedangkan di Jepang cuma 1 orang.***
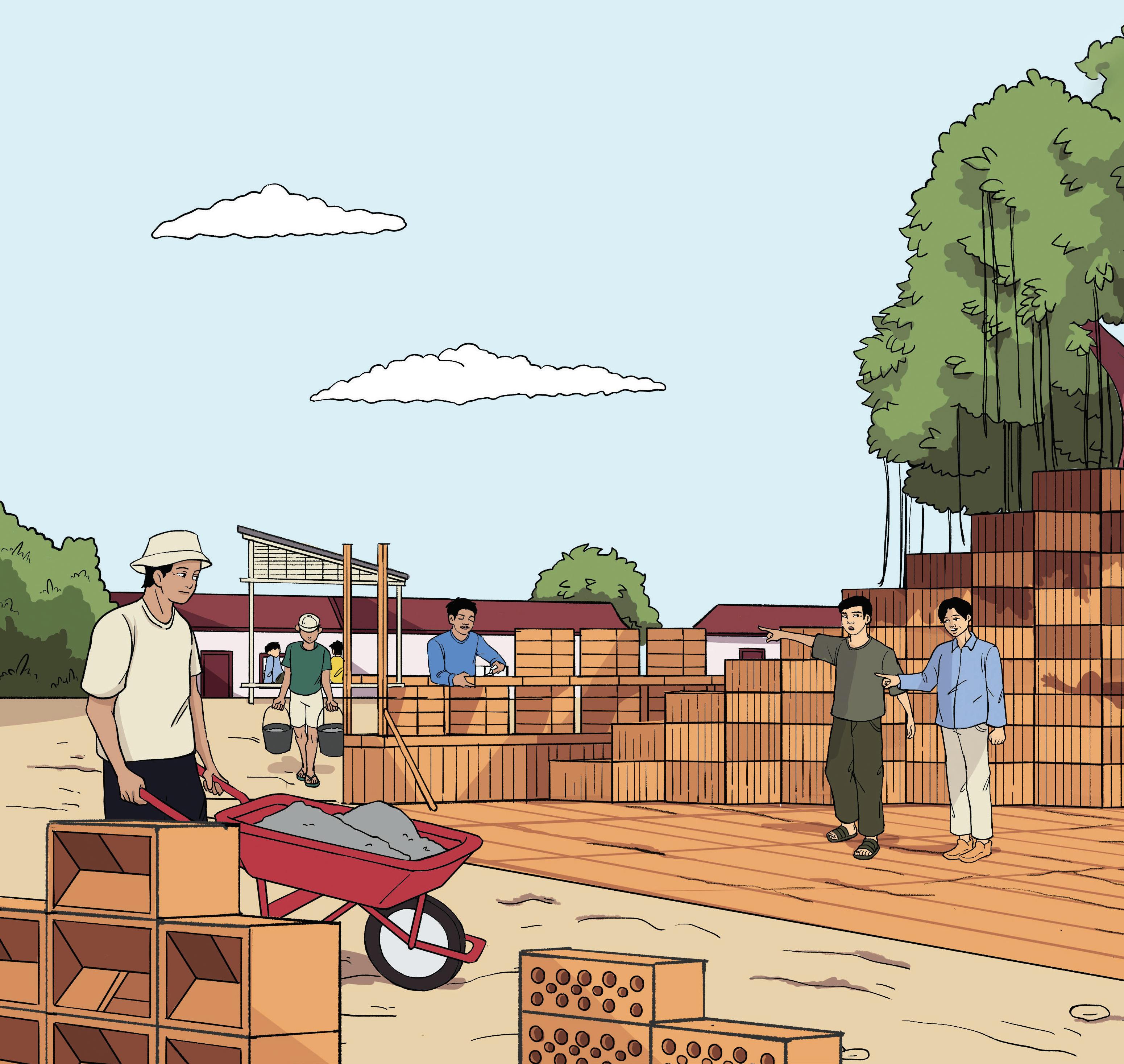
Etalase Kota Terakota

 Dr. Agus Suharjono Ekomadyo
Dr. Agus Suharjono Ekomadyo
PADA dekade 1980-an hingga 1990-an, Jatiwangi dikenal sebagai penghasil genting yang mendunia. Genting produksi Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini dikirim sampai ke Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan Eropa. Sungguh sayang, pamornya kian memudar. Infrastruktur dan inovasi yang berkelanjutan dalam pengembangan kreativitas tanah liat mendukung tujuan pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11) dan infrastruktur, industri, dan inovasi (SDG 9).
TANAH liat yang menjadi bahan baku genting, menurun dari segi jumlah maupun kualitasnya. Sementara, pengusaha genting punya produk lain, mereka hanya membuat genting dengan cara dan alat yang sama seperti dulu. Sementara, zaman terus berubah. Sektor konstruksi menuntut segala sesuatunya lebih efisien. Sejak 2000-an mulai diperkenalkan metal roof yang lebih mudah didapat dan mudah memasangnya. Genting ini menjadi pilihan bagi rumah minimalis yang trennya semakin positif. Situasi ini semakin membelit pengusaha genting Jatiwangi. Satu per satu mereka gulung tikar. Jika pada 1980-1990 masih ada sekitar 630 pabrik genting di Jatiwangi, data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011-2018 menunjukkan, jumlahnya tinggal 150 pabrik saja.
Kelesuan itu didobrak oleh Jatiwangi Art Factory (JAF). Komunitas yang berdiri pada 2005 ini menjadikan seni sebagai pendekatan baru menghidupkan kembali Jatiwangi.
Komunitas ini tidak hanya berhasil membangkitkan kreativitas menghasilkan produk-produk tanah liat, tetapi juga menggelar berbagai pertunjukan seni dan budaya yang bersumber tanah liat.
Tanah liat tidak hanya dipandang sebagai komoditas yang mendatangkan banyak uang (dari berdagang genting tanah liat). Lebih dari itu, tanah liat diperlakukan sebagai budaya, sumber kehidupan, juga urat nadi masyarakatnya. Pendekatan ini rupanya berhasil membuat masyarakat setempat kembali mencintai tanah liat yang selama ini telah menghidupinya.
Jatiwangi pun dilirik kembali. Tidak semata karena bernostalgia dengan genting tanah liat, tetapi telah lahir berbagai karya-karya baru dari sana dengan tanah liat tetap sebagai porosnya. Masyarakat mulai membuat produk-produk baru, misalnya alat musik dari tanah liat, berbagai produk tembikar, dan sebagainya.
JAF kemudian menggulirkan wacana Kota Terakota. Sebuah gagasan untuk mendorong inovasi produk tanah liat Jatiwangi. Harapannya, produk tanah liat akan lebih beragam, tidak hanya genting. Bisa juga berbagai macam produk lain yang berbahan tanah liat. Meski disambut positif, para pelaku usaha belum terlalu optimistis. Mereka tak mau buru-buru, cenderung melihat situasi dahulu untuk memastikan produk baru bisa terserap pasar. Ide Kota Terakota ini digaungkan lewat Program Pengabdian Masyarakat ITB 2021 yang dilaksanakan oleh Dr. Agus Suharjono Ekomadyo, S.T., M.T. dari Kelompok Keahlian Perancangan Arsitektur. Program ini berupa pembuatan Alun-Alun Desa Jatipura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.
Program ini dilakukan dengan pendekatan modal budaya (cultural capital) dan produksi ruang (production of space). Pendekatan ini dirasa sesuai dengan kondisi Jatiwangi yang sudah memiliki tradisi tanah liat. Budaya kreatifnya pun sudah terbangun lewat pendekatan budaya kreatif yang digairahkan oleh JAF.
Pendekatan produksi ruang digunakan agar pembangunan alun-alun itu tidak sekadar menciptakan objek baru. Konstruksi arsitektural yang dibangun di alun-alun tersebut menjadi representasi aspirasi dan nilainilai yang diperjuangkan oleh semua pelaku yang terlibat. Pembangunan Alun-Alun Desa Jatisura ini melibatkan pemerintah desa pemangku kebijakan, komunitas JAF sebagai lokomotif pergerakan seni budaya, serta masyarakat setempat sebagai pemilik artefak budaya ini.
Tanah liat tidak hanya dipandang sebagai komoditas yang mendatangkan banyak uang. Lebih dari itu, tanah liat diperlakukan sebagai budaya, sumber kehidupan, juga urat nadi masyarakatnya.
Keragaman bentuk dan desain
Pembuatan desain dan konstruksi Alun-Alun Jatisura dimulai sejak 2021. Ide dasar desainnya berasal dari wacana Kota Terakota. Terakota berasal dari bahasa Latin yang artinya tanah bakar. Terakota merujuk pada material yang berasal dari tanah liat yang halus dibentuk sesuai dengan keinginan selanjutnya dikeringkan, lalu dibakar pada suhu 1.000 derajat Celsius.
Terakota bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang rumit tanpa ada sumber daya yang besar dan teknologi tinggi. Ukuran terakota yang dihasilkan juga sangat beragam. Selama material tidak pecah saat dikeringkan dan cukup dibakar di tungku pembakaran, terakota bisa diproduksi dengan beragam ukuran. Produk terakota biasanya untuk ubin dan genting dibatasi ukuran 400 mm x 400 mm.
Karakter produk terakota memiliki struktur yang kuat terhadap tekanan, tetapi lemah jika ditarik. Produk terakota relatif berukuran kecil-kecil dan perlu disusun untuk menciptakan bentuk yang diinginkan.
Karakteristik ini membuat penggunaan produk terakota sangat fleksibel, sesuai dengan cara menyusunnya.
Terakota biasanya difungsikan sebagai elemen struktur tekan, pembentuk bidang utama, juga sebagai ornamen tambahan pada bidang lain. Terakota juga bisa dibentuk sesuai dengan kebutuhan desain, bisa lurus ataupun melengkung, dibuat semitransparan untuk membuat bidang yang halus maupun kasar. Spektrumnya sangat luas sehingga terakota sangat potensial untuk dikembangkan.
Dengan potensi yang demikian besar, alun-alun berkonsep terakota di Desa Jatisura ini tidak bertujuan untuk menarik perhatian orang saja. Lebih dari itu, alun-alun ini dibuat sebagai etalase keragaman sisi dan bentuk terakota. Pendeknya, setiap orang yang datang dan melihat alun-alun ini akan mengetahui keunggulan terakota dan potensi yang dimiliki Jatiwangi. Semua produk terakota produksi Jatiwangi akan dipajang di alun-alun ini sehingga tergambar betapa kentalnya budaya tanah liat Jatiwangi.
Teknologi Pelestari / 113
Alun-Alun Jatisura
Alun-Alun Jatisura merupakan area publik yang digunakan untuk beragam aktivitas warga. Lahan terbuka berukuran sekitar 10x12 meter ini dikelilingi bangunan publik seperti sekolah, kantor desa, juga masjid.
Di tengah alun-alun terdapat pohon beringin yang membuat alun-alun ini rindang. Pepohonan di sekitar alun-alun menjadi peneduh bagi pengunjung yang biasa berkumpul pada sore hari. Sebagian bermain badminton, sebagian lain bermain sepak bola. Pada saat Idulfitri dan Iduladha digunakan untuk salat.
Desain alun-alun dibuat agar tidak ada fungsi Alun-Alun Jatisura yang hilang atau berkurang. Pembangunannya juga diusahakan seminimal mungkin dilakukan intervensi sehingga bisa efisien. Itu sebabnya pohon beringin dibiarkan di tempatnya, hanya ditambah pot yang disesuaikan dengan desain alun-alun. Panggung yang sudah ada juga tidak dihilangkan. Batasan-batasan alun-alun juga tetap seperti semula. Dengan memperhatikan fungsi dan kondisinya, gestur desain dibuat menghampar. Terakota disusun menghampar di alun-alun.
Desain yang dibuat memaksimalkan tiga fungsi terakota, yakni sebagai struktur, pembentuk bidang, dan ornamen. Sebagai struktur bisa dilihat di area dudukan yang dibuat bertingkat sehingga terlihat bata bisa digunakan sebagai struktur. Bata juga digunakan sebagai pembentuk dinding yang menonjol. Dinding ini berfungsi sebagai pembentuk bidang utama. Terakota sebagai ornamen bisa dilihat dari fungsinya sebagai batu tempel. Dengan demikian, desain alun-alun ini menampilkan ketiga fungsi terakota.
Desain yang dibuat seluruhnya menggunakan batu bata (full brick) yang disusun sedemikian rupa sesuai gambar sehingga proses pembangunannya memanfaatkan sifat batu bata yang bisa disusun lapisan demi lapisan tanpa perlu membuat cetakan.
Desain terakota yang dibuat selain memaksimalkan fungsi juga mengeksplor berbagai bentuk sehingga potensi materialnya pun turut terekspos maksimal. Material terakota yang menggunakan batu bata sering kali tidak tampak keindahannya karena ditutup dengan batu tempel. Sementara, batu tempel sendiri bukanlah material unggulan Majalengka. Batu tempel didatangkan dari Plered karena kualitasnya lebih baik. Jelas ini tidak sejalan dengan tujuan utama alun-alun sebagai etalase terakota Majalengka.
Batu tempel yang digunakan sebagai ornamen juga dibuat dari terakota yang tidak sekadar sebagai penutup, tetapi menjadi bentuk yang independen. Ini sekaligus menunjukkan keunggulan terakota yang mudah dibentuk karena bersifat lunak sebelum dibakar. Di proyek ini, seluruh opsi penggunaan terakota yang beragam, mulai dari paving, hollow grid, batu tempel, krawang, atap sirap, dan lainnya. Ada dua tipe terakota yang digunakan, yaitu terakota custome tile berukuran 20 x 20 cm dengan motif yang unik dan post terakota. Post terakota ini menunjukkan sisi lain terakota, yaitu penggunaan ulang limbah terakota yang ada.
Proses yang tidak mudah
Proses pembuatan konstruksi alun-alun ini cukup njelimet. Para pekerja harus membuat bentuk terakota yang beragam, bentuk lurus, lengkung, dan bentuk-bentuk unik lainnya. Belum lagi menyiapkan lahan agar sesuai dengan kebutuhan desain. Hal ini tergolong baru bagi para pekerja. Eksekusi gambar desain jadi tidak mudah. Beberapa kekeliruan terjadi di lapangan sehingga gambar desain harus dikompromikan dengan situasi di lapangan.
Situasi ini sulit dihindari karena tim dari ITB tidak bisa setiap hari berada di lapangan. Sementara, proses harus jalan terus. Memberi instruksi di lapangan menjadi tantangan tersendiri.
Belum lagi keterbatasan pendanaan sehingga proses pembuatan tidak bisa diselesaikan langsung. Jeda pengerjaan memiliki risiko kerusakan. Beberapa sudut menjadi sasaran vandalisme. Selain itu, lumut mulai ditemui di permukaan.
Program pengabdian masyarakat yang direncanakan dua tahun ini akan segera dirampungkan. Beruntung program ini mendapat sokongan penuh dari Kepala Desa Jatisura sehingga beberapa kesulitan dalam proyek ini bisa teratasi dengan baik.
Bagi warga setempat yang terlibat, proyek ini seperti membantu meningkatkan kemampuan mereka. Mereka jadi punya pengalaman mengerjakan konstruksi terakota sehingga bisa menerima proyek serupa di lain hari. Sejumlah tukang dari warga setempat pun jadi lebih berdaya.
Teknologi Pelestari / 117
Jatiwangi
dan Sokka
Selain di Jatiwangi, program pengabdian masyarakat ini juga akan dilakukan di komunitas genting Sokka, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Rencananya program di sana akan dimulai tahun 2022 juga. Meski samasama memproduksi genting, kondisi Jatiwangi dan Sokka cukup berbeda. Jika kelesuan Jatiwangi diakibatkan disrupsi industri genting, pudarnya pamor Sokka terjadi perlahan. Sokka kini dikembangkan sebagai destinasi wisata. Perbedaan karakter ini membutuhkan sentuhan yang berbeda pula.
Program pengabdian masyarakat di Sokka bentuknya ialah sayembara desain ruang publik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya tanah liat di Sokka. Sayembara ini diharapkan mampu menggali berbagai sisi budaya tanah liat wisata Sokka.
Meski bentuk kegiatannya berbeda, program pengabdian masyarakat di Jatiwangi dan Sokka mesti saling terhubung. Para penggerak komunitas di dua lokasi tersebut bisa saling belajar dan memperluas jejaring masingmasing. Itu sebabnya, program di Kebumen nantinya akan melibatkan para penggerak dari Jatiwangi. Para penggerak di Jatiwangi akan dilibatkan sebagai juri sayembara di Kebumen. Penggerak di Kebumen juga akan bertandang ke Majalengka untuk belajar bagaimana mewujudkan desain yang terpilih nanti.***
Sayembara desain ruang publik yang sesuai dengan nilai-nilai budaya tanah liat di Sokka diharapkan mampu menggali berbagai sisi budaya tanah liat wisata Sokka.
Desain Kolektif Alun-alun
INFRASTRUKTUR yang berfungsi dan tangguh merupakan fondasi dari komunitas yang sukses. Sustainable Development Goals (SDGs) meletakkan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan inovasi sebagai agenda global kesembilan yang ditargetkan tercapai pada 2030. Infrastruktur dan inovasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, mendukung pembangunan ekonomi sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Alun-Alun Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka merupakan salah satu upaya untuk membangun infrastruktur ruang publik yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
Pemberdayaan masyarakat lewat arsitektur sudah dikenal lama. Misalnya saja konsep pembangunan berbasis komunitas (community based development/CBD) yang dulu banyak digunakan. Konsep ini lahir dengan semangat memberdayakan masyarakat. Meski bertujuan mulia, konsep ini tidak lepas dari kritik. Kritik utamanya karena pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berbasis komunitas ini dikembangkan atas dasar niat mengurangi kesenjangan pembangunan antara negara maju dan berkembang. Negara maju beranggapan, dalam jangka
panjang kesenjangan pembangunan itu akan membahayakan dunia. Itu sebabnya negara maju terdorong untuk turun tangan membantu negara berkembang.
Setelah itu, lahirlah perencanaan partisipatif. Konsep ini melibatkan komunitas secara aktif dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan yang biasanya menjadi ranah pemerintah kemudian diturunkan ke masyarakat jadi dibalik. Masyarakat yang menjadi aktor utama dalam perencanaan partisipatif. Model bottom-up seperti ini dinilai lebih efektif ketimbang top-down yang kerap tidak efektif dan tepat sasaran.
Transformasi perkampungan di bantaran Kali Code, Yogyakarta, merupakan contoh keberhasilan perencanaan partisipatif. Kampung yang semula kumuh berubah menjadi lebih tertata, indah, dan terasa nyeni. Keberhasilan ini tidak lepas dari keterlibatan Romo Mangunwijaya. Kerjakerjanya di Kali Code banyak dipengaruhi oleh filsafat fenomenologi dari Martin Heidegger (1927). Tokoh lainnya, Hasan Poerbo, profesor arsitektur ITB ini berhasil membangun Rancamanyar sebagai eco-village. Berbeda dari Romo Mangunwijaya, Hasan lebih banyak dipengaruhi oleh System Thinking dari Benjamin Handler (1970). Romo Mangunwijaya dan Hasan Poerbo merupakan dua tokoh utama desain partisipatif di Indonesia.
Meski telah menunjukkan keberhasilan, konsep ini bukan tanpa cela. Setidaknya ada tiga kelemahan perencanaan partisipatif ini. Pertama, selalu ada partisipasi dari orang lain selain perancang dan pemberi tugas yang sering disebut pemangku kepentingan/stakeholders dengan tingkat partisipasi yang berbeda-beda. Pada hakikatnya, desain merupakan proses sosial sehingga banyak pihak yang terlibat.
Masing-masing mempunyai pengetahuan, sudut pandang, preferensi, dan kepentingan masing-masing. Bahkan, dalam pekerjaan desain paling sederhana sekalipun, seorang arsitek akan melibatkan para pemangku kepentingan. Misalnya proyek membangun rumah tinggal, maka arsitek akan melibatkan bapak, ibu, anak, dan orang yang tinggal di rumah itu, misalnya pembantu rumah tangga meskipun sering kali aspirasi para pemangku kepentingan tersebut hanya diwakili oleh satu orang saja. Biasanya diwakili oleh bapak sebagai pemberi tugas. Namun, dalam banyak kasus, sang bapak sebagai pemberi tugas melibatkan anggota keluarga lainnya dalam pengambilan keputusan desain karena kenyamanan dalam menggunakan rumah sebagai hasil rancangan akan bergantung pada preferensi masingmasing anggota keluarga. Kedua, pendekatan desain partisipatif yang dilakukan oleh Hasan Poerbo dan Romo Mangunwijaya mendapat kritik sepeninggal keduanya. Praktik desain partisipatif yang dilakukan Hasan Poerbo bertujuan untuk mengembangkan komunitas secara sistematis sehingga aspek artistik desain tidak ditonjolkan. Padahal, sisi artistik penting mengingat arsitek merupakan makhluk kreatif. Sementara, Romo Mangunwijaya yang banyak dipengaruhi oleh pendekatan
fenomenologi jadi menekankan pada subjektivitas. Hal ini membuat keberhasilan program yang dijalankan sangat bergantung pada kehadiran Romo Mangun. Saat Romo Mangun absen, proyek terhenti. Ini terjadi pada proyek di Sendang Sono. Keberhasilan desain partisipatif di Kali Code juga memudar setelah Romo Mangun berpulang. Roh perjuangan Romo Mangun mendampingi kelompok marginal perkotaan yang disebut sebagai ‘girli’ (pinggir kali) perlahan menghilang. Bahkan, di kampung itu kini muncul bangunan-bangunan permanen yang membahayakan ekosistem sungai.
Ketiga, tokenisme atau perencanaan partisipatif yang sering hanya menjadi stempel terhadap pembangunan tertentu. Kondisi ini sering dijumpai pada proyek-proyek pemerintah. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi arsitek dalam membuat perencanaan.
Keempat, prosedur perencanaan dan perancangan partisipatif yang sudah pakem sering kali tidak realistis jika dihadapkan pada kompleksitas dunia sosial dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki arsitek. Prosedur perencanaan partisipatif mensyaratkan adanya konsensus dari pemangku kepentingan terhadap rancangan pembangunan. Konsensus semacam itu hampir mustahil sebab tidak ada jaminan semua pihak bersepakat dan berkomitmen. Ketidaksetujuan itu tidak bisa dihapus seluruhnya sehingga bisa jadi konsesnsus yang terbentuk bersifat semu. Sumber daya untuk mencapai konsensus teramat besar, baik berupa biaya, waktu, maupun tenaga. Tidak semua tim arsitek memiliki sumber daya yang memadai.
Kelemahan-kelemahan ini memunculkan pendekatan kolektif sebagai pendekatan baru agar desain tetap bisa menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Pendekatan kolektif memberi
ruang untuk aspek artistik pada desain arsitektur. Nilai-nilai dasar kreativitas arsitek dalam berkarya tetap ditonjolkan. Istilah kolektif pada pendekatan ini merujuk pada relasi-relasi manusia yang dinamis. Relasi itu selalu berubah, penuh kontroversi, bisa terjadi konsensus, tetapi juga mungkin terjadi pengkhianatan. Produk arsitektur yang dihasilkan lewat desain bisa menstabilkan relasi antarmanusia meskipun keberadaannya bisa berganti secara tiba-tiba.
Dengan demikian, upaya rekayasa sosial bisa dilakukan dengan menciptakan objek teknis yang mampu menstabilkan relasi antarmanusia. Pendekatan inilah yang digunakan dalam merancang Alun-Alun Desa Jatisura. Perbedaan antara pendekatan desain partisipatif dengan kolektif utamanya terletak pada peran arsitek. Pada desain partisipatif, arsitek atau desainer berperan sebagai fasilitator. Arsitek lebih pasif, sedangkan yang berperan aktif ialah masyarakat. Pendekatan ini tidak akan berjalan mulus jika masyarakat tidak proaktif dan belum mempunyai tujuan yang jelas.
Sementara, pada pendekatan kolektif, arsitek yang berperan aktif. Pendekatan ini menciptakan objek teknis yang bisa menstabilkan relasi antarmanusia. Untuk membuat objek teknis tersebut memerlukan kompetensi teknis dari para pelaku yang terlibat. Arsitek dan desainer mempunyai kompetensi untuk membuat objek teknis ini dibandingkan dengan pelaku lain yang terlibat.
Keterlibatan arsitek atau desainer sebagai pelaku yang proaktif memunculkan keraguan bagaimana objek teknis tersebut memiliki relasi dengan masyarakat? Maka, desain yang dibuat harus bisa mewakili kehendak masyarakat. Jika objek teknis tersebut semakin menggambarkan kehendak masyarakat, semakin kuat relasinya.
Rasa kepemilikian masyarakat terhadap objek teknis yang dibuat ini oleh Bruno Latour dijelaskan dalam empat tingkatan, interference , memengaruhi tindakan; composition , menggabungkan berbagai tindakan; folding space and time ; ketika aneka tindakan itu terajut secara intensif; dan delegasi, ketika manusia mewakilkan kehendaknya pada objek teknis yang dibuat atau digunakan.
Perancangan desain Alun-Alun Jatisura berpusat pada arsitek yang memiliki kompetensi teknis untuk merancang desainnya. Desain yang dibuat mewakili kehendak masyarakat. Itu sebabnya proses perencanaannya melibatkan Jatiwangi Art Factory (JAF) sebagai komunitas penggerak masyarakat setempat serta pemerintah desa yang memiliki kewenangan dan menjadi lembaga formal yang menaungi berbagai aspirasi masyarakat. Setelah industri genting Jatiwangi terdisrupsi, masyarakat yang digerakkan oleh JAF bangkit kembali dengan pendekatan budaya tanah liat. Masyarakat berharap keberhasilan ini bisa dilanggengkan lewat ide kota terakota.
Inilah yang ditangkap oleh Dr. Agus Suharjono Ekomadyo, S.T., M.T. bersama timnya dalam program pengabdian masyarakat. Tim merancang desain Alun-Alun Desa Jatisura dengan ide kota terakota. Alun-alun ini merupakan objek teknis yang bisa menstabilkan relasi antarmanusia di sana. Alun-alun ini bisa menjadi ruang publik yang menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Dirancang dengan desain yang menonjolkan produk-produk tanah liat unggulan desa tersebut. Sebagai produk kreativitas, tentu saja aspek artistik tetap dikedepankan.***
Teknologi Pelestari / 121

Konflik di Gugusan Pulau

 Teti Armiati Argo, Ph.D.
Teti Armiati Argo, Ph.D.
Ketika pertama kali mendengar nama Karimunjawa, hal pertama yang dipikirkan banyak orang adalah destinasi wisata eksotis, terutama bentang alam dan keindahan pantai serta bawah lautnya. Saking favoritnya sebagai destinasi wisata, Karimunjawa punya julukan mentereng seperti The Caribbean van Java atau The Paradise of Java. Penataan kawasan konservasi untuk menjaga fungsi alami ekosistem dan pengelolaan konflik pemanfaatan wilayah pesisir dan laut selaras dengan pencapaian kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11) serta perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat (SDG 16).
TERLETAK di pertengahan Pulau Jawa dan Kalimantan, Karimunjawa merupakan gugusan yang memiliki 27 pulau, 5 di antaranya berpenghuni sekitar 9.514 jiwa. Selain keindahan alamnya, secara ekologis, Karimunjawa juga sangat penting. Karimunjawa adalah rumah bagi lima ekosistem unik, yaitu terumbu karang, lamun, mangrove, hutan pantai, dan hutan hujan tropis. Selain flora yang yang beragam, di kawasan ini juga hidup 400 spesies fauna laut, termasuk 242 jenis ikan hias dan satwa langka seperti penyu sisik, penyu hijau, dan elang laut dada putih, Sejak tahun 2001, pemerintah menetapkan Karimunjawa sebagai taman nasional, kawasan konservasi dan pelestarian alam yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya serta sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
Mengingat status konservasi yang dimiliki, prioritas utama pengelolaan kawasan Taman Nasional Karimunjawa adalah menjaga fungsi alami ekosistem yang ada di sekitarnya sehingga manfaat lingkungannya dapat dinikmati secara berkelanjutan.
Persoalannya, kawasan konservasi kerap terbebani oleh kepentingan multisektor yang melihatnya dari sisi berbeda, khususnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Di kawasan konservasi laut seperti di Karimunjawa, setidaknya ada empat sektor yang sering berkonflik yaitu perikanan, pariwisata, perhubungan laut, dan energi. Persaingan kepentingan tersebut melahirkan kon flik pengelolaan yang mengancam pencapaian tujuan kawasan konservasi.
Dalam upaya mereduksi konflik pemanfaatan tersebut, salah satu alat yang digunakan adalah perencanaan spasial. Metode perencanaan ini menitikberatkan pada pendekatan berdasarkan daya dukung ruang dengan memanfaatkan berbagai data, informasi, dan referensi kebumian. Dalam konteks di Taman Nasional Karimunjawa, data dan informasi geospasial laut berorientasi masyarakat menjadi penting untuk mereduksi konflik yang terjadi di kawasan pesisir dan laut.
Sayangnya, identifikasi konflik yang terjadi selama ini belum cukup menangkap kompleksitas masalah yang dihadapi Balai Taman Nasional Karimunjawa. Kondisi tersebut menyebabkan zonasi sebagai bentuk perencanaan spasial laut di Taman Nasional Karimunjawa belum optimal menyentuh berbagai permasalahan.
Melalui Program Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) berupaya mengungkap konflik yang terjadi dalam pemanfaatan pesisir dan laut di Taman Nasional Karimunjawa untuk kemudian menyediakan alternatif manajemen yang sesuai sehingga dapat menjadi referensi bagi pengelola taman nasional maupun otoritas terkait lainnya.
P3MI di Kepulauan Karimunjawa ini dipimpin dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Ir. Teti Armiati Argo, M.E.S., Ph.D. dari Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Pedesaan. Ia dibantu dua koleganya, Wilmar A. Salim, S.T., M.Reg.Dev., Ph.D. (KK Perencanaan Wilayah dan Pedesaan) dan Andrian Ramadhan.
Untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, tim P3MI berupaya mengeksplorasi sumber dan akar permasalahan dalam konflik perencanaan spasial pesisir dan laut di Taman Nasional Karimunjawa, mengidentifikasi konflik laten dan manifest yang terjadi, serta mengetahui dan merekomendasikan bentuk manajemen konflik dalam perencanaan spasial pesisir dan laut yang berorientasi pada masyarakat.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan tim P3MI ITB kemudian diketahui adanya tiga bentuk konflik yang lahir dari tiga akar permasalahan. Ketiganya adalah konflik pembangunan, sumber daya. dan kepemilikan.
Konflik pembangunan menunjukkan adanya pertarungan kepentingan lingkungan dan kesetaraan sosial dalam pemanfaatan ruang laut. Di satu sisi, eksploitasi yang tidak terkendali terbukti telah mengakibatkan ekosistem terdeplesi, khususnya terumbu karang sehingga berdampak pula pada kelimpahan sumber daya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat berhak memanfaatkan sumber daya, baik karena alasan kesejarahan maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Konflik ini melibatkan Balai Taman Nasional Karimunjawa dan masyarakat secara berhadap-hadapan.
Konflik sumber daya mencerminkan pertarungan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Konflik ini secara intensitas terdiri dari konflik laten dan konflik terbuka.
Konflik laten berupa alih fungsi lahan pesisir untuk kepentingan pariwisata dan budidaya tambak yang akan memberikan dampak negatif di masa datang. Perubahan
yang sifatnya gradual membuat masyarakat tidak langsung menyadari dampaknya sehingga konflik belum naik ke permukaan.
Sementara, konflik kepemilikan berkaitan dengan pertentangan kepentingan ekonomi dan kesetaraan sosial. Privatisasi ruang pesisir dan laut membuat masyarakat termarginalkan karena kesulitan mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi sebagaimana sebelumnya. Padahal, ruang yang diklaim secara hukum merupakan ruang publik yang tidak dapat diprivatisasi. Bentuk yang mudah terlihat adalah berdirinya bangunan di atas perairan untuk kepentingan wisata meskipun wilayah tersebut secara tradisional dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kepentingan.
Ketiga bentuk konflik tersebut memengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan zonasi dan regulasi yang ada di dalamnya. Lahirnya zonasi dan regulasi terkait ternyata melahirkan bentuk konflik lain yang disebut minnery sebagai conflict through planning. Isu yang menonjol adalah pertentangan antarsektor yang merasa terganggu kepentingannya.
Tiga sektor yang cukup merasakan dampaknya adalah perikanan, pariwisata, dan perhubungan. Sektor perikanan berkaitan dengan penutupan beberapa lokasi perairan untuk penangkapan ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Begitu juga dengan regulasi yang melarang pemanfaatan jenis-jenis sumber daya perikanan tertentu seperti ikan napoleon, kima, penyu, dan lainnya.
Pariwisata sebetulnya memiliki keselarasan tujuan dengan konservasi karena wisata membutuhkan objek alam yang dapat ditawarkan. Sayangnya, dalam perilaku terdapat ketidaksesuaian karena pengembangan wisata cenderung mengadopsi pendekatan wisata massal.
Berdasarkan praktik wisata yang berjalan diketahui bahwa aktivitas wisata berdampak negatif terhadap ekosistem, terutama terumbu karang. Perhubungan memiliki kepentingan terhadap alur pelayaran bagi kapal-kapal yang melintas.
Kawasan Karimunjawa yang relatif berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan Kalimantan merupakan tempat strategis untuk disinggahi. Kepentingan keselamatan seperti berlindung dari cuaca buruk adalah justifikasi utama bagi kapal-kapal tongkang untuk merapat ke perairan yang dangkal. Sayangnya selama ini alur laut untuk pelayaran kapal-kapal besar belum terakomodasi dalam rencana zonasi. Secara prinsip, Balai Taman Nasional Karimunjawa berdiri di atas argumentasi kuat karena keberadaan mereka mengancam eksistensi terumbu karang sebagaimana terbukti pada berbagai kasus yang terjadi di sekitar Kepulauan Karimunjawa. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu aktivitas nelayan lokal khususnya nelayan cumi dan jaring.
Penelitian ini merekomendasikan perbaikan manajemen konflik dalam perencanaan pesisir dan laut untuk lebih berorientasi pada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menitikberatkan pada pengurangan kesenjangan pemahaman sehingga proses demokratisasi pengambilan keputusan tidak membahayakan tujuan dari pengelolaan kawasan sebagai taman nasional laut.



Program edukasi masyarakat juga tidak boleh berhenti pada skala yang sempit seperti hanya kepada tokoh masyarakat, tetapi juga masyarakat secara luas. Salah satu cara dengan menggandeng komunitas pariwisata, nelayan, adat, dan sebagainya. Bahkan perlu dipikirkan program jangka panjang dengan mengedukasi generasi muda, baik melalui jalur formal maupun informal. Selain itu, penyelesaian konflik juga harus menyentuh akar masalah dan tidak berhenti pada yang tampak di permukaan. Pelanggaran zonasi, khususnya oleh pihak korporasi atau pemilik modal harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Toleransi atau bahkan legalisasi tindakan yang tidak sesuai aturan oleh pihak korporasi akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tentang tujuan pengaturan spasial laut ini. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan konflik yang lebih dalam dan luas, khususnya terkait kepatuhan terhadap zonasi yang dibuat.***


Zonasi sebagai Solusi Konflik
SEBAGAI kawasan konservasi, Taman Nasional Karimunjawa wajib melakukan sistem zonasi sebagai alat mengendalikan pemanfaatan ruang. Awalnya, berdasarkan SK. Dirjen PHKA No.127/Kpts/DJVI/1989 ditetapkan hanya ada empat zonasi yakni zona inti, perlindungan, pemanfaatan, dan penyangga.
Namun, seiring dengan perkembangan, zonasi di Taman Nasional Karimunjawa berubah menjadi tujuh berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. SK.79/IV/Set-3/2005 dan kemudian bertambah menjadi sembilan berdasar Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 28/IV-SET/2013 tertanggal 6 Maret 2013.
Sejak dibuat tahun 1989, zonasi di Karimunjawa telah dua kali mengalami revisi. Pertama, tahun 2005 dan kedua 2012. Latar belakang yang mendasari rezonasi berdasarkan review dokumen cukup berbeda di antara keduanya.
Pada rezonasi tahun 2005, perhatian besar diberikan pada isu degradasi lingkungan atas berbagai aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan. Zonasi yang ada ternyata tidak berjalan karena minimnya sosialisasi dan
pengaturan yang tidak memadai. Penyebab lainnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong perubahan paradigma pengelolaan dari top-down menjadi bersama. Pengakuan masyarakat akan zonasi menjadi salah satu pertimbangan penting agar zonasi tidak hanya di atas kertas, tetapi di lapangan. Kondisi ini sedikit bergeser pada saat rezonasi kedua pada tahun 2012. Isu utama yang diangkat adalah ketidaksesuaian dengan dinamika pengelolaan yang pada kenyataannya mengacu pada praktik pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan peruntukan zonasi. Beberapa yang menjadi isu adalah sengketa lahan pesisir, bangunan atas laut yang tidak sesuai, pengembangan wisata pada pulau-pulau kecil, dan penggunaan ruang laut untuk budi daya perikanan. Selain itu, ada pula tuntutan untuk menambah luasan zonasi inti yang dirasa tidak proporsional dengan luas kawasan. Luas zonasi inti tercatat hanya sebesar 0,4%.
Terlepas dari berbagai alasan tersebut, rezonasi nyatanya merupakan respons atas permintaan pasar yang menuntut perlunya penyesuaian tata ruang untuk pengembangan destinasi wisata di kawasan Karimunjawa.
Zonasi dan rezonasi inilah yang kemudian menjadi pemicu ketegangan antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan dalam melihat sumber daya kawasan. Masyarakat menganggap sumber daya di Karimunjawa adalah anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup mereka. Sementara, otoritas pengelola harus menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan keberlanjutan.
Dalam perjalanannya, konflik masyarakat dan pengelola Taman Nasional Karimunjawa seperti timbul tenggelam, sifat konfliknya berganti-ganti antara laten dan terbuka. Semua itu disebabkan proses perumusan zonasi, implementasi dan penegakan regulasi zonasi, pembuatan kebijakan pendukung dan zonasi kawasan.
Belajar dari konflik yang terjadi di masa lalu, zonasi ke depan hendaknya memberikan porsi lebih pada aspek dimensi manusia. Hal ini sebagai tindakan antisipasi atas berbagai konflik yang bersifat laten. Aspek ini menyasar tiga hal yaitu pengakuan, representasi dan distribusi. Pengakuan bermakna mempertimbangkan aspek sosial budaya yang berlaku di masyarakat dan menggunakannya secara mendalam pada penentuan tiap-tiap zonasi.
Representasi berarti memberi ruang politik bagi berbagai komponen masyarakat dalam setiap fase perencanaan khususnya kelompok-kelompok marginal. Masalah ketimpangan pengetahuan dapat diatasi melalui komunikasi yang tulus dan berulang. Bahkan komunikasi seperti ini harus terbangun jauh dari waktu melakukan zonasi kawasan untuk membangun rasa saling percaya. Selanjutnya terkait distribusi adalah mengatur keadilan manfaat dari wilayah pesisir dan laut. Bahkan keadilan ini harus melintasi waktu mengingat adanya hak generasi mendatang untuk menikmati manfaatnya. Bersama dengan masyarakat, BTNKJ perlu merumuskan aturan main agar pemanfaatan sumber daya tidak dikuasai hanya oleh orang-orang bermodal sehingga privatisasi ruang pesisir dapat dikendalikan.
Melalui tiga hal di atas, harapannya zonasi menjadi solusi konflik bukan sumber konflik sebagaimana selama ini terjadi. Zonasi menjadi bentuk pengendalian ruang yang dinginkan bersama berdasarkan tujuan yang disepakati. Mereka tidak hanya akan mematuhi zonasi yang dihasilkan, namun terlibat aktif untuk menjaganya. Pada akhirnya, zonasi dan aturan main yang melekat memberi masyarakat harapan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik.***

Pendidikan Tak Henti Meski Pandemi

 Adi Indrayanto, Ph.D.
Adi Indrayanto, Ph.D.
Pandemi COVID-19 benar-benar memengaruhi dan mengubah setiap lini kehidupan. Sektor pendidikan juga terdampak. Masalahnya ada di daerah pelosok atau pedalaman yang minim peralatan dan materi digital, atau bahkan sama sekali tidak ada jaringan internet. Memastikan keberlangsungan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia selama pandemi COVID-19 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pendidikan bermutu (SDG 4) serta kota dan komunitas yang berkelanjutan (SDG 11).
DARI semua jenjang pendidikan, mulai usia dini hingga perguruan tinggi, harus mengubah pola pembelajaran tatap muka menjadi dalam jaringan (daring) alias online. Di dunia pendidikan Indonesia, kemudian dikenal istilah pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
Di kota-kota besar di Indonesia yang infrastrukturnya sudah terbangun dengan baik, bukan perkara sulit untuk mentransformasi pola pembelajaran tatap muka menjadi daring. Terlepas dari kemungkinan kendala ekonomi, perangkat digital penunjang PJJ seperti laptop dan tablet bisa didapatkan dengan mudah dan jaringan internet pun relatif sudah tersedia di seluruh pelosok kota.
Persoalan ini tentu saja membutuhkan solusi karena penduduk yang tinggal di pelosok daerah seperti itu pun tetap warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak
mendapatkan pendidikan memadai seperti orang kota. Ketika pembelajaran tatap muka tak bisa dilakukan akibat pandemi COVID-19, mereka pun tetap harus bisa mengakses pembelajaran jarak jauh.
Sebagai solusi, Ir. Adi Indrayanto, M.Sc., Ph.D. menggagas pembuatan tablet sebagai buku elektronik atau e-book yang belakangan diberi merek nonkomersial DiktiEdu. Gagasan dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) dari Kelompok Keahlian Elektronika ini mendapatkan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI yang pada tahun 2020 langsung memesan 5.000 unit untuk dibagikan kepada mahasiswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Teknologi Pelestari / 135
Dukungan Ditjen Dikti Kemendikbudristek RI terhadap pengembangan dan pembuatan tablet yang berisi modul pembelajaran ini sebagai bentuk kehadiran negara terhadap persoalan warganya, yang dalam hal ini mahasiswa di daerah 3T. Berdasarkan data dari pemerintah, tidak kurang dari 124.000 mahasiswa di daerah 3T mengalami kesulitan mengikuti perkuliahan jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 akibat keterbatasan akses telekomunikasi.
Menurut Adi, jika negara tidak hadir mengatasi persoalan di daerah 3T, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran undang-undang tentang kesamaan hak mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, jika tidak ada solusi, kesenjangan generasi antara kota dan daerah 3T bakal semakin menganga.
Bagi Adi dan ITB, pembuatan tablet yang berisi modul pembelajaran untuk mahasiswa di daerah 3T ini sebenarnya merupakan lanjutan dari pengembangan SmartEdu, perangkat evaluasi pembelajaran online berbasis Android Smartphone yang sudah dilakukan pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 datang. Perangkat ini dikembangkan Adi bersama koleganya Prof. Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D. (KK Teknologi Informasi), Dr. Beni Rio Hermanto, S.T., M.M. (KK Teknik Biomedika), dan Muhammad Iqbal Arsyad, S.T., M.T. (KK Elektronika).
Berbekal pengembangan SmartEdu, ketika pandemi COVID19 datang, pembuatan tablet yang berisi modul perkuliahan jarak jauh untuk daerah 3T mulai dilakukan.
Ketika itu, pilihannya tablet karena ukuran layarnya lebih nyaman untuk kepentingan membaca e-book ketimbang laptop atau smartphone
Untuk menjamin kualitas, pembuatan tablet DiktiEdu melewati sejumlah tahapan yang prosesnya dilakukan dan diawasi secara ketat. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari proses penentuan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan, perancangan, penyiapan aplikasi prainstalasi, pembuatan aplikasi katalog, produksi tablet, pengujian dan sertifikasi, hingga packaging dan pengiriman.
Pembuatan tablet DiktiEdu dimulai dari penentuan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, batasan dan kondisi infrastruktur penggunaannya. Dari aspek kebutuhan, tablet ini akan digunakan sebagai e-book tanpa perlu akses internet, berisi modul pembelajaran program studi (prodi) tertentu untuk seluruh semester yang disimpan berupa file multimedia seperti video audio dan textbook berformat pdf.
Secara fungsional, tablet ini juga hanya akan digunakan untuk perangkat belajar, bukan bermain game dan tidak disediakan application stores secara otomatis. Selain itu, tablet ini akan digunakan dalam kondisi infrastruktur sangat minim seperti minimnya ketersediaan listrik dan akses internet.
Selanjutnya, pembuatan tablet DiktiEdu memasuki tahapan perancangan. Dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, spesifikasi teknis yang dipilih adalah display 8 inci agar mudah digenggam, tetapi tetap mudah dibaca dengan
resolusi 800x1200, prosesor high performance untuk multimedia dan low power agar penggunaan baterai irit yaitu Quad-core Arm-Cortex A53 (MTK 8168), storage (penyimpan) yang cukup besar untuk menampung seluruh bahan mata pelajaran sebuah prodi (128 GB), memori kerja (RAM) minimal cukup untuk membaca modul pembelajaran (2 GB), konektivitas minimum karena akan digunakan di daerah yang tidak memiliki akses internet atau akses internet sangat terbatas Wifi (2.5GHz & 5GHz), sistem operasi open source (Android 10) serta tanpa GMS.
Sementara, spesifikasi aplikasi terdiri dari pembaca modul pembelajaran multimedia yang dapat diakses tanpa jaringan internet. Prodi berbeda dengan mengubah setup configuration file atau opsi, terdapat word processing, spreadsheet, fitur browsing jika mendapatkan akses internet dan fitur Android standar lainnya.
Dalam proses perancangan juga didesain identitas Dikti pada boot splash tablet dan etnik Indonesia pada giftbox. Selain itu, ditetapkan dan didesain juga merek nonkomersial yaitu DiktiEdu.
Setelah perancangan rampung, pembuatan tablet DiktiEdu dilanjutkan ke penyiapan aplikasi prainstalasi. Selain aplikasi standar dari Android OS, ada beberapa aplikasi untuk mendukung pembelajaran yang diprainstalasi pada atlet. Aplikasi pendukung tersebut adalah Microsoft Office, Calculator N+ - Math Solver – CAS Calculator, Video Transcoder, WavePad Audio Editor Free, VLC for Android, katalog, Amaze dan MuPDF Viewer.
Proses selanjutnya adalah penyiapan modul pembelajaran. Sesuai rencana, terdapat 6 prodi modul pembelajaran dari berbagai perguruan tinggi yang akan diprainstalasi pada tablet DiktiEdu. Penyusunannya mengikuti standar target mutu minimum masing-masing 1 file salindia (PDF), video ajar (MP4), kuis (PDF) dan pembahasan kuis (PDF ber-password), serta ukuran file tiap modul sebesar 70 MB. Kemudian data modul pembelajaran 6 prodi sebesar 72,3 GB prainstalasi pada tablet DiktiEdu. Sedangkan total data yang tersimpan pada tablet, termasuk aplikasi sebesar 88 GB.
Teknologi Pelestari / 137
Spesifikasi aplikasi terdiri dari pembaca modul pembelajaran multimedia yang dapat diakses tanpa jaringan internet.

























Tahapan selanjutnya adalah pembuatan aplikasi katalog. Ini merupakan aplikasi pembaca modul pembelajaran DiktiEdu. Aplikasi ini dibuat khusus untuk kemudahan mengakses modul pembelajaran masing-masing prodi. Setelah pemilihan komponen sesuai spesifikasi detail tablet DiktiEdu, proses dilanjutkan ke tahapan produksi, pengujian, sertifikasi, pengemasan, pengriman dan pengujian akhir sebelum didistribusikan kepada para mahasiswa di daerah 3T dengan status pinjaman.





Sebagai catatan, dengan pertimbangan praktis, seluruh proses perakitan tablet DiktiEdu dilakukan di Tiongkok. Menurut Adi, hal ini dilakukan bukan karena Indonesia tidak bisa melakukannya, melainkan semata pertimbangan praktis dan ekonomis. Jika dilakukan di Indonesia, di tengah berbagai pembatasan akibat pandemi COVID-19, perakitan akan berlangsung lama, berbiaya tinggi, dan membutuhkan effort lebih. Berdasarkan data dari Kemendikbudristek, tablet DiktiEdu buatan ITB yang berisi 300 modul elektronik perkuliahan dari 5 prodi ini sudah didistribusikan kepada mahasiswa kurang mampu di daerah 3T yang tak terjangkau internet.***









Berlanjut ke Laptop Merah Putih
SEBANYAK 5.000 unit tablet DiktiEdu sudah didistribusikan kepada para mahasiswa kurang mampu yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Dalam evaluasi programnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menilai, proyek pengembangan tablet DiktiEdu oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) berhasil dilakukan. Keberhasilan ITB mengembangkan tablet DiktiEdu yang berisi modul elektronik pembelajaran dari 5-6 program studi (prodi) tersebut menginspirasi Ditjen Dikti Kemendikbudristek untuk melanjutkannya ke proyek pengadaan laptop Merah Putih buatan anak bangsa. Apalagi, pada pertengahan tahun 2021 tersebut, pandemi COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda mereda
sehingga pola pembelajaran jarak jauh masih harus dilanjutkan dengan dukungan perangkat digital yang lebih memadai. Berbeda dengan tablet DiktiEdu, laptop Merah Putih ini rencananya dikomersialisasi dengan harga jual di kisaran Rp5 juta sampai Rp7,5 juta.
Untuk mengerjakan proyek pengadaan laptop Merah Putih yang pada tahap awal direncanakan sebanyak 10.000 unit, Kemendikbudristek membentuk konsorsium perguruan tinggi yang terdiri atas ITB, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia, dan Telkom University. Setiap perguruan tinggi memiliki 5 koordinator yang akan mengelola kegiatan pengembangan untuk bagian-bagian berbeda dari sistem laptop tersebut, dari mulai platform hardware, sistem operasi, software aplikasi, perangkat peripherals, hingga komponen.
Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) dari Kelompok Keahlian Elektronika, Ir. Adi Indrayanto, M.Sc., Ph.D., menjelaskan, program pengadaan laptop Merah Putih ini sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2021. Sebagai langkah awal, ketiga perwakilan perguruan tinggi mengadakan pertemuan daring dengan Ditjen Dikti Kemendikbudristek, Kementerian Perindustrian, dan Qualcomm untuk membahas perencanaan program pengembangan laptop Merah Putih ini. Adi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa untuk tahun 2021, konsorsium fokus pada pematangan perencanaan laptop Merah Putih. Baru pada tahun 2022, konsorsium bisa fokus pada pelaksanaan produksi laptop Merah Putih, termasuk lulus pengujian elektronis dan fi sik dengan harapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dapat bergerak meningkat ke hulu.
Spesifikasi laptop disesuaikan dengan kebutuhan proses dan level pendidikan. Menurut Adi, spesifikasi produk bisa jadi lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan inovasi perguruan tinggi masing-masing. Sementara, komponen produk tetap berasal dari mancanegara. Menurut Adi, hal itu karena tidak ada produk elektronika yang semua komponennya dibuat oleh sebuah negara. Menurutnya, TKDN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan industri dalam negeri. Menurut Adi, hal terpenting dari program ini adalah meningkatnya kompetensi industri dalam negeri dalam memproduksi perangkat digital dan membuka lapangan kerja di bidang rekayasa produk digital. ***

Menangkap Jejak Visual

 Dr. Fadhil Hidayat
Dr. Fadhil Hidayat
Sariwangi merupakan sebuah desa di Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kendati secara administratif termasuk kawasan perdesaan, karakteristik Sariwangi sudah menyerupai wilayah perkotaan. Maklum, selain berada di jalur pelintasan alternatif yang menghubungkan Kota Bandung dan Cimahi serta ke Lembang, Desa Sariwangi berdekatan dengan kawasan wisata bunga andalan KBB di sepanjang Jalan Cihideung. Pendekatan cerdas dalam membangun wilayah secara integrasi lewat kolaborasi dengan masyarakat merupakan perwujudan tujuan kota dan komunitas berkelanjutan (SDG 11) dan kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17).
TIDAK mengherankan jika Desa Sariwangi mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk pertumbuhan penduduknya. Hal itu dibuktikan dengan semakin luasnya alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan serta permukiman, termasuk untuk warga yang bekerja di perkotaan.
Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan kawasan yang semakin pesat, permasalahan yang muncul di Desa Sariwangi pun kian kompleks. Dari mulai kemacetan, pencurian, kebakaran akibat kelalaian warga, perkelahian, kejahatan jalanan hingga premanisme, mulai terjadi dan meresahkan masyarakat setempat. Untuk mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di Desa Sariwangi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM ITB) melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) menawarkan konsep Smart X. Konsep ini merupakan pendekatan cerdas dalam membangun wilayah secara terintegrasi untuk mengatasi permasalahan yang semakin bertambah kompleks seiring dengan perkembangan zaman.
Dalam proses menuju Smart X muncul pertanyaanpertanyaan seperti bagaimana proses ini dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan menjadi tangguh, komponen apa dan harus bagaimana melakukan implementasi Smart X, apakah konsep ini telah diterapkan dengan baik, di mana harus memulai proses transformasi menuju Smart X, proses apa yang harus diubah, dan bagaimana melakukan proses perubahan.
Dalam konteks yang lebih umum, pertanyaan yang dicuatkan antara lain siapa saja yang terlibat dalam pengembangan Smart X, serta bagaimana peranan berbagai pihak serta masyarakat dalam merancang dan merencanakan wilayah dan sektor yang cerdas.
Dalam praktiknya, Smart X bukan hanya tentang smart city, tetapi bisa dalam lingkup lain seperti provinsi, kecamatan, desa atau kelahiran hingga wilayah-wilayah cerdas yang lebih kecil. Jika semua wilayah, mulai dari provinsi, kota/kabupaten, hingga daerah terkecil seperti kecamatan, desa, dan bahkan RT/RW dapat berkolaborasi dan bergerak bersama, negara cerdas bisa terwujud.
Bukan hanya wilayah, konsep ini bisa dilakukan untuk berbagai isu di setiap wilayah atau sektor tertentu seperti mobilitas, keselamatan dan keamanan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain.
Kecerdasan ditandai oleh konektivitas, integrasi dan keberlanjutan. Karakteristik ini memungkinkan konsep Smart X menjadi perkembangan berikutnya untuk upaya pengembangan wilayah yang menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan, sensor, teknologi seluler, dan analisis data besar.
Oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) yang dipimpin Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. dari Kelompok Keahlian Teknologi Informasi, Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika (STEI) ITB, konsep Smart X coba dikembangkan di Desa Sariwangi.
Pertimbangannya, meskipun permasalahan di desa tersebut semakin kompleks, upaya-upaya smartization, terutama smart safe and secure, belum diinisiasi dengan baik.
Dalam pelaksanaannya dalam rentang waktu, 3 Februari hingga 15 Desember 2020, anggota tim yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertajuk “Implementasi dan Kajian Berbasis Artificial Intelligence, Big Data, dan Internet of Things untuk Mewujudkan Desa Cerdas dan Gagas” ini adalah I Gusti Bagus Bagaskara Nugraha, S.T., M.T., Ph.D dengan bidang keahlian image processing dan video compression, serta Dr. Fetty Fitriyanti Lubis, S.T., M.T. dengan bidang keahlian data science dan data engineering
Ketiga dosen STEI ITB ini dibantu oleh asisten peneliti/mahasiswa dari PIKKC yaitu Iqbal Ahmad Dahlan S.T., M.T. (artificial intelligence, IoT). Kendati COVID-19 sedang mewabah dengan berbagai kebijakan pembatasan kegiatan sosial, pengembangan platform smart safe and secure di Desa Sariwangi bisa tetap berjalan. Kegiatan difokuskan di wilayah RT 02 RW 16. Pemilihan kawasan ini karena sebagian besar masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang tinggi pada teknologi. Dengan begitu, kawasan ini bisa dijadikan kawasan percontohan untuk wilayah-wilayah lainnya.
Setelah beberapa kali melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga, tim pengabdian kepada masyarakat mulai melakukan pemasangan infrastruktur jaringan RT/RW untuk mendukung kegiatan. Infrastruktur pertama yang dipasang adalah sistem jaringan (backbone) di satu titik menggunakan sebuah antena pemancar sektoral 120o yang dipasangkan pada ketinggian 15 meter. Fungsinya untuk melayani kebutuhan jaringan hingga jangkauan lebih dari 10 kilometer. Selain itu, sistem jaringan pada satu titik menggunakan 2 antena pemancar 60o juga dipasang di menara Masjid AlAniah dengan ketinggian 15 meter. Kemudian, sistem penerima sinyal jarak jauh untuk menangkap sinyal di udara yang berasal dari sistem jaringan dipasang di empat titik.
Selanjutnya, Smart CCTV dan video analytics dipasang di beberapa titik. Kamera pengawas ini dipasang untuk mendeteksi kerumunan orang, kendaraan, perilaku mencurigakan, dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan.
Setelah sistem jaringan, Smart CCTV, dan video analitycs terpasang, tim pengabdian masyarakat mulai mengimplementasikan platform safe and secure yang berpusat di Masjid Al-Aniah. Beberapa hal yang dilakukan adalah instalasi NVR dengan HDD untuk merekam video dari CCTV, NAS 16 TB untuk menyimpan file dan aplikasi dan sistem AI yang menggunakan Jetson TX2. Kegiatan selanjutnya adalah pemasangan access point dengan sistem mesh sehingga dapat terhubung langsung secara seamless. Kemudian, running system smart safe and secure pada Jetson TX2 untuk mendeteksi kejadian-kejadian yang tertangkap di CCTV. Pada saat aktivitas ini dilakukan, secara tidak sengaja sistem menangkap kejadian kebakaran rumah warga. Selanjutnya, sistem smart safe and secure diinstalasi pada dua unit telepon seluler yang dipegang petugas keamanan atau sekuriti.
Kegiatan terakhir yang dilakukan sebelum aktivasi sistem smart safe and secure adalah pembangunan pos pemantau keamanan berbasis teknologi.
Setelah beberapa kali uji coba, sistem smart safe and secure ini akhir bisa diimplementasikan. Setelah diaktivasi, beberapa peristiwa seperti warga kemalingan sepeda, gerak-gerik mencurigakan, dan notifikasi pelaku kejahatan bisa terdeteksi oleh sistem ini.
Dari kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat ITB mengharapkan sejumlah manfaat antara lain adanya sistem keamanan berbasis CCTV yang terintegrasi di dalam satu RT/RW, sistem jaringan RT/RW dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keekonomian warga dan membantu pihak keamanan. Selain itu, nantinya sistem ini diharapkan dapat dikoneksikan ke internet dan dapat dikembangkan untuk sistem IoT. Berdasarkan testimoni yang dihimpun tim pengabdian kepada masyarakat, warga pun mengaku mendapatkan manfaat dan merasa terbantu dengan implementasi Smart CCTV tersebut. Ketua RT 02/RW 16 menyampaikan, Smart CCTV sangat bermanfaat, khususnya untuk mendukung dan menunjang kinerja petugas keamanan di wilayahnya. Ia bahkan berharap, daya jangkau dan sistem AI-nya bisa terus dikembangkan agar berfungsi sebagai peringatan dini yang bersifat preventif.
Bagi tim pengabdian kepada masyarakat ITB, harapan warga Desa Sariwangi itu tentu saja menjadi motivasi untuk pengembangan sistem smart safe and secure ini di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sariwangi memang tidak berhenti sampai dengan instalasi Smart CCTV. Apalagi, pada kenyataannya masih ada sejumlah permasalahan yang ditemukan. Salah satunya pada switch di sistem jaringan yang mengalami bottle neck akibat kerusakan sehingga alat tersebut harus diganti pada tahap berikutnya. Selain itu, tim pengabdian masyarakat juga merencanakan penambahan jumlah kamera pengawas, akses poin, pemasangan sensor lingkungan, bridging jaringan ke kantor Desa Sariwangi, inisiasi untuk terkoneksi ke jaringan internet, serta tata kelola sistem yang sustainable dan dikelola warga secara swadaya.***
Sejumlah manfaat adanya sistem keamanan berbasis CCTV yang terintegrasi di dalam satu RT/RW, dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keekonomian warga dan membantu pihak keamanan.
Masyarakat Guyub dan Antusias
KENDATI dilaksanakan pada saat pandemi COVID-19, warga RT 02/RW 16 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap guyub dan antusias terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat Institut Teknologi Bandung (ITB). Kondisi tersebut tentu saja sangat melegakan buat tim pengabdian kepada masyarakat yang dipimpin Dr. Fadhil Hidayat, S.Kom., M.T. dari Kelompok Keahlian Teknologi Informasi Sekolah Tinggi Elektro dan Informatika (STEI) ITB ini.
Menurut Fadhil, guyub dan antusiasnya warga membuat timnya bisa dengan cepat memberikan edukasi, pemahaman, dan bahkan mengeksekusi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah direncanakan. Dengan keguyubannya, warga Desa Sariwangi juga antusias ketika diminta bantuan untuk proses instalasi Smart CCTV yang akan dikembangkan di wilayah tersebut.
Kemudahan di tengah lumayan ketatnya pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 tersebut, menurut Fadhil, tidak terlepas dari tingkat pendidikan warga Desa Sariwangi. Meski berada di kawasan perdesaan, warga Desa Sariwangi sebagian besar mengenyam pendidikan yang cukup tinggi
dan terlibat dalam pergaulan kota sehingga proses edukasi dan pemahaman terhadap program tidak membutuhkan waktu terlalu lama.
Cepatnya pemahaman warga itu memudahkan pencarian solusi ketika tim pengabdian kepada masyarakat menghadapi masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Fadhil mencontohkan, ketika membutuhkan listrik untuk pemasangan CCTV, warga yang tinggal di rumah terdekat bersedia mengalokasikan daya listriknya. Begitu juga ketika tim pemberdayaan kepada masyarakat membutuhkan tenaga untuk instalasi jaringan dan pekerjaan lainnya secara gotong royong. Fadhil mengatakan, besarnya peran masyarakat sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program pengabdian, termasuk dalam pengembangan Smart CCTV dalam sistem smart safe and secure ini. Tingginya peran serta masyarakat, menjamin keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat setelah kegiatan berakhir. Ia mencontohkan, ketika kegiatan instalasi dan aktivasi Smart CCTV berakhir, pengelolaan dan monitoring berbagai peralatan bisa dilakukan oleh masyarakat, termasuk admin yang mengawasi Smart CCTV.***
Teknologi Pelestari / 151

Bagian 3 Mencipta Kesejahteraan
Rekayasa teknologi memungkinkan masyarakat menikmati siklus penuh produktivitas dan bahkan berpotensi mengembangkan produk energi baru dari proses budi daya pertanian, peternakan dan perikanan, serta optimasi pola budi daya dari hulu ke hilir secara sirkular.


Harta Karun Pisang Bali

 Prof. Ketut Wikantika, Ph.D.
Prof. Ketut Wikantika, Ph.D.
Hampir setiap hari masyarakat Bali membutuhkan pisang, baik untuk peribadatan maupun konsumsi. Kebutuhan pisang di Bali mencapai 300 ribu ton per tahun dengan nilai ekonomi hingga Rp3 triliun. Pemberdayaan masyarakat melalui program Banana Smart Village dengan memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan ITB
merupakan perwujudan tujuan SDGs khususnya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) serta infrastruktur, industri, dan inovasi (SDG 9).
BALI merupakan pasar pisang yang potensial. Survei menunjukkan, tingkat konsumsi pisang masyarakat Bali merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sayangnya, Bali belum bisa mencukupi kebutuhan pisangnya sendiri. Sebagian besar masih harus didatangkan dari Jawa. Padahal, Bali mempunyai potensi yang besar untuk membudidayakan pisang. Lahan masih tersedia, masyarakat pun sudah tidak asing dengan bercocok tanam. Semua potensi itu diberdayakan, ditunjang dengan teknologi informasi yang mumpuni, maka lahirlah Banana Smart Village (BSV).
Para ilmuwan ITB dari berbagai bidang ilmu dan kepakaran bergerak bersama membidani lahirnya BVS. Bermula dari perjalanan Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng., Ph.D. dari Kelompok Keahlian Inderaja dan Sains Informasi Geografis (InSIG) berjalan menyusuri Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali pada 2018. Desa Bukti berada di dekat laut utara Bali. Lokasinya ini membuat desa ini hidup dari pariwisata.
Akan tetapi, kondisi Desa Bukti sendiri sebenarnya kering. Penduduknya banyak yang hidup kekurangan. Sebanyak 20 persen penduduknya tidak memiliki pekerjaan tetap. Prof. Ketut kemudian menggandeng ilmuwan ITB lainnya dari berbagai latar disiplin keilmuan untuk bersama-sama mengabdikan ilmunya di Desa Bukti dalam membangun Banana Smart Village. Pisang dipilih karena kebutuhannya sangat tinggi di Bali. Jika dikembangkan dengan baik, perkebunan pisang bisa memberi dampak ekonomi yang tinggi bagi masyarakat.
Selain itu, kajian tentang tanaman pisang sudah banyak dikembangkan oleh ITB. Prof. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D. dari Kelompok Keahlian Genetika dan Bioteknologi Molekular, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati merupakan peneliti yang mendapat julukan sebagai “ratu pisang”. Ia turut ambil bagian dalam tim ini untuk mengembangkan BSV yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Bali dengan memanfaatkan teknologi yang telah dikembangkan ITB.
Sejak mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia telah berkomitmen untuk membangun bangsa ini dari desa. Desa tidak boleh lagi menjadi tempat tinggal bagi para lanjut usia, sedangkan anak mudanya merantau ke kota demi penghasilan yang lebih baik. Itu sebabnya desa harus mandiri, mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, menyediakan pendidikan yang baik, kondisi sosial yang nyaman, lingkungan yang terjaga, serta ekonomi yang bersaing. Dengan begitu, masyarakat desa tidak perlu meninggalkan kampung halamannya agar bisa sejahtera. Tujuan ini yang ingin dicapai melalui BSV di Desa Bukti.
Program ini dimulai pada 2019 dengan menanam 700 pisang memanfaatkan lahan-lahan yang tidak tergarap. Sekarang sudah ada 6.000 pohon pisang yang tertanam. Luas areanya mencapai 4 ha lebih. Targetnya Desa Bukti bisa memiliki 50-60 ha lahan dari tanah desa, tanah adat, dan milik masyarakat bisa ditanami pisang.
Keberhasilan penanaman pisang di Desa Bukti ini tidak lepas dari respons positif masyarakatnya. Mereka bersedia menerima informasi dan berkolaborasi dengan para ilmuwan ITB. Mereka kini bisa menikmati hasilnya. Mereka bisa memenuhi kebutuhan pisang masyarakat di Desa Bukti sendiri, juga bagi desa-desa lain di sekitarnya. Di hari-hari besar agama Hindu, permintaan pisang Desa Bukti meningkat pesat dengan harga yang tinggi. Pada waktu istimewa itu, satu buah pisang bisa dihargai Rp2.000. Hal ini membuat masyarakat Desa Bukti semakin gigih mengembangkan pisang.
Perbedaan utama Desa Bukti dengan daerah penghasil pisang lainnya di Indonesia ialah pemanfaatan teknologi yang membuat desa ini memiliki kecerdasan (smart). Selain melakukan pelatihan dan membangun masyarakatnya, penelitian dan pengembangan menjadi fondasi dalam mengembangkan BSV.
Ada dua kegiatan utama dari riset dan pengembangan BSV ini, yaitu database development dan industrial network development. Data, baik kualitatif maupun kuantitatif, akan menjadi acuan kerja. Sementara jaringan industri dibutuhkan untuk kepentingan pemasaran juga berbagai upaya untuk menghasilkan pisang dengan kualitas yang semakin baik.
Basis data yang dibangun ialah geospatial database. Data geospasial berhubungan dengan lokasi dan ruang yang bisa menjadi dasar untuk berbagai pengembangan teknologi. Prof. Ketut bersama timnya membuat pemotretan udara Desa Bukti dengan menggunakan drone. Peta udara itu kemudian dijadikan bahan untuk menyusun peta yang bisa menunjukkan dengan pasti area permukiman, sawah, perkebunan, pantai, dan objek geospasial lain di Desa Bukti yang luasnya mencapai 650 hektare.
Data geospasial itu sangat diperlukan untuk pengembangan Desa Bukti. Pemerintah juga masyarakat bisa melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur berdasarkan kebutuhan yang bisa dianalisis dari data geospasial tadi. Pemerintah bisa mengetahui daerah mana yang belum memiliki sekolah, jaringan jalan, saluran irigasi, atau lainnya.
Foto udara bisa mengarakterisasi aspek sosial dari sebuah wilayah, dalam hal ini Desa Bukti. Sifat geografisnya bisa diketahui, area mana yang termasuk dataran rendah dan mana yang termasuk dataran tinggi. Dengan begitu, bisa
diketahui jenis tanaman apa yang cocok dibudi daya di sana. Apakah ada tanaman lain yang cocok dikembangkan di Desa Bukti selain pisang? Adakah vegetasi khas yang dimiliki atau mungkin ada fauna yang harus dilindungi? Semua bisa dijawab dengan memanfaatkan citra udara. Lebih lanjut, foto udara juga bisa digunakan untuk menjaga kualitas tanaman pisang yang sudah tertanam.
Pengindraan jauh dimanfaatkan untuk mencermati penyakit pisang yang sedang menyebar. Menggunakan analisis spektral, bisa dihitung energi pantulan dari pisang yang terkena penyakit sehingga bisa diperkirakan sampai mana penyakit tersebut telah menyebar.
Pengindraan jauh memungkinkan pemantauan terhadap pohon pisang bisa dilakukan lebih cepat. Dari database analisis pohon yang sehat dan sakit, profil setiap pohon bisa dilakukan dengan cepat. Dengan memasang sensor khusus pada drone, bisa terpantau mana pohon yang sehat dan mana yang sakit.
Geospatial database yang sudah dibangun sejak 2019 terus diperbarui sehingga terlihat perkembangan Desa Bukti dari hari ke hari. Tim Prof. Ketut membuat dasbor yang digunakan untuk memperbarui data-data spasial di Desa Bukti. Penambahan, perubahan, juga pengurangan bangunan bisa dilaporkan dan diperbarui datanya lewat dasbor tersebut. Para peneliti ini melatih anak muda yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan teknologi agar bisa mengakses dan melakukan pembaruan di dasbor yang telah dibuat.
Dasbor ini bisa dipakai untuk fungsi yang lebih luas sekaligus spesifik, yaitu terkait produksi pisang. Dasbor ini memiliki fitur yang bisa menunjukkan di mana saja terdapat kebun pisang, bagaimana persebarannya. Tidak hanya data pisang di Desa Bukti saja yang tercantum, pisang di daerah lain juga tersedia. Pengguna bisa menambahkan informasi yang ia ketahui sehingga memperkaya database. Teknologi ini yang menjadi dasar pembuatan Bali Banana Dashboard. Sistem ini menyediakan informasi statistik serta informasi spasial distribusi pisang. Sistem ini dirancang agar mudah diakses dan interaktif.
Database yang sudah terbangun memungkinkan dilakukan berbagai pengembangan. Salah satu pengembangan yang dilakukan ialah pembuatan aplikasi Antar Antar Pisang. Aplikasi ini merupakan e-commerce dengan pisang sebagai komoditasnya. Sistemnya lebih sederhana ketimbang e-commerce yang selama ini sudah dikenal luas masyarakat. Meski begitu, aplikasi ini bisa menjadi saluran bagi masyarakat memasarkan pisangnya. Konsumen juga mempunyai saluran untuk mendapatkan produk pisang dengan spesifikasi dan harga yang sesuai dengan keinginannya.
Alih teknologi merupakan salah satu bagian yang tak boleh ditinggal saat memperkenalkan teknologi baru kepada masyarakat. Agar mereka bisa terus memanfaatkannya, tanpa bergantung pada pengembang (peneliti) yang tidak berada di lokasi seterusnya. Pelatihan penguasaan teknologi ini dilakukan secara reguler di Desa Bukti. Perkembangan teknologi tak pernah berhenti sehingga pelatihan tidak bisa dilakukan hanya sesekali.
Kesiapan sumber daya manusia juga sistem yang sudah terbangun menjadi modal besar untuk mengembangkan program ini. Pada masa yang akan datang, tidak hanya pisang yang bisa dibeli di Antar Antar Pisang. Produkproduk turunan pisang lainnya bisa didapatkan juga, seperti misalnya tepung pisang yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga jual yang tinggi dan permintaan yang tinggi pula. Produk tanaman lain juga bisa turut dipasarkan. Pisang kemudian menjadi ikon Desa Bukti, tetapi sesungguhnya produk yang dihasilkan bisa lebih banyak.
BSV di Desa Bukti menunjukkan bahwa ilmu dan teknologi canggih akan lebih berarti jika dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sinergi antara masyarakat dan para ilmuwan ini telah mengantarkan Desa Bukti sebagai desa terbaik tingkat nasional.***
BSV di Desa Bukti menunjukkan bahwa ilmu dan teknologi canggih akan lebih berarti jika dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pendekatan Multidisiplin Mulai Bibit hingga Pascapanen
PENGEMBANGAN Banana Smart Village (BSV) di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali menggunakan pendekatan mulitidisiplin. Dengan kapakaran yang komplet, budi daya pisang bisa dilakukan terintegrasi, mulai pembibitan hingga pascapanen. Semua bagian pohon pisang termanfaatkan, tidak ada yang terbuang sia-sia. Pisang merupakan tanaman ekonomis, seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan. Sifat pisang ini yang membuat program pengembangan BSV bisa berkelanjutan. Menanam pisang bukan hal yang aneh bagi negara tropis seperti Indonesia. Meski pohonnya mudah ditemukan, akan tetapi menghasilkan bibit pisang yang unggul, tidak semua orang bisa. Semula pisang yang ditanam di Desa Bukti berasal dari bibit yang dibeli dengan harga sekitar Rp10.000-Rp15.000. Jika bibit ini bisa diproduksi sendiri, biaya bisa dihemat. Bahkan, bibit pisang bisa memberi keuntungan ekonomi tersendiri mengingat belum banyak yang bisa memasok bibit pisang. Laboratorium kultur jaringan bermanfaat untuk menjaga kualitas pisang. Hasil panennya pun jadi lebih terjaga. Inilah yang mendasari pengembangan kultur jaringan di BSV yang dikoordinasi oleh Dr. Rizkita Rachmi Esyanti .
Saat ini Desa Bukti sudah memiliki laboratorium kultur jaringan. Penelitian terus dikembangkan untuk menghasilkan bibit pisang yang tahan penyakit dan menghasilkan buah yang berkualitas tinggi. Fasilitas dan perlengkapan laboratorium terus dilakukan.
Perkara bibit ini bukan menjadi urusan ilmuwan atau peneliti semata. Masyarakat Desa Bukti sebagai aktor utama juga harus terlibat. Para peneliti melatih masyarakat agar menguasai teknik kultur jaringan untuk menghasilkan bibit sendiri. Beberapa warga Desa Bukti ada yang dikirim ke SITH ITB untuk mempelajari kultur jaringan ini.
Jika berhasil mengembangkan bibit sendiri dan menghasilkan 1.000-2.000 bibit, kultur jaringan bisa menjadi penggerak roda perekonomian tersendiri.
Bibit yang sudah ditanam dipupuk dengan menggunakan Masaro buatan Dr. Zainal Abidin dari Fakultas Teknik Industri ITB. Pupuk ini berasal dari pengolahan sampah. Hasilnya menggembirakan. Melihat hasilnya yang memuaskan, mendorong masyarakat untuk mulai menanam pisang. Apa yang dilakukan para peneliti di Desa Bukti berhasil ditransformasikan ke masyarakat.
Tak lagi hanya buahnya
Pisang selama hidup hanya berbuah sekali. Setelah itu, pohonnya akan mati hingga tumbuh tunas baru. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, batang pohon pisang bisa berakhir menjadi limbah. Budi daya pisang di Desa Bukti berupaya untuk memanfaatkan semua bagian pohon pisang sehingga tidak menyisakan sampah (zero waste).
Pelepah pisang bisa digunakan untuk kerajinan tangan, selain bisa menjadi bahan membuat kertas yang estetik. Pelepah pisang juga bisa digunakan untuk pembuatan tekstil, terutama varian pisang seperti pisang ambon yang paling bagus dijadikan serat tekstil. Saat ini juga tengah dikembangkan alat supaya produk yang dihasilkan bisa masuk kategori food grade dan tidak mencemari lingkungan. Pelatihan ke masyarakat juga sudah dimulai.
Batang pohon pisang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Setiap batang bisa dijual dengan harga Rp50.000. Masyarakat setempat banyak yang memelihara sapi. Batang pohon bisa dimanfaatkan untuk memberi akan ternaknya. Selain batang, bungkil pisang juga bisa dimanfaatkan
sebagai pakan ternak. Bungkil pisang yang dicampur dengan prebiotik terbukti mampu meningkatkan berat sapi sekitar 0,8-1,2 kg setiap hari.
Buahnya menjadi produk utama. Pisang di Desa Bukti berukuran besar. Bisa dijual dalam bentuk buah atau bisa dikembangkan menjadi produk olahannya juga. Seperti keripik pisang, salai pisang, tepung pisang, dan sebagainya. Selain baik untuk diversifikasi produk, produkproduk olahan ini memiliki harga jual yang lebih tinggi. Sementara, daun pisang bisa dijual sebagai pembungkus nasi.
Nyaris tidak ada bagian pisang yang sia-sia sehingga budi daya pisang ini tidak menghasilkan limbah yang membebani lingkungan. Kolaborasi ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu membuat semua aspek bisa diantisipasi dan diintegrasikan.
Berbagai produk hasil perkebunan pisang ini bahkan bisa menjadi daya ungkit potensi wisata di Desa Bukti. Lokasinya yang dekat dengan pantai utara Bali menjadikan Desa Bukti sebagai kawasan wisata yang potensial sehingga mampu membuka jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keterlibatan ilmuwan-ilmuwan ITB ini membuat budi daya pisang disokong dengan riset dan penelitian yang mumpuni. Sebelumnya juga sempat dibentuk Bali International Research Center for Banana yang merupakan pusat penelitian gabungan antara ITB dan Universitas Udayana. Harapannya, penelitian tentang pisang bisa terus dikembangkan. Hasilnya bisa diaplikasikan ke Desa Bukti atau wilayah lain yang cocok untuk budi daya pisang. Secara teori, pisang bisa dibudidayakan di daerah dataran rendah dan tinggi. Pisang dari dataran tinggi cenderung lebih manis. Pisang dikenal dengan buah yang kaya nutrisi. Indonesia sendiri memiliki 500 jenis pisang. Jika potensi ini diberdayakan maksimal, Indonesia mestinya tidak akan pernah mengalami krisis pangan. Keberhasilan BSV di Desa Bukti menjadi pemantik upaya yang sama di desa-desa lain. Tim peneliti juga sebelumnya telah berkomunikasi dengan desa lain untuk melihat kemungkinan mengembangkan desa cerdas yang berbasis perkebunan pisang. Akan tetapi, tidak semua berhasil. Niat dan integritas masyarakat menjadi kunci gagal tidaknya ikhtiar ini.
Kerja-kerja para peneliti memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru, tidak akan berhasil tanpa kegigihan, semangat, dan niat baik masyarakat itu sendiri. Masyarakat fokus pada pengembangan desa yang berorientasi jangka panjang. Bukan semata-mata menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi kemudian hilang tak berbekas. Sinergi antara peneliti dan masyarakat inilah yang tidak mudah diduplikasi.***
Budi daya pisang di Desa Bukti berupaya untuk memanfaatkan semua bagian pohon pisang sehingga tidak menyisakan sampah (zero waste).

Bekal Es Para Nelayan

 Dr. Yuli Setyo Indartono
Dr. Yuli Setyo Indartono
Sektor perikanan memiliki peranan penting dalam pembangunan Indonesia. Dengan wilayah lautan mencapai 2/3 dari keseluruhan luas wilayah, potensi perikanan Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pengembangan sistem smart microgrid berbasis energi terbarukan dalam pengoperasian mesin pembuat es untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas ikan dari nelayan sejalan dengan tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8) serta energi bersih dan terjangkau (SDG 7).
MENURUT data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia mencatat pertumbuhan ekspor perikanan hingga 5,7% di tengah perlambatan ekonomi global akibat pandemi COVID-19 dan naik ke peringkat ke-8 negara eksportir produk perikanan global tahun 2020. Angka ini akan terus didorong mencapai target 2024 sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan hingga beberapa tahun ke depan. U ntuk mencapai target tersebut, pembangunan serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang bisnis perikanan perlu terus dikembangkan. Namun, kendalanya adalah mayoritas nelayan di Indonesia merupakan nelayan tradisional yang menggunakan kapal kecil (di bawah 30 gross tonnage) dengan teknologi yang masih rendah. Nelayan di daerah-daerah terpencil (remote area) kerap menghadapi kesulitan, terutama dalam memperoleh es balok sebagai media untuk mendinginkan ikan hasil tangkapan.
Tidak adanya akses terhadap es balok maupun cold storage sebagai sarana untuk menjaga kualitas ikan kerap membuat nelayan mengurungkan niat untuk berlayar atau tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Alhasil, nelayan terpaksa sering menjual hasil tangkapan ikan dengan harga murah. Sebenarnya, pemerintah telah memasukkan pembangunan integrated cold strorage sebagai salah satu proyek strategis nasional dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 untuk mengatasi permasalahan teknologi pengolahan ikan bagi nelayan.
KKP juga memprioritaskan enam jenis sarana dan prasarana teknologi pengolahan perikanan yang salah satunya adalah pembangunan pabrik es bagi nelayan.
Namun, upaya-upaya tersebut dirasa kurang optimal karena terkendala ketersediaan pasokan listrik. Hal inilah yang menjadi masalah utama bagi nelayan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) maupun daerah-daerah lain yang memiliki keterbatasan pasokan listrik yang tidak stabil. Teknologi Pelestari / 169
Hal serupa sangat dirasakan oleh masyarakat di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kecamatan Karimunjawa merupakan wilayah kepulauan yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Permasalahan utama nelayan di Karimunjawa adalah ketersediaan es balok untuk mengawetkan ikan selama melaut. Mereka harus pergi ke Jepara untuk membeli es dengan perahu yang menghabiskan bahan bakar solar sebanyak 80 liter.
Setiap kali melaut nelayan membutuhkan biaya bahan bakar sebanyak Rp560.000 untuk membeli es. Setibanya di Jepara, nelayan membeli es balok sebanyak 20-25 buah dengan harga es per buah adalah berkisar Rp25.000 sampai Rp50.000 untuk jangka waktu melaut sekitar satu minggu. Belum jika gelombang sedang tinggi, distribusi es balok akan sedikit terhambat. Padahal, nelayan itu seberapa jauh dia bisa melaut berdasarkan ketersediaan es balok karena kualitas ikan sangat dipengaruhi oleh proses pendinginan.
Untuk itu, tim Institut Teknologi Bandung (ITB) dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) mengembangkan sistem smart microgrid berbasis energi terbarukan untuk pengoperasian mesin pembuat es balok sebagai jawaban optimal untuk mengatasi permasalahan. Tim terdiri atas Dr. Eng. Yuli Setyo Indartono (ketua) bersama dengan Wildan Rahmawan Ruiss, B.Eng., Robertus Kristianto Sukoco, S.T., M.T., Mus fi rin, S.T., M.T. , Andhita Mustikaningtyas, S.T. , Aldrin, S.T., M.T. , dan Muhammad Azka, S.T.
Sejak tahun 2017, utilitas listrik dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) telah tersedia di Desa Karimunjawa dan Kemujan. Daya listrik umum untuk keperluan rumah tangga adalah 900 W. Namun, terkadang ada gangguan pada pembangkit listrik dan transmisi kabel yang membuat listrik padam. Padahal, pasokan listrik yang tidak stabil tidak cocok untuk pengoperasian terus-menerus dari mesin pembuat es. Teknologi ini diterapkan untuk membantu ketersediaan es balok bagi nelayan agar ikan hasil tangkapan kualitasnya terjaga. Selain itu, dapat memangkas biaya operasional nelayan yang selama ini dikeluarkan untuk pembelian es balok ke Jepara. Hal itu sejalan dengan kepentingan pemerintah untuk merealisasikan industri perikanan yang berkelanjutan. Pengutamaan sumber energi berbasis energi terbarukan pada sistem smart microgrid rancangan tim ITB menjadikan sistem ini lebih ramah lingkungan.
Tim menempatkan mesin pembuat es balok dengan teknologi smart microgrid berbasis energi terbarukan di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. Desa ini merupakan desa dengan jumlah nelayan terbanyak di wilayah tersebut. Pertimbangan Desa Kemujan, Karimunjawa sebagai tempat penerapan teknologi microgrid karena saat itu belum terlistriki dengan standar. Bahkan, saat tim merancang sistem smart microgrid, PLTD belum ada di sana. Sebelumnya, Pulau Seribu dan pulau-pulau terluarnya juga masuk pilihan untuk dijadikan subjek penerapan teknologi smartgrid. Namun, Pulau Seribu lebih dekat dengan wilayah DKI Jakarta dan telah tersambung listrik dengan pemasangan kabel listrik di bawah laut.
Apa itu microgrid?
Microgrid merupakan pembangkit energi yang terdistribusi dengan satu atau lebih sumber energi terbarukan, perangkat penyimpanan, beban, dan peralatan kontrol yang dapat bekerja secara mandiri (off grid) atau bersama grid (on grid). Sistem microgrid yang dirancang tim ITB mampu mengelola demand energi dari beberapa sumber energi yang sifatnya energi terbarukan dan juga tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan tersebut berasal dari pusat listrik tenaga surya (PLTS) menggunakan fotovoltaik (PV), dan generator berbahan bakar nabati (biofuel), sedangkan energi tidak terbarukannya, yaitu listrik PLN dari PLTD. Sumbersumber energi ini disatukan dalam satu sistem agar bisa saling melengkapi. Sistem microgrid bisa mengatur lalu lintas, input, storage, demand sumber pembangkit yang diperlukan. Sistem ini mengatur untuk perpindahan energi yang digunakan dari suplainya. Oleh karena itu, dinamakan smart microgrid. Pemakaian sumber energi yang diutamakan adalah dari sumber energi terbarukan, yaitu dari pembangkit listrik tenaga surya dengan panel surya dan generator berbahan minyak nabati. Pemakaian sumber energi dari PLN (PLTD) merupakan opsi terakhir.
Karena mesin pembuat es balok harus bekerja 24 jam, sedangkan PLTS memiliki keterbatasan waktu pemakaian, genset memiliki tingkat kebisingan yang mengganggu, dan PLN sering on/off, ditambahkan baterai sebagai penyimpan
energi. Pengaturan dan pengontrolan tersebut dilakukan oleh alat inverter yang dipasang di sistem. Sistem ini cocok digunakan untuk penerapan energi terbarukan yang didampingkan dengan kelistrikan yang ada. Jadi, bukan hanya bisa diterapkan di pulau-pulau terluar. Sistem ini bisa diterapkan untuk area perkotaan. Pada dasarnya, rumah dan gedung di perkotaan yang memasang rooftop fotovoltaik (PV) itu ada sistem kontrol (untuk mengatur suplai listrik dari PV dan/atau PLN) yang bisa dimasukkan ke grid. Begitu energi dari PV masuk, energi dari PLN akan ditekan. Kalau energi dari PV kurang, energi dari PLN yang masuk.
Fotovoltaik merupakan bagian penting dari microgrid karena memiliki masa pakai yang lama, kapasitas fleksibel, biaya pemasangan yang wajar, dan biaya perawatan yang rendah. Selain itu, banyak lagi tempat yang dihuni manusia memiliki penyinaran matahari yang cukup.
Rancangan sistem smart microgrid menggunakan panel surya berkapasitas 5 kWp, generator berbasis bahan bakar minyak nabati kapasitas 4 kW, bidirectional inverter kapasitas 5 kW, baterai 100 Ah/12 V berjumlah 20 buah, dan listrik PLN 1400 W.
Bahan bakar yang digunakan untuk generator yaitu biofuel, tetapi levelnya bukan biodiesel. Untuk membuat biodiesel diperlukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah dimurnikan yang menghasilkan pure plant oil (PPO). Tahapan selanjutnya yaitu transesterifikasi yang nantinya menghasilkan biodiesel.
Biodiesel tersebut jika dicampur dengan solar menjadi B20, B-30. Yang digunakan oleh tim sebagai bahan bakar untuk generator tidak sampai ke biodiesel, tetapi sampai ke tahap pure plant oil sehingga prosesnya lebih sederhana. Namun, karena pure plant oil sifatnya lebih kental, diperlukan pemanasan sebelum digunakan sebagai bahan bakar. Untuk keperluan tersebut, tim sedikit memodifikasi mesin dengan penambahan preheater. Preheater digunakan untuk memanaskan pure plant oil supaya kekentalannya (viskosotas) turun.
Sebagai bahan baku digunakan tanaman lokal biji nyamplung. Tim juga melakukan riset pembuatan minyak tumbuhan dari biji nyamplung tersebut. Sebenarnya di Karimunjawa berlimpah buah kelapa untuk dijadikan minyak nabati, tetapi konflik kepentingan dengan bahan makanan. Sementara, nyamplung merupakan tanaman bukan pangan (non-edible).
Mesin pembuat es balok dijalankan secara kontinu untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Supaya mesin tetap beroperasi, suplai energi harus terus tersedia. Sistem smart microgrid mengatur suplai energi listrik tersebut dengan berbagai skenario pemakaian energi.
Beban utama smart microgrid adalah mesin pembuat es, sedangkan pasokan listriknya berasal dari grid PLN, PV, dan generator atau mesin diesel berbasis biofuel. Karena biaya pengoperasian mesin relatif tinggi, utilitas dan PV akan memasok sebagian besar listrik yang dibutuhkan oleh mesin pembuat es.
Baterai yang digunakan pada smart microgrid adalah 12 V, 80 Ah, 20 buah, dengan total penyimpanan energi 19,2 kVAh. Karena pembuat es membutuhkan sekitar 2,4 kW, baterai dapat memasok listrik ke pembuat es hingga 4 jam (50% DOD). Mesin diesel yang digunakan dalam sistem ini adalah silinder tunggal, injeksi tidak langsung, tenaga 16 hp, kapasitas silinder 903 cm 3 , dan putaran 2.200 rpm. Pembangkit yang terhubung ke mesin satu fasa dengan kapasitas 5 kW, 220 C, 22,7 A, dan frekuensi 50Hz. Waktu transien mesin adalah 5-7 menit sebelum dapat dihubungkan ke inverter. Inverter mengatur komunikasi antara suplai dan permintaan listrik. Aturan yang ditetapkan untuk inverter adalah PV diprioritaskan untuk menangani beban. Jika daya dari PV lebih tinggi dari beban, kelebihannya listrik akan mengisi baterai. Sementara, apabila daya dari PV kurang dari beban, baterai mengambil bagian untuk memasok listrik ke beban. Ketika daya dari PV rendah dan tegangan baterai kurang dari 46 V, utilitas listrik masuk sistem. Dalam situasi ini, utilitas listrik memasok listrik ke beban dan juga mengisi daya baterai. Akan tetapi, ketika utilitas listrik mati, mesin diesel beroperasi untuk memasok beban dan mengisi baterai.
Untuk peningkatan efisiensi panel surya digunakan analisis jarak optimum antara panel surya dan permukaan atap. Panel surya diberi dudukan berbahan aluminium dengan gap antara 0, 13, dan 30 cm terhadap atap. Panel surya dengan gap 30 cm secara umum memberikan daya output yang paling baik dibandingkan gap yang lain.
Sebelum utilitas listrik tersedia di Desa Kemujan, tim peneliti ini mengembangkan secara mandiri smart microgrid berbasis energi terbarukan untuk mengoperasikan pembuat es. Pada sistem sebelumnya, fotovoltaik 5 kWp digunakan untuk mengisi 16 baterai (12 V, 80 Ah). Listrik arus searah dari baterai diubah menjadi arus bolak-balik melalui 5 kW inverter sebelum memasuki sistem pembuat es 2 kW. Ketika status pengisian (SOC) baterai kurang dari 50%, mesin diesel berbasis biofuel yang terhubung ke generator listrik akan dioperasikan.
Setelah listrik tersedia di Desa Kemujan, sistem listrik untuk pembuat es telah diubah. Grid dan fotovoltaik memasok listrik untuk pembuat es, sedangkan generator bertindak sebagai cadangan pembangkit. Biaya pengoperasian mesin diesel berbasis biofuel secara signifikan lebih tinggi daripada biaya listrik dari PLN.
Manfaat dan potensi pengembangan
Penggunaan smart microgrid akan meningkatkan keandalan sistem dalam menyuplai kebutuhan energi ke mesin pembuat balok. Operasional sistem smart microgrid juga dipandang lebih murah dan hemat.
Penerapan teknologi smart microgrid berbasis teknologi terbarukan ikut mendorong dan memasyarakatkan penggunaan energi bersih di masyarakat pulau terpencil seperti Desa Kemujan, Karimunjawa. Selain itu, memberi solusi yang lebih murah dan efisien bagi penyediaan es balok untuk nelayan dibandingkan dengan pendirian pabrik es yang memerlukan biaya besar, terutama untuk daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal). Adanya sistem ini menghasilkan inovasi produk dalam negeri yang tidak hanya memberi nilai tambah, tetapi juga berdaya guna besar terhadap peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.
Pengembangan sistem smart microgrid di pulaupulau terpencil juga dapat dijadikan sebagai sarana penelitian dan pembelajaran mahasiswa dan
pelajar lain yang tertarik dengan bidang energi terbarukan.
Penggunaan teknologi smart microgrid berbasis teknologi terbarukan untuk pembuatan es balok di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Sebagai negara maritim, Indonesia berlimpah energi surya yang tinggi di berbagai sentra perikanan dan kelautan. Tangkapan mataharinya pun baik serta kebutuhan es baloknya ada.
Dengan menggunakan PLTS, pengoperasian mesin es balok tidak bergantung pada listrik PLN). Nelayan yang berada di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan aliran listrik bisa memanfaatkan teknologi ini sehingga kebutuhan es balok untuk pendinginan ikan bisa memadai. Mestinya penerapan teknologi ini menjadi program strategis pemerintah karena Indonesia memiliki garis pantai yang banyak. Setelah Karimunjawa, tim ITB saat ini sedang mengusulkan ke Pemprov Jabar untuk penerapan di wilayah Sukabumi yang juga memiliki masyarakat nelayan.
Selain itu, tim ITB telah melakukan kajian Detail Engineering Desain (DED) untuk membangun sistem serupa di Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas.***
Teknologi Pelestari / 175
Mesin Pembuat Es Ramah Lingkungan
KONSEP mesin pembuat es bukan teknologi baru dan sudah banyak digunakan. Basisnya ada dua, yaitu yang menggunakan brine (cairan pendingin berupa air garam) atau tidak menggunakan brine (kering) yaitu dari sistem refrigrasi langsung dihubungkan ke kontainer untuk mencetak es balok. Air garam tersebut akan mengelilingi cetakan-cetakan esnya.
Tim Institut Teknologi Bandung mengembangkan smart microgrid berbasis energi terbarukan untuk mengoperasikan mesin pembuat es balok di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. Sistem smart microgrid yang dikembangkan memanfaatkan grid PLN, energi surya melalui panel surya/fotovoltaik (PV), dan mesin diesel (generator) berbasis bahan bakar biofuel. PV digunakan untuk mengurangi konsumsi listrik PLN, sedangkan mesin diesel digunakan sebagai tenaga cadangan ketika listrik PLN tidak tersedia.
Dari hasil pengujian, smart microgrid dapat mengatur input dan output listrik secara otomatis serta cukup andal dalam menyuplai kebutuhan energi mesin es balok dengan masa operasional 24 jam. Listrik dari PV mampu menyumbang
15,18% dari listrik yang dibutuhkan dari satu siklus produksi. Mesin pembuat es balok tersebut dapat memproduksi enam es balok untuk satu siklus produksi. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi es secara terus-menerus adalah 20-30 jam, tergantung massa air. Proses produksi es harus dilakukan secara kontinu untuk mencegah peningkatan temperatur brine.
Sementara, mesin yang dirancang terbagi beberapa bagian, seperti kompresor, kondensor, pipa kapiler, evaporator, pompa, tangki pendingin, cetakan es, dan chain hoist Perancangan mesin juga terbagi ke dalam beberapa tahap. Untuk tahap awal adalah penentuan sistem mesin pembuat es. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana proses pembuatan es sehingga dapat diketahui jenis alat apa saja yang akan digunakan. Dalam sistem ini akan ditentukan jenis peralatan referigasinya, jenis refrigeran, dan jenis bahan yang digunakan untuk membuat air menjadi es. Tahap berikutnya adalah menentukan jumlah es yang akan diproduksi, menentukan ukuran dan jumlah cetakan es yang akan dipakai, serta menentukan ukuran tangkai media pendingin.
Setelah itu lalu dihitung beban pendinginan yang terdiri atas beban pendinginan untuk mendinginkan air menjadi es, beban pendinginan dari media pendingin, beban pendingin dari udara luar, beban pendinginan dari infiltrasi udara. Setelah beban pendingin diketahui lalu dihitung jumlah refrigeran, daya kompresor dengan mengacu pada siklus refrigerasinya. Pembuatan mesin pembuat es rancangan tim ITB dilakukan di sebuah workshop di Tangerang.
Kelebihan dari mesin pembuat es balok rancangan tim ITB terletak pada refrigeran yang digunakan. Jika untuk mesin pembuat es biasa digunakan R-134a atau lebih dikenal nama Tetraflouroethan (CF3CH2F), untuk mesin pembuat es balok ini tim lebih memilih menggunakan hidrokarbon Propana (R290). Hidrokarbon Propana lebih ramah lingkungan. Refrigeran ini memiliki nilai potensi pemanasan global (global warming potential/GWP) sangat rendah dan nilai nol untuk ozone depletion potential (ODP). Sementara, Tetraflouroethan masih menimbulkan dampak pemanasan global.
Refrigeran hidrokarbon Propana ini memiliki kinerja termal yang sangat baik, harganya murah, dan kompatibel dengan pelumas mesin dan struktur material. Propana memiliki sifat termodinamika yang sangat baik yang menunjukkan efisiensi tinggi dan biaya rendah dengan dimensi penukar kalor dan pipa lebih kecil. Walaupun memiliki sifat mudah terbakar (flammable), asal digunakan sesuai dengan prosedur, Propana aman digunakan.
Tim juga melakukan simulasi terkait desain posisi cetakan es dengan memakai software Fluent untuk melihat posisi terbaik. Hal ini yang membedakan dengan mesin es balok yang dijual bebas di pasaran. Tim menambahkan modifikasi alat baffle untuk mengarahkan aliran brine (air garam) ke enam cetakan es yang ada sesuai rute tertentu. Setelah itu dilihat optimasinya secara keseluruhan. Baffle yang dipasang (opsional) untuk memandu aliran air brine melalui wadah es. Penggunaan baffle dalam wadah air brine (campuran air dan garam dengan kadar tertentu) membantu meratakan aliran air garam melalui kontainer es. Hal itu membantu kinerja mesin es yang lebih baik dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan es balok. Sementara, sistem refrigerasi yang dipilih adah sistem refrigerasi sekunder (secondary refrigeration system). Pada sistem refrigerasi ini proses pembuatan es dilakukan oleh refrigeran sekunder. Prosesnya dimulai dengan pendinginan brine oleh refrigeran primer dalam evaporator. Brine sebagai refrigeran sekunder dimanfaatkan untuk mendinginkan air dalam cetakan agar dapat membeku menjadi es. Keuntungan sistem yang menggunakan brine adalah lebih stabil dalam hal pendinginan dan pembuatan es balok. Terdapat enam wadah es yang direndam dalam larutan brine. Kompresor yang digunakan adalah kompresor satu fasa dan membutuhkan daya sekitar 1.8 kW. Sementara, kipas kondensor 500 W, dan daya yang dibutuhkan pompa brine adalah 200 W.
Mesin pembuat es balok yang dibuat terdiri atas dua bagian, yaitu tangki produk es dan mesin refrigerasi. Tangki produksi es terdiri atas berbagai komponen yang mendukung berjalannya proses pada larutan garam, air, dan produksi es. Sementara, mesin refrigasi terdiri atas berbagai komponen yang mendukung terjadinya pendinginan larutan garam yang nantinya akan mendinginkan es.
Berikut bagian-bagian penyusun mesin pembuat es balok yang dikembangkan oleh tim ITB:
1. Tangki produksi es
Tangki ini terdiri atas beberapa komponen, yaitu pompa air, tangki pendingin, cetakan es, pipa sirkulasi larutan garam, larutan garam, dan chain hoist.
2. Pompa air
Pompa air digunakan untuk memindahkan larutan garam dari tempat pendinginan air ke ruang evaporator. Jenis pompa air yang dipilih adalah pompa air listrik non-otomatis.
3. Tangki pendingin
Tangki pendingin terdiri atas dua bagian yang dipisahkan dengan sebuah pelat. Bagian pertama adalah tempat evaporator yang akan mendinginkan brine yang keluar dari pompa sirkulasi. Bagian kedua adalah tempat cetakan es yang berisi air yang akan didinginkan oleh brine yang mengalir dari ruang
evaporator. Tangki pendingin mempunyai ukuran panjang 121 cm, lebar 107 cm, dan tinggi 131,5 cm. Bahan tangki pendingin adalah pelat dari carbon steel dengan ketebalan 7 mm. Tangki pendingin didesain menggunakan tiga lapisan untuk mengurangi perpindahan panas dari lingkungan ke dalam tangki tersebut. Lapisan luar dari bahan pelat carbon steel 7 mm. Carbon steel mempunyai yield strength yang kuat. Lapisan tengah adalah isolator dari bahan polyurethane 10 cm. Polyurethane memiliki karakteristik konduktivitas termal yang rendah. Sementara lapisan dalam menggunakan pelat carbon steel 7mm. lapisan ini untuk melindungi dinding dari gejolak aliran brine dan menjaga isolator dan brine
4. Cetakan es
Cetakan es merupakan cetakan yang diisi air untuk menjadi es melalui media pendingin (brine). Materialnya merupakan konduktor yang baik agar perpindahan panas dapat berlangsung lebih cepat dan baik. Material cetakan es yang digunakan juga tahan karat untuk menjaga mutu es dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Cetakan es yang digunakan berbahan stainless steel. Cetakan es yang dibuat berbentuk taper (meruncing) untuk mempermudah ketika mengeluarkan es dari cetakan. Ukuran cetakan es 260x170 mm pada bagian atas, 220x120 mm pada bagian bawah, dan tinggi 1.150 mm. Cetakan yang digunakan berjumlah enam buah.
Teknologi Pelestari / 179
5. Pipa sirkulasi larutan garam
Larutan garam dari tempat pendinginan air dialirkan ke ruang evaporator untuk didinginkan kembali. Pemindahan larutan garam menggunakan pompa dan alirannya melalui pipa. Pipa yang digunakan bahannya dari paralon yang diberi isolasi dengan bahan glasswool.
6. Larutan garam (brine)
Larutan garam yang digunakan adalah garam dapur (NaCl) dan air. Konsentrasi massa garam yang biasa digunakan pada mesin es balok adalah 15-20%. Hasil pengujian, larutan garam NaCl 20% dapat digunakan dalam proses pembuatan es balok, sedangkan larutan garam NaCl 15% tidak bisa digunakan karena terjadinya kekurangan konsentrasi garam yang menyebabkan terbentuknya bunga es di evaporator. Larutan garam dalam tangki akan disirkulasikan dengan pompa air dan didinginkan oleh cool pipe coller (evaporator).
7. Chain hoist
Alat ini digunakan untuk memindahkan cetakan es dari tempat pengisian air ke titik pendingin dan sebaliknya ketika es sudah jadi chain hoist digunakan untuk memindahkan cetakan es ke tempat pelepasan es. Chain hoist yang digunakan memiliki dua derajat kebebasan yaitu bergerak maju dan mundur sepanjang jalur rel dan bergerak naik turun.
8. Baffle
Baflle dirancang untuk meningkatkan kinerja mesin pembuat es balok. Baflle merupakan lembaran vertikal yang ditempelkan pada dinding tangki. Tujuan penggunaan baffle adalah sebagai penyearah aliran larutan garam di antara cetakan es. Baffle yang dirancang berukuran 1.150 x 400 mm, 2 buah berbahan pelat baja 10 mm.
9. Kompresor dan kondensor
Kompresor berfungsi untuk kompresi uap refrigeran dan mengalirkan refrigeran supaya bisa terus bersirkulasi. Daya input listrik kompresor diusahakan serendah mungkin. Sementara itu, kondensor yang digunakan harus mampu mendinginkan refrigeran sehingga refrigeran menjadi cair kembali pada tempo yang diinginkan.
10. Evaporator
Evaporator digunakan untuk mendinginkan secondary coolant yang berfungsi mendinginkan air menjadi es. Bentuk evaporator dibuat seringkas mungkin. Perancangannya menggunakan evaporator coil/tube 1,3 cm dengan panjang 2.304 cm yang dibenamkan ke dalam brine. Pemasangan dan perawatan evaporator mudah dan harganya pun terjangkau.
11. Pipa kapiler
Alat ekspansi yang digunakan pada perancangan ini harus mampu menurunkan tekanan sesuai dengan tekanan yang dikehendaki. Alat ekspansi yang dipilih adalah pipa kapiler berbahan tembaga dengan diameter 0,7 mm dan panjang 30 cm.
Prosedur pembuatan es pada mesin ini diawali dengan memasukkan larutan media pendingin ke dalam tangki, kemudian memasukkan cetakan es ke dalam tangki lalu diisi air. Langkah selanjutnya adalah menutup cetakan tangki dan menutup tangki es. Setelah itu mesin refrigerasi dihidupkan.
Setelah es terbentuk mesin pendingin harus dimatikan lalu membuka tutup tangki dan mengeluarkan cetakan es dari tangki dan dimasukkan ke dalam bak air. Cetakan es didiamkan beberapa saat di dalam bak air kemudian diangkat keluar dan es balok dikeluarkan dari cetakan es.
Pengujian
Pengujian mesin es balok diperlukan untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan. Tujuan dari sistem ini adalah mengurangi konsumsi utilitas listrik dengan menggunakan PV. Enam balok es akan diproduksi di akhir satu percobaan. Berdasarkan temperatur air garam di awal pengujian, dua tes dilakukan, yakni saat temperatur awal air garam sama dengan temperatur lingkungan, dan saat temperatur awal air garam lebih rendah dibandingkan temperatur lingkungan. Bisa diperkirakan bahwa penggunaan air garam dengan temperatur rendah akan membutuhkan energi yang lebih rendah untuk pembuatan es balok. Namun, penting untuk memeriksa seberapa jauh perbedaan antara kedua kondisi.
Pada pengujian sistem smart microgrid yang dilakukan bersama mahasiswa Program Studi Magister Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, yaitu Musfirin dan Aldrin pada medio tahun 2019, didapat bahwa untuk satu siklus produksi mesin es balok dengan kondisi awal larutan garam bertemperatur lingkungan didapatkan waktu produksi sekitar 62,5 jam dengan total kebutuhan energi 121,591 kWh. Dari total kebutuhan energi tersebut, suplai listrik dari PV sebesar 18,462 kWh dan suplai dari listrik PLN sebesar 99,709 kWh. Biaya listrik PLN untuk satu siklus ini adalah Rp146.301,00.
Sementara pada pengujian dengan kondisi awal larutan garam bertemperatur rendah (-7°C) dibutuhkan waktu produksi sekitar 30 jam untuk menghasilkan es balok dengan kebutuhan energi 54,568 kWh. Dari total kebutuhan energi tersebut, suplai listrik dari PV sebesar 4,965 kWh dan suplai dari PLN sebesar 48,510 kWh. Biaya untuk listrik PLN untuk satu siklus ini adalah Rp71.177. Produksi es balok untuk satu siklus sebanyak enam balok dengan harga jual Rp20.000 sehingga pendapatan untuk satu siklus produksi adalah Rp120.000.
Produksi es balok dengan kondisi awal larutan garam bertemperatur lingkungan mengalami kerugian, sedangkan produksi es balok dengan kondisi awal larutan garam bertemperatur rendah mengalami keuntungan. Dari dua pengujian mesin pembuat es balok untuk satu siklus produksi es balok dengan kondisi awal larutan garam bertemperatur rendah, penggunaan baffle adalah yang terbaik karena mempercepat waktu pembekuan air dan meningkatkan kinerja mesin pembuat es balok.
Dari dua pengujian tersebut dapat disimpulkan pengoperasian mesin es balok harus dilakukan secara kontinu untuk menjaga temperatur brine tetap rendah agar menghasilkan keuntungan. Pada pengujian PV didapatkan efisiensi PV monocrystalline 8,20 dan PV polycrystalline 7,23% dengan rasio performansi berturut-turut 50,12% dan 52,74%.
Pengujian berdasarkan penyinaran matahari dilakukan tiga fase, yaitu saat hari cerah, hari mendung, dan pada malam hari (tanpa produksi listrik PV). Tujuan dari tes ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari pengontrol di dalam inverter. Kontroler mengatur suplai listrik ke pembuat es. Ada tiga pasokan energi, yaitu utilitas listrik (grid), PV, dan generator, dan satu penyimpanan energi (baterai).
Pada pengujian saat hari cerah, sistem smart microgrid mampu menyuplai kebutuhan daya beban dari energi surya dan baterai dengan e fisiensi inverter 81,18%. Untuk pengujian saat hari mendung, sistem smart microgrid menyuplai kebutuhan daya beban dari energi surya, baterai, dan grid (PLN/generator) dengan efisiensi inverter 81,38%. Sementara itu, untuk pengujian pada malam hari, sistem smart microgrid mampu menyuplai kebutuhan daya beban dari baterai dan grid (generator/PLN) dengan efisiensi inverter 89,39%.
Dari dua pengujian tersebut dapat disimpulkan pengoperasian mesin es balok harus dilakukan secara kontinu untuk menjaga temperatur brine tetap rendah agar menghasilkan keuntungan.
Pelibatan masyarakat
Pengembangan teknologi sarana dan prasarana sektor perikanan tentu tidak cukup. Dibutuhkan pelibatan langsung masyarakat agar benar-benar memahami teknologi yang dibawa ke tengah-tengah mereka. Masyarakat nelayan membutuhkan pelatihan dan pendampingan dalam operasional mesin es balok dengan teknologi ini.
Teknologi smart microgrid berbasis energi terbarukan merupakan teknologi yang baru bagi masyarakat nelayan di Desa Kemujan, Kecamatan Karimaujawa sehingga perlu edukasi pengenalan teknologi sekaligus pengoperasian dan perawatannya. Selain itu, dengan disepakatinya pengelolaan pabrik es balok berteknologi smart microgrid oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kemujan, diperlukan pula pendampingan bagi BUMDes dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar dapat mencapai kemandirian secara ekonomis pada akhirnya. Untuk keperluan tersebut, tim bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa pada 2020. Ruang lingkup pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah penambahan instalasi air dari sumur, yaitu berupa sistem pompa dan perpipaan untuk memudahkan pengisian air ke dalam kontainer mesin pembuat es balok, perbaikan sistem mesin pembuat es balok termasuk
pengisian refrigeran, penggantian pipa kapiler, penambahan pressure gauge, perbaikan hoist crane, serta instalasi listrik dan mencakup wiring dari PLN dan inverter/sistem off grid ke sistem mesin pembuat es. Selain itu, tim menyiapkan buku panduan pengoperasian, perawatan, dan troubleshooting yang mudah dipahami oleh masyarakat awam (dengan kemampuan teknik minimalis).
Tim juga mengadakan program pelatihan menyeluruh dengan materi mulai dari pengenalan dasar teknologi sampai praktik pengoperasian, perawatan, dan troubleshooting. Selanjutnya, tim menyediakan jalur komunikasi dan konsultasi secara intensif agar tenaga operasional di lapangan dapat memperoleh bimbingan dan arahan yang diperlukan. Semua kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2020 masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat lokal dari berbagai kalangan diharapkan bisa terampil dan terlibat aktif dalam proses pengoperasian, perawatan, dan perbaikan secara baik dan maksimal ketika tim ITB telah meninggalkan pulau.
Kendala paling kentara yang dirasakan adalah ketika terjadi kerusakan atau gangguan cukup berarti pada sistem smart microgrid mesin pembuat es balok berbasis energi terbarukan. Hal itu karena berada di remote area, penanganannya terkendala jarak. Untuk menuju ke pulau diperlukan biaya dan waktu, tidak bisa direspons secara cepat.***
Mencari Solusi Alternatif Pengganti Es Balok
PENGGUNAAN es balok oleh nelayan tradisional sangat tinggi. Dengan kapal berkapasitas kecil, mereka tidak dapat memasang freezer untuk menyimpan ikan atau mesin es untuk membuat es di atas kapal. Es balok menjadi senjata andalan bagi mereka agar ikan tangkapan tetap segar dan berharga tinggi ketika dilepas di pasaran. Dengan kondisi tersebut, es balok menjadi pengeluaran yang signifikan bagi nelayan tradisional, terutama yang berada di pulau terpencil. Setelah mencair, es balok tidak bisa digunakan lagi. Nelayan harus terus-menerus menambah es balok sehingga meningkatkan biaya pengeluaran.
U ntuk itu, tim Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB yang dipimpin Dr. Eng. Yuli Setyo Indartono bersama Robertus Kristianto Sukoco, S.T. melakukan penelitian terkait penggunaan bahan berubah fasa (phase change material/PCM) sebagai pengganti es balok untuk mendinginkan ikan. Bahan berubah fasa ketika dikemas dengan baik akan dapat digunakan kembali. Sebagai bahan berubah fasa digunakan larutan kalium klorida (KCl) eutektik (eutectic potassium chloride). Bahan berubah fasa ini memiliki komposisi eutektik 19,5% (wt.%) KCL. Bahan ini meleleh pada -10,7 derajat Celsius sehingga cocok untuk media wadah pendingin dan kalor perubahan fasa sebesar 253 kJ/kg.
Bahan berubah fasa tersebut diwadahi pada pouch (kantong) zip-lock berbahan aluminium foil untuk mencegah kebocoran larutan dan mencegah kontaminasi dengan ikan. Tiap pouch mewadahi 670 gram larutan KCl eutektik. Sementara, dua boks Polystyrene dengan volume 53 liter digunakan untuk menyimulasikan boks pendingin yang digunakan nelayan atau pengepul ikan. Dua boks ini berisi media penyimpanan dingin berbeda, yaitu larutan KCl eutektik dan es batu dengan dua konfigurasi berbeda: es diwadahi di pouch yang sama dengan larutan KCl dan es batu atau pecahan es. Hasil percobaan menunjukkan boks pendingin yang dilengkapi pouch larutan KCl eutektik memiliki temperatur yang konsisten pada 0 hingga 3 derajat Celsius dan bisa bertahan selama 18-24 jam, tergantung pada peletekan boks. Temperatur bahan berubah fasa tersebut konsisten pada sekitar -11 derajat Celsius. Kualitas ikan di dalam boks pendingin berisi pouch bahan berubah fasa dinilai lebih baik daripada boks berisi pouch es batu ataupun pecahan es. Meskipun penyimpanan selama 24 jam tidak menghasilkan kualitas ikan yang berbeda jauh, untuk durasi yang lebih lama, yaitu 2 hingga 3 hari, perbedaan kualitas ikan dapat menjadi signifikan.
Uji organoleptik juga dilakukan untuk mengukur kesegaran ikan. Hasilnya, penggunaan larutan kalium klorida (KCl) eutektik sebagai pendingin ikan menghasilkan ikan dengan kualitas yang lebih baik dan lebih terjaga.

Hasil penelitian ini telah dibawa dan diperkenalkan kepada masyarakat nelayan di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa. Namun, karena masih merupakan hal yang baru, belum sempat digunakan karena bahan-bahan kimia yang diperlukan hanya tersedia di kota-kota besar. Hal itu menjadi kendala jika diterapkan di pulau terluar.***

Memaksimalkan Produksi Minyak Nyamplung di Pulau Terluar
PEMANFAATAN bahan bakar nabati menawarkan manfaat memproduksi energi tanpa meningkatkan kadar karbon di atmosfer sehingga lebih ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025 yang setara dengan 92,2 million tonnens of oil equivalent (MTOE) dan seperempat dari porsi tersebut dicanangkan dari bahan bakar nabati. Saat ini, bahan bakar nabati masih dominan berbasis minyak sawit atau biodiesel sawit. Untuk pemenuhan bauran tersebut perlu pengembangan karena Indonesia memiliki kekayaan sumber energi terbarukan yang melimpah.
Apa yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB) patut menjadi contoh. Sistem smart microgrid berbasis energi terbarukan yang dikembangkan tim Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) ITB di Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa memadukan pemanfaatan energi surya melalui panel surya/fotovoltaik (PV), mesin diesel, dan listrik PLN. Pemanfaatan ketiga sumber energi listrik tersebut digunakan untuk menjalankan mesin pembuat es balok.
Bahan bakar yang digunakan untuk generator yaitu biofuel, tetapi levelnya bukan biodiesel. Untuk membuat biodiesel diperlukan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah dimurnikan yang menghasilkan pure plant oil (PPO). Tahapan selanjutnya yaitu transesterifikasi yang nantinya menghasilkan biodiesel. Biodiesel tersebut jika dicampur dengan solar menjadi B-20, B-30. Karena bahan bakar untuk generator yang digunakan adalah pure plant oil, prosesnya menjadi lebih sederhana. Namun, pure plant oil sifatnya lebih kental untuk penggunaan sebagai bahan bakar sehingga diperlukan adanya pemanasan. Untuk keperluan tersebut, tim memodifikasi mesin dengan menambahkan preheater Preheater digunakan untuk memanaskan pure plant oil supaya kekentalannya (viskositas) turun.

Salah satu bahan bakar nabati yang digunakan adalah minyak dari biji tanaman nyamplung (Calophyllum inophyllum L). Minyak dari biji nyamplung juga sudah banyak digunakan sebagai minyak lampu, obat tradisional, dan bahan untuk kosmetik. Pemanfaatan bahan bakar nabati minyak nyamplung potensial dikembangkan di Indonesia, terutama di daerah pesisir pulau-pulau terluar. Di daerah tersebut pohon nyamplung tumbuh subur. Pohon ini menghasilkan biji berkadar minyak tinggi sehingga potensial untuk diekstraksi menjadi bahan bakar nabati. Kadar lemak atau kadar minyak biji nyamplung dalam keadaan kering mencapai 75%, lebih tinggi dibandingkan dengan biji jarak dan biji karet yang hanya sekitar 50% dan 40%.
Produktivitas biji nyamplung juga sangat tinggi, bervariasi antara 40-150 kg/pohon/tahun atau sekitar 20 ton/ha/tahun dan lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman lain seperti jarak pagar 5 ton/ha/tahun dan sawit 6 ton/ha/tahun. Sebenarnya Indonesia berlimpah buah kelapa untuk dijadikan minyak nabati, tetapi ada konflik kepentingan dengan bahan makanan. Sementara, biji nyamplung pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan karena tidak dapat dikonsumsi (nonedible). Pohon nyamplung juga regenerasinya mudah dan berbuah sepanjang tahun, daya tahan terhadap lingkungan tinggi, dan relatif mudah dibudidayakan.
Untuk pengembangan bahan bakar nabati minyak nyamplung, tim yang terdiri atas Dr. Eng. Yuli Setyo Indartono, Heriawan, dan Dr. Ir. Ika Amalia Kartika, M.T. dari Institut Pertanian Bogor (IPB) melakuan penelitian untuk merancang sekaligus memproduksi mesin pengekstrak minyak nyamplung secara mekanik berkonfigurasi ulir tunggal
fl
eksibel (flexible single screw extruder). Kelebihannya dibandingkan dengan mesin ekstrasi yang ada di pasaran adalah konfigurasi ulir tunggal fleksibel rancangan tim ITB tiap bagiannya bisa dilepas sehingga bisa disesuaikan dengan jenis bahan biji yang akan diekstrak. Mesin ekstraksi ini memiliki kecepatan putar ulir yang rendah, yaitu 15-25 rpm, memiliki dua pemanas yang dapat diatur posisi dan temperaturnya, dan berkapasitas kecil, yaitu 5 kg biji per jam. Penelitian ini merupakan lanjutan, perbaikan, dan pengembangan dari penelitian terdahulu.***

Peternakan Sapi Nirlimbah

Dr. Pramujo Widiatmoko
Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat masyhur sebagai sentra peternakan sapi perah sejak zaman kolonial Belanda. Seiring dengan waktu, peternakan sapi di daerah ini terus berkembang. Menghadirkan peternakan sapi yang ramah lingkungan serta pengembangan inovasi energi terbarukan dari pemanfaatan limbah menjadi wujud nyata tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), infrastruktur, industri, dan inovasi (SDG 9), serta energi bersih dan terjangkau (SDG 7).
PARA peternak mendirikan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) pada 1969 untuk pengumpulan dan pengolahan produk susu mereka. Data KPBS, produk susu dari anggotanya pada 2017 mencapai 85 ton/hari dari 4.500 anggotanya yang memelihara lebih dari 15.000 ekor sapi. Jumlah sapi dan produksi susu yang meningkat tentu diiringi pula dengan jumlah kotoran sapi yang melimpah. Sementara, hanya 57% kotoran sapi yang diolah, yaitu 21% untuk kompos dan 14% untuk biogas. Sisanya dibuang langsung ke saluran air. Peternak enggan beranjak dari kebiasaan lama, membuang langsung kotoran sapi ke sungai-sungai kecil terdekat. Dampaknya, pencemaran di wilayah hulu Sungai Citarum makin mengkhawatirkan. Padahal, alih-alih jadi pencemar lingkungan, kotoran sapi berpotensi menjadi bernilai ekonomis jika diproses menjadi biogas. Cara itu dapat menurunkan kandungan biological oxygen demand (BOD) di air buangan peternakan sapi. Selain itu, peternak mendapatkan keuntungan lain berupa pengurangan ongkos pembelian gas elpiji.
Pemanfaatan tersebut sejalan dengan proyek-proyek pemerintah untuk mendukung perbaikan kualitas air Sungai Citarum. Pada 2018, pemerintah meluncurkan program “Citarum Harum” untuk mengembalikan kebersihan Sungai Citarum dalam proyek jangka panjang. Proyek ini merupakan kelanjutan dari “Citarum Bergetar” (2001) dan “Citarum Bestari” (2013).
Mendukung program Citarum Harum, tim dari Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan program pengabdian masyarakat berupa percontohan produksi biogas di Desa Margamulya, Pangalengan. Tim ITB terdiri atas Dr. Pramujo Widiatmoko dari KK Energi dan Sistem Pemroses Teknik Kimia sebagai ketua dan Dr. Jenny Rizkiana sebagai anggota. Sementara, Susilo Yuwono, M.B.A., Mohammad Taufiq, M.T., dan Candra Purnama Hadi, S.T., dari Yayasan Cendekia Salim Mulia membantu pelaksanaan di lapangan. Tim juga bermitra dengan (alm) Ir. Adang Shalahuddin dan berterima kasih kepada Ketua KPBS Pangalengan, H. Aun Gunawan, S.E. Teknologi Pelestari / 193
Pemanfaatan biogas
Pemanfaatan biogas dari limbah menjadi penting untuk menyediakan sumber energi lokal terbarukan di daerah peternakan sapi. Biogas merupakan campuran sekitar 60% gas metana dan 40% karbon dioksida hasil dari aktivitas anaerobik bakteri dalam menguraikan bahan-bahan organik. Komposisi biogas bergantung pada persentase lemak, protein, dan karbohidrat pada substrat yang digunakan. Di Indonesia, biogas telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an. Pemanfaatannya dipercepat pada tahun 1981 selama proyek pengembangan biogas yang didanai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Namun, pemanfaatan kotoran ternak untuk biogas masih rendah, hanya 14%. Perlu peran serta dan dukungan berbagai pihak, terutama untuk mencapai target nasional bauran energi baru terbarukan biogas sebesar 489,8 juta m3 pada 2025. Data juga menunjukkan bahwa realisasi target 2019 hanya 25,67 miliar metrik kubik. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan kembali pemanfaatan biogas.
Masalah utama adopsi teknologi biogas adalah biaya instalasi reaktor yang tinggi. Untuk satu reaktor ukuran 4 m3 berbahan fiberglass dibutuhkan biaya Rp4 juta-Rp5 juta dengan estimasi biaya instalasi keseluruhan sampai penyaluran ke rumah warga bisa mencapai Rp13 juta.
Permasalahan lain yang kerap ditemui dalam pemanfaatan biogas ialah ketersediaan lahan untuk instalasi. Untuk bisa mendapatkan aliran gas yang baik dan cukup besar, jarak maksimal rumah dengan lokasi reaktor idealnya tak lebih dari 10 meter. Itu disebabkan kebutuhan tempat pemasangan reaktor yang banyak dan berbeda-beda jika akan mengaliri biogas untuk seluruh warga.
Semakin jauh lokasi rumah dari reaktor maka api yang dihasilkan akan lebih kecil. Penyebarluasan, pelatihan, dan pemantauan program berkelanjutan yang tidak memadai juga menyebabkan adopsi teknologi biogas tersendat.
Program biogas ITB di peternakan sapi Pangalengan dilakukan dalam jangka waktu tiga periode, yaitu 2019, 2020, dan 2021. Pada tahun pertama pelaksanaan, tim memasang satu reaktor biogas tipe Tenari berkapasitas 4 m3. Reaktor Tenari (Teknologi Anak Negeri) merupakan produk dari alumnus Teknik Kimia ITB, Andrias Widji, S.T. Kegiatan awal tersebut didanai dari Program Pengabdian Masyarakat Kemenristek-Dikti 2019. Program yang berlangsung dari April hingga November 2019 dilaksanakan di peternakan milik Adang Shalahuddin di Kampung Mekar Mulya RT 02/RW 24, Margamulya, Pangalengan yang memiliki 20 ekor sapi.
Dengan populasi sapi perah di KPBS Pangalengan sekitar 15 ribu ekor, potensi produksi biogas diperkirakan mencapai 6.000 meter kubik (m3)/hari. Kotoran dari 10 sapi bisa untuk memenuhi kebutuhan gas lima rumah selama 5 jam sehari. Jika seluruh kotoran sapi dapat dimanfaatkan, biogas yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan 7.000 rumah. Pemanfaatan besar ini hanya bisa terwujud dengan upaya kolektif berbagai pihak.
Kotoran dari 10 ekor sapi digunakan untuk memasok bahan baku ke reaktor biogas berukuran 4 m3. Biogas yang dihasilkan diditribusikan ke peternakan sapi dan tiga rumah terdekat. Warga memanfaatkannya sebagai pengganti elpiji untuk bahan bakar memasak. Reaktor biogas yang dipasang tim diperkirakan dapat menghemat Rp69.000 hingga Rp295.000 per bulan dari pengurangan
ongkos pembelian elpiji. Program awal ini memancing gairah para peternak sapi di KPBS Pangalengan untuk memasang reaktor biogas secara mandiri.
Namun, kurangnya volume kerja reaktor menyebabkan produksi biogas menjadi tidak optimal. Budaya sosial masyarakat juga sulit diubah. Mereka menganggap biogas tidak layak dijadikan sumber energi pengganti elpiji karena khawatir menyebabkan bau pada makanan. Memang, biogas masih mengandung hidrogen sulfida (H2S) sehingga ketika belum dibakar akan tercium bau. Namun, begitu kompor dinyalakan dan terbakar, hidrogen sulfida akan berubah menjadi H20 dan SO2, SO3 sehingga tidak akan menimbulkan bau.
Untuk menjamin kelangsungan program ini perlu terobosan. Oleh karena itu, tim melaksanakan program lanjutan kedua pada tahun 2020 yang bertujuan menambah jumlah instalasi. Dengan begitu, akan lebih banyak kotoran sapi yang dapat termanfaatkan. Produk biogas yang dihasilkan pun akan meningkat.
Dana dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITB digunakan untuk pemasangan dua reaktor biogas tambahan. Dengan begitu, telah terpasang tiga reaktor biogas dengan total kapasitas terpasang sebesar 12 m3.
Biogas tersebut digunakan untuk keperluan peternakan dan enam rumah tangga di sekitar peternakan. Potensi penghematan dari pemasangan tiga reaktor ini bisa mencapai Rp885.000 per bulan.
fikasi.
Program ini merupakan percontohan dengan menggunakan reaktor fiberglass dan dilaksanakan di peternakan peternak yang memiliki lebih dari 30 ekor sapi.
Penggunaan reaktor berbahan plastik yang lebih murah dan hanya bisa bertahan selama dua tahun. Selain reaktor tambahan, ruang lingkup dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 2020 ialah pemasangan sistem penangkap air dan gas hidrogen sulfida (H2S) serta pemasangan data logger untuk memantau kondisi reaktor.
Reaktor dirancang untuk pengoperasian dan perawatan yang lebih mudah. Kotoran sapi bisa langsung masuk ke ruang mixing dan control tank melalui saluran khusus yang dimodi fi kasi. Sebelumnya, peternak secara manual harus mengumpulkan kotoran sapi memakai ember sebelum dimasukkan ke lubang pengumpan. Hal ini cukup memberatkan peternak karena waktu berharga untuk mengurus sapi menjadi tersita. Dengan rancangan ini, pengisian kotoran sapi lewat ember tidak diperlukan lagi dan tentu saja mengurangi beban kerja para peternak yang terlibat.
Selain itu, tim merintis konsep desa binaan dengan dukungan Himpunan Mahasiswa Bioenergi dan Kemurgi (HMTB) ITB, RINUVA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan operator serta memastikan pemantauan program secara terus-menerus agar instalasi tetap terawat dan dimanfaatkan dengan baik.
Reaktor dirancang untuk pengoperasian dan perawatan yang lebih mudah. Kotoran sapi bisa langsung masuk ke ruang mixing dan control tank melalui saluran khusus yang dimodi
Proses pembentukan biogas
Kotoran sapi merupakan bahan baku biogas yang paling ideal jika dibandingkan dengan kotoran ternak lain, seperti ayam dan kambing. Biogas sendiri merupakan campuran sekitar 60% gas metana dan 40% karbon dioksida. Biogas dapat dimanfaatkan untuk memasak, memproduksi listrik, ataupun sumber gas metana untuk industri. Penghilangan kandungan karbon dioksida akan meningkatkan nilai kalor bakar dan nilai ekonomis biogas secara signifikan. Biogas dihasilkan dari proses anaerobik (fermentasi) bahan-bahan organik. Bahan yang sangat dibutuhkan dalam membuat biogas yaitu asam-asam organik yang terkandung di dalam bahan organik oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Proses pembuatan dan pembentukan biogas dimulai dari memasukkan bahan organik kompleks berupa karbohidrat, protein, lemak dari kotoran sapi ke reaktor biogas. Setelah itu akan terjadi reaksi kimia, yang pertama adalah reaksi kimia hidrolisis. Di tahap ini molekul-molekul organik kompleks dipecah menjadi gula sederhana, asam amino, dan asam lemak oleh bakteri dengan bantuan eksoenzim karena senyawa-senyawa kompleks terlalu besar untuk dapat diserap secara langsung.
Tahap kedua adalah proses biologi sacidogenesis lebih lanjut dengan acidogens menjadi molekul sederhana, asam lemak volatil (VFAs) terjadi, memproduksi amonia, karbon dioksida dan hidrogen sul fi da sebagai produk sampingan. Pada tahap ketiga terjadi proses asetogenesis, yakni molekul sederhana dari acidogenesis lebih lanjut dicerna oleh acetogens untuk menghasilkan karbondioksida, hidrogen, dan terutama asam asetat. Tahap keempat adalah proses biologis metanogenesis metana (CH4),
karbon dioksida (CO2), dan air yang diproduksi oleh metanogen.
Gas metana dalam biogas dapat dibakar untuk menghasilkan listrik yang disalurkan melalui pipa-pipa khusus ke peternakan maupun rumah warga. Gas tidak dibuang langsung ke atmosfer sehingga tidak memberikan kontribusi untuk meningkatkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Oleh karena itu, dianggap menjadi sumber energi yang ramah lingkungan.
Impian besar dari tim adalah membuat sistem proses skala industrial komersial yang diharapkan bisa diterapkan untuk meningkatkan keekonomian masyarakat. Selain untuk keperluan listrik lampu penerangan juga untuk menggerakkan vakum pompa susu di peternakan. Hal ini bisa membantu para peternak, terlebih di daerah tersebut masih sering terjadi pemadaman listrik.
Pelaksanaan program pun mengusung sinergi pengabdian masyarakat dan penelitian. Saat ini tim tengah meneliti pemanfaatan CO2 yang merupakan sisa dari proses pembuatan biogas untuk dikonversi menjadi bahan kimia bernilai tambah (menjadi bahan bakar), sekaligus mengurangi efek rumah kaca. Penelitian lain yang dilakukan pada program ini yaitu pengembangan fuel cell untuk pembangkit listrik skala rumah tangga.
Keberlanjutan dan pengembangan
Untuk keberlanjutan program, tim telah merintis konsep desa binaan dalam proyek ini dengan dukungan dari Himpunan Mahasiswa Bioenergi dan Kemurgi (HMTB) ITB, RINUVA. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan operator serta memastikan pemantauan program secara terus-menerus agar instalasi tetap terawat dan dimanfaatkan dengan baik.
Mahasiswa ITB juga secara rutin mengunjungi lokasi biogas untuk melakukan praktik kerja lapangan serta kegiatan MBKM di lokasi kegiatan. Hal itu penting dilakukan agar warga tidak akan langsung ditinggalkan tanpa pendampingan pascaprogram rampung. Di masa depan, mereka dapat meningkatkan skala proyek dan teknologi ke yang paling canggih. Penerapan teknologi biogas di peternakan sangat mungkin dikembangkan di Indonesia. Potensi biogas di Indonesia cukup melimpah. Peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di antara jenis ternak, sapi merupakan penghasil kotoran yang paling besar. Untuk itu, peternakan sapi sangat potensial dijadikan sebagai sumber penghasil biogas karena penerapannya bisa dilakukan sepanjang tahun. Harapan ke depan, biogas menjadi salah satu energi alternatif utama bagi masyarakat Indonesia dan turut menjaga kelestarian lingkungan. Pemanfaatan dan pengolahan limbah organik menjadi biogas merupakan salah energi alternatif yang dapat mendukung pencapaian bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% di 2025.***
Teknologi Pelestari / 201Manfaat Ekstra Lumpur Sisa Biogas
PADA 2021, program tim fokus pada pengembangan produk samping dari biogas. Permasalahan umum dari instalasi biogas adalah limbah dari kotoran sapi perah yang telah diambil biogasnya. Wujudnya berupa lumpur campuran padat dan encer antara kotoran hewan dan air. Setiap penambahan masukan bahan baku biogas ke dalam reaktor biogas, dengan sendirinya akan keluar limbah dengan ukuran yang sama dengan masukan bahan baku. Dengan demikian, setiap hari akan dihasilkan limbah. Apabila lumpur sisa dibiarkan keluar begitu saja hingga mengalir ke saluran air dan masuk ke sungai, akan menimbulkan pencemaran.
Agar konsep zero waste paripurna, lumpur sisa biogas diolah menjadi produk samping bernilai ekonomis. Sisa lumpur reaktor biogas dapat digunakan sebagai bahan pupuk padat dan cair, media pembiakan cacing, dan komponen pelet ikan. Rasio C/N dari lumpur tersebut lebih kecil dibandingkan kotoran segar sehingga baik digunakan sebagai pupuk.
Pupuk digunakan untuk tanaman pertanian, yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai pakan sapi. Padatan yang diperoleh dari sisa lumpur cair juga bisa digunakan sebagai media pembiakan cacing. Cacing tersebut dapat diolah sebagai bahan pakan bernilai gizi dan ekonomi tinggi.
Keluaran akhir dari reaktor hanya tinggal menyisakan fasa cair dengan kandungan organik rendah yang aman bagi lingkungan. Pengolahan sisa lumpur biogas diharapkan mampu menjadi alternatif pendapatan bagi para peternak sapi perah, sekaligus mengurangi pencemaran sungai. Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan Dr. Eng. Pramujo Widiatmoko (ketua), Dr. Jenny Rizkiana dan Dr. Ir. Dianika Lestari (anggota tim dari dosen) serta Ira Febrianty Sukmana, Hadi Mulya Anzhari, Nurul Siti Ramadini (asisten dan mahasiswa). Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada rentang waktu Maret sampai November 2021 di peternakan Adang Shalahuddin, Kampung Mekar Mulya RT 02/RW 24, Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan.
Kerja sama dilakukan dengan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan di Sungai Citarum melalui penerapan teknologi tepat guna berupa pembuatan pelet pupuk dan pakan ikan dengan memanfaatkan lumpur sisa biogas. Kegiatan ini bekerja sama dengan peternak sapi yang tergabung dalam Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan. Target utama kegiatan ini adalah pemasangan instalasi percontohan produksi pelet serta sosialisasi kegiatan tersebut untuk meningkatkan minat peternak.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan Himpunan Mahasiswa Teknik Bioenergi dan Kemurgi dalam rangka pengembangan desa binaan serta masuk dalam program MBKM ITB. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan harmonis antara ITB dan masyarakat di desa binaan sekaligus meningkatkan penghasilan dari peternak sapi.
Mesin pembuat pelet yang digunakan merupakan produk jadi yang ada di pasaran. Tim mengawasi instalasi dan uji coba mesin yang dilakukan sendiri oleh peternak. Untuk mendapatkan hasil maksimal, bahan organik lain ditambahkan. Formulasi bahan pembuatan pelet terdiri atas lumpur sisa pembuatan biogas, bubuk katul, dan daun-daunan. Bahan-bahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencetak untuk dijadikan pelet. Dari uji coba pemberian kepada ikan di kolam peternakan, ikan-ikan tersebut makannya jadi banyak. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas ikan.
Pengering pelet
Pelet yang baru dicetak biasanya memiliki kontur yang basah dan lembek sehingga gampang hancur. Menyiasatinya, tim merancang mesin pengering pelet menggunakan teknologi panas sinar matahari (panel surya). Panel surya dipasang di atas mesin pengering untuk mengoperasikan kipas pengering selama 24 jam sehingga waktu pengeringan lebih cepat. Simulasi dilakukan untuk mengetahui profil udara dalam pengering. Biasanya mesin pengering tersebut hanya memakai lemari dengan kipas yang mengalirkan udara. Tim kemudian memasang panel surya di atas lemari pengering untuk menggerakkan pengeringnya.***
Pemanfaatan Biogas di Pangalengan
PEMANFAATAN biogas dari limbah penting untuk menyediakan sumber energi lokal terbarukan di peternakan sapi perah. Metode ramah lingkungan ini bertujuan untuk mengurangi kandungan organik di limbah peternakan sapi perah. Dengan kandungan energi 4.800-6.700 kkal/m3, biogas adalah potensi untuk menggantikan gas bersubsidi untuk memasak, bahkan untuk pembangkit listrik dalam pertanian mandiri energi. Data International Renewable Energy Agency (2020) menunjukkan bahwa produsen biogas terbesar di dunia adalah Amerika Serikat dengan kapasitas 2368 MW. Di Asia, Cina menjadi yang teratas dengan biogas kapasitas 799 MW. Di Indonesia, biogas telah diperkenalkan sejak tahun 1970-an. Pemanfaatannya dipercepat pada tahun 1981 selama proyek pengembangan biogas yang didanai oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO). Pada 2019, kapasitas biogas Indonesia mencapai 22 MW.
Kapasitasnya sama sejak 2015, yang menunjukkan perlambatan pada instalasi biogas. Sementara itu, Masterplan Energi Nasional (Rencana Umum Energi Nasional, RUEN) mengamanatkan kontribusi bioenergi 5,5 GW pada energi baru dan bauran energi terbarukan dan khususnya 489,8 miliar metrik kubik sebagai biogas pada tahun 2025. Data menunjukkan bahwa realisasi target 2019 hanya 25,67 miliar metrik kubik. Oleh karena itu, perlu dilakukan percepatan kembali pemanfaatan biogas.
Sebagai sentra peternakan sapi perah, Pangalengan dan Lembang di wilayah Bandung, Jawa Barat, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk pemanfaatan biogas. Daerah Pangalengan dikenal sebagai peternakan sapi perah paling awal di Barat wilayah Jawa. Salah satu program yang diinisiasi oleh Kementerian ESDM dan Hivos (organisasi pembangunan nonpemerintah Belanda) yaitu melalui program Biogas Rumah (BIRU) telah berhasil membangun 25.157 unit bidogester dan lebih dari 119 ribu orang telah merasakan manfaatnya. Sejak diluncurkan 2009, program ini diharapkan akan terus berjalan menuju target 1 juta biodigester.
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu sasaran program BIRU. Dari 24 Oktober 2009 hingga Februari 2015, telah terpasang 1.283 reaktor di Provinsi Jawa Barat (dari total 14.173 instalasi). Distribusi reaktor tersebut termasuk peternak sapi perah dari KPSBU Lembang Bandung Barat, KPGS Cikajang Garut Selatan, KUD Tanjungsari Sumedang, KPS Gunung Gede Pangrango Sukabumi, dan lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok, Serang Banten, Cariu, dan Bekasi.
Pada semester pertama 2017, program BIRU melaporkan tiga kerja sama yang secara aktif memberikan dukungan keuangan untuk biogas instalasi reaktor, yaitu Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU), Koperasi Peternak Sapi Cianjur Utara (KPSCU), dan Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS). Di wilayah Pangalengan, program BIRU secara signifikan meningkatkan adopsi biogas.
206 / Teknologi Pelestari
Biogas yang dihasilkan digunakan untuk menggantikan kayu bakar, minyak tanah, dan penerangan di pertanian dengan potensi penghematan hingga Rp2 juta per tahun.
Pada tahun 2009, adalah melaporkan bahwa 7 petani di Pangalengan telah menerima reaktor biogas dari pemerintah. BIRU Program tahun 2017 juga bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta II, Pangalengan untuk pemasangan fixed dome reaktor biogas beton.
Menyusul proyek besar pemerintah tersebut, reaktor biogas sporadis dipasang di kawasan Pangalengan. Pada tahun 1994, Adisasmito dan Sukandar memasang reaktor biogas fixed dome beton di Unit Usaha Swa Karya Kartika, Pangalengan. Dengan volume 33 m3, reaktor menangani kotoran dari 50 sapi perah. Biogas yang dihasilkan digunakan untuk menggantikan kayu bakar, minyak tanah, dan penerangan di pertanian dengan potensi penghematan hingga Rp2 juta per tahun.
Hingga tahun 2000-an, belum ada peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan biogas karena ketersediaan kayu dan minyak tanah bersubsidi. Namun, kenaikan harga minyak tanah akibat krisis ekonomi membuat biogas menjadi alternatif yang menarik. Antara tahun 2002 hingga 2004, berbagai organisasi mengembangkan dan memasang instalasi biogas. Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjadjaran mengembangkan dan memasang digester kantong plastik
di Pangangalengan. Digester terdiri atas digester plastik 4 m3 dan penampung gas plastik 2,5 m3.
Pada tahun 2003, sebuah start-up bisnis di bawah Pusat Inkubator Bisnis Institut Teknologi Bandung, Cipta Tani Lestari, berupaya mempercepat pemasangan reaktor biogas berbasis plastik di kawasan Pangalengan. Kantong plastik digester dipilih karena biaya modal yang rendah yang cocok untuk petani. Dari tahun 2003 hingga 2005, mereka telah memasang sekitar 35 reaktor. Meskipun biaya instalasi rendah, reaktor berbahan dasar plastik mudah rusak.
Oleh karena itu, Cipta Tani Lestari mengembangkan reaktor berbasis fiberglass terkenal yang dikenal sebagai reaktor biogas Tenari. Tercatat dari tahun 2006 hingga 2011 terdapat 796 reaktor yang terpasang di Kabupaten Bandung melalui pendanaan pemerintah, antara lain di Kecamatan Arjasari, Cilengkrang, Pasirjambu, Ciwidey, Kertasari dan Pangalengan. Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Energi dan Pertambangan telah memasang 750 pembangkit biogas hingga akhir tahun 2007. Pada pertengahan 2008, sebanyak 369 pembangkit biogas lainnya telah diinstalasi.***
Teknologi Pelestari / 207

Kelapa untuk Mandiri Energi
 Dr. Arno Adi Kuntoro
Dr. Arno Adi Kuntoro
Mengantisipasi kelangkaan energi, pemerintah terus mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensinya sangat melimpah di Indonesia yaitu biomassa. Penggunaan EBT dari biomassa yang berasal selaras dengan tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), infrastruktur, industri, dan inovasi (SDG 9), serta energi bersih dan terjangkau (SDG 7).
BIOMASSA yang digunakan sebagai sumber energi di Indonesia pada umumnya memiliki nilai ekonomis rendah atau merupakan limbah yang telah diambil produk primernya. Biomassa tersebut dapat berasal dari tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak.
Dalam laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa potensi sumber daya biomassa di Indonesia diperkirakan sebanyak 49.810 MW yang berasal dari tanaman dan limbah. Potensi besar biomassa yang ada untuk energi saat ini adalah limbah hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa, dan tebu serta limbah hasil hutan, seperti limbah gergajian dan limbah produksi kayu.
Salah satu provinsi di Indonesia yang fokus dalam pengembangan energi baru terbarukan adalah Bali. Pemerintah Provinsi Bali memiliki visi dan misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Salah satu capaian dalam visi dan misi yakni mewujudkan energi bersih dan mandiri di Pulau Dewata.
Pemerintah Bali bertekad selain untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan energi harus berdasarkan pada keseimbangan serta keharmonisan manusia dan alam di Bali. Artinya, sumber-sumber energi dikembangkan dalam konsep energi yang ramah lingkungan, energi baru dan terbarukan alias green energy.
Potensi biomassa tumbuhan sejauh ini belum termanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi terbarukan. Salah satu tanaman yang potensial sebagai sumber bioenergi ialah kelapa (Cocos nucifera). Berdasarkan data statistik perkebunan Indonesia tahun 2019-2021, produksi kelapa di Provinsi Bali mencapai sekitar 67 ribu ton per tahun dengan luas lahan perkebunan kelapa sekitar 71 ribu hektare.
Untuk mendukung visi misi Provinsi Bali tersebut, Pusat Pengembangan Sumber Daya Air (PPSDA) yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat (LPPM) ITB melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendorong pemanfaatan komoditas kelapa secara terpadu sebagai sumber energi biomassa terbarukan dan produk turunan lain yang menunjang ketahanan pangan.
Bermitra dengan Insan Bisnis dan Industri Manufaktur (Ibima), tim menyelenggarakan pengabdian masyarakat di Desa Bantiran, Kabupaten Tabanan. Acara ini diselenggarakan selama dua hari (28-29 Agustus 2021) diikuti peserta dari tiga desa, yakni Belimbing, Bantiran, dan Pupuan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian Masyarakat skema bottom-up LPPM ITB dengan ketua tim pelaksana Dr. Eng. Arno Adi Kuntoro, S.T., M.T. dari KK Teknik Sumber Daya Air, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan serta anggota utama Prof. I Nyoman Pugeg Aryantha, Ph.D.
Bali dipilih karena merupakan salah satu provinsi yang sumber energinya disuplai dari pulau lain. Listriknya sebagian besar disuplai dari Pulau Jawa. Sementara, Indonesia merupakan daerah rawan bencana, seperti bencana geologi, gempa, tsunami. Jika sewaktu-waktu bencana tersebut terjadi, ada bahaya sangat besar yang mengancam ketersediaan energi di Bali. Hal itu disebabkan suplai energi tersebut dialirkan lewat kabel bawah laut. Untuk itu, ada upaya menjadikan Bali mandiri energi dan bersih.
Sementara pemilihan biomassa karena kaitannya erat dengan Bali. Bali mempunyai budaya yang unik sebagai tempat tujuan wisata. Secara visual, tujuan wisatawan ke Bali adalah mencari tempat yang indah sehingga tidak
memungkinkan membuat area yang luas untuk hutan tanaman industri.
Bali juga mempunyai keunikan, yaitu tempat yang ikatan adatnya kuat di level desa. Bahkan, di Bali ada desa adat. Keunikan-keunikan ini yang akhirnya memunculkan ide kalau misalkan upaya untuk menyediakan energi baru terbarukan didukung mulai dari tingkat bawah, ini kesinambungannya bisa menjadi lebih baik.
Sebenarnya banyak pilihan vegetasi untuk dijadikan sebagai sumber energi. Ada tanaman yang secara umum produksinya cepat dan kalau dibakar kalori yang dihasilkannya besar. Namun, untuk Bali yang tidak mempunyai lahan cukup luas untuk melakukan hal tersebut, pilihan yang paling tepat adalah memaksimalkan potensi kelapa.
Kelapa merupakan tanaman keseharian. Kelapa memiliki nilai strategis yang dapat menunjang berbagai sektor kehidupan. Kelapa tidak membutuhkan pembukaan lahan baru karena dapat ditanam di pematang sawah, tumpang sari di perkebunan palawija, dan lahan-lahan lain yang masih ada ruang kosong secara ko-lokasi.
Penanaman kelapa secara ko-lokasi dengan perencanaan tata ruang yang tepat dan asri akan menjadi daya tarik pemandangan tersendiri bagi wisatawan sekaligus dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.
Dilihat dari kecocokan, kelapa juga ideal ditanam di lahan yang agak rendah. Untuk Indonesia secara umum cocok. Setiap bagian kelapa juga bisa dimanfaatkan. Namun, jika melihat kelapa sebagai sumber energi listrik atau rumah tangga saja, tidak terlalu ekonomis. Oleh karena itu, ada upaya bagaimana kelapa ini diolah dari hulu sampai hilir agar bisa dimaksimalkan manfaat lainnya. Untuk menunjang energi baru terbarukan perlu optimalisasi tidak hanya ke bentuk energi, tetapi juga diolah jadi produk lain yang bermanfaat banyak. Selain itu, bagaimana teknologinya cukup mudah sehingga bisa diaplikasikan ke masyarakat umum dan level desa yang memiliki komunitas. Kalau dijadikan kebijakan umum, bisa dilaksanakan secara kontinu. Pemanfaatan kelapa sebagai sumber energi terbarukan dapat lebih berkesinambungan jika dibarengi dengan pemanfaatan produk turunan kelapa yang lain. Pelatihan pemanfaatan kelapa ini terbagi menjadi beberapa segmen, mulai dari pembuatan virgin coconut oil (VCO) dan minyak goreng dari daging kelapa, budi daya magot Black Soldier Fly (BSF) dari ampas kelapa, produksi pupuk cair hayati dari air kelapa, pembuatan cocochip untuk bahan bakar kompor rumah tangga beserta demonstrasi aplikasinya, pembuatan cocofiber dari sabut kelapa dan cocopeat sebagai media tanam pertanian dari pemisahan serat cocofiber.
Di tempat pelatihan ini akan dijalankan program proyek percontohan bersama IBIMA. Hal ini agar masyarakat yang berminat bisa menindaklanjutinya secara berkolaborasi. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata mengenai aplikasi pengolahan kelapa secara terpadu yang dapat dijalankan oleh masyarakat Bali secara umum dalam skema UKM atau BUMDes, tentunya dengan dukungan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Dengan gerakan pengolahan kelapa terpadu secara massal, terlebih lagi berbasis Desa Adat Pekraman, diharapkan kemandirian energi dan ketahanan pangan di Bali dalam jangka panjang bisa diwujudkan.
Pada akhir penutupan acara pelatihan dilakukan penyerahan lima bibit kelapa hibrida secara simbolik kepada setiap peserta. Nantinya para peserta dapat menanam bibit tersebut di pekarangan rumah masingmasing sebagai wujud kesungguhan untuk mendukung dan meneruskan program.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemanfaatan produk kelapa secara terpadu dapat lebih ditingkatkan, sehingga dapat berkontribusi nyata terhadap pengembangan sektor ekonomi, pangan, dan energi, khususnya di Provinsi Bali.***
Pengembangan EBT dari Produk Turunan Kelapa
POHON kelapa dikenal sebagai tumbuhan paling serbaguna. Setiap bagiannya memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Buah, daging, air, dan cangkang/batok semua bisa digunakan untuk beragam keperluan. Namun, kalau dimanfaatkan untuk sumber energi, hanya cangkang atau batang yang sudah tua yang bisa digunakan. Bisa dibayangkan, untuk dikonversi menjadi energi listrik, berapa banyak cangkang kelapa yang mesti digunakan.
Akan tetapi, dari sisi produk turunan lain, kelapa bisa bisa lebih bermanfaat. Buah kelapa bisa dijadikan santan yang kemudian diolah menjadi VCO dan minyak kelapa. Hal ini berkontribusi positif bagi isu lingkungan. Bagi Bali misalnya, dengan mendeklarasikan sebagai produsen minyak kelapa bukan kelapa sawit bisa meningkatkan statusnya sebagai kota pariwisata yang hijau dan ramah lingkungan. Selama ini, pemakaian kelapa sawit untuk bahan baku minyak memiliki citra kurang baik terkait dengan kerusakan lingkungan.
Walaupun yang dihasilkan sedikit, harga jual VCO minyak kelapa tergolong tinggi. Jika dikolektifkan, bisa menjadi usaha tingkat desa. Masing-masing rumah tangga memiliki penyalur dan penampung. Sementara, minyak kelapa yang dihasilkan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga mengurangi pemakaian minyak sawit. Ampas kelapa sisa perasan santan kalau digunakan untuk pakan Black Soldier Fly (BSF), magotnya menjadi bagus. Hal itu karena kelapa memiliki protein tinggi, jauh lebih baik ketimbang sisa sayur/sampah.
Selain itu, ampas tersebut bisa diproduksi menjadi pakan ikan dan pakan bebek sehingga berkontribusi positif bagi para peternak. Kebutuhan protein masyarakat juga terbantu sehingga berkontribusi juga terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara, air kelapa setelah ditambah bakteri dan diinkubasi akan menjadi pupuk cair. Pupuk cair dari air kelapa bisa mengurangi pemakaian pupuk kimia dalam keseharian sehingga lebih ramah lingkungan.Untuk cangkangnya, setelah dipecah menjadi potongan kecil dipakai untuk bahan bakar kompor rumah tangga sehingga mengurangi pemakaian elpiji.
Tim ITB mengadakan pelatihan pemanfaatan kelapa bagi masyarakat dari tiga desa di Kabupaten Tabanan, Bali. Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 15 peserta dari Desa Belimbing, Bantiran, dan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok.
Peserta mendapatkan pelatihan mengenai pembuatan minyak VCO dan minyak goreng dari daging kelapa, budi daya magot Black Soldier Fly (BSF) dari ampas kelapa, produksi pupuk cair hayati dari air kelapa, pembuatan cocochip untuk bahan bakar kompor rumah tangga beserta demonstrasi aplikasinya, pembuatan cocofiber dari sabut kelapa, dan cocopeat sebagai media tanam pertanian dari pemisahan serat cocofiber

Pembuatan VCO dan minyak kelapa
Untuk pembuatan VCO dan minyak kelapa, mekanisme kerja produksinya adalah pertama buah kelapa dipecahkan. Setelah itu, tempurung dikupas dan air kelapa dipisahkan pada tempat yang berbeda. Daging buah dibersihkan dengan air bersih yang mengalir.
Setelah itu daging buah dipotong sedang (sesuai dengan ukuran mesin) dan dimasukkan pada mesin parut untuk dihasilkan parutan kelapa. Parutan kelapa disatukan dalam wadah dan dimasukkan pada mesin peras (press) untuk dihasilkan santan. Mesin parut dan peras merupakan rancangan tim yang dibuat sedemikian rupa.
Setelah itu, santan yang sudah jadi dimasukkan ke tabung fermentasi kemudian bakteri asam laktat dimasukkan ke dalam tabung fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan wadah tertutup selama 6-12 jam.
Keran tabung fermentasi dibuka untuk dipisahkan airnya. Endapan minyak dimasak dengan pemanasan sesuai tujuan menggunakan kompor dan wajan dengan api kecil atau besar. Klengisan/belondo dipisahkan setelah menjadi kremesan. Pemanasan membutuhkan waktu bervariasi sesuai tujuan dan kuantitas. Setelah disaring, minyak dapat dikemas sesudah dingin.
Budi daya dan produksi pelet Black
Soldier Fly (BSF)
Alat yang dibutuhkan dalam proses ini adalah mesin pelet manual, baki plastik berlubang, love cage atau kandang lalat portabel. Sementara, untuk bahan membutuhkan telur BSF larva Instar 5-6 ambas sisa perasan santan. Mekanisme budi daya BSF adalah sebagai berikut, pertama-tama BSF dengan berbagai fase dimasukkan pada kandang yang sesuai.
Pakan larva BSF menggunakan ampas kelapa dari hasil sisa pemerasan santan produksi minyak kelapa. Ampas kelapa diberikan campuran probiotik dan cairan gula untuk meningkatkan nafsu makan larva. Larva diletakkan pada wadah/baki, sedangkan lalat dimasukkan pada kandang lalat dengan tersedia gantungan daun pisang kering sebagai tempat hinggap dan diberikan love cage untuk proses kawin larva serta diberikan air gula untuk minum tambahan.
Mekanisme pembuatan pelet protein, Instar 5-6 larva dimasukkan ke penggilingan pelet manual dan dapat dicampurkan dengan klengisan/belondo hasil penggorengan minyak kelapa. Setelah proses penggilingan, hasil pelet dapat dipisahkan dan dikering jemur untuk memperpanjang umur simpan pelet. Proses budi daya dikenalkan dengan fase-fase perkembangan lalat dan cara handling tiap fase.

Produk biofertilizer
Untuk pembuatan biofertilizer/pupuk cair hayati diperlukan bahan air kelapa, biji padi, biji kacang hijau, bintil akar, dan gula merah. Produksi biofertilizer dibagi menjadi dua fase utama, yaitu penyiapan starter dan produksi. Untuk starter disiapkan dengan memanfaatkan mikroba lokal pada bintil akar. Mekanisme kerja produksi biofertilizer, pertamatama biji padi dan kacang hijau dikecambahkan pada baki kecambah. Setelah itu kecambah padi dan tauge yang telah siap, dihancurkan dengan menggunakan blender dengan dicampurkan air. Untuk memisahkan ampas digunakan penyaring sehingga sari-sarinya bisa didapat. Ampas yang dihasilkan dapat dipakai pada sistem budi daya BSF. Campuran jus kecambah dicampurkan dengan gula merah yang telah larut dan siap untuk di masukkan dalam bioreaktor starter. Kemudian, ekstrak bintil akar yang telah disiapkan dimasukkan ke dalam bioreaktor starter. Bioreaktor disambungkan dengan pompa aerator. Proses inkubasi dilakukan selama 1-2 hari. Setelah itu starter siap dipakai produksi biofertilizer.
Produksi biofertilizer dilakukan secara aerob dengan menggunakan pompa submerged selama 7 hingga 12 hari setelah proses pencampuran dengan starter. Pada proses inkubasi dilakukan pengecekan pada pompa sesuai kapasitas produksi dan selang agar terhindar dari sumbatansumbatan yang mungkin terjadi. Setelah inkubasi selesai, pupuk dapat dipanen dengan cara menggunakan pompa atau keran yang tersedia. Hasil pupuk dapat dimasukkan pada kemasan dan ditutup rapat setelah produksi gas berhenti.
Produksi biofertilizer dibagi menjadi dua fase utama, yaitu penyiapan starter dan produksi. Untuk starter disiapkan dengan memanfaatkan mikroba lokal pada bintil akar.
Cocochips tempurung kelapa, bahan bakar alternatif
Batok kelapa atau tempurung kelapa merupakan limbah yang memiliki nilai ekonomi sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil seperti gas dan minyak tanah. Keunggulan lain pemanfaatan tempurung kelapa untuk bahan bakar alaternatif adalah panas yang dihasilkan pembakarannya sangat tinggi.
Pada pelatihan ini, untuk membuat cocochip dari tempurung kelapa dibutuhkan beberapa alat seperti mesin crusher, tempurung kelapa, serta kompor “Nurhuda”. Untuk membuat cocochips dibutuhkan tempurung yang kering. Tempurung dimasukkan dalam mesin crusher untuk dicacah hingga berupa chips disesuaikan dengan ukuran lubang kompor Nurhuda. Cocochips selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor Nurhuda. Semua proses pembuatan dibuat sesederhana mungkin. Dibawah kompor dilengkapi kipas kecil yang bisa mengatur besar kecilnya api yang dihasilkan.
Selain itu, pada pelatihan dikenalkan pula cara pembuatan cocofiber dari sabut kelapa dan cocopeat sebagai media tanam pertanian dari pemisahan serat cocofiber. Cara membuat cocofiber terbilang mudah karena hanya memisahkan antara serabut kelapa dan kulitnya.
Cocopeat didapat dari sabut kelapa yang dihaluskan sehingga menyerupai serbuk. Cocopeat merupakan media tanam alternatif yang bisa digunakan untuk budi daya berbagai jenis tanaman, khususnya hidroponik. Cocopeat memiliki sifat mudah menyerap dan menyimpan air. Ia juga memiliki poripori, yang memudahkan pertukaran udara, dan masuknya sinar matahari. Cocopeat mudah ditumbuhi trichoderma, jamur yang dapat mengurangi penyakit dalam tanah. Dengan demikian, cocopeat dapat menjaga tanah tahan penyakit disamping gembur dan subur. Semua pengolahan produk samping dari kelapa ini memiliki konsep biorefinery. Biorefinery dapat digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomi biomassa dan limbahnya menjadi sumber energi dan produk-produk bernilai tambah. Biorefinery dapat didefinisikan sebagai kegiatan industri yang kompleks, yang mengonversi bahan-bahan terbarukan (biomassa), menjadi serat, bahan-bahan kimia, bahan bakar, panas dan produk-produk lainnya dengan efek yang minimal atau tanpa efek sama sekali terhadap kelestarian lingkungan. Respons masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini sangat tinggi. Apalagi bahan dan alat yang digunakan tidak terlalu sulit didapat. Teknologi yang dipakai pun tidak terlalu canggih sehingga terjangkau oleh masyarakat. Untuk program yang dimulai dari bawah, program ini sangat cocok diterapkan di Bali. Dengan budayanya yang khas dan ikatan ketaatan adat yang tinggi, program ini sangat mungkin berhasil dijalankan di Bali.***

Menjaring Energi Matahari


Miga Magenika Julian, M.T.
Pandemi COVID-19 menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan pendapatan. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi dalam pengembangan usaha membantu perwujudan tujuan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), energi bersih dan terjangkau (SDG 7), serta infrastruktur, dan industri, dan inovasi (SDG 9).
KEBUTUHAN operasional bagi UMKM semula tidak terasa berat. Akan tetapi, menurunkan pendapatan secara drastis membuat para pelaku usaha kepayahan menanggung beban operasional.
Berangkat dari niatan membantu masyarakat bangkit dari kemerosotan ekonomi, peneliti Institut Teknologi Bandung Miga Magenika Julian, S.T., M.T. dari Kelompok Keahlian Hidrografi melaksanakan pengabdian masyarakat berupa pemasangan instalasi sistem energi surya di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Instalasi ini dipasang di rumah produksi makaroni goreng “Mamimut” yang berlokasi di Desa Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pengabdian masyarakat ini merupakan kolaborasi antara peneliti ITB dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Ide dasarnya sederhana saja. Pelaku UMKM dibantu untuk memasang solar panel sehingga bisa memanfaatkan
matahari sebagai sumber energi. Listrik yang diperlukan untuk semua proses produksi dipasok oleh tenaga surya. Teknologi solar panel, meski belum digunakan secara masal, relatif sudah banyak diketahui. Hal yang membedakan proyek ini dengan instalasi solar panel lainnya ialah bagaimana peneliti memanfaatkan data iklim global untuk memasang instalasi tenaga surya.
Indonesia sendiri memiliki banyak potensi energi terbarukan, seperti matahari, panas bumi, angin, biomassa, dan laut. Dari kajian dan pemetaan, akhirnya dipilih matahari untuk dijadikan sebagai sumber energi terbarukan di rumah produksi makaroni goreng “Mamimut” di Indramayu. Secara teknologi, instalasi solar panel untuk membangkitkan energi matahari tidak terlalu mahal. Pemasangannya pun tidak terlalu sulit. Tinggal mempertimbangkan kemiringan dan penempatan agar sinar matahari yang ditangkap bisa optimal.
Pemilihan energi matahari ini juga membawa misi untuk memperkenalkan sumber energi terbarukan kepada masyarakat. Informasi tentang energi terbarukan memang sudah mulai banyak dan masyarakat dengan mudah mengaksesnya. Akan tetapi, lewat pengalaman langsung menggunakan energi matahari sebagai sumber listrik diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan energi bersih. Masyarakat dapat memanfaatkan energi dari alam sekaligus menjaga lingkungan. Sebelum melakukan perancangan dan pemasangan instalasi solar panel, terlebih dahulu dilakukan pemetaan potensi radiasi matahari menggunakan data iklim global. Data ini untuk melihat seberapa besar potensi energi matahari yang tersedia. Data tersebut berupa tren potensi radiasi matahari selama 30 tahun ke belakang, estimasi radiasi bulanan dan harian. Estimasi radiasi bulanan menunjukkan, secara umum potensi hariannya menunjukkan 11-12 jam sehari. Radiasi paling tinggi terjadi sekitar pukul 12.00-13.00. Potensi sinar matahari paling tinggi berada pada rentang Juni hingga Oktober. Potensinya 120-160 kWh setiap meter persegi.
Berbekal hasil pemodelan data iklim global tersebut, tim peneliti memasang tiga solar panel di lokasi. Tim peneliti menghitung pada posisi mana dan kemiringan berapakah solar panel tersebut harus diletakkan sehingga potensi bisa dimanfaatkan maksimal. Selanjutnya dirancang desain solar panel seperti apa yang akan dipasang.
Tim dari ITS bertanggung jawab pada pemilihan teknologi yang tepat dengan kondisi di lokasi. Solar panel yang dipasang merupakan pilihan tim setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Selain teknologi, aspek kemudahan perawatan dan pemeliharaan juga menjadi pertimbangan.
Tiga solar panel yang dipasang tersebut menghasilkan daya listrik 1.300 watt. Daya tersebut setara dengan kebutuhan rumah tangga kelas menengah.
Solar panel yang dipasang merupakan tipe off grid atau tidak terhubung dengan jaringan PLN sehingga kelebihan listrik yang diproduksi tidak bisa dijual ke PLN. Pemilihan off grid ketimbang on grid ini karena instalasi ini baru kali pertama dipasang di Indramayu. Alat yang dipasang dirancang untuk bisa digunakan sampai 10 tahun.
Mahasiswa dan tim peneliti juga memberi pendampingan terkait cara merawat instalasi dan peralatannya. Perawatan solar panel ini penting agar performanya sesuai dengan yang diharapkan dan tahan lama. Harapannya, meski program ini telah usai, pelaku usaha bisa melakukan perawatan sendiri.
Sampai saat ini, pelaku usaha masih harus melaporkan perkembangan pemanfaatan tenaga surya ini. Pelaku diwajibkan mengisi formulir digital untuk memantau seberapa banyak produksi listrik setiap bulannya serta memantau berapa penurunan biaya listrik yang dicapai.
Menekan biaya produksi
Di rumah produksi makaroni goreng “Mamimut”, listrik merupakan infrastruktur penting. Beberapa alat produksi dioperasikan menggunakan listrik. Selain untuk penerangan, listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan alat peniris. Setelah digoreng, makaroni ditiriskan menggunakan alat khusus. Alat untuk mengemas makaroni juga menggunakan listrik.
Selain kebutuhan produksi, listrik juga diperlukan untuk pemasaran digital. Pemasaran lewat lokapasar (marketplace) dan saluran online lainnya memerlukan gambar-gambar desain untuk kebutuhan digital marketing.
Seluruh perangkat memerlukan daya listrik.
Setiap bulan biaya yang diperlukan untuk membayar tagihan listrik berada di kisaran Rp300.000 hingga Rp350.000. Setelah memanfaatkan tenaga matahari, biaya listrik ini baru menurun pada bulan ketiga atau mulai terlihat pada Desember 2021 setelah instalasi terpasang pada September 2021. Artinya, pelaku usaha bisa menghemat pengeluaran sekitar Rp100.000 setiap bulan.
COVID-19 menjadi pukulan telak bagi perekonomian Indonesia, termasuk UMKM. Omzet menurun tajam karena pelaku usaha kesulitan menjual barangnya. Pelajar sekolah selama ini menjadi pasar besar makaroni “Mamimut”. Pada awal pandemi, mobilitas masyarakat dibatasi. Aktivitas di sekolah ditiadakan. Semua kegiatan dilakuan dari rumah. Pasar makaroni “Mamimut” seolah menghilang. Upaya untuk mencari dan mengoptimalkan pasar lain tentu perlu waktu. Oleh karena itu, penghematan sekecil apa pun akan meringankan biaya produksi. Pemanfaatan energi tenaga surya bisa menekan biaya produksi sehingga pelaku usaha bisa terhindar dari kerugian.
Desember 2021 setelah instalasi terpasang pada September 2021.
Setelah memanfaatkan tenaga matahari, biaya listrik ini baru menurun pada bulan ketiga atau mulai terlihat pada
Nilai keekonomian
Secara umum, seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi sumber energi matahari. Sebagai negara tropis dengan dua musim, paparan sinar matahari bisa berlangsung selama enam bulan penuh. Dari data global, potensi terbesar berada di wilayah Indonesia bagian timur. Kondisi ini membuat tenaga surya bisa dikembangkan hampir di seluruh kawasan Indonesia.
Masyarakat sendiri sebenarnya tidak terlalu asing dengan pembangkit tenaga listrik tenaga surya. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang masih meragukan nilai keekonomiannya. Perlu biaya besar untuk memasang instalasinya. Tiga solar panel yang dipasang di rumah produksi makaroni goreng “Mamimut” membutuhkan biaya Rp35 juta. Jika masyarakat ingin memasangnya sendiri, setidaknya harus siap biaya sebesar itu. Sementara, penghematan biaya dari pemasangan instalasi ini “hanya” Rp100.000.
Modal awal yang tergolong tinggi ini yang masih menghalangi masyarakat mengganti sumber listriknya dengan tenaga matahari. Bagi masyarakat yang berada di wilayah yang sudah terlayani listrik, harga tenaga surya kurang bersaing. Hal ini tentu akan berbeda dengan daerah yang belum tersentuh layanan listrik.
Beruntung pemilik usaha makaroni goreng “Mamimut”, Adi Setia Perwira tergolong masyarakat yang memiliki kesadaran pentingnya mencoba sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Kesadaran dan keterbukaan pada gagasan mutakhir semacam ini yang membuatnya bersedia menjajal memproduksi listrik dari radiasi matahari.
Masyarakat sekitar juga memberi dukungannya. Pemasangan solar panel di sana mendorong masyarakat sekitar untuk mencari tahu lebih banyak soal pembangkit listrik tenaga surya ini. Meski saat ini pemanfaatannya masih sebatas untuk rumah produksi “Mamimut”, tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan pada masa yang akan datang. Misalnya untuk keperluan komunal seperti penerangan jalan umum, balai desa, dan lainnya.
Meski saat ini masih terbilang mahal, teknologi solar panel akan semakin berkembang dan semakin murah. Seiring meningkatkan kesadaran global akan krisis iklim, akan mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Harganya akan ditekan semakin murah agar bisa digunakan oleh lebih banyak orang. Di masa yang akan datang, bisa jadi solar panel yang terpasang di setiap rumah menjadi hal yang biasa.
Rencana lanjutan
Pemanasan global telah menjadi perhatian seluruh warga dunia. Para ilmuwan mengembangkan riset untuk mengatasi krisis iklim ini. Termasuk penelitian tentang apakah peningkatan suhu bumi ini berpengaruh positif pada penyinaran matahari yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya.
Riset tentang pemanfaatan tenaga surya ini masih akan dilanjutkan. Tawaran dari kampus asing datang untuk melakukan riset pemetaan tenaga surya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang belum teraliri listrik.
Di daerah terpencil, PLN kesulitan menghadirkan listrik. Jaringan PLN belum bisa menjangkau daerah-daerah tersebut. Tenaga surya menjadi alternatif solusi menghadirkan nyala di lokasi-lokasi sulit. Tantangannya berada pada biaya transportasi ke lokasi untuk mengirim berbagai bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk instalasi.
Tim peneliti bertekad mengembangkan penelitian lanjutan yang bertujuan memetakan seluruh potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia sehingga nantinya setiap daerah tidak harus diseragamkan pada sumber energi tertentu. Bergantung pada potensi yang dimiliki, apakah air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, atau bahkan biomassa.
Sampai saat ini, baru energi air dan surya yang mendapat perhatian cukup besar. Sementara, sumber energi lainnya belum terpetakan dengan baik.
Kunci keberhasilan riset ini salah satunya terletak pada kolaborasi apik antara peneliti ITB dan ITS. Tidak hanya lintas kampus, tetapi juga lintas ilmu. Keterlibatan peneliti Teknik Fisika ITS memperkuat tim, utamanya di sisi teknis pemilihan alat dan perancangan instalasi.
Kerja sama riset pengabdian masyarakat ini sebelumnya juga pernah dilakukan di Banyuwangi. Lalu dilanjutkan di Indramayu. Kerja sama semacam ini memungkinkan terjadinya sharing knowledge. Pembelajaran di lapangan jadi lebih komprehensif. Mahasiswa yang terlibat juga mendapat kesempatan untuk memperluas jaringan.
Program pemasangan instalasi pembangkit tenaga surya ini bisa menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lain. Selain menghemat biaya, juga untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Tentu saja tidak semua harus menggunakan energi matahari. Energi apa yang akan digunakan, disesuaikan dengan kondisinya. Lokasi di pada penduduk, bisa menerapkan instalasi ini. Bagi daerah yang sering hujan, atau berada pada daerah dengan kemiringan tertentu, bisa jadi lebih cocok menggunakan pembangkit listrik tenaga air.***

