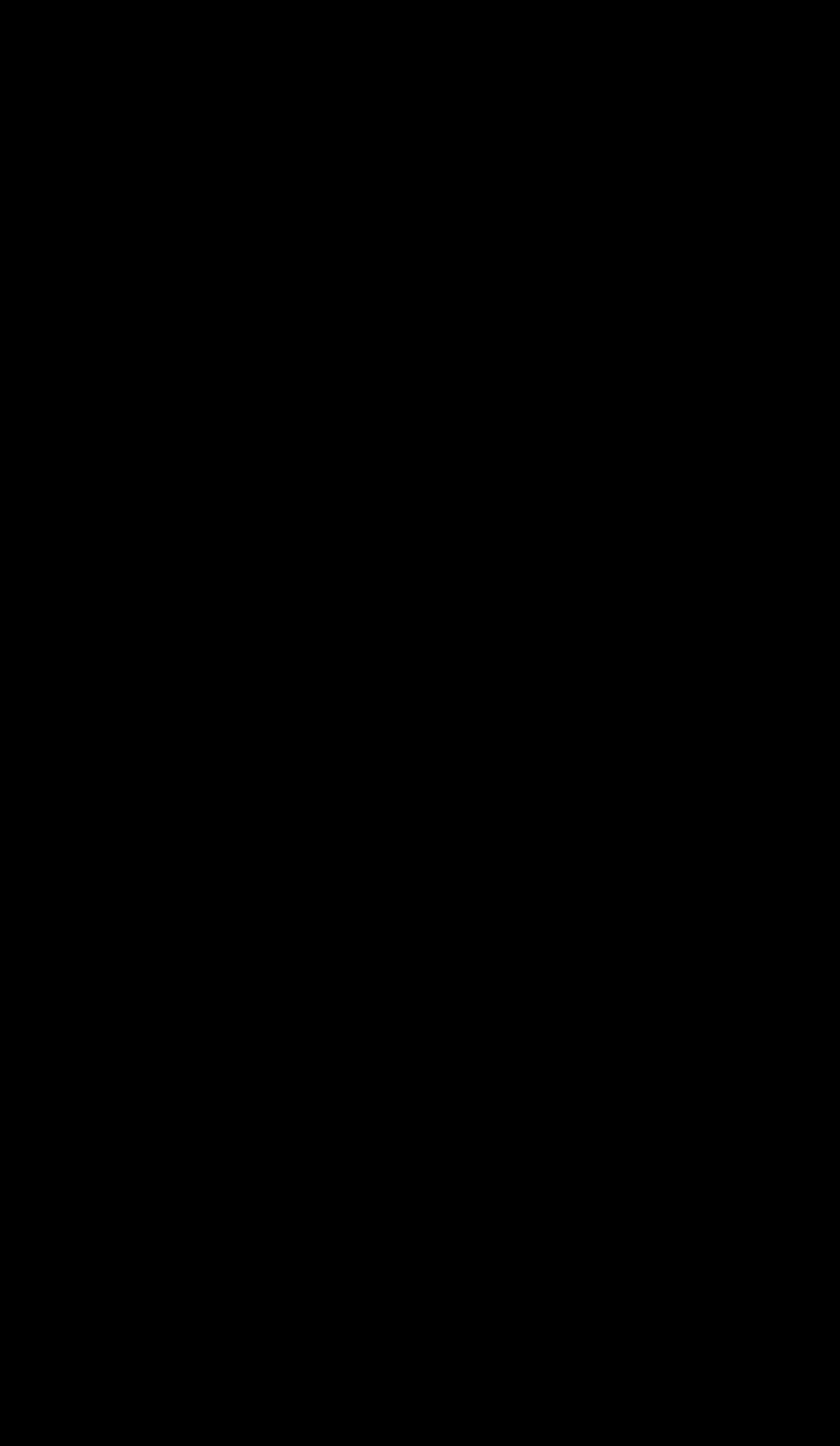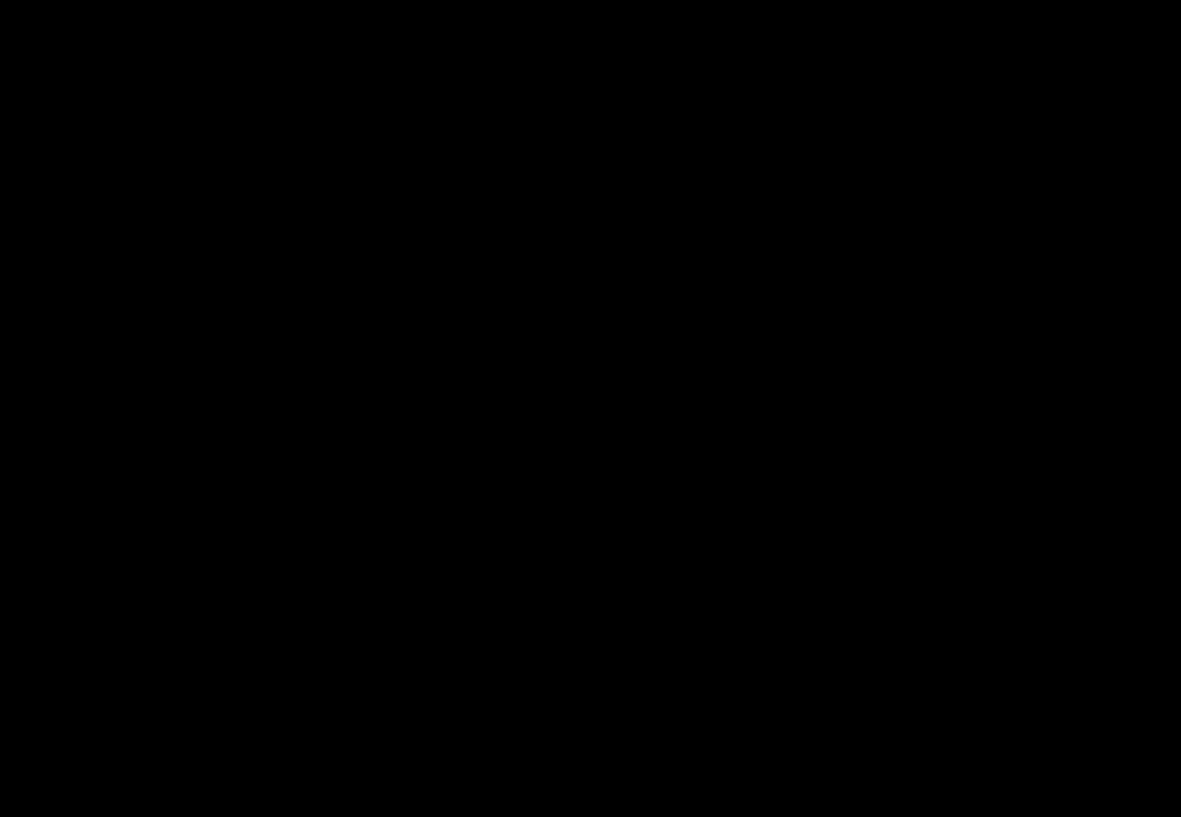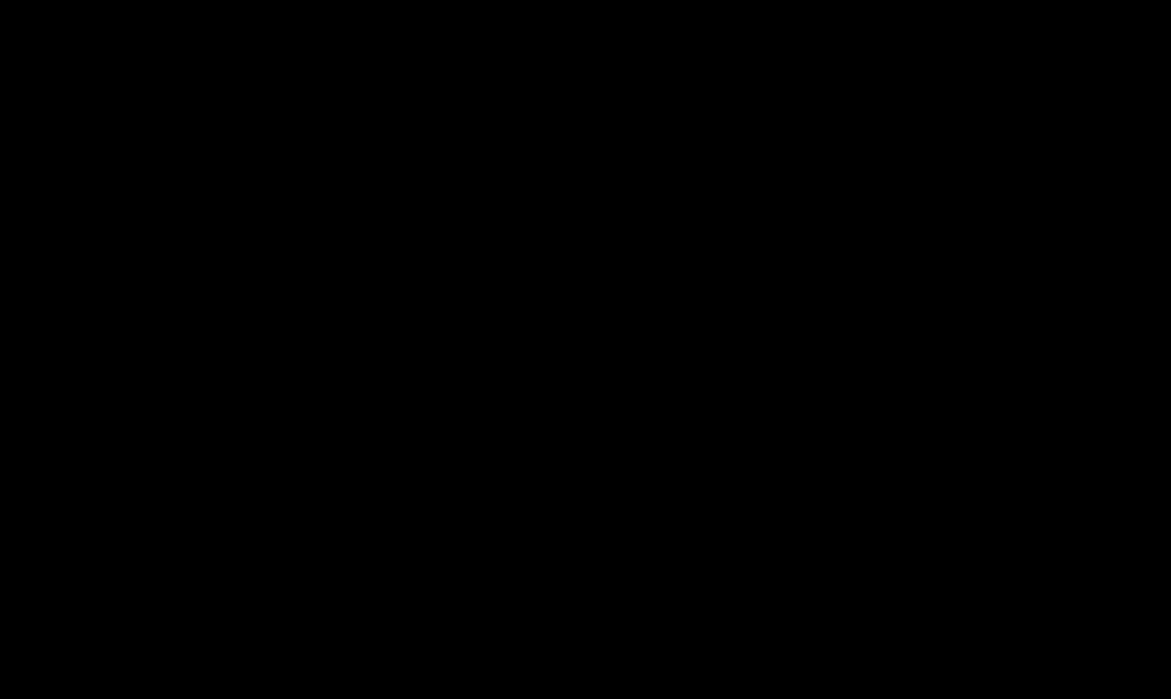10 minute read
Menghapus Hujan
oleh PKPS
Ketika itu matahari mulai pergi dan digantikan teman-temannya yang telah lebih jauh diserakkan masa lalu. Titik-titik cahaya itu berkelip pelan dan damai bahkan sanggup menjelma sebagai nada-nada tinggi nan harmonis yang berasal dari kotak musik seorang gadis. Bersama dengan mereka, pun di sana ada bulan yang menyembunyikan dirinya di balik bayang-bayang takdir sebagaimana tertulis di kitab-kitab ilmu pengetahuan. Juga dengan segala mantra dan pesona yang tertuang di dalam kitab-kitab itu, mam pulah manusia meramal bagaimana malam ini akan berlaku. Lalu turunlah titik-titik air membasahi semua yang ada di atas tanah dan ranah. Menyusuri dedaunan kerbang lagi tak lupa dengan lengkungan gerbang. Hingga akhirnya berhimpun mengisi ruang-ruang kosong di bawah sana. Lalu, kapankah semua ini bisa berakhir? Bolehkah sebentar lagi saja?
Advertisement
Hujan pun belum reda.
Sorot cahaya kuning menabrak jejeran batang-batang besi di hadapannya. Klakson dibunyikan panjang dua kali berjuang mengalahkan gemuruh angin di luar kaca mobil. Seperti suara suling yang memanggil ular kobra untuk menari, muncullah siluet seorang pria dari samping dan membukakan gerbang pada tembakan klakson yang ketiga. Tebakanku dia adalah satpam penjaga rumah ini dan tentu saja itu benar. Klakson lagi dibunyikan pendek sebagai pengganti ucapan terima kasih kepada si Bapak Satpam. “Yooo...”, sahut si Bapak Satpam dengan agak ceria di tengah bisingnya hujan. Seketika, kedua ujung bibir temanku naik. Giginya mulai kelihatan ketika ia menengok kaca spion yang memperlihatkan Bapak Satpam yang langsung menutup gerbang dengan buru-buru. Terbirit-birit dia menuju ruangannya di dekat situ lalu melepas jas hujannya. Temanku ini pun tak kuasa lagi menahan tawa kecilnya. Entahlah, suasana hatinya benar-benar gembira sejak tadi. Sejak tadi kali pertama kami bertemu di bar. Bar selalu menjadi tempat bagiku bertatap muka dengan teman-teman daringku. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang baru kukenal dan langsung ingin bertemu. Salah satunya adalah Raku, begitu dia memperkenalkan dirinya. Dia yang lebih dulu menghubungiku setelah mengetahui jasa yang bisa kuberikan kepada mereka yang menginginkannya. Tidak sulit pula menemukan seorang anak muda yang memakai jaket biru gerau dengan kemeja biru langit serta celana jin biru dongker. Sepatu putihnya yang sudah lama tidak dicuci sehingga memiliki bercak noda di beberapa tempat mengayun-ayun di kaki meja. Bukan pertama kali sebenarnya bagiku, tapi tetap aku sedikit terkejut dan juga prihatin melihat ruwet raut mukanya. “Aku menginginkannya,” ujarnya di saat aku bahkan belum sempat duduk. Aku terdiam menyaksikan perubahan rona wajahnya yang tiba-tiba berseri. “Aku selalu gagal mencobanya sendiri. Temanilah aku malam ini,” lanjutnya dengan sedikit mengotot. Badannya agak condong ke depan dan matanya sedikit melotot. Tak sedikit pun aku heran karena mereka memang selalu seperti ini. Aku pun hanya tersenyum ramah. Ya, biarkan aku menemanimu malam ini.
Lalu udara pun tega memerangi saudaranya sendiri. Saling menghempas di awang-awang, saling membantai di bentang langit. Sang angin pun tak jemu mengamuk hebat menyaksikan pertengkaran alot di penjuru jumantara. Gelegarnya terlempar ke sana lalu kemari. Gemuruhnya terhampar ke buana juga ke mentari. Badai semakin hebat, hujan pun kian lebat. Tetesan air tak henti-hentinya menyerbu setiap jengkal raganya, mulai dari
dedaunan yang baru saja terlepas sampai lekuk guratan yang terselubung. Perlahan ia pun mulai goyah merasakan betapa gigih mereka menerpa dan menerjang. Siapalah aku, katanya, yang saban hari hanya mampu memercayai satu-satunya akarku yang terpendam? Lalu akhirnya ia terjungkal dan terdampar di bentala sebab tak berdaya menahan serangan mara bahaya cakrawala. Oh, racau batinnya, sudahkah semua ini berakhir? Namun, mengapa aku masih mendengar siulan nyaring di sudut sana?
Hujan pun belum reda. Decit dan gesekan ban berbunyi cukup keras hingga terdengar oleh kami yang berada di dalam mobil. Hening kemudian mengisi ruang kosong di antara kami dan saling terdengarlah hembusan nafas kami yang pelan-pelan memelan. Punggung kami kembali menempel dengan sandaran jok setelah barusan mendadak miring ke depan. Hujan malam ini pastilah sangat deras sampai mampu menjatuhkan pohon besar tepat di depan garasi. Gelap malam ini pun pastilah sangat pekat sampai mampu menyamarkan pohon besar itu dari pandangan. Aku lantas terpaku dalam perasaan heran dengan alis yang sedikit terangkat. Malam ini bukanlah malam yang biasa, adalah satu-satunya yang sempat terlintas di pikiranku. Aku menolehkan wajahku melihat Raku. Raku menolehkan wajahnya melihat ke luar jendela. Lidahnya mendecak samar tapi aku mendengarnya. Di bawah hujan kami berjalan cepat menuju pintu depan rumah. Padahal hanya sekitar sepuluh meter tapi ini sudah bisa disebut basah kuyup. Kami mengentak-entakkan kaki dan menghempas-hempaskan tangan; membuang sebanyak mungkin air hujan yang sudah melekat di tubuh dan pakaian kami. Raku menarik nafas panjang dan melepasnya dengan mata tertutup. Mulutnya mengulum-ngulum sesuatu yang tidak ada. Sedikit lama aku menunggu dan matanya dipenuhi kebimbangan walau akhirnya tangannya sanggup membuka pintu. Di saat ini pulalah penantian itu tiba, sebab dingin digantikan hangat dan khawatir digantikan getir namun yang hitam tetaplah hitam. Dia beruntung karena matanya sempat berkedip. Sebab bertepatan dengan itu, kopi yang masih terlihat kepulan asapnya tercurah tepat menutupi seluruh wajahnya. Raku segera mengerang pelan tak tahan dengan panasnya kopi itu. Langkahnya dibawa jauh ke belakang menjauh dari sosok hitam di sebelah sana yang siap mengeluarkan amuk amarahnya. Diusapnya cepat mukanya yang memerah ketakutan lalu membiru kebingungan. Sayang, yang melayang bukan kopi saja. Cangkir wadah kopi tadi juga turut mengudara, lalu mengantuk pelipisnya sehingga jatuh pecah di lantai terbelah-belah. Raku mengerang
lebih keras dari sebelumnya tetapi sosok hitam itu berteriak lebih keras lagi; tak sekalipun aku memahami maksud dari setiap teriakan dan erangan yang memenuhi ruangan ini. Berkali-kali Raku meraung keras, berkali-kali pula sosok hitam itu berteriak lebih keras lalu semakin keras; membuat Raku hanya bisa membungkus kepalanya dengan kedua tangannya. Aku mulai dilingkupi kegelisahan saat si sosok hitam mengepalkan tangannya dan membenturkannya ke pipi Raku. Raku tak membalas atau tak mau membalas atau tak bisa membalas atau tak sempat membalas karena kepalan tangan itu untuk kali ketujuh membentur kepalanya. Raku mengerang kesakitan dalam ketidakberdayaan. Tangisnya pecah dari ruang tenggorokannya yang terguncang. Giginya terdengar bergeretak dalam nafasnafas pendeknya yang bergoyang tidak beraturan. Dadanya bergetar dan rintihannya terputus-putus melemas. Lehernya tercekik lalu matanya meminta tolong; akhirnya. Ya, tak kan kubiarkan ayahmu membunuhmu.
Sekarang, semuanya menjadi kacau. Segalanya kacau balau, centang perenang, morat-marit. Lantaran, ada yang tega mencelakai ubin demi ubin teraso berkualitas baik buatan tangan tanpa rasa bersalah. Tentu ada juga yang gemas gara-gara elok coraknya dinodai hitam seteguk espresso. Ditambah lagi, ada yang melayang menemani suara-suara lantang di udara, namun malah hancur luluh menubruk segala yang keras. Kemudian, ada pula noda entah dari mana yang terpercik-percik tak sengaja. Awalnya merah, terus cokelat, lalu bening, dan semuanya bercampur begitu saja. Percikan itu kemudian terserak-serak diiringi lantai yang berdegup-degup. Iramanya tidak jelas persis seperti langkah kaki si hitam. Lantas, tibalah satu degupan terakhir yang paling kencang hingga seluruh kekacauan tadi rasanya berakhir. Senyap pun kembali datang dengan tiba-tiba. Ia tercengang atas apa yang dilihatnya. Lalu dengan santun ia bertanya, apa kiranya yang telah terjadi? Dan, apa gerangan cairan yang berwarna merah seperti darah itu?

Hujan pun belum reda. Perlahan aku menuntun Raku menaiki tangga ke kamarnya di lantai dua. Aku di kanannya berusaha menenangkan. Tangan kananku menggenggam tangan kanannya sedangkan tangan kiriku merangkul pundak kirinya dari belakang lehernya. Kami cukup dekat sehingga aku masih bisa melihat sisa-sisa air matanya. Nafasnya terdengar masih berat dan tangan kiriku ikut terayun bersama dengan bahunya yang naik turun. Melihat betapa kosong tatapannya, aku memilih untuk diam. Alih-alih menjernihkan pikiran, dia malah membuka percakapan dengan suaranya yang bergetar, “Aku masih belum percaya ayahku sudah meninggal.” Menurutnya, ayahnya adalah orang yang sangat baik. Raku menceritakan betapa banyaknya orang yang mengenal ayahnya sebagaimana dia mengenal ayahnya sendiri. Baik itu rekan kerjanya, tetangga-tetangga dekat rumahnya, juga temannya ketika sekolah atau kuliah dulu. Ayahnya memang senang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Itulah kenapa dia selalu berusaha terus menjaga komunikasi dengan mereka dan jika ada yang butuh bantuan, dia menjadi tahu dan mengusahakan yang terbaik. Itu juga satu. Ayahnya selalu mengusahakan yang terbaik. Untuk orang lain, terlebih lagi untuk keluarganya sendiri. Dia mengingat kembali bagaimana dia hampir setiap hari bermain bersama ayah dan kakaknya. Ibunya lebih sering di dapur menyiapkan camilan untuk dimakan selepas bermain. Dia juga ingat ketika ayahnya selalu memboncengnya entah ke mana hanya untuk cuci mata, istilah yang belum dipahaminya waktu itu. Senyumnya kembali terpahat dari kedua ujung bibirnya, begitu pula denganku. Bahkan, dia sangat ingat bagaimana dulu dia malah diajak ke pasar malam saat ayahnya tahu dia tidak naik kelas sekali pas SD. “Mungkin ayahku kasihan melihat mukaku yang cemberut takut dimarahi,” lanjutnya diakhiri tawa kecil, tawa yang sama ketika di mobil tadi. Sekarang dia terlihat lebih baik dari sebelumnya, juga setelahnya. “Tapi, aku sendiri lupa kapan pertama kali ayahku marah-marah tidak jelas seperti tadi ha-ha,” sambungnya ketika kami tiba di depan pintu kamarnya. Jelas bahwa yang tadi bukan yang pertama kali dan tak perlu juga dia membuang energi untuk mengingat-ingatnya. Seperti bisa membaca pikiranku, dia hanya mengangkat pundaknya sesaat dan memasang wajah tak acuh. Raku memutar kunci dua kali membuka pintu. Ia lalu menghadap ke arahku dengan sedikit menelengkan kepalanya lalu mengangkat alisnya. Aku mematung sebentar menatap ke dalam matanya. Dalam pikiranku aku bertanya-tanya: apakah kau masih perlu kutemani malam ini? Ya, tolonglah, sahutnya melalui tatapan matanya yang ma
sih sedikit syok dan senyumnya yang agak hambar. Wajahnya berusaha terlihat yakin, walau aku tahu dia sebenarnya ragu apakah yang akan kami lakukan ini tepat atau tidak. Entahlah, aku tetap masuk ke dalam kamarnya. Ya, baik, sebab kau yang menginginkannya.
Di atas sini gegana masih membahana. Kumandang petir berhamburan mencari tempat-tempat terjauh. Rentetan kilat terus bergantian memamerkan jilatnya. Awan hitam juga masih tetap hitam dan angin pun mengajaknya melanglang buana. Hujan mengekor dari belakang membawa serta rintik-rintiknya. Satu per satu rintik itu turun bertualang meninggalkan dingin dari atas. Sebagian angin penasaran. Ia lalu ikut dan bersahabat dengan si rintik. Rintik itu damai. Namun, bersama angin ia menggelora. Maka, lenyaplah mereka menuju seluruh lekuk dan ceruk; juga segala liang dan ruang. Lalu, mendesak masuk dan menyingkap tutup. Akan tetapi, selalu ada asap kelabu dari api yang membara; selalu ada yang sakit hati dari laku yang lajak. Ialah riuh rusuh yang kerap berseru, sampai kapankah kalian berhenti? Sekali lagi dengan lebih perih ia berseru, sampai kapankah kalian berhenti?
Hujan pun belum reda. Raku menutup jendela kamarnya rapat-rapat. Suara yang sangat keras terdengar dari jendela yang menghantam kusennya. Sepertinya, hujan di luar makin deras sampai-sampai airnya berhasil menerobos ke dalam kamar. Gordennya tidak terlalu kuyup karena terombang-ambing dilanda angin tapi akibatnya sebagian besar air jatuh ke lantai. Raku langsung saja membuka dan menggesekkan kemejanya ke lantai yang basah. Aku lirih menggantungkan jaketku dan diam memperhatikan dia yang gusar. Sejenak kemudian dia menenangkan diri menghela nafas lalu menghadap ke arahku. Bersama dengan ributnya angin di luar, ia pun bersuara, Aku siap. Tubuhnya kutuntun telentang di atas kasur sedangkan aku duduk di pinggirnya. Tanganku menyusuri tepian tubuhnya dengan perlahan. Berharap agar dia rileks tapi mungkin malah semakin tegang. Kakinya kaku dan aku tambah ragu dia siap untuk ini. Meski begitu, aku sadar ini bukan saatnya untuk mundur. Kurasa lebih baik aku melakukannya dengan cepat. Ataukah, kucoba saja menikmati tiap detiknya seperti sebelum-sebelumnya? Sialnya, badannya mulai menggigil karena tidak ditutupi selembar kain pun. Atau mungkin juga karena gores tanganku yang mulai menyisiri jalur-jalur yang terbentuk di perut dan dadanya. Aku baru saja mulai menikmatinya, namun memang lebih baik aku lekas menyelesaikannya sebelum dia berubah pikiran. Tenanglah, Raku,
tenanglah sebab ini semua akan segera berakhir. Aku menyeka jejak air mata di sebelah pipinya. Matanya memejam dalam keresahan yang tak dapat disembunyikan. Sementara itu, tibalah jariku di ujung bibirnya. Pelan celah bibirnya membuka. Pelan juga tiga jariku mendesak masuk. Pelan kuletakkan salah satu lututku di perutnya. Pelan pula badannya menyamankan diri. Pelan tanganku yang lain beranjak pergi. Pelan lagi ujung pisauku menusuk. Sontak kemudian dia menggigit keras jariku. Matanya membelalak terkejut. Badannya mengaku. Tangannya memberontak. Lidahnya pun berusaha mengusir tapi jemariku sama sekali tak terusik. Tanganku terus merajah setiap sisi lehernya, berusaha mengoyak sebanyak mungkin saluran darah. Mengabaikan gigitannya yang makin kuat dan matanya yang kembali berair, tikamanku tidak berhenti. Kemudian, pukulannya mulai melemah. Begitu pula gigitannya. Raku akhirnya bisa tenang sebab ini semua sudah berakhir. Aku bukanlah profesional tapi setidaknya aku bisa melakukannya dengan cepat. Dan dia pasti bahagia, walau yang tampak adalah merah murung di bibirnya, semerah lumur di pisauku. Ya, berbahagialah kau di sana.
Tibalah saatnya di suatu malam yang lain. Dia berjalan dengan rada tergesa-gesa karena waktu sudah lewat dari yang dijanjikan. Rambutnya basah, pakaiannya berantakan, mukanya kusam. Semoga saja ia masih sabar menunggu, batinnya. Sebab, mungkin inilah satu-satunya kesempatan dia bertemu dengan orang yang dikenalnya lewat media sosial itu. Kabarnya, orang itu adalah satu-satunya orang yang tidak akan mengambil apa pun selain nyawa pelanggannya. Ini penting sebab jasa seperti itulah yang saat ini dibutuhkan oleh beberapa orang yang ingin mengakhiri hidupnya, tapi tak sanggup dengan tangannya sendiri. Warganet mengenalnya dengan sebutan Penghapus Hujan, baik dalam setiap obrolan mengenai aksi-aksi pembunuhan yang belum diketahui motifnya maupun kisah-kisah konspirasi yang sedang hangat dibicarakan. Ialah yang ketika itu sudah menunggu di bar selama beberapa jam namun tetap tersenyum ramah menyambut yang sudah ia nantikan. Sambutannya itu pun segera dibalas dengan sebuah pertanyaan yang sudah ia duga. Bisakah kita tetap melakukannya malam ini juga?
Hujan pun belum reda.
- SELESAI -