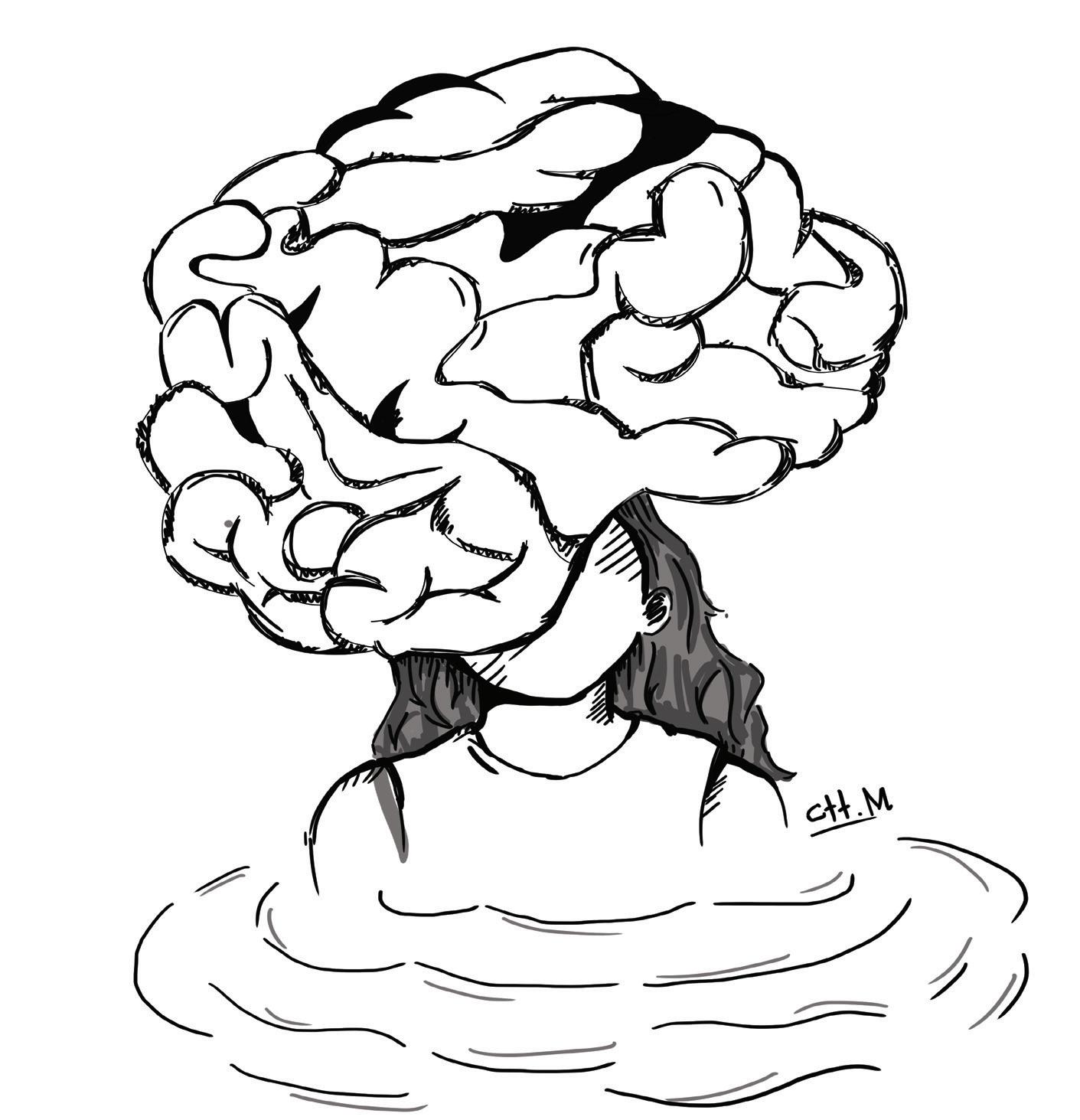
4 minute read
Cerpen
Mengusaikan Sumpah
n Ilara Dina Yahya
Advertisement
Ilustrasi: Faiq Y
Hari ini Minggu. Hari dimana Umi akhirnya berhasil memaksaku untuk mengobati rindu yang sudah lima tahun menumpuk di dada. Dan aku? Biasa saja. Bahkan ketika langkahku sampai di halaman bangunan yang bagiku rindunya sudah membusuk.
Bangunan itu ialah rumah, yang sempat menjadi saksi pada saat alasan menangis paling hebat adalah ketika umi menyuruhku tidur dan tidak mengijinkanku bermain. Bangunan yang seharusnya tetap menjadi saksi aku tumbuh sampai sekarang di usia
dua puluh. Dan bangunan yang lima tahun ini setengah mati aku hindari.
Aku ingat sekali pernah dengan cepat ingin pulang sembari tersenyum sumringah, membayangkan saat itu abah dan umi tergopoh menyambutku di depan pintu dan aroma masakan yang sudah enam bulan ini libur masuk ke perutku karena kewajiban belajar di tanah rantau kala itu.
“Ayo nak dipercepat semua hanya tinggal menunggu kamu”, ucap umi sambil menyentuh bahuku sebab aku masih berpaku pada pikiranku. Dan langkahku kian dalam memasuki rumah ini, samar-samar mulai terdengar ramai orang yang sedang membaca lantunan surat Yasin. Hatiku mulai bergetar dengan mata yang rasanya tak kalah panas karena terlalu kuat menahan air mata yang harus jatuh. Sekuat tenaga tidak kubiarkan berlinang memilih meninggikan ego, dan berusaha tidak peduli sama sekali. Namun tiba-tiba hening saat seseorang tergopoh-gopoh menghampiriku dengan mata merah bengkak dan tubuh yang kurasa semakin kurus dari terakhir kali aku melihat.
“Maaf, maafkan kesalahanya. Jangan siksa dia kumohon, agar ajalnya dipermudah” kata seseorang tersebut dengan nada serak.
“Tapi nanti dulu tadi apa katanya? Menyiksa? Bukankah segalanya begini sebab dia yang merusak lalu kenapa dia pula yang merasa tersiksa?” Batinku berontak.
Mari berbicara tentang menyiksa, saat lima tahun lalu dimana rinduku masih sederhana ingin pulang dan makan masakan umi namun harus dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari bayangan.
“Hancur mbak hancur, sudah usai segalanya”, umi berkali-kali berkata, tanpa aku tau maksudnya. Lalu pandanganku beralih ke abah, bertanya dengan isyarat mengapa umi seperti ini. Lama, sampai akhirnya abah dengan pelan menyentuh pundak umi dan meminta untuk menyudahinya. Belum penuh tangan abah menyentuh pundaknya tiba-tiba umi berkata kepada abah dengan kata dan nada yang tak pernah kudengar sebelumnya.
“Jangan menyentuhku dan anakku, kau yang menghancurkan segalanya. Lihatlah apa yang kau lakukan, lihatlah anakmu ini, tak berpikirkah engkau sebelum bertindak”.
Keterkejutanku tidak sampai di situ kala sorak-sorai teriakan warga memenuhi halaman rumah. Dan tiba-tiba orang yang ku kenal sebagai guru abah sudah di sini dengan raut wajah yang sulit aku artikan, ia meminta abah untuk bersumpah atas nama Tuhan bahwa ia tidak pernah melakukan hal yang hina itu.
Aku bahkan masih mencerna, ketika orangorang berduyun-duyun datang memenuhi halaman rumah.
“Kita bantu abahmu nak, umi sudah salah menebak. Abahmu tidak bersalah dia hanya korban. Tidak pernah umi melihat dia mempermainkan sumpah, maka umi yakin abahmu benar”.
Umi tiba-tiba berubah pikiran berbelok ingin membela abah. Dan aku bertanya-tanya kenapa. Umi menghela napas seperti sedang mengatur kata yang kiranya pas untuk diberi tahu kepadaku.
“Abahmu terfitnah zina kala sedang menerima tamu seorang perempuan, entahlah bagaimana cerita aslinya sebab umi juga sempat
percaya bahwa abahmu punya seorang yang lain,” ucap umi.
Aku terdiam tak sanggup berkata. Keadaan di luar rumah sangat mengenaskan. Pot bunga yang umi rawat rusak, kaca jendela yang pecah dan teras yang penuh dengan tanah bercampur kotoran.
“Dasar ustad gadungan,” ucap warga satu. “ngaku pinter agama tapi zina,” ucap warga lainya “ndue utek tapi rak dinggo, mikir!,” ucap warga lainnya lagi. Mereka saling menimpali satu sama lain. Aku sudah tidak lagi peduli siapa yang berkata demikian. Karena ada hal yang lebih aku pedulikan, adalah aku serta abah umiku yang diminta pergi oleh warga-warga ini. Bukan diminta tetapi diusir lebih tepatnya.
Hei apa-apaan kalian! Rumah ini adalah rumah pemberian kakekku. Rumah masa kecil abah dan aku. Kalian tak ada hak mengusir kami. Aku hanya mampu mengatakan hal tersebut di dalam hati, terlalu takut memperkeruh suasana.
Abah memilih mengalah meninggalkan semuanya sebab kulihat dari wajahnya sudah lelah karena percuma saja abah sudah dianggap salah maka segala kata bahkan sumpah hanya isapan jempol tanpa makna. Entah kekuatan darimana sebelum pergi keberanianku tiba-tiba memuncak dan berkata. “Aku bersumpah ini adalah fitnah, siapapun dia yang sudah memfitnah kudoakan ajalnya dipermudah ketika maafku dan kedua orang tuaku sudah sampai,” kataku sambil menatap seseorang yang kurasa sebagai biang kekacauan ini.
“Nak ikhlaskan yang sudah terjadi yaaa. Karena kebenaranpun sudah terbukti.” Ucap abah sembari merangkul bahuku dan menyadarkanku dari bayangan lima tahun yang lalu.
Sungguh aku masih berat untuk melakukannya apalagi jika teringat orang yang memfitnah abah adalah pakdhe, kakak abah sendiri yang setelahnya ku tau karena atas dasar iri serta ingin merebut rumah yang kakek berikan padaku. Tetapi nuraniku juga memberontak. Tak tega melihat tangisan budhe yang memohon karena keadaan pakdhe yang masih mengambang antara hidup dan mati.
Akhirnya aku hanya bisa mengangguk pertanda memaafkan. Lalu terdengar banyak helaan nafas lega dan innalillahi wa innailaihi rojiun pakdhe sudah tiada, setelah dua malam sulit meregang nyawa. Terdengar isakan lebih histeris dari budhe dan anak-anaknya. Lalu aku pergi memilih menyendiri merenungkan apakah aku sudah benar-benar bisa memafkan? Dan tiba-tiba aku didekap abah sembari abah berkata “kamu hebat nak! Abah bangga kamu mampu mengikhlaskan dan berdamai dengan semuanya,” kata abah dengan air matanya. Kami menangis berdua, mungkin sangat lama mengingat masa sulit selama lima tahun kemarin.
Sampai umi memanggil kami mengatakan bahwa jenazah pakdhe akan segera dikebumikan. Dan di sinilah aku sekarang, di antara orang-orang yang berpakaian serba hitam, di antara orang-orang yang membawa bunga-bunga untuk taburan makam. Saat jenazah mulai di penuhi tanah, budhe kembali menghampiriku dan mengatakan terimakasih tanpa henti. Dan di situ aku merasa bahwa sudah semestinya aku berdamai dengan masa lalu, mengusaikan sumpah yang seharusnya memang sudah usai, dan tidak memupuk luka sampai menjadi busuk sampai berakahir dengan penyakit hati. Nauzubillah.n










