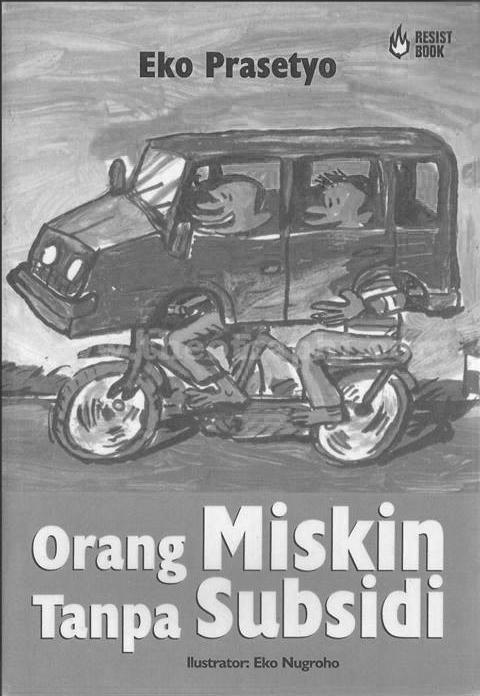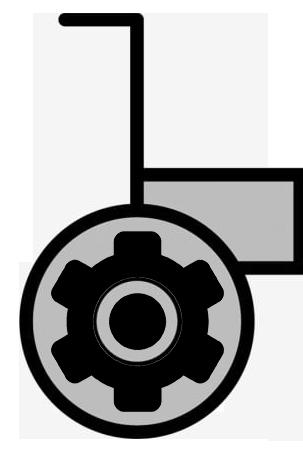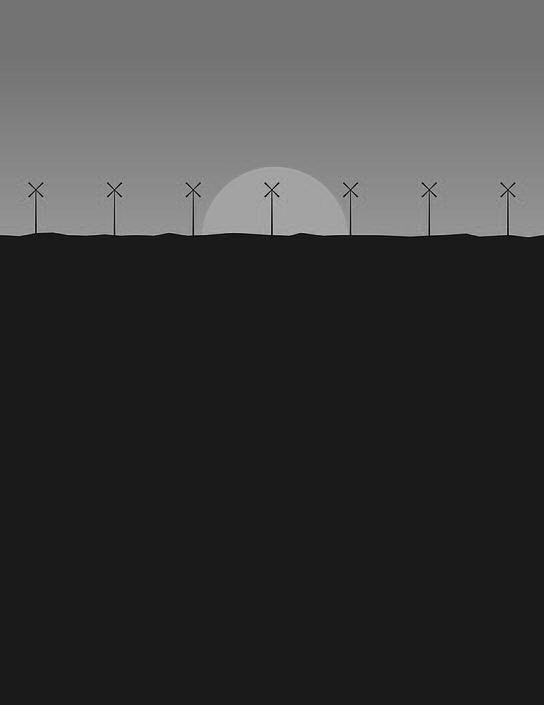9 minute read
Karena Terbatas Bukan Batasan
Tuntaskan Diferensiasi Pendidikan Disabilitas, Karena Terbatas Bukan Batasan
Oleh Nuzuli Rohmah
Advertisement
Istilah disabilitas dan difabel sudah tidak asing lagi didengar dalam setiap berita dan kontestasi. Disabilitas sendiri berasal dari dua kata yakni dis yang berarti tidak dan ability yang berarti kemampuan. Disabilitas dalam KBBI adalah suatu keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Sedangkan difabel berasal dari kata different ability, berarti kemampuan yang berbeda, hanya saja dalam opini masyarakat difabel erat dikaitkan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Berbeda dengan disabilitas yang merujuk pada istilah yang lebih netral dan tidak mengandung diskriminasi.
Menurut International Classification of Functioning, Disability and Health yang kemudian disepakati oleh World Health Assembly dan digunakan secara internasional oleh World Health Organization (WHO), “Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitation or participant restrictions” (Disabilitas itu seperti payung terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi). Menurut WHO penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi tiga kategori.
Pertama, impairment, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikis atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori impairment ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental, dan penglihatan yang tidak normal.
Kedua, disability, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktivitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi impairment tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktivitas pada umumnya, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.
Ketiga, handicap, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosialekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik dok.dim/ria karena sebab abnormalitas fungsi (impairment), atau karena disabilitas (disability) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ketiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas. Hal ini seperti terisolasi oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain.
Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangan waktu lama. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 bulan dan/atau bersifat permanen. Mereka mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Lalu bagaimana dengan layanan pendidikan penyandang disabilitas atau yang sering kita kenal Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)? Sebelum adanya UU Nomor 8 Tahun 2016 hal ihwal tentang disabilitas diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, ini dinilai lebih bersifat belas kasihan (charity based) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih sebatas pemenuhan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Padahal menganut pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang di mana pemenuhan hak asas/dasar manusia tanpa membedakan hal apapun, artinya memandang kedudukan manusia itu sama. Tentu saja hal ini akan mencederai hak para penyandang disabilitas, yang seharusnya dipandang sama dengan yang lain. Termasuk dengan pendidikan penyandang disabilitas.
Sebelumnya Indonesia menganut model pendidikan segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan siswa, model segregasi memang menguntungkan, lantaran mudah bagi guru dan administrator dalam menangani siswa disabilitas. Hanya saja pertimbangannya adalah saat ini kita tahu bahwa tidak semua disabilitas memiliki keterbatasan yang sama satu sama lain. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 ada 4 ragam disabilitas, yakni disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, dan disabilitas sensorik. Dari banyaknya klasifikasi tersebut, apakah semua siswa disabilitas bisa dikatakan layak untuk masuk Sekolah Luar Biasa (SLB)? Jawabannya belum tentu sempurna jika hal tersebut dipandang sama. Misal ada siswa disabilitas fisik yang memiliki potensi intelektual yang tinggi dengan IQ di atas normal. Ini tentu tidak adil jika siswa tersebut harus masuk SLB yang pada dasarnya menggunakan sistem kurikulum berbeda dengan standar reguler. Dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan. Model segregasi tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Selain itu, dari perspektif wali peserta didik beberapa dari mereka belum bisa menerima kenyataan bahwa anak mereka memiliki kemampuan berbeda, sebab menganggap model segresi sebagai wujud diferensiasi dan ketidakadilan pendidikan. Terlebih lagi para wali peserta didik menganggap biaya di sekolah model segregasi ini mahal dan tidak setiap desa memiliki sekolah model segregasi atau biasa dikenal SLB.

Dari berbagai problematika yang ada, sebelumnya pemerintah mewujudkan model pendidikan mainstream, model ini memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi ABK. Model mainstream adalah salah satu cara yang mendukung proses pengaplikasian gerakan Indonesia Inklusi 2030. Model inilah juga yang kemudian dinamai istilah pendidikan inklusif. Konsep yang ditawarkan yakni dengan menempatkan ABK secara penuh di kelas reguler. Melalui pendidikan inklusif, ABK dididik lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pendidikan inklusif menyediakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa tanpa melihat kondisi fisiknya. Pendidikan inklusif bukan sekadar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antarmanusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua orang tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan (education for all).
Menurut Staub dan Peck (1994/1995) ada lima kelebihan dari program pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada ABK akibat sering berinteraksi dengan ABK; anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK; banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan selfesteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah; anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika; anak non-ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK.
Meskipun demikian, kehidupan tak akan lepas dari problem. Dari problem solving yang kian diwujudkan justru dalam pengaplikasiannya masih saja memunculkan problematika baru. Bukan karena problem solving yang tidak tepat, tapi keseriusan dan komitmen dalam mengentaskan diskriminasi disabilitas bisa dibilang cukup miris. Dari tahun ke tahun, janji-janji pemeritah belum juga terekspos optimal. Sehingga tidak dapat dimungkiri atau bahkan tidak dapat disalahkan bila kemudian melahirkankan wajahwajah stereotip baru di masyarakat. Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Olifia Rombot, salah satu Dosen Asisten Ahli di Universitas Bina Nusantara Jakarta, mengungkapkan,
“Sistem pendidikan inklusif di negara kita menunjukkan belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Dan sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang belum mengakomodasi keberadaan anakanak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel). Sehingga sepertinya program pendidikan inklusif hanya terkesan eksperimental saja.” Alhasil sistem kurikulum yang diterapkan untuk sekolah inklusi pun masih mengambang. Tentang bagaimana merancang kurikulum yang fleksibel selaras dengan zaman dan kontekstual berbasis teknologi kemudian dibaurkan dengan kurikulum untuk ABK. Menyamaratakan dan mengembangkan mengenai kurikulum yang sesuai untuk kedua potensi yang berbeda, namun dimaksudkan untuk dapat menghasilkan produk mutu pendidikan yang optimal untuk siswa secara keseluruhan bukan suatu hal yang mudah. Hal ini perlu melibatkan kesungguhan para tenaga pendidik dan warga sekolah serta lembaga pendidikan dan pemerintah.
Jika kita telusuri lebih lanjut dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak sekolah yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan belum memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Mulai dari fasilitas yang belum terkontribusi akan aksesibilitasnya. Padahal seorang penyandang disabilitas berbeda dengan nondisabilitas sehingga titik poinnya tidak melulu soal fasilitasnya saja, tetapi juga lebih merujuk pada aksesibilitasnya. Mulai dari kemudahan menjangkau akses kelas dan pos-pos penting dalam gedung sekolah (seperti: perpustakan, kantin, dan kamar mandi) serta kemudahan akses di luar gedung sekolah (seperti: jalan, gerbang sekolah, dan aksesakses lainnya). Juga kesiapan sekolah inklusi dalam memberikan pelayanan pendidikan yang lebih intensif, sarana pembelajaran yang mudah dan fleksibel, kesiapan literatur untuk pengguna disabilitas, dan masih banyak lagi. Guru yang mengajar peserta didik pun diharuskan benarbenar serius untuk belajar memahami karakteristik peserta didik, karena yang menjadi beban bukan hanya peserta didik secara general, tapi juga ABK sehingga nantinya mampu dalam mengajar, mendidik, bahkan menangani segala kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didiknya. Namun, pada fakta di lapangan menunjukkan guru justru mengabaikan atau bahkan bisa dibilang tak acuh kepada ABK, karena menganggap sudah tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK). Padahal gurulah penanggung jawab di segala sudut letak tepat di mana ia mengajar. Di sinilah terjadi kesalahpahaman, guru kelas bukan melepaskan tanggung jawab peserta didik begitu saja karena merasa tugas telah dilimpahkan kepada GPK, tetapi guru harus lebih proaktif untuk menjalin kerja sama dengan GPK. Akibat fenomena tersebut banyak peserta didik yang tidak terjangkau bahkan tidak terkontrol. Masalahnya tepat pada mutu guru.

Dalam perguruan tinggi khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di IAIN Tulungagung misalnya, tidak semua menerapkan mata kuliah rencana, kurikulum, dan proses pembelajaran untuk penyandang disabilitas yang seharusnya disematkan pada setiap jurusan kependidikan yang ada. Ratarata hanya penanganan realitas saja dan itu pun belum secara mendalam. Jika problematika tersebut diarahkan solusinya, maka ini akan menambah potensi dan kualitas mutu tenaga pendidik Indonesia yang ada sehingga bermanfaat dalam pengaplikasian sosialnya.
Tenaga pendidik tidak hanya pandai dalam bidang keahliannya, tetapi juga paham bagaimana cara mengajar dan sistem proses pembelajaran untuk peserta didik yang multitalenta. Guru seharusnya juga mahir dalam mutu karakter, sebelum pada akhirnya mengolah karakter peserta didiknya serta handal dalam menangani setiap fleksibilitas kondisi dan segala kemungkinan yang akan terjadi pada peserta didiknya, baik dari segi penanganan psikis maupun sosialnya. Guru kelas memiliki tanggung jawab lebih dari 10 peserta didik yang beragam sifat, karakter, dan kemampuannya. Maka dari itu, adanya GPK juga tetap sangat dibutuhkan. Namun faktanya kesediaan GPK yang berpotensi bahkan mahir di bidangnya belum terpenuhi. Seperti minimnya lulusan yang berlatar belakang relevan, yang jika ditarik benang kesimpulan menunjukkan bahwa minat pemuda kita begitu miris untuk berperan aktif dalam kesadaran akan kesetaraan penyandang disabilitas, khususnya di bidang pendidikan.
ABK memiliki tempat dan perhatian tersendiri oleh pemerintah. Namun mereka lupa memperhatikan dan melibatkan tenaga pendidik penyandang disabilitas. Menurut Freire dalam bukunya “Pendidikan Kaum Tertindas”, pendidikan yang efektif adalah pendidikan
yang diajar, dibimbing, dan dikontrol langsung oleh tenaga pendidik yang sama atau pernah merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh peserta didiknya, sehingga problem nyata yang ada pada peserta didik ini mendapat solusi yang tepat berdasar pada pengalaman guru dan bukan sekadar bayangan saja. Termasuk dalam komposisi pembangunan pendidikan inklusif, tenaga pendidik penyandang disabilitas seharusnya juga dilibatkan dan diberikan ruang tersendiri dalam upaya menggerakkan sekolah inklusi. Setidaknya, minimal 20% dari jumlah guru keseluruhan dalam satu sekolah. Apa manfaat lainnya? Selain hal di atas salah satunya memberikan pandangan kepada peserta didik bahwa tidak hanya proses belajar tapi ada bukti-bukti masa depan yang baik yang dapat dijadikan contoh, arah, ataupun motivasi oleh peserta didik penyandang disabilitas.
Penciptaan lapangan pendidikan yang setara dan tanpa termarginalkan memang menguntungkan dan menjadi dambaan setiap orang tua anak disabilitas, akan tetapi biaya atau sumbangan untuk bersekolah inklusi dikategorikan relatif mahal untuk sebagian masyarakat Indonesia yang rata-rata memiliki taraf ekonomi rendah. Tidak menutup kemungkinan jika terdapat wali peserta didik mengeluh kesulitan mengenai hal tersebut. Karena siswa disabilitas membutuhkan biaya tambahan sebagai bentuk apresiasi terhadap GPK. Maka dari itu, pemerintah sebagai penggalang cita-cita pembangunan Indonesia Inklusi 2030 akan dipandang totalitas jika berani untuk membantu bahkan menanggung seluruh biaya pendidikan khususnya wajib belajar 12 tahun untuk seluruh peserta didik, termasuk penyandang disabilitas. Dengan begitu diharapkan mutu pendidikan dasar dan menengah meningkat dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Serta dengan begitu secara gradual dapat menghapus diferensiasi dan stratifikasi sosial khususnya dalam pendidikan. Dari beberapa sampel masalah yang ada masih diperlukan terus adanya perbaikan, pembaharuan, dan modifikasi serta evaluasi mengenai program apakah yang tepat dalam menangani disabilitas khususnya di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan pembangunan Indonesia Inklusi 2030. Apakah sudah tepat dengan sekolah inklusi atau ada cara yang lainnya. Kiranya pemerintah perlu adanya kontrol ganda dan lebih peka serta peduli terhadap kelompok penyandang disabilitas.