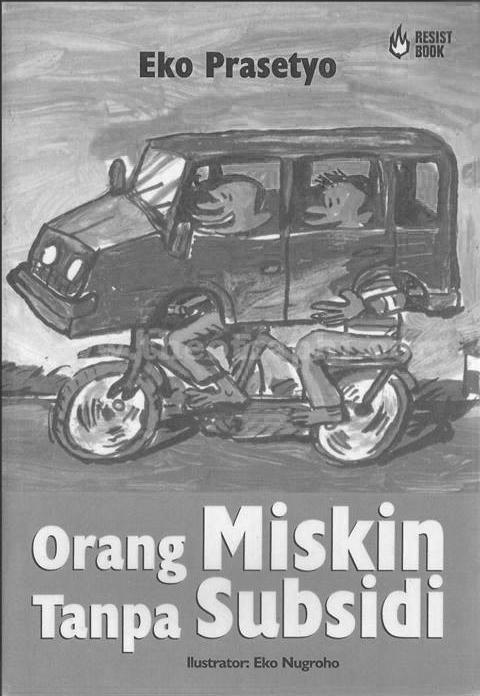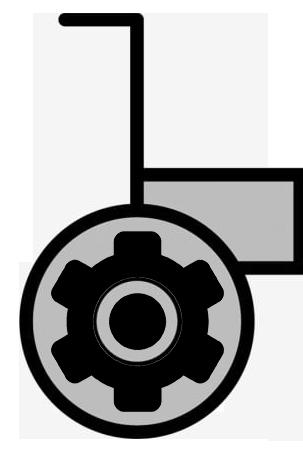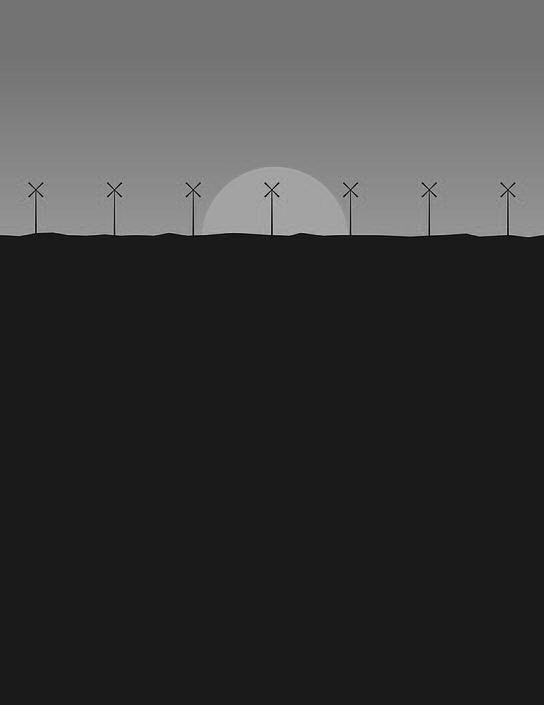5 minute read
Cuma Delusi
Kampus Merdeka: Merdeka Bagi Mahasiswa, Itu Cuma Delusi
“Kehidupan yang menyejahterakan bagi seluruh industri, mungkin itu kata yang tepat untuk menanggapi kebijakan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan Nadiem
Advertisement
Makarim. Kampus seharusnya sebagai media pendidikan yang mampu menciptakan generasi intelektual telah mengalami distorsi peran yang hanya sebagai budak kapitalis.
Oleh Hendrick Nur C.
Penulis adalah Kru LPM Dimensi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, pada 24 Januari 2020, mengusung kebijakan baru mengenai perguruan tinggi, yaitu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka merupakan episode kedua setelah Merdeka Belajar yang berisi: ujian sekolah berstandar nasional diganti asesmen, penghapusan ujian nasional, rancangan pelaksanaan pembelajaran yang dipersingkat, dan peraturan zonasi penerimaan peserta didik baru. Kampus Merdeka merupakan sebuah gebrakan baru yang diusung Kemendikbud untuk membuka seluasluasnya mimbar kebebasan akademik.
Kebijakan Kampus Merdeka yang diluncurkan Kemendikbud ini berisi empat poin. Pertama, kampus punya otonomi membuka program studi baru. Syaratnya Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTN dan PTS) harus memiliki akreditasi A atau B. Sebelumnya yang bisa membuka prodi baru hanya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang berjumlah 11, per April tahun lalu.
Syarat tambahannya, prodi tersebut baru dapat dibentuk jika kampus telah menjalin kerja sama dengan mitra perusahaan, organisasi nirlaba, institusi multilateral, dan universitas peringkat Top 100 Quacquarelli Symonds (QS), serta bukan bidang kesehatan dan pendidikan. Kerja sama yang dilakukan di luar negeri bermitra dengan universitas peringkat Top 100 QS. Kemudian kampus harus membuktikan bentuk kerja samanya kepada pemerintah. Ada tiga kriteria yang menunjukkan kerja sama dengan pihak ketiga, yaitu penyusunan kurikulum, program magang, dan kerja sama dari sisi rekrutmen.
Kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi bersifat sukarela. Proses akreditasi ini mengutamakan peran industri dan asosiasi profesi untuk melaksanakan akreditasi, serta bukan mengutamakan pemerintah. Sementara saat ini, proses akreditasi dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Ketiga, kebijakan mengenai status PTN yang dipermudah. Ada tiga jenis status PTN, yaitu Satuan Kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum (BH). Hingga saat ini dok.dim/rifqi yang mempunyai status PTN-BH adalah PTN yang berakreditasi A.
Keempat, hak belajar tiga semester di luar prodi. Perguruan Tinggi wajib memberikan dua semester atau setara 40 sistem kredit semester di luar perguruan tinggi yang digunakan untuk magang. Magang bisa dilakukan di industri, mengajar, melakukan riset, pertukaran pelajar, dan wirausaha. Sedangkan untuk satu semester belajar di luar prodi yang diambil.
Senja Kala Mahasiswa
Kebijakan Kampus Merdeka yang diusung Direktur Gojek ini dinilai dapat mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan tinggi. Namun jika kita selisik lebih dalam, semua poin yang ditawarkan hanya menjawab kebutuhan industri. Kampus seakan hanya dijadikan wadah penyedia tenaga kerja, bukan sebagai pencetak tenaga ahli, berdaya pikir kritis, dan agen intelektual.
Dalih kampus yang bersifat lebih otonom sebenarnya menggambarkan negara yang ingin meninggalkan kewajibannya dalam dunia pendidikan. Pertama, kebijakan pembukaan prodi baru yang otonom. Kampus yang menjadi otonom dituntut bermitra dengan industri. Negara dalam hal ini berperan sebagai penjamin kualitas pendidikan malah mendukung industri terkait pemenuhan kebutuhan industri itu sendiri. Kampus seakan hanya menjawab kebutuhan pasar, apa yang sebenarnya dibutuhkan industri, bukan menjawab permasalahan umat.
Kedua, kebijakan mengenai akreditasi yang bersifat sukarela. Akreditasi sebagai bahan evaluasi bersama lembaga pendidikan yang sebelumnya dilakukan lima tahun sekali, sekarang menjadi sukarela dan lebih mengutamakan industri daripada pemerintah. Proses akreditasi yang bersifat sukarela ini saya kira masih sangat tabu. Akreditasi yang lebih mementingkan industri daripada pemerintah, berarti kita hanya menjawab kebutuhan pasar yang ada, bukan malah mengembangkan kualitas pendidikan.
Akreditasi yang bersifat sukarela saya kira sangat abstrak. Bayangkan jika akreditasinya sudah A, maka besar kemungkinan tidak akan mengajukan proses akreditasi lagi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengevaluasi itu kembali jika sistem yang ada masih seperti ini? Serta untuk yang belum mendapatkan akreditasi A, mereka akan disibukkan dengan masalah administrasi.
Ketiga, kebijakan mengenai status PTN yang dipermudah. Kalau kita melihat dari pandangan hak asasi manusia, negara wajib menjamin pendidikan dalam negeri. Dalam hal ini pemerintah seakan melepaskan tanggung jawabnya untuk menjamin pendidikan dalam negeri dengan dipermudahnya status perguruan tinggi. Ketika kampus semakin otonom, maka subsidi yang dilakukan negara pasti akan dikurangi atau bahkan dicabut.
Perubahan status juga akan berdampak pada regulasi kampus. Dampak dari PTN-BH yang jelas adalah kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Hal ini karena subsidi yang diberikan pemerintah perlahan dikurangi atau bahkan dicabut. Kenaikan UKT berdampak sangat besar, seakan yang bisa menempuh pendidikan tinggi hanya mereka yang mempunyai uang dan orang miskin dilarang kuliah. Kalaupun ada beasiswa untuk orang miskin, mengapa harus bersyarat pintar atau berprestasi? Pendidikan yang mahal merupakan salah satu bentuk komersialisasi pendidikan.
Selain perubahan status perguruan tinggi yang dipermudah, kampus yang masih berstatus Satker maupun BLU pasti akan disibukkan dengan masalah administrasi, bukan masalah akademik. Penilaian pun dilakukan lebih mengutamakan industri daripada pemerintah. Dalam hal ini seakan-akan pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dalam hal memperbaiki kualitas pendidikan dalam negeri dan hanya menjawab kebutuhan pasar.
Keempat, adalah kebijakan magang tiga semester, yakni dua semester magang dan satu semester di luar prodi yang diambil. Program magang dua semester di luar kampus atau industri ini, diklaim berdampak pada mahasiswa yang hanya dijadikan robot industri. Kebijakan ini perlu dikritisi dalam proses magang di industri, apakah dibayar atau tidak? Kalaupun dibayar apakah itu layak dan sesuai dengan keringat yang mereka keluarkan untuk magang selama dua semester? Jika ketimpangan ini terjadi, mahasiswa hanya dijadikan budak yang sangat menyejahterakan kaum kapitalis. Bukankah proses magang yang lama sudah disediakan di sekolah-sekolah vokasi yang jelas setelah mereka lulus langsung bekerja.
Program magang yang dilakukan mahasiswa selama dua semester di industri membuat mahasiswa hanya dijadikan budak industri yang tak berdaya. Pendidikan jenis ini bukan malah semakin membebaskan, malah semakin menindas. Menurut Paulo Freire, suatu penindasan, apapun namanya dan alasannya adalah tidak manusiawi, sesuatu yang menafikan harkat manusiawi (dehumanisasi). Lebih baik program magang selama dua semester itu ditiadakan saja, ketimbang malah semakin menindas.
Kebijakan dilakukan
Kampus Merdeka yang oleh Mas Menteri berusaha memperbaiki kualitas pendidikan kita ini patut diapresiasi, meskipun banyak yang perlu dikoreksi— tanpa melihat latar belakangnya dari pengusaha. Para ahli perlu dipertemukan untuk memberikan evaluasi, pertukaran gagasan, dan memberikan sebuah alternatif baru untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.