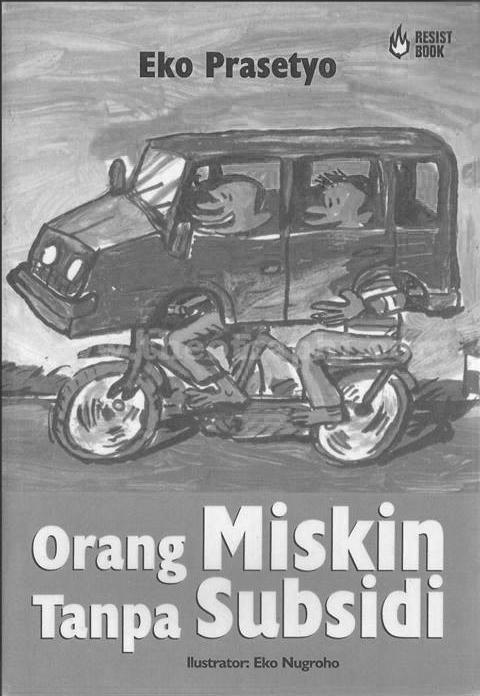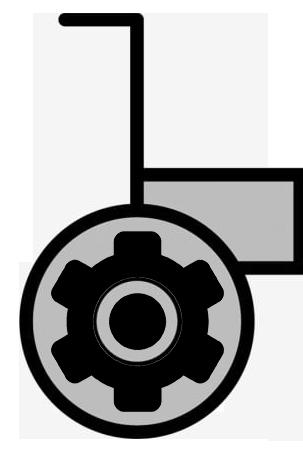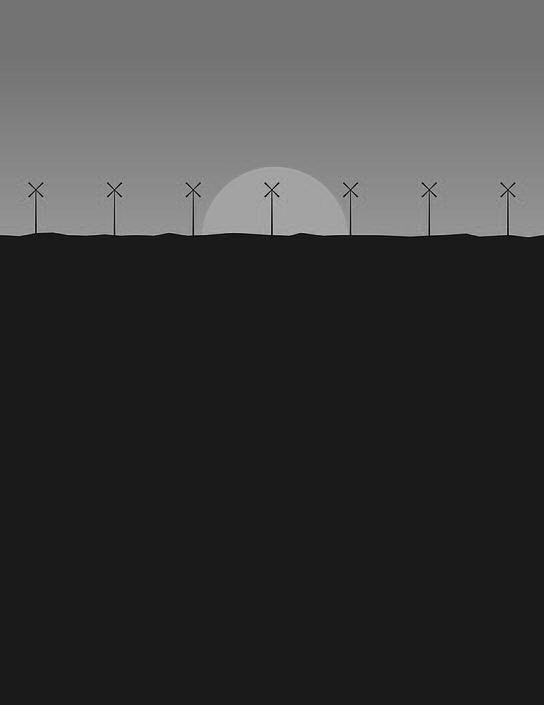5 minute read
BUDAYA
Napak Tilas Jejak Leluhur
Sentono “ Abu Mansur merupakan penyebar Islam di wilayah Tulungagung, sekaligus sebagai pendiri Desa Tawangsari. Desa ini kental dengan tradisi yang bernapaskan Islam, salah satu agenda besarnya adalah Hadeging sebagai peringatan Hari Jadi Desa Tawangsari.
Advertisement
Gerbang Masjid tertua di Tulungagung/dok.dim/lukman
Sejarah adalah bukti tanda adanya perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan suatu kemajuan, keberhasilan, atau kesejahteraan. Tak terkecuali sejarah Desa Tawangsari, yang berada di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ini menjadi saksi keluhuran Keluarga Sentono, keturunan Abu Mansur.
Ialah Raden Qasim, seorang sufi keturunan dari Raja Kartasura, yakni Mangkurat Jawi ke-4 dari istrinya yang seorang sufi. Keturunan dari Mangkurat Jawi ke-4 ini termasuk Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Dari silsilah inilah yang menyebabkan Desa Tawangsari berhubungan erat dengan Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta.
Raden Qasim dengan nama semasa kecilnya Raden Mas Tolo ini kemudian dikenal dengan Abu Mansur. Abu Mansur adalah gelar yang ia peroleh dari Turki, sebab kesenangannya untuk keluar dan mengambil jalur penyucian jiwa guna menyiarkan agama Islam. Abu Mansur kemudian bergelar Kiai Kanjeng Abu Mansur yang disematkan setelah ia berhaji. Abu Mansur menikah dengan Nyai Lidah Hitam, putri dari Bagus Harun Basyariah, seorang syekh di Madiun.
Sejarah Desa Tawangsari
Ada beberapa pandangan mengenai sejarah Tawangsari. Kru Dimёnsi berupaya menggali sejarah Tawangsari dengan mendatangi tokoh masyarakat Desa Tawangsari, Muhammad Abdillah. Ia merupakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zumrotus Salamah, sekaligus keturunan ke-6 dari Abu Mansur. Abdillah pun menceritakan kronologis asal-usul Desa Tawangsari. Abdillah menjelaskan bahwa Desa Tawangsari masih mempunyai hubungan erat dengan Kerajaan Mataram. Sebagai keluarga kerajaan, Abu Mansur mendapatkan sebidang tanah di wilayah Jawa Timur yang sekarang disebut sebagai Desa Tawangsari. Di wilayah kekuasaan inilah, Abu Mansur mempunyai kewenangan untuk mengelola, mengatur kemudian menjadi pemimpin rakyat di Tawangsari. Daerah kekuasaan ini diberikan kepada Abu Mansur sekitar tahun 1750-an. “Diawali dengan Perang Suksesi ke-3. Di zamannya, Amangkurat IV dimusuhi oleh saudarasaudaranya seperti Pangeran Blitar, dsb. Ketika Mataram mengalami gejolak besar, Raja Kartasura dibunuh dan beberapa pusakanya itu dicuri orang-orang. Sehingga untuk menyelamatkan pusaka lainnya dititipkan di sini (Desa Tawangsari, red), total ada sebelas pusaka. Hal ini sudah jelas, kalau Raden Qasim adalah pewaris Mataram,” terang Abdillah.
Di Tawangsari ini Abu Mansur mewarisi daerah kekuasaan bukan dari sisi tahta, melainkan mewarisi secara tradisi, budaya, keilmuan, ideologi, terlebih di agama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdillah. “Tawangsari ini memang punya kekuasaan sendiri, punya otonom sendiri, tapi nuansa lebih kepada agama. Seperti tonggak awal munculnya peradaban di wilayah timur Mataram pada abad ke-17. Tawangsari itu ‘Tawang’ yang berarti langit, ‘Sari’ artinya inti. Berartikan memang daerah sini kental dengan sufi, sebab tasawuf itu sebagai ‘ilmu langit’. Semua ajaranajaran di sini (Tawangsari, red) itu baik yang berbasis
53
fiqih, tasawuf, dsb. Itu diramu dan dijadikan sebagai budaya atau tradisi yang positif. Yang jelas di daerah sini itu semuanya bernuansa agama dan agamanya berbasis tasawuf.”
Pada saat itu, masih banyak kerajaan yang berdiri di Indonesia. Desa Tawangsari dikatakan sebagai desa perdikan. Desa perdikan merupakan desa atau daerah yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pada penjajahan Belanda saat itu. Selain itu, Perdikan Tawangsari memiliki beberapa hak istimewa lainnya, seperti warga perdikan itu bebas kerja rodi semasa penjajahan, penguasa perdikan bebas dalam menggunakan pakaian kebesarannya, hingga terlepas dari kekuasaan Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Perdikan Tawangsari mempunyai wewenang untuk menghukum warganya yang melanggar peraturan perdikan. Di tanah perdikan ini setiap warganya juga mempunyai tanggung jawab sendiri, seperti bertanggung jawab atas keamanan, keuangan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya roda pemerintahan. Perdikan ini juga harus memberikan laporan satu tahun sekali pada Kesultanan Yogyakarta.
Pada tahun 1965, perekonomian Perdikan Tawangsari melemah. Salah satu penyebabnya adalah banjir yang merendam persawahan warga. Tentunya hal ini sangat berdampak merugikan masyarakat, karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Maka, tulang punggung perekonomian Tawangsari pun merosot. Jika biasanya sawah dapat dipanen dua kali dalam setahun, di tahun itu hanya bisa sekali panen, belum lagi jika hasil pertanian diserang hama.
Setelah ada beberapa masalah yang datang, akhirnya Perdikan di Tawangsari ini diubah dari status desa perdikan menjadi desa biasa. Tepatnya pada tanggal 18 Juni 1979, Pemerintah Tingkat II Tulungagung mengeluarkan surat keputusan yang berisikan tentang penetapan dan pemberhentian pejabat dan pamong desa disertai dengan pemberian tunjangan atau ganti rugi sebesar Rp11.500 bagi pejabat yang bersangkutan.
Sedangkan untuk permasalahan tanah, penyelesaiannya ada pada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Tanah Perdikan Tawangsari masing-masing dibuatkan sertifikat tanah oleh Gubernur Tingkat II Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri secara simbolis, di mana serfikat itu telah diserahkan oleh Gubernur kepada para pemegang haknya (Imam Bukhori: 1990).
Tradisi Desa Tawangsari

Tawangsari kental dengan tradisi bernuansa agama dan sudah dilakukan secara turun-temurun, seperti pembacaan tahlil, peringatan hari besar Islam seperti Suroan, dsb. Uniknya, tahlil dan doa yang digunakan di Tawangsari ini masih kental dengan Jawa, yakni lafaz yang ada di dalam tahlil yang biasanya menggunakan bahasa Arab diganti dengan menggunakan langgam jawa, yaitu Tahlil Tegal Saren. Selain itu juga berkembang Tarekat Syattariyyah, tarekat yang dinisbahkan kepada tokoh agama bernama Abdullah asy-Syattar. Tarekat ini muncul sekitar abad ke-15. Isu yang beredar di masyarakat ialah bahwa tarekat ini dibawa ke Indonesia oleh Abu Mansur.
Selain itu, terdapat suatu tradisi yang dilaksanakan satu tahun sekali oleh warga Tawangsari, yakni Hadeging atau Kirab Budaya. Acara ini digelar selama delapan hari. Hadeging didatangi tamu dari berbagai kalangan, seperti pejabat pemerintah desa hingga pemerintah kabupaten. Acara kirab budaya juga dikunjungi prajurit dari Keraton Yogyakarta beserta abdi dalem. “Kalau tiap bulan Safar, itu diadakan hari jadi Desa Tawangsari. Ditandai dengan kirap dan gunungan (tumpeng) yang dibawa keliling desa dan berakhir di masjid dan dibacakan doa,” ucap Siti Fatimah selaku ibu dari Abdillah, keturunan Abu Mansur.
Kirab budaya yang diadakan ini dikonsep dengan modern dan lebih meriah dengan tujuan agar masyarakat juga ikut andil dalam acara tersebut. Budaya yang ditunjukkan tetap pada aturan agama yang berlaku dan tidak menyalahi syariat, yang artinya tidak menyimpang dari pijakan Islam.
Hadeging biasanya diawali dengan tahlilan, lalu menyekar ke makam leluhur beserta tokoh masyarakat, dan malamnya digelar pengajian oleh masyarakat desa. Di akhir acaranya akan ditutup dengan pameran dan bazar Usaha Mikro Kecil Menengah.
Kirap budaya rutin digelar tiap tahunnya, agar masyarakat Desa Tawangsari memiliki semangat dalam syiar Islam dengan tetap mempertahankan nuansa Jawanya. Sebagai bagian dari kerajaan pula, tradisi yang dimiliki Tawangsari pun tidak jauh-jauh dari nuansa Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta. (Bay, Nis,