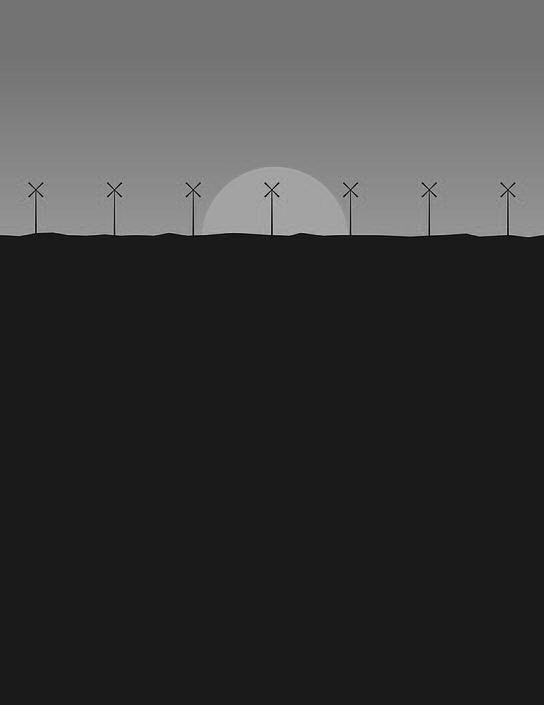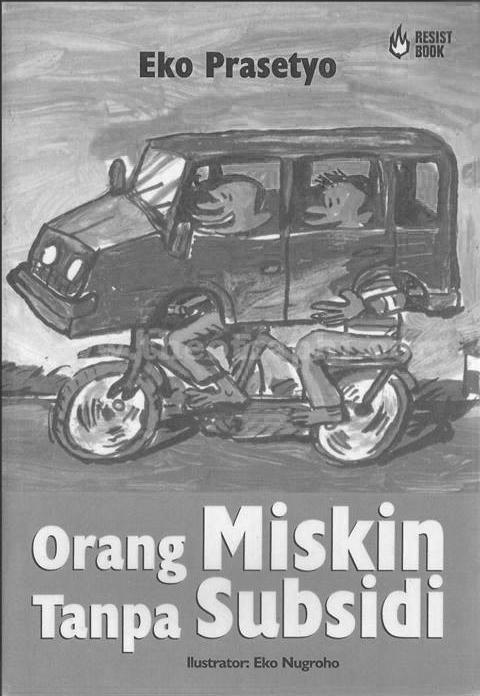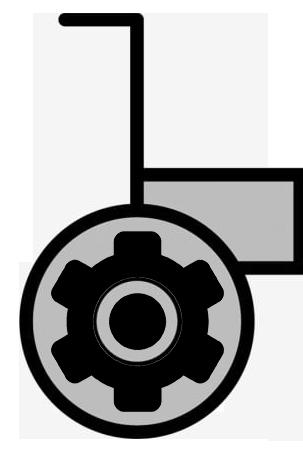4 minute read
EDITORIAL
Lapis Kemas Disabilitas
Sesak Regulasi, Minim Akomodasi
Advertisement
Hak asasi manusia merupakan prinsip dasar bagi setiap individu untuk memperoleh keadilan dan kesetaraan. Pendekatan berbasis hak ini bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar mereka turut berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karenanya, dibutuhkan perubahan-perubahan di tengah masyarakat untuk memastikan tercapainya tujuan ini.
Sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas telah disahkan baik oleh pemerintah sebagai pengampu kebijakan. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang menjamin hak setiap laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan hidup secara bermartabat; Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak warga negara; serta UU Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas. Di samping itu, pada November 2011,
Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Artinya,
Indonesia telah memberikan perhatian lebih dalam mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas.
Namun demikian, pelbagai kebijakan tersebut mestinya harus diimbangi dengan langkah praktis untuk mewujudkan “Indonesia Ramah Disabilitas” dari berbagai sisi kehidupan. Namun di balik regulasi tersebut, dengan penyebutan diksi ‘disabilitas’ pada setiap pasalnya, terdapat proses panjang dalam penggunaannya. Sebelumnya, diksi ‘disabilitas’ ini bermula dari penderita cacat yang kemudian menjadi penyandang cacat. Hingga muncul istilah difabel. Difabel merupakan eufemisme untuk menyebutkan seseorang yang berbeda kemampuan. Diksi ini disinyalir lebih tepat dan ramah, namun malah diksi ‘disabilitas’lah yang disahkan. Hal ini tidak dapat terlepas dari “Semiloka Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) di awal tahun 2009” dan “Diskusi Pakar untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat”. Semiloka dalam hal tersebut secara khusus membahas istilah apa yang paling tepat untuk menerjemahkan kata ‘disability’ dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities, namun tidak sampai pada suatu keputusan dan hanya menghasilkan istilah-istilah alternatifnya.
Sedangkan dalam acara “Diskusi Pakar untuk Memilih Terminologi Pengganti Istilah Penyandang Cacat” yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada 19–20 Maret 2010 di Jakarta, diputuskan diksi ‘disabilitas’. Padahal ‘disabilitas’ sendiri tidak termasuk dalam istilah alternatif yang sebelumnya dibahas pada “Semiloka Komnas HAM”. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah secara sepihak memutuskan penggunaan diksi ‘disabilitas’. Hingga secara otoritas pemerintah menggunakan ‘disabilitas’ dalam berbagai regulasi untuk selanjutnya dipakai dalam berbagai kesempatan, hingga seolah terdengar “lebih ramah” oleh masyarakat.
Perlakuan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam “Buku Panduan Aksesibilitas Layanan Universitas Brawijaya”, tidak dapat terlepas dari cara pandang masyarakat yang lebih kepada charity model atau medical model dibandingkan social model. Charity model inilah yang pada akhirnya memberikan stigma kepada penyandang disabilitas. Cara pandang ini menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek untuk santunan atau amal. Sedangkan medical model memandang disabilitas adalah sebuah penyakit, yang kemudian menempatkan penyandang disabilitas sebagai pasien yang harus disembuhkan, sehingga terapi atau rehabilitasi menjadi cara jitu dalam memperlakukan penyandang disabilitas. Kedua cara pandang ini membuat penyandang disabilitas seakan tersisih, dipandang sebelah mata, dan hanya dilirik karena belas kasihan di tengah masyarakat.
Berbeda dengan social model yang melihat disabilitas sebagai dampak dari lingkungan dan sistem sosial yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Cara pandang ini melihat hambatan partisipasi penyandang disabilitas muncul dari cara pemerintah membangun kesadaran masyarakat. Bagaimana masyarakat dibangun dan dikelola, sehingga memunculkan sikap dan asumsi yang salah tentang penyandang disabilitas, termasuk bagi penyandang disabilitas sendiri. Mereka menganggap kondisinya sebagai keniscayaan, sehingga peran pemerintah dalam menjamin hidup mereka tak begitu diperhitungkan.
Selama ini infrastruktur dan aksesibilitas memang sudah tersedia di berbagai tempat umum, namun masih minim dan jauh dari optimal. Padahal, jumlah penyandang disabilitas selalu bertambah setiap tahunnya, baik kondisi yang disebabkan oleh penyakit kronis, kecelakaan, atau bencana alam. Masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundangan dan kebijakan yang ada secara efektif, agar para penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan di tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan mengakses pendidikan.
Pun pendidikan terhadap penyandang disabilitas, pemerintah telah mengusung peraturan dalam mendukung pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. Pemerintah Pusat:
1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif
3. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
5. Permendiknas Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
6. UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
Provinsi Jawa Timur:
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Disabilitas
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur
3. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
Pendidikan di semua jenjang adalah hak seluruh masyarakat, tanpa membedakan kondisi dan golongan. Setiap masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan akses pendidikan pada jenjang yang mereka inginkan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusif merupakan salah satu perwujudan nyata pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang sama, rata, dan adil. Namun pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih termarginalkan dan terdiskriminasi dalam hal akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pekerjaan.